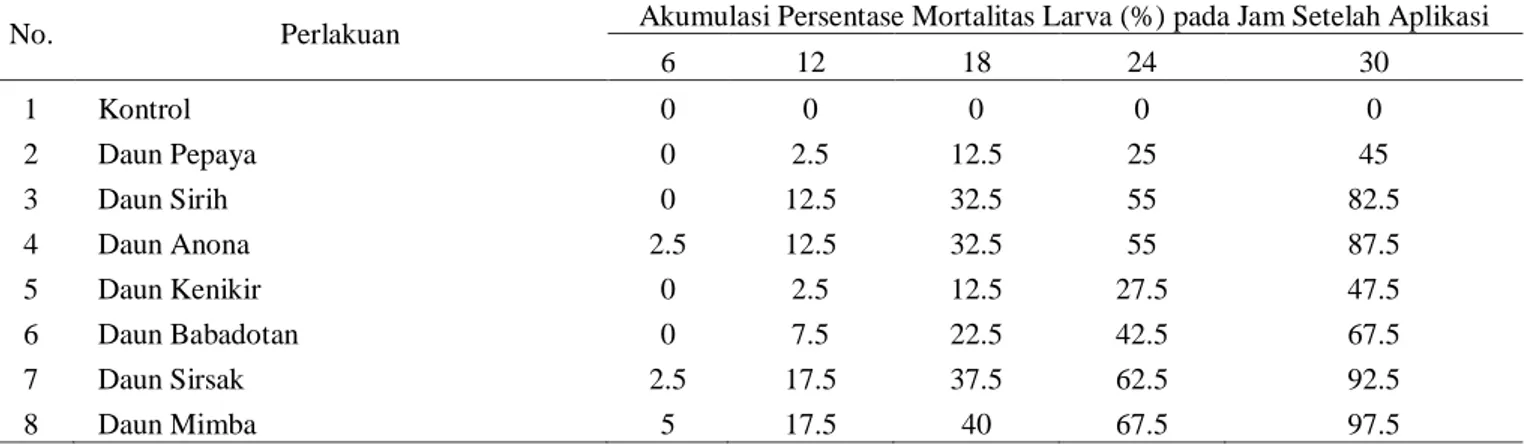Pemanfaatan Bahan Nabati Lokal Berefek Pestidida untuk Mengendalikan Hama Cylas formicarius pada
Tanaman Ubi Jalar
(Utilization of Local Vegetable Materials Effecting Pesticides to Control Cylas formicarius Pests in Sweet Potatoes)
Nina Jeni Lapinangga
1dan Yosefus F. da Lopez
21