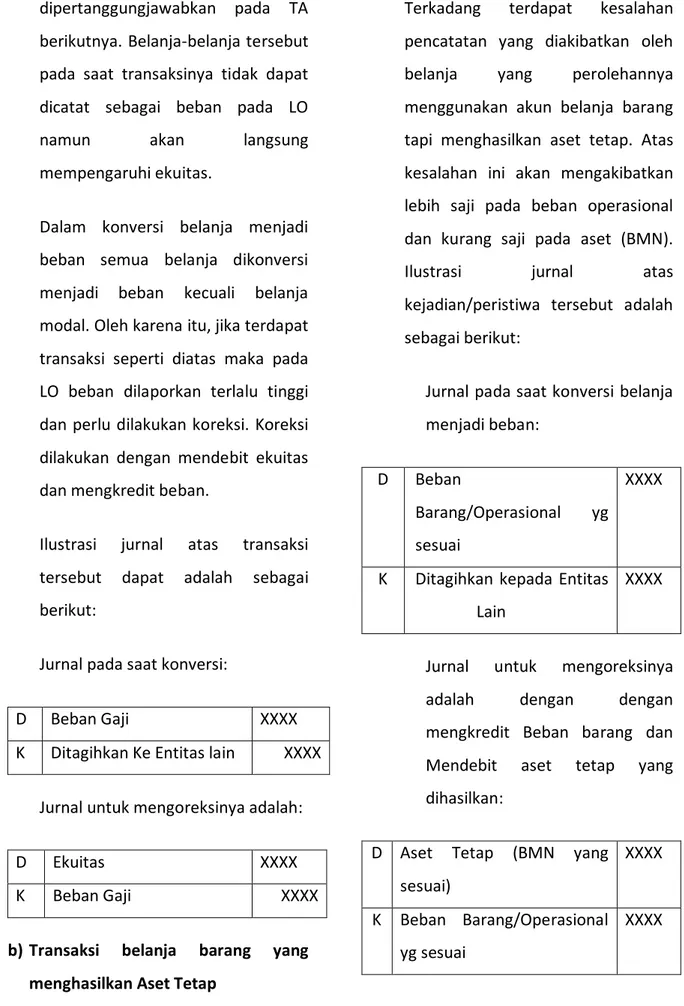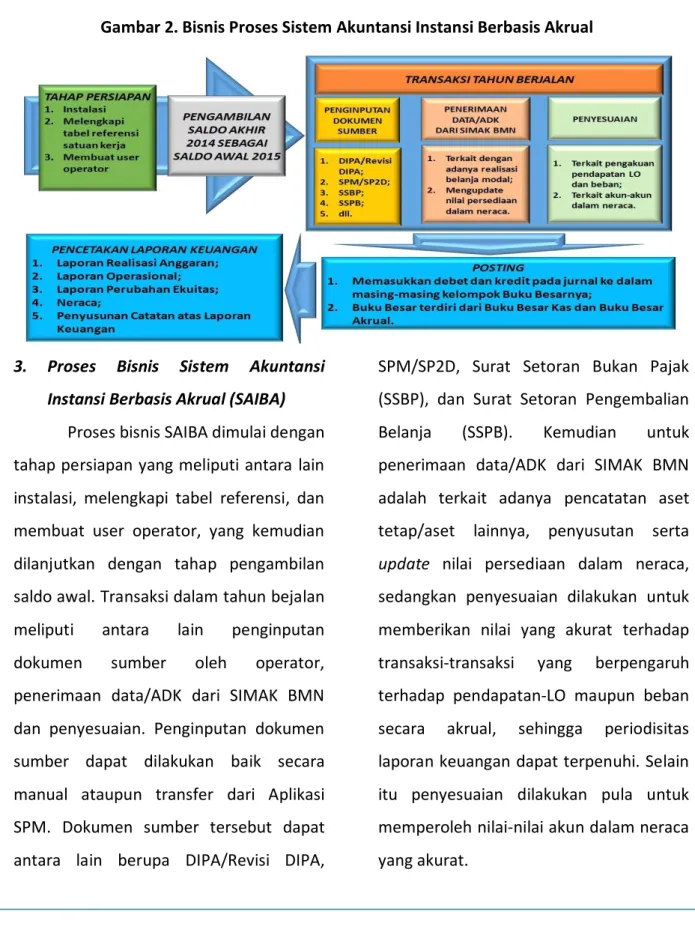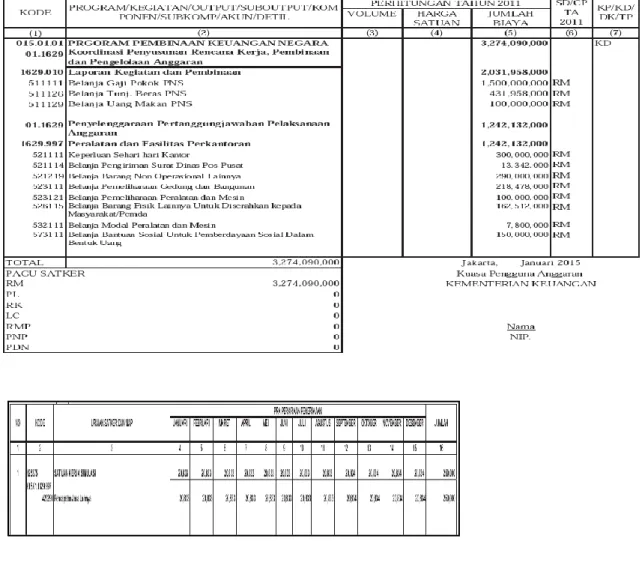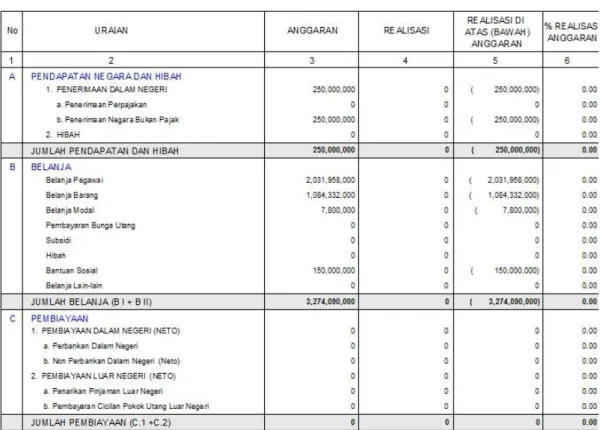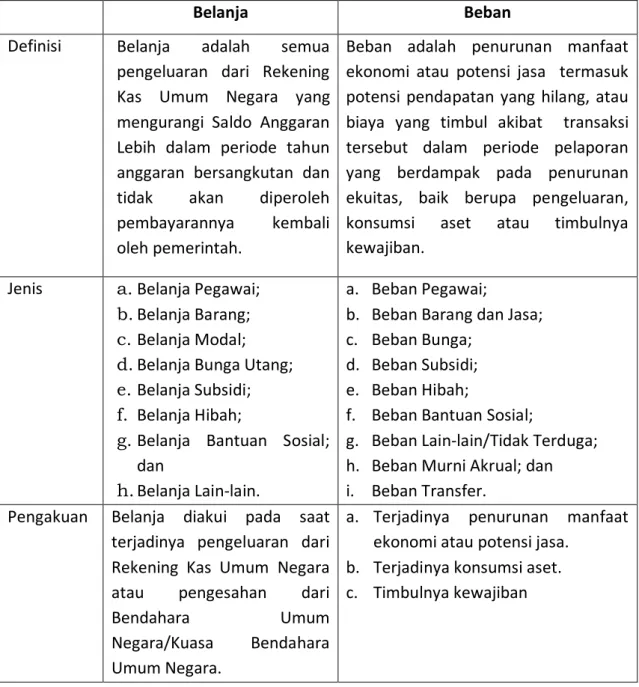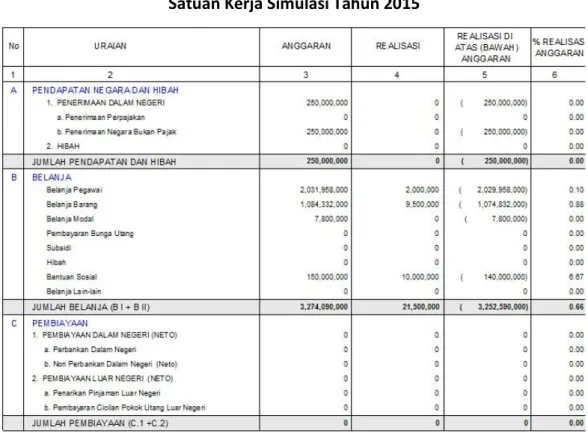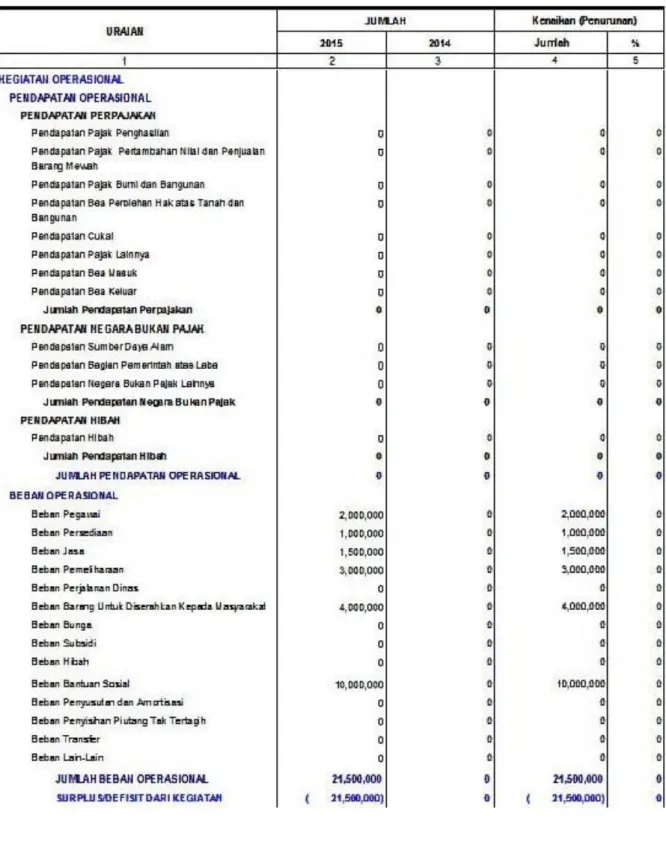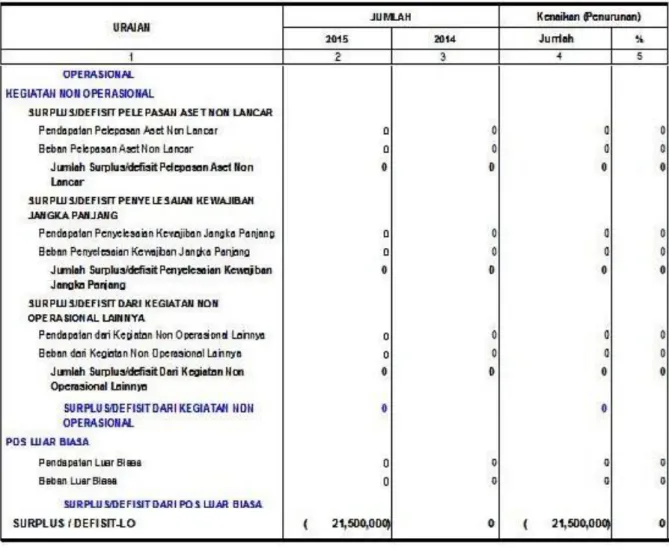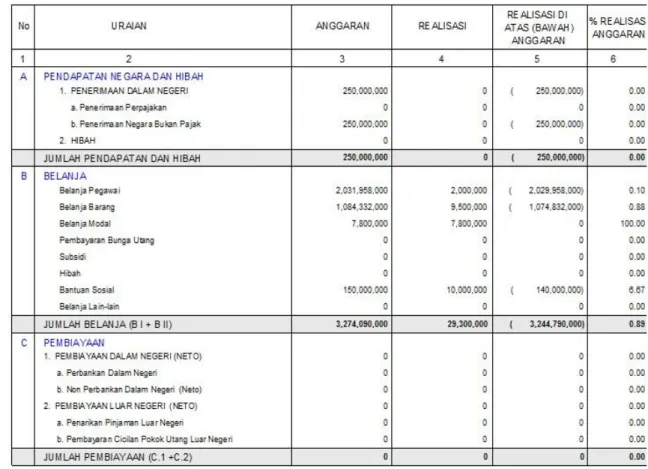SELAYANG PANDANG PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
Oleh: Fitra Riadian dan Komang Ayu Kumaradewi
Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Keuangan Negara
tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Standar Akuntansi
Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
yang sama, menyatakan bahwa
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, namun hingga tahun 2008 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR membuat
kesepakatan bahwa implementasi
akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada tahun 2015. Salah satu tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang
diselenggarakan pada tanggal 12
September 2013 telah dideklarasikan kebulatan tekat baik dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah akan mensukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Adapun deklarasi dimaksud ditandatangani oleh Menteri Keuangan mewakili penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mewakili penyusun Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL), dan
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,
Bupati Kabupaten Bondowoso dan
Walikota Bandar Lampung mewakili penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Laporan keuangan yang dihasilkan dengan basis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para
pemangku kepentingan, baik para
pengguna maupun pemeriksa laporan
keuangan pemerintah, yaitu dapat
memberikan informasi yang lebih
komprehensif, tidak hanya capaian
realisasi anggaran, namun juga kinerja pengelolaan keuangan negara.
Dasar Hukum Penerapan Pelaporan Keuangan dengan Basis Akrual
Perubahan basis akuntansi berakibat pada perlunya perubahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya. Selain
mengubah basis Sistem Akuntansi
menjadi akrual, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus sebagai penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan keuangan negara
yang terus berkembang. Dengan
demikian, diharapkan proses
implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dapat berjalan dengan
baik.Adapun peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual, antara lain:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
Dalam menyusun Laporan Keuangan
dengan menggunakan Akuntansi,
diperlukan adanya Standar Akuntansi. Pada tahun 2005, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP), namun
masih menggunakan basis Kas
Menuju Akrual. Kemudian diterbitkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari dua lampiran, yaitu Lampiran I yang berisi SAP Berbasis Akrual dan Lampiran II yang berisi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Hal ini karena dari tahun 2010 hingga tahun 2014
pemerintah masih dapat
menggunakan SAP berbasis Kas Menuju Akrual, dan pada tahun 2015 harus menggunakan SAP Basis Akrual.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Selain memerlukan Standar Akuntansi, dalam menyusun Laporan Keuangan juga diperlukan sistem (cara) dalam menyusun Laporan Keuangan. Untuk
itu, diterbitkan PMK
No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat berbasis akrual yang mengatur sistem dalam menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Barang Milik Negara (L-BMN), termasuk tata cara
rekonsiliasi, reviu atas Laporan
Keuangan, dan Pernyataan Tanggung Jawab. Peraturan ini menggantikan
PMK No.171/PMK.05/2007 yang
mengatur system dalam menyusun Laporan Keuangan dengan basis Kas Menuju Akrual.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar
Peraturan ini berisi tentang segmen-segmen Bagan Akun Standar yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-KL/RDP-BUN, penyusunan DIPA,
pelaksanaan anggaran, pelaporan
keuangan Pemerintah Pusat, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat.
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215 Tahun 2013 tentang Jurnal
Akuntansi Pemerintah pada
Pemerintah Pusat
PMK ini berisi tentang jurnal standar dan jurnal detail yang digunakan dalam pencatatan setiap transaksi
pelaporan keuangan pemerintah dengan basis akrual.
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Peraturan ini berisi tentang kebijakan akuntansi yang dipilih dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat yang berbasisakrual.
f. Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor
KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
Keputusan ini berisi daftar kode akun (beserta uraian penjelasannya) yang digunakan dalam implementasi basis akrual. Pada Kepdirjen ini terdapat akun-akun pendapatan dan belanja yang digunakan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan akun-akun pendapatan dan beban yang digunakan pada Laporan Operasional. Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, terdapat
beberapa dasar hukum penerapan
akuntansi berbasis akrual yang akan diterbitkan, antara lain:
a. Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan mengenai Pelaporan Badan Layanan Umum;
b. Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan mengenai Pendapatan pada Laporan Operasional;
c. Peraturan Menteri Keuangan
tentangSistem Akuntansi Hibah,
termasuk hibah langsung.
Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan
Mengapa kita harus menyusun laporan
keuangan? Karena setiap entitas
pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk laporan keuangan pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan:
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas pelaporan dalam
periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas
pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan
4. Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas
pelaporan, terutama dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
Selain bermanfaat dalam menilai
akuntabilitas, laporan keuangan juga harus dapat membantu para penggunanya
dalam membuat keputusan, baik
keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut (akuntabilitas dan pengambilan keputusan), maka penggunaan basis akrual akan lebih membantu apabila dibandingkan dengan menggunakan basis kas menuju akrual karena antara lain:
1. Basis akrual dapat memberikan
gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah;
2. Basis akrual dapat menyajikan
informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah;
3. Basis akrual bermanfaat dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.
Definisi Basis Akrual
Apakah yang dimaksud dengan Basis Akrual? Kerangka Konseptual Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I (KK-PSAP Lamp.I) Paragraf 43 dan 45 menyatakan basis akrual adalah suatu basis yang menyatakan bahwa:
Pendapatan diakui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
Contoh:
Satker ABC memiliki Gedung yang disewa oleh Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp10.000.000,-. Pembayaran diterima oleh Satker ABC dari Pihak Ke-III pada tanggal 3 Januari 2016. Atas transaksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2015 telah terpenuhi hak
untuk memperoleh pendapatan
karena telah diselesaikannya transaksi
sewa-menyewa, walaupun
kas/pembayarannya belum diterima. Sehingga Satker ABC:
o Pada tanggal 28 Desember 2015
(atau pada laporan keuangan
tahun 2015) harus mencatat
adanya pendapatan sewa sebesar Rp 10.000.000,-.
o Pada saat menerima
kas/pembayaran pada tanggal 3
Januari 2016, tidak mencatat
adanya pendapatan sewa.
Beban diakui pada saat kewajiban
yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
Contoh:
Satker ABC menyewa Gedung Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp 20.000.000,-. Satker ABC membayar sewa gedung tersebut pada tanggal 25 Januari 2016. Atas transaksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2015 telah
terpenuhi kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih karena telah
diselesaikannya transaksi
sewa-menyewa, walaupun
kas/pembayarannya belum dilakukan. Sehingga Satker ABC:
o Pada tanggal 28 Desember 2015
(atau pada laporan keuangan
tahun 2015) harus mencatat
adanya beban sewa sebesar Rp 20.000.000,- .
o Pada saat pembayaran pada
tanggal 25 Januari 2016, tidak
mencatat adanya beban sewa.
Transaksi Pendapatan dan Beban
diatas dilaporkan dalam suatu laporan yang dinamakan Laporan Operasional
(LO), sehingga disebut sebagai
Pendapatan-LO dan Beban-LO.
Untuk Neraca, aset, kewajiban dan
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan basis yang kita gunakan sampai
dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, yaitu suatu basis yang menyatakan bahwa: (KK-PSAP Lamp II Par.40 & 41)
Pendapatan diakui pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
Contoh:
Satker ABC memiliki Gedung yang disewa oleh Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp 10.000.000,-. Pembayaran diterima oleh Satker ABC dari Pihak K-III pada tanggal 3 Januari 2016. Atas transaksi diatas, pendapatan sewa diakui pada saat kas diterima, yaitu pada tanggal 3 Januari 2016. Sehingga Satker ABC:
o Pada tanggal 28 Desember 2015
(atau pada laporan keuangan
tahun 2015) tidak mencatat
adanya pendapatan sewa.
o Pada saat menerima pembayaran
pada tanggal 3 Januari 2016, mencatat adanya pendapatan sewa sebesar Rp 10.000.000,-.
Belanja diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas
pelaporan. Contoh:
Satker ABC menyewa Gedung Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp 20.000.000,-. Satker ABC membayar sewa gedung tersebut pada tanggal 25 Januari 2016. Atas transaksi diatas, belanja
kas/pembayarannya dilakukan, yaitu pada tanggal 25 Januari 2016. Sehingga Satker ABC:
o Pada tanggal 28 Desember 2015
(atau pada laporan keuangan
tahun 2015) tidak mencatat
adanya beban sewa.
o Pada saat melakukan
pembayaran pada tanggal 25 Januari 2016, mencatat adanya
beban sewa sebesar Rp
20.000.000,-.
Pada saat berlakunya basis akrual,
pencatatan transaksi pendapatan dan belanja dengan basis diatas masih dilaksanakan dan dilaporkan dalam
suatu laporan yang dinamakan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
sehingga disebut sebagai
Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA.
Untuk Neraca, pengakuannya adalah
sama seperti pada basis akrual.
Komponen Laporan Keuangan
Bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, terdapat 2 Laporan Keuangan baru pada laporan keuanganberbasis akrual, yaitu Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan demikian komponen laporan keuangan pokok yang disusun oleh KLada 5, yaitu:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Operasional
c. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Neraca
e. Catatan atas Lapran Keuangan
Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan
wajib menyajikan laporan lain dan/atau
elemen informasi akuntansi yang
diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara garis besar, masing-masing
komponenlaporan keuangan pokok
dijelaskan sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tujuan pelaporan realisasi anggaran
adalah memberikan informasi
realisasi dan anggaran entitas
pelaporan. Perbandingan antara
anggaran dan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap
APBN/APBD.
Adapun informasi yang tersaji dalam LRA adalah realisasi pendapatan-LRA dan belanja dari suatu entitas
pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan
anggarannya. Informasi tersebut
berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran, karena menyediakan
informasi sebagai berikut:
1. Informasi mengenai sumber,
alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal
efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran.
LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi apakah:
1. telah dilaksanakan secara efisien,
efektif dan hemat;
2. telah dilaksanakan sesuai dengan
anggarannya (APBN/APBD); dan
3. telah dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, LRA akan dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) dan memuat hal-hal
yang memengaruhi pelaksanaan
anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya
perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Contoh format LRA:
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN PERPAJAKAN
3 Pendapatan Pajak Penghas ilan xxx xxx xx xxx 4 Pendapatan Pajak Pertam bahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah xxx xxx xx xxx 5 Pendapatan Pajak Bum i dan Bangunan xxx xxx xx xxx 6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xx xxx
7 Pendapatan Cukai xxx xxx xx xxx
8 Pendapatan Bea Mas uk xxx xxx xx xxx 9 Pendapatan Pajak Eks por xxx xxx xx xxx 10 Pendapatan Pajak Lainnya xxx xxx xx xxx 11 Jum lah Pendapatan Perpajakan (3 s /d 10)(3 s /d 10) xxx xxx xx xxx 12
13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
14 Pendapatan Sum ber Daya Alam xxx xxx xx xxx 15 Pendapatan Bagian Pem erintah atas Laba xxx xxx xx xxx 16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xx xxx 17 Jum lah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s /d 16)(14 s /d 16) xxx xxx xx xxx 18
19 PENDAPATAN HIBAH
20 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx
21 Jum lah Pendapatan Hibah (20 s /d 20)(20 s /d 20) xxx xxx xx xxx 22 JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)(11 + 17 + 21) xxx xxx xx xxx 23 24 BELANJA 25 BELANJA OPERASI 26 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx 27 Belanja Barang xxx xxx xx xxx 28 Bunga xxx xxx xx xxx 29 Subs idi xxx xxx xx xxx 30 Hibah xxx xxx xx xxx
31 Bantuan Sos ial xxx xxx xx xxx
32 Belanja Lain-lain xxx xxx xx xxx
33 Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)(26 s /d 32) xxx xxx xx xxx 34
35 BELANJA MODAL xxx xxx xx xxx
36 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx
37 Belanja Peralatan dan Mes in xxx xxx xx xxx 38 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx 39 Belanja Jalan, Irigas i dan Jaringan xxx xxx xx xxx 40 Belanja As et Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx 41 Belanja As et Lainnya xxx xxx xx xxx 42 Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)(36 s /d 41) xxx xxx xx xxx 43 JUMLAH BELANJA (33 + 42)(33 + 42) xxx xxx xx xxx 44
45 TRANSFER
46 DANA PERIMBANGAN
47 Dana Bagi Has il Pajak xxx xxx xx xxx 48 Dana Bagi Has il Sum ber Daya Alam xxx xxx xx xxx
49 Dana Alokas i Um um xxx xxx xx xxx
50 Dana Alokas i Khus us xxx xxx xx xxx 51 Jum lah Dana Perim bangan (47 s /d 50)(47 s /d 50) xxx xxx xx xxx 52
53 TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)
54 Dana Otonom i Khus us xxx xxx xx xxx
55 Dana Penyes uaian xxx xxx xx xxx
56 Jum lah Trans fer Lainnya (54 s /d 55)(54 s /d 55) xxx xxx xx xxx 57 JUMLAH TRANSFER (51 + 56)(51 + 56) xxx xxx xx xxx 58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)(43 + 57) xxx xxx xx xxx 59
60 SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)(22 - 58) xxx xxx xx xxx PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 da n 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0
Apabila dibandingkan dengan LRA pada saat memberlakukan basis kas menuju akrual, perbedaannya adalah dalam LRA pada saat memberlakukan basis akrual tidak ada lagi pencatatan atas pendapatan non kas dan belanja non kas. LRA hanya mencatat transaksi kas, transaksi non kas dicatat dalam Laporan Operasional.
Contoh transaksi non kas adalah
pendapatan hibah dalam bentuk barang
yang tidak akan dicatat sebagai
pendapatan pada LRA namun dicatat sebagai pendapatan hibah pada LO.
b. Laporan Operasional (LO)
Tujuan pelaporan operasi adalah
memberikan informasi tentang
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas
pelaporan. Di samping melaporkan
kegiatan operasional, LO juga
melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
61 PEMBIAYAAN
62 PENERIMAAN
63 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
64 Penggunaan SAL xxx xxx xx xxx 65 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx xx xxx 66 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 67 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 68 Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xx xxx 69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 71 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)(64 s/d 70) xxx xxx xx xxx 72
73 PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
74 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx xxx 75 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx xx xxx 76 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)(74 s/d 75) xxx xxx xx xxx
77 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)(71 + 76) xxx xxx xx xxx
78
79 PENGELUARAN
80 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx xx xxx 82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 84 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) xxx xxx xx xxx 85 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 86 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 87 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)(81 s/d 86) xxx xxx xx xxx 88
89 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI xxx xxx xx xxx
90 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx xxx 91 Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx xx xxx 92 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)(90 s/d 91) xxx xxx xx xxx
93 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)(87 + 92) xxx xxx xx xxx
94 PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)(77 - 93) xxx xxx xx xxx
95
96 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94) (62 + 94) xxxx xxxx xx xxxx
(Dalam Rupiah) NO. URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0
LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pengguna laporan
membutuhkan Laporan Operasional
dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga LO menyediakan informasi:
1. mengenai besarnya beban yang
harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. mengenai operasi keuangan
secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam hal efisiensi,
efektivitas, dan kehematan
perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi;
3. yang berguna dalam memprediksi
pendapatan-LO yang akan
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan
4. mengenai penurunan ekuitas (bila
defisit operasional), dan
pengingkatan ekuitas (bila surplus operasional).
LO disusun untuk melengkapi
pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual (full accrual
accounting cycle) sehingga
penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai
keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Contoh format LO:
No 20x1 20x 0 Kenaik an/ (%) 1PENDAPATAN 2 PENDAPATAN PERPAJAKAN
3 Pendapatan Pajak Penghasilan xxx xxx xxx xxx 4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah xxx xxx xxx xxx 5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan xxx xxx xxx xxx 6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xxx xxx
7 Pendapatan Cukai xxx xxx xxx xxx
8 Pendapatan Bea Masuk xxx xxx xxx xxx 9 Pendapatan Pajak Ekspor xxx xxx xxx xxx 10 Pendapatan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx
11 Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 ) xxx xxx xxx xxx
12
13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
14 Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx 15 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba xxx xxx xxx xxx 16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx
17 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) xxx xxx xxx xxx
18
19 PENDAPATAN HIBAH
20 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx
21 Jumlah Pendapatan Hibah (20) xxx xxx xxx xxx
22 JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) xxx xxx xxx xxx
KEGIATAN OPERASIONAL
PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah) URAIAN
23 24BEBAN 25 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx 26 Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx 27 Beban Jasa xxx xxx xxx xxx 28 Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx
29 Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx
30 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx
31 Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx
32 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx
33 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx
34 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx
35 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx
36 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx
37 JUMLAH BEBAN (25 s/d 36) xxx xxx xxx xxx
38
39 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37) xxx xxx xxx xxx
40
41KEGIATAN NON OPERASIONAL
42 Surplus Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx 43 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx 44 Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx 45 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx 46 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
47 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46) xxx xxx xxx xxx
48 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47) xxx xxx xxx xxx
49
50POS LUAR BIASA
51 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
52 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
53 POS LUAR BIASA (51-52) xxx xxx xxx xxx
54 SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53) xxx xxx xxx xxx
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal,
surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan, koreksi-koreksi yang
langsung menambah/mengurangi
ekuitas, dan ekuitas akhir.
Koreksi-koresksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas,
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar,
misalnya:
1. Koreksi kesalahan mendasar dari
persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena
revaluasi aset tetap.
Untuk pemerintah pusat, dalam LPE ditambahkan pos transaksi antar entitas, yaitu akun Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain. Akun Diterima dari Entitas Lain
berfungsi sebagai akun lawan
transaksi penyetoran PNBP ke Kas Negara atau penerimaan aset dari
entitas lain, sedangkan akun
Ditagihkan ke Entitas Lain berfungsi sebagai akun lawan transaksi belanja (terbitnya SP2D) atau transfer aset ke entitas lain.
d. Neraca
Neraca menggambarkan posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset
nonlancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria tersebut
diklasifikasikan sebagai aset
nonlancar.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan.
Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
2. Kewajiban adalah utang yang
timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah mempunyai kewajiban masa kini
yang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan
sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
Kewajiban dikelompokkan ke
dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek
merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas setelah
tanggal pelaporan. Sedangkan
kewajiban jangka panjang adalah
kelompok kewajiban yang
penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
Contoh format Neraca:
No. 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Bank Indonesia xxx xxx
5 Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxx xxx
6 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx
7 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx
8 Investasi Jangka Pendek xxx xxx
9 Piutang Pajak xxx xxx
10 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak xxx xxx
11 Penyisihan Piutang (xxx) (xxx)
12 Beban Dibayar Dimuka xxx xxx
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
18 Piutang Lainnya xxx xxx
19 Persediaan xxx xxx
20 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) xxx xxx
21
22 INVESTASI JANGKA PANJANG
23 Investasi Nonpermanen
24 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
25 Dana Bergulir xxx xxx
26 Investasi dalam Obligasi xxx xxx
27 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
28 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
29 Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28) xxx xxx
30 Investasi Permanen
31 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx
32 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
33 Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) xxx xxx
34 Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33) xxx xxx
35
36 ASET TETAP
37 Tanah xxx xxx
38 Peralatan dan Mesin xxx xxx
39 Gedung dan Bangunan xxx xxx
40 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx
41 Aset Tetap Lainnya xxx xxx
42 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx
43 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)
44 Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43) xxx xxx PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah) Uraian
46 ASET LAINNYA
47 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
48 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
49 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
50 Aset Tak Berwujud xxx xxx
51 Aset Lain-Lain xxx xxx
52 Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51) xxx xxx
53
54 JUMLAH ASET (20+34+44+52) xxxx xxxx
55
56 KEWAJIBAN
57
58 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
59 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx
60 Utang Bunga xxx xxx
61 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx
62 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
63 Utang Belanja xxx xxx
64 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
65 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64) xxx xxx
66
67 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
68 Utang Luar Negeri xxx xxx
69 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx
70 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
71 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx
72 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx
73 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72) xxx xxx
74 JUMLAH KEWAJIBAN (65+73) xxx xxx
75
76 EKUITAS
77 EKUITAS xxx xxx
78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77) xxxx xxxx
79
Apabila dibandingkan dengan Neraca pada saat memberlakukan basis kas menuju akrual, perbedaannya adalah
dalam Neraca pada saat
memberlakukan basis akrual hanya terdapat satu pos Ekuitas, tidak ada lagi pos Diinvestasikan dalam Aset Lancar, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Cadangan Piutang dsb.
e. Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK)
Laporan keuangan mungkin
mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman
di antara pembacanya.
Kesalahpahaman tersebut dapat
disebabkan oleh persepsi pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran, mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa
dengan laporan keuangan komersial, cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, untuk
menghindari kesalahpahaman
tersebut, atas sajian laporan
keuangan, harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Selain itu, tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi laporan.
CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. CaLK juga
mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan
serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan dalam menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara
wajar. CaLK
mengungkapkan/menyajikan/menyed iakan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengungkapkan informasi umum
tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang
kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian
target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang
dasar penyusunan laporan
keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan
penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang
diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi lainnya
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Siklus Akuntansi Akrual
Sebagaimana diuraikan diatas,
terdapat lima laporan yang disusun. Dari
kelima laporan tersebut terdapat
keterkaitan (siklus) diantara laporan-laporan tersebut. Siklus tersebut terjadi diantara LO, LPE dan Neraca sebagai berikut:
Transaksi Operasional
(Pendapatan-LO dan Beban-(Pendapatan-LO), Transaksi Non
Operasional (Keuntungan/Kerugian
Penjualan Aset Tetap) dan Transaksi Luar Biasa dicatat pada Laporan
Operasional. Penjumlahan dari
transaksi-transaksi diatas menjadi nilai akhir Laporan Operasional dengan nama “Surplus/Defisit LO”.
Nilai “Surplus/Defisit LO” akan
menjadi salah satu nilai pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada LPE, “Surplus/Defisit LO” akan dijumlahkan dengan transaksi lain pada LPE yaitu Ekuitas Awal, Koreksi dan Transaksi Antarentitas yang akan menjadi nilai akhir LPE dengan nama “Ekuitas Akhir”.
Nilai “Ekuitas Akhir” dari LPE akan
menjadi Nilai Ekuitas pada Neraca. Pada Neraca Akrual, hanya terdapat satu akun pada pos Ekuitas, yaitu “Ekuitas”.
Khusus transaksi DIPA maupun Revisi DIPA, hanya akan dicatat pada LRA sebagai pagu. Transaksi DIPA tidak dicatat baik pada LO, LPE maupun Neraca.
Aplikasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual
Sebagaimana penyusunan laporan keuangan sampai dengan tahun 2014 yang berbasis kas menuju akrual,
penyusunan laporan keuangan
dilaksanakan dengan menggunakan
aplikasi komputer yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.Pada tahun 2015, sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual tetap menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK). Aplikasi yang digunakan pada masing-masing sub-sistem tersebut adalah:
SIMAK-BMN: terdiri dari Aplikasi
Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN;
SAK: terdiri dari Aplikasi Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), SAIBA-W, SAIBA-E1 dan SAIBA-KL.
Sekilas Aplikasi SAIBA
Pada dasarnya aplikasi SAIBA adalah pengembangan dari aplikasi SAKPA. Pengembangan yang dilakukan adalah:
Sesuai dengan komponen laporan
keuangan yang harus disusun
berdasarkan basis akrual, maka Aplikasi SAIBA dapat menghasilkan LO
dan LPE, selain menghasilkan LRA dan Neraca.
Dalam rangka menghasilkan
laporan-laporan tersebut, maka dalam aplikasi SAIBA terdapat tambahan menu
transaksi, yaitu menu Jurnal
Penyesuaian. Menu ini digunakan untuk meng-input transaksi-transaksi yang melibatkan akun-akun akrual, seperti:
o Pendapatan Diterima diMuka;
o Pendapatan yang Masih Harus
Diterima;
o Beban Dibayar diMuka;
o Beban yang Masih Harus Dibayar;
o Beban Persediaan;
o Beban Penyisihan Piutang; dan
o Beban Penyusutan;
Sedangkan tata cara penggunaan aplikasi SAIBA pada dasarnya sama dengan aplikasi SAKPA, yaitu:
1. Input dokumen sumber (DIPA, Revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB) 2. Input jurnal Neraca
3. Input Jurnal Penyesuaian 4. Posting
5. Cetak Laporan-Laporan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI)
Saat ini, Kementerian Keuangan tengah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang disingkat SAKTI. Aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang mencatat, mengolah dan
menghasilkan laporan-laporan atas
seluruh transaksi keuangan yang ada pada kementerian negara/lembaga dalam 1 (satu) aplikasi yaitu:
Transaksi penganggaran, mulai dari RKA-KL sampai menjadi DIPA dan Revisinya;
Transaksi kas pada Bendahara mulai
dari Uang Persediaan, Kas Lainnya di
Bendahara, penerimaan dan
penyetoran PNBP/Pajak hingga
dihasilkan Laporan
pertanggungjawabannya;
Transaksi Komitmen seperti
pencatatan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak serta pengawasannya;
Transaksi pembayaran yang meliputi
SPP, SPM hingga pencatatan SP2D-nya;
Transaksi Aset yaitu pencatatan
Persediaan dan Aset tetap/Aset lainnya hingga dihasilkan laporan BMN-nya;
Transaksi Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan yang melakukan
jurnal-jurnal penyesuaian, posting dan
menghasilkan laporan keuangan yang telah berbasis akrual.
Dengan disatukannya semua transaksi tersebut dalam 1 (satu) aplikasi, maka diharapkan terjadi:
Efisiensi yaitu tidak terjadinya
pengulangan input data yang sama
pada beberapa aplikasi. Misalnya, paguDIPA yang selama ini di-input 3 (tiga) kali yaitu dalam aplikasi RKA-KL, SPM dan SAKPA. Dengan disatukannya dalam satu aplikasi, maka data pagu
cukup di-input padamodul
RKA-KL/DIPA saja, pada SPM dan akuntansi otomatis data tersebut akan terisi.
Akurasi pencatatan dan pelaporan
yang lebih baik. Dengan disatukannya
aplikasi, maka tidak ada lagi
perbedaan data antar aplikasi yang selama ini kerap terjadi. Misalnya, data pagu DIPA yang selama ini dimungkinkan terdapat perbedaan diantara aplikasi RKAKL/DIPA, SPM dan SAKPA. Dengan SAKTI, perbedaan tersebut tidak terjadi lagi.
Pada saat aplikasi SAKTI diterapkan,
maka dalam penyusunan laporan
keuangan tidak lagi menggunakan aplikasi SAIBA, tetapi menggunakan aplikasi SAKTI.
Konversi Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual Menjadi
Laporan Keuangan Berbasis Akrual: Sebuah Alternatif di Masa
Transisi
Oleh: Kadek Eriksiawan
1. Pendahuluan
Salah satu bagian dari reformasi keuangan negara adalah reformasi di bidang akuntansi pemerintahan yaitu perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual. Dengan perubahan ini, diharapkan akan dapat
meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara serta mengikuti international best
practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selanjutnya, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual/cash toward accrual (CTA)
berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Hal ini berarti bahwa implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan pada tahun 2015.
Namun perubahan sebuah sistem akuntansi tidaklah semudah membalikkan
telapak tangan. Setiap perubahan
memerlukan tahapan-tahapan yang
panjang dan melelahkan. Perubahan memerlukan penyediaan prasana fisik, peraturan yang mendukung, sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi dan yang terpenting kemauan serta dukungan pimpinan dalam mengawal proses perubahan ini.
Selain itu, proses perubahan
terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan baik karena kendala intern maupun ekstern entitas. Salah satu kemungkinan penyebabnya
adalah belum selesainya sistem informasi atau aplikasi yang menjadi komponen terpenting dalam perubahan sistem akuntansi kas menuju akrual ke sistem akuntansi akrual.
Berbagai alternatif hendaknya
disiapkan untuk mengantisipasi apabila pengembangan sebuah sistem akuntansi tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, sistem belum selesai sesuai dengan waktu
yang direncanakan, belum siapnya
infrastrusktur untuk implementasi sistem atau kendala-kendala lainnya. Dengan
demikian, meskipun sistem yang
dikembangkan belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan namun tetap dapat dihasilkan laporan keuangan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dan perlu dipahami bahwa solusi alternatif adalah bukan merupakan sistem utama yang dikembangkan dan tentunya kekurangan-kekurangan minor tidak bisa dihindari.
Dalam tulisan ini, akan diuraikan salah satu alterntif dalam implementasi akuntansi akrual. Alternatif tersebut adalah melalui konversi laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi CTA menjadi laporan keuangan dengan basis akrual. Pada awal tulisan akan dijelaskan tentang basis akuntansi beserta kelebihan
dan kekurangannya serta jenis laporan yang dihasilkan, kemudian akan dibahas
faktor-faktor yang mendukung
keberhasilan pelaksanaan konversi sistem akuntansi ini, serta yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam konversi laporan keuangan akuntansi CTA ke laporan keuangan akuntansi akrual.
2. Basis Akuntansi
Basis Akutansi adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang menentukan kapan
pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Jenis dan kualitas informasi yang dihasilkan dalam suatu sistem akuntansi akan ditentukan oleh basis akuntansi yang dianut oleh suatu entitas.
Secara umum terdapat dua basis
akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual. Namun dalam prakteknya berkembang
basis pencatatan yang merupakan
modifikasi antara basis kas dan akrual antara lain basis kas modifikasian, akrual modifikasian, termasuk basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Basis yang dianut oleh suatu entitas biasanya ditentukan antara lain oleh informasi yang dibutuhkan, sumber daya yang dimiliki, dan regulasi yang berlaku.
Sampai dengan saat ini hampir seluruh entitas pelaporan baik pada
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah masih mengimplementasikan
akuntansi berbasis kas menuju akrual. Akuntansi berbasis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan dan beban dalam basis kas serta mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan basis akrual. Dengan basis akuntansi ini dihasilkan Laporan
Realiasasi Anggaran (LRA) yang
memberikan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan dan belanja yang dikeluarkan untuk membiayai program-programnya yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPR/DPRD. Di samping itu juga dihasilkan neraca yang memberikan gambaran kondisi keuangan entitas pada tanggal pelaporan.
Basis akuntansi kas menuju akrual mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan basis akuntansi akrual. Kelebihannya antara
lain, pertama, penyusunan laporan
keuangan relatif mudah. Pendapatan hanya akan dicatat apabila terdapat transaksi kas masuk dan belanja dicatat pada saat ada transaksi kas keluar dari kas umum negara/daerah. Sedangkan neraca disusun dengan membukukan data aset, kewajiban dan ekuitas hanya pada tanggal
neraca. Kedua, informasi yang disajikan cukup memadai baik untuk akuntabilitas pelaksanaan APBN/D yaitu LRA dan neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas.
Namun demikian, basis kas menuju akrual juga tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Pertama, informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan tidak lengkap karena belum dapat menyajikan informasi terkait kinerja dan perubahan ekuitas suatu entitas. Kedua, kekurangakuratan penyajian informasi dalam neraca, hal ini disebabkan karena neraca yang dihasilkan tidak melalui siklus akuntansi yang utuh.
Implementasi akuntansi berbasis
akrual lebih sulit dibandingkan dengan akuntansi kas menuju akrual. Akuntansi akrual lebih banyak melibatkan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi. Selanjutnya, akuntansi akrual dalam proses penyusunan laporan keuangannya dilakukan dengan siklus akuntansi yang utuh guna menjamin keintegrasian dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Selain itu, membutuhkan sistem informasi yang lebih kompleks karena proses
akuntansi akrual mencatat semua
peristiwa/kejadian yang mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan entitas.
3. Konversi Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual ke Laporan Keuangan Berbasis Akrual sebagai Alterntif
Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi pemerintah
pusat/daerah dalam implementasi
akuntansi berbasis akrual. Pertama, kompleksitas dan jumlah transaksi yang harus dicatat dalam akuntansi semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan makin meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat dan transparansi. Prinsip dan kebijakan akuntansi yang dilibatkan dalam proses penyusunan laporan akan semakin bervariasi. Kedua, kompetensi SDM yang terlibat dalam akuntansi tidak merata. Misalnya, untuk pemerintah pusat terdapat kurang lebih 25.000 entitas yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kompetensi SDM yang beragam dalam akuntansi dan teknologi
informasi. Ketiga, sistem informasi
akuntansi yang masih dalam tahap
pengembangan. Sistem informasi
akuntansi yang didedikasikan untuk akuntansi akrual secara umum baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah masih dalam tahap
pengembangan. Seperti diketahui untuk implementasi sebuah sistem informasi
baru diperlukan tahapan-tahapan. Proses
tersebut antara lain, penyiapan
infrastrutur, pelatihan SDM, uji coba
sistem, kemudian evaluasi untuk
perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada. Dan tantangan terbesarnya adalah lamanya waktu dan biaya yang dihabiskan sampai dengan sistem yang baru dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
Berkenaan dengan uraian di atas, salah satu alternatif solusi dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan konversi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi kas menuju akrual menjadi laporan keuangan berbasis akrual. Cara ini bukan merupakan cara terbaik, akan tetapi dapat merupakan solusi di masa transisi hingga SDM, infrastruktur dan sistem informasi yang memadai telah tersedia.
Pada dasarnya, akuntansi kas menuju akrual berbeda dengan akuntansi akrual, namun terdapat beberapa persamaan yang dapat ditarik. Pertama, kedua basis akuntansi menghasilkan laporan yang
membandingkan pendapatan-LRA/LO
dengan belanja/beban. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO memang berbeda namun secara umum dapat dikonversi antara satu dengan lainnya dengan
penyesuaian dan koreksi. Demikian halnya belanja dan beban dengan cara yang sama dapat dikonversi antara satu dengan yang lainnya. Kedua, kedua basis akuntansi
mampu menghasilkan neraca yang
menggambarkan posisi keuangan entitas. Penyusunan neraca awal untuk akuntansi akrual dapat dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Hal ini akan memudahkan dalam implementasi tahap awal akuntansi akrual.
Terdapat beberapa faktor yang mendukung kesuksesan implementasi akuntansi akrual dengan konversi laporan keuangan berbasis CTA. Pertama, SDM pada entitas akuntansi saat ini sudah memahami dengan baik proses bisnis dan prinsip-prinsip akuntansi CTA yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan
akuntansi basis akrual. Termasuk
didalamnya aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan modifikasi aplikasi yang ada saat ini,
memungkinkan pelatihan terhadap
operator menjadi lebih singkat. Di samping itu, kebutuhan biaya untuk
penambahan kapasitas hardware dan
infrastruktur lainnya dapat dilakukan secara bertahap. Selanjutnya pelatihan SDM penyusun laporan juga mejadi lebih
mudah karena akuntansi akrual
merupakan penyempurnaan dari proses bisnis akuntansi CTA yang sudah mereka pahami.
4. Langkah-Langkah Konversi Laporan
Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Berbasis Akrual
a. Konversi Neraca
Langkah pertama adalah
menyesuaikan neraca tahun terakhir diimplementasikannya akuntansi kas
menuju akrual menjadi neraca
berbasis akrual. Misalnya, 2014
sebagai tahun terakhir
diimplementasikan akuntansi kas
menuju akrual, maka neraca tanggal 31 Desember 2014 dikonversi terlebih
dahulu sehingga pada awal
diimplementasi akrual yaitu tahun 2015 kita sudah memiliki neraca akrual per 01 Januari 2015.
Neraca yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis CTA tentunya berbeda dengan neraca berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi akrual. Neraca kas
menuju akrual secara umum
dihasilkan dengan melakukan
inventarisasi data-data berkaitan
dengan aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki entitas. Di sisi lain,
pencatatan transaksi dan memiliki
hubungan dengan Laporan
Operasional (LO) dan Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
Perbedaan yang jelas antara neraca kas menuju akrual dan neraca akrual adalah adalah pada pos ekuitas. Ekuitas pada neraca kas menuju akrual merupakan akun penyeimbang dari pos-pos aset dan kewajiban yang ditemukan pada tanggal pelaporan. Misalnya jika entitas pada tanggal pelaporan memiliki aset piutang maka pada ekuitas akan diseimbangkan
dengan akun cadangan piutang, aset tetap maka akan dimunculkan akun penyeimbang diinvestasikan dalam aset tetap dan seterusnya. Sedangkan ekuitas pada neraca akrual berasal dari saldo ekuitas akhir pada LPE.
Dalam LPE akan tergambar
perubahan dari saldo akun ekuitas awal, penambahan dan pengurangan dari LO dan koreksi-koreksi atas
ekuitas. Oleh karena itu konversi neraca kas menuju akrual menjadi neraca akrual mutlak dibutuhkan sebagai pondasi awal perubahan dari akuntansi kas menuju akrual ke akuntansi akrual.
Konversi neraca akrual awal dilakukan dengan menyesuaikan akun-akun ekuitas. Ekuitas yang terbagi-bagi dalam akuntansi CTA seperti
cadangan piutang, cadangan
persediaan, diinvestasikan dalam aset tetap dan lain-lain disatukan ke dalam satu akun ekuitas. Setelah neraca
awal akrual tersusun maka
perubahannya dalam pos aset dan
kewajiban dilakukan dengan
pencatatan melalui transaksi
penyesuaian dan koreksi, sedangkan akun ekuitas dihasilkan dari LPE.
b. Konversi LRA
Selanjutnya adalah pada tanggal pelaporan dilakukan konversi (LRA) menjadi (LO). Konversi dilakukan secara global sehingga nantinya akan dihasilkan LO yang belum disesuaikan. Diawali dengan melakukan konversi
pendapatan LRA menjadi
Pendapatan-LO. Konversi dilakukan
terhadap keseluruhan akun
pendapatan-LRA tanpa
memperhatikan apakah memenuhi
definisi dan prinsip pengakuan
pendapatan-LO.
Selanjutnya adalah akun-akun belanja dikonversi menjadi akun-akun beban kecuali akun-akun belanja modal. Sama halnya dengan pendapatan LRA, konversi belanja dilakukan tanpa
memperhatikan pengertian dan
prinsip pengakuan beban, misalnya belanja pegawai dikonversi menjadi
beban pegawai, belanja bunga
menjadi beban bunga, dan
seterusnya.
Konversi belanja barang dan jasa menjadi beban barang dan jasa dilakukan dengan sedikit berbeda.
Kita harus dapat membedakan
belanja-belanja barang yang
menghasilkan persediaan dan yang tidak. Terdapat banyak komponen dalam akun belanja barang seperti
perjalanan dinas, honor-honor
kegiatan, belanja jasa yang tidak menghasilkan persediaan. Penyajian belanja barang dan jasa dalam LO akan dibagi menjadi beberapa janis beban antara lain beban persediaan, beban jasa, beban perjalan dinas dan lain-lain.
Konversi pendapatan-LRA dan belanja ini akan dapat menghasilkan LO sebelum disesuaikan karena masih
kasar. Koreksi-koreksi dan
penyesuaian-penyesuaian atas akun-akun Pendapatan-LO dan beban hasil konversi mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan karena pertama, tidak semua akun pendapatan-LRA adalah merupakan pendapatan-LO. Kedua, tidak semua akun belanja, misalnya belanja modal adalah merupakan
beban. Ketiga, terdapat banyak transaksi-transaksi pendapatan LO dan beban yang pengakuannya tidak dipicu oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Keempat, penyajian format LO mensyaratkan penyajian berbeda yaitu terdapat surplus dan defisit dari kegiatan dan operasional dan terdapat pos-pos luar biasa yaitu pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.
c. Koreksi dan Penyesuaian
Seperti telah diuraikan di atas bahwa konversi LRA dan neraca kas menuju
akrual ke LO dan neraca akrual tidak dapat dilakukan secara langsung.
koreksi-koreksi harus dilakukan karena secara prinsip akuntansi kas menuju akrual berbeda dengan akuntansi akrual. Dalam tulisan ini koreksi dan penyesuaian yang harus
dilakukan akan dikelompokkan
menjadi tiga jenis yaitu transaksi
pendapatan-LRA yang bukan
pendapatan-LO, transaksi belanja yang bukan beban dan transaksi akrual non pendapatan-LRA dan non belanja. Dalam penyajian artikel ini, ilustrasi yang digunakan adalah
transaksi pada entitas
kementerian/lembaga pada
pemerintah pusat.
1. Transaksi Pendapatan-LRA yang
Bukan Merupakan Pendapatan-LO
Terdapat transaksi-transaksi
pendapatan LRA yang didasarkan atas akuntansi kas yang tidak memenuhi
kriteria pengakuan sebagai
pendapatan-LO antara lain:
a) Transaksi Pelunasan Piutang/
TPTGR dan Klaim Lainnya
Tidak semua Pendapatan-LRA
merupakan Pendapatan-LO. Salah satunya adalah penerimaan kas yang bersumber dari pelunasan piutang. Transaksi ini akan dicatat oleh LRA sebagai Pendapatan-LRA
karena terdapat aliran masuk ke Kas Umum Negara. Namun, dalam LO transaksi pelunasan piutang ini bukanlah merupakan Pendapatan-LO karena pengakuan pendapatan-LO sudah dilakukan pada saat pengakuan piutang.
Untuk menghindari pencatatan ganda atas Pendapatan-LO maka transaksi pelunasan piutang tersebut harus dikoreksi yaitu dengan mendebit Pendapatan-LO dan mengkredit Piutang. Ilustrasi jurnalnya adalah sebagai berikut:
Jurnal pada saat konversi
pendapatan-LRA ke Pendapatan-LO:
D Diterima dari Entitas
lain
XXXX
K Pendapatan LO XXXX
Sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah:
D Pendapatan LO XXXX
K Piutang XXXX
b) Transaksi Pendapatan-LRA atas
Peristiwa/Kejadian pada Tahun Anggaran (TA) yang Lalu
Pendapatan-pendapatan yang berasal dari TA yang lalu dan belum dicatat
sebagai piutang dalam laporan
keuangan serta baru diketahui pada
perode berjalan maka atas
pendapatan tersebut perlu dilakukan
koreksi. Misalnya, terdapat
pendapatan denda TA yang lalu dan baru diketahui periode berjalan yaitu pada saat dilakukan pembayaran dan belum dilakukan pengakuan sebagai piutang pada periode sebelumnya. Transaksi atas pembayaran tersebut yang dicatat sebagai Pendapatan-LRA tidak memenuhi kriteria sebagai Pendapatan-LO namun harus dicatat sebagai penambah ekuitas. Ilustrasi jurnalnya adalah sebagai berikut: Pada saat konversi LRA ke LO akan dijurnal sebagai berikut:
D Diterima dari
Entitas lain
XXXX
K Pendapatan-LO XXXX
Selanjutnya untuk mengkoreksi
pendapatan LO tersebut dapat dibuat jurnal sebagai berikut:
D Pendapatan-LO XXXX
K Ekuitas XXXX
Sebaliknya jika terdapat
pengembalian atas pendapatan yang pada TA sebelumnya sudah dicatat
sebagai pendapatan-LO dan
pengembalian dilakukan pada periode berjalan maka atas pengembalian pendapatan tersebut akan dicatat sebagai berikut:
Jurnal pada saat dilakukan
pengembalian Pendapatan-LO:
D Pendapatan-LO XXXX
K Ditagihkan ke Entitas lain XXXX
Selanjutnya, jurnal untuk melakukan koreksi adalah:
D Ekuitas XXXX
K Pendapatan-LO XXXX
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Par 22 PSAP 10 menyatakan bahwa “Koreksi
kesalahan atas penerimaan
pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.”
c) Transaksi Pendapatan yang
Berasal dari Kegiatan Non
Operasional dan Kejadian Luar Biasa
Berbeda dengan LRA, LO dalam
penyajiannya membedakan
kegiatan operasional, non
operasional dan pos-pos luar biasa. Dalam konversi LRA ke dalam LO
semua pendapatan-LRA akan
dikonversi menjadi pendapatan-LO
tanpa memperhatikan apakah
pendapatan tersebut berasal dari aktivitas operasional atau aktivitas lainnya. Oleh karena itu, terhadap
pendapatan-LRA yang bukan
berasal dari aktivitas utama harus direklasifikasi ke akun yang sesuai pada LO.
Salah satu contoh dari transaksi tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pelepasan/penjualan Barang Milik Negara (BMN). Pada proses konversi Pendapatan-LRA
dari penjualan BMN akan
dikonversi menjadi Pendapatan-LO yang merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional entitas. Hal ini tidak sesuai perinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum yaitu bahwa
penerimaan kas dari pelepasan BMN adalah merupakan kegiatan non operasional.
Dalam pencatatan transaksi
pelepasan BMN harus dilakukan
perhitungan apakah dalam
transaksi tersebut menghasilkan surplus (keuntungan) atau defisit (kerugian). Surplus dan defisit dihitung dengan membandingkan nilai buku aset tetap yang dilepas dengan kas yang diterima. Jika kas yang diterima lebih dari nilai buku aset tetap maka akan dicatat Surplus Penjualan Aset Tetap dan jika sebaliknya maka akan dicatat
defisit. Ilustrasi jurnal atas
transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
Jurnal saat konversi pendapatan-LRA:
D Diterima dari
Entitas Lain
XXXX
K Pendapatan-LO XXXX
Jurnal koreksi yang diperlukan apabila kas yang diterima lebih dari nilai buku aset tetap tersebut atau terjadi surplus:
D Pendapatan-LO XXXX D Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXXX K Surplus Penjualan Aset Tetap XXXX K Aset Tetap XXXX
Sedangkan apabila terjadi defisit yaitu kas yang diterima kurang dari nilai buku aset tersebut maka akan dijurnal: D Pendapatan-LO XXXX D Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXXX D Defisit Penjualan Aset Tetap XXXX K Aset Tetap XXXX
2. Transaksi Belanja yang Bukan
Merupakan Beban
a) Transaksi belanja atas kejadian
atau peristiwa Tahun
sebelumnya.
Sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan, yaitu Par 18 PSAP 10 “Koreksi kesalahan atas beban
yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan
beban, yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan
mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun ekuitas.” Hal ini berarti atas belanja untuk membayar peristiwa/kejadian yang terjadi pada tahun yang lalu tidak dapat dikategorikan sebagai beban namun sebagai transaksi yang
langsung mengoreksi entitas.
Misalnya terdapat transaksi untuk membayar kekurangan gaji tahun yang lalu dan belum dilaporkan serta baru dibayar pada tahun berjalan dengan menggunakan akun belanja gaji.
Termasuk dalam transaksi ini adalah
belanja-belanja yang belum
dipertanggungjawabkan sampai
dipertanggungjawabkan pada TA berikutnya. Belanja-belanja tersebut pada saat transaksinya tidak dapat dicatat sebagai beban pada LO
namun akan langsung
mempengaruhi ekuitas.
Dalam konversi belanja menjadi beban semua belanja dikonversi menjadi beban kecuali belanja modal. Oleh karena itu, jika terdapat transaksi seperti diatas maka pada LO beban dilaporkan terlalu tinggi dan perlu dilakukan koreksi. Koreksi dilakukan dengan mendebit ekuitas dan mengkredit beban.
Ilustrasi jurnal atas transaksi
tersebut dapat adalah sebagai berikut:
Jurnal pada saat konversi:
D Beban Gaji XXXX
K Ditagihkan Ke Entitas lain XXXX
Jurnal untuk mengoreksinya adalah:
D Ekuitas XXXX
K Beban Gaji XXXX
b) Transaksi belanja barang yang
menghasilkan Aset Tetap
Terkadang terdapat kesalahan
pencatatan yang diakibatkan oleh
belanja yang perolehannya
menggunakan akun belanja barang tapi menghasilkan aset tetap. Atas kesalahan ini akan mengakibatkan lebih saji pada beban operasional dan kurang saji pada aset (BMN).
Ilustrasi jurnal atas
kejadian/peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:
Jurnal pada saat konversi belanja menjadi beban:
D Beban
Barang/Operasional yg
sesuai
XXXX
K Ditagihkan kepada Entitas
Lain
XXXX
Jurnal untuk mengoreksinya
adalah dengan dengan
mengkredit Beban barang dan
Mendebit aset tetap yang
dihasilkan:
D Aset Tetap (BMN yang sesuai)
XXXX
K Beban Barang/Operasional yg sesuai