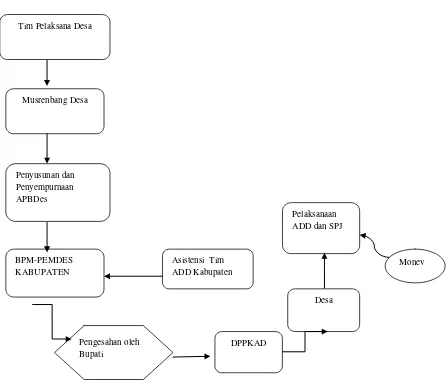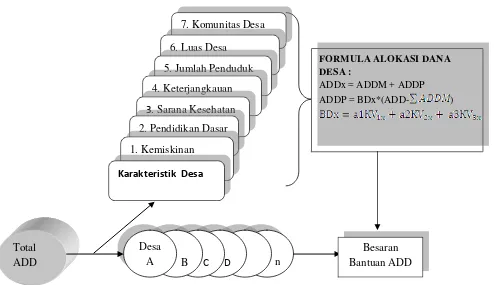BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perkembangan Desa, Otonomi dan Desentralisasi Desa
Istilah desa berasal dari bahasa India, swadesi yang berarti tempat asal,
tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup
dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan
Poernomo, 2003).
Menurut Wasistiono (dalam Hargono, 2010) dalam sejarah perkembangan
manusia, Desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang
pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan,
kekaisaran dan negara-negara modern sebagaimana yang dikenal dewasa ini.
Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung
bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang
menunjukkan perkembangan baru, yaitu timbulnya industri-industri kecil di
daerah pedesaan yang merupakan “rural industries”.
Salah satu peran pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah
pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor.
Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat
kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan
masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting
sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor
Secara Sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang
membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke (dalam
Wasistiono, 2007) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa
adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan
kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat
diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di
dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan juga
persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak tidaknya
sebagian besar daripada penduduk pribumi menjadi anggotanya.
Jika dipandang dari sudut politik dan administrasi pemerintahan, maka
desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal
suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan
sendiri (Wasistiono dalam Hargono, 2010). Pengertian ini menekankan adanya
otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang
mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan
disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Kesatuan masyarakat
hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan
wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan
masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari
sinilah asalnya mengapa ‘Desa’ disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda
dengan ‘daerah otonom’ lainya seperti Daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi
yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional
Setelah Indonesia merdeka, maka para founding fathers kita menyusun
UUD 1945 dan meletakkan kedudukan hukum Desa pada pasal 18, yang berbunyi
sebagai berikut :
“ Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan derah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa”
Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah Undang-Undang Nasional tentang
Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang
ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan desa dapat
diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan
: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
UU Nomor 5 Tahun 1979 sama sekali tidak memberikan hak kepada
pemerintahan desa atau Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa,
yang peraturan peraturannya bersumber dari otonomi desa. Akan tetapi
pemerintahan desa menurut UU ini hanya berhak menyelenggarakan
pemerintahan umum yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah yang otonom di atasnya. Kedudukan desa tidak lebih dari wilayah
administratif seperti wilayah administratif kelurahan dalam kawasan kota. UU
dipandang sangat condong menopang Orde Baru dengan politik stabilitas dan
sentralisasinya, sehingga menghambat demokratisasi desa.
Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin
diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik
pemerintah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam
UUNomor 5 Tahun 1979, bahwa : “….. sesuai dengan sifat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan,
dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang
masih berlaku”. Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya
kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan
penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal
disbanding masyarakat lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang
kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan
ketidakberdayaan dan ketergantungan.
Dengan bergulirnya reformasi maka dilakukan pembenahan mendasar dari
sentralisasi menuju desentralisasi. Dalam kaitannya dengan adanya reformasi
pemerintahan Desa, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa, segera diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Desa. Dalam pasal 1 huruf (o) UU Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa :
istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.
UU Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan
wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari
system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus
senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi
bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang
istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten, dimana
setiap warga desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi
sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih penting
adalah bagaimana mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut dalam
pemerintahan nasional.
Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya adalah pada saat
diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa
memang tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, karena sesuai amanat
UUD 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam
susunan system pemerintahan Negara Indonesia.
Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan
pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang
sistemastis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya
tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan
supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan,
personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan RI. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan
masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan
dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan
Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan
masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta
sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat secara langsung dan cepat.
Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di
wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka kepada desa diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya
dalam menjalankan roda pemerintahannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200
mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Berdasarkan Pasal 206 diatas, khususnya pada butir b, maka sebagai upaya
untuk lebih memberdayakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan
dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, pemerintah Kabupaten/Kota
dapat menyerahkan pengaturan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kepala Desa. Oleh karena itu, penyerahan sebagai urusan tersebut
harus dilakukan dengan semangat pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang
diserahkan adalah yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan layanan
publik di desa, bukan urusan dan kewenangan yang akan menjadi beban bagi
Pemerintah Desa.
Selain daripada itu pada pasal 215 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang
dilakukan oleh Kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembiayaan atau keuangan
merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa,
sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang
memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.
Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan
yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 secara
tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh
Kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 72 tahun
2005 tentang desa, maka semakin jelas kedudukan desa dalam pemerintahan
Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk
mengatur dan mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan desa pun menjadi
wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang
anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan
yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari
retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara
proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan
itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan
usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa
sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan
berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi
PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan
penjelasannya menyebutkan :
(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan
asli desa yang sah.
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa.
Penjelasan
Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) diberikan langsung kepada Desa. Dan retribusi
Kabupaten/Kotasebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara
professional.
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan
Alokasi Dana Desa Penjelasan
Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam
ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari
Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh
untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh
puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
Penjelasan
Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala
Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten/Kota
digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Penjelasan
Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk
hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan, serta pemberian
sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan
hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, khususnya tentang pendapatan asli desa
sangat terbatas, kas desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sangat minim,
bahkan tidak ada. Padahal desa menjalankan fungsi pemerintahan yang tidak jauh
berbeda dengan sub system pemerintahan lainnya. Untuk mengantisipasi hal
tersebut maka pemerintah melalui UU Nomor 34 sebagai perubahan atas UU
dengan PP Nomor 65 dan 66 Tahun 2001, menetapkan 10% diperuntukkan bagi
Desa di Kabupaten. Kemudian bagian hasil pajak Provinsi dan Kabupaten, dan
Dana Perimbangan dapat pula ditetapkan 10%, sedang Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota setelah dikurang belanja pegawai 10% dari DAU. Perimbangan
Dana Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa merupakan kelanjutan proses
desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan
Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, desentralisasi keuangan ke tingkat desa
tersebut terkadang diserahkan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Pada
akhirnya sering perimbangan dana ini berhenti pada level jargon maupun retorika
politik, faktor kepedulian pemerintah kabupaten terhadap desa lebih nampak
daripada wujud integritas dan kesadaran terhadap “rule of law”. Dalam konteks ketidakpastian regulasi dan formulasi perimbangan dana perimbangan kabupaten
ke desa inilah urgensi mendorong desentralisasi keuangan di desa harus terus
dilakukan (Wasistiono dalam Hartono, 2010).
Desentralisasi dan otonomi merupakan dua istilah yang memiliki makna
berbeda namun dalam prakteknya sering dianggap sama. Turner dan Hulme
(1997) menyimpulkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan
kewenangan (transfer ot authority) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau ke agensi lain yang lebih dekat dalam
Peraturan perundangan – undangan telah menegaskan adanya pemberian
kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sendiri, pengertian kewenangan pemerintahan desa untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri diatas, menjadi substansi
desentralisasi di tingkat desa. Desentralisalasi desa dapat diartikan secara
fungsional yaitu pendelegasian untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan
secara teritotial merupakan kewenangan untuk mengatur masyarakat dalam batas
kewilayahan tertentu. Dengan demikian desentralisasi desa pada intinya
merupakan pelimpahan kewenangan kepada desa untuk mengurs dirinya sendiri
(Hamid, 2010).
Otonomi berasal dari bahasa yunani autos dan nomos yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi disebut
sebagai local self government yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai local state government (Nugroho, 2000). Selain itu otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat (Suparmoko, 2001). Sebuah daerah otonom memiliki hak dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman ini merupakan dasar adanya
self governing community (penjelasan umum PP Nomor 76 tahun 2001). Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi
dan kewenangan pemerintahan supra desa ke desa. Secara umum fungsi dan
kewenangan tersebut adalah menjalankan roda pemerintahan di desa dalam rangka
Pilihan pada model kebijakan ADD ini dalam perspektif konvensional
analisis kebijakan publik merupakan upaya mereplikasi kebijakan serupa,
sebagaimana model relasi keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Sedangkan
dalam perspektif kritis pemahaman substansi kebijakan secara mendalam, ADD
adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam
memberikan pelayanan publik. Untuk mencapainya, harus ada konsistensi
pemerintah dalam menjalankan desentralisasi keuangan. Kalau pemerintah
propinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pemerintah pusat,
seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama (Dunn,
2003).
Dari aspek kebijakan, desa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh
bagian dari bagian daerah Kabupaten. Skema anggaran yang dikembangkan di
tingkat Kabupaten secara umum, masih belum terlihat adanya realisasi kongkrit
dari pembagian tersebut. Serapan dana untuk kegiatan rutin hanya menyisakan
20-25% untuk dana pembangunan, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha
untuk mewujudkan suatu dana perimbangan daerah dengan desa. Realisasi dana
perimbangan desa akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kabupaten dan desa
bisa memperjelas apa yang akan dilayani di masing-masing level. Dana
perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi
dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan melalui pembagian sama rata,
melainkan bagian desa dihitung dengan porsi kebutuhan dan potensi desa tersebut.
Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel : jumlah penduduk, luas
wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan
adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa, baik dari sektor pertanian
maupun dari sektor lainnya. Perhitungan ini sendiri diharapkan merupakan
perhitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa.
Pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah desa ini
harus sejalan dengan pengembangan sistem perencanaan partisipatif, dimana
proses perencanaan didorong kearah penyederhanaan jenis perencanaan,
pentingnya pengembangan desentralisasi fiskal yang terdiri dari pelimpahan
kewenangan dan transfer fiskal, penyederhanaan mekanisme perencanaan,
penataan fungsi dan peranan kelembagaan serta berbagai pihak yang
berkepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan. Tanpa adanya sinergi
antara desentralisasi fiskal dengan perencanaan partisipatif, dalam pengertian
perimbangan keuangan, tidak diletakkan dalam kerangka perencanaan partisipatif
akan menyebabkan tidak terwujudnya tujuan peningkatan penyediaan barang dan
jasa publik serta peningkatan manfaat yang diterima oleh masyarakat desa. Begitu
pula ruang partisipasi yang ada tidak akan dapat dioptimalkan oleh pemerintah
dan masyarakat desa, sehingga tujuan umum desentralisasi dalambentuk
pelimpahan kewenangan dan transfer fiskal tidak akan dapat dicapai.
Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif yang diimplementasikan
dalam bentuk tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran
2.2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa
Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan
menjadi tiga yaitu:
a. Fungsi alokasi (allocation function) b. Fungsi distribusi (distribution function)
c. Fungsi stabilisasi (stabilization function) (Musgrave and Musgrave, 1989:6). Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam mengediakan barang
publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme
pasar. System pasar tidak dapat menyediakan barang/ jasa tertentu karena
manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan
tetapi dinikmati orang lain. Contoh barang dan jasa yang tidak dapat disediakan
melalui sistem pasar adalah jalan, pembersihan udara dan sebagainya. Fungsi
distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan
dan kesejahteraan kapada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi
adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi
tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga
pada level yang rasional atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
diinginkan (Guritno, 1993). Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan
pemerintah desa dalam perekonomian desa, untuk itu pemerintah desa
memerlukan berbagai kewenangan.
Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa secara formal
merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa bab III pasal 7 bahwa terdapat
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan
Pemerintah Kabupaten / Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan
pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan Kepada Desa.
2.3. Tranfer Keuangan dan Pembiayaan Pemerintahan Desa
Sesuai dengan asas money follow function, kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa harus disertai pendanaan untuk menjalankan
kewenangan tersebut. Pada tahun anggaran 1969/1970 Pemerintah Pusat mulai
menganggarkan dana untuk desa melalui instruksi Presiden (Inpres) bantuan
Pembangunan Desa. Inpres ini bertujuan untuk mendorong peningkatan gotong
royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Inpres diberikan ke
daerah berdasarkan jumlah desa dikalikan jumlah subsidi per desa (Mahi Dan
Ardiansyah, 2002).
Pada tahun anggaran 1994/1995 terdapat jenis baru untuk pendanaan
pembangunan desa yaitu melalui IDT (Inpres Desa Tertinggal). Inpres ini
dimaksudkan untuk memberikan bantuan khusus (special assistance) kepada daerah-daerah yang dikategorikan tertinggal dalam hal pembangunan
dibandingkan daerah lain. Target utama anggaran ini adalah untuk menekan
khusus mengkaji keberhasilan pembiayaan Pemerintah Pusat ke Desa melalui
berbagai jenis inpres tersebut, namun seperti halnya keberadaan transfer
Pemerintah Pusat ke daerah pada masa lalu menyisakan dua persoalan utama,
yaitu tidak sesuainya berbagai jenis inpres tersebut dengan kebutuhan daerah dan
meningkatkan kesenjangan fiskal antar daerah (Mahi dan Ardiyansyah, 2002).
Berdasarkan pengalaman transfer pemerintah pada masa – masa sebelum
lahir Perundang - Undangan Otonomi Daerah, maka melalui konsep desentralisasi
fiskal Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999, transfer dana dari Pemerintah
lebih menekankan peranan bantuan yang bersifat umum (general Purpose grant). Dalam hubungannya dengan pembiayaan di Daerah, perlu diketahui sumber
pendapatannya yang pasti agar terdapat kepastian pula mengenai pelaksanaan dan
kelangsungan kegiatan Pemerintahan di Daerah. Seperti telah seringkali di
singgung sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa pada
prinsipnya pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli
Daerah, (2) Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, (3) Pinjaman
Daerah. Sedangkan perimbangan keunagan antara Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten terdiri dari : (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana
Alokasi Khusus.
Jika ini di bandingkan dengan Pemerintahan Desa maka transfer Keuangan
antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa juga terjadi. Hal ini
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 68 mengatur
sumber pembiayaan pemerintahan desa berasal dari lima komponen yaitu :
2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 10% untuk Desa dan
dari retribusi Kabupaten / Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk
setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan
Pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka urusan pemerintah.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang
desa diketahui bahwa hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten
Dengan Pemerintahan Desa berupa bagi hasil pendapatan (revenue sharing) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dan bantuan (grants) yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten. Pendapatan desa dari dana perimbangan
belum ada pengaturannya, padahal bagi desa sumber penerimaan ini sangat
penting.
Tujuan adanya dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah
Desa pada prinsipnya sama dengan tujuan dana bantuan antara Pemerintah Pusat
ke Kabupaten. Menurut (Simanjuntak dan Hidayanto, 2002) pada prinsipnya ada
tiga tujuan adanya transfer dana bantuan antar tingkat pemerintah :
1. Meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal yaitu mengurangi perbedaan
kemampuan fiskal antara pemerintah yang pusat dengan pemerintah daerah.
2. Meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal yaitu mengurangi perbedaan
3. Sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan
dengan manfaat yang menyebar. Insentif ini juga dapat diberikan berdasarkan
pertimbangan lain misalnya prestasi Pemerintah Daerah dalam
mengupayakan penerimaan dari sumber daya yang dimiliki prestasi atas
penyelenggaran pelayanan publik.
Simanjuntak dan Hidayanto dalam Hamid (2010) menyebutkan bahwa
perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan
stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana
Pemerintah Daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan
kemampuan Pemerintah Pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian
bagi Pemerintah Daerah dalam mendapatkan alokasi dana.
Berdasarkan praktek ada tiga cara dalam menentukan jumlah alokasi dan
transfer, yaitu :
1. Proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah atau persentase tertentu dari
penerimaan pemerintah.
2. Secara adhoc dialokasikan seperti halnya pengalokasian keperluan belanja lainnya.
3. Menggunakan formulasi tertentu misalnya dikaitkan dengan proporsi dari
pengeluaran spesifik atau karakteristik daerah penerima bantuan.
Pendistribusian transfer dana antar tingkat pemerintah, yaitu dana bantuan
pemerintah Kabupaten ke Pemerintahan Desa pada prinsipnya sama dengan
pendistribusian dana bantuan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hasil studi Ma
pendistribusian yang dipraktekkan (Yansekardias, 2001: 24-28). Model tersebut
antara lain :
1. Model kesenjangan fiskal (fiskal gap).
Pendistribusian transfer didasarkan atas perbedaan antara kebutuhan dan
kemampuan fiskal, sehingga merupakan model transfer yang paling baik. Model
ini memerlukan persyaratan ketersediaan data khususnya yang terkait dengan
pengeluaran. Persyaratan ini belum banyak dipenuhi di Negara – Negara
berkembang, karena keterbatasan data yang dimiliki pemerintah.
2. Model kapasitas fiskal (fiscal capacity)
Transfer dengan model ini didasarkan atas kemampuan atau kapasitas
fiskal (fiscal capacity) daerah dan mengabaikan prebedaan kebutuhan fiskal antar daerah. Menurut model ini daerah yang memiliki kapasitas fiskal dibawah
rata-rata nasional akan mendapat dana transfer yang lebih besar, sehingga disimpulkan
tujuannya adalah pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.
3. Model transfer berdasarkan indikator kebutuhan
Model ini didasarkan atas pemikiran agar setiap daerah mampu memenuhi
kebutuhan pelayanan publik minimum yang telah ditentukan. Indikatornya sangat
tergantung dari berbagai sudut pandang seperti tujuan pemerintah, faktor sejarah,
dan politik. Indikator – indikator yang digunakan antara lain tingkat pendapatan
perkapita, kepadatan penduduk, luas daerah, tingkat kemiskinan, tingkat
pengangguran, tingkat kematian bayi, tingkat harapan hidup, tingkat putus
4. Model transfer berdasarkan kesamaan basis pajak perkapita
Model ini didasarkan atas rasio total transfer terhadap jumlah penduduk
serta dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar
daerah. Walaupun tidak dapat menjamin kondisi tersebut berlangsung dalam
kurun waktu lama.
2.4. Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan
beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer
dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan,
sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima
sebagai landasan.
Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar
tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten
dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang
sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki
pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program
desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka
desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan
kepadanya.
Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang
diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan
Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD
Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen).
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan
pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
sesuai dengan potensi desa.
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari
dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya
pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa).
Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai
dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan,
keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu :
a. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
b. Pendidikan dasar,
d. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota
dan Kecamatan),
e. jumlah penduduk,
f. Luas wilayah, dan
Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ,
tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan
berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang
sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan
asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan
rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan,
Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa
Proporsional (ADDP).
Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan
sebagai berikut :
1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa
diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU Nomor 34
Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu
diamanatkan dalam UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah
Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5%
sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk
Dana Alokasi Khusus.
Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat
(3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti
dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1).
Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam
Negeri tanggal 22 Maret 2003 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana
Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perhitungan besarnya ADD
untuk tiap desa, yaitu :
1. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap
Desa.
2. Ketersediaan data untuk perhitungan ADD merupakan prasarat pertama.
3. Rumus yang digunakan harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD harus sama untuk setiap desa (ADDM = Alokasi
Dana Desa Minimal), dengan prosentase 60% dari ADD. Asas adil adalah
besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa
berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable
tertentu (ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional) dengan prosentase 40% dari
Dalam pengalokasian dana tersebut sudah pasti akan dapat terjadi
ketimpangan fiskal antardesa, dan hal tersebut akan menyebabkan tidak dapat
tercapainya keadilan dalam pengalokasian tersebut. Kebijakan ADD memang
menjadi instrumen bagi terselenggarannya pemerintahan desa secara partisipatif.
Hal ini karena ADD terintegrasi ke dalam APBdes dan tahap perencanaan,
penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBdes menghendaki
partisipasi warga. Namun demikian ADD juga menjadi arena bagi elemen-elemen
penyelenggara pemerintahan desa untuk mengusung kebijakan dan program yang
responsif bagi kepentingan masyarakat. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai
program yang diusung Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya
dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotongroyong yang signifikan. Tidak
kalah penting prgram itu juga diawasi pelaksanaannya sehingga mendorong
akuntabilitas dan transparasi di dalam melaksanakan pekerjaannya. ADD juga
menjadi alat yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri
di wilayahnya. Dengan adanya ADD warga dapat belajar menangani projek secara
swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun
desanya (Hargono, 2010).
2.5.Ruang Lingkup Yuridis Alokasi Dana Desa (ADD)
Pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD), dapat ditelusuri
dari uraian pasal telah dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara implisit, dapat dicermati melalui
a. Pendapatan Asli Desa.
b. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima
Kabupaten/Kota.
d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga
Memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) di atas,
dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa
terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi :
a. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
b. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupeten/Kota dari
Pemerintah Pusat.
c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa
berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/sj Tanggal 22 Maret
2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2.6. Keadilan (equity) Alokasi Dana Desa
Rahardjo (2011) menyebutkan ada tiga fungsi pokok Pemerintah secara
khusus di bidang ekonomi yakni : (1) Efisiensi, (2) Stabilitas, (3) Keadilan.
Tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk
memperbaiki kesalahan pasar seperti misalnya monopoli dan dampak eksternalitas
negatif. Dalam menjaga stabilitas, ini berkaitan dengan makro ekonomi. Dengan
kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan keijakan makro ekonomi,
pemerintah dapat mempengaruhi jumlah output, angkatan kerja, dan pola harga
(inflasi) dalam suatu perekonomian. Tindakan pemerintah yang menyangkut
keadilan berkaitan dengan mendorong tersedianya lapangan kerja, mengentaskan
kemiskinan, memberikan banyuan kepada kelompok masyarakat yang
membutuhkan. Dengan kata lain keadilan merupakan kebijakan pemerintah yang
memperlakukan semua orang/ warga negaranya dan semua pihak dalam
masyarakat secara sama, tidak berat sebelah dan tidak pilih kasih.
Dalam prinsip pemberian bantuan Alokai Dana Desa (ADD) prinsip
keadilan ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah/ Kabupaten mengalokasikan
ADD tidak sama bagi setiap desa. Akan tetapi pemerintah membagi Alokasi
Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa sesuai dengan variable yang
telah di tetapkan. Variable yang telah ditetapkan tersebut antara lain adalah
jumlah penduduk, kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan
lain-lain. Jadi dengan fungsi keadilan ini maka setiap desa akan memperoleh
bantuan alokasi dana desa tidak sama setiap desa, karena desa memiliki jumlah
penduduk yang berbeda, jumlah penduduk miskin yang berbeda, jumlah
yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan Alokai Dana Desa
yang diterima masing-masing desa.
Seperti halnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdasarkan prinsip
keadilan dalam pembagiannya, untuk meratakan pendapatan antar daerah, Dana
Alokasi Desa (ADD) juga memiliki tujuan untuk meratakan pendapatan antar
desa. Akan tetapi secara konseptual prinsip keadilan ini berkaitan dengan besaran
jumlah dana Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa. Saat ini
alokasi dana untuk desa dirasa masih terlalu kecil dan pendistribusiannya masih
bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan. Selama ini alokasi dana untuk
desa dibagi berdasarkan anggaran yang ada di Kabupaten. Dan dalam
penerapannya terkadang tidak menggunkan kriteria-kriteria yang dipertimbangkan
seperti jumlah penduduk, dan sebagainya. Ini memungkinkan pembagian alokasi
dana ke desa bisa dianggap adil untuk Kabupaten tersebut namun tidak adil bila
dilihat secara nasional atau bahkan mungkin pembagian alokasi dana ke desa bisa
dianggap belum adil untuk kabupaten apalagi bila dilihat secara nasional.
Hal ini dimungkinkan karena formula dari pemerintah pusat mengenai
Alokasi Dana Desa baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa belum memberikan formula yang baku dan multitafsir
sesuai dengan kebijakan daerah. Sebenarnya pemerintah pusat telah mengeluarkan
suatu pedoman formula namun hanya dituangkan dalam Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari
Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Desa, yang menggunakan sistem
pembobotan desa berdasarkan variabel seperti kemiskinan, pendidikan dasar dan
Memang undang – undang tersebut mengamanatkan otonomi lebih pada
Pemerintah Kabupaten / Kota namun tidak berarti Pemerintah Desa harus
bergantung penuh terhadap Pemerintah Kabupaten / Kota, karena sesungguhnya
Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus wilayahnya
bahkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa telah diatur tersendiri, seperti
yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2007 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Sasaran utama Alokasi Dana Desa menurut peraturan Bupati Labuhanbatu
Selatan nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Alokasi dana
Desa adalah :
1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
2.7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena
itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:
1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan
untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,
teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,
terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat
terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan
kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang
dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang
berlaku.
2.8. Penetapan Jumlah Alokasi Desa Desa
Dalam Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22
maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana desa dari Pemerintah Kabupaten /
Kota Kepada Pemerintah Desa tertulis bahwa rumus alokasi dana desa yang
Asas penentuan ADD adalah adil dan merata, oleh karena itu, ditetapkan
bahwa dari total ADD dibagi atas :
a. 60% terbagi habis secara merata untuk seluruh desa di Kabupaten/Kota dan
disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)
b. 40% dilakukan pemetaan dengan pola pikir yang telah ditentukan dan disebut
Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
Gambar 2.1 Kebijakan Alokasi Dana Desa
KEBIJAKAN dan Daerah Yg Diterima
Kab/Kota Utk Belanja PNS Daerah
Minimal 10% untuk ADD bagi Seluaruh Desa
Pola Alokasi
Alokasi Dana Desa Minimal 60%dari total ADD dibagi secara Merata utk seluruh Desa
Alokasi Dana Desa Prprsional 40% dari total ADD dibagi untuk desa Desa tertentu Sesuai Hasil Penilaian
TOTAL ADD TIAP DESA Diatur & diurus Oleh
Rumus penentuan ADDP dilakukan sebagai berikut :
ADDPx = BDX x (ADD –ADDM) Keterangan :
BDX = Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota
ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
Penentuan Bobot Desa dilakukan Sebagai Berikut :
a. Nilai Bobot Desa (BDX) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independent. Variabel independent merupakan indicator
yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDX) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
b. Variabel independent yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa
(BDX) dibedakan atas variable utama dan variable tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan karakter, budaya dan ketersediaan data
daerah.
c. Variabel independent utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk
menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa
secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa.
Variabel independent utama meliputi:
a. Kemiskinan
b. Pendidikan dasar
c. Kesehatan, dan
d. Variabel independent tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan
oleh masing-masing daerah. Variabel independent tambahan meliputi:
a. Jumlah penduduk
b. Luas Wilayah
c. Potensi ekonomi
d. Partisipasi Masyarakat
e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, RW dan RT)
2.9. Sasaran dan Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat 1 d
penjelasan dinyatakan bahwa :
a. Alokasi dana sebesar 30 % yaitu untuk belanja aparatur dan biaya operasional
Pemerintahan Desa.
b. Alokasi dana sebesar 70% yaitu untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD
terintegrasi dalam APBDesa. Mekanisme pelaksanaannya adalah dimulai dengan
dibentuknya tim pelaksana Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana Desa, BPD, LKMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di
desa ( seperti PKK,RT/RW, Karang Taruna, dll) dengan difasilitasi Camat
melakukan Musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana
kegiatan pembangunan ditingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD,
Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Penetapan recana kegiatan
pembangunan yang didanai dengan ADD didasarkan pada skala prioritas
pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan
untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa. Hasil musrenbang desa dapat
dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu :
a. Program-program yang dapat dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan
b. Program-program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan
dan menjadi ususlan ke tingkat Kabupaten melalui musrenbang tingkat
Kecamatan.
Kemudian Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi
Dana Desa kepada Bupati Labuhanbatu Selatan melalui Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim
Pendamping Kecamatan. Kemudian Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah. Kemudian
Kepala DPKAD menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas
daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.
Program yang tertuang dalam APBDesa yang telah disetujui Bupati, dapat
diimplementasikan dan dibuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ). Selama kegiatan
berlangsung, dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev), baik oleh Tim
Pendamping Kecamatan maupun oleh Tim Kabupaten. Hasil monev ini menjadi
Adapun mekanisme pelaksanaan ADD dapat dilihat dalam gambar
dibawah ini :
Gambar 2.2. Alur Pelaksanaan ADD
Tim Pelaksana Desa
Musrenbang Desa
Penyusunan dan Penyempurnaan APBDes
BPM-PEMDES KABUPATEN
Asistensi Tim ADD Kabupaten
Pengesahan oleh Bupati
DPPKAD
Desa Pelaksanaan ADD dan SPJ
2.10. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa
Guna menunjang efektifitas pengolahan ADD dibentuk Tim perumus
ADD, tim penyuluhan dan tim koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat
Kabupaten yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati dan tim pendamping
tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat serta tim pelaksana
ADD di tingkat desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2.11. Penelitian Terdahulu
Dini Gemala (2010), melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Alokasi
Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”.
Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat hubungan antara Alokasi Dana
Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
Hubungan tersebut dapat dilihat dengan adanya pemberian alokasi dana desa
memiliki efek yang sangat besar dari peningkatan pembangunan desa di wilayah
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dari pemberian alokasi dan desa terdapat
pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, drainase/selokan, tempat
ibadah, sekolah-sekolah diperbaiki, puskesmas diperbaikan, sarana pelayanan
masyarakat, selain itu peningkatan kebersihan pasar tradisional, peningkatan SDM
masyarakat desa dengan` menggunakan kegiatan pelatihan keterampilan yang
bertujuan untuk meningkatakan swadaya masyarakat desa. Peningkatan swadaya
masyarakat desa merupakan target utama dari program otonomi daerah, hal ini sangat
bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan
Yunita Sari (2009) meneliti tentang kebutuhan dan potensi fiskal antar desa di
Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam penelitiannya dia menggunakan variable
kebutuhan fiskal yang secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap
pengeluaran desa di Kaupaten Ogan Ulu adalah jumlah penduduk. Dan dari hasil
perhitungan diketahui rata-rata kebutuhan fiskal desa di Kabupaten Ogn Ulu adalah
Rp.80.343.730. dan potensi fiskal sebesar Rp. 9.730.066, ketimpangan fiskal terjadi
rata-rata Rp. 76.613.664.
Edy Suandy Hamid (2010) dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Mengenai
Formula Alokasi Dana Desa” menyatakan Bahwa Alokasi Dana Desa menggunakan
formula yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum
memberikan keadilan dan pemerataan Alokasi Dana Desa antar desa di seluruh
Indonesia namun hanya memberikan keadilan dan pemerataan hanya pada desa dalam
ruang lingkup kabupaten / kota tersebut. Beliau menyatakan Formula penghitungan
Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara
selayaknya dicoba untuk diterapkan guna memberikan keadilan dan pemerataan
penyaluran Alokasi Dana Desa antar desa di seluruh Indonesia dan menghilangkan
kesan bahwa Pemerintah Desa bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah
Kabupaten, dimana jumlah dana Alokasi Dana Desa yang disalurkan keseluruh desa
di Indonesia diperhitungkan sebesar sepuluh persen dari total penerimaan dalam
negeri neto.
Nani Farida Susanti (2008) dalam penelitiannya tentang formula Alokasi
Dana Desa Daerah Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Karimun Provinsi Kepri Tahun
2007, hasil penelitiannya menetapkan bahwa pembobotan variable yang
menghasilkan nilai rata-rata indeks Williamson terkecil. Formula ADD simulasi 3
menjadi 0,0520, sehingga penggunaan formul ADD memberikan gambaran semakin
meratanya pendistribusian ADD dan semakin mengecilnya ketimpangan antardesa.
Didiek Setiabudi Hargono (2010) dalam penelitiannya tentang Efektifitas
Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat desa di Kabupaten Karangasem Propinsi
Bali. Hasil penelitiannya dia menyatakan analisa yang dilakukan di empat desa pada
empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Bali menunjukkan bahwa
penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas
yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan (disparitas)
pembangunan ekonomi antar wilayah kecamatan dan cenderung meningkat yang
tergambar dari meningkatnya nilai Indeks Williamson dari tahun 2004 hingga tahun
2008 mendekati nilai 1 (satu). Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh karena
penentuan kuantitas Alokasi Dana Desa per desa belum menggunakan formula
Alokasi Dana Desa yang ditentukan oleh pemerintah dalam Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, sehingga aspek keadilannya masih kurang
terpenuhi. Tidak dipergunakannya pembobotan Desa dalam penentuan ADD
Proporsional dengan mempertimbangkan tujuh actor esensial di desa, turut
mempengaruhi disparitas tersebut
2.12. Kerangka Konseptual
Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Alokasi Dana Desa ke setiap
desa sebagai wujud nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program
Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat di desa. Pemberian Aloksi Dana Desa tersebut
pemerintah memperhatikan karakteristik dari masing-masing desa dan mentapkan
pertimbangan tersebut dimasukkan dalam rumus pembagian ADD yang ada di
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/sj Tanggal 22 Maret 2005
perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
pemerintah desa. Sehingga diperoleh besaran Alokasi Dana Desa untuk