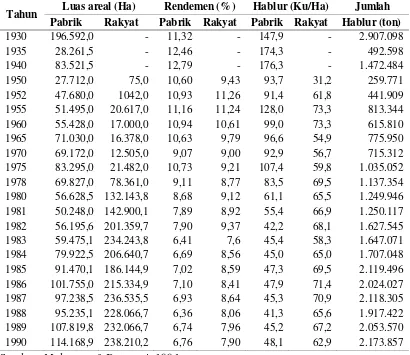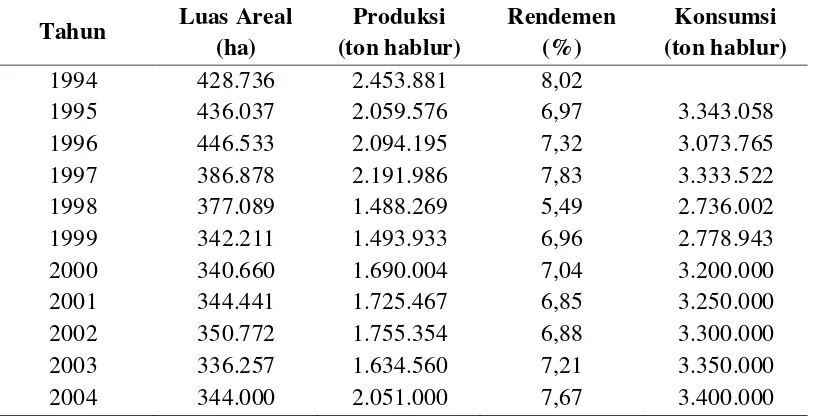BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Tanaman perkebunan merupakan salah satu tanaman yang prospektif untuk
dikembangkan di Indonesia. Letak geografis dengan iklim tropis dan memiliki
luas wilayah yang begitu luas menjadikan Indonesia merupakan daerah yang
cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Salah satu komoditas
perkebunan yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah tebu. Tanaman tebu
merupakan tanaman perkebunan semusim yang menghasilkan bahan pangan
pokok, yaitu gula. Gula diolah dari batang tebu hingga menjadi butiran gula pasir
yang putih dan terasa manis. Dalam bahasa Inggris, tebu disebut sugar cane. Tebu
mempunyai sifat tersendiri, sebab di dalam batangnya terdapat zat gula dan hanya
tumbuh di daerah tropis. Tebu memiliki usia panen kurang lebih satu tahun sejak
ditanam.
Awal mula penanaman tebu adalah pada Sistem Tanam Paksa, yang memberikan
keuntungan besar untuk kas Negara kolonial. Setelah Sistem Tanam Paksa
dihentikan, perkebunan tebu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta.
Perluasan perkebunan tebu tidak pernah melampaui Pulau Jawa. Jenis tanah dan
pola pertanian di Pulau Jawa lebih sesuai untuk penanaman tebu. Gairah
perekonomian kolonial sangat dipengaruhi oleh daya tarik dan keuntungan yang
diperoleh dari perkebunan tebu. Penanaman tebu mendorong pendirian pabrik
-pabrik pembuatan gula. Perkebunan tebu dan -pabrik gula menjadi motor
Daerah jantung perkebunan tebu yang tumbuh sejak tahun 1840-an dan
berkembang sampai abad berikutnya adalah daerah pesisir utara dari Cirebon
hingga Semarang, di sebelah selatan gunung Muria hingga Juwana, daerah
kerajaan (Vorstenlanden), Madiun, Kediri, Besuki, di sepanjang Probolinggo
hingga ke Malang melalui Pasuruan, dari Surabaya barat daya sampai ke
Jombang.
Saat Indonesia merdeka, tebu rakyat berkembang dengan sendirinya tanpa ada
campur tangan dari pemerintah. Namun, perkembangan kembali tebu rakyat juga
mengalami kendala. Modal yang cukup tinggi dibutuhkan dalam penanaman tebu
rakyat. Petani pun cukup kesulitan untuk memperoleh modal.
Perkembangan industri gula memberikan keuntungan yang besar untuk
pemiliknya dan memberikan pajak untuk pemerintah kolonial. Berkat keuntungan
dari perdagangan gula, beberapa kota di Pulau Jawa berkembang pesat, seperti
kota pelabuhan Semarang dan Surabaya, dan kota-kota lainnya. Industri gula
menyerap tenaga kerja yang banyak dari kalangan Eropa yang terampil dan
buruh-buruh pribumi. Melalui perkebunan tebu, masyarakat pulau Jawa mengenal upah
yang diberikan dalam bentuk alat pembayaran yang sah atau uang. Namun, arti
penting dari sumbangsih perkebunan dan pabrik gula adalah memberi contoh
tentang organisasi, kekuatan keuangan, kemajuan teknik, efisiensi dan laba yang
melahirkan kemajuan pesat dalam pertanian terhadap bidang usaha lainnya yang
kemudian berkembang pesat hingga melampaui perkembangan industri gula
Dari waktu ke waktu, industri gula selalu menghadapi berbagai masalah, sehingga
produksinya belum mampu mengimbangi besarnya permintaan masyarakat.
Meningkatnya konsumsi gula dari tahun ke tahun disebabkan oleh pertambahan
penduduk, peningkatan pendapatan penduduk, dan bertambahnya industri yang
memerlukan bahan baku berupa gula (Tim Penulis PS, 1994).
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gula, selama ini negara kita
mengimpornya dari negara lain. Cara ini kurang tepat untuk memecahkan masalah
kekurangan gula. Cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah memantapkan
produksi gula dalam negeri. Upaya itu antara lain dengan pencanangan program
Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).
Pogram TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) merupakan program pemerintah untuk
mendorong kembali semangat petani tebu dalam meningkatkan produktivitas areal
tanam sehingga tercapai swasembada gula yang telah dicanangkan mulai tahun
2014. Program ini dilaksanakan untuk menjawab rendahnya produksi gula
nasional dibandingkan tingginya permintaan yang masih disiasati dengan impor
gula. Ketergantungan impor mengakibatkan Indonesia sebagai negara ke-3
pengimpor gula terbesar, setelah Rusia dan India. Padahal ketika tahun
1984-1985, Indonesia pernah mengalami masa swasembada gula. Waktu yang singkat
dan tidak berkelanjutan tersebut disebabkan karena Pabrik Gula (PG) tidak dapat
memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, krisis ekonomi, dan
sebagainya (Wulanamigdala, 2013).
Sebelum tahun 1975, keikutsertaan petani dalam pengadaan tebu hanya terbatas
tanggal 22 April 1975 dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1975 (Inpres
9/1975) mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Yang dimaksud dengan
Intensifikasi Tebu Rakyat atau dikenal dengan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)
adalah pengertian menurut Inpres No 9 tahun 1975, yaitu “Langkah-langkah yang
bertujuan untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula di
atas tanah sewa, ke arah tanaman tebu tanpa mengabaikan upaya peningkatan
tanaman tebu rakyat tersebut dilakukan sistem BIMAS secara bertahap”.
Menurut Inpres No 9/1975 tersebut pada dasarnya maksud yang terkandung antara
lain :
1. Menghasilkan pengusahaan tanaman tebu dari sistem sewa tanah oleh Pabrik
Gula menjadi Tebu Rakyat yang diusahakan petani di atas lahan/tanah milik
sendiri.
2. Meningkatkan produksi gula nasional dan pendapatan petani tebu melalui pola
TRI.
3. Mengusahakan Pabrik gula dalam fungsinya dan peranan sebagai Pimpinan
Kerja Operasional Lapangan (PKOL) guna melaksanakan alih teknologi
budidaya tebu petani kepada petani.
4. Mengikutsertakan KUD dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani TRI
agar produksi gula dan pendapatannya meningkat (Asnur, 1999).
Setelah TRI berjalan, perkembangan tebu semakin pesat. Tahun 1975 – 1980 luas
lahan tebu dari 104.777 ha menjadi 188.772 ha. Pada periode yang sama, produksi
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Gula Tebu di Indonesian Tahun 1930 – November 1990
Tahun Luas areal (Ha) Rendemen (%) Hablur (Ku/Ha) Jumlah Pabrik Rakyat Pabrik Rakyat Pabrik Rakyat Hablur (ton)
1930 196.592,0 - 11,32 - 147,9 - 2.907.098
Program TRI dikelola dalam wadah koordinasi Bimas dengan melibatkan
lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI, KUD, dan pabrik gula. Dalam program
ini, BRI berperan sebagai pemberi kredit dan KUD sebagai penyalur kredit. Tugas
pabrik gula dalam program TRI meliputi penyediaan bibit tebu, pimpinan kerja,
memberikan bimbingan teknis di lapangan bagi para petani, serta pengolah tebu
Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Gula Tebu di Indonesia Tahun 1994 –
Terlihat pada Tabel 2 bahwa produksi gula sempat menurun pada Tahun 1998 –
2003 dan meningkat kembali pada Tahun 2004. Namun, konsumsinya tetap
melebihi produksi yang dihasilkan. Ini menandakan masih belum cukupnya upaya
pemerintah dalam menggalakkan produksi gula.
Dalam pelaksanaannya, usahatani tebu memerlukan lahan yang luas. Untuk
memudahkan, maka dibentuklah kelompok-kelompok tani. Luas lahan setiap
kelompok biasanya antara 10 – 25 ha. Tiap kelompok merupakan gabungan
beberapa petani dengan luas antara 0,2 – 0,3 ha. Sekarang, kelompok-kelompok
tani tersebut tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
Ternyata program TRI yang diusahakan pemerintah belum dapat mencapai
sasaran secara mantap. Banyak masalah yang dihadapi, terutama dalam
lahan, biaya usaha tani, penerapan teknis budidayaa, tenaga kerja, sampai pada
masalah panen dan pasca panen (Tim Penulis PS, 1994).
Petani dengan lahan sempit dan pengairan yang baik, umumnya sangat berat
untuk merelakan lahannya ditanami tebu. Petani TRI kebanyakan memiliki modal
yang kecil dan lahan yang sempit sehingga mereka bertindak lebih selektif dalam
memilih pola usaha tani. Dalam membiayai usahatani tebu, pemerintah
memberikan kredit melalui BRI yang disalurkan lewat KUD setempat. Kredit
yang diharapkan dapat membantu petani dalam membiayai usahatani tebu ini
ternyata sukar dicairkan. Pihak KUD sendiri tidak sanggup mengatasi mengingat
terbatasnya dana yang ada. Masih berkaitan dengan masalah kredit, banyak petani
yang menyalahgunakan fasilitas kredit (Tim Penulis PS, 1994).
Penyuluhan dilakukan oleh mandor pabrik kepada ketua kelompok tani dan
selanjutnya meneruska kepada para petani. Namun, teknologi belum dapat diserap
secara sempurna oleh petani sehingga mengakibatkan rendahnya rendemen tebu.
Rendemen tebu yang tinggi menjadi idaman para petani tebu. Sebab, semakin
tinggi rendemen tebu, semakin tinggi pula pendapatan yang mereka peroleh. Pada
dasarnya, pendapatan petani tebu banyak ditentukan oleh tingkat produksi, harga
input, harga produksi dan sistem bagi hasil (Tim Penulis PS, 1994).
Dalam praktiknya, salah satu desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten
Deli Serdang yaitu Desa Bulu Cina, di desa ini usaha tani tebu dilakukan dengan
sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang terbagi atas TRI Mitra dan TRI
Murni. TRI Mitra diusahakan di atas lahan PTPN II dengan sewa lahan per ha Rp.
ini tidak ada lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI, KUD ataupun penyuluh
yang membantu petani dalam mengelola usaha tani tebu dengan sistem TRI
kecuali Pabrik Gula sebagai jasa penggiling. Hal ini tidak sesuai dengan Program
TRI yang diusahakan pemerintah bahwa Program TRI dikelola dalam wadah
koordinasi Bimas dengan melibatkan lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI,
KUD dan pabrik gula. Dari sini, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana
sebenarnya mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di desa
tersebut.
Untuk TRI Mitra dan TRI Murni, bibit dibeli dari PTPN II seharga Rp.
350/batang dengan kebutuhan per hektar 10.000 batang dan hasil panen digiling di
Pabrik Gula PTPN II Sei Semayang dengan pembagian hasil 35% untuk PTPN II
dan 65% untuk petani. Pendapatan petani per ton tebu bisa dihitung berdasarkan
jumlah gula yang dapat dihasilkan melalui penggilingan tebu dikali dengan harga
gula dan dipotong ongkos tebu angkut.
Hasil panen yang diperoleh TRI Mitra biasanya lebih tinggi dari TRI Murni
karena pada TRI Mitra hasil panen harus sesuai dengan ketentuan atau target yang
ditetapkan oleh pabrik. Jika tidak mencapai target, maka petani tidak diizinkan
lagi untuk menyewa lahan. Pada PC (Plant Cane) yaitu tanaman tebu sistem awal,
hasil TRI Mitra harus mencapai 65 ton/ha sedangkan hasil TRI Murni bergantung
pada perlakuan petani itu sendiri karena diusahakan di atas lahan sendiri dalam
pemeliharaan dan perawatannya. Biasanya hasil TRI Murni berkisar antara 50 –
60 ton/ha pada tanaman tebu sistem awal (Plant Cane). Dari hal ini, tentu ada
Mitra dan TRI Murni dan peneliti bermaksud untuk mengetahui berapa besar
perbedaan pendapatan masyarakat sistem TRI Mitra dengan sistem TRI Murni.
Saat ini, banyak petani tebu mulai enggan untuk menanam tebu dan beralih
menanam komoditi lain. Pendapatan yang rendah dibarengi dengan kewajiban
untuk membayar sewa lahan membuat petani merugi. Kondisi ini perlu dicari
jalan keluar dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang
serta ancaman untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tani tebu. Dari
hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana strategi pengembangan
pengelolaan usaha tani tebu dengan sistem TRI Mitra dan sistem TRI Murni.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan usaha tani tebu dengan
sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Desa Bulu Cina dengan membahas
mekanisme pelaksanaan, besar pendapatan dan strategi pengembangan dari
pengelolaan usaha tani tebu tersebut.
1.2Identifikasi Masalah
1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di
daerah penelitian?
2) Berapa besar perbedaan pendapatan masyarakat Sistem TRI Mitra dengan
Sistem TRI Murni?
3) Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan usaha tani tebu dengan
Sistem TRI Mitra?
4) Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan usaha tani tebu dengan
1.3Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi
(TRI) di daerah penelitian.
2) Untuk mengetahui besar perbedaan pendapatan masyarakat Sistem TRI
Mitra dengan Sistem TRI Murni
3) Untuk menentukan strategi pengembangan pengelolaan usahatani tebu
dengan Sistem TRI Mitra
4) Untuk menentukan strategi pengembangan pengelolaan usahatani tebu
dengan Sistem TRI Murni
1.4Kegunaan Penelitian
1) Sebagai bahan informasi bagi petani tebu dalam mengembangkan usaha
taninya.
2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam
membuat kebijakan untuk menangani permasalahan dan pengembangan
usahatani tebu.