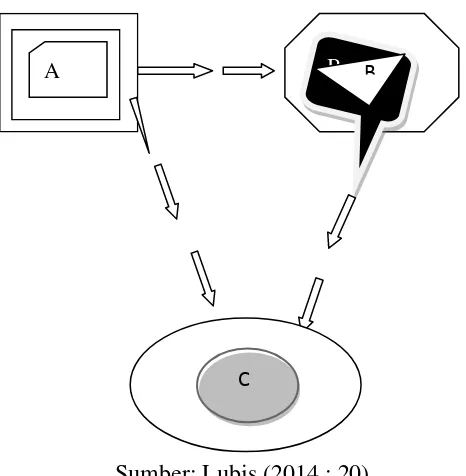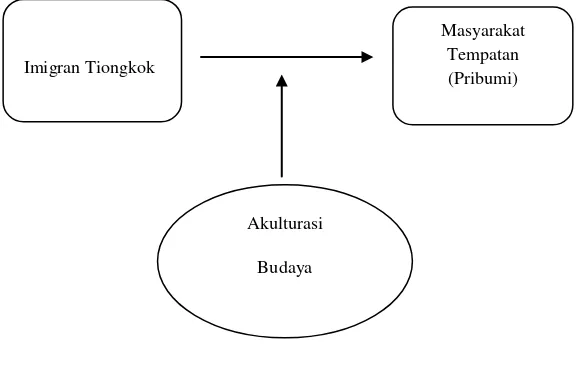BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Paradigma Kajian
2.1.1 Paradigma Interpretif
Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu
distruktur atau bagaimana bagian-bagian berfungsi. Dalam definisi lainnya
menurut Harmon (dalam Moleong, 2009:49) Paradigma merupakan cara yang
mendasar untuk mempersepsi, berpikir,menilai, dan melakukan dua hal:
1. Membangun dan mendefinisikan batas-batas
2. Menceritakan kepada anda bagaimana seharusnya melakukan sesuatu di
dalam batas-batas tersebut sehingga menjadi berhasil.
Dalam keilmuannnya ada bermacam-macam paradigma yang berlaku,
akan tetapi ada 2 yang mendominasi ilmu pengetahuan, yaitu, scientific paradigm
(paradigma ilmiah) atau yang biasa disebut sebagai kuantitatif dan naturalistic
paradigm (paradigma natural) yang biasa disebut sebagai penelitian kualitatif.
Paradigma ilmiah bersumber dari pandangan positivisme sedangkan paradigma
alamiah bersumber dari fenomenologisme.
Penelitian sosial merupakan suatu penelitian yang mengacu kepada pola
dinamis manusia yang selalu berbeda-beda atau berubah setiap harinya. Dalam
penelitian ini mempunyai ruang lingkup humanistik yang berusaha mengkaji
bagaimana sebenarnya akulturasi yang terjadi terhadap pekerja Tiongkok yang
bekerja di Indonesia. Maka dalam kajian penelitian ini paradigma yang tepat
adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif.
Kualitatif-interpretif merupakan metode yang berasal dari paradigma
konstruktivis yang memandang jika manusia merupakan makhluk sosial yang
melibatkan niat, kesadaran dan motif atau alasan-alasan tertentu, yang tidak dapat
dijabarkan melalui pendekatan positivistik atau paradigma ilmiah. Selain karna
ruang lingkup penelitian yang diteliti ini berada dibidang sosial, penulis memakai
pendekatan interpretif karena ia juga mampu menjabarkan realitas sosial secara
berasal dari data lapangan, studi kepustakaan dan sudut pandang atau kacamata
peneliti.
2.2Kerangka Teori
Kerangka teoretis adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur
yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Dalam kerangka teoretis
secara logis dikembangkan, digambarkan, dan dielaborasi jaringan-jaringan dari
asosiasi antara variabel-variabel yang diidentifikasi melalui survey atau telaah
literatur (Silalahi, 2009:92). Maka dari penelitian ini didapatkan beberapa teori
dasar sebagai penghubung dalam masalah yang sedang peneliti ini, adapun teori
yang dipakai sebagai berikut:
2.2.1 Komunikasi
Sejak dahulu kala manusia sudah mulai mempelajari cara untuk
berinteraksi dengan sesamanya. Para ahli memperkirakan manusia mulai mampu
berinteraksi sekitar 90.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Pada masa itu bentuk
bahasa lisan biasanya mulai dipakai untuk menjembatani pemikiran, hasrat,
pengetahuan, dalam mempertahankan hidup dan eksistensi mereka di kehidupan
yang liar (Amir dkk, 2010:5). Sejak saat itu komunikasi manusia pada zaman
dahulu terus mengalami perkembangan,seiring dengan perkembangan populasi
manusia kuno, mereka mulai berusaha merepresentasikan apa yang ada di dalam
pikirannya dan dituangkan kedalam relif dan goresan-goresan abstrak seperti
lukisan atau gambar didinding-dinding gua.
Salah satu contoh dari perkembangan komunikasi yang mulai mengarah
ke bentuk tulisan ini ialah ditemukannya lukisan cap tangan dan gambar pada saat
berburu binatang, gambar benda-benda angkasa dan gambar-gambar lainnya yang
abstrak. Lukisan tersebut diperkirakan berumur kurang lebih 15.000 tahun.
selanjutnya manusia terus mengembangkan teknik komunikasinya agar lebih
efektif dan menjangkau khalayak luas, manusia pada zaman dahulu tepatnya
seperti pada masyarakat kuno Sumeria dan Mesir mulai mengembangkan
komunikasi tulisan menggunakan daun papirus yang dijemur hingga kering. Tidak
hanya mereka yang mulai berinovasi dalam mengembangkan komunikasi,
menggunakan alat atau media seperti bangsa Romawi yang merupakan salah satu
contoh peradaban manusia yang menggunakan media dalam proses komunikasi
mereka.
Hingga sekarang manusia seakan tak pernah berhenti mengeluarkan
terobosan-terobosan penting melalui teknologi dan inovasi yang pada hakekatnya
dapat mempengaruhi kualitas dan cara berkomunikasi umat manusia modern.
Seiring dengan majunya teknologi dan kebutuhan informasi yang semakin cepat
maka komunikasi akan terus mengalami perkembangan dalam kehidupan
manusia, sehingga tak bisa dipungkiri lagi jika komunikasi merupakan hal yang
sangat vital yang telah mempengaruhi peradaban manusia.
Secara epistemologi, komunikasi berasal dari bahasa latin (communicatio)
dan bersumber dari kata communis yang artinya “sama.” Sama di sini
dimaksudkan dalam “sama makna”, secara sederhana proses komunikasi
bermuara pada usaha untuk mendapatkan kesamaan makna atau pemahaman pada
subjek yang melakukan proses komunikasi tersebut.
Dalam definisi para ahli seperti menurut Carl L. Hovland menyatakan
bahwa komunikasi merupakan proses di mana seorang (Komunikator)
menyampaikan perangsang-perangsang (lambang-lambang dalam bentuk
kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain (Komunikan). Harold D. Laswell
menjelaskan jika kegiatan komunikasi dilakukan dengan cara menjawab
pertanyaan “Siapa-berkata apa-melalui saluran apa-kepada siapa-dengan efek apa
(who-says what-in which channel-to whom-with what effect) yang kemudian
rangkaian proses ini dikenal dengan sebutan model Laswell.
2.2.1.1Dimensi Ilmu Komunikasi
A. Bentuk / Tatanan Komunikasi
Dalam bentuk/ tatanannya komunikasi juga dapat dibagi menjadi beberapa
bagian, yaitu:
1. Komunikasi antar pribadi
a. Komunikasi antarpribadi
b. Komunikasi Intrapribadi
2. Komunikasi Kelompok
b. Komunikasi Kelompok Besar
3. Komunikasi Organisasi
4. Komunikasi Massa
a. Komunikasi massa cetak
b. Komunikasi massa elektronik
B.Sifat Komunikasi
Berdasarkan sifatnya komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Komunikasi Verbal
a. Komunikasi lisan
b. Komunikasi Tulisan
2. Komunikasi nonverbal
a. Komunikasi kial
b. Komunikasi gambar
3. Komunikasi tatap muka
4. Komunikasi bemedia
C.Tujuan Komunikasi
Berdasarkan tujuannya, komunikasi terbagi empat, yakni:
1. Untuk mengubah sikap
2. Untuk mengubah opini/pendapat
3. Untuk mengubah perilaku
4. Untuk mengubah masyarakat
D. Fungsi Komunikasi
1. Menginformasikan
2. Mendidik
3. Menghibur
4. Mempengaruhi
E. Bidang Komunikasi
1. Komunikasi Sosial
2. Komunikasi Bisnis
3. Komunikasi Politik
4. Komunikasi Internasional
6. Komunikasi Pembangunan
7. Komunikasi Tradisonal
8. Komunikasi Lingkungan.
2.2.2 Komunikasi AntarBudaya
Komunikasi merupakan suatu sarana yang digunakan manusia sebagai alat
untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial
dengan orang di sekitar,untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berfikir,
berperilaku seperti yang kita inginkan dan juga mengendalikan lingkungan fisik
dan psikologis manusia.Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi suatu
Pengantar (2007:7) mengatakan jika komunikasi merupakan sebuah mekanisme
untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat baik secara horizontal,
maupun vertikal, dari suatu generasi ke generasi lainnya.
Komunikasi sebenarnya dipengaruhi oleh budaya-budaya yang melekat
dalam kedirian manusia sehingga kita bisa mengenal identitas kebudayaan
seseorang hanya dari bahasa yang dipakainya, tutur kata yang diucapkan dan
kalimat pesan yang disampaikannya.
Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman,
kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan
ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh
sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu atau
kelompok. Budaya juga merupakan pewarisan sosial yang mengandung
pandangan yang sudah dikembangkan jauh sebelum kita lahir. Dalam praktiknya
budaya sangat berkaitan dengan komunikasi, sebab budaya mempengaruhi cara
orang untuk berkomunikasi dan budaya dapat pula dikenal dan dipelajari melalui
komunikasi. Secara umum, komunikasi antarbudaya ialah suatu alat untuk
menyatakan identitas sosial dan menjembatani perbedaan antarbudaya melalui
proses perolehan informasi baru, mempelajari sesuatu yang baru yang tidak
pernah ada dalam kebudayaan,serta sekedar mendapat hiburan atau melepaskan
diri. Menurut Tubbs dan Moss, komunikasi antarbudaya terjadi di antara
orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (ras,etnis,sosio ekonomi,atau
Menurut Samovar dan Porter (dalam Lubis, 2014 : 18) kebudayaan itu
dapat dipelajari dan budaya itu dapat juga dipertukarkan, oleh karena itu budaya
bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikasi dan makna
yang dimiliki tiap-tiap individu. Konsekuensinya, perbendaharaan inilah yang
akan menimbulkan segala macam kesukaran dalam keberlangsungan komunikasi.
Samovar dan porter juga menggambarkan suatu model komunikasi antarbudaya
yang menggambarkan perubahan budaya yang terjadi ketika ada interaksi
antarbudaya, seperti gambar di bawah ini:
Gambar 2.1.2 : Model Komunikasi Antarbudaya Samovar dan Porter
Sumber: Lubis (2014 : 20)
Komunikasi antar budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sisi
komunikasi antarpribadi, sebab komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi
antarpribadi yang dengan perhatian khusus dilihat pada faktor-faktor kebudayaan
yang mempengaruhinya. Pada kajian komunikasi antarbudaya, benang merah
yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip hubungan antarpribadi seperti yang
dituangkan oleh Lubis dalam bukunya Pemahaman Praktis Komunikasi
Antarbudaya (2014 : 102) yaitu :
A B B
a. Homofili
Homofili merupakan derajat kesamaan antara individu-individu yang terlibat
dalam interaksi antarpribadi. Seringkali kita mendapatkan bahwa kita lebih
percaya pada orang-orang yang sudah dikenal daripada orang yang masih asing,
atau kadang-kadang sesudah berkenalan dengan seseorang kita telah merasakan
kecocokan dengannya. Salah satu yang dapat menjelaskan ini ialah adanya
persepsi akan identifikasi, yakni dirasakan semacam hubungan karena adanya
kesamaan, baik dalam segi penampilan,unsure, pendidikan, etnisitas, tempat
tinggal atau wilayah geografi, pandangan politik moral, dan lain sebagainya. Hal
ini merupakan modal dasar sebelum berlanjut kepada interaksi yang lebih akrab
dilakukan. Intensitas hubungan antarpribadi yang baik akan memunculkan
kepercayaan terhadap komunikan atau sebaliknya penilaian komunikan terhadap
komunikator.
b. Kredibilitas
Percaya atau tidaknya seseorang kepada orang lain tergantung kepada
beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas komunikasi yang dilakukan,
yaitu:
1. Kompetensi: dengan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang
dipersepsikan dengan orang lain.
2. Karakter : persepsi tentang moral, nilai-nilai, etika, dan integritas komunikasi.
3. Ko-orientasi : derajat kesamaan yang dipersepsikan mengenai tujuan dan nilai.
4. Kharisma : derajat kepercayaan akan kualitas-kualitas kepemimpinan khusus
yang dipersepsikan, terutama dalam keadaan krisis.
5. Dinamika: derajat tentang entusiasme dan perilaku-perilaku nonverbal yang
dipersepsikan.
6. Jiwa sosial : derajat keramahan dari seseorang.
c. Kesediaan membuka diri (Self-disclosure)
Self Disclosureterjadi bilamana seseorang menyampaikan informasi tentang
dirinya sendiri pada orang lain. Kesediaan membuka diri menunjukkan adanya
kepercayaan yang terjalin ketika komunikasi dilakukan antara komunikan dan
menjalin interaksi mendapatkan kepercayaan dan kesukaan. Jika saling percaya
meningkat maka makin meningkat pula keterbukaan (self disclosure).
d. Dominasi dan Submisi
Dalam kesediaan membuka diri tingkat hubungan antarpribadi tidak sama
antara pelaku komunikasi. Hubungan antarpribadi diatur oleh suatu hubungan
dominasi dan submisi, misalnya antara majikan dan bawahan, dokter dan pasien,
orang tua dan anak, guru-murid dan lain sebagainya. Dominasi dan submisi
dipengaruhi oleh peranan sosial dalam masyarakat dan status dari satu individu di
dalam organisasinya.
e. Formalitas dan Informalitas
Formalitas dan Informalitas juga mengatur keterbukaan diri, sebab dalam suatu
sistem telah diatur sebuah tata cara yang disebut dengan manajemen, sistem ini
terkait dengan tingkatan atau hirarki, pangkat, status sosial, umur, rekan sebaya
dan lain sebagainya. Konsep formalitas – dan informalitas ini dipandang sebagai
tolak ukur kedekatan antar pribadi seseorang.
f. Ketertarikan AntarPribadi
Ketertarikan antarpribadi sangat jelas menggambarkan keterbukaan diri
seseorang, sebab dari sinilah awal mula pelaku komunikasi memulai interaksi, dan
berlanjut menuju akulturasi.
g. Hubungan-Hubungan Kerja Antarpribadi
Hubungan kerja antar pribadi jika ditinjau dalam konteks komunikasi antar
budaya juga memengaruhi keterbukaan diri seseorang, sebab hubungan ini mau
tak mau harus diterapkan dalam interaksi sehari-hari seperti dalam pekerjaan,
persahabatan, pergaulan.
Berbicara mengenai komunikasi antarbudaya tidak terlepas dari
komunikasi yang efektif, sebab telah disinggung di atas jika komunikasi
antarbudaya merupakan suatu alat untuk menjembatani perbedaan budaya yang
dimiliki oleh masing-masing individu, maka dari itu, efektivitas komunikasi
antarbudaya sangat di tentukan oleh kesadaran pada setiap individu, untuk
berusaha mempelajari tatanan kebudayaan yang berasal dari luar dirinya, dan
menciptakan suatu hubungan berkelanjutan, dan semakin meningkat, sehingga
budaya berbeda, kemudian efektivitas Komunikasi antarbudaya (dalam Liliweri,
2001 :171) yang efektif harus memperhatikan empat syarat, yaitu:
1. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia
2. Menghormati budaya lain sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang
kita kehendaki
3. Menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara
bertindak dan
4. Komunikator antarbudaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup
bersama orang lain.
Dalam komunikasi antarbudaya juga diperlukan kemampuan atau kompetensi
dasar yang harus dimiliki oleh tiap-tiap komunikator maupun komunikan
antarbudaya yang meliputi:
1. kemampuan seseorang untuk menyampaikan semua maksud atau isi hati secara
profesional sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dia tampilkan
secara prima
2. kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara baik, misalnya mampu
mengalihbahasakan semua maksud dan isi hatinya secara tepat.
3. Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan kebudayaan pribadinya dengan
kebudayaan yang sedang dihadapinya meskipun dia harus berhadapan dengan
berbagai tekanan dalam proses tersebut.
4. Kemampuan seseorang untuk memberikan fasilitas atau jaminan bahwa dia
bisa menyesuaikan diri atau bisa mengelola pelbagai tekanan kebudayaan lain
terhadap dirinya. (Lubis, 2014 : 145 ).
2.2.3 Akulturasi Budaya
Pada awalnya manusia mempelajari dan menginternalisasi pola-pola
budaya yang ada di sekitarnya untuk kemudian dijadikan bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan individu tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan
sebutan enkulturasi. Kemudian ketika individu atau kelompok tertentu mulai
memasuki budaya yang berbeda dari budaya awalnya dan berusaha untuk
mempelajari serta mengadopsi nilai-nilai dari budaya barunya tersebut, maka
Akulturasi sendiri merupakan suatu proses di mana imigran menyesuaikan
diri dengan memperoleh budaya pribumi. Akulturasi mengacu pada proses di
mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung
dengan kultur lain. Akan tetapi walaupun kedua nya terlibat pertukaran budaya,
menurut Mulyana & Rakhmat akulturasi akan terlihat lebih dominan terhadap
masyarakat pendatang dibandingkan dengan masyarakat pribumi.
Proses komunikasi sangat mendasari proses akulturasi seorang imigran,
karena melalui komunikasi para imigran yang datang ke suatu wilayah tertentu
memperoleh pola-pola budaya yang ada di wilayah tersebut. Lewat komunikasi
juga para pendatang akan memahami dan mengidentifikasi dan menginternalisasi
lambang-lambang yang berlaku baik segi bahasa, struktur sosial masyarakat, dan
lain sebagainya. Dalam proses identifikasi tersebut para imigran biasanya
mengalami trial dan error dalam interaksinya baik dalam hal bahasa,
simbol-simbol nonverbal, perbedaan dan pengaturan ruang serta jarak antar pribadi,
ekspresi wajah, gerak mata, gesture tubuh lainnya, dan persepsi tentang penting
tidaknya perilaku nonverbal serta dimensi-dimensi budaya pribumi yang
tersembunyi, yang mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh masyarakat pribumi.
Hal di atas semakin mengokohkan pernyataan jika semakin jauh perbedaan
kebudayaan yang dimiliki oleh para imigran terhadap penduduk pribumi maka
semakin sulit pula masing-masing budaya, baik dari pihak imigran maupun
pribumi untuk mengenal.
Menurut Samovar & Porter dalam bukunya Komunikasi Lintas Budaya
(2010 : 482) sukses atau tidaknya akulturasi yang terjadi didasarkan pada strategi
adaptasi yang dilakukan oleh pendatang asing terhadap kultur tuan rumah, adapun
strategi adaptasi yang dijelaskan yaitu:
1. Buatlah Hubungan Pribadi dengan Budaya Tuan Rumah
Hubungan langsung dengan budaya tuan rumah mendorong dan
memfasilitasi sukses atau tidaknya proses adaptasi dengabn suatu budaya.
Seorang pendatang diwajibkan untuk melakukan kontak langsung melalui
percakapan sehari-hari dari orang yang memiliki budaya tersebut serta melakukan
hubungan pertemanan terhadap mereka.
Mengembangkan pandangan dan pengetahuan mengenai budaya baru yang
akan dimasuki merupakan langkah terpenting di dalam meningkatkan kemampuan
komunikasi antarbudaya, sehingga dari proses tersebut kita akan mendapatkan
kesadaran budaya yang berarti mengenal pola budaya sendiri dan juga sekaligus
memahami jika pola budaya orang lain berbeda dengan budaya yang kita miliki.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya
Cara terbaik dalam mempelajari budaya baru ialah ikut serta berperan aktif
di dalam budaya tersebut. Hadirilah kegiatan sosial, religius dan budaya dan
cobalah terus berinteraksi dengan mereka maka dalam beberapa kesempatan
penduduk tuan rumah akan mempersilahkan anda untuk membaur dan
membagikan budaya mereka dengan anda.
Manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan bersinggungan dengan
kebudayaan lain. Singgungan antarbudaya ini akan memiliki efek psikologis yang
biasanya dirasakan langsung oleh para pendatang baru yang memasuki wilayah
kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan yang telah ada dan yang telah
terenkulturasi di dalam dirinya. Kejanggalan-kejanggalan yang berasal dari
budaya yang berlainan ini disebut dengan kejutan budaya (culture shock).
Culture shockdidefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul
akibat kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam
hubungan sosial. Tanda-tanda atau petunjuk–petunjuk itu meliput seribu satu cara
yang kita lakukan dalam mengendalikan diri kita sendiri untuk menghadapi situasi
sehari-hari (Mulyana dan Rakhmat dalam Lubis, 2014: 177). Culture shock
dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pendatang yang tinggal menetap untuk
sementara waktu pada suatu wilayah tertentu dan pendatang yang memilih untuk
menetap secara permanen di dalam wilayah tertentu.
Reaksi terhadap culture shockatau gegar budaya biasanya bervariasi antara
individu satu dengan individu lainnya, dan gegar budaya dapat juga muncul pada
waktu yang berbeda-beda. menurut Samovar porter & Mc.Daniel (dalam Lubis,
2014; 178) mengatakan jika ada 9 reaksi yang biasanya terjadi,dan sering dialami
oleh individu saat mengalami culture shock, yaitu:
1. Antagonis/ memusuhi lingkungan baru
3. Rasa penolakan
4. Gangguan lambung dan sakit kepala
5. Homesick/rindu rumah
6. Rindu pada teman dan keluarga
7. Merasa kehilangan status dan pengaruh
8. Menarik diri
9. Menganggap orang – orang dalam budaya tuan rumah tidak peka.
Fase dalam culture shock terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu:
1. Fase Optimistik, fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan, dan
euphoria, sebagai antisipasi individu sebelum memasuki budaya baru.
2. Fase Masalah Kultural, Fase kedua di mana masalah dengan lingkungan baru
mulai berkembang, fase ini biasanya ditandai dengan rasa kecewa dan
ketidakpuasan akan harapan awal. Ini adalah periode krisis dalam periode
culture shock, di mana ke Sembilan tekanan yang telah dijelaskan di atas
terjadi.
3. Fase Kesembuhan, fase ketiga di mana orang mulai mengerti dan mengenal
budaya barunya.
4. Fase Penyesuaian, fase terakhir di mana orang telah mengerti elemen kunci
dari budaya barunya(nilai-nilai khusus, keyakinan dan pola komunikasi) fase
inilah yang nantinya akan mengarahkan suatu individu menuju ketahap
selanjutnya dari akulturasi, yaitu tahap asimilasi.
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari peneliti dilandasi
dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah
penelitian. Hal ini juga sama halnya seperti yang dikatakan jika kerangka konsep
sebagai hasil pemikiran yang rasional merupakan uraian yang bersifat kritis dan
memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai dan dapat
mengantarkan penelitian pada rumusan hipotesa (Nawawi,2001:40). Dalam
kerangka pemikiran ini, peneliti membuat konsep sederhana yang bermula melihat
bagaimana para imigran Tiongkok mempelajari, dan menggali budaya barunya
terakulturasi dalam diri mereka masing-masing. Berikut adalah kerangka
pemikiran dari penelitian ini.
Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran Akulturasi
Budaya