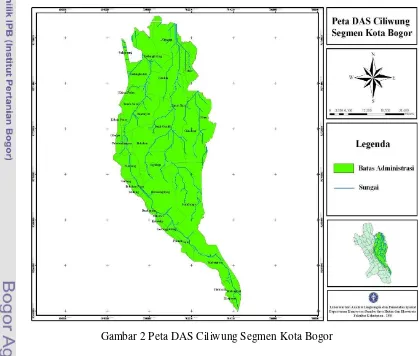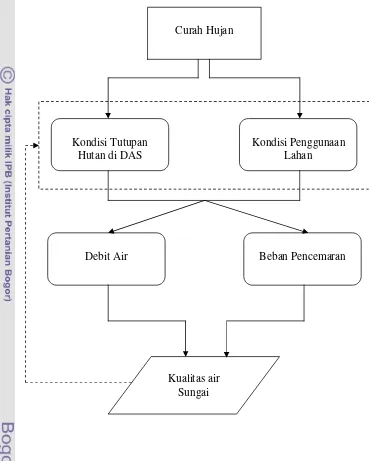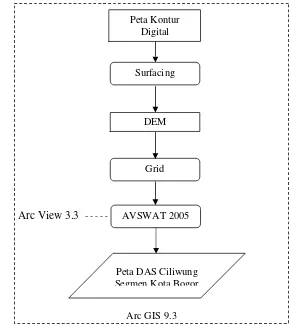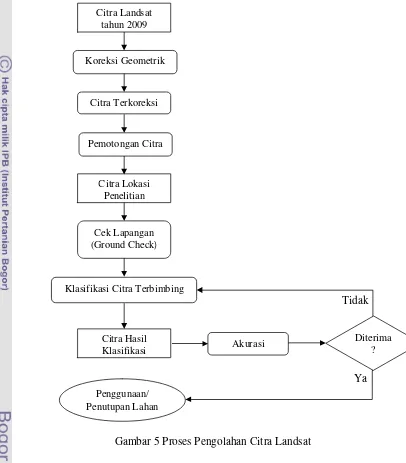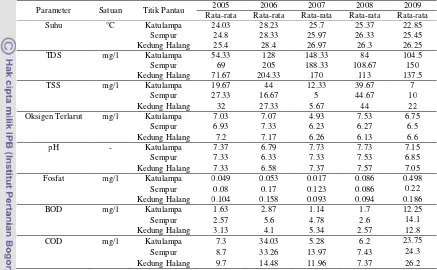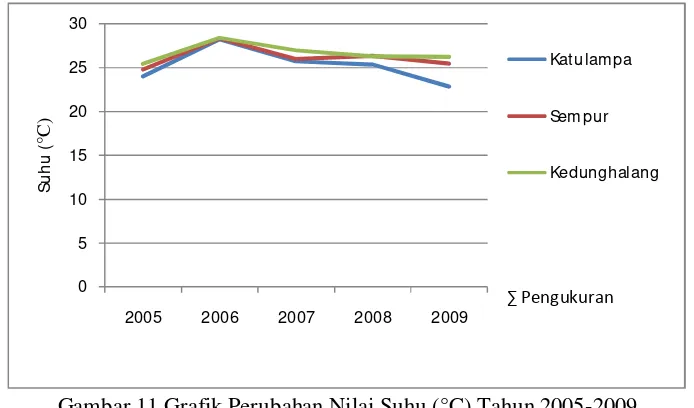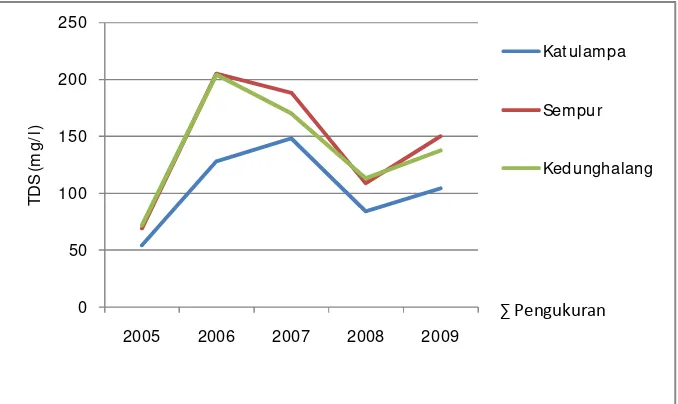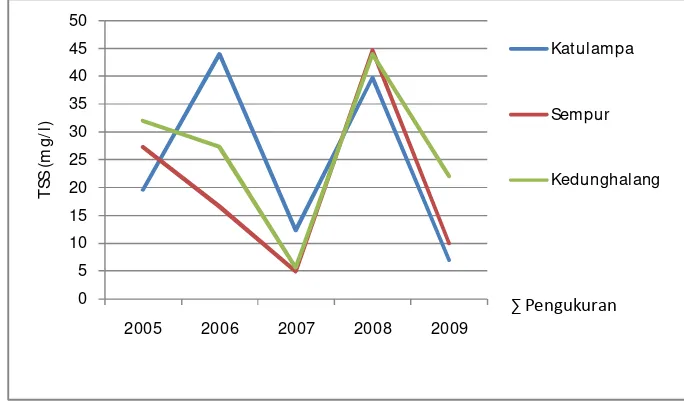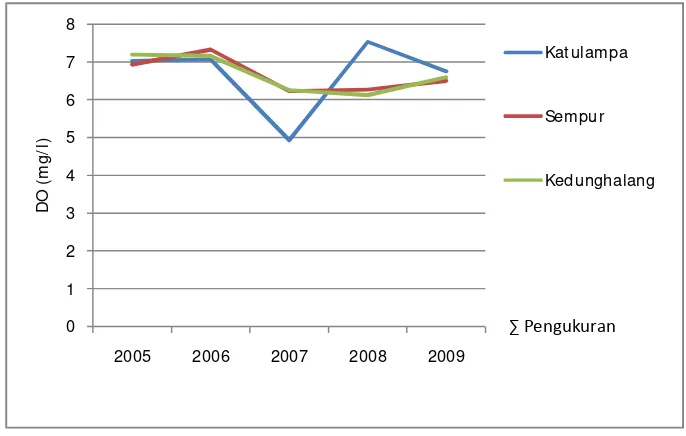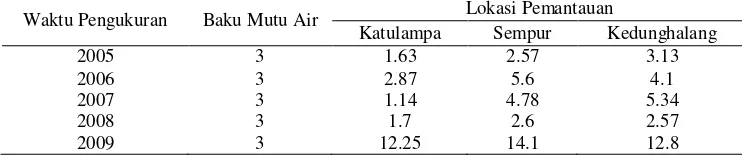PENCEMARAN SUNGAI CILIWUNG DI SEGMEN KOTA BOGOR
DANY TROFISA
DEPARTEMEN
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN
Kajian Beban Pencemaran dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung di Segmen Kota Bogor. Oleh Dany Trofisa (E34050861) di bawah bimbingan Ir. Agus Priyono, MS dan Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc.
Perkembangan kependudukan di DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor mendorong peningkatan kebutuhan hidup sehingga bermunculan berbagai macam industri dan peternakan. Sungai Ciliwung sebagai ekosistem terbuka menerima beban pencemaran melalui saluran-saluran air dari berbagai sumber pencemar seperti limbah rumah tangga, industri, peternakan dan pertanian. Disamping itu, pemanfaatan air sungai Ciliwung oleh masyarakat juga menyebabkan penurunan kualitas dan mutu air sungai. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan industri-industri serta peternakan dengan menggunakan SIG sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung secara keseluruhan.
Penelitian ini dilakukan di wilayah DAS Ciliwung segmen Kota Bogor. Pengambilan data sekunder pada Februari - Maret 2010, sedangkan data primer ke lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2010. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor, mengevaluasi perkembangan kondisi mutu air Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir di segmen Kota Bogor, menghitung besar beban pencemaran setiap sumber-sumber pencemar, menghitung besar daya tampung beban pencemaran. Metode yang digunakan untuk data sekunder adalah inventarisasi data dari beberapa sumber/instansi meliputi: data kualitas air, debit sungai, data kependudukan, dan peta tutupan lahan kota bogor, sedangkan untuk data primer adalah observasi lansung ke industri-industri dan peternakan serta wawancara masyarakat mengenai persepsi dan perilaku mereka terhadap sumberdaya air Sungai Ciliwung.
Sumber pencemar yang mencemari Sungai Ciliwung di Segmen Kota Bogor berasal dari limbah domestik, industri dan peternakan. Sumber pencemar ini banyak berada di pinggiran sungai. Nilai parameter kualitas air seperti suhu, TDS, TSS, DO, pH dan Fosfat masih berada dalam baku mutu air kecuali BOD dan COD. Status mutu air berdasarkan metode IKA dan Storet tergolong dalam kategori sedang-buruk. Hal ini karena akumulasi pencemaran dari arah hulu. Limbah domestik memberikan kontribusi beban pencemaran yang besar jika dibandingkan dengan limbah industri dan peternakan. Besarnya beban pencemaran yang bersumber dari domestik, industri dan peternakan telah melebihi daya tampung beban pencemaran. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan tercemar. Berdasarkan hasil wawancara kepada 150 responden sebanyak 30.67% responden masih memanfaatkan sungai Ciliwung dan banyak digunakan untuk kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK). Pada tahun 2007-2009 pengunaan lahan di Kota Bogor setiap tahun cenderung beralih menjadi permukiman. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin pesat.
Terdapat sumber- sumber pencemar di DAS Ciliwung Kota Bogor seperti limbah dari domestik, industri, peternakan dan pertanian. Kualitas air Sungai Ciliwung mengalami penurunan dari hulu ke hilir di segmen Kota Bogor, ditandai dengan peningkatan BOD dan COD yang melebihi baku mutu air berdasarkan PP No.82 tahun 2001. Status mutu air Sungai Ciliwung segmen Kota Bogor berdasarkan metode IKA dan Storet tergolong kategori sedang-buruk. Beban pencemaran banyak bersumber dari limbah domestik. Beban pencemaran limbah domestik potensial (843,36 ton/bulan BOD, 1.495,47 ton/bulan COD, 112,16 ton/bulan TN, 679,76 ton/bulan TP) dan riil (351,36 ton/bulan BOD, 784,75 ton/bulan COD, 58,86 ton/bulan TN, 356,71 ton/bulan TP). Daya tampung maksimum berada pada bulan Februari dan minimum berada pada bulan September.
Study of Waste Discharge and Pollution’s Capacity of Ciliwung River at Bogor City’s Segment. By Dany Trofisa (E34050861) under supervise of Ir. Agus Priyono, MS and Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc.
Population growth in DAS Ciliwung at Bogor City’s segment lead to increasing of daily need, thus emerge many kinds of industry and farms. Ciliwung River as an open ecosystem receives waste discharge through water channels and many source of pollutants such as household waste, industrial waste, farming and agricultural waste. Moreover, water utilization of Ciliwung River by community causes the decreasing of river water’s quality. Thus need an inventory and mapping of industries and also farms by GIS as a base of efforts to control the pollution of Ciliwung River entirely.
This research carried out in region of DAS Ciliwung at Bogor City’s segment. Secondary data collection held on February – March 2010, while primary data collection in field held on October – November 2010. The objectives of this research are to identify the source of pollution in DAS Ciliwung at Bogor City’s segment, to evaluate the conditional development of ciliwung river water quality from upstream to downstream in bogor city’s segment, to calculate the total of waste discharge of each source of pollutant, and to calculate the pollution’s capacity of DAS Ciliwung at Bogor City’s segment. Method used to collect secondary data was data inventory from some source/instances, included data of water quality, data of river’s debit, data of population, and map of Bogor City’s land cover, while method for primary data was direct observation to industries and farms and also interview to community about their perceptions and habits to water resource of Ciliwung River.
Source of pollutant which pollutes Ciliwung River at Bogor city’s segment originated from domestic, industrial and farming wastes. These pollutant sources were mostly located in the edge of river. Water quality parameters value such as temperature, TDS, TSS, DO, pH, and Phosphate were still in ambience of water quality standard, exception for BOD and COD. Status of water quality, based on IKA and Storet method, was included into moderate-worse category. It was caused by the accumulation of pollutant from the upstream. Domestic waste has a greater contribution than industrial and farming wastes. Amount of waste discharge from domestic, industry and farming have passed the ambience of waste discharge capacity. It indicates that the water has been polluted. Based on interview result fro 150 respondents, 30.67% of them still use Ciliwung River mostly for self hygiene. At 2007-2009, land use of Bogor City keep changing into settlements. It was caused by the growth of population.
There are source of pollutant in DAS Ciliwung at Bogor City’s segment such as domestic, industrial and farming wastes. Water quality of Ciliwung river keep decreasing from upstream to downstream in Bogor City’s segment, indicated by the increasing of BOD and COD which over the ambience of water quality standards of PP No. 82 2001. Status of Ciliwung River at Bogor City’s water quality, based on IKA and Storet method, was included into moderate-worse category. Te greatest waste discharge was originated from domestic waste. Potential of domestic waste discharge was 843.36 ton/month of BOD, 1,495.47 ton/month of COD, 112.16 ton/month of TN, and 679.76 ton/month of TP, while the real domestic waste discharge was 351.36 ton/month of BOD, 785.75 ton/month of COD, 58.86 ton/month of TN, and 356.71 ton/month of TP. Maximum capacity of waste discharge was in February and minimum capacity of waste discharge was in September.
KOTA BOGOR
DANY TROFISA
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kajian Beban Pencemaran dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung di Segmen Kota Bogor adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah
digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak ditertibkan dari
penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian
akhir skripsi ini.
Bogor, Juni 2011
Nama Mahasiswa : Dany Trofisa
NRP : E34050861
Menyetujui,
Pembimbing I, Pembimbing II,
Ir. Agus Priyono, MS Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc
NIP. 19610812 198601 1 001 NIP. 19620316 198803 1 002
Mengetahui,
Ketua Departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
Fakultas Kehutanan IPB
Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS
NIP. 19580915 198403 1 003
Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kasih saying-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dengan judul
“Kajian Beban Pencemaran dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung di Segmen
Kota Bogor”.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu dan kedua adikku tercinta, serta
seluruh keluarga dan rekan-rekan atas do’a, dukungan dan kasih sayangnya. Ungakapan
terima kasih juga disampaikan kepada Ir. Agus Priyono, MS dan Prof. Dr. Ir. Lilik Budi
Prasetyo, M.Sc yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi input serta memberikan kontribusi
terhadap strategi dan proses pengendalian pencemaran air DAS Ciliwung khususnya Kota
Bogor guna menjaga kualitas air sungai. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam
penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan
dan pengembangan penelitian selanjutnya. Harapan penulis, sebuah karya kecil ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.
Bogor, Juni 2011
Penulis dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1987 dari pasangan
Bapak Andi Suwandi dan Ibu Dariah Eliana. Penulis merupakan anak pertama dari tiga
bersaudara.
Pendidikan penulis diawali pada tahun 1993-1999 di SDN 08 Pagi Pela Mampang dan
melanjutkan ke SLTPN 141 Jakarta pada tahun 1999-2002. Tahun 2002 meneruskan
pendidikan ke SMUN 55 Jakarta dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun itu juga penulis lulus
seleksi masuk Perguruan Tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis memilih Departemen Konservasi Sumberdaya
Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.
Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan
yaitu anggota dan pengurus Kelompok Pemerhati Flora Himpunan Mahasiswa Konservasi
Sumberdaya Hutan (HIMAKOVA) tahun 2006-2007, ketua umum Lembaga Dakwah
Fakultas DKM ‘Ibaadurrahmaan Fakultas Kehutanan tahun 2007-2008, dan tahun 2008-2009
diamanahkan sebagai ketua MS DKM ‘Ibaadurrahmaan, serta sejumlah kepanitiaan kegiatan
kemahasiswaan IPB dari tahun 2005-2009.
Pada tahun 2007 penulis mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di
Indramayu-Kuningan dan Praktek Umum Konservasi Ex-situ (PUKES) di Taman Mini
Indonesia Indah (TMII) yaitu di Taman Burung dan Museum Serangga serta di Taman
Sringanis tahun 2008. Tahun 2009 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang Profesi
(PKLP) di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Jawa Barat.
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas
Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melaksanakan penelitian dengan judul: “Kajian
Segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang telah memberikan hidayah,
karunia, cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ayahanda Andi Suwandi, ibunda Dariah dan kedua adikku tercinta Anisa
Septiwindari dan Tiara Rayna Yustika serta keluarga-keluarga lainnya atas do’a,
motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
2. Bapak Ir. Agus Priyono, MS dan Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc selaku dosen
pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan selama
penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS sebagai dosen penguji yang telah memberikan
masukan dan saran dalam penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf di Fakultas Kehutanan IPB, khususnya
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata.
5. Seluruh pihak dan instansi yang telah memberikan bantuan berupa data-data
sekundernya.
6. Murabbiku dan teman seperjuangan dalam bundaran kecil yang telah berbagi suka
dan duka, berbagi tausiyah sehingga saya masih bias diberikan kekuatan dalam meniti
jalan yang panjang ini.
7. Keluarga besar Lembaga Dakwah Fakultas DKM Ibaadurrahmaan .
8. Keluarga besar SALAM ISC 2007 atas ukhuwah yang selama ini terjalin begitu
akrab.
9. Keluarga besar Ikhwah IPB khususnya Ikhwah Fahutan.
10.Keluarga besar KSHE 42 (Tarsius 42).
11.Ahmad Wahyudi, Harry Tri Atmojo, Teguh Pradityo, Hafiz Herbowo, Agus Prayitno,
Azhar Anas dan Ahmad Baiquni atas bantuan baik moral dan moril selama penulis
melaksanakan penelitian sampai sidang komprehensif.
12.Penghuni Madani, Wisma Biru, Dar’Esyabaab dan Wisma Krakatau atas ukhuwah
yang selama ini terjalin.
13.Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan
Bogor, Juni 2011
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... i
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR GAMBAR ... v
DAFTAR LAMPIRAN ... vi
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Tujuan Penelitian ... 2
1.3 Manfaat Penelitian ... 2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian dan Batasan Daerah Aliran Sungai (DAS) ... 3
2.2 Pencemaran Air dan Sumber Pencemaran Sungai Ciliwung ... 4
2.3 Beban Pencemaran dan Daya Tampung ... 5
2.4 Parameter Pencemaran Air ... 6
2.5 Kriteria, Status, dan Baku Mutu Air. ... 11
2.6 Tata Guna Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Air ... 12
2.7 Penginderaan Jauh ... 13
2.8 Sistem Informasi Geografis ... 14
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 18
3.2 Alat dan Bahan ... 18
3.3 Kerangka Pemikiran ... 19
3.4 Pengumpulan Data... 21
3.5 Analisis Data ... 21
BAB IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Kondisi Umum Kota Bogor ... 29
4.2 Kondisi Umum Sungai Ciliwung ... 29
4.3 Kependudukan ... 30
4.4.Industri ... 30
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Sumber Limbah Cair dan Karakteristiknya ... 32
5.2 Kondisi Kualitas Air Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2005-2009 ... 34
5.3 Status Mutu Air ... 50
5.4 Beban Pencemaran Setiap Sumber Pencemardi Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor... 53
5.5 Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 61
5.6 Pemanfaatan Sungai dan Air Sungai serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pencemaran Air Sungai Ciliwung Kota Bogor ... 62
5.7 Pengaruh Penggunaan Lahan terhadap Kualitas Air Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 64
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 68
6.2 Saran ... 69
DAFTAR PUSTAKA ... 70
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kegiatan dan Jenis Limbah Yang Dihasilkan ... 5
Tabel 2. Penggolongan Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Oksigen Terlarut ... 9
Tabel 3. Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD ... 9
Tabel 4. Bahan-bahan yang Digunakan dalam Penelitian ... 19
Tabel 5. Bobot Parameter Dalam Perhitungan Indeks Kualitas Air-NSF WQI ... 22
Tabel 6. Kriteria Indeks Kualitas Air – National Sanitation Foundation ... 23
Tabel 7. Penentuan Sistem Nilai Untuk Menentukan Status Mutu Air ... 24
Tabel 8. Klasifikasi Mutu Air Berdasarkan EPA (Environmental Protection Agency) ... 24
Tabel 9. Faktor Konversi Beban Limbah ... 27
Tabel 10 Jumlah Penduduk Kota Bogor ... 30
Tabel 11 Penggunaan Lahan di DAS Ciliwung segmen Kota Bogor ... 31
Tabel 12 Bentuk Penanganan Sampah Oleh Masyarakat ... 33
Tabel 13 Nilai Rata-rata Kualitas Air Sungai dari Beberapa Parameter Tahun 2005-2009 ... 35
Tabel 14 Hasil Pengamatan Nilai Suhu (°C) tahun 2005-2009 ... 37
Tabel 15 Hasil Pengamatan Nilai TDS (mg/l) tahun 2005-2009 ... 38
Tabel 16 Hasil Pengamatan Nilai TSS (mg/l) tahun 2005-2009 ... 40
Tabel 17 Hasil Pengamatan Nilai DO (mg/l) tahun 2005-2009 ... 42
Tabel 18 Hasil pengamatan Nilai BOD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 44
Tabel 19 Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD ... 44
Tabel 20 Hasil Pengamatan Nilai COD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 46
Tabel 21 Hasil Pengamatan Nilai pH tahun 2005-2009 ... 47
Tabel 22 Hasil Pengamatan Nilai Fosfat (mg/l) tahun 2005-2009 ... 48
Tabel 23 Nilai IKA-NSF WQI tahun 2005-2009 ... 50
Tabel 24 Nilai Storet dan Status Mutu Air DAS Ciliwung segmen Kota Bogor Tahun 2005-2009 ... 52
Tabel 26 Potensi Beban Pencemaran Limbah Industri Kecil ... 57
Tabel 27 Potensi Beban Pencemaran Limbah Peternakan ... 60
Tabel 28 Daya Tampung Beban Pencemaran ... 62
Tabel 29 Persentase Pemanfaatan Sungai dan Air Sungai di DAS Ciliwung
Segmen Kota Bogor ... 63
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Komponen Dasar SIG (Sistem Informasi Geografi) ... 16
Gambar 2. Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor... 18
Gambar 3. Kerangka Alir Pemikiran Kajian Beban Pencemaran Air Sungai Ciliwung Di Kota Bogor ... 20
Gambar 4. Proses Pembuatan Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 25
Gambar 5. Proses Pengolahan Citra Landsat ... 26
Gambar 6. Limbah Domestik ... 32
Gambar 7. Limbah Peternakan ... 32
Gambar 8. Fluktuasi Nilai Rata-rata Kualitas Air di Katulampa ... 36
Gambar 9. Fluktuasi Nilai Rata-rata Kualitas Air di Sempur ... 36
Gambar 10. Fluktuasi Nilai Rata-rata Kualitas Air di Kedunghalang ... 36
Gambar 11. Grafik Perubahan Nilai Suhu (°C) Tahun 2005-2009 ... 35
Gambar 12. Grafik Perubahan Nilai TDS (mg/l) Tahun 2005-2009 ... 39
Gambar 13. Grafik Perubahan Nilai TSS (mg/l) Tahun 2005-2009 ... 41
Gambar 14. Grafik Perubahan Nilai DO (mg/l) tahun 2005-2009 ... 43
Gambar 15. Grafik Perubahan Nilai BOD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 45
Gambar 16. Grafik Perubahan Nilai COD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 47
Gambar 17. Grafik Perubahan Nilai pH tahun 2005-2009 ... 48
Gambar 18. Grafik Perubahan Nilai Fosfat (mg/l) tahun 2005-2009 ... 50
Gambar 19. Perbandingan Fluktuasi Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Dari Tahun 2005-2009 ... 51
Gambar 20. Fluktuasi Beban Pencemaran Limbah Domestik Potensial ... 55
Gambar 21. Fluktuasi Beban Pencemaran Limbah Domestik Riil ... 55
Gambar 22. Industri Tempe... 58
Gambar 23. Industri Tahu ... 59
Gambar 24. Peternakan Sapi Perah... 60
Gambar 25. Peternakan Ayam Potong ... 60
Gambar 26. Aktivitas Mencuci Masyarakat di Katulampa ... 63
Gambar 27. Aktivitas Penggalian Pasir di Kedunghalang ... 64
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 75
Lampiran 2. Peta Lokasi Wawancara ... 76
Lampiran 3. Peta Lokasi Titik Pantau Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 77
Lampiran 4. Peta Sebaran Industri dan Peternakan (Beban Pencemaran Riil)... 78
Lampiran 5. Peta Sebaran Industri dan Peternakan (Beban Pencemaran Potensial) ... 79
Lampiran 6. Peta Sebaran Industri dan Peternakan dengan Tutupan Lahan Tahun 2009... 80
Lampiran 7. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2007 ... 81
Lampiran 8. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2008 ... 82
Lampiran 9. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2009 ... 83
Lampiran 10. Perhitungan Modifikasi Bobot Parameter (Wi) ... 84
Lampiran 11. Hasil Pengukuran Kualitas Air per Titik Pantau pada 14x Pengukuran ... 85
Lampiran 12 Hasil Pengukuran dan Perhitungan IKA-NSF WQI ... 86
Lampiran 13. Perhitungan Metode Storet ... 92
Lampiran 14. Beban Pencemaran Air DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor.... 94
Lampiran 15. Faktor Konversi Beban Limbah Domestik, Industri dan Peternakan... 96
Lampiran 16. Hasil Perhitungan Daya Tampung Sungai Ciliwung Tahun 2009 ... 97
Lampiran 17. Kurva Sub-Indeks TDS, DO, pH, BOD, Fosfat dan Suhu ... 98
Lampiran 18. Contoh Foto-foto Kondisi Sungai Ciliwung ... 99
Lampiran 19. Daftar Pertanyaan Wawancara ... 100
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dengan luas areal 347 km2 mencakup
areal mulai dari bagian hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor sampai di hilir Teluk
Jakarta sebagai outlet DAS. Kegiatan pembangunan di DAS Ciliwung, baik di
hulu maupun di hilir tergolong sangat intensif dengan pertambahan penduduk
yang tinggi, sebagai dampak tingginya dinamika pembangunan di wilayah
Jabodetabek.
Perkembangan penduduk Kota Bogor dengan laju pertumbuhan 2,39 persen
per tahun berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kota Bogor mendorong peningkatan berbagai kebutuhan pangan,
sandang dan papan sehingga bermunculan berbagai macam industri dan
peternakan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kota Bogor laju pertumbuhan
industri mencapai 2,82 persen pada tahun 2010 dan total produksi daging Kota
Bogor tahun 2010 mencapai 13.241.967 kg. Meningkatnya jumlah dan jenis
industri serta peternakan di Kota Bogor diperkirakan telah banyak menimbulkan
beban pencemaran pada Sungai Ciliwung. Kondisi hutan DAS Ciliwung yang
juga berkurang menyebabkan debit sungai fluktuatif, sehingga berpengaruh
terhadap dinamika fluktuasi kualitas air sungai.
Berbagai program pengendalian pencemaran sungai pada umumnya belum
menyentuh permasalahan pencemaran mulai dari limbah domestik, industri kecil
sampai besar dan peternakan. Terutama beragamnya jenis industri kecil serta
penyebarannya yang sporadis hingga kawasan pemukiman sangat sulit untuk
dikelola dengan efektif. DAS Ciliwung sebagai ekosistem terbuka dan mengalir,
maka pencemaran industri-industri kecil dari wilayah daerah aliran sungai akan
memasuki Sungai Ciliwung melalui saluran-saluran air ataupun anak-anak sungai.
Dengan demikian akumulasi beban pencemar di bagian hulu di Cisarua
Kabupaten Bogor akan membuat tingkat pencemaran Sungai Ciliwung di wilayah
Dampak lain dari adanya pencemaran limbah domestik, industri dan
peternakan selain menurunkan mutu air sungai, juga menimbulkan bau busuk dan
sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan industri-industri di wilayah Kota
Bogor sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung secara
keseluruhan. Adapun penyediaan data dan informasi yang akurat, cepat dan
mencakup areal yang luas dapat dilakukan dengan aplikasi SIG dan teknik
penginderaan jauh (remote sensing).
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di DAS Ciliwung Segmen
Kota Bogor.
2. Mengevaluasi perkembangan kondisi mutu air Sungai Ciliwung dari hulu
ke hilir di segmen Kota Bogor.
3. Menghitung besar beban pencemaran setiap sumber-sumber pencemar.
4. Menghitung besar daya tampung beban pencemaran.
1.3 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat: memberikan informasi yang
berguna, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap
pengelolaan DAS Ciliwung seperti pemerintah Kota Bogor, Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ciliwung, Balai Pengelolaan Sumberdaya Air
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian dan Batasan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, disebutkan bahwa Daerah
Aliran Sungai adalah suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa
puncak-puncak, gunung dan punggung-punggung bukit. Bentang alam tersebut
menyimpan curah hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengatur dan
mengalirkannya secara langsung maupun tidak langsung beserta muatan sedimen
dan bahan-bahan lainnya ke sungai utama yang akhirnya bermuara ke laut
maupun danau. Sub DAS adalah bagian DAS dimana air hujan diterima dan
dialirkannya melalui anak sungai utama. Setiap DAS terbagi ke dalam sub
DAS-sub DAS.
Menurut Seyhan (1990), sungai memiliki tiga sifat aliran:
1. Aliran yang bersifat sementara, hanya dapat mengalir setelah terjadinya
hujan badai yang menghasilkan limpasan permukaan yang memadai.
Permukaan air bumi selalu berada di bawah dasar sungai.
2. Aliran yang terputus-putus, mengalir selama musim hujan saja.
Selanjutnya debit ini terdiri atas pemberian limpasan permukaan dan air
bumi pada dasar sungai. Permukaan air buni berada diatas dasar sungai
hanya selama musim hujan. Pada musim kemarau permukaan tersebut
berada di dasar sungai.
3. Aliran abadi/permanen, mengalir sepanjang tahun dengan debit-debit yang
lebih tinggi selama musim penghujan. Debit sungai terdiri atas pemberian
limpasan permukaan dan air bumi pada dasar bumi. Permukaan air tanah
selalu berada di atas dasar sungai.
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan wilayah bersifat
kompleks yang dipengaruhi karakteristik fisik variabel meteorologinya.
Karakteristik fisik yang berupa pola penggunaan lahan, bentuk jaringan sungai,
kondisi tanah, topografi, dan ketinggian tempat merupakan karakteristik DAS
yang sifatnya dapat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Sedangkan variabel
kecepatan angin bersifat sangat berubah-ubah tergantung kondisi klimatnya
(Dewan Riset Nasional Kelompok II, Sumberdaya Alam dan Energi, 1994).
2.2 Pencemaran Air dan Sumber Pencemaran Sungai Ciliwung
Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup
zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukkannya (Peraturan Pemerintah No. 20 tahun
1990). Bahan-bahan yang masuk dan mencemari lingkungan menurut Hynes
(1978) dalam Nugroho (2003) dapat berupa zat-zat beracun, bertambahnya
padatan tersuspensi, dioksidasi dan naiknya air akan merubah kondisi ekologi
perairan pada umumnya dan kualitas biota pada khususnya.
Sumber pencemaran air sungai dapat dibedakan menjadi sumber
domestik dan sumber non domestik. Termasuk ke dalam sumber domestik adalah
perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal dan rumah sakit. Sementara yang
termasuk sumber non domestik adalah pabrik, industri, pertanian, peternakan,
perikanan dan transportasi. Lahan di sepanjang Sungai Ciliwung dipergunakan
untuk berbagai kegiatan antara lain untuk pemukiman, pertanian, perkebunan dan
industri. Limbah tersebut didistribusikan ke badan sungai sepanjang DAS
Ciliwung sehingga terjadi pencemaran air (Sastrawidjaya, 1991).
Menurut Saeni (1989) sumber pencemaran yang terjadi di Sungai
Ciliwung berasal dari buangan penduduk, pertanian dan industri. Sugiharto (1987)
menyebutkan sumber pencemar yang berasal dari permukiman (penduduk) akan
menghasilkan limbah detergen, zat padat, BOD, COD, DO, nitrogen, fosfor, pH,
kalsium, klorida dan sulfat. Sumber pencemar yang berasal dari pertanian akan
menghasilkan limbah pestisida, bahan beracun dan logam berat. Sumber
pencemar yang berasal dari industri antara lain akan menghasilkan limbah BOD,
COD, DO, pH, TDS, minyak dan lemak, urea, fosfor, suhu, bahan beracun dan
kekeruhan. Jenis kegiatan industri dengan limbah yang dihasilkan disajikan pada
Tabel 1 Kegiatan dan Jenis Limbah yang Dihasilkan No Jenis Kegiatan Limbah yang Dihasilkan
1 Industri pangan BOD, COD, TOC, TOD, pH, suspended solid, minyak dan lemak, logam berat, sianida, klorida, amoniak, nitrat, fosfor dan fenol.
2 Industri minuman BOD, pH, suspended solid, settleable solid, TDS, minyak dan lemak, warna, jumlah coli, bahan beracun, suhu kekeruhan dan buih.
3 Industri makanan BOD, COD, TOC, pH, minyak dan lemak, logam berat, nitrat, fosfor dan fenol.
4 Industri percetakan BOD, COD, TOC, total solids, suspended solid, TDS, minyak dan lemak, logam berat, amoniak, sulfit, nitrat, fosfor, warna, jumlah coli, coli faeces, bahan beracun, suhu, kekeruhan, klorinated benezoid.
5 Perkayuan dan motor COD, logam berat, dan bahan beracun.
6 Industri pakaian jadi BOD, COD, TOD, suspended solid, TDS, minyak dan lemak, logamberat, kromium, warna, bahan beracun, suhu, klorinated, benezoid dan sulfida.
7 Industri plastik BOD, COD, total solids, settleable solid, TDS, minyak dan lemak, seng, sianida, sulfat, amoniak, fosfor, urea
anorganik, bahan beracun, fenol dan sulfida. 8 Industri kulit Total padatan, penggaraman, sulfida, kromium, pH,
endapan kapur, dan BOD.
9 Industri besi dan logam COD, suspended solids, minyak dan lemak, logam berat, bahan beracun, sianida, pH, suspended solid, kromium, besi, seng, klorida, sulfat, amoniak, dan kekeruhan. 10 Aneka industri BOD, pH, suspended solid, settleable solid, TDS, minyak
dan lemak, warna, jumlah coli, bahan beracun, suhu, kekeruhan, amoniak dan kekeruhan.
11 Pertanian/tanaman pangan Pestisida, bahan beracun, dan logam berat.
12 Perhotelan Deterjen, zat padat, BOD, COD, TOC, TOD, nitrogen, fosfor, warna, jumlah coli, bahan beracun, dan kekeruhan.
13 Rekreasi BOD, COD, kekeruhan dan warna.
14 Kesehatan Bahan beracun, logam berat, BOD, COD, TOM dan jumlah coli.
15 Perdagangan BOD, pH, suspended solid, settleable solid, TDS, minyak dan lemak, amoniak, urea, fosfor, warna, jumlah coli, bahan beracun dan kekeruhan.
16 Pemukiman Deterjen, zat padat, BOD, COD, TOD, TOC, nitrogen, fosfor, kalsium, klorida dan sulfat.
17 Perhubungan darat Logam berat, bahan beracun dan COD.
18 Perikanan darat BOD, COD, TOM dan pH.
19 Peternakan BOD, COD, TOC, pH, suspended solid, klorida, nitrat, fosfor, warna, bahan beracun, suhu dan kekeruhan. 20 Perkebunan COD, pH, suspended solid, TDS, minyak dan lemak,
kromium, kalsium, klorida, sulfat, amoniak, sodium, nitrat, fosfor, urea anorganik, coli faeces dan suhu.
Sumber: Donal W. S dan H. E. Klei (1979) dalam Sugiharto dalam Taufik (2003)
2.3 Beban Pencemaran dan Daya Tampung
Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 beban pencemaran
adalah jumlah suatu pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah.
kapasitas aliran air yang mengandung bahan pencemar, artinya adalah jumlah
berat pencemar dalam satuan waktu tertentu, misalnya kg/hari. Istilah beban
pencemaran dikaitkan dengan jumlah total pencemar atau campuran pencemar
yang masuk ke dalam lingkungan (langsung atau tidak langsung) oleh suatu
industry aatau kelompok industry pada areal tertentu dalam periode waktu
tertentu. Pada kasus limbah rumah tangga dan kota, istilah beban pencemaran
berkaitan dengan jumlah total limbah yang masuk ke dalam lingkungan (langsung
atau tidak langsung dari komunitas kota selama periode waktu tertentu
(Djajadiningrat dan Amir, 1991).
Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 daya tampung beban
pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima
masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
Daya tampung beban pencemaran diartikan sebagai kemampuan air pada suatu
sumber air atau badan air untuk menerima beban pencemaran tanpa
mengakibatkan air tersebut menjadi cemar (Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup No.110 tahun 2003).
2.4 Parameter Pencemaran Air 2.4.1 Parameter Fisik
2.4.1.1 Suhu
Suhu merupakan salah satu faktor dalam reaksi kimia dan aktifitas biologi
di dalam suatu perairan yang sangat berperan dan berpengaruh dalam
mengendalikan kondisi ekosistem perairan, terutama terhadap kelangsungan hidup
suatu organisme (Palmer, 2001). Kenaikan suhu sebesar 10°C menyebabkan
kebutuhan oksigen hewani perairan naik hampir dua kali lipat. Sebaliknya
peningkatan suhu menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut akan menurun dan
peningkatan suhu ini juga akan dapat menaikan daya racun polutan terhadap
organisme perairan (Moriber, 1974). Menurut Hawkes (1979) suhu perairan yang
tidak lebih dari 30°C tidak akan berpengaruh secara drastis terhadap
makrozoobenthos.
Fardiaz (1992) mengungkapkan bahwa kenaikan suhu air akan
a. Jumlah oksigen terlarut dalam air akan menurun.
b. Kecepatan reaksi kimia meningkat.
c. Kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu.
d. Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya
mungkin akan mati.
Temperatur air terutama merupakan pencerminan dari kondisi iklim.
Bagaimanapun manusia mampu memodifikasi temperatur misalnya air digunakan
untuk pendinginan dalam pembangkit listrik, dimana mentransfer buangan limbah
panas ke dalam perairan. Pembuangan limbah mungkin juga meningkatkan
temperatur air. Pelepasan air pada dasar perairan dari waduk-waduk mungkin
memasukkan air yang lebih dingin ke dalam sungai penerima.
2.4.1.2 Total Padatan Terlarut (Total Dissolved Solid/TDS)
Fardiaz (1992) menyatakan bahwa padatan terlarut adalah padatan-padatan
yang mempunyai ukuran-ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi.
Padatan-padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik yang larut dalam
air/mineral dan garam-garamnya. Padatan terlarut mempengaruhi ketransparanan
dan warna air yang ada hubungannya dengan produktifitas (Sastrawijaya, 1991).
Keberadaan sebagai larutan-larutan ditunjukkan dalam keberadaan fisik dan kimia
air. Nilai TDS perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari
tanah, dan pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri).
Menurut Priyono (1994) aliran dasar dari suatu jalan air mendapatkan
mineral yang terpilih dalam bentuk garam-garam terlarut dalam larutan seperti
sodium, khlorit, magnesium, sulfat, dan lain-lain. Aliran ini dapat mengkontribusi
bahan-bahan terlarut untuk perairan.
2.4.1.3 Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS)
Padatan tersuspensi total (TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter
> 1 µm) yang tertahan pada saringan milipore dengan pori-pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, terutama disebabkan
TSS dapat meningkatkan nilai kekeruhan sehingga akan mempengaruhi
penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses
fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan air yang selanjutnya akan
mengurangi pasokan oksigen terlarut dan meningkatkan pasokan CO2 di perairan.
Menurut Priyono (1994) Bahan partikel yang tidak terlarut seperti pasir,
lumpur, tanah, dan bahan kimia inorganik menjadi bentuk bahan tersuspensi di
dalam air, sehingga bahan tersebut menjadi penyebab polusi tertinggi di dalam air.
Kebanyakan sungai dan daerah aliran sungai selalu membawa endapan lumpur
yang disebabkan erosi alamiah dari pinggir sungai. Akan tetapi, kandungan
sedimen yang terlarut pada hampir semua sungai meningkat terus karena erosi
dari tanah pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan. Partikel yang
tersuspensi menyebabkan kekeruhan dalam air, sehingga mengurangi kemampuan
ikan dan organisme air lainnya memperoleh makanan dan mengurangi tanaman
air melakukan fotosintesis.
2.4.2Parameter Kimia
2.4.2.1 Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO)
Oksigen terlarut (DO) merupakan parameter kualitas air yang penting.
Umumnya konsentrasi DO di suatu perairan akan bersifat sementara atau
musiman dan berfluktuasi. Biasanya organisme air seperti ikan memerlukan
oksigen terlarut antara 5,8 mg/l (Palmer, 2001).
Oksigen terlarut dalam perairan dapat merupakan faktor pembatas dalam
penentuan kehadiran makhluk hidup dalam air. Kepekatan oksigen terlarut
bergantung kepada suhu, kehadiran tanaman fotosintesis, tingkat penetrasi cahaya
yang tergantung pada kedalaman dan kekeruhan air, tingkat kederasan aliran air
dan jumlah bahan organik yang diuraikan dalam air (Sastrawidjaya, 1991).
Kandungan oksigen terlarut yang tinggi adalah pada sungai yang relatif dangkal
dan adanya turbulensi oleh gerakan air. Daya larut oksigen akan menurun dengan
kenaikan suhu, sebaliknya pada air yang dingin kadar oksigen akan meningkat
(Odum, 1971). Berdasarkan kandungan oksigen terlarut Shandi dalam
Sutamiharja (1978) melakukan penggolongan kualitas air (Tabel 2) sebagai
Tabel 2 Penggolongan Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Oksigen Terlarut
DO (mg/l) Tingkat Pencemaran
>5 Tercemar Ringan
2-5 Tercemar Sedang
0-2 Tercemar Buruk
Kelarutan oksigen di air berasal dari atmosfer atau fotosintesis tumbuhan
akuatik termasuk phytoplankton. Penyebab utama berkurangnya oksigen terlarut
di dalam air adalah bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen.
Bahan-bahan tersebut terdiri dari Bahan-bahan yang mudah dibusukkan atau diuraikan oleh
bakteri dengan adanya oksigen.
2.4.2.2 Kebutuhan Oksigen Biologi (Biological Oxygen Demand/BOD)
Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) merupakan banyaknya oksigen yang
dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik yang ada. Menurut APHA (1978)
nilai BOD yang besar menunjukkan aktivitas mikroorganisme yang semakin
tinggi dalam menguraikan bahan organik.
Menurut Fardiaz (1992) bahan-bahan buangan yang memerlukan oksigen
terutama terdiri dari bahan-bahan organik dan mungkin beberapa bahan
anorganik, kotoran manusia dan hewan, tanaman-tanaman yang mati atau sampah
organik, bahan-bahan buangan industri dan sebagainya. Air yang hampir murni
mempunyai nilai BOD kira-kira 1 mg/l, dan air yang mempunyai nilai BOD 3
mg/l masih dianggap cukup murni, tetapi kemurnian air diragukan jika nilai BOD
nya mancapai 5 mg/l atau lebih. Lee et al. (1978) telah melakukan kasifikasi kualitas air (Tabel 3) berdasarkan nilai BOD, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3 Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD
Nilai BOD (mg/l) Kualitas Air
< 3,0 Tidak Tercemar
3.0 – 4,9 Tercemar Ringan
5,0 – 15,0 Tercemar Sedang
> 15,0 Tercemar Berat
Bahan organik di perairan yang mengalir berasal dari sumber alam seperti
gangguan atau kerusakan tumbuh-tumbuhan akuatik. Tetapi pulp, paper, dan
sampah pertanian dapat juga menambah kuantitas yang berarti dari permintaan
2.4.2.3 Derajat Keasaman (pH)
Menurut Sutamihardja (1978) derajat keasaman merupakan kekuatan
antara asam dan basa dalam air dan suatu kadar konsentrasi ion hidrogen dalam
larutan. Nilai pH menggambarkan kekuatan bahan pelarut dari air, karena itu
penunjukkannya mungkin dari reaksi kimia pada batu-batuan dan tanah-tanah.
Pertumbuhan organisme perairan dapat berlangsung dengan baik pada kisaran pH
6,5-8,5.
Menurut Brook et al. (1989) dalam Fakhri (2000) menyebutkan bahwa perairan sudah dianggap tercemar jika memiliki nilai pH < 4,8 dan > 9,8. Derajat
keasaman atau pH air biasanya digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran
dengan melihat tingkat keasaman atau kebasaan air yang dikaji. Mackereth et al. dalam Effendi (2003) berpendapat bahwa pH berkaitan erat dengan karbondioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai
alkalinitas dan semakin rendah kadar karbondioksida bebas. Larutan yang bersifat
asam akan bersifat korosif. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimia
perairan, misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika kadar pH rendah.
Keberadaan karbonat, hidroksida dan bikarbonat bertambah pada dasar
perairan, sementara keberadaan mineral bebas asam dan asam karbonik bertambah
dalam keasaman. Perairan asam tidak lebih umum dari pada perairan alkali.
Sumber pembuangan air asam dan sampah-sampah industri yang sudah tidak
dinetralkan akan bersamaan dengan pengurangan pH dari air.
2.4.2.4 Fosfat
Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan
(Dugan, 1972). Menurut Moriber dalam Anggraeni (2002), senyawa fosfat dalam
perairan dapat berasal dari sumber alami seperti erosi tanah, buangan dari hewan
dan lapukan tumbuhan. Dalam perairan senyawa fosfat berada dalam bentuk
anorganik (ortofosfat, metafosfat dan polifosfat) dan organik (dalam tubuh
organisme melayang, asam nukleat, fosfolipid, gula fosfat, dan senyawa organik
lainnya).
Menurut Effendi (2003), semua polifosfat mengalami hidrolisis
mendekati titik didih, perubahan polifosfat menjadi ortofosfat berlangsung cepat.
Kecepatan ini meningkat dengan menurunnya nilai pH.
Secara umum kandungan fosfat meningkat terhadap kedalaman.
Kandungan fosfat yang rendah dijumpai di permukaan dan kandungan fosfat yang
lebih tinggi dijumpai pada perairan yang lebih dalam (Hutagalung dan Rozak,
1977). Senyawa ortofosfat merupakan faktor pembatas bila kadarnya di bawah
0,009 mg/l, sementara pada kadar lebih dari satu mg/l PO4-P dapt menimbulkan
blooming (Mackentum dalam Abdurochman, 2005).
Menurut Effendi (2003) bahwa sumber alami fosfor di perairan adalah
pelapukan batuan mineral. Sumber antropogenik fosfor adalah limbah industri dan
domestik, yakni fosfor yang berasal dari detergen. Limpasan dari derah pertanian
yang menggunakan pupuk juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
keberadaan fosfor.
2.4.2.5 Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/COD)
Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik yang terdapat di perairan menjadi
CO2 dan H2O. Nilai COD ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya bahan
organik di perairan (APHA, 1976).
Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20
mg/l. Sementara pada perairan yang tercemar memiliki nilai COD dapat melebihi
200 mg/l. Oleh karena itu perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak baik
untuk kegiatan perikanan (Fakhri, 2000).
2.5 Kriteria, Status, dan Baku Mutu Air
Kriteria kualitas air merupakan batas konsentrasi parameter-parameter
kualitas air yang diinginkan bagi kelayakan kualitas air untuk penggunaan
tertentu. Sedangkan baku mutu air merupakan peraturan menurut undang-undang
yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencamtumkan pembatasan konsentrasi
berbagai parameter kualitas air (Rushayati, 1999).
Kualitas suatu perairan sangat ditentukan oleh konsentrasi bahan
Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air, disebutkan bahwa pencemaran air adalah
memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen
lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke
tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya. Pada pasal 8 disebutkan penggolongan air berdasarkan
peruntukkannya yang diikuti dengan kriteria kualitas air tersebut sesuai dengan
golongannya, yaitu:
1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air
minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,
air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan
tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut.
2.6 Tata Guna Lahan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Air
Vink (1975) menyebutkan bahwa perubahan atau perkembangan
penggunaan lahan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor alam seperti iklim,
topografi, tanah, atau bencana alam dan faktor manusia yang berupa aktivitas
manusia pada sebidang lahan.
Menurut Leopold and Dunne (1978) dalam Sudadi et al. (1991) perubahan
penggunaan lahan secara umum akan mengubah: karakteristik aliran sungai, total
aliran permukaan, kualitas air dan sifat hidrologi daerah yang bersangkutan.
aliran sungai terutama erat kaitannya terhadap fungsi vegetasi sebagai penutup
lahan dan sumber bahan organik yang dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi.
Sedangkan menurut Sutamiharja (1978) kegiatan pertanian secara langsung
ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas perairan yang diakibatkan
oleh penggunaan bermacam-macam pupuk buatan dan pestisida. Perubahan lahan
menjadi daerah pemukiman cenderung berdampak negatif, khususnya bila ditinjau
dari segi erosi.
2.7 Penginderaan Jauh
Penginderaan jauh adalah ilmu serta seni untuk memperoleh informasi
tentang suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh
dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena
yang dikaji. Dengan menggunakan berbagai sensor, dilakukan pengumpulan data
dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang obyek,
daerah, atau fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dari jarak jauh dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk variasi agihan daya, agihan gelombang
bunyi, maupun agihan elektromagnetik (Lillesand dan Kiefer, 1987). Lebih lanjut
dikatakan, sistem penginderaan jauh yang paling sering digunakan bekerja pada
satu atau beberapa spektrum tampak, inframerah dekat, inframerah termal atau
gelombang mikro.
Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi
mengenai obyek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik. Teknik
ini menghasilkan beberapa bentuk citra yang selanjutnya diproses dan
diinterpretasi untuk menghasilkan data yang bermanfaat untuk aplikasi di bidang
pertanian, arkeologi, kehutanan, geografi, geologi, perencanaan dan
bidang-bidang lainnya (Lo, 1995). Komponen dasar suatu sistem penginderaan jauh
ditunjukkan dengan adanya hal suatu sumber tenaga yang seragam, atmosfer yang
tidak mengganggu, sensor yang sempurna, serangkaian interaksi yang unik antara
tenaga dengan benda di muka bumi, sistem pengolahan data tepat waktu dan
berbagai penggunaan data (Lillesand dan Kiefer, 1990).
Citra merupakan gambar yang terekam oleh kamera atau sensor lainnya
pembuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud mengidentifikasi
obyek dan menilai arti pentingnya obyek tersebut (Este dan Simonett, 1975 dalam
Sutanto, 1986). Foto udara merupakan sumber informasi yang penting mengenai
perubahan-perubahan tata guna lahan sepanjang waktu (Paine, 1981).
Citra Landsat merupakan citra satelit untuk penginderaan sumberdaya
bumi. Thematik Mapper (TM) adalah suatu sensor optik penyiaman yang
beroperasi pada cahaya tampak dan inframerah bahkan spektral (Lo, 1995).
Thematik Mapper dipasang pada Landsat dengan tujuan untuk perbaikan resolusi spasial, pemisaan spektral, kecermatan data radiometrik dan ketelitian geometrik.
Lillesand dan Kiefer (1990) menyatakan analisis data Landsat dengan
komputer dapat dikelompokkan atas butir berikut:
1. Pemulihan citra (image restoration), meliputi koreksi berbagai distorsi radiometrik dan geometrik yang mungkin ada pada data citra asli.
2. Penajaman citra (image enhancement) sebelum menayangkan data citra untuk
analisis visual teknik, penajaman dapat diterapkan untuk menguatkan tampak
kontras diantara kenampakan di dalam adegan.
3. Klasifikasi citra (image classification), pada proses ini maka tiap pengamatan pixel dievaluasi dan diterapkan pada suatu kelompok informasi jadi mengganti
arsip data citra dengan suatu matriks jenis kategori yang ditentukan
berdasarkan nilai kecerahan (brighteness value/VB atau digital number/DN) pixel yang bersangkutan.
2.8 Sistem Informasi Geografis
Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem berdasarkan komputer
yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografi
(georeference) dalam hal pemasukan, manajemen data, memanipulasi dan menganalisis serta pengembangan produk dan percetakan (Aronof, 1989).
Sedangkan menurut Bern (1992) dalam Prahasta (2001) mengemukakan bahwa
sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang digunakan untuk
memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk: (1) Akuisisi dan verifikasi data (2)
Manajemen dan pertukaran data (6) Manipulasi data (7) Pemanggilan dan
presentasi data (8) Analisa data.
Selain itu juga, Barus (1999) menyatakan, kelebihan SIG terutama
berkaitan dengan kemampuannya dalam menggabungkan berbagai data yang
berbeda struktur, format, dan tingkat ketepatan.
Ardiansyah et al (2002) mengelompokkan komponen SIG ke dalam empat
komponen yaitu:
1. Perangkat keras
Perangkat keras komputer utama dalam SIG adalah sebuah Personal
Computer (PC) yang terdiri dari:
Central Processing Unit (CPU) sebagai pemroses data
Keyboard untuk memasukkan data atau perintah
Mouse untuk memasukkan perintah
Monitor untuk menyajikan hasil atau menampilkan proses yang
sedang berlangsung
Hard disk untuk menyimpan data
Perangkat keras tambahan yang diperlukan adalah:
Digitizer untuk memasukkan data spasial yang nantinya akan
tersimpan sebagai data vektor
Scanner untuk memasukkan data spasial yang nantinya akan
tersimpan sebagai data raster
Plotter untuk mencetak hasil keluaran data spasial berkualitas tinggi baik utnuk data vektor atau data raster
CD Writer sebagai media penyimpanan cadangan (back up) selain
hard disk
2. Perangkat lunak
SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular
dimana basis data memegang peranan kunci.Saat ini banyak sekali
perangkat lunak SIG baik yang berbasis vektor maupun yang berbasis
raster. Nama perangkat lunak SIG yang berbasis vektor antara lain
sedangkan perangkat lunak SIG yang berbasis raster antara lain ILWIS,
IDRISI, ERDAS, dan sebagainya.
3. Data dan Informasi Geografi
Data yang dapat diolah dalam SIG merupakan fakta-fakta data di
permukaan bumi yang memiliki referensi keruangan baik referensi secara
relative maupun referensi secara absolute, dan disajikan dalam sebuah
format yang bernama peta. SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data
dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara
meng-import-nya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan
memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan
menggunakan keyboard (Gistut, 1994 dalam Prahasta, 2001).
4. Sumberdaya Manusia
Komponen terakhir yang tidak terelakkan dari SIG adalah sumberdaya
manusia yang terlatih.Peranan sumberdaya manusia ini adalah untuk
menjalankan sistem yang meliputi pengoperasian perangkat keras dan
perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan kedua perangkat
tersebut.Sumberdaya manusia juga merupakan sistem analisis yang
menerjemahkan permasalahan riil di permukaan bumi dengan bahasa SIG,
sehingga permasalahan tersebut bisa teridentifikasi dan memiliki
pemecahannya.
Gambar 1 Komponen Dasar SIG SDM
SIG
Perangkat Keras Perangkat
Lunak
Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk perencanaan lalu lintas
dan transportasi, perencanaan pertanian, manajemen sumberdaya alam dan
lingkungan, perencanaan rekreasi, lokasi/alokasi keputusan, perencanaan tata
guna lahan (landuse), perencanaan pelayanan umum (pendidikan, pelayanan
social, kepolisian, dan lain-lain). Penerapan SIG lainnya dapat dilakukan antara
lain dalam kegiatan jaringan jalan dan pipa, pertanian, penggunaan tanah,
kehutanan, pengelolaan kehidupan liar, geologi, dan perencanaan kota (Aronof,
1989 dalam Febriana, 2004).
Manfaat utama penggunaan sistem informasi spasial dengan komputer
dibandingkan dengan pembuatan konvensional dan masukan data manual atau
informasi manual adalah memperkecil kesalahan manusia dan kemampuan
memangil kembali peta tumpang tindih (overlay) dari simpanan atau SIG secara cepat. Program tumpang tindih (overlay) digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih data-data SIG dan menghasilkan data baru yang dikehendaki pengguna.
Teknik tumpang tindih dapat digunakan bagi peta-peta yang sudah sama
formatnya dan skalanya. Tumpang tindih dapat menghasilkan peta tematik
kesesuaian lahan untuk suatu wilayah.Analisis kesesuian lahan suatu wilayah
dapat dihitung dalam satuan areal luasan (hektar) maupun perhitungan presentase
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah DAS Ciliwung di wilayah
Kota Bogor. Sungai Ciliwung dengan panjang aliran sungai ± 117 Km, dengan
luas DAS sekitar 347 km². Pengambilan data sekunder dilaksanakan pada bulan
Februari - Maret 2010, sedangkan data primer ke lapangan dilaksanakan pada
[image:34.612.102.521.266.622.2]bulan Oktober - November 2010.
Gambar 2 Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor
3.2 Alat dan Bahan
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung dan
dari berbagai instansi dan hasil survey penelitian sebelumnya. Peralatan yang
digunakan untuk mengolah data-data yang didapatkan yaitu alat tulis dan hitung,
kamera, Global Positioning System (GPS) dan seperangkat komputer dilengkapi
dengan paket SIG (perangkat keras dan lunak) termasuk software ArcGIS 9.3 dan
ArcView Avswat 2005. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian
ini dapat dilihat dalam Tabel 4.
Tabel 4 Data yang Digunakan dalam Penelitian
No Jenis Data Sumber Data
1 Data Kualitas Air Tahun 2005-2009 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat
2 Data Debit Sungai Tahun 2005-2009 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat
3 Data Curah Hujan Tahun 2005-2009 Balai Pendayagunaan Sumberdaya Air (BPSDA) Ciliwung-Cisadane
4 Data Jenis dan Jumlah Industri yang ada di
DAS Ciliwung Observasi Lapangan
5 Data Kependudukan Kota Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor
6 Data Jumlah Ternak Observasi Lapangan
7 Peta (topografi, penutupan lahan,
administrasi) KLH, PPLH IPB
3.3 Kerangka Pemikiran
Sungai Ciliwung di Kota Bogor merupakan bagian dari lingkungan hidup
yang senantiasa akan terus mengalami perubahan, khususnya kualitas air.
Perubahan tersebut cenderung berupa penurunan kualitas air yang disebabkan oleh
pencemaran yang masuk ke badan perairan sungai. Kondisi penutupan lahan suatu
DAS berpengaruh terhadap kondisi kualitas air sungai di DAS tersebut. Ketika
debit sungai besar akan menyebabkan pengenceran berbagai bahan pencemar di
sungai, sebaliknya ketika debit kecil maka terjadi peningkatan kadar bahan
pencemar. Hal ini dimungkinkan pula oleh kondisi beban pencemaran yang
relative stabil sepanjang tahun. Untuk itu upaya pengelolaan kualitas air adalah
melalui pengendalian kondisi dan pemanfaatan DAS secara tepat. Secara skematik
pengaruh kondisi DAS terhadap kualitas air Sungai Ciliwung dapat digambarkan
Gambar 3 Kerangka Alir Pemikiran Kajian Beban Pencemaran Air dan Daya Tampung Sungai Ciliwung di Kota Bogor
Curah Hujan
Kualitas air Sungai Kondisi Tutupan
Hutan di DAS
Kondisi Penggunaan Lahan
[image:36.612.103.472.125.586.2]3.4 Pengumpulan Data 3.4.1 Jenis Data
Pengumpulan data terdiri atas data spasial dan data atribut. Data spasial
merupakan data yang bersifat keruangan atau diperoleh dari pengolahan peta-peta
tematik dan penginderaan jauh, diantaranya peta topografi, peta, peta ketinggian
tempat atau elevasi, peta penutupan lahan, peta saluran atau sungai. Selain data
spasial, data lain yang diperlukan adalah data atribut, yaitu data dalam bentuk
tulisan ataupun angka-angka, diantaranya data kualitas air dan debit sungai, data
jumlah ternak, data kependudukan, data jumlah dan jenis indutri-industri.
3.4.2 Sumber Data
3.4.2.1 Data primer
Sumber data primer dalam kegiatan ini diperoleh dari hasil observasi
lapangan dan wawancara di lapangan (daftar pertanyaan terlampir). Wawancara
masyarakat dilakukan di lima kelurahan yaitu Katulampa, Sukasari, Sempur,
Kebon Pedes dan Kedunghalang. Masing-masing kelurahan sebanyak 30
responden.
3.4.2.2 Data sekunder
Sumber data sekunder dapat dilihat pada Tabel 4.
3.4.3 Cara Pengumpulan Data
3.4.3.1 Observasi langsung
Observasi langsung dilakukan di lapangan dengan bantuan kamera, GPS
dan pengamatan fisik.
3.4.3.2Mencatat dokumen (content analysis)
Mencatat dokumen/data/informasi dari berbagai instansi.
3.5 Analisis Data
3.5.1 Analisis Status Mutu Air
3.5.1.1 Analisis Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)
Untuk melihat kondisi kualitas air pada sungai secara keseluruhan
contoh yang sama. Metode IKA ini pada dasarnya merupakan indeks yang
digunakan untuk menentukan mutu air untuk peruntukan air minum.
Perhitungan Indeks Kualitas Air – National Sanitation Foundation
(IKA-NSF) dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
IKA−NSF = .
Keterangan:
IKA-NSF = Indeks kualitas air – national sanitation foundation
Wi = Bobot akhir masing-masing parameter setelah disesuaikan
Ii = Sub indeks kualitas air tiap parameter yang di dapat dari hasil
analisis dan hasil pengukuran yang dibandingkan dengan kurva sub
indeks
n = Jumlah parameter
Tahap-tahap pemakaian indeks tersebut adalah:
1. Menentukan terlebih dahulu jumlah parameter yang akan digunakan atau yang
diamati.
2. Penentuan nilai bobot dari masing-masing parameter yang digunakan (Wi)
dengan menggunakan standar yang digunakan Ott (1978) maupun dengan cara
melakukan penyesuaian (Lampiran 10).
Adapun bobot parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Air-NSF
WQI dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Bobot Parameter Dalam Perhitungan Indeks Kualitas Air-NSF WQI (Ott, 1978)
No Parameter Bobot Parameter
(Wa)
Bobot Parameter
Penyesuaian (Wb) Satuan
1 Oksigen Terlarut 0.17 0.25 % saturnasi
2 pH 0.12 0.18 -
3 BOD 0.10 0.15 Mgl
4 Nitrat 0.10 - Mgl
5 Fospat 0.10 0.15 Mg/l
6 Suhu 0.10 0.15 °C
7 Kekeruhan 0.08 - NTU
8 Padatan Total 0.08 0.12 mg/l
3. Menghitung nilai Ii dengan cara memplotkan nilai hasil pengukuran setiap
parameter dengan kurva sub indeks dari Ott (1978).
4. Setelah nilai Wi dan Ii didapat, dihitung indeks dengan menggunakan
persamaan IKA-NSF diatas.
Adapun kriteria indeks kualitas air – National Sanitation Foundation dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Kriteria Indeks Kualitas Air – National Sanitation Foundation (Ott, 1978)
No Nilai Kriteria
1 0 – 25 Sangat Buruk
2 26 – 50 Buruk
3 51 – 70 Sedang
4 71 – 90 Baik
5 91 - 100 Sangat Baik
Sumber: Ott, (1978) dalam Perdani (2001)
3.5.1.2 Analisis Metode Storet
Metode storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status
mutu air yang digunakan. Dengan metode Storet ini dapat diketahui
parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip
metode Storet adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu
air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air.
Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan mengguunakan
sistem nilai dari US-EPA (Environmental Protection Agency) dengan
mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas. Sedangkan untuk klasifikasi
mutu air berdasarkan EPA dapat dilihat pada Tabel 8.
Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Storet dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data kualitas air secara periodik sehingga
membentuk data dari waktu ke waktu.
2. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter air
dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan kelas air.
3. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran ≤
4. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil
pengukuran > baku mutu), maka diberi skor:
5. Jumlah negatif dari seluruh parameter yang dihitung dan ditentukan status
mutunya dari jumlah skor yang didapat dengan menggunakan sistem nilai.
Adapun penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air dapt
dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Penentuan Sistem Nilai Untuk Menentukan Status Mutu Air (Canter, 1977)
Jumlah Contoh
*) Nilai
Parameter
Fisika Kimia Biologi
< 10
Maksimum -1 -2 -3
Minimum -1 -2 -3
Rata-rata -3 -6 -9
≥ 10 Maksimum Minimum -2 -2 -4 -4 -6 -6
Rata-rata -6 -12 -18
Ket *) Jumlah parameter yang digunakan dalam menentukan status mutu air.
Tabel 8 Klasifikasi Mutu Air Berdasarkan EPA (Environmental Protection
Agency)
Kelas Jumlah Total Skor Mutu Air
A 0 Baik Sekali
B -1 s.d -10 Baik
C -11 s.d -30 Sedang
D ≤ -31 Buruk
3.5.2 Analisis Sumber Pencemaran dengan Sistem Informasi Geografis
Analisis ini menggunakan software sistem informasi geografis berupa Arc
GIS 9.3 dan ArcView Avswat 2005 yang berhubungan dengan proses
pembangunan basis data. Proses pembangunan basis data terdiri dari 3 kegiatan
yaitu pembuatan peta digital, peta DAS Ciliwung segmen Kota Bogor dan peta
sebaran industri di DAS Ciliwung segmen Kota Bogor. Proses dari
masing-masing kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:
3.5.2.1Pembuatan Peta Digital
Pada penelitian kali ini peta digital berupa peta topogarafi telah tersedia,
diperoleh dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB dan peta tutupan
lahan DAS Ciliwung segmen Kota Bogor tahun 2007-2009 diperoleh dari
Arc View 3.3
Arc GIS 9.3
3.5.2.2Pembuatan Peta DAS Ciliwung segmen Kota Bogor
Pada proses pembuatan peta DAS dibutuhkan peta topografi/kontur yang
kemudian diubah menjadi DEM untuk selanjutnya diolah menjadi peta DAS yang
diinginkan. Proses pembuatan peta DAS Ciliwung selengkapnya dapat dilihat
pada Gambar 4 sebagai berikut :
[image:41.612.165.456.182.516.2]Arc View 3.3
Gambar 4 Proses Pembuatan Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor
3.5.2.3Peta Sebaran Industri dan Peternakan
Peta sebaran industri dibuat setelah dilakukan pengecekan di lapangan
dengan penitikan pada setiap industri yang menghasilkan limbah cair.
3.5.2.4Peta Penutupan Lahan
Pemetaan penutupan lahan (land cover) merupakan suatu upaya untuk menyajikan informasi tentang pola penggunaan lahan atau tutupan lahan di
Surfacing
DEM
Grid Peta Kontur
Digital
AVSWAT 2005
suatu wilayah secara spasial. Berikut ini disajikan gambar proses
pengolahan citra untuk memperoleh peta penutupan lahan.
Tidak
[image:42.612.106.512.136.599.2]
Ya
Gambar 5 Proses Pengolahan Citra Landsat
3.5.3 Analisis Beban Pencemaran
Perhitungan beban pencemaran dari berbagai sumber pencemar dilakukan
melalui pendekatan Rapid Assesment of Sources of Air, Water, and Land Polution
yaitu perhitungan beban pencemaran dari setiap unit penghasil limbah
masing-Citra Landsat tahun 2009
Pemotongan Citra Koreksi Geometrik
Citra Terkoreksi
Citra Lokasi Penelitian
Cek Lapangan (Ground Check)
Klasifikasi Citra Terbimbing
Citra Hasil
Klasifikasi Akurasi
Diterima ?
masing dari pemukiman, industri, peternakan, pertanian dan tata guna lahan.
Setelah semua informasi yang diperlukan dikumpulkan, beban limbah dan
pencemaran air dapat dihitung mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memasukkan data produksi dan limbah ke dalam tabel kerja yang sesuai.
2. Mencari faktor limbah atau pencemaran yang berkaitan untuk
masing-masing proses industri atau sumber pencemar dan dicatat dalam kolom
yang tersedia. Adapun faktor konversi beban limbah dari suatu pencemar
dapat dilihat pada Tabel 9.
3. Jumlah produksi atau limbah tersebut dikalikan dengan faktor limbah atau
pencemaran dalam kolom yang disediakan.
4. Membuat ringkasan beban limbah dan pencemaran yang sudah dihitung
dalam tabel ringkasan untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai
total pencemaran air di areal studi.
Selain dengan langkah diatas, perhitungan beban pencemaran dapat
dirumuskan sebagai berikut:
P = C x L x R
Diketahui:
P = Beban Pencemaran (ton/bulan) C = Koefisien Beban Polutan
L = Kapasitas Limbah Cair (liter/hari) R = (3x10-8)
Tabel 9 Faktor Konversi Beban Limbah
Sumber Limbah
BOD (kg/unit/
tahun)
COD (kg/unit
/tahun)
TSS (kg/unit
/tahun)
TN (kg/unit
/tahun)
TP (kg/unit
/tahun)
Limbah Cair Domestik 19.7 44 20 3.3 0.4
Sapi potong/Kerbau 250 - 1716 80.3 -
Sapi perah 539 - - - -
Ayam potong/Itik 1.4 - 14.6 0.51 -
Ayam p