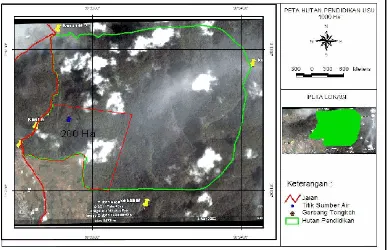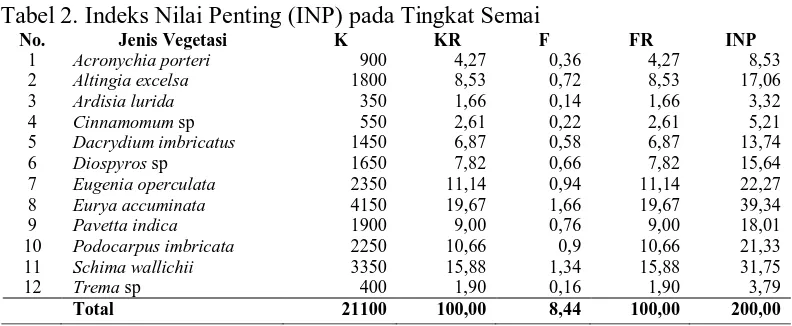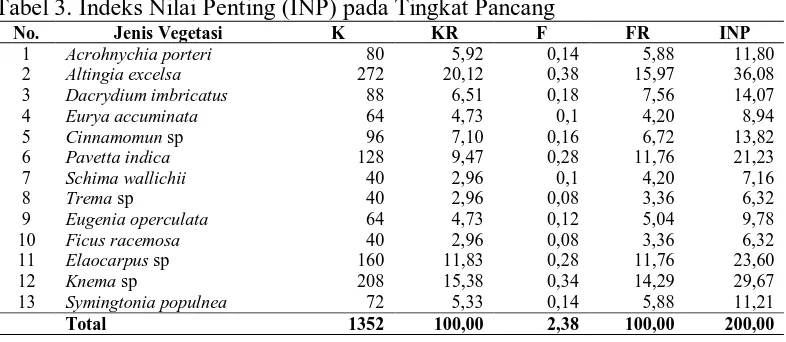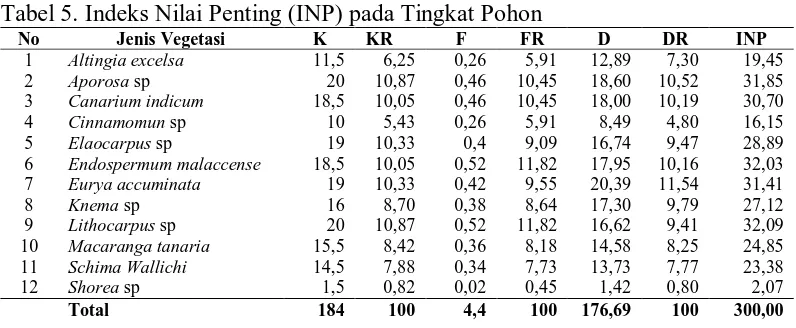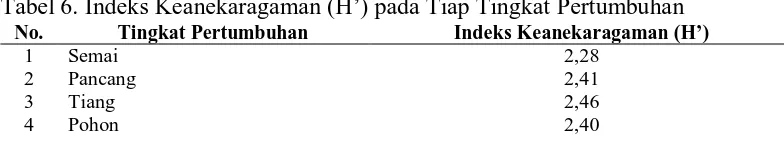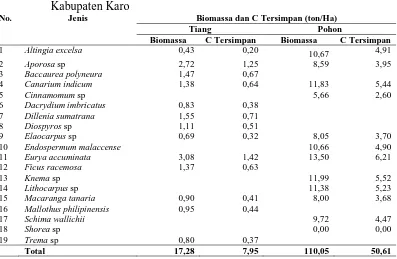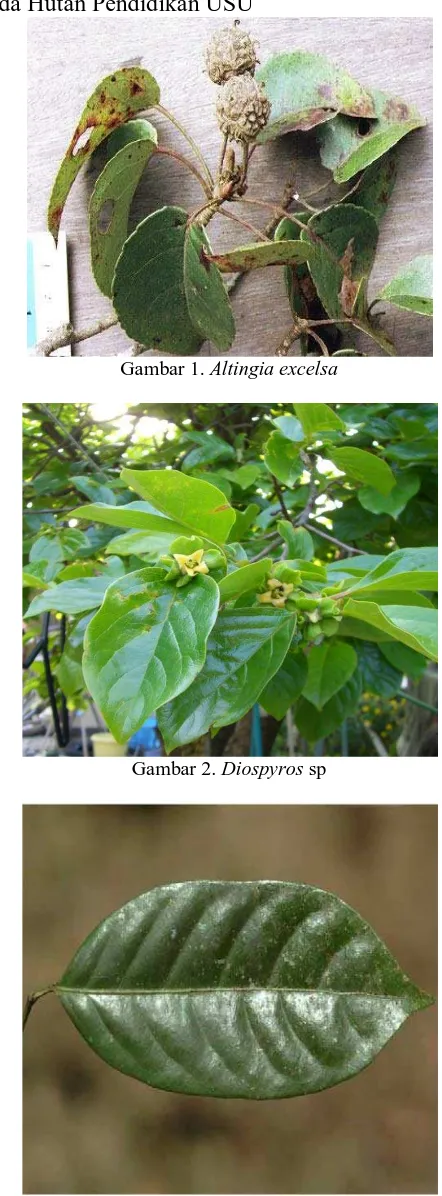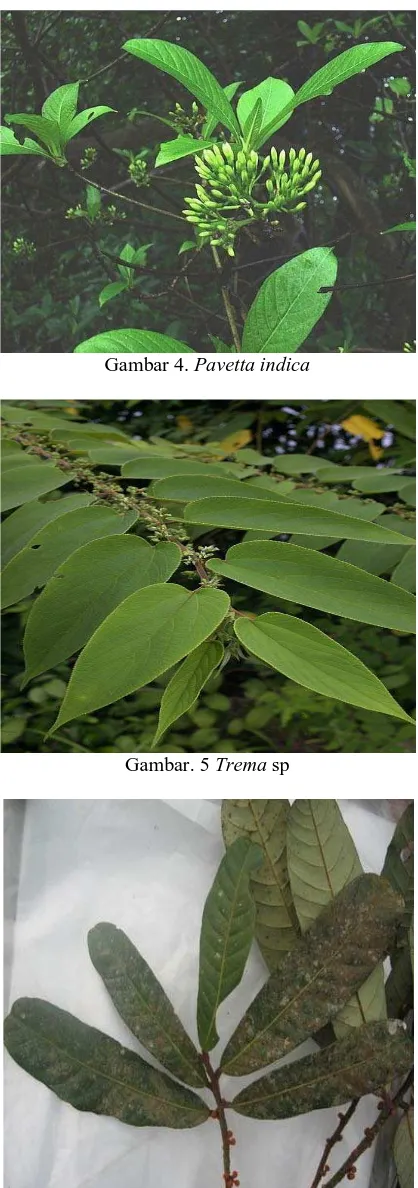KEANEKARAGAMAN HAYATI DI HUTAN PENDIDIKAN
USU TONGKOH KABUPATEN KARO
SKRIPSI
Togar Harapan Tampubolon 051202027
PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LEMBAR PENGESAHAN
Judul : Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan USU
Tongkoh Kabupaten Karo
Nama : Togar Harapan Tampubolon
NIM : 051202027
Program Studi : Kehutanan
Jurusan : Budidaya Hutan
Menyetujui,
Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing
Dr.Budi Utomo S,P. M,P Luthfi Hakim S.Hut, M.Si
NIP.19700820 200312 1 002 NIP. 19791017 200312 1 002
Mengetahui,
Ketua Program Studi Kehutanan
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat dan rahmatNyalah penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.
Adapun skripsi ini yang berjudul “Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan
USU Tongkoh Kabupaten Karo”.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi yaitu
Dr.Budi Utomo S,P. M,P dan Luthfi Hakim S.Hut, M.Si selaku ketua dan anggota
komisi pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam
penulisan skripsi ini, serta teman-teman yang turut memberi dukungan dalam
penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan,
untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi
kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pembaca maupun bagi penulis dikemudian hari. Akhir kata penulis ucapkan
terimakasih.
Medan, Agustus 2011
ABSTRACT
TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Biodiversity in the Forests of Education USU Tongkoh Karo Regency.
Supervised by: BUDI UTOMO and LUTHFI HAKIM.
The purpose of this study was to determine the structure, vegetation composition and carbon content stored on the Forest Education USU Tongkoh Karo. The research was conducted in the area of education Forest USU Tongkoh Karo, North Sumatra.
Materials studied were forest vegetation in the area of Forest Education Tongkoh USU. The method used was a method in which the placement berpetak line plot by systematic sampling with random start or systematically with the initial selection of a random path, the path width 20 x 20 meters. Laying the first plot was randomly while in the second plot and so systematically with the intensity of sampling (IS) of 1%, the distance between the plots is 200 m, with the number of 50 plots / unit example.
The results of vegetation analysis has been done on the Forest Education USU Tongkoh Karo, recorded 25 types of vegetation found in the growth rate, whereas the biodiversity index was classified at any level of growth. Forest carbon stocks stored at USU Education which has total area of 200 ha is equal to 11,712 tons.
ABSTRAK
TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo.
Dibimbing oleh: BUDI UTOMO dan LUTHFI HAKIM.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur, komposisi vegetasi, dan kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
Bahan yang diteliti adalah vegetasi hutan di kawasan Hutan Pendidikan USU Tongkoh. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak dimana penempatan plot dengan cara systematic sampling with random start atau secara sistematis dengan pemilihan awal jalur secara acak, dengan jalur selebar 20 x 20 meter. Peletakan plot pertama dilakukan secara acak sedangkan pada plot kedua dan seterusnya secara sistematik dengan intensitas sampling (IS) sebesar 1%, jarak antar plot adalah 200 m, dengan jumlah 50 plot/unit contoh.
Hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo, tercatat 25 jenis vegetasi yang ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan, sedangkan pada indeks keanekaragaman jenisnya tergolong sedang pada setiap tingkat pertumbuhannya. Cadangan karbon tersimpan pada Hutan Pendidikan USU yang memiliki luas areal 200 Ha adalah sebesar 11.712 ton.
DAFTAR ISI
Tujuan Penelitian ... 4
Manfaat Penelitian... 4
Analisis Vegetasi ... 10
Struktur dan Komposisi Hutan ... 11
Mengapa C Tersimpan Perlu Diukur... 12
Kondisi Umum Hutan Pendidikan USU ... 15
BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat ... 17
Bahan dan Alat ... 17
Bahan ... 17
Alat ... 17
Batasan Penelitian ... 18
Metode Pengumpulan Data ... 18
Metode Pengumpulan Contoh ... 18
Metode Analisis Data ... 19
Kelimpahan (Dominansi) Jenis ... 19
Keanekaragaman Jenis ... 20
Kandungan Karbon Tersimpan ... 20
HASIL DAN PEMBAHASAN Kekayaan Jenis ... 22
Kelimpahan (Dominansi) Jenis ... 22
Dominansi Semai ... 23
Dominansi Pancang ... 24
Dominansi Tiang ... 24
Dominansi Pohon ... 25
Keanekaragaman Jenis... 27
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan ... 31
Saran ... 31
DAFTAR PUSTAKA ... 32
DAFTAR GAMBAR
No. Halaman
1. Peta Lokasi Hutan Pendidikan USU ... 17
ABSTRACT
TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Biodiversity in the Forests of Education USU Tongkoh Karo Regency.
Supervised by: BUDI UTOMO and LUTHFI HAKIM.
The purpose of this study was to determine the structure, vegetation composition and carbon content stored on the Forest Education USU Tongkoh Karo. The research was conducted in the area of education Forest USU Tongkoh Karo, North Sumatra.
Materials studied were forest vegetation in the area of Forest Education Tongkoh USU. The method used was a method in which the placement berpetak line plot by systematic sampling with random start or systematically with the initial selection of a random path, the path width 20 x 20 meters. Laying the first plot was randomly while in the second plot and so systematically with the intensity of sampling (IS) of 1%, the distance between the plots is 200 m, with the number of 50 plots / unit example.
The results of vegetation analysis has been done on the Forest Education USU Tongkoh Karo, recorded 25 types of vegetation found in the growth rate, whereas the biodiversity index was classified at any level of growth. Forest carbon stocks stored at USU Education which has total area of 200 ha is equal to 11,712 tons.
ABSTRAK
TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo.
Dibimbing oleh: BUDI UTOMO dan LUTHFI HAKIM.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur, komposisi vegetasi, dan kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
Bahan yang diteliti adalah vegetasi hutan di kawasan Hutan Pendidikan USU Tongkoh. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak dimana penempatan plot dengan cara systematic sampling with random start atau secara sistematis dengan pemilihan awal jalur secara acak, dengan jalur selebar 20 x 20 meter. Peletakan plot pertama dilakukan secara acak sedangkan pada plot kedua dan seterusnya secara sistematik dengan intensitas sampling (IS) sebesar 1%, jarak antar plot adalah 200 m, dengan jumlah 50 plot/unit contoh.
Hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo, tercatat 25 jenis vegetasi yang ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan, sedangkan pada indeks keanekaragaman jenisnya tergolong sedang pada setiap tingkat pertumbuhannya. Cadangan karbon tersimpan pada Hutan Pendidikan USU yang memiliki luas areal 200 Ha adalah sebesar 11.712 ton.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hutan merupakan masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh
pohon- pohon yang menempati tempat dimana terdapat hubungan timbal balik
antara tumbuhan tersebut dengan lingkungannya. Pepohonan yang tinggi sebagai
komponen dasar dari hutan memegang peranan penting dalam menjaga kesuburan
tanah dengan menghasilkan serasah sebagai sumber unsur hara penting bagi
vegetasi (Ewusie,1990). Menurut Bachelard et al. (1985), pohon berperan dalam
perlindungan tanah dan daur hidrologi (cadangan air tanah), pencegah erosi dan
banjir, peredam polusi, menjaga keseimbangan iklim global dan sebagai sumber
plasma nutfah. Hutan hujan tropis merupakan salah satu tipe vegetasi hutan tertua
yang telah menutupi banyak lahan, terletak 100 LU dan 100 LS. Tegakan hutan
hujan tropis didominasi oleh pepohonan yang selalu hijau. Keanekaragaman
spesies tumbuhan dan binatang yang ada di hutan hujan tropis sangat tinggi
(Indriyanto, 2006).
Sebagian besar hutan-hutan di Indonesia termasuk dalam hutan hujan
tropis, yang merupakan masyarakat yang kompleks, tempat yang menyediakan
pohon dari berbagai ukuran. Di dalam kanopi iklim mikro berbeda dengan
keadaan sekitarnya, cahaya lebih sedikit, kelembaban sangat tinggi, dan
temperatur lebih rendah. Pohon-pohon kecil berkembang dalam naungan pohon
yang lebih besar, di dalam iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di dalam
lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro dari kanopi berkembang juga
tumbuhan yang lain seperti pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik, parasit dan
Greg-Smith (1983), menyatakan bahwa dengan analisis vegetasi dapat
diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas
tumbuhan. Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi
dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu (1) pendugaan komposisi vegetasi
dalam suatu areal dengan batas-batas jenis dan membandingkan dengan areal lain
atau areal yang sama namun waktu pengamatan berbeda; (2) menduga tentang
keragaman jenis dalam suatu areal; (3) melakukan korelasi antara perbedaan
vegetasi dengan faktor lingkungan tertentu atau beberapa faktor lingkungan.
Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu koleksi yang
unik dan mempunyai potensi genetik yang besar pula. Namun hutan yang
merupakan sumberdaya alam ini telah mengalami banyak perubahan dan sangat
rentan terhadap kerusakan. Sebagai salah satu sumber devisa negara, hutan telah
dieksploitasi secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Eksploitasi ini
menyebabkan berkurangnya luasan hutan dengan sangat cepat. Keadaan semakin
diperburuk dengan adanya konversi lahan hutan secara besar-besaran untuk lahan
pemukiman, perindustrian, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan serta
kebakaran hutan yang selalu terjadi di sepanjang tahun.
Keanekaragaman spesies, ekosistem dan sumberdaya genetik semakin
menurun pada tingkat yang membahayakan akibat kerusakan lingkungan.
Perkiraan tingkat kepunahan spesies di seluruh dunia berkisar antara 100.000
setiap tahun, atau beberapa ratus setiap hari. Kepunahan akibat beberapa jenis
tekanan dan kegiatan, terutama kerusakan habitat pada lingkungan alam yang
kaya dengan keanekaragam hayati, seperti hutan hujan tropik dataran rendah.
sebanyak 25% kehidupan akan hilang dari permukaan bumi. Hal tersebut
disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengarah pada kerusakan habitat maupun
pengalihan fungsi lahan. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena kita
ketahui keanekaragaman hayati mempunyai peranan penting sebagai penyedia
bahan makanan, obat-obatan dan berbagai komoditi lain penghasil devisa negara,
juga berperan dalam melindungi sumber air, tanah serta berperan sebagai
paru-paru dunia dan menjaga kestabilan lingkungan (Budiman, 2004).
Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan Sumatera Utara ditetapkan
dalam satu unit pengelolaan yang berintikan kawasan hutan lindung dan kawasan
konservasi. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun l988 tanggal 19
November 1988 Kawasan Hutan Sibolangit telah ditetapkan menjadi Taman
Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan dengan luas areal seluruhnya 51.600 Ha,
yang meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten. Kawasan tersebut, sebagian besar
merupakan hutan lindung, yaitu hutan lindung Sibayak I, hutan lindung Simacik,
hutan lindung Sibayak II, hutan lindung Simacik II, hutan lindung Sinabung dan
Suaka Margasatwa Langkat Selatan (Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara,
2006).
Hutan Pendidikan USU ini merupakan bagian dari kawasan Taman Hutan
Raya Bukit Barisan dimana luas hutannya mencakup 1000 Ha tepatnya di desa
Tongkoh, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo. Hutan Pendidikan USU
sendiri belum seluruhnya diketahui struktur dan komposisi vegetasi serta pola
komunitas vegetasinya, sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut
dalam rangka pengelolaan kawasan hutan pendidikan ini, apalagi kawasan ini
maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang keanekaragaman
hayati untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan USU Tongkoh, Kabupaten
Karo.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
1. Mengetahui struktur vegetasi dan komposisi kawasan Hutan Pendidikan
USU Tongkoh Kabupaten Karo,
2. Mengetahui kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan
USU Tongkoh Kabupaten Karo.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah
1. Memberikan informasi tentang keanekaragaman hayati pada Hutan
Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo,
2. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan
kawasan Hutan pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo dan
TINJAUAN PUSTAKA
Hutan
Hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi pepohonan, juga termasuk
tanaman kecil lainnya seperti, lumut, semak belukar, herba dan paku-pakuan.
Pohon merupakan bagian yang dominan diantara tumbuh-tumbuhan yang hidup di
hutan. Berbeda letak dan kondisi suatu hutan, berbeda pula jenis dan komposisi
pohon yang terdapat pada hutan tersebut. Sebagai contoh adalah hutan di daerah
tropis memiliki jenis dan komposisi pohon yang berbeda dibandingkan dengan
hutan pada daerah temprate (Rahman, 1992).
Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta
tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan
sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan juga merupakan suatu asosiasi
dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi
berkayu yang menempati areal luas. Hutan juga sebagai masyarakat
tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan
berbeda dengan keadaan di luar hutan. Di dalam hutan juga akan terjadi
persaingan antar anggota-anggota yang hidup saling berdekatan, misalnya
persaingan dalam penyerapan unsur hara, air, sinar matahari, ataupun tempat
tumbuh. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, tetapi juga pada
binatang (Arief, 2001).
Irwan (1992), mengatakan hutan hujan tropis sangat menarik, merupakan
ekosistem yang klimaks. Tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan ini tidak
pernah menggugurkan daunnya secara serentak, kondisinya sangat bervariasi
perkecambahan atau berada dalam tingkatan kehidupan sesuai dengan sifat atau
kelakuan masing-masing jenis tumbuh-tumbuhan tersebut. Hutan hujan tropis
memiliki vegetasi yang khas daerah dan menutupi semua permukaan daratan yang
memiliki iklim panas, curah hujan cukup tersebar merata.
Hutan memiliki manfaat bagi manusia berupa manfaat langsung dirasakan
maupun manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila
hutan terjamin ekosistemnya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Manfaat
hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin ekosistensinya sehingga dapat
berfungsi secara optimal. Manfaat hutan secara tidak langsung meliputi fungsi
fungsi ekologi seperti membantu memperbaiki atmosfer dengan penyediaan
oksigen, memperbaiki lingkungan hidup dalam berbagai bentuk misalnya
mencegah terjadinya tanah longsor dengan menahan air hujan, serta menjadi
tempat tinggal beberapa jenis tanaman dan binatang tertentu yang tidak bisa hidup
di tempat lainnya. Manfaat hutan secara langsung dapat berupa fungsi ekonomi
dan sosial dari hutan yang akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan
sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna
mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Zain, 1992).
Daniel et al. (1992), menyatakan bahwa hutan memiliki beberapa fungsi
bagi kehidupan manusia antara lain : (1) pengembangan dan penyediaan atmosfer
yang baik dengan komponen oksigen yang stabil, (2) produksi bahan bakar fosil
(batubara), (3) pengembangan dan proteksi lapisan tanah, (4) produksi air bersih
dan proteksi daerah aliran sungai terhadap erosi, (5) penyediaan habitat dan
makanan untuk binatang, serangga, ikan, dan burung, (6) penyediaan materil
estetis, rekreasi, kondisi alam asli, dan taman. Semua manfaat tersebut kecuali
produksi bahan bakar fosil , berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Hutan alam di indonesia sebagian besar menempati tipe hutan tropis basah
yang didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae (Marsono, 1991). Dataran yang
ditempati oleh hutan ini adalah rata dan juga bergelombang, meskipun hutan ini
dapat meluas ke bagian bawah lereng-lereng gunung sampai ketinggian kira-kira
100 meter diatas permukaan laut (3.218 kaki) atau bahkan lebih (Polunin, 1990).
Hutan Hujan Tropis
Hutan hujan tropis merupakan jenis vegetasi yang paling subur. Hutan
jenis ini terdapat di wilayah baru tropika atau didekat wilayah tropika di bumi
yang menerima curah hujan berlimpah sekitar 2000 – 4000 mm setahunnya.
Suhunya tinggi (sekitar 250 – 260 C) dan seragam, dengan kelembaban rata-rata
sekitar 80%. Komponen dasar hutan itu adalah pohon tinggi dengan tinggi
maksimun rata-rata 30 m. Tajuk pepohonan dengan tumbuhan terna, perambat,
epifit, pencekik, saprofit dan parasit (Ewusie, 1980).
Hutan hujan tropik (tropical rain forest) terdapat di daerah tropis basah
dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, seperti di Amerika Tengah dan
selatan, Afrika, Asia Tenggara Timur Laut. Dalam kawasan ini pohon-pohonnya
tinggi, pada umumnya berdaun lebar, hijau dan jenisnya besar
(Syahbuddin, 1987).
Sebagian besar hutan-hutan di Indonesia termasuk dalam hutan hujan
tropis, yang merupakan masyarakat yang kompleks, tempat yang menyediakan
pohon dari berbagai ukuran. Di dalam kanopi iklim mikro berbeda dengan
temperatur lebih rendah. Pohon pohon kecil berkembang dalam naungan pohon
yang lebih besar, di dalam iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di dalam
lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di
dalam lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro dari kanopi berkembang juga
tumbuhan yang lain seperti pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik, parasit dan
saprofit (Irwanto, 2006).
Arief (1986) dalam Indriyanto (2006), menjelaskan bahwa di hutan hujan
tropik terdapat stratifikasi tajuk dari berbagai spesies pohon yang berbeda
ketinggiannya. Tajuk pohon yang bersatu dan rapat dtambah dengan adanya
tumbuh-tumbuhan pemanjat yang menggantung dan menempel pada dahan pohon,
misalnya rotan, anggrek, dan paku-pakuan. Hal itu, menyebabkan sinar matahari
tidak dapat menembus sampai ke lantai hutan. Hal itu juga menyebabkan tidak
memungkinkan semak-semak tumbuh dan berkembang, kecuali jenis cendawan
yang suka hidup di tempat yang kurang cahaya. Ciri-ciri khas tersebut dimiliki
oleh hutan hujan tropik. Di indonesia, hutan hujan tropik terdapat di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Hutan tersebut mempunyai lebih
kurang 3000 jenis pohon besar dan termasuk ke dalam 450 marga atau genus.
Longman & Jenik (2008), mendefinisikan hutan hujan tropik sebagai
hutan yang selalu hijau, bersifat higrofilus, tinggi pohon paling rendah 30 m, kaya
akan liana berbatang tebal dan memiliki epifit bersifat herba dalam jumlah yang
besar. Meyers (1976) dalam Mabberly (1983), memberi definisi hutan hujan
tropik dengan sebutan hutan evergreen, memiliki curah hujan tidak kurang dari
100 mm setiap bulan dengan suhu rata-rata tahunan lebih dari 240C serta bebas
Posisi hutan hujan tropik di daerah ekuator menjadikannya lebih banyak
mendapat radiasi matahari daripada hutan-hutan yang ada di luar ekuator serta
tidak adanya periode musim yang mengurangi lamanya hari terang. Sekalipun
demikian, daerah tropik tidak termasuk daerah yang memiliki iklim seragam, arah
angin dan arus laut kontinental membuatnya memiliki variasi curah hujan,
kelembaban relatif, temperatur dan angin (Longman & Jenik 1987).
Pohon
Pohon-pohon menjadi organisme dominan di hutan tropis, bentuk
kehidupan pohon berpengaruh pada psiognomi umum, produksi dasar dan
lingkaran keseluruhan dari komunitas. Banyak ciri-ciri pohon tropis berbeda
dengan daerah lain mengingat terdapat ciri-ciri tertentu dan kebiasaan bercabang
buah-buahan dan sistem akar yang jarang dan tidak pernah dijumpai di bagian
bumi lain (Longman & Jenik, 1987).
Menurut Sutarno & Soedarsono (1997), pohon hutan merupakan
tumbuhan yang berperawakan pohon, batangnya tunggal berkayu, tegak biasanya
beberapa meter dari tanah tidak bercabang, mempunyai tajuk dengan percabangan
dan daun yang berbentuk seperi kelapa. Menurut Whitmore (1986) dalam Tamin
(1991), pohon tumbuh serta alami di hutan dalam bentukyang dominan dalam
hutan hujan, bahkan tumbuhan bawah sebagian besarnya terdiri daripada
tumbuhan berkayu yang mempunyai bentuk pohon. Untuk keperluan
inventarisasi, pohon dibedakan menjadi stadium seedling, sapling, pole, dan
pohon dewasa. Wyatt-Smith (1963) dalam Soerianegara & Indrawan (1978),
membedakan sebagai berikut :
b) Sapling (pancang, sapihan) yaitu permudaan yang tingginya 1,5 m lebih
sampai pohon-pohon muda berdiameter kurang dari 10 cm.
c) Pole (tiang) yaitu pohon-pohon muda yang berdiameter 10-35 cm.
d) Tree (pohon dewasa) yaitu pohon yang berdiameter lebih dari 35 cm yang
diukur 1,3 m dari permukaan tanah.
Vegetasi
Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang
tumbuh bersama-sama pada satu tempat dimana antara individu penyusunnya
terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan
hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Dengan kata
lain, vegetasi tidak hanya kumpulan dari individu-individu tumbuhan melainkan
membentuk suatu kesatuan dimana individu-individunya saling tergantung satu
sama lain, yang disebut sebagai suatu komunitas yumbuh-tumbuhan (Ruslan,
1986).
Analisis Vegetasi
Menurut Soerianegara & Indrawan (1978) yang dimaksud analisis vegetasi
atau studi komunitas adalah suatu cara mempelajari susunan (komposisi jenis) dan
bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Cain & Castro
(1959) dalam Soerianegara & Indrawan (1978) mengatakan bahwa penelitian
yang mengarah pada analisis vegetasi, titik berat penganalisisan terletak pada
komposisi jenis atau jenis. Struktur masyarakat hutan dapat dipelajari dengan
mengetahui sejumlah karakteristik tertentu diantaranya, kepadatan, frekuensi,
Struktur dan Komposisi Hutan
Struktur merupakan lapisan vertikal dari suatu komunitas hutan. Dalam
komunitas selalu terjadi kehidupan bersama saling menguntungkan sehingga
dikenal adanya lapisan-lapisan bentuk kehidupan (Syahbudin, 1987). Selanjutnya
Daniel et al. (1992), menyatakan struktur tegakan atau hutan menunjukkan
sebaran umur atau kelas diameter dan kelas tajuk. Soerianegara & Indrawan
(1978) dalam Indriyanto (2005), menguraikan stratifikasi hutan hujan tropis
menjadi lima stratum yaitu :
1. Stratum A (A-storey), yaitu lapisan tajuk (kanopi) hutan paling atas yang
dibentuk oleh pepohonan yang tingginya lebih dari 30 m.
2. Stratum B (B-storey), yaitu lapisan tajuk kedua dari atas yang dibentuk
oleh pepohonan yang tingginya 20-30 m.
3. Stratum C (C-storey), yaitu lapisan tajuk ketiga dari atas yang dibentuk
oleh pepohonan yang tingginya 4-20 m.
4. Stratum D (D-storey), yaitu lapisan tajuk keempat dari atas yang dibentuk
oleh spesies tumbuhan semak dan perdu yang tingginya 1-4 m.
5. Stratum E (E-storey), yaitu lapisan tajuk paling bawah (lapisan kelima dari
atas) yang dibentuk oleh spesies-spesies tumbuhan penutup tanah (ground
cover) yang tingginya 0-1 m.
Mengapa C Tersimpan Perlu Diukur
Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena
tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau
karbondioksida (CO2), metana (CH4) dan nitrogen oksida (N2O) yang lebih
dikenal dengan gas rumah kaca (GRK). Saat ini konsentrasi GRK sudah mencapai
tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistem
(Hairiah dan Rahayu, 2007).
Konsentrasi GRK di atmosfir meningkat sebagai akibat adanya
pengelolaan lahan yang kurang tepat, antara lain adanya pembakaran vegetasi
hutan dalam skala luas pada waktu yang bersamaan dan adanya pengeringan lahan
gambut. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada awal alih guna
lahan hutan menjadi lahan pertanian. Kebakaran hutan dan lahan serta gangguan
lahan lainnya telah menempatkan Indonesia dalam urutan ketiga negara penghasil
emisi CO2 terbesar di dunia. Indonesia berada di bawah Amerika Serikat dan
China, dengan jumlah emisi yang dihasilkan mencapai dua miliar ton CO2
pertahunnya atau menyumbang 10% dari emisi CO2 di dunia
(Hairiah dan Rahayu, 2007).
Tumbuhan memerlukan sinar matahari, gas asam arang (CO2) yang
diserap dari udara serta air dan hara yang diserap dari dalam tanah untuk
kelangsungan hidupnya. Melalui proses fotosintasis, CO2 di udara diserap oleh
tanaman dan diubah menjadi karbohidrat, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh
tanaman dan akhirnya ditimbun dalam tubuh tanaman berupa daun, batang,
ranting, bunga dan buah. Proses penimbunan C dalam tubuh tanaman hidup
dinamakan proses sekuestrasi (Csequestration). Dengan demikian mengukur
dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfir yang diserap oleh tanaman
(Hairiah dan Rahayu, 2007).
Lebih lanjut Hairiah dan Rahayu (2007) mengatakan, tanaman atau pohon
berumur panjang yang tumbuh di hutan maupun di kebun campuran (agroforestri)
merupakan tempat penimbunan atau penyimpanan C (rosot C = C sink) yang jauh
lebih besar daripada tanaman semusim. Oleh karena itu, hutan alami dengan
keragaman jenis pepohonan berumur panjang dan seresah yang banyak
merupakan gudang penyimpanan C tertinggi (baik di atas maupun di dalam
tanah). Hutan juga melepaskan CO2 ke udara lewat respirasi dan dekomposisi
(pelapukan) seresah, namun pelepasannya terjadi secara bertahap, tidak sebesar
bila ada pembakaran yang melepaskan CO2 sekaligus dalam jumlah yang besar.
Bila hutan diubah fungsinya menjadi lahan-lahan pertanian atau perkebunan atau
ladang pengembalaan maka C tersimpan akan merosot. Berkenaan dengan upaya
pengembangan lingkungan bersih, maka jumlah CO2 di udara harus dikendalikan
dengan jalan meningkatkan jumlah serapan CO2 oleh tanaman sebanyak mungkin
dan menekan pelepasan (emisi) CO2 ke udara serendah mungkin. Jadi,
mempertahankan keutuhan hutan alami, menanam pepohonan pada lahan-lahan
pertanian dan melindungi lahan gambut sangat penting untuk mengurangi jumlah
CO2 yang berlebihan di udara. Jumlah “C tersimpan” dalam setiap penggunaan
lahan tanaman, seresah dan tanah, biasanya disebut juga sebagai “cadangan C”.
Penebangan hutan akan menyebabkan terbukanya permukaan tanah
terhadap radiasi dan cahaya matahari. Dampak langsungnya adalah meningkatnya
suhu tanah dan turunnya kadar air tanah. Dampak langsung lainnya dari kegiatan
(above-ground carbon stocks) dan selanjutnya akan mempengaruhi penyusutan cadangan
karbon bawah-permukaan (below-ground carbon stocks) (Murdiyarso et al, 2004).
Kegiatan konversi hutan menjadi lahan pertanian melepaskan cadangan
karbon ke atmosfir dalam jumlah yang cukup berarti. Namun jumlah tersebut
tidak memberikan dampak yang berarti terhadap jumlah CO2 yang mampu diserap
oleh hutan dan daratan secara keseluruhan. Dampak konversi hutan ini baru terasa
apabila diikuti dengan degradasi tanah dan hilannya vegetasi, serta berkurangnya
proses fotosintesis akibat munculnya hutan beton serta lahan yang dipenuhi
bangunan- bangunan dari aspal sebagai pengganti tanah atau rumput. Meskipun
laju fotosintesis pada lahan pertanian dapat menyamai laju fotosintesis pada hutan,
namun jumlah cadangan karbon yang terserap lahan pertanian jauh lebih kecil.
Selain itu, karbon yang terikat oleh vegetasi hutan akan segara dilepaskan kembali
ke atmosfir melalui pembakaran, dekomposisi sisa panen maupun pengangkutan
hasil panen. Masalah utama yang terkait dengan alih guna lahan adalah perubahan
jumlah cadangan karbon. Pelepasan karbon ke atmosfir akibat konversi hutan
berjumlah sekitar 250 Mg ha-1 C yang terjadi selama penebangan dan
pembakaran, sedangkan penyerapan kembali karbon menjadi vegetasi pohon
relatif lambat, hanya sekitar 5 Mg ha-1 C. Penurunan emisi karbon dapat dilakukan
dengan: (a) mempertahankan cadangan karbon yang telah ada dengan mengelola
hutan lindung, mengendalikan deforestasi, menerapkan praktek silvikultur yang
baik, mencegah degradasi lahan gambut dan memperbaiki pengelolaan cadangan
bahan organik tanah, (b) meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman
dapat diperbarui secara langsung maupun tidak langsung (angin, biomassa, aliran
air), radiasi matahari, atau aktivitas panas bumi (Rahayu, S et al, 2007).
Peningkatan penyerapan cadangan karbon dapat dilakukan dengan: (a)
meningkatkan pertumbuhan biomasa hutan secara alami, (b) menambah cadangan
kayu pada hutan yang ada dengan penanaman pohon atau mengurangi pemanenan
kayu, dan (c) mengembangkan hutan dengan jenis pohon yang cepat tumbuh.
Karbon yang diserap oleh tanaman disimpan dalam bentuk biomasa kayu,
sehingga cara yang paling mudah untuk meningkatkan cadangan karbon adalah
dengan menanam dan memelihara pohon (Hairiah dan Rahayu, 2007).
Kondisi Umum Hutan Pendidikan USU
Taman Hutan Raya Bukit Barisan Sumatera Utara ditetapkan dalam satu
unit pengelolaan yang berintikan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.
Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun l988 tanggal 19 November
1988 Kawasan Hutan Sibolangit telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya
(Tahura) Bukit Barisan dengan luas areal seluruhnya 51.600 Ha. Yang
meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten. Kawasan tersebut, sebagian besar
merupakan hutan lindung, yaitu hutan lindung Sibayak I, hutan lindung Simacik,
hutan lindung Sibayak II, hutan lindung Simacik II, hutan lindung Sinabung dan
Suaka Margasatwa Langkat Selatan.
Wilayah kerja pengembangan meliputi seluruh kawasan Taman Hutan
Raya Bukit Barisan yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten
Luas keseluruhan areal Taman Hutan Raya Bukit Barisan berdasarkan
Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1988 seluas 51.600 Ha, dan terletak di empat
Kabupaten, yaitu :
- Kabupaten Langkat seluas 13.000 Ha
- Kabupaten Deli Serdang seluas 17.150 Ha
- Kabupaten Simalungun seluas 1.645 Ha
- Kabupaten Tanah Karo seluas 19.805 Ha
Perincian letak per-kawasan hutan adalah sebagai berikut :
- Lindung Sinabung seluas 13.448 Ha
- Hutan Lindung Sibayak 1 seluas 7.030 Ha
- Hutan Lindung Sibayak II seluas 6.350 Ha
- Hutan Lindung Simacik 1 seluas 9.800 Ha
- Hutan Lindung Simacik II seluas 1.645 Ha
- Taman Wisata Alam Lau Debuk-debuk seluas 7 Ha
- Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit seluas 200 Ha
- Cagar Alam/Taman Wisata Alam Sibolangit seluas 120 Ha
- Suaka Margasatwa Langkat Selatan seluas 13.000 Ha
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Januari 2011
sampai dengan bulan Maret 2011. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan
pendidikan USU Tongkoh, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
Gambar.1 Peta Lokasi Hutan Pendidikan USU
Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang diteliti adalah vegetasi hutan di kawasan Hutan Pendidikan
USU Tongkoh.
Alat
Alat yang digunakan meliputi GPS (Global Positioning System), kompas,
altimeter, clinometer, pita ukur/ roll/ phi band/ tali, pisau, kamera, dan alat tulis
kertas koran, label, dan oven dalam menganalisis vegetasi yang jenisnya tidak
dikenali untuk diidentifikasi lebih lanjut.
Batasan Penelitian
Pada awalnya penelitian ini dilakukan pada Hutan Pendidikan USU
dengan luasan 200 Ha, akan tetapi pada bulan Mei 2011 telah diresmikannya
hutan ini dengan luasan 1000 Ha. Untuk itu, batasan penelitian yang digunakan
adalah 200 Ha bukan untuk 1000 Ha.
Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari survei secara langsung dengan menganalisis
vegetasi hutan sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur pustaka.
Metode pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara metode
garis berpetak (plot).
Metode Pengambilan Contoh
Metode garis berpetak dimana penempatan plot dengan cara systematic
sampling with random start atau secara sistematis dengan pemilihan awal jalur
secara acak, dengan jalur selebar 20 x 20 meter. Peletakan plot pertama dilakukan
secara acak sedangkan pada plot kedua dan seterusnya secara sistematik dengan
intensitas sampling (IS) sebesar 1%, jarak antar plot adalah 200 m, dengan jumlah
50 plot/unit contoh. Dari setiap petak dihitung jumlah individu setiap spesies dan
diukur diameter serta tinggi pohon vegetasi tingkat pohon (diameter > 20 cm)
plot 10 x 10 m, tingkat pancang (diameter < 10 cm) dengan ukuran plot 5 x 5 m,
serta tingkat semai (diameter < 1,5 cm) dengan ukuran plot 2 x 2 m.
Gambar. 2 Desain Unit Contoh Analisis Vegetasi
Metode Analisis Data
Kelimpahan (Dominansi) Jenis
Data vegetasi yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui
kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, dominansi relatif, frekuensi
jenis dan frekuensi relatif serta indeks nilai penting menggunakan rumus sebagai
berikut :
Kerapatan = Jumlah individu
Luas petak ukur
Kerapatan relatif = Kerapatan satu jenis x 100% Kerapatan seluruh jenis
Dominansi = Luas penutupan suatu jenis
Luas petak
Dominansi relatif = Dominansi suatu jenis x 100% Dominansi seluruh jenis
Frekuensi = Jumlah petak penemuan suatu jenis
Frekuensi relatif = Frekuensi suatu jenis x 100% Frekuensi seluruh jenis
Indeks nilai penting = Kerapatan relatif +Frekuensi relatif + Dominansi relatif
(Indeks nilai penting untuk tingkat pohon dan tiang), dan
Indeks nilai penting = Kerapatan relatif + Frekuensi relatif
(Indeks nilai penting untuk tingkat pancang dan semai).
Keanekaragaman Jenis
Untuk mengetahui keanekaragaman jenis vegetasi, digunakan indeks
keragaman Shannon-Wienner’s, dimana : • Indeks diversitas Shannon-Wienner’s
Keterangan :
H’ = Indeks diversitas Shannon-Wienner’s
Ni = Jumlah individu jenis ke-i
N = Total jumlah individu
S = Jumlah jenis
Ln = Logaritma natural
Pendugaan Karbon Tersimpan
Pendugaan cadangan karbon di atas permukaan terlebih dahulu diduga
jumlah biomassa vegetasi. Pendugaan biomassa vegetasi ini menggunakan
persamaan allometrik :
Keterangan :
BK = Biomassa pohon (kg/m2)
D = Diameter batang (cm)
ρ = Berat jenis kayu (gr/cm3)
Untuk berat jenis kayu (ρ) diperoleh dari Wood Density Database (Worldagroforestry, 2010), Global wood density database (Zanne et.al., 2009)
dan Woody Density Phase 1 (National Carbon Accounting System, 2009).
Hairiah dan Rahayu (2007) menyatakan bahwa untuk melakukan estimasi
jumlah C tersimpan dalam bahan organik adalah 46%, oleh karena itu estimasi
jumlah C tersimpan per komponen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
C tersimpan per hektar = Biomassa (kg ha-1) x 0.46
Untuk mendapatkan data karbon tersimpan di dalam kawasan Hutan
Pendidikan USU, maka didapatkan hasil akhir karbon tersimpan dalam tiap hektar
dikalikan dengan luas kawasan yaitu :
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekayaan Jenis
Berdasarkan hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan pada Hutan
Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo, tercatat 25 jenis vegetasi yang
ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan yaitu pada tingkat semai, pancang,
tiang, dan pohon.
Tabel 1. Jenis Vegetasi pada Hutan Pendidikan USU
No Tingkat Pertumbuhan Jumlah Jenis Jenis Vegetasi
1 Semai 12 Acronychia porteri, Altingia excelsa, Ardisia lurida, Cinnamomum sp, Dacrydium imbricatus, Diospyros sp, Eugenia operculata, Eurya accuminata, Pavetta indica, Podocarpus imbricata, Schima wallichii, Trema sp.
2 Pancang 13 Acrohnychia porteri, Altingia excelsa, Dacrydium imbricatus, Eurya accuminata, Cinnamomun sp, Pavetta indica, Schima wallichii, Trema sp, Eugenia operculata, Ficus racemosa, Elaocarpus sp, Knema sp, Symingtonia populnea.
3 Tiang 13 Altingia excelsa, Aporosa sp, Baccaurea polyneura, Canarium indicum, Dacrydium imbricatus, Dillenia sumatrana, Diospyros sp, Elaocarpus sp, Eurya accuminata, Ficus racemosa, Macaranga tanaria, Mallothus philipinensis, Trema sp.
4 Pohon 12 Altingia excelsa, Aporosa sp, Canarium indicum, Cinnamomun sp, Elaocarpus sp, Endospermum malaccense, Eurya accuminata, Knema sp, Lithocarpus sp, Macaranga tanaria, Schima Wallichi, Shorea sp.
Hasil analisis vegetasi hutan yang meliputi komposisi jenis tumbuhan di
Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo dapat dilihat pada Tabel 1,
diperoleh jenis vegetasi pada tingkat semai (12 jenis), tingkat pancang (13 jenis),
tingkat tiang (13 jenis), dan tingkat pohon (13 jenis).
Kelimpahan (Dominansi) Jenis
Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai
untuk menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam
komunitas tumbuhan akan memiliki indeks nilai penting yang tinggi
(Indriyanto, 2006).
Indeks Nilai Penting menyatakan kepentingan suatu jenis tumbuhan serta
memperlihatkan peranannya dalam komunitas, di mana nilai penting itu pada
tingkatan pohon didapat dari hasil penjumlahan kerapatan relatif (KR), frekuensi
relatif (FR) dan dominansi relatif (DR). Sedangkan pada tabel didapat dari
penjumlahan nilai kerapatan relatif (KR) dan Frekuensi relatif (FR).
Dominansi Semai
Tabel 2. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Semai
No. Jenis Vegetasi K KR F FR INP
Semai adalah permudaan mulai kecambah sampai setinggi 1,5 m. Pada
Hutan Pendidikan USU didapatkan 12 jenis vegetasi pada tingkat semai, seperti
pada Tabel 2, dalam tabel tersebut diperoleh INP tertinggi pada jenis Eurya
accuminata (INP = 39,34 %), diikuti jenis Eugenia operculata (INP = 22,27 %)
Dominansi Pancang
Tabel 3. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Pancang
No. Jenis Vegetasi K KR F FR INP
Pancang adalah permudaan yang tingginya 1,5 m dan lebih sampai
pohon-pohon muda yang berdiameter kurang dari 10 cm. Pada Hutan Pendidikan USU
didapatkan 13 jenis vegetasi pada tingkat pancang, seperti pada Tabel 3, dalam
tabel tersebut diperoleh INP yang tertinggi Altingia excelsa (INP = 36,08 %),
diikuti jenis Knema sp (INP = 29,67 %), dan yang terendah didapatkan pada dua
jenis vegetasi yaitu pada jenis Trema sp dan Ficus racemosa (INP = 6,32 %).
Dominansi Tiang
Tabel 4. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Tiang
No Jenis Vegetasi K KR F FR D DR INP
Tiang meliputi pohon- pohon yang memiliki diameter 10-20cm. Pada
(INP = 51,67 %), diikuti jenis Eurya accuminata (INP = 42,59 %), dan INP yang
terendah pada jenis Elaocarpus sp (INP = 13,19 %).
Dominansi Pohon
Tabel 5. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Pohon
No Jenis Vegetasi K KR F FR D DR INP
Pohon meliputi pohon- pohon dewasa yang memiliki diameter > 20 cm.
Pada hutan Pendidikan USU didapatkan 12 jenis vegetasi pada tingkat tiang,
seperti pada Tabel 5, diperoleh INP yang tertinggi pada jenis Lithocarpus sp (INP
= 32,09 %), diikuti jenis Endospermum mallaccense (INP = 32,03 %), dan INP
yang terendah pada jenis Shorea sp (INP = 2,07 %).
Menurut Nevada (2007), besarnya nilai INP suatu jenis memperlihatkan
peranan suatu jenis dalam komunitas. Suatu jenis yang memiliki nilai INP lebih
besar dibandingkan dengan jenis lainnya menandakan bahwa suatu jenis pada
komunitas tersebut dikatakan mendominasi atau menguasai ruang di dalam
komunitas tersebut. Hal ini disebabkan jenis tersebut mempunyai kesesuaian
tempat tumbuh yang baik serta mempunyai daya tahan hidup yang baik pula jika
dibandingkan dengan jenis lain yang ada dalam komunitas tersebut.
Spesies- spesies yang dominan (yang berkuasa) dalam suatu komunitas
paling dominan tentu saja memiliki indeks nilai penting yang paling besar
(Indriyanto, 2006).
Menurut Odum (1971), jenis yang dominan mempunyai produktivitas
yang besar, dan dalam menentukan suatu jenis vegetasi dominan yang perlu
diketahui adalah diameter batangnya. Keberadaan jenis dominan pada lokasi
penelitian menjadi suatu indikator bahwa komunitas tersebut berada pada habitat
yang sesuai dan mendukung pertumbuhannya.
Nilai Kerapatan Relatif (KR) tertinggi terdapat pada jenis Altingia excelsa
dengan nilai sebesar 20,12%. Tingginya nilai ini menunjukkan banyaknya jenis
tersebut pada hutan ini. Beragamnya nilai kerapatan relatif ini mungkin
disebabkan karena kondisi hutan pegunungan yang memiliki variasi lingkungan
yang tinggi. Menurut Loveless (1989), sebagian tumbuhan dapat berhasil tumbuh
dalam kondisi lingkungan yang beraneka ragam sehingga tumbuhan tersebut
cenderung tersebar luas.
Nilai frekuensi relatif (FR) tertinggi terdapat pada jenis Eurya accuminata
dengan nilai sebesar 19,67%. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa jenis-jenis ini
banyak terdapat pada hutan pendidikan USU. Berdasarkan nilai FR tersebut dapat
dilihat proporsi antara jumlah pohon dalam suatu jenis dengan jumlah jenis
lainnya di dalam komunitas serta dapat menggambarkan penyebaran individu di
dalam komunitas.
Nilai Dominansi Relatif tertinggi ditempati oleh jenis Aporosa sp yaitu
sebesar 18,08 %, sedangkan yang terendah ditempati oleh jenis Shorea sp yaitu
yang ditutupi oleh jenis tumbuhan dengan luas total habitat serta menunjukkan
jenis tumbuhan yang dominan didalam komunitas (Indriyanto, 2006).
Menurut Odum (1971), jenis yang dominan mempunyai produktivitas
yang besar, dan dalam menentukan suatu jenis vegetasi dominan yang perlu
diketahui adalah diameter batangnya. Keberadaan jenis dominan pada lokasi
penelitian menjadi suatu indikator bahwa komunitas tersebut berada pada habitat
yang sesuai dan mendukung pertumbuhannya.
Keanekaragaman Jenis
Komposisi vegetasi pada suatu tipe hutan sangat penting diketahui,
komposisi dimaksud meliputi vegetasi pada lapisan tajuk di bagian atas (pohon)
dan vegetasi pada lapisan bawah (lantai hutan). Tingginya tingkat
keanekaragaman hayati (biodiversity) di hutan tropis merupakan satu kekayaan
tersendiri yang tidak ternilai harganya. Hutan tropis dengan kondisi vegetasi yang
masih baik merupakan laboratorium hidup yang menyimpan berbagai rahasia
alam yang masih perlu dipelajari. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya
mempertahankan hutan tropis perlu dilakukan demi pemenuhan kebutuhan hidup
di masa depan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(Sidiyasa, 2006).
Tabel 6. Indeks Keanekaragaman (H’) pada Tiap Tingkat Pertumbuhan
No. Tingkat Pertumbuhan Indeks Keanekaragaman (H’)
1 Semai 2,28
2 Pancang 2,41
3 Tiang 2,46
4 Pohon 2,40
Berdasarkan indeks keanekaragaman jenis (H’) yang didapatkan pada
Tabel 6, bahwa tingkat pertumbuhan pada tingkat tiang diperoleh indeks
= 2,41), kemudian pada tingkat pohon (H’ = 2,40) dan yang paling rendah
didapatkan pada tingkat semai (H’ = 2,28).
Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi
jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies, dan sebaliknya suatu komunitas
dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitasnya itu
disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan
(Indriyanto,2006).
Menurut Mason (1980), jika nilai indeks keanekaragaman lebih kecil dari
1 berarti keanekaragaman jenis rendah, jika diantara 1-3 berarti keanekaragaman
jenis sedang, jika lebih besar dari 3 berarti keanekaragaman jenis tinggi, sehingga
didapatkan bahwa hutan Pendidikan USU memiliki indeks keanekaragaman jenis
sedang pada setiap tingkat pertumbuhannya.
Kandungan Karbon Tersimpan
Nilai karbon tersimpan ditentukan dengan pengukuran biomassa pohon.
Karbon tersimpan merupakan 46% dari biomassa pohon yang diukur. Biomassa
pohon (dalam berat kering) dihitung menggunakan "allometric equation"
berdasarkan pada diameter batang setinggi 1,3 m di atas permukaan tanah (dalam
cm).
Perbedaan jumlah cadangan karbon pada setiap lokasi penelitian
disebabkan karena perbedaan kerapatan tumbuhan pada setiap lokasi. Cadangan
karbon pada suatu sistem penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis vegetasinya.
Suatu sistem penggunaan lahan yang terdiri dari pohon dengan spesies yang
dibandingkan dengan lahan yang mempunyai spesies dengan nilai kerapatan kayu
rendah (Rahayu et al, 2007).
Tabel 7. Biomassa dan Karbon Tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Kabupaten Karo
No. Jenis Biomassa dan C Tersimpan (ton/Ha)
Tiang Pohon
Biomassa C Tersimpan Biomassa C Tersimpan
1 Altingia excelsa 0,43 0,20 10,67 4,91
10 Endospermum malaccense 10,66 4,90
11 Eurya accuminata 3,08 1,42 13,50 6,21
12 Ficus racemosa 1,37 0,63
13 Knema sp 11,99 5,52
14 Lithocarpus sp 11,38 5,23
15 Macaranga tanaria 0,90 0,41 8,00 3,68
16 Mallothus philipinensis 0,95 0,44
17 Schima wallichii 9,72 4,47
18 Shorea sp 0,00 0,00
19 Trema sp 0,80 0,37
Total 17,28 7,95 110,05 50,61
Dari Tabel 7, di atas dapat dilihat bahwa cadangan karbon di Hutan
Pendidikan USU Kabupaten Karo pada tingkat tiang sebanyak 7,95 ton/Ha,
sedangkan pada tingkat pohon sebanyak 50,61 ton/Ha, sehingga didapatkan
cadangan karbon total pada kedua tingkat pertumbuhan tersebut yaitu pada tingkat
tiang dan tingkat pohon adalah sebanyak 58,56 ton/Ha. Dari hasil tersebut
diperoleh cadangan karbon untuk Hutan Pendidikan USU yang memiliki luas
areal 200 Ha adalah sebesar 11.712 ton.
Untuk kandungan biomassa dalam pendugaan karbon didapatkan pada
tingkat tiang sebesar 17,28 ton/Ha, sedangkan pada tingkat pohon didapatkan
110,05 ton/Ha. Pada jenisnya, biomassa yang tertinggi didapatkan pada jenis
Eurya accuminata sebesar 3,08 ton/Ha, dan pada tingkat pohon didapatkan
Kandungan karbon pada tingkat pohon berkisar antara 0,00 ton/Ha sampai
dengan 6,21 ton/Ha, dimana yang memiliki nilai kandungan karbon terbesar
adalah jenis Eurya accuminata (6,21 ton/Ha). Kandungan karbon pada tingkat
tiang berkisar antara 0,20 ton/Ha sampai dengan 6,21 ton/Ha, dan jenis Eurya
accuminata yang memiliki nilai kandungan karbon terbesar (6,21 ton/Ha).
Nilai karbon tersimpan menyatakan banyaknya karbon yang mampu
diserap oleh tumbuhan dalam bentuk biomassa. Jumlah karbon yang semakin
meningkat pada saat ini harus diimbangi dengan jumlah serapannya oleh
tumbuhan guna menghindari pemanasan global. Dengan demikian dapat
diramalkan berapa banyak tumbuhan yang harus ditanam pada suatu lahan untuk
mengimbangi jumlah karbon yang terbebas di udara.
Nilai cadangan karbon mencerminkan dinamika karbon dari sistem
penggunaan lahan yang berbeda, yang nantinya digunakan untuk menghitung
timeaveraged karbon di atas permukaan tanah pada masing-masing sistem.
Timeaveraged karbon tergantung pada laju akumulasi karbon, karbon maksimum
dan minimum yang tersimpan dalam suatu sistem penggunaan lahan, waktu untuk
mencapai karbon maksimum dan waktu rotasi
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil analisis vegetasi ditemukan 25 jenis vegetasi pada tingkat
pertumbuhan semai, pancang, tiang dan pohon, untuk Indeks Nilai Penting (INP)
yang tertinggi didapatkan pada jenis Aporosa sp (INP = 51,76%) pada tingkat
tiang, sedangkan yang terendah didapatkan pada jenis Shorea sp (INP = 2,07%)
pada tingkat pohon. Indeks Keragaman (H’) yang tertinggi didapatkan pada
tingkat pancang sebesar 2,46 dan terendah didapatkan pada tingkat semai 2,28.
Jumlah kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh
Kab. Karo adalah sebesar 11.712 ton.
Saran
Diharapkan penelitian lanjutan pada luasan 1000 Ha, untuk mengetahui
DAFTAR PUSTAKA
Arief, Arifin. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
Bachelerd. E.P.R. Stevens., M. Butz., W.J.B. Crane. 1985. Think Trees Grow Grow Trees. Canberra Australia : Australian Government Publishing Service.
Bakri, 2009. Analisis Vegetasi dan Pendugaan Cadangan Karbon Tersimpan pada Pohon di Hutan Taman Wisata Alam Taman Eden Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir. Universitas Sumatera Utara.
Daniel, T. W., J.A. Helms, F.S. Baker. 1992. Prinsip-Prinsip Silvinatural. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Ewusie, J.Y. 1990. Ekologi Tropika. Bandung : Penerbit ITB.
Greg-Smith, P.G.1983. Quantitative Plant Ecology, Blackwell Scientific Publications. Oxford : Blackwell Scientific Publications
Hairiah, K dan Rahayu, S. 2007. Pengukuran .Karbon Tersimpan. Di Berbagai Macam Penggunaan Lahan. Bogor: World Agroforestry Centre.
Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
Irwan, Z.D. 1992. Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
Irwanto. 2006. Analisis Struktur dan Komposisi Vegetasi untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Pulau Marsegu, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Ketterings, Q.M., Coe, R., Van Noordwijk, M., Ambagau', Y., dan Palm, C.A., 2001. Reducing Uncertainty in The Use of Allometric Biomass Equations for Predicting Above-Ground Tree Biomass in Mixed Secondary Forest. Forest Ecology and Management. 146 : 199-209. Kurniawan, Harry. 2010. Pengukuran dengan Metode CSS. pengukuran-potensi-tegakan-dengan.html [3 Juni 2010]
Longman, K.A. & J.Jenik. 1987. Tropical Forest and its Environment. London : Longman Group Limited.
Murdiyarso, D, Rosalina, U, Hairiah, K, Muslihat, L, Suryadipura, IN.N dan Jaya, 2004. Petunjuk Lapangan: Pendugaan Cadangan Karbon pada Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.
Nevada, FT. 2007. Komposisi dan Struktur Tegakan Areal Bekas Tebangan Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (Studi Kasus di Areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat) [Skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan. Polunin, N. 1990. Pengantar Geografi Tumbuhan dan Beberapa Ilmu Serumpun. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Rahayu, S, Lusiana, B, van Noordwijk, M 2007. Pendugaan Cadangan Karbon di Atas Permukaan Tanah pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Bogor: World Agroforestry Centre.
Odum, P. E. 1971. Dasar-Dasar Ekologi. Terjemahan Ir. Thahjono Samingan, M.Sc. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rahman, M. 1986. Jenis dan Kerapatan Pohon Dipterocarpaceae di bukit Gajabuih Padang. Jurnal Matematika dan Pengetahuan Alam. Vol 2.
Ruslan, M. 1986. Studi Perkembangan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Kawasan Daerah Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Mandailing Kalimantan Selatan.
Sidiyasa K, Zakaria, dan Iwan, R. 2006. Hutan Desa Setulang dan Sengayan Malinau, Kalimantan Timur: Potensi dan Identifikasi Langkah-Langkah Perlindungan Dalam Rangka Pengelolaannya Secara Lestari. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor, Indonesia. Soerianegara, I, & A.Indrawan. 1978. Ekologi hutan Indonesia. Bogor : Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan.
Sutarno, H & R. Soedarsono. 1997. Latihan Mengenal Pohon Hutan (Kunci Identifikasi dan Fakta Jenis). Bogor : Yayasan Prosea.
Syahbudin. 1978. Dasar-Dasar Ekologi Tumbuhan. Padang : Universitas Andalas Press.
Tamin, N.M. 1991. Hutan Hujan Tropika di Timur Jauh. Cetakan 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Tuhono, Eling. 2010. Komposisi Vegetasi dan Cadangan Karbon Tersimpan pada Tegakan Hutan di Kawasan Ekowisata Tangkahan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Universitas Sumatera Utara.
LAMPIRAN
Lampiran 1
Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Semai
PU Nama Jenis Jumlah Individu
1 Eugenia operculata 3
Eurya accuminata 1
Schima wallichii 2
Pavetta indica 2
2 Eugenia operculata 4
Eurya accuminata 3
Altingia excelsa 2
Pavetta indica 3
3 Eurya accuminata 4
Acronychia porteri 2
Trema sp 1
Schima wallichii 2
Altingia excelsa 2
Podocarpus imbricata 1
4 Eugenia operculata 4
Altingia excelsa 2
Trema sp 2
Schima wallichii 1
Podocarpus imbricata 2
5 Eugenia operculata 3
Trema sp 4
Schima wallichii 2
Eurya accuminata 4
Pavetta indica 2
6 Eugenia operculata 3
Eurya accuminata 2
Schima wallichii 1
7 Eugenia operculata 3
Schima wallichii 4
Pavetta indica 4
8 Eurya accuminata 2
Schima wallichii 3
Podocarpus imbricata 4
9 Trema sp 1
Schima wallichii 1
Podocarpus imbricata 3
10 Eurya accuminata 2
Schima wallichii 1
Podocarpus imbricata 4
11 Acronychia porteri 2
Altingia excelsa 1
Podocarpus imbricata 4
12 Eurya accuminata 2
Altingia excelsa 4
Podocarpus imbricata 2
Schima wallichii 2
13 Eugenia operculata 2
14 Altingia excelsa 1
Acronychia porteri 4
Schima wallichii 5
Eurya accuminata 3
15 Eugenia operculata 3
Eurya accuminata 4
Altingia excelsa 1
Schima wallichii 1
16 Eugenia operculata 2
Eurya accuminata 2
17 Eurya accuminata 1
Altingia excelsa 2
Schima wallichii 2
18 Eugenia operculata 2
Eurya accuminata 3
Altingia excelsa 4
Eurya accuminata 3
19 Eurya accuminata 2
Schima wallichii 2
Podocarpus imbricata 3
Pavetta indica 3
20 Altingia excelsa 4
Acronychia porteri 2
Pavetta indica 3
21 Altingia excelsa 4
Pavetta indica 1
Podocarpus imbricata 3
Schima wallichii 3
22 Eugenia operculata 1
Eurya accuminata 4
Altingia excelsa 3
23 Eurya accuminata 2
Altingia excelsa 2
Pavetta indica 3
Podocarpus imbricata 4
24 Altingia excelsa 2
Podocarpus imbricata 2
Schima wallichii 3
25 Altingia excelsa 2
Eurya accuminata 3
Eugenia operculata 2
26 Eurya accuminata 3
Podocarpus imbricata 4
Schima wallichii 2
Diospyros sp 2
Dacrydium imbricata 1
27 Eurya accuminata 3
Schima wallichii 2
Diospyros sp 3
Dacrydium imbricata 2
28 Podocarpus imbricata 2
Pavetta indica 4
Schima wallichii 1
Dacrydium imbricata 2
29 Dacrydium imbricata 1
Diospyros sp 4
Schima wallichii 3
Schima wallichii 2
Podocarpus imbricata 3
31 Ardisia lurida 1
Diospyros sp 2
Dacrydium imbricata 1
32 Diospyros sp 3
Schima wallichii 2
Podocarpus imbricata 1
33 Ardisia lurida 2
Diospyros sp 1
Schima wallichii 2
34 Podocarpus imbricata 3
Pavetta indica 3
Diospyros sp 2
Schima wallichii 2
35 Acronychia porteri 2
Pavetta indica 1
Diospyros sp 1
36 Dacrydium imbricata 1
Cinnamomum sp 3
Ardisia lurida 4
37 Dacrydium imbricata 4
Cinnamomum sp 2
Pavetta indica 4
38 Diospyros sp 3
Cinnamomum sp 1
Schima wallichii 2
39 Eugenia operculata 3
Cinnamomum sp 1
Dacrydium imbricata 2
40 Eugenia operculata 2
Eurya accuminata 3
Schima wallichii 3
Diospyros sp 1
41 Eurya accuminata 3
Acronychia porteri 2
Schima wallichii 3
Pavetta indica 3
42 Eurya accuminata 2
Acronychia porteri 4
Schima wallichii 4
Diospyros sp 3
43 Eugenia operculata 2
Dacrydium imbricata 2
Diospyros sp 1
44 Eurya accuminata 3
Dacrydium imbricata 4
Pavetta indica 2
45 Eurya accuminata 4
Eugenia operculata 2
Dacrydium imbricata 3
46 Eurya accuminata 2
Dacrydium imbricata 4
47 Eurya accuminata 2
Diospyros sp 3
Schima wallichii 2
48 Eugenia operculata 3
Eurya accuminata 4
Schima wallichii 2
49 Eugenia operculata 3
Eurya accuminata 3
50 Diospyros sp 2
Dacrydium imbricata 2
Cinnamomum sp 4
Total 422
Lampiran 2
Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Pancang
PU Nama Jenis Jumlah Individu
1 Acronychia porteri 2
Altingia excelsa 1
2 Dacrydium imbricatus 2
Eurya accuminata 2
3 Cinnamomum sp 1
Pavetta indica 1
Schima wallichii 1
4 Trema sp 1
Eugenia operculata 2
5 Ficus racemosa 1
Elaocarpus sp 1
6 Knema sp 3
Schima wallichii 1
7 Pavetta indica 2
Schima wallichii 1
8 Trema sp 2
Eurya accuminata 2
9 Acronychia porteri 1
Altingia excelsa 2
10 Eurya accuminata 2
Eugenia operculata 1
Knema sp 1
11 Altingia excelsa 2
Eurya accuminata 1
Cinnamomum sp 1
12 Altingia excelsa 2
Eurya accuminata 1
Knema sp 1
13 Dacrydium imbricatus 1
Cinnamomum sp 2
Knema sp 1
14 Trema sp 1
Eugenia operculata 1
Schima wallichii 1
15 Ficus racemosa 1
Elaocarpus sp 1
Knema sp 2
16 Cinnamomum sp 2
Altingia excelsa 2
Knema sp 1
17 Elaocarpus sp 1
Symingtonia populnea 1
Elaeocarpus sp 1
19 Altingia excelsa 2
Pavetta indica 1
20 Symingtonia populnea 1
Knema sp 1
21 Acronychia porteri 2
Altingia excelsa 3
22 Dacrydium imbricatus 1
Cinnamomum sp 1
23 Elaocarpus sp 2
Altingia excelsa 2
24 Knema sp 2
Pavetta indica 1
25 Trema sp 1
Eugenia operculata 1
26 Knema sp 2
Eugenia operculata 2
27 Altingia excelsa 1
Dacrydium imbricatus 1
Pavetta indica 1
28 Knema sp 2
Cinnamomum sp 3
29 Altingia excelsa 2
Dacrydium imbricatus 1
30 Symingtonia populnea 2
Elaocarpus sp 2
Eugenia operculata 1
Cinnamomum sp 1
31 Knema sp 2
Pavetta indica 1
Altingia excelsa 1
32 Symingtonia populnea 1
Knema sp 1
33 Elaocarpus sp 1
Acronychia porteri 1
Dacrydium imbricatus 1
34 Pavetta indica 1
Symingtonia populnea 1
Elaocarpus sp 1
35 Altingia excelsa 2
Symingtonia populnea 1
Pavetta indica 1
36 Elaocarpus sp 2
Altingia excelsa 1
Acronychia porteri 1
37 Symingtonia populnea 2
Knema sp 2
38 Altingia excelsa 1
Elaocarpus sp 2
Acronychia porteri 2
39 Knema sp 1
Ficus racemosa 1
40 Altingia excelsa 3
Elaeocarpus sp 1
41 Pavetta indica 1
Dacrydium imbricatus 1
42 Knema sp 1
Acronychia porteri 1
43 Altingia excelsa 2
Elaocarpus sp 2
44 Pavetta indica 2
Dacrydium imbricatus 2
45 Knema sp 2
Altingia excelsa 1
46 Cinnamomum sp 1
Pavetta indica 1
47 Altingia excelsa 2
Elaocarpus sp 2
48 Pavetta indica 1
Dacrydium imbricatus 1
49 Altingia excelsa 2
Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Tiang
PU Nama Jenis Diameter (m) Tinggi (m) LBDS (m2)
1 Aporosa sp 0,13 10 0,01
Aporosa sp 0,15 13 0,02
Dillenia sumatrana 0,13 12 0,01
2 Diospyros sp 0,14 11 0,02
Mallothus philipinensis 0,13 15 0,01
3 Ficus racemosa 0,12 13 0,01
Mallothus philipinensis 0,15 15 0,02
12 Aporosa sp 0,19 14 0,03
Mallothus philipinensis 0,18 13 0,03
37 Eurya accuminata 0,15 14 0,02
Dacrydium imbricatus 0,15 15 0,02
Dacrydium imbricatus 0,18 17 0,03
Dacrydium imbricatus 0,17 14 0,02
38 Macaranga tanaria 0,15 16 0,02
Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Pohon
Altingia excelsa 0,29 14 0,066
Endospermum malaccense 0,3 22 0,071
Altingia excelsa 0,28 14 0,062
Endospermum malaccense 0,27 16 0,057
Endospermum malaccense 0,29 17 0,066
Schima Wallichi 0,35 27 0,096
Endospermum malaccense 0,38 26 0,113
Altingia excelsa 0,4 30 0,126
Altingia excelsa 0,37 28 0,107
10 Lithocarpus sp 0,26 14 0,053
Lithocarpus sp 0,29 18 0,066
Endospermum malaccense 0,4 29 0,126
11 Cinnamomum sp 0,42 34 0,138
Endospermum malaccense 0,32 27 0,080
Endospermum malaccense 0,35 28 0,096
Aporosa sp 0,32 24 0,080
Endospermum malaccense 0,42 33 0,138
Endospermum malaccense 0,35 27 0,096
Schima Wallichi 0,26 17 0,053
Schima Wallichi 0,3 23 0,071
17 Macaranga tanaria 0,38 25 0,113
Macaranga tanaria 0,42 31 0,138
Canarium indicum 0,42 32 0,138
Endospermum malaccense 0,48 34 0,181
22 Macaranga tanaria 0,36 24 0,102
Elaocarpus sp 0,27 16 0,057
Knema sp 0,37 26 0,107
Aporosa sp 0,26 13 0,053
Aporosa sp 0,28 18 0,062
Endospermum malaccense 0,3 28 0,071
Schima Wallichi 0,47 34 0,173
Endospermum malaccense 0,34 23 0,091
Endospermum malaccense 0,32 21 0,080
Eurya accuminata 0,37 26 0,107
25 Aporosa sp 0,35 25 0,096
Aporosa sp 0,32 20 0,080
Aporosa sp 0,4 35 0,126
Endospermum malaccense 0,42 33 0,138
Schima Wallichi 0,4 31 0,126
Endospermum malaccense 0,37 30 0,107
Endospermum malaccense 0,39 30 0,119
Lithocarpus sp 0,3 27 0,071
Endospermum malaccense 0,35 26 0,096
Endospermum malaccense 0,35 23 0,096
Schima Wallichi 0,34 22 0,091
Schima Wallichi 0,35 21 0,096
32 Elaocarpus sp 0,34 20 0,091
Endospermum malaccense 0,34 22 0,091
Lithocarpus sp 0,23 14 0,042
Canarium indicum 0,38 26 0,113
Canarium indicum 0,28 17 0,062
Macaranga tanaria 0,4 32 0,126