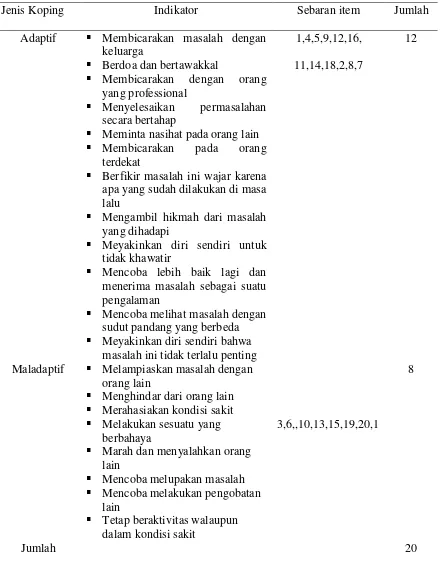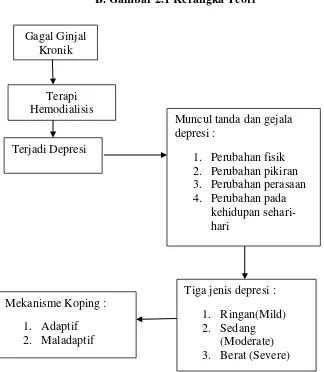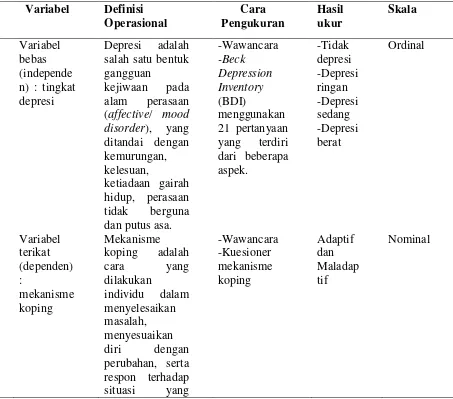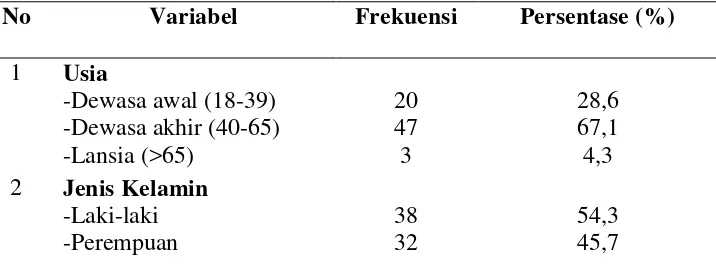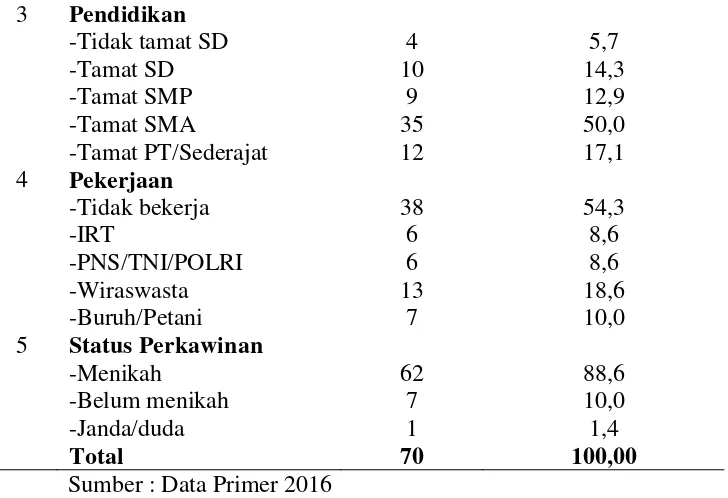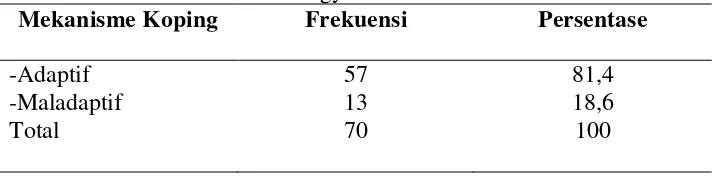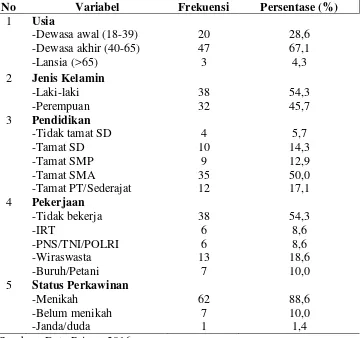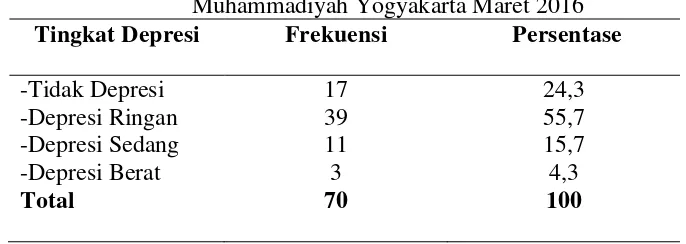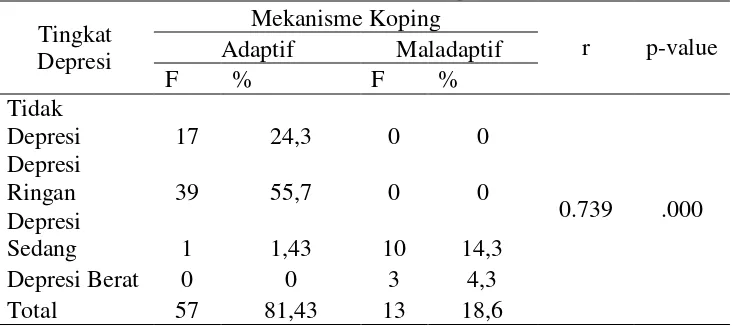i
KARYA TULIS ILMIAH
HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RS PKU
MUHAMMADIYAH II YOGYAKARTA
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Disusun Oleh
ELVIRA MARIDHA A. BOMBAY 20120320114
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
i
KARYA TULIS ILMIAH
HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RS PKU
MUHAMMADIYAH II YOGYAKARTA
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Disusun Oleh
ELVIRA MARIDHA A. BOMBAY 20120320114
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
ii
HALAMAN PENGESAHAN KTI
HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RS PKU
MUHAMMADIYAH II YOGYAKARTA
Disusun oleh:
ELVIRA MARIDHA A. BOMBAY 20120320114
Telah disetujui dan diseminarkan pada tanggal 22 Agustus 2016
Dosen Pembimbing
Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp. Kep.MB
NIK : 173185
Dosen Penguji
Shanti Wardaningsih, M.Kep., Ns., Sp.,Jiwa., Ph.D
NIK : 173058
Mengetahui
Kaprodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Elvira Maridha A. Bombay
NIM : 20120320114
Program Studi : Ilmu Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya tulis ini
merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalm bentuk apapun kepada
perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang
diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Karya Tulis Ilmiah ini.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Karya Tulis Ilmiah ini
hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Yogyakarta, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Untuk Engkau Yang Maha Segalanya, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
Untuk kedua orang tua, Ayah (Asjan S. Bombay) dan Ibu (Nurlaila Hi. Husen) yang sangat luar biasa, terima kasih penulis ucapkan untuk doanya yang tidak pernah henti kepada penulis, untuk segala bentuk kasih sayang, perhatian dan nasehat serta dukungan yang luar biasa untuk penulis. Hasil dari perjuangan ini kupersembahkan untuk kalian,walaupun tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan kalian. semoga ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk melangkah kedepannya dan membuat ayah dan ibu lebih bangga lagi.
Untuk kakek Salim Bombay (Alm) dan paman Kadafi S. Bombay (Alm), hasil ini untuk kalian. Semoga kalian bangga dan tenang di alam sana.
Untuk nenek tercinta Bida Abu, terima kasih yang luar biasa. Terima kasih selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan pengorbanan kepada penulis.
Untuk adikku satu-satunya Wahyu Sah Budi A. Bombay, terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi adik yang pengertian dan sabar. Ayo kita berdua berjuang untuk orang tua dan keluarga kita.
Untuk Yati Bombay, Mama Ain, Andi Bombay, Mama Jija, Papa Dula, Hilda Bombay, Ikhy Bombay, Rifda Bombay, Ririn Bombay, Fandi Bombay, Fadli Bombay, Kausar Hi Husen dan seluruh keluarga Hi Husen yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa.
Untuk Deva Prayunika, Tiffani Aprilia, Nadia Imara Fasa, Ina Fadillah, Sitti Nursanti, Adelia Pramudita Monanda terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk doa, semangat, bantuan dan perhatiannya untuk penulis. Semoga kita terus sukses ke depannya.
Untuk teman-teman seperjuangan dan satu bimbingan (Indah, Asri, Atsna, Novia, Suci). Terima kasih untuk semangat, motivasi dan doanya. Selamat dan semangat berjuang sahabat.
Untuk Nurrahmi Umanailo, Eka Wulandari, Dewi Makhrantika Madiong, Megawati Abd Rachman, Yuli Jois, Nuryati Saleh, Pipit Pellu, Farrah HSN, Rukmah Khairiah, Asmalina Rahayu yang tidak hentinya memberikan semangat,motivasi dan dukungan. Terima kasih sudah menjadi teman dan saudara yang luar biasa selama ini.
Untuk personil Palahega Logistik ( bunda Mhia Joram, ibu Nani Dero, Onaa, Rasdiyana Usman, Mami Imha, ante Vhylot, Miggo). Terima kasih selalu ada untuk penulis, terima kasih untuk canda tawanya.
v
MOTTO
“Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Shalat”
(Qs. Al-Baqarah: 153)
“Ilm (Pengetahuan) Tanpa „Aql (Kecerdasan) Adalah Seperti Memiliki Sepatu Tanpa Kaki”
(Ali Bin Abi Thalib)
“Jangan Bersedih, Allah Bersama Kita” (La Tahzan)
“Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Hubungan Tingkat Depresi dengan Mekanisme Koping Pasien Gagal Ginjal Kronik Yng Menjalani Hemodialisis di
RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita. Karya Tulis Ilmiah ini diajukan
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana Keperawatan di Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama
penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, antara lain:
1. Bapak Asjan Bombay dan Ibu Nurlaila Hi. Husen selaku orang tua yang telah mendukung
dengan semua perhatian, nasihat, motivasi dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.
2. dr. H. Ardi Pramono, Sp.An.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran danIlmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sri Sumaryani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Mat.,HNC., selaku Ketua Program Studi Ilmu
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. (Almarhumah) Yuni Permatasari Istanti, Ns., M.Kep., Sp.KMB., CWCS.,HNC selaku
pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis di setengah
perjalanan pertama untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp.Kep.MB selaku pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu dan membimbing penulis di setengah perjalan terakhir untuk
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Shanti Wardaningsih, Ns., M. Kep., Sp. Jiwa., Ph.D selaku dosen penguji yang telah
memberikan saran perbaikan demi kemajuan peneliti.
7. Direktur Pendidikan dan Penelitian RS PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang telah
memberi izin dalam melakukan penelitian ini.
8. Seluruh staf perawat dan pasien hemodialisis di unit hemodialisis RS PKU Muhammadiyah
vii
9. Seluruh keluarga besar Bombay dan Hi. Husen, terima kasih telah memberikan semangat
dan dukungan.
10. Mhia Joram, Nani Dero, Onaa, Rasdiyana Usman, Irmawati, Vhylat Mansur,
Miggo yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, yang
selalu menghadirkan tawa disetiap saat.
13. Seluruh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan angkatan 2012.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan
karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun untuk dikemudian hari.
Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada
umumnya, semoga kita semua selalu dalam karunia Allah SWT.
Wassalamualaikum Wr Wb.
Yogyakarta, 23 Agustus 2016
viii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
LEMBAR PENGESAHAN ... ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv
B.Populasi dan Sampel Penelitian ... 33
1. Populasi ... 33
2. Sampel ... 33
C.Lokasi dan Waktu Penelitian ... 34
D.Kriteria Inklusi dan Ekslusi ... 34
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ... 34
1. Variabel Penelitian ... 34
2. Definisi Operasional ... 35
F. Instrumen Penelitian ... 36
G.Cara Pengumpulan Data ... 37
ix
I. Pengolahan Data ... 39
J. Analisis Data ... 40
K.Etika Penelitian ... 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A.Gambaran Lokasi Penelitian ... 42
B.Hasil Penelitian ... 43
1. Analisis Univariat ... 43
2. Analisis Bivariat ... 48
C. Pembahasan ... 49
1. Karakteristik Responden ... 49
2. Tingkat Depresi Responden ... 55
3. Mekanisme Koping Responden ... 58
4. Hubungan Tingkat Depresi dengan Mekanisme Koping Pasien Gagal Ginjal Kronik di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta ... 61
D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian ... 64
BAB V PENUTUP A.Kesimpulan ... 64
B.Saran ... 65
DAFTAR PUSTAKA ... 66
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kisi-kisi Kuesioner Mekanisme Koping ... 29
Tabel 3.1 Definisi Operasional ... 35
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden ... 44
Tabel 4.2 Karakteristik Tingkat Depresi Responden ... 45
Tabel 4.3 Karakteristik Mekanisme Koping Responden ... 55
Tabel 4.4 Crosstab Karakteristik Responden dengan Tingkat Depresi dan Mekanisme Koping ... 46
xi
DAFTAR GAMBAR
xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lembar Permohonan Menjadi Responden Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden Lampiran 3. Data Demografi Responden Penelitian Lampiran 4. Kuesioner Tingkat Depresi
Lampiran 5. Kuesioner Mekanisme Koping Lampiran 6. Surat Izin Survey Pendahuluan Lampiran 7. Surat Izin Penelitian
xiii
Elvira Maridha A. Bombay (2016) : Hubungan Tingkat Depresi Dengan Mekanisme Koping Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah Unit II Yogyakarta.
Pembimbing : Resti Yulianti Sutrisno, M. Kep., Ns., Sp.Kep.MB.
INTISARI
Latar Belakang : Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan rawat jalan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan perubahan seperti perilaku penolakan, marah, perasaan takut, dan depresi. Mekanisme koping pasien yang merupakan proses mengembangkan perilaku baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi dampak kecemasan bahkan stress dalam kehidupan.
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan rancangan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada tanggal 1 Maret – 30 Maret 2016. Populasi penelitian ini adalah pasien hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta. Tekhnik pengambilan sampel dengan total sampling, didapatkan 70 responden. Analisa data yang digunakan adalah spearman untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta, dengan nilai dari spearman = 0,000 atau p<0,01. Hasil crosstabs kekuatan korelasi (r) = 0.739 yang artinya kekuatan korelasi antara tingkat depresi dan mekanisme koping adalah kuat.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antar tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.
xiv
Elvira Maridha A. Bombay (2016):The Correlation Level of Depression with Mechanism Coping Chronic Kidney Disease Patients Who Undergoing Hemodialysis in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta
Advisor: Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp. Kep.MB ABSTRACK
Background: Renal failure classified as a chronic disease that requires treatment and outpatient care in the long term. The condition is of course cause behavioral changes such as denial, anger, fear and depression. Patients coping mechanism which is the process of developing a new behavior that aims to cultivate the power of the individual, reducing the impact of stress and even anxiety in life.
Objective: This study aims to determine the correlation between depression and coping mechanisms of patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.
Methods: This study is a non-experimental studies with correlative descriptive design with cross sectional study conducted on March 1 - March 30, 2016. The study population was hemodialysis patients in RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Technique that used with total sampling, obtained 70 respondents. Data Analysis used was spearman to know the correlation between depression and coping mechanism.
Results : Research result show that there is a relationship with the depressed levels in hemodialysis patients coping mechanism RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II, with a value of Spearman 0.000 or P <0.01. Results crosstabs strength of the correlation (r) 0739, which means the strength of the correlation between the level of depression and coping mechanisms are strong.
Conclusion : There is a relationship between the level of depression and coping mechanisms in patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.
i
Elvira Maridha A. Bombay (2016) : Hubungan Tingkat Depresi Dengan Mekanisme Koping Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah Unit II Yogyakarta.
Pembimbing : Resti Yulianti Sutrisno, M. Kep., Ns., Sp.Kep.MB.
INTISARI
Latar Belakang : Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan rawat jalan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan perubahan seperti perilaku penolakan, marah, perasaan takut, dan depresi. Mekanisme koping pasien yang merupakan proses mengembangkan perilaku baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi dampak kecemasan bahkan stress dalam kehidupan.
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan rancangan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada tanggal 1 Maret – 30 Maret 2016. Populasi penelitian ini adalah pasien hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta. Tekhnik pengambilan sampel dengan total sampling, didapatkan 70 responden. Analisa data yang digunakan adalah spearman untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta, dengan nilai dari spearman = 0,000 atau p<0,01. Hasil crosstabs kekuatan korelasi (r) = 0.739 yang artinya kekuatan korelasi antara tingkat depresi dan mekanisme koping adalah kuat.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antar tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.
ii
Elvira Maridha A. Bombay (2016):The Correlation Level of Depression with Mechanism Coping Chronic Kidney Disease Patients Who Undergoing Hemodialysis in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta
Advisor: Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp. Kep.MB ABSTRACK
Background: Renal failure classified as a chronic disease that requires treatment and outpatient care in the long term. The condition is of course cause behavioral changes such as denial, anger, fear and depression. Patients coping mechanism which is the process of developing a new behavior that aims to cultivate the power of the individual, reducing the impact of stress and even anxiety in life.
Objective: This study aims to determine the correlation between depression and coping mechanisms of patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.
Methods: This study is a non-experimental studies with correlative descriptive design with cross sectional study conducted on March 1 - March 30, 2016. The study population was hemodialysis patients in RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Technique that used with total sampling, obtained 70 respondents. Data Analysis used was spearman to know the correlation between depression and coping mechanism.
Results : Research result show that there is a relationship with the depressed levels in hemodialysis patients coping mechanism RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II, with a value of Spearman 0.000 or P <0.01. Results crosstabs strength of the correlation (r) 0739, which means the strength of the correlation between the level of depression and coping mechanisms are strong.
Conclusion : There is a relationship between the level of depression and coping mechanisms in patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Ginjal memiliki peranan yang sangat vital sebagai organ tubuh manusia terutama
dalam sistem urinaria. Ginjal manusia berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan
dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah, dan mengatur keseimbangan
asam-basa darah, serta sekresi bahan buangan dan kelebihan garam (Potter & Perry, 2006). Gagal
ginjal dinyatakan terjadi jika fungsi kedua ginjal terganggu sampai pada titik ketika ginjal
tidak mampu menjalani fungsi regulatorik dan ekskretorik untuk mempertahankan
keseimbangan (Nabilla, Esrom, Ferdinand, 2013).
Data dari National Kidney and Urologic Disease Information Clearinghouse (NKUDIC) (2012) pada akhir tahun 2009, prevalensi penderita penyakit ginjal stadium
akhir di Amerika Serikat yaitu 1.738 penderita persatu juta penduduk dan 370.274
diantaranya menjalani hemodialisis. Populasi di Malaysia dengan 18 juta orang,
diperkirakan terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal pertahunnya. Tahun 2010 mengalami
peningkatan yang tinggi yaitu lebih dari dua juta orang yang menderita penyakit ginjal
kronik (Rustina, 2012). Insiden ini di negara berkembang lainnya, diperkirakan sekitar
40-60 kasus perjuta penduduk pertahun (Sudoyo, 2006).
Prevalensi penderita penyakit ginjal kronik berdasarkan Indonesia Renal Registry pada tahun 2008 yaitu sekitar 200-250 per satu jutapenduduk dan yang menjalani
hemodialisis mencapai 2.260 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Klien
yang menggunakan pelayanan khusus pada tahun 2005 sebanyak 11.219 dan pada tahun
hemodialisis sebanyak 17.815 pasien (Depkes RI, 2008). Data Depkes Provinsi D.I.
Yogyakarta menyebut bahwa sepanjang tahun 2009 terdapat 461 kasus baru penyakit gagal
ginjal kronik yang terbagi atas kota Yogyakarta 175 kasus, Kabupaten Bantul 73 kasus,
Kabupaten Kulon Progo 45 kasus dan Kabupaten Sleman 168 kasus, serta pasien yang
meninggal di kota Jogja 19 orang, Bantul 8 orang, Kulon progo 45 orang, Sleman 23 orang
(Mayangsari, 2013). Menurut data PT Askes, ada sekitar 14,3 juta orang penderita gagal
ginjal tahap akhir saat ini menjalani pengobatan yaitu dengan prevalensi 433 juta perjumlah
penduduk. Jumlah ini akan meningkat hingga melebihi 200 juta pada tahun 2025 (Febrian,
2009).
Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan rawat jalan
dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan perubahan seperti
perilaku penolakan, marah, perasaan takut, rasa tidak berdaya, putus asa, cemas bahkan
bunuh diri (Chanafie, 2010). Depresi merupakan masalah psikologis yang paling sering
dihadapi oleh pasien penyakit ginjal kronik dan yang menjalani hemodialisis. Depresi
merupakan penyakit yang melibatkan tubuh, suasana hati, dan pikiran (Shanty, 2011).
Depresi yang paling sering muncul pada pasien-pasien dialisis adalah anhedonia, perasaan
sedih, tidak berguna, merasa bersalah, putus asa, gangguan tidur, diikuti dengan nafsu
makan menurun, dan libido menurun, dalam jurnal Suryaningsih, Esrom, Ferdinand (2010).
Berdasarkan penelitian Nabila, dkk (2013) pasien yang paling banyak mengalami depresi
adalah laki-laki dan yang baru pertama kali menjalani hemodialisis. Saat seseorang berada
dalam situasi yang terancam, maka respon koping perlu segera dibentuk. Mekanisme koping
yang dapat diterapkan oleh individu yaitu mekanisme koping adaptif dan maladaptif
Mekanisme koping pasien merupakan proses yang aktif di mana menggunakan
sumber-sumber dari dalam pribadi pasien dan mengembangkan perilaku baru yang
bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi dampak kecemasan
bahkan stress dalam kehidupan (Yemi ma, Esrom, Ferdinand, 2013). Terdapat berbagai cara
yang dilakukan pasien dalam menghadapi masalah tersebut baik secara adaptif seperti
bicara dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, tekhnik relaksasi dan olahraga,
atau menggunakan cara yang maladaptif seperti minum alkohol, reaksi lambat atau
berlebihan, menghindari, mencederai atau lain sebagainya (Azizah, 2011). Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Yemi ma, dkk(2013) tentang mekanisme koping didapat
45,8% responden melakukan koping adaptif dan 54,2% responden melakukan koping
maladaptif.
Seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’rij ayat 19-21 tentang tabiat
manusia yang suka sedih dan berkeluh-kesah, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat
keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia
mendapat kebaikan ia amat kikir". (QS. Al- Ma'arij: 19-21). Berdasarkan ayat tersebut dapat
disimpulkan bahwa manusia sering mengeluh jika ditimpa musibah dan apabila diberikan
kesenangan manusia sering kufur nikmat.
Hasil studi pendahuluan yang di lakukan peneliti di RS PKU Muhammadiyah II
didapatkan data pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis rutin di RS PKU
Muhammadiyah II tahun 2015 sebanyak 125 orang dan dari 10 responden didapatkan hasil
5 orang mengalami depresi dan 5 orang tidak mengalami depresi dan dari 10 orang tersebut
yang menggunakan mekanisme koping berfokus pada masalah (adaptif) 6 orang sedangkan
Berdasarkan latar belakang mengenai tingkat depresi pada pasien hemodialisa dan
dampaknya terhadap mekanisme koping maka peneliti tertarik melakukan penelitian
mengenai hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal
kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II 2016.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
ada hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal
kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta tahun
2016.
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping
pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU
Muhammadiyah II Yogyakarta tahun 2016.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik berupa usia, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan pada pasien gagal ginjal kronik yang
menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta tahun 2016.
b. Untuk mengetahui tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani
c. Untuk mengetahui jenis mekanisme koping adaptif dan maladaptif pada pasien gagal
ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II
Yogyakarta tahun 2016.
d. Menganalisa hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien
gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II
Yogyakarta tahun 2016.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan
antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang
menjalani hemodialisa.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Tenaga Keperawatan
Dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk membantu dalam melakukan
tindakan keperawatan pada pasien depresi dengan penyakit gagal ginjal yang
menjalani hemodialisis.
b. Bagi Institusi Pendidikan
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian tentang masalah penyakit
gagal ginjal kronik.
d. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagaimana kejadian depresi
pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis.
E. Keaslian Penelitian
1. Nabilla Lukman, Esrom Kanine, Ferdinand Wowiling(2013), meneliti Hubungan
Tindakan Hemodialisa dengan Tingkat Depresi Klien Penyakit Ginjal Kronik di RSUP
Prof Dr Kandou Manado. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan
analitik dengan menggunakan desain Cross-Sectional. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan tindakan hemodialisa dengan tingkat depresi klien penyakit ginjal kronik
sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, dan dilihat dari distribusi pekerjaan,
sebagian besar bekerja. Penelitian ini membuktikan responden yang paling banyak
mengalami depresi adalah responden yang baru pertama kali menjalani tindakan
hemodialisa. Persamaan penelitian Nabilla, dkk dengan penelitian yang diteliti adalah
rancangan penelitian Cross-Sectional dengan metode pendekatan deskriptif dan analitik.
Perbedaan penelitian Nabilla dkk dengan penelitian yang diteliti adalah variabel terikat
(mekanisme koping), metode penelitian (purposive sampling), lokasi penelitian, waktu
2. Yemima G.V Wurara, Esrom Kanine, Ferdinand Wowiling (2013), meneliti Mekanisme
Koping pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisis di
Rumah Sakit Prof.Dr.R.D Kandou Manado. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang
menggunakan koping adaptif 27 orang (45,5%), sedangkan yang menggunakan koping
maladaptif 32 orang (54,2%). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasien
penyakit ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis lebih banyak menggunakan
mekanisme koping maladaptif. Persamaan penelitian Yemi ma, dkk dengan penelitian
yang diteliti adalah jenis penelitian (deskriptif). Perbedaan penelitian Yemi ma, dkk
dengan penelitian yang diteliti adalah variabel bebas (mekanisme koping), metode
penelitian (aksidental sampling), lokasi penelitian, waktu penelitian dan subjek
penelitian.
3. Ni Ketut Romani, Sri Hendarsih, Fajarina Lathu Asmarani (2012), meneliti Hubungan
Mekanisme Koping Individu Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Gagal Ginjal
Kronik di Unit Hemodialisis RSUP Dr, Soeradji Tirtonegoro Klaten. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analitik dengan studi korelasi serta dengan rancangan Cross-Sectional. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan antara mekanisme koping individu dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronis di Unit Hemodialisis
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Persamaan penelitian Ni Ketut Romani, dkk
dengan penelitian yang diteliti adalah metode penelitian (deskriptif dan analitik), dan
rancangan penelitian (Cross-Sectional). Perbedaan penelitian Ni Ketut Romani, dkk
pengambilan sampel (Accidental sampling) lokasi penelitian, waktu penelitian dan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori
1. Penyakit Gagal Ginjal Kronik
a. Definisi Gagal Ginjal Kronik (GGK)
Gagal ginjal kronik atau penyakit renal tahap akhir adalah
merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan ireversibel
dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme,
keseimbangan cairan dan elektrolit menyebabkan uremia (retensi urea
dan sampah nitrogen lain dalam darah) (Sudoyo, 2007). Gagal ginjal
kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang
beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan
pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal
adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi
ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi
pengganti ginjal yang tetap, berupa dialysis atau transplantasi ginjal
(Sudoyo, 2006).
Gagal ginjal kronik adalah ketidakmampuan ginjal untuk
mempertahankan keseimbangan dan integritas tubuh yang muncul
secara bertahap sebelum terjun ke fase penurunan faal ginjal terhadap
akhir atau dapat diartikan pula sebagai semua faal ginjal secara
bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan
menyebutkan bahwa gagal ginjal kronik adalah suatu proses
patofisiologis dengan penyebab yang beragam, sehingga ginjal
mengalami penurunan fungsi secara progresif dan pada umumnya
berakhir dengan gagal ginjal.
b.Etiologi Gagal Ginjal Kronik
Menurut Suwitra (2006) etiologi penyakit ginjal kronik sangat
bervariasi antara lain sebagai berikut :
1) Glomerulonefritis, di perkirakan sekitar 25% menjadi penyebab
utama gagal ginjal kronik (Suwitra, 2006). Glomerulonefritis
merupakan proses inflamasi pada glomeruli dan dapat merusak
ginjal secara perlahan. Gagal ginjal kronik bisa terjadi
kemungkinan disebabkan oleh terapi glomerulonefritis yang agresif
(Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam, edisi 13).
2) Diabetes Melitus, merupakan salah satu penyakit yang
menghambat penggunaan glukosa oleh tubuh, bila di tahan dalam
darah dan tidak diuraikan, glukosa dapat bertindak sebagai racun
sehingga akan merusak nefron dan menyebabkan gagal ginjal
(Brunner & Suddarth, 2007).
3) Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama gagal ginjal
kronik yang di perkirakan sekitar 20% (Suwitra, 2006). Penyakit
hipertensi dapat menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah
dimana awal mulanya terjadi kerusakan vaskuler pembuluh darah,
pembuluh darah vasokontriksi, maka akan terjadi gangguan
sirkulasi pada ginjal (Muttaqin, 2009). Menurut Alam dan
Hadibroto (2007) menjelaskan bahwa ginjal bergantung dari
sirkulasi darah untuk menjalankan fungsinya sebagai pembersih
darah dari sampah tubuh. Apabila terjadi gangguan sirkulasi darah
maka akan terjadi hipertensi kronik yang berdampak pada
kerusakan ginjal dan fungsinya akan menurun.
c. Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik
Pembagian stadium gagal ginjal kronik menurut Smeltzer dan
Bare (2006) adalah :
1. Stadium I, stadium I ini disebut dengan penurunan cadangan ginjal,
tahap inilah yang paling ringan dimana faal ginjal masih baik.
Selama tahap ini kreatinin serum dan kadar BUN (Blood Urea
Nitrogen) dalam batas normal dan penderita asimtomatik, laju filtrasi glomerolus/glomeruler Filtration rate (GFR) < 50 % dari normal,
bersihan kreatinin 32,5-130 ml/menit ( Cut Hasna, 2010).
2. Stadium II, Stadium II ini disebut dengan insufiensi ginjal, pada
tahap ini lebih dari 75 % jaringan yang berfungsi telah rusak, GFR
besarnya 25 % dari normal, kadar BUN baru mulai meningkat diatas
batas normal (Chaidar, 2011)
3. Stadium III, Stadium ini disebut gagal ginjal tahap akhir atau uremia,
timbul karena 90% dari massa nefron telah hancur atau sekitar
dan kadar kreatinin mungkin sebesar 5-10 ml/menit atau kurang.
Sampai stadium akhir gagal ginjal, penderita mulai merasakan gejala
yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan
homeostatis caiaran dan elektrolit dalam tubuh. Penderita biasanya
menjadi oliguri (pengeluaran kemih) kurang dari 500/hari karena
kegagalan glomerulus meskipun proses penyakit mula-mula
menyerang tubulus ginjal, kompleks perubahan biokimia dan gejala
gejala yang dinamakan sindrom uremik mempengaruhi setiap sistem
dalam tubuh, dengan pengobatan dalam bentuk transplantasi ginjal
atau dialysis (Melti, Arthur, Firginia, 2014).
d.Patofisiologi Gagal Ginjal Kronik
Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung
pada penyakit yang mendasarinya, tapi dalam perkembangan
selanjutnya proses yang terjadi kurang lebih sama. Fungsi renal
menurun, produk akhir metabolisme protein (yang normalnya
diekskresikan ke dalam urin) tertimbun dalam darah (Brunner &
Suddart, 2007).
Stadium yang paling dini penyakit ginjal kronik terjadi
kehilangan daya cadang ginjal (renal reserve), pada keadaan mana
basal LFG masih normal atau malah meningkat. Kemudian secara
perlahan tapi pasti akanterjadi penurunan fungsi nefron yang progresif,
yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kreatinin serum.
keluhan (asimtomatik), tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan
kreatinin serum. Sampai pada LFG sebesar 30%, mulai terjadi keluhan
pada pasien seperti nokturia, badan lemah, mual, nafsu makan kurang
dan penurunan berat badan. Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien
memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti anemia,
peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium,
pruritus, mual, muntah dan lain sebagainya.
Pasien juga mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih,
infeksi saluran napas, maupun infeksi saluran cerna. Ketika LFG
dibawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan
pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal (renal replacement
therapy) antara lain dialisis atau transplantasi ginjal. Keadaan ini pasien dikatakan sampai pada stadium gagal ginjal (Nova Faradilla, 2009).
2. Hemodialisis
a. Pengertian Hemodialisis
Hemodialisis adalah tindakan untuk mengambil zat-zat nitrogen
yang toksik dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebih
(Smeltzer, 2007). Hemodialisis merupakan suatu proses yang
digunakan pada pasien dalam keadaan sakit akut dan memerlukan terapi
dialisis jangka pendek (beberapa hari hingga beberapa minggu) atau
Terapi hemodialisis merupakan suatu tekhnologi tinggi sebagai
terapi pengganti untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun
tertentu dari peredaran darah manusia seperti air, natrium, kalium,
hydrogen, urea, kreatinin, asam urat, dan zat-zat lain melalui membrane
semi permeable sebagai pemisah darah dan cairan dialisat sebagai ginjal
buatan di mana terjadi proses difusi, osmosis, dan ultrafiltrasi
(Setyawan, 2001).
b.Cara Kerja Hemodialisa
Hemodialisa dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang
dilengkapi dengan membran permeabel (ginjal buatan) yang
memindahkan produk-produk limbah yang terakumulasi dari darah ke
mesin dialysis (Potter & Perry, 2006). Darah dimasukkan ke salah satu
ruang, sedangkan ruang yang lain diisi oleh cairan pendialisis, dan
diantara keduanya akan terjadi difusi (Corwin, 2009).
Aliran darah yang penuh dengan toksin dan limbah nitrogen
dialirkan dari tubuh pasien ke dialyzer tempat darah tersebut
dibersihkan dan kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien (Brunner
& Suddart, 2007).
c. Pertimbangan Psikososial
Menurut Brunner & Suddart (2007) ada beberapa pertimbangan
psikososial yang dihadapi oleh pasien gagal ginjal kronik yang
1) Individu dengan hemodialisa jangka panjang sering merasa
khawatir akan kondisi sakitnya yang tidak dapat diramalkan
dalam kehidupannya. Pasien biasanya mengalami masalah
financial, kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, dorongan
seksual yang menghilang serta impotensi, depresi akibat sakit
yang kronis dan ketakutan terhadap kematian.
2) Pasien dengan hemodialisa akan menjalani gaya hidup yang
terencana berhubungan dengam terapi dialysis dan pembatasan
asupan makanan serta cairan sering menghilangkan semangat
hidup pasien dan keluarga.
3) Dialysis yang dilakukan oleh pasien akan menyebabkan
perubahan gaya hidup pada keluarga. Waktu yang diperlukan
untuk terapi dialysis akan mengurangi waktu yang tersedia untuk
melakukan aktivitas sosial dan dapat menciptakan konflik,
frustasi, rasa bersalah serta depresi dalam keluarga. Pasien
hemodialisa akan mengalami perasaan kehilangan karena setiap
aspek kehidupan normalnya yang pernah dimiliki pasien telah
terganggu. Jika perasaan tersebut tidak diungkapkan, mungkin
akan diproyeksikan ke dalam diri sendiri dan menimbulkan
3. Depresi
a. Pengertian Depresi
Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai
dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan
bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak dapat tidur, kehilangan
selera makan, hasrat seksual dan minat serta kesenangan dalam
aktivitas yang biasa dilakukan. Depresi sering kali berhubungan dengan
berbagai masalah psikologis lain, seperti serangan panik,
penyalahgunaan zat, disfungsi seksual dan gangguan kepribadian
(Davison dkk, 2006). Individu yang mengalami depresi pada umumnya
menunjukkan gejala psikis, gejala fisik dan sosial yang khas, seperti
murung, sedih berkepanjangan, sensitive, mudah marah dan
tersinggung, hilang semangat, hilangnya percaya diri, hilangnya
konsentrasi, dan menurunnya daya tahan (Lubis, 2009).
Depresi merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan trias
depresi, yaitu kesedihan berkepanjangan, motivasi menurun, dan
kurang tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Keliat, 2011).
Depresi adalah gangguan mental umum dengan tanda kehilangan minat
atau kesenangan, perasaan bersalah atau rendah diri, tidur terganggu
atau nafsu makan menurun, energi rendah, dan hilang konsentrasi
b.Etiologi Depresi
Etiologi depresi secara pasti belum diketahui, ada beberapa
hipotesis yang berhubungan dengan faktor biologik dan psikososial.
1. Faktor Biologik
a) Biogenik Amin. Biogenik amin ini dilepaskan dalam ruang
sinaps sebagai neurotransmiter. Neurotransmiter yang banyak
berperan pada depresi adalah norepinefrin dan serotonin ( Idrus,
2007).
b) Hormonal, pada depresi ditemukan hiperaktivitas aksis system
limbic hipotalamus-hipofisis-adrenal yang menyebabkan
peningkatan sekresi kortisol. Selain itu juga ditemukan juga
penurunan hormone lain seperti GH, LH, FSH, dan testosterone
( Idrus, 2007 ).
c) Tidur, pada depresi ditemukan peningkatan aktivitas rapid eye movement (REM) pada fase awal memasuki tidur dan penurunan REM pada fase latensi ( Idrus, 2007).
d) Genetik, gangguan ini diturunkan dalam keluarga. Jika salah
seorang dari orang tua mempunyai riwayat depresi maka 27 %
anaknya akan menderita gangguan tersebut. Sedangkan bila
kedua orang tuanya menderita depresi maka kemungkinanya
2. Faktor Psikososial
Peristiwa kehidupan dan stres lingkungan dimana suatu
pengamatan klinik menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian dalam
kehidupan yang penuh ketegangan sering mendahului episode
gangguan mood. Suatu teori menjelaskan bahwa stres yang menyertai episode pertama akan menyebabkan perubahan fungsional
neurotransmitter dan sistem pemberi tanda intra neuronal yang
akhirnya perubahan tersebut menyebabkan seseorang mempunyai
resiko yang tinggi untuk menderita gangguan mood selanjutnya (Sadock & Sadock,2010).
Menurut penelitian Bibring mengatakan depresi sebagai suatu
efek yang dapat melakukan sesuatu terhadap agresi yang diarahkan
kedalam dirinya. Apabila pasien depresi menyadari bahwa mereka
tidak hidup sesuai dengan yang dicita-citakannya akan
mengakibatkan mereka putus asa.
c. Gambaran Klinis Depresi
Penderita depresi dapat ditemukan beberapa tanda dan gejala
umum menurut Diagnostic Manual Statistic IV (DSM-IV): (American Psychiatric Association, 2000) yaitu perubahan fisik dengan tanda penurunan nafsu makan,gangguan tidur, kelelahan atau kurang energy,
agitasi, nyeri, sakit kepala tanpa penyebab fisik. Kedua adalah
perubahan pikiran dengan tanda merasa bingung, lambat berpikir, sulit
mau dikritik, dan adanya pikiran untuk membunuh diri. Ketiga,
perubahan perasaan dengan ciri-ciri penurunan ketertarikan dengan
lawan jenis, merasa sedih, sering menangis tanpa alasan yang jelas,
irritabilitas, mudah marah dan terkadang agresif. Keempat, perubahan
pada kebiasaan sehari-hari dengan tanda menjauhkan diri dari
lingkungan social, penurunan aktivitas, serta menunda pekerjaan
rumah.
Menurut Maslim (2002) dalam PPDGJ-III, tingkatan depresi ada
3 berdasarkan gejala-gejalanya yaitu depresi ringan, gejalanya adalah
kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energy yang menuju
meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas,
konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri
yang kurang, lama gejala tersebut berlangsung sekurang-kurangnya 2
minggu. Depresi sedang, gejalanya adalah gagasan tentang rasa
bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan
pesimistis, lama gejala berlangsung minimum 2 minggu. Depresi berat,
dengan gejala mood depresif, perbuatan yang membahayakan dirinya
sendiri atau bunuh diri, tidur terganggu disertai halusinasi, lama gejala
berlangsung selama 2 minggu.
d.Penatalaksanaan Depresi
Penatalaksanaan depresi menurut Agus dalam Setiawan (2011)
antara lain yaitu terapi keluarga, problem keluarga dapat berperan
terhadap pasien sangat penting. Tujuan dari terapi terhadap keluarga
pasien yang depresi adalah untuk meredakan perasaan frustasi dan
putus asa, merubah dan memperbaiki sikap atau struktur dalam
keluarga yang menghambat proses penyembuhan pasien. Terapi
kognitif-perilaku, bertujuan mengubah pola pikir pasien yang selalu
negative (persepsi diri yang buruk, masa depan yang suram, diri yang
tak berguna lagi) ke arah pola pikir yang netral atau positif. Terapi seni
menurut The American Art Therapy Association dalam Mukhlis (2011),
terapi seni banyak digunakan sebagai sarana menyelesaikan konflik
emosional, meningkatkan kesadarn diri, mengembangkan keterampilan
social, mengontrol perilaku, menyelesaikan permasalahan, mengurangi
kecemasan, meningkatkan harga diri dan berbagai gangguan psikologis
lainnya.
Menurut Case dan Dalley dalam Mukhlis (2011), terapi seni
merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis terapi ekspresif
melibatkan individu dalam aktivitas kreatif dalam bentuk penciptaan
(karya atau produk) seni. Holt dan Kaiser dalam Mukhlis (2011)
mengatakan bahwa melalui aktivitas seni tersebut individu diasumsikan
mendapat media paling aman untuk memfasilitasi komunikasi melalui
eksplorasi pikiran, persepsi, keyakinan, dan pengalaman, khususnya
e. Pengukuran Tingkat Depresi
Gejala depresi diukur menurut tingkatan sesuai dengan gejala
yang termanifestasi. Jika dicurigai terjadi depresi harus dilakukan
pengkajian dengan alat pengkajian yang terstandarisasi dan dapat
dipercaya serta valid dan memang dirancang untuk diujikan kepada
pasien depresi (Azizah, 2011)
Beck Depression Inventory (BDI) merupakan salah satu
instrumen yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat
keparahan depresi. BDI dikembangkan untuk menilai jenis dan tingkat
keparahan depresi berdasarkan gejala (Beck dalam Ahn jo et al, 2006).
Instrumen ini terdiri dari 21 item yang memuat tentang kesedihan
pesimisme, perasaan gagal, perasaan tidak puas, perasaan bersalah atau
berdosa, perasaan dihukum, rasa benci pada diri sendiri, mudah
tersinggung,menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mampu
mengambil keputusan, penyimpangan citra tubuh, kelambanan dalam
bekerja, menangis, gangguan tidur, kelelahan, hilangnya nafsu makan,
penurunan berat badan, kecemasan fisik, dan penurunan libido
(Setiawan, 2011).
Skala BDI merupakan skala pengukuran yang mengevaluasi 21
gejala depresi, 15 di antaranya menggambarkan emosi, 4 perubahan
sikap, 6 gejala somatik. Setiap gejala dirangking dalam skala intensitas
4 poin dan nilainya ditambahkan untuk memberi total nilai dari 0-63,
untuk depresi, 0-9 mengindikasikan tidak ada depresi, 10-18 untuk
depresi ringan, 19-29 depresi sedang, dan 30-63 mengindikasikan
adanya depresi berat.
4. Mekanisme Koping
a. Pengertian Mekanisme Koping
Mekanisme koping adalah setiap upaya yang diarahkan pada
penatalaksanaan stres. Termasuk didalamnya upaya penyelesaian
langsung dan mekanisme koping pertahanan yang digunakan untuk
melindungi diri (Stuart, 2007). Mekanisme koping adalah cara yang
dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri
dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam
(Keliat, 1999 dalam Sulistiawati, 2005).
Koping merupakan respon individu terhadap situasi yang
mengancam dirinya baik fisik maupun psikologik. Menurut Nasir &
Muhith (2011), koping adalah proses dimana seseorang mencoba untuk
mengatur perbedaan yang diterima antara keinginan (demands) dan
pendapatan (resources) yang dinilai dalam suatu keadaan yang penuh
tekanan. Lebih lanjut Nasir & Muhith menjelaskan koping merupakan
suatu tindakan mengubah kognitif dan usaha tingkah laku untuk
mengatasi tuntutan internal atau eksternal yang dinilai membebani atau
b.Jenis Mekanisme Koping
Menurut Stuart (2009) mekanisme koping dibagi menjadi 3
bagian antara lain :
1) Problem Focused Coping
Problem Focused Coping merupakan mekanisme koping individu yang melibatkan tugas dan usaha langsung yang digunakan
individu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri.Termasuk dalam
koping ini adalah negosiasi, konfrontasi dan menerima nasihat.
2) Cognitively Focused Coping
Cognitively Focused Coping merupakan mekanisme koping dimana reaksi individu untuk mengontrol masalah dan berusaha
menetralisirnya. Termasuk dalam koping ini adalah perbandingan
positif, pengabaian secara elektif dan mengontrol keinginan.
3) Emotional Focused Coping
Emotional Focused Coping merupakan mekanisme koping dimana pasien berorientasi terhadap tekanan emosional. Contohnya
termasuk penggunaan mekanisme pertahan ego, seperti
penyangkalan, penindasan, atau proyeksi.
Menurut (Kelliat, 1999 dalam Ihdaniyati & Arifah, 2009)
mekanisme koping ada dua macam yaitu mekanisme koping adaptif,
adalah suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan
lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan
seimbang dan aktifitas konstruktif. Mekanisme koping maladaptif,
suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah
akibat adanya stressor atau tekanan yang bersifat negatif, merugikan
dan destruktif serta tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.
Kategorinya adalah makan berlebihan atau tidak makan, bekerja
berlebihan, menghindar, marah-marah, mudah tersinggung, dan
menyerang. Mekanisme koping yang maladaptif dapat memberikan
dampak yang buruk bagi seseorang seperti isolasi diri, berdampak
pada kesehatan fisik dan bahkan resiko bunuh diri.
c. Sumber Koping
Stuart dan Sundeen (2008) mengemukakan bahwa kemampuan
koping dipengaruhi oleh faktor internal meliputi umur, kepribadian,
intelegensi, pendidikan, nilai, kepercayaan, budaya, emosi, dan
kognitif. Faktor eksternal meliputi support sistem, lingkungan, dan
keadaan finansial penyakit. King dalam Family Focus Publication of National Kidney Foundation (2005) menyatakan bahwa salah satu cara koping yang dapat dilakukan oleh pasien GGK adalah dari segi
kerohanian dengan kegiatan seperti berdoa, meditasi, serta dating ke
tempat beribadah seperti masjid, gereja sesuai dengan kepercayaan
yang diyakini.
Stuart (2009) menyatakan bahwa salah satu sumber koping yaitu
menghadapi situasi stressful. Pendidikan yang tinggi dapat memiliki pengetahuan yang luas dan pemikiran yang lebih realistis dalam
pemecahan masalah yaitu salah satunya tentang kesehatan sehingga
dapat menerapkan gaya hidup sehat agar terhindar dari penyakit
(Notoatmodjo, 2011).
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Koping
1) Harapan akan self-efficacy, harapan akan self-efficacy berkenaan dengan harapan kita terhadap kemampuan diri dalam mengatasi
tantangan yang kita hadapi, harapan terhadap kemampuan diri
untuk menampilkan tingkah laku terampil, harapan terhadap
kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup yang
positif.
2) Dukungan sosial, individu dengan dukungan sosial tinggi akan
mengalami stress yang rendah ketika mengalami stress, dam
mereka akan mengatasi stress atau melakukan koping lebih baik.
Selain itu dukungan sosial juga menunjukkan kemungkinan untuk
sakit lebih rendah, mempercepat proses penyembuhan ketika sakit
dan untuk mengurangi resiko kematian terhadap penyakit yang
serius. Menurut hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan
sosial juga mempunyai hubungan positif yang dapat
mempengaruhi kesehatan individu dan kesejahteraannya atau dapat
meningkatkan kreativitas individu dalam kemampuan penyesuaian
3) Optimisme, pikiran yang optimis dapat menghadapi suatu masalah
lebih efektif dibanding pikiran yang pesimis berdasarkan cara
individu melihat suatu ancaman. Pikiran yang optimis dapat
membuat keadaan stressful sebagai sesuatu hal yang harus dihadapi
dan diselesaikan, oleh karena itu individu akan memilih
menyelesaikan dan menghadapi masalah yang ada dibandingkan
dengan individu yang mempunyai pikiran pesimis.
4) Jenis kelamin, menurut Yin, Chen & Cheng (2008) bahwa ada
perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam kontrol diri.
Anak laki-laki lebih sering menunjukkan perilaku-perilaku yang
dianggap sulit yaitu gembira berlebihan dan kadang-kadang
melakukan kegiatan fisik yang agresif, menentang, menolak
otoritas. Perempuan diberi penghargaan atas sensitivitas,
kelembutan, dan perasaan kasih, sedangkan laki-laki didorong
untuk menunjukkan emosinya, juga menyembunyikan sisi lembut
mereka dan kebutuhan mereka akan kasih sayang serta kehangatan.
Sebagian anak laki-laki, menganggap kemarahan adalah reaksi
emosional terhadap rasa frustasi yang paling diterima secara luas
(Affandi, 2009).
5) Periode Penyesuaian Psikologik
Hemodialisis akan menjadi gaya hidup bagi pasien dan
keluarganya, waktu yang dihabiskan untuk hemodialisis, berobat
marah, dan depresi. Hal ini dapat menyulitkan pasien, pasangan
dan keluarga untuk mengekspresika perasaan (Daugirdas, 2001
dalam Pratiwi, 2008). Menurut Kubler-Ross dalam Iyus Yosep
(2007) penyesuaian psikologis memiliki beberapa tahap, yaitu :
a) Pengingkaran atau denial, reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya atau menolak
kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi. Bagi individu atau
keluarga yang mengalami penyakit terminal, akan terus
menerus mencari informasi tambahan.
b) Marah atau anger, fase ini dimulai dengan timbulnya kesadaran
akan kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan
perasaan meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang
yang ada di lingkungannya, orang-orang tertentu atau ditujukan
pada dirinya sendiri. Reaksi yang ditujukan pada fase ini adalah
agresif, bicara kasar, menolak pengobatan dan menuduh dokter
dan perawat yang tidak kompeten.
c) Tawar-menawar atau bargaining, apabila individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif maka ia
akan maju ke tahap tawar-menawar. Pada tahap ini biasanya
pasien akan mengeluarkan kata-kata seperti “seandainya dulu
saya mau menjaga kesehatan”.
berbicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat
baik dan menurut atau dengan ungkapan yang menyatakan
keputusasaan, perasaan tidak berharga.
e) Penerimaan atau acceptance, fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran selalu terpusat
kepada objek atau orang hilang akan mulai berkurang.
e. Pengukuran Mekanisme Koping
Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui mekanisme
koping yang digunakan oleh pasien gagal ginjal yang menjalani
hemodialisa adalah The ways of coping yang telah dimodifikasi oleh Lita Purnama Sari (2013) yang terdiri dari 20 pertanyaan seperti yang
Tabel 2.1 Kisi-kisi pertanyaan tentang mekanisme koping
Jenis Koping Indikator Sebaran item Jumlah
Adaptif Membicarakan masalah dengan keluarga
Berdoa dan bertawakkal
Membicarakan dengan orang yang professional
Menyelesaikan permasalahan secara bertahap
Meminta nasihat pada orang lain Membicarakan pada orang
terdekat
Berfikir masalah ini wajar karena apa yang sudah dilakukan di masa lalu menerima masalah sebagai suatu pengalaman
Mencoba melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda Meyakinkan diri sendiri bahwa
masalah ini tidak terlalu penting
1,4,5,9,12,16,
11,14,18,2,8,7
12
Maladaptif Melampiaskan masalah dengan orang lain
Menghindar dari orang lain Merahasiakan kondisi sakit Melakukan sesuatu yang
berbahaya
Instrumen mekanisme koping ini menggunakan skala Likert
pernyataan bersifat favorabel, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Tahu
(TT),Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor
pernyataan yang bersifat unfavorabel, Sangat Setuju (SS), Setuju (S),
Tidak Tahu (TT),Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).
Kriteria pemberian skor untuk item favorabel meliputi jawaban
Sangat Setuju (SS) mendapatkan nilai 5, Setuju (S) mendapat nilai 4,
Tidak Tahu (TT) mendapatkan nilai 3, Tidak Setuju (TS) mendapatkan
nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) mendapatkan nilai 1. Kriteria
pemberian skor untuk item unfavorabel meliputi jawaban Sangat Setuju
(SS) mendapatkan nilai 1, Setuju (S) mendapat nilai 2, Tidak Tahu (TT)
mendapatkan nilai 3, Tidak Setuju (TS) mendapatkan nilai 4, Sangat Tidak
Setuju (STS) mendapatkan nilai 5. Skor total dari pernyataan favorabel
adalah 60 sementara skor total dari pernyataan unfavorable adalah 40.
Untuk menentukan responden yang menggunakan mekanisme koping
adaptif atau maladaptif dengan melihat nilai perbandingan skor pernyataan
yang lebih besar yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Nilai perbandingan skor adaptif =
Nilai perbandingan skor maladaptive =
Keterangan :
x : nilai skor pernyataan adaptif
B.Gambar 2.1 Kerangka Teori
Gambar 2.1.Kerangka Teori Penelitian
Sumber Modifikasi Roy (1979) , Health Belief Model, dan Thallis (1995).
Gagal Ginjal Kronik
Terapi Hemodialisis
Terjadi Depresi
Tiga jenis depresi :
1. Ringan(Mild) 2. Sedang
(Moderate) 3. Berat (Severe) Muncul tanda dan gejala depresi :
1. Perubahan fisik 2. Perubahan pikiran 3. Perubahan perasaan 4. Perubahan pada
kehidupan sehari-hari
Mekanisme Koping :
C.Gambar 2.2 Kerangka Konsep
Keterangan :
= Variabel yang diteliti
A.HIPOTESIS
Ha : Terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien
gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU
Muhammadiyah II Yogyakarta.
Ho :Tidak terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pada
pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU
Muhammadiyah II Yogyakarta. Depresi
Ringan
Sedang
Berat
Mekanisme Koping:
Adaptif Maladaptif
Pasien
BAB III
METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah Correlational Penelitian ini bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan, menguraikan dan menganalisa suatu populasi
dengan didasarkan dari hasil kesimpulan atau hasil analisis dari penelitian sampel yang
berasal dari populasi yang sedang diteliti (Machfoedz, 2010). Cross sectional disebut juga studi potong lintang dan juga mencari hubungan sebab akibat. Suatu rancangan penelitian
yang pengukuran atau pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat atau sekali
waktu (Hidayat, 2007).
B. Populasi dan Sampel 1. Populasi
Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pasien yang menjalani terapi
hemodialisis rutin di RS PKU Muhammadiyah II sebanyak 125 orang.
2. Sampel
Tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling dengan total sampling 70 orang karena banyak responden yang masuk dalam kriteria eksklusi.
Tempat penelitian yang digunakan adalah unit hemodialisa RS PKU
Muhammadiyah II Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian selama 1 bulan mulai 1 Maret 2016 sampai 30 Maret 2016.
D. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 1. Kriteria Inklusi
a. Pasien yang menjalani terapi hemodialisa, rutin dan terdata di RS PKU
Muhammadiyah II Yogyakarta.
b. Masih bisa berkomunikasi dengan baik dan kesadaran composmentis (kesadaran normal).
c. Bersedia menjadi responden.
2. Kriteria Eksklusi
a. Pasien yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap.
b. Pasien yang berpindah tempat dari unit hemodialisa RS PKU Muhammadiyah II
Yogyakarta ke rumah sakit lain.
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operational 1. Variabel Penelitian
Variabel dikarakteristikan sebagai derajat, jumlah dan perbedaan. Macam-macam
tipe variabel meliputi : independen, dependen, moderator (intervening), perancu dan
kendali/control (Nursalam, 2008). Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel
independen dan dependen.
Variabel bebas (independent) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau
perubahannya variable dependen (Sugiyono, 2007). Variabel independen dalam
penelitian ini adalah tingkat depresi.
b. Variabel Dependen (Terikat)
Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah mekanisme koping.
mengancam.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi
pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kuesioner dibagikan langsung
oleh peneliti kepada klien yang menderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi
hemodialisis untuk diisi dan dilengkapi. Untuk kuesioner tingkat depresi mengacu pada
Beck Depression Inventory (BDI). Skala BDI ( Beck Depression Inventory), terdiri dari 21 kelompok item yang menggambarkan 21 kategori sikap dan gejala depresi, yaitu : sedih,
pesimis, merasa gagal, merasa tidak puas, merasa bersalah, merasa dihukum, perasaan benci
pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kecenderungan bunuh diri, menangis, mudah
tersinggung, menarik diri dari hubungan sosial, tidak mampu mengambil keputusan, merasa
dirinya tidak menarik secara fisik, tidak mampu melaksanakan aktivitas, gangguan tidur,
merasa lelah, kehilangan selera makan, penurunan berat badan, preokupasi somatic dan
kehilangan libido sex (dalam Lestari, 2003).
Masing-masing kelompok item terdiri dari 3-6 pernyataan yang menggambarkan dari
tidak adanya gejala sampai adanya gejala yang paling berat. Pada klasifikasi Bumberry
(1987) skor 0-9 tidak mengalami depresi, skor 10-15 depresi ringan, skor 16-23 depresi
sedang, skor 24-63 depresi berat. Rentang skor pada Beck Depression Inventory (BDI) adalah 0-63 dengan skor minimal 0 dan skor maksimal 63. Alat ukur yang digunakan untuk
mengetahui mekanisme koping yang digunakan oleh pasien gagal ginjal yang menjalani
G. Cara Pengumpulan Data
1. Peneliti mengajukan surat permohonan izin dari institusi kepada Direktur RS PKU
Muhammadiyah II Yogyakarta
2. Peneliti mendapat surat persetujuan dari Direktur RS PKU Muhammadiyah II
Yogyakarta
3. Peneliti bertemu dan meminta bantuan kepada kepala ruang atau bangsal hemodialisa
yang bertanggung jawab di tempat penelitian untuk mengumpulkan data pasien
hemodialisis
4. Peneliti melakukan pendekatan dan penjelasan kepada responden tentang penelitian dan
mempersilahkan responden menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.
5. Peneliti memberikan penjelasan cara mengisi kuesioner dan memberikan waktu kepada
responden untuk mengisi kuesioner.
6. Setelah seluruh pernyataan dalam kuesioner dijawab, maka peneliti mengumpulkan dan
memeriksa kembali kelengkapan data kemudian mengolah datanya.
H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument 1. Uji Validitas (kesahihan)
Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip
keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa
yang seharusnya diukur (Nursalam, 2009). Instrument penelitian yang pertama adalah
melakukan beberapa kali penelitian. Kuesioner mekanisme koping telah diuji oleh Lita
Purnama Sari (2013) dan dinyatakan valid oleh expert dan layak digunakan sebagai instrument dalam penelitian.
2. Uji Reliabilitas (keandalan)
Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau
kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan
(Nursalam, 2009). Beck Depression Inventory (BDI) merupakan instrument pengumpulan
data yang sudah baku. Korelasi Beck Depression Inventory (BDI) dengan penelitian klinis diperoleh uji validitas rxy = 0,67. Uji reliabilitas Beck Depression Inventory (BDI)
dilakukan oleh Beck dengan (1985) teknik belah dua, diperoleh rxy = 0,86 dan meningkat
menjadi rxy = 0,93 setelah dikorelasi dengan rumus Spearman. Kuesioner mekanisme
telah diuji menggunakan koefisien alpha cronbach didapatkan hasil sebesar 0,916 dan dikatakan reliable.
I. Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden
selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Editing
Merupakan kegiatan pengecekan kembali data-data yang telah terkumpul untuk
mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan lengkap. Peneliti memeriksa kembali
kebenaran data pasien dengan yang ada di kuesioner.
2. Coding
Pada tahap ini data diubah dalam bentuk kode, yaitu dari data yang berbentuk