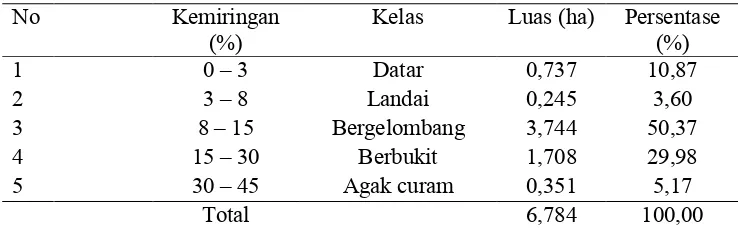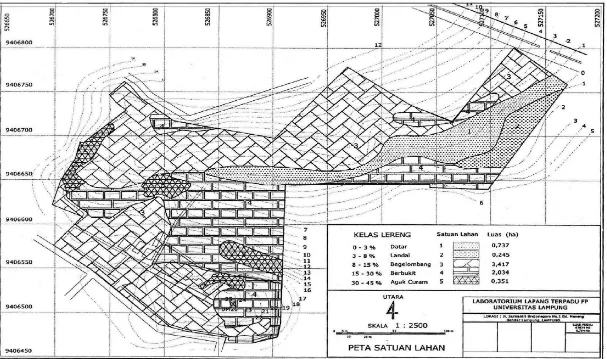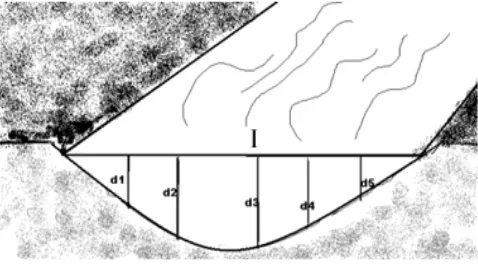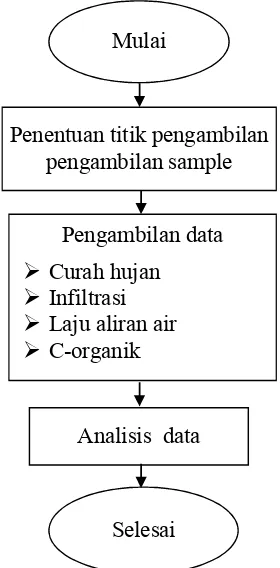ABSTRAK
DINAMIKA AIR PERMUKAAN DAN EVALUASI KARBON TERSIMPAN DALAM TANAH DI LABORATORIUM LAPANG TERPADU
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
Oleh
ADE HANDEKA PUTRA
Luas Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung lebih kurang 6.784 ha dan digunakan untuk melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan ilmu pertanian. Kondisi lereng dominan landai sampai bergelombang, jenis dan jumlah vegetasi yang bervariasi di masing-masing kelas kemiringan lereng, serta curah hujan yang tinggi, maka potensi erosi diperkirakan cukup besar sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kesuburan tanah serta berkurangnya lapisan atas tanah (top soil) apabila tidak di kelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan vegetasi terhadap dinamika air permukaan dan mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan vegetasi terhadap kandungan karbon tersimpan dalam tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2014 di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Data sekunder berupa data kandunga C-organik tahun 2012 dan peta kelas lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan data primer berupa curah hujan, infiltrasi, debit aliran air, dan C-organik. Data-data yang diperoleh diolah untuk mengetahui dinamika air permukaan dan mengevaluasi perubahan kandungan C-organik dalam tanah dari tahun 2012 sampai dengan 2014.
Rata-rata besar penurunan C-organik yang terjadi adalah sebesar 42,365 % dari Rata-rata-Rata-rata C-organik pada tahun 2012.
ABSTRACT
DYNAMICS OF SURFACE WATER AND EVALUATION OF CARBON STORED IN LABORATORIUM LAPANG TERPADU FACULTY OF
AGRICULTURE UNIVERSITY LAMPUNG
By
ADE HANDEKA PUTRA
Area of Laboratorium Lapang Terpadu Faculty of Agriculture University of Lampung approximately 6.784 ha and is used to perform a variety of research related to agricultural science. Conditions dominant slope sloping to undulating, the type and amount of vegetation that vary in each slope, and rainfall is high, then the estimated erosion potential is large enough so that it is feared will be a decrease in soil fertility and reduced topsoil (top soil) if not managed properly. The purpose of this study was to determine the effect of slope and vegetation on the surface of the water dynamics and determine the effect of the slope and vegetation carbon stored in the soil in the laboratorium lapang terpadu, Faculty of Agriculture, University of Lampung.
This research was conducted in June thru July 2014 in the Laboratorium Lapang Terpadu Faculty of Agriculture University of Lampung. The secondary data of C-organic in 2012 and the map slope class Laboratorium Lapang Terpadu Faculty of Agriculture University of Lampung and primary data in the form of precipitation, infiltration, water flow rate, and C-organic. The data have been obtained were processed to determine the dynamics of surface water and evaluate of C-organic content changes in soil from 2012 through 2014.
0.93, and 0.98%. whereas at a depth of 20-40 cm is 1.01, 0.71, 0.68, 0.58, and 0.67%. The content of C-organic at a depth of 0 – 20 cm has decreased in every slope respectively by 25.17, 56.12, 36.00, 48.04, and 42.35% of the amount of C-organic in 2012. the average score of the decline occurring C-C-organic is equal to 42.365% of the C-organic average in 2012.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Desa Negararatu, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, pada tanggal 5
November 1989, dengan nama Ade Handeka Putra. Penulis
merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak
Asmaun dan Ibu Hayati.
Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 1 Rumbih pada tahun 1996 –
2002, SMP N 1 Pakuan Ratu 2002 – 2005, SMA Yayasan Pendidikan Islam Bina
Mulya (YPI BM) Bandar Lampung pada tahun 2005 – 2008. Kemudian pada tahun
2008 penulis diterima di Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung melalui jalur
MANDIRI.
Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya kecilku ini
sebagai tanda bakti, cinta, dan kasih sayangku
Kepada
Ayahanda dan ibunda tercinta,
Atas segala cinta , kasih sayang, dan pengorbanan yang begitu
besar untukku,
Almamater tercinta,
&
Setiap peristiwa di jagad raya ini adalah potongan-potongan
moziak, terserak disana sini, tersebar dalam rentang waktu dan
ruang. Namun ia akan bersatu perlahan-lahan membangun siapa
diri kita. Lalu apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini akan
bergema dalam keabadian (Andrea Hirata)
Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras
Keyakinan adalah percaya terhadap apa yang tidak bisa kita
lihat, dan buah dari keyakinan adalah melihat apa yang kita yakini
SANWACANA
Segala Puji Syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan
anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
“Dinamika Air Permukaan Dan Evaluasi Karbon Tersimpan Dalam Tanah Di
Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung”.
Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan
bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan skripsi ini tidak
sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu, Penulis
mengucapkan terima kasih kepada :
1.
Bapak Ir. Iskandar Zulkarnain, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus
pembimbing akademik yang telah banyak membantu, membimbing dan
memberikan saran serta motivasi selama kuliah hingga selesainya sekripsi ini.
2.
Bapak Dr. Ir. Henrie Buchari, M.Si., selaku pembimbing dua yang telah banyak
membantu selama proses penelitian dan penyelesaian skripsi.
3.
Bapak Ir. Oktafri, M.Si., selaku pembahas atas saran dan masukan bagi penulis.
5.
Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung.
6.
Bapak Warji, S.Tp., M.Sc., selaku Kepala Laboratorium Lapang Terpadu
Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
7.
Seluruh Dosen dan karyawan Jurusan Teknik Pertanian atas semua bantuan yang
telah diberikan.
8.
Bapak dan Ibu tercinta beserta keluarga besar Pangeran Lambung yang selalu
senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat yang tak terbatas kepada
penulis.
9.
Keluarga besar RAGAPALA atas kekeluargan dan sebagai tempat penulis
banyak mendapatkan pendidikan.
10.
Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian Universitas
Lampung.
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa maupun
masyarakat luas. Penulis selalu berdo’a semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah
SWT, amin.
Bandar Lampung, 2014
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... i
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR GAMBAR ... iv
DAFTAR LAMPIRAN ... v
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1
1.2. Tujuan Penelitian ... 4
1.3. Manfaat Penelitian ... 4
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kemiringan Lereng ... 5
2.2. Vegetasi ... 7
2.3. Infiltrasi ... 9
2.4. Aliran Permukaan ... 11
2.5. Karbon Tersimpan ... 15
III. METODE PENELITIAN 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... 18
3.2. Alat dan Bahan ... 18
3.3. Jenis dan Sumber Data ... 18
3.4. Metode Penelitian ... 19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian ... 25
4.1.1. Curah Hujan... 25
ii
4.1.3. Debit Air ... 31
4.1.4. Karbon Tersimpan ... 32
4.2. Pembahasan ... 34
4.2.1. Curah Hujan... 34
4.2.2. Infiltrasi ... 34
4.2.3. Debit Air ... 38
4.2.4. Runoff ... 42
4.2.5. Karbon Tersimpan ... 45
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 51
5.2. Saran ... 51
DAFTAR PUSTAKA ... 52
1
DAFTAR TABEL
Tabel Teks Halaman 1. Kelas dan luas lereng laboratorium lapang terpadu Fakultas
Pertanian Universitas Lampung ... 19
2. Infiltrasi di masing-masing kelas kemiringan lereng ... 26
3. Kandungan karbon organik tanah tahun 2012 pada kedalaman 0 – 20 cm ... 32
4. Kandungan C-organik tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2014 ... 33
5. Volume curah hujan harian ... 34
6. Debit air hasil pengukuraan di sungai ... 40
7. Perkiraan run off yang terjadi selama penelitian ... 44
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Teks Halaman
1. Curah hujan harian pada bulan Juni dan Juli 2014 ... 56
2. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 0-3% ... 57
3. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 3-8% ... 58
4. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 8-15% ... 59
5. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 15-30% ... 60
6. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 30-45% ... 61
7. Perkiraan runoff ... 62
8. Debit air hari ke-1 (23 juni2014) ... 63
9. Debit air hari ke-2 (24 juni2014) ... 64
10. Debit air hari ke-3 (25 juni2014) ... 65
11. Debit air hari ke-4 (26 juni2014) ... 66
12. Debit air hari ke-5 (27 juni2014) ... 67
13. Debit air hari ke-6 (28 juni2014) ... 68
14. Debit air hari ke-7 (29 juni2014) ... 79
15. Debit air hari ke-8 (11 juli2014) ... 70
16. Penurunan karbon organik pada kedalaman 0-20 cm ... 71
vi
18. Data jumlah hujan maksimum harian stasiun kemiling ... 73
1
DAFTAR GAMBAR
Gambar Teks Halaman 1. Peta kelas lereng Lahan Laboratorium Lapang Terpadu
Fakultas Pertanian Universitas Lampung ... 20
2. Pengukuran luas penampang ... 22
3. Diagram alir penelitian ... 24
4. Grafik curah hujan bulan Juni dan Juli 2014 ... 25
5. Grafik log (f0-fc) terhadap waktu pada setiap kelas lereng ... 27
6. Grafik waktu terhadap laju infiltrasi pada setiap kelas lereng ... 27
7. Debit aliran air di dalam saluran selama pengukuran berlangsung ... 32
8. Masuknya air ke dalam tanah dari Double Ring Infiltrometer ... 37
9. Denah lokasi pengukuran debit aliran air ... 39
1
I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Lahan merupakan sumberdaya alam yang jumlahnya terbatas dan seiring
berjalannya waktu terjadi penurunan kualitas lahan. Menurut Asdak (2003) dalam
Saribun (2007) kebutuhan akan sumberdaya lahan oleh manusia yang semakin
meningkat telah memberikan corak tersendiri terhadap pola penggunaan lahan di
suatu kawasan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan tata guna
lahan, seperti perubahan pemanfaatan lahan dari hutan ke pertanian dan
pemanfaatan lahan lainnya, yang dapat mengganggu stabilitas tata air dan tanah.
Laboratorium Lapang Terpadu Fakutas Pertanian Universitas Lampung berperan
penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Kelancaran belajar mengajar
sangat diperlukan untuk mendukung visi Unversitas Lampung maupun visi dan
misi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Menurut Banua, Syam, dan
Wiharso (2011) dalam Zulkarnain (2012), Laboratorium Lapang Terpadu tersebut
selain sebagai pendukung proses belajar mengajar dan penelitian, juga dapat
dijadikan etalase (show window). Keberadaan Laboratorium Lapang Terpadu ini
diharapkan dapat membangun image baru pada bidang pertanian, khususnya bagi
generasi muda, bahwa bidang pertanian tidak kalah dengan bidang yang lain,
2
Luas Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung
lebih kurang 6,784 ha terletak di komplek kampus Universitas Lampung.
Laboratorium ini digunakan untuk melakukan berbagai penelitian yang berkaitan
dengan ilmu pertanian. Kondisi lereng dominan landai sampai bergelombang,
serta curah hujan yang tinggi, maka potensi erosi diperkirakan cukup besar
sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kesuburan tanah serta
berkurangnya lapisan atas tanah (top soil) apabila tidak di kelola dengan baik
(Zulkarnain, 2012).
Kemiringan lereng dan vegetasi mempengaruhi dinamika air permukaan.
Menurut Maro’ah (2011), model tanaman diharapkan mampu meningkatkan laju
infiltrasi dan permeabilitas tanah dengan memperbaiki sifat-sifat tanah. Dengan
kajian laju infiltrasi dan permeabilitas tanah pada beberapa tanaman diharapkan
mampu untuk meningkatkan upaya perbaikan sifat-sifat tanah. Sehingga nantinya
mampu mengurangi aliran permukaan tanah (run off) yang dapat menyebabkan
erosi.
Aliran permukaan (run off) dan infiltrasi dipengaruhi oleh kemiringan lereng.
Semakin curam lereng maka semakin besar potensi terjadinya run off dan semakin
kecil potensi terjadinya infiltrasi. Santosa (2013), menyatakan bahwa gaya
gravitasi menyebabkan aliran selalu menuju ketempat yang paling rendah.
Sedangkan gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Air kapiler
3
Selain penggunaan lahan, kemiringan lereng merupakan faktor lain yang
mempengaruhi keadaan suatu lahan. Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng
curam berpotensi mengalami erosi yang besar. Menurut Saribun (2007)
Kemiringan lereng merupakan faktor lain yang mempengaruhi keadaan suatu
DAS selain penggunaan lahan. Wilayah DAS bagian hulu yang terletak di
dataran tinggi yang pada umumnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan
lereng di atas 15 %. Kondisi wilayah tersebut berpotensi mengalami erosi yang
besar. Erosi akan meningkat apabila lereng semakin curam. Selain dari
memperbesar jumlah aliran permukaan, semakin curamnya lereng juga
memperbesar energi angkut air. Hal ini disebabkan gaya berat yang semakin
besar sejalan dengan semakin miringnya permukaan tanah dari bidang horizontal,
sehingga lapisan tanah atas yang tererosi akan semakin banyak.
Vegetasi dapat membuat keadaan tanah menjadi lebih gembur serta memperhalus
agregat tanah. Terbentuknya agregat tanah yang lebih halus akan menyebabkan
bobot isi tanah menurun dan porositas tanah yang tinggi. Hal ini akan
menyebabkan terdapat banyak pori makro dan mikro sehingga permeabilitas lebih
cepat dan meningkatkan kadar air tanah. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh
terhadap laju infiltrasi dan menurunkan aliran permukaan tanah. Sebaliknya,
hilangnya vegetasi (hutan) pada daerah aliran sungai, terutama di bagian hulu
dapat menyebabkan meningkatnya laju erosi. Erosi yang berlangsung secara
terus menerus dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas (top-soil),
4
Pertumbuhan tanaman dipengaruhi sifat-sifat kesuburan tanahnya yakni
kesuburan fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologos. Analisis kadar unsur
hara Karbon Organik dan Nitrogen dapat dijadikan parameter dalam pengujian
kimia tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Karbon penting sebagai
bahan pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan kereing tanaman
terdiri dari bahan organik (Fauzi, 2008).
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan vegetasi terhadap dinamika air
permukaan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas
Lampung.
2. Mengetahui pengaruh kemiringan lereng terhadap kandungan karbon
tersimpan dalam tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian
Universitas Lampung.
3. Mengetahui pengaruh vegetasi terhadap kandungan karbon tersimpan dalam
tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas
Lampung.
1.3 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai data dinamika
aliran permukaan dan kandungan kerbon tersimpan dalam tanah dengan analisis
kadar C-organik dalam tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian
5
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kemiringan Lereng
Menurut Kurnia, Rahman, dan Daraih (2004, dalam Sugiono, 2007) menyatakan
bahwa tanah di Indonesia tergolong peka terhadap erosi karena terbentuk dari
bahan-bahan yang relatif mudah lapuk. Erosi yang terjadi akan memperburuk
kondisi tanah tersebut dan menurunkan produktivitasnya.
Hasil analisis kandungan C-tanah akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan
pertanian menurun dengan nyata. Sedangkan kandungan C-organik berbagai
lahan pertanian tidak berbeda nyata bila dibandingkan satu dengan lainnya.
Secara keseluruhan nampak bahwa alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian
menunjukkan adanya penurunan kadar C-organik tanah. Lahan hutan memiliki
kandungan bahan organik tinggi karena adanya suplai bahan organik yang
terus-menerus dari vegetasi hutan sehingga terjadi penumpukan. Kondisi stabil tersebut
memungkinkan dekomposisi bahan organik berlangsung secara alami, sebaliknya
pada lahan pertanian proses dekomposisi berlangsung dengan cepat karena adanya
pengelolaan dari petani. Hal ini dapat dipahami karena dengan terbukanya lahan
suhu meningkat sehingga laju dekomposisi bahan organik berlangsung lebih
6
bahan organik tanah tebawa erosi ketika terjadi aliran permukaan (Monde,
Sinukaban, Murtilaksono, dan Pandjaitan, 2008).
Kehilangan C-organik melalui aliran permukaan relatif tidak bebeda nyata satu
dengan lainnya akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian. Hal ini
terjadi karena bahan organik yang terangkut aliran permukaan umumnya dalam
bentuk koloid sehingga yang berbeda diduga adalah konsentrasi. Meskipun total
aliran permukaan pada lahan hutan kecil namun konsentrasi C-organiknya relatif
tinggi. Dilihat dari kehilangan C, nampaknya kehilangan melalui erosi jauh lebih
besar dibanding dengan aliran permukaan. Unsur yang paling besar terbawa erosi
dan aliran permukaan adalah C-organik. Kehilangan unsur ini berkaitan erat
dengan besarnya erosi yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan.
Semakin besar erosi maka karbon yang terangkut semakin banyak pula (Monde
dkk. 2008).
Bahan organik mempunyai peranan penting sebagai bahan pemicu kesuburan
tanah, baik secara langsung sebagai pamasok hara bagi organisme authotrof
(tanaman) juga sebagai sumber energi bagi organisme heterotrof (fauna dan
mikroorganisme tanah). Meningkatnya aktivitas biologi tanah akan mendorong
terjadinya perbaikan kesuburan tanah, baik kesuburan fisik, kimia maupun biologi
tanah. Perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang searah dengan
kebutuhan tanaman (plant requirement) tanaman target akan mampu memperbaiki
7
2.2 Vegetasi
Menurut Monde dkk. (2008) total karbon serasah pada lantai lahan hutan jauh
lebih banyak dan berbeda nyata dibandingkan dengan lahan yang ditanami kakao.
Total serasah pada setiap tingkatan umur kakao tidak berbeda nyata satu dengan
lainnya. Meskipun demikian terjadi peningkatan jumlah serasah dengan
bertambah besarnya tanaman kakao, terutama bila ditanam dengan sistem
agroforestri. Jumlah serasah pada permukaan tanah sangat mempengaruhi
penutupan permukaan lahan pada masing-masing penggunaan lahan. Ada
korelasi positif antara jumlah serasah persatuan luas dengan tingkat penutupan
lahan, artinya semakin bertambahnya jumlah serasah yang ada dipermukaan lahan
akan mengakibatkan meningkatnya prosentase penutupan permukaan tanah.
Selanjutnya Monde (2009) menyatakan bahwa secara umum alih guna lahan hutan
menjadi lahan kakao menyebabkan terjadinya penurunan kadar C organik.
Kondisi ini terjadi karena sebagian telah terangkut oleh erosi, aliran permukaan,
hilang dalam bentuk gas dan diperparah lagi oleh tidak adanya usaha pemupukan
organik untuk mensuplai karbon ke dalam tanah. Status karbon organik tersebut
dalam tanah yang ditanami kakao rendah hingga sedang. Kandungan C-organik
lahan hutan relatif lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding dengan kakao umur
6 – 7 tahun dan >10 tahun baik monokultur maupun agroforestri. Persediaan
karbon pada lahan hutan umumnya sangat tinggi baik dalam tubuh vegetasi,
dalam tanah ataupun dalam bentuk serasah, dibandingkan dengan dengan lahan
kakao. Ini berarti bahwa lahan hutan sangat efektif menyerap dan menyimpan
8
Vegetasi adalah sumber utama bahan organik tanah. Bahan induk organik yang
dikenal dengan sebutan gambut berasal dari vegetasi. Berbeda dengan batuan
induk dan iklim yang merupakan faktor mandiri, vegetasi bergantung pada hasil
interaksi antara batuan, iklim, dan tanah. Vegetasi dan tanah bersifat timbal balik.
Ragam vegetasi dalam kawasan luas terutama ditentukan oleh keadaan iklim.
Maka ragam pokok vegetasi berkaitan dengan iklim. Namun demikian vegetasi
tetap berdaya pengaruh khusus atas pembentukan tanah, yaitu menyediakan bahan
induk organik, menambahkan bahan organik kepada tanah mineral, menentukan
ragam humus yang terbantuk, menciptakan iklim meso dan mikro dengan
mengurangi rentang suhu dan kelembaban ekstrim, melindungi permukaan tanah
terhadap erosi, pengelupasan, penampatan dan pergerakan, memperlancar
infiltrasi dan perkolasi air, memelihara ekosistem tanah, menyerap hara yang
terdapat di bagian bawah tubuh tanah dengan system perakarannya dan
mengangkat hara ke permukaan tanah dalam bentuk seresah atau yang disebut
dengan konversi daur hara (Notohadiprawiro, 2006).
Kehilangan vegetasi penutup tanah akibat panen menyebabkan penetrasi sinar
matahari sehingga meningkatkan temperatur tanah sehingga memacu
dekomposisi residu tanaman. Selain itu, penggunakan alat-alat panen memberi
peluang untuk terjadinya pencampuran serasah sisa panen dengan tanah yang
juga memacu proses dekomposisi. Respirasi oleh mikrobia heterotrofik
merupakan salah satu mekanisme penting dalam dekomposisi bahan organik yang
terakumulasi baik di atas maupun di bawah permukaan tanah (sabaruddin, Fitri,
dan Lestari, 2009). Hutan merupakan rintangan terhadap gerakan menurunnya
9
lebih tinggi karena timbunan seresah, penetrasi akar (pengaruh perforasi) ke
dalam system tanah, dan aktifitas organisme (Seyhan, 1977)
2.3 Infiltrasi
Infiltrasi adalah perjalanan air masik ke dalam tanah. perkolasi adalah proses
kelanjutan perjalanan air tersebut ke tanah yang lebih dalam. Dengan kata lain,
infiltrasi adalah perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat gaya kapiler
(gerakan air ke arah leteral) dan gravitasi (gerakan air ke arah vertikal). Setelah
keadaan jenuh pada lapisan tanah bagian atas terlampaui, sebagian air tersebut
mengalir ke tanah yang lebih dalam sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan
dikenal sebagai proses perkolasi. Laju maksimal gerakan air ke dalam tanah
dinamakan kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi terjadi ketika intensitas hujan
melebihi kemampuan tanah dalam menyerap air. Sebaliknya, apabila intensitas
hujan lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan
laju hujan. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan
satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam (mm/jam) (Asdak, 1995).
Model Horton adalah salah satu model infiltrasi yang terkenal dalam hidrologi.
Horton mengakui bahwa kapasitas infiltrasi berkurang seiring dengan
bertambahnya waktu hingga mendekati nilai yang konstan. Ia menyatakan
pandangannya bahwa penurunan kapasitas infiltrasi lebih dikontrol oleh faktor
yang beroperasi di permukaan tanah dibanding dengan proses aliran di dalam
tanah. Faktor yang berperan untuk pengurangan laju infiltrasi seperti penutupan
retakan tanah oleh koloid tanah dan pembentukan kerak tanah, penghancuran
10
oleh tetesan air hujan. Model Horton dapat dinyatakan secara matematis
mengikuti persamaan berukut :
f = fc + (fo – fc)e-kt; fc dan k = konstan ………. (1)
Keterangan;
f : laju infiltrasi nyata (cm/jam)
fc : laju infiltrasi tetap (cm/jam)
fo : laju infiltrasi awal (cm/jam)
k : konstanta geofisik
Model ini sangat simpel dan lebih cocok untuk data percobaan. Kelemahan utama
dari model ini terletak pada penentuan parameternya f0, fc, dan k dan ditentukan
dengan data-fitting. Meskipun demikian dengan kemajuan system computer
proses ini dapat dilakukan dengan program spreadsheet sederhana (Achmad,
2011).
Infiltrometer merupakan suatu tabung baja silinder pendek, berdiameter besar
(atau suatu batas kedap air lainnya) yang mengitari suatu daerah dalam tanah.
infiltrometer cincin konsentrik terdiri dari dua cincin konsentrik yang ditekan ke
dalam permukaan tanah. kedua cincin tersebut digenangi secara terus-menerus
untuk mempertahankan tinggi yang konstan (jeluk air). Masing-masing
penambahan air untuk mempertahankan tinggi air yang konstan ini hanya diukur
(waktu dan jumlah) pada cincin bagian dalam. Cincin bagian luar digunakan
untuk mengurangi pengaruh batas dari tanah sekitarnya yang lebih kering. Kalau
tidak, air dari cincin bagian dalam yang berinfiltrasi juga dapat menyebar secara
11
Seyhan (1977) menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi
infiltrasi, yaitu :
1. Karakteristik-karakteristik hujan (hubungan I dan fc)
2. Kondisi-kondisi permukaan tanah
3. Tetesan hujan, hewan maupun mesin yang memadatkan permukaan tanah.
4. Pencucian partikel halus dapat menyumbat pori pada permukaan tanah.
5. Laju infiltrasi awal (f0).
6. Kemiringan tanah.
7. Pembekuan permukaan tanah.
8. Vegetasi
2.4 Aliran Permukaan
Sudarmanto, Buchori, dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa proses infiltrasi
merupakan proses yang paling penting dalam siklus hidrologi. Dengan adanya
infiltrasi, maka akan tersedia air untuk evaporasi dan transpirasi, serta tersedianya
peluang dalam peningkatan cadangan air tanah, yang berpengaruh juga pada
kontinuitas aliran permukaan baik dari subsurface flow dan base flow.
Selanjutnya Sudarmanto dkk. (2013) menambahkan jika merujuk pada hasil
analisis hidrometeorologis dan analisis kondisi resapan air dari data karakteristik
Daerah Aliran Sungai (DAS) bahwa akumulasi infiltrasi yang mempengaruhi
perubahan cadangan air tanah menunjukkan terjadi defisit akibat kebutuhan alami
air pada musim kemarau, maka seharusnya perlu dilakukan upaya-upaya
peningkatan kemampuan infiltrasi dengan cara meningkatkan nilai dari
12
Sedangkan pada kondisi sangat kritis perlu dilakukan tindakan yang lebih serius,
misalnya membuat waduk. Kemudian untuk lahan-lahan dengan kondisi kritis
lebih cenderung berpenggunaan lahan persawahan dan lahan permukiman,
sehingga upaya serius yang perlu dilakukan yaitu pada lokasi permukiman lebih
ditekankan pada peningkatan pemanfaatan biopori pada cekungan-cekungan tanah
pekarangan, selain itu juga perlu menerapkan konsep“rain harvesting” agar
pemakaian air tanah domestik berkurang, sehingga dapat memperlambat
penurunan cadangan airtanah. Sedangkan pada lahan persawahan, yang memiliki
permeabilitas resapan tanah sangat kecil, kiranya perlu diterapkan sistem
eco-drainase pada sungai-sungai yang dapat meningkatkan kemampuan infiltrasi,
sehingga dapat meresapkan air dari aliran permukaan.
Pada prinsipnya jumlah air di alam ini tetap, namun dengan adanya faktor energi
panas matahari, dan faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya proses
evapotranspirasi ke atmosfer dari vegetasi, permukaan tanah, laut dan badan air
lainnya. Hasil evapotranspirasi tersebut yang berupa uap air akan terbawa oleh
angin melintasi daratan, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan, sebagian
dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun sebagai air hujan. Sebelum
mencapai permukaan tanah air hujan akan tertahan oleh vegetasi (interception).
Sementara air hujan yang mampu mencapai permukaan tanah, sebagian akan
teresapkan ke dalam tanah (infiltrasi) hingga mencapai tingkat kapasitas lapang,
dan sisanya akan melimpas melalui permukaan tanah (direct run-off) menuju ke
13
Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah kemiringan (slope),
panjang lereng dan bentuk lereng. Kemiringan lereng mempengaruhi kecepatan
dan volume limpasan permukaan. Semakin curam suatu lereng, maka laju
limpasan permukaan akan semakin cepat, dan laju infiltrasi juga akan berkurang
sehingga volume limpasan semakin besar. Panjang lereng ini mempengaruhi
energi untuk erosi, terutama karena panjang lereng mempengarui volume
limpasan sehingga juga mempengaruhi kemampuan untuk membuat tanah tererosi
(Asmaranto, Suhartanto, dan Permana, 2009)
Akhir-akhir ini timbul kekhawatiran akan semakin meningkatnya kerusakan
berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, pada musim hujan semakin
banyak sungai yang meluap dan banjir sedangkan pada musim kemarau banyak
wilayah mengalami kekeringan. Diantara masalah yang cukup dianggap
mendesak dan perlu penanggulangan serius adalah semakin kritisnya keadaan
hidrologi beberapa sungai yang ditandai dengan semakin besarnya angka rasio
antara debit maksimum pada musim hujan dengan debit minimum pada musim
kemarau, serta semakin mundurnya produktivitas lahan terutama di bagian hulu
DAS. Kegiatan manusia yang bersifat merubah tipe atau jenis penutup lahan
dalam suatu DAS seringkali dapat memperbesar atau memperkecil hasil air (water
yield).
Perubahan dari jenis vegetasi hutan, perladangan berpindah, atau perubahan
tataguna lahan hutan menjadi areal pertanian atau padang rumput adalah
contoh-contoh kegiatan yang sering dijumpai di daerah hulu sungai. Perilaku masyarakat
14
degradasi lingkungan, sehingga memperbesar limpasan air. Kebanyakan
masyarakat menginginkan prodiktivitas yang tinggi tanpa menghiraukan
terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
Konversi hutan menjadi lahan pertanian khususnya pada lahan miring merupakan
kegiatan yang beresiko tinggi ditinjau dari sudut pandang pengelolaan Daerah
Aliran Sungai (DAS). Masalah utama yang dihadapi akibat adanya Perubahan
penutupan lahan di suatu DAS khususnya lahan hutan adalah tingginya nilai erosi
dan fluktuasi debit, sehingga dalam hal ini pendugaan nilai erosi dan sedimen
sangat diperlukan. Salah satu metode yang digunakan untuk menduga besarnya
nilai erosi dan sedimen yaitu melalui pendekatan model hidrologi (Slamet, 2011).
Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di dalam
tanah air mengalir dalam arah lateral, sebagai aliran antara (interflow) menuju
mata air, danau, dan sungai; atau secara vertikal, yang dikenal dengan perkolasi
(percolation) menuju air tanah. Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan
tanah, seperti rumput atau hutan, dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah
tersebut. Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan
tanah, dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang atau
tempat hidup serangga. Apabila terjadi hujan lapisan humus mengembang dan
lobang-lobang (sarang) yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeabel.
Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup
tanaman. Kondisi topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan
kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air
15
permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar air menggenang, sehingga
mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi (Santosa, 2013).
2.5 Karbon Tersimpan
Tingginya kandungan bahan organik dapat menyebabkan banyaknya air yang
dapat disimpan dalam tanah sehingga pemberian bahan organik dapat
meningkatkan kadar air tersedia. Pada tanah yang diberi bahan organik baik
berupa pupuk kandang dan kompos mampu meningkatkan kadar air tersedia
dalam tanah dibandingkan dengan tanpa bahan organik. Keadaan tersebut diduga
dengan meningkatnya bahan organik dalam tanah akan meningkatkan daya
pegang tanah terhadap air (Intara, Sapei, Erizal, Sembiring, dan Djoefrie, 2011).
Rendahnya kandungan bahan organik dapat disebabkan oleh pengolahan lahan
yang belum berbasis konservasi dengan memanfaatkan potensi sumber bahan
organik yang ada. Bahan organik mempunyai peran yang penting yaitu
menentukan kualitas tanah untuk kelestarian produksi pertanian melalui
pengaruhnya pada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Oleh karena itu
pelestarian peningkatan kandungan bahan organik tanah seharusnya merupakan
prioritas untuk meningkatkan kualitas tanah dan untuk penyimpanan karbon.
Langkah yang bisa dilakukan adalah mempertahankan sisa panen dan
mengaplikasikannya sebagai kompos, mengurangi intensitas pengolahan tanah,
pendekatan pola tanam dengan rotasi tanaman, penerapan sistem agroforestri, dan
pemanfaatan teknologi mikoriza (Supriadi, 2008).
Sumber primer bahan organik adalah jaringan tanaman berupa akar, batang, daun,
16
fotosintesis sehingga unsur karbon merupakan penyusun utama dari bahan
organik tersebut. Unsur karbon ini berada dalam bentuk senyawa-senyawa
polisakarida seperti selulosa, hemi-selulosa, pati dan bahan-bahan pektin dan
lignin. Selain itu nitrogen merupakan unsur yang paling banyak terakumulasi
dalam bahan organik karena merupakan unsur yang paling penting bagi mikroba
yang terlibat dalam proses perombakan bahan organik tanah. Jaringan tanaman
ini akan mengalami dekomposisi dan terangkut ke lapisan bawah (Sutanto, 2002
dalam Katonsasongko, 2013)
Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanah,
baik secara fisik atau kimia. Bahan organik tanah memiliki banyak kegunaan,
diantaranya dalam mempertahankan struktur tanah, meningkatkan kemampuan
tanah untuk menyimpan dan mendistribusikan air dan udara di dalam tanah, serta
nutrisi-nutrisi ntuk pertumbuhan tanaman dan organisme didalam tanah (Oktavia,
2006)
Dekomposisi bahan organik dapat terjadi pada kondisi aerob dan anaerob. Kedua
proses tersebut dibedakan dalam dua hal, yaitu kecepatan dekomposisi dan hasil
akhir dekomposisi. Bentuk NO3- dan NH4+ tanah diperlukan oleh jasad-jasad
renik dalam proses dekomposisi bahan organik. Apabila bahan yang dihancurkan
kaya akan N dibandingkan dengan kadar C, maka tidakakan terjadi imobilisasi N,
sebaliknya jika kadar N lebih rendah dari kadar C, maka akan terjadi proses
imobilisasi N-tanah oleh mikroorganisme. Laju dekomposisi bahan organik
dipengaruhi oleh: (a) bahan asal tumbuhan, meliputi jenis, umur, dan komposisi
17
dan, tingkat kesuburan), (c) faktor iklim, Kandungan hara dalam pupuk organik
yang mencukupi, akan menunjang peningkatan produksi pertanian (Soepardi 1983
18
III. METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2014 di
Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3.2 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta, meteran, mistar,
stopwatch, bola pimpong, double ring infiltrometer, cangkul, bor tanah, benang,
alat tulis, kamera, komputer.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data
sekunder berupa data kandungan C-organik dan peta yang akan digunakan untuk
menentukan titik pengambilam sampel.
Data kelas dan luas lereng disajikan pada Tabel 1, dan peta satuan lahan
Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung disajikan
19
Tabel 1. Kelas dan luas lereng laboratorium lapang terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung
No Kemiringan
(%) Kelas Luas (ha) Persentase (%)
1 0 – 3 Datar 0,737 10,87
2 3 – 8 Landai 0,245 3,60
3 8 – 15 Bergelombang 3,744 50,37
4 15 – 30 Berbukit 1,708 29,98
5 30 – 45 Agak curam 0,351 5,17
Total 6,784 100,00
Sumber : Hasil pengukuran peta topografi skala 1 : 500 (Banuwa dkk, 2011 dalam Zulkarnain, 2011)
3.4 Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan peta satuan lahan
berdasarkan kemiringan lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Lampung
Universitas Lampung hasil pengukuran Banuwa, Syam, dan Wiharso, (2011)
dalam Zulkarnain (2012).
Kemiringan lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Lampung Universitas
Lampung terbagi menjadi 5 kelas kemiringan yaitu datar, landai, bergelombang,
berbukit, dan agak curam.
a. Infiltrasi
Infiltrasi di ukur menggunakan Double Ring Infilrometer. Pengukuran dilakukan
satu kali di masing-masing kelas kemiringan lereng.
1. Double ring dimasukkan ke dalam tanah sampai sedalam separuh tinggi alat,
dengan kedudukan diusahakan tegak lurus serta tanah dalam silinder dijaga
20
21
2. Sebelum penuangan air pada silinder tengah, maka silinder luar diisi air
terlebih dahulu supaya perembesan ke arah luar terkurangi, ring tengah harus
selalu terisi air saat pengamatan.
3. Setelah air diisikan ke dalam ring tengah sampai ketinggian tertentu lalu
dibaca skala penurunan air setiap 2 menit sampai penurunan air dalam silinder
konstan.
4. Hal tersebut dilakukan juga terhadap titik-titik pengukuran infiltrasi lainnya.
b. Curah Hujan
Data curah hujan menggunakan data yang diambil dari hasil pengamatan di
laboratorium lapang terpadu Fakiltas Pertanian Universitas Lampung.
c. Laju Aliran Air
Menentukan lokasi daerah pengukuran
1. Memasang pasak 1 disebelah kiri saluran, kemudian tegak lurus ke arah
seberang, pasak no. 2.
2. Menghubungkan antara pasak no. 1 dengan pasak no. 2 menggunakan tali
rafia. (sebagai batas daerah pengukur I)
3. Memasang pasak no. 3 dan no. 4. Menghubungkan antara pasak no. 3
dan pasak no. 4 dengan tali rafia (sebagai batas daerah pengukur II)
4. Jarak I dan II = (D) dalam satuan meter
Menentukan kecepatan aliran air (V)
1. Memastikan semua peralatan dengan kondisi baik dan siap
22
2. Memulai dengan menghanyutkan bola pimpong dengan jarak 5
meter dari batas pengukuran I ke arah hulu saluran.
3. Menghidupkan stopwatch saat bola pimpong tepat berada di bawah
tali batas daerah penampang I.
4. Mematikan stopwatch sesaat bola pimpong telah mencapai tepat di
bawah tali batas daerah penampung II.
5. Mencatat waktu untuk menempuh jarak dari daerah penampang I ke
daerah penampang II (t).
6. Menghitung kecepatan aliran air dengan menggunakan rumus
Keterangan :
V = kecepatan aliran air sungai (m/detik)
D = jarak antara daerah penampang I dengan II (meter)
t = waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak (detik)
[image:41.612.202.441.498.631.2] Menentukan luas penampang basah saluran (A)
Gambar 2. Pengukuran luas penampang
1. Menentukan lebar saluran (I) pada daerah penampang.
23
2. Mengukur kedalaman air (d) pada daerah penampang I kemudian
diulangi hingga lima tempat (d1, d2, d3, d4, d5)
3. Menentukan rata-rata dalam air (d) pada daerah penampang I
4. menghitung luas penampang basah dengan menggunakan rumus :
keterangan :
A= luas penampang basah (m2)
I= lebar saluran (meter)
d = kedalaman air rata-rata (meter)
Menghitung debit aliran air
Keterangan :
Q = debit air yang mengalir (m3/detik)
V= kecepatan aliran air (m/detik)
A= Luas penampang basah (m2)
Pengukuran debit aliran air ini dilakukan satu kali dalam sehari selama 7 kali di
tempat yang sama. Setiap pengukuran dilakukan 3 kali ulangan.
e. C-organik
Pada masing-masing kelas kemiringan lereng sampel tanah diambil pada
kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm, setelah itu sampel tanah di analisis di
Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk
mengetahui kandungan C-organiknya.
A = I x d ………...(3)
24
[image:43.612.244.384.121.405.2]Diagram alir penelitian disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
Penentuan titik pengambilan pengambilan sample
Pengambilan data Curah hujan Infiltrasi Laju aliran air C-organik
Mulai
Analisis data
1
. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1. Kemiringan lereng dan vegetasi berkaitan dengan dinamika air permukaan di
Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Dinamika air permukaan juga dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi.
2. Ada penurunan kandungan C-organik di Laboratorium Lapang Terpadu
Fakultas Pertanian Universitas Lampug dari tahun 2012 ke tahun 2014.
3. Faktor vegetasi mempengaruhi kandungan C-organik di Laboratorium Lapang
Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
5.2 Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan interval satu tahun untuk terus
memantau dinamika air permukaan dan kandungan karbon organik di
Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Disarankan untuk melakukan pengukuran Infiltrasi pada tanah yang belum
tergangu.
3. Perlu dilakukan penambahan bahan organik untuk meningkatkan kandungan
52
DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. 2011. Buku Ajar Hidrologi Teknik. Universitas Hasanuddin. Makasar. 127 hal
Arifin, M. 2010. Kajian Sifat Fisik Tanah dan Berbagai Penggunaan Lahan
dalam Hubungannya dengan Pendugaan Erosi Tanah. Jurnal
Pertanian MAPETA. Vol. 12. No. 2 : 111 – 115
Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 571 hal
Asmaranto, A., E. Suhartanto., B. S. Permana. 2009. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Identifikasi Lahan Kritis dan Arahan Fungsi Lahan Daerah Aliran Sungai Sampean. Jurusan Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Malang .
Astari, D. 2004. Model Hujan-Limpasan di Daerah Permeable dan Impermeable dengan Peubah Kemiringan Lahan. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Fauzi. A. 2008. Analisa kadar unsur hara karbon organik dan nitrogen di dalam tanah perkebunan kelapa sawit bengkalis riau. Tugas Akhir Program Studi D3Kimia Analisis. Departemen Kimia. Fakiltas MIPA. Universitas Sumatera Utara. Medan
Intara, T. I., A. Sapei., Erizal., N. Sembiring., M. H. B. Djoefrie. 2011. Pengaruh pemberian bahan organik pada tanah liat dan lempung berliat terhadap kemampuan mengikat air. Jurnal Iimu Pertanian Indonesia. Vol. 16 NO. 2 : 130-135
Katonsasongko. 2013. Bahan Organik Tanah. Universitas Gajah Mada. Diakses 26 Maret 2013. Pkl 10.00 WIB
Maro’ah, S. 2011. Kajian Laju Infiltrasi dan Permeabilitas Tanah pada Beberapa Model Tanaman. Skripsi Program Studi Ulmu Tanah. Fakultas
53
Monde. A., N. Sunukaban., K. Murtilaksono., N. Pandjaitan. 2008. Dinamika Karbon (c) Akibat Alih Guna Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian.
Jurnal Agroland. Vol. 15. No. 1 : 22 – 26
Monde. A. 2009. Degradasi Stok Karbon (C) Akibat Alih Guna Lahan Hutan Menjadi Lahan Kakao Di Das Nopu, Sulawesi Tengah. Jurnal Agroland. Vol. 16. No. 2 : 110 – 117
Notohadiprawito, T. 2006. Tanah dan Lingkungan. Repro Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
Nursa’ban, M. 2006. Pengendalian Erosi Tanah Sebagai Upaya Melestarikan Kemampuan Fungsi Lingkungan. Geomedia. Vol. 4. No. 2 : 93 – 116
Oktavia, D. 2006. Perubahan Karbon Organik Dan Nitrogen Total Tanah Akibat Perlakuan Pupuk Organik Pada Budidaya Sayuran Organik. Skripsi Departemen Kimia. Fakultas MIPA. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Purba, M., P. 2009. Besaran Aliran Permukaan (run-off) pada Berbagai Tipe Kelerengan Dibawah Tegakan Eucaliptus spp (Studi kasus di HPHTI PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. Sektor Aek Nauli). Skripsi Departemen Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan
Sabaruddin. S. N. A. Fitri., L. Lestari. 2009. Hubungan antara kandungan bahan organik tanah dengan periode pasca tebang tanaman HTI acacia mangium Willd. Jurnal Tanah Trop. Vol. 14. No. 2 : 105 – 110
Santosa, D. 2013. Pengertian dan Faktor Infiltrasi.
http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertian-dan-faktor-infiltrasi.html. Diakses tanggal 27 April 2014 pukul 09:18 WIB.
Saribun, D. S. 2007. Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Kemiringan Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-das Cikapundung Hulu. Skripsi Jurusan Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Universitas Padjadjaran. Jatinangor
Seyhan, E. 1977. Dasar-dasar Hidrologi. Gajah Mada University Press. Jogjakarta. 380 hal
Slamet, B. 2011. Model Hidrologi Daerah Aliran Sungai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Domestik. http://pemodelanku.blogspot.com/2011/06/ model-hidrologi-daerah-aliran-sungai.html. Diakses tanggal 29 April 2014 pukul 15:26 WIB.
54
Sudarmanto, A., I. Buchori., Sudarno. 2013. Analisis Kemampuan Infiltrasi Lahan BerdasarkanKondisi Hidrometeorologis dan Karakteristik Fisik DAS Pada Sub DAS Kreo Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. UNDIP. Semarang
Sugiono. 2007. Enaluasi Status Hara N, P, K Dan C-Organik yang Terangkut Erosi Akibat Penerapan Berbagai Terknik Mulsa Vertikal Di Lahan Miring pada Pertanaman Jeruk (Citrus Sinensis) di Desa Rumah Galuh
Kecamatan Sei Bengei Kabupaten Langkat. Skripsi Departemen Ilmu
Tanah. Fakultas Pertanian. USU. Medan
Supriadi, S. 2008. Kandungan Bahan Organik Sebagai Dasar Pengolahan Tanah Di Lahan Kering Madura. Embryo Vol. 5 No. 2. 176 – 183
Wibowo, A. T., D. Panalosa., A. Firmansyah., Arifin., I. K. A. PWijaya., H. Candra., M. Suito., N. Septiando. 2014. Mengukur Laju Infiltrasi. Laporan praktikum hidrologi (tidak di publikasikan). Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung