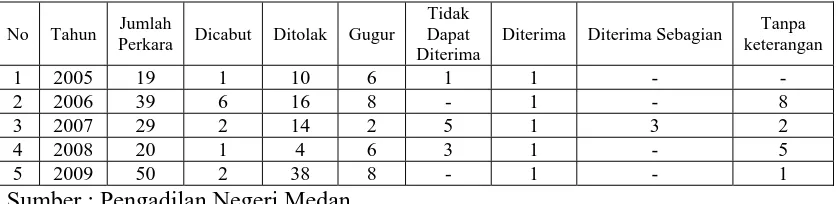EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
TESIS
Oleh
WESSY TRISNA 087005084 / Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana
Oleh
WESSY TRISNA 087005084 / Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
Judul Tesis : EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
Nama Mahasiswa : Wessy Trisna Nomor Pokok : 087005084 Program Studi : Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Ketua
(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum) (Dr. Marlina, SH, M.Hum)
Anggota Anggota
Ketua Program Dekan
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)
Telah Diuji
Pada tanggal : 29 September 2010
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS
Anggota : Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum Dr. Marlina, SH, M.Hum
ABSTRAK
Lembaga praperadilan merupakan salah satu lembaga yang diperkenalkan oleh KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, fungsi pengawasan lembaga yang diberikan undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahannya bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana dan bagaimana faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan serta bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dan pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu: Substansi Hukum (Legal Substance), Struktur Hukum (Legal structure) dan Kultur Hukum (Legal Culture). Analisis putusan praperadilan di dalam praktek hukum perkara pidana yaitu berupa isi putusan hakim yang memutuskan bahwa putusan praperadilan ditolak atau diterima, dari analisis tersebut putusan praperadilan yang ditolak pada hakekatnya pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan tuntutannya sedangkan putusan yang diterima berupa penyidik harus membebaskan tersangka dari tahanan dan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
ABSTRACT
Pretrial institution is one of the institutions introduced by the Indonesian Criminal Codes in law reinforcement neither as an independent trial institution nor as a court-level institution with an authority to make a final decision for a criminal case. A pretrial institution which functions to control the implementation of force attempt as given by the legislation cannot run smoothly because of existing constraints. Based on the background above, the research questions to be answered in this study were how the legislation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is regulated, the factors that fail the applicant who applied for a pretrial in the legal process of criminal case in Medan Court of First Instance and how the decision of pretrial was analyzed in legal practice.
This study employed normative legal research method and the data for this study were qualitatively obtained through observation and each of the data obtained was related to the existing stipulations or legal principles.
Legal regulation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is stated in Article 1 (10) in connection with Article 77 of Law No. 8/1981 and the basic law for the pretrial is regulated in Article 9 of Law No.48/2009 on Main Stipulation on Judicial Authority. The factors causing the failure of the applicant who applies for a pretrial in legal process of criminal case in Medan Court of First Instance can be seen from 3 (three) components: Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture. The analysis of the pretrial decision in the legal practice of criminal case is in the form of judge’s decision that determines whether the pretrial decision is rejected or accepted. Based on the analysis, the rejected pretrial decision usually occurs because the applicant failed to prove the argumentations of the demand he/she applied while the accepted pretrial decision will say that the investigator must release the suspect from the prison and the investigation and indictment on the suspect must be continued because the closing of investigation and indictment is illegal.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat
dan hidayah-Nya, tesis ini telah selesai penulis susun dengan baik.
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar
Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
Adapun judul tesis ini adalah: ”EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM
PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
MEDAN”. Penulis menyadari bahwa mulai dari persiapan sampai penulisan tesis ini
penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah membimbing,
mengarahkan, memberi dorongan semangat dan sumbangan pemikiran lain yang
sangat berharga kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih
yang sebanyak-banyaknya kepada yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin,
SH., MS, Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum., dan Ibu Dr. Marlina, SH.,
M.Hum, selaku komisi pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan
dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada yang terhormat dan terpelajar
Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, dan Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH,
MH, DFM, yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif
dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai tahap ujian
Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, M.Sc (CTM), Sp.A (K), selaku Rektor
Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada
kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu
Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Pada bapak dan Ibu Guru Besar serta Dosen Pengajar pada Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah
mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Ilmu Hukum.
6. Orang tua tercinta Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum dan Jasmi Riva’i ,SH., yang
senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, do’a, cinta, pengertian dan
membimbing serta menyediakan segala kebutuhan penulis.
7. Kepada abangda, kakanda, dan adik penulis yakni dr. Raufen Rissyamdani, Serli
Dwi Warmi, SH, MKn. dan Ahmad Fadli, yang telah membantu dan memberikan
8. Teristimewa kepada Joko Santoso, yang telah memberikan kasih sayang,
dorongan, semangat dan do’a kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Adi Mansyar, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
10.Kepada Tek Rat, Tek Ema, Devi serta seluruh staf Law Office Ediwarman &
Associates, yang telah memberikan semangat dan doa serta perhatian kepada
penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11.Para sahabat yang berbaik hati, yaitu Serenity, Mala, Kak Umi, Kak Mia, bu
Saniah, Rini, Nancy, bang syaiful, bang angkat, Pak nur, bang James, bang Jaka,
dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
banyak memberikan support kepada penulis selama masa pendidikan.
12.Para pegawai/karyawan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa tesis ini
tidak luput dari ketidak sempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik ALLAH
SWT semata. Namun demikian besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat
khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin ya Robbal Alamin.
Medan, September 2010 Penulis,
RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
Nama Lengkap : Wessy Trisna
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 23 Januari 1986
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Kota Baru II No. 44 Medan
II. PENDIDIKAN
- SD : Tahun 1992 s/d 1998
SD Perguruan Nasional Khalsa – Medan
- SLTP : Tahun 1998 s/d 2001
SLTP Swasta Harapan – Medan
- SMU : Tahun 2001 s/d 2004
SMU Swasta Harapan – Medan
- Perguruan Tinggi/S1 : Tahun 2004 s/d 2008
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK... . i
ABSTRACT... ii
KATA PENGANTAR... iii
RIWAYAT HIDUP... vi
DAFTAR ISI... vii
BAB I PENDAHULUAN... 1
A. Latar Belakang... 1
B. Perumusan Masalah... 10
C. Tujuan Penelitian... 11
D. Manfaat Penelitian... 11
E. Keaslian Penelitian... 11
F. Kerangka Teori dan Konsep... 12
1. Kerangka Teori... 12
2. Kerangka Konsepsi... 22
G. Metode Penelitian ... 24
1. Spesifikasi Penelitian ... 24
2. Metode Pendekatan ... 24
3. Sumber Data... 25
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ... 25
BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG
PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM
PERKARA PIDANA... 27
A. Sejarah Pengaturan Praperadilan... 27
B. Praperadilan Menurut HIR... 31
C. Praperadilan Menurut KUHAP... 32
D. Praperadilan Menurut RUU KUHAP... 59
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEMOHON PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN... 73
A. Substansi Hukum (Legal Substance)... 73
B. Struktur Hukum (Legal Sutructure)... 80
C. Kultur Hukum (Legal Culture)... 89
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PRAKTEK HUKUM PERKARA PIDANA... 95
A. Analisis Putusan Kasus Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan... 95
B. Putusan Praperadilan Ditolak... 110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 119
A. Kesimpulan... 119
B. Saran... 121
ABSTRAK
Lembaga praperadilan merupakan salah satu lembaga yang diperkenalkan oleh KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, fungsi pengawasan lembaga yang diberikan undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahannya bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana dan bagaimana faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan serta bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dan pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu: Substansi Hukum (Legal Substance), Struktur Hukum (Legal structure) dan Kultur Hukum (Legal Culture). Analisis putusan praperadilan di dalam praktek hukum perkara pidana yaitu berupa isi putusan hakim yang memutuskan bahwa putusan praperadilan ditolak atau diterima, dari analisis tersebut putusan praperadilan yang ditolak pada hakekatnya pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan tuntutannya sedangkan putusan yang diterima berupa penyidik harus membebaskan tersangka dari tahanan dan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
ABSTRACT
Pretrial institution is one of the institutions introduced by the Indonesian Criminal Codes in law reinforcement neither as an independent trial institution nor as a court-level institution with an authority to make a final decision for a criminal case. A pretrial institution which functions to control the implementation of force attempt as given by the legislation cannot run smoothly because of existing constraints. Based on the background above, the research questions to be answered in this study were how the legislation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is regulated, the factors that fail the applicant who applied for a pretrial in the legal process of criminal case in Medan Court of First Instance and how the decision of pretrial was analyzed in legal practice.
This study employed normative legal research method and the data for this study were qualitatively obtained through observation and each of the data obtained was related to the existing stipulations or legal principles.
Legal regulation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is stated in Article 1 (10) in connection with Article 77 of Law No. 8/1981 and the basic law for the pretrial is regulated in Article 9 of Law No.48/2009 on Main Stipulation on Judicial Authority. The factors causing the failure of the applicant who applies for a pretrial in legal process of criminal case in Medan Court of First Instance can be seen from 3 (three) components: Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture. The analysis of the pretrial decision in the legal practice of criminal case is in the form of judge’s decision that determines whether the pretrial decision is rejected or accepted. Based on the analysis, the rejected pretrial decision usually occurs because the applicant failed to prove the argumentations of the demand he/she applied while the accepted pretrial decision will say that the investigator must release the suspect from the prison and the investigation and indictment on the suspect must be continued because the closing of investigation and indictment is illegal.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut.
Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di
pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan
perundang-undangan. Dengan demikian, Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud
perundang-undangan.1
Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 bahwa di dalam negara kesatuan RI, hukum merupakan urat nadi seluruh
aspek kehidupan, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya
jaminan kedudukan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum, tidak terkecuali juga kepada
tersangka/terdakwa.
Seorang tersangka/terdakwa berhak atas perlakuan yang wajar dan adil
terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya, maka dari itu segala tindakan para
penegak hukum harus berdasarkan kepada hukum bukan kekuasaan.
Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus
mempengaruhi, karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung
1
terus menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia,
keyakinan agama, sosial, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban
dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontrasi dengan
kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang
berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata
manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.2
Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan
masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan
dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.
Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat
terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu
harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur harus dipenuhi yaitu
: Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zwechmaasigheit), Keadilan
(Gerechetigheit)3.
Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya
hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak
dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat justitia et pereat
mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan
oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel
2
Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), halaman 2-3.
3
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum
masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena
bertujuan ketertiban masyarakat.
Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau
penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau
penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum
tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang,
bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang
yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.
Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan
nilai kegunaan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat
berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai
kegunaan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum
itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang
merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kegunaan merupakan suatu
kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan
hukum.4
Hukum hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman begitu
juga dengan sistem peradilan kita. Sistem peradilan kita dapat ditinjau dari beberapa
segi, yaitu:5 Pertama; Segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan,
mencakup seperti kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan
lain-lain, Kedua; Sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa
dan memutus perkara). Sebagai sebuah sistem, peradilan meliputi proses
kelembagaan, ketenagaan yang bekerja mempertahankan dan menegakkan hukum
secara pro justitia (mempertahankan dan menegakkan hukum dapat juga dilakukan
secara non justitia).6
Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan
kejahatan dengan tujuan untuk7 :
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.
4
Sacjipto Raharjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 20.
5
Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), halaman 14
6
Ibid, halaman 57.
7
Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan
ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan
berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. 8 Dalam hal pemeriksaan perkara
pidana umumnya berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, tidak sederhana seperti
disebutkan aturan-aturan normatif/formal (KUHAP).9
Sistem peradilan pidana merujuk pada suatu konsep hukum dari ketentuan
normatif suatu perundang-undangan. Hukum acara pidana adalah ketentuan normatif
sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa
kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan
sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik.10
Mekanisme terhadap sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP ada
terdapat lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan ini dimaksudkan untuk
pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional
dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Lembaga praperadilan ini dimasukkan
sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara.11
Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang
mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari rumusan
Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah
8
Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, (Bandung: Refika Aditama, 2004), halaman 1
9
Ibid, halaman 5.
10
Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2008), halaman 1.
11
wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada
pengadilan negeri).12 Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum merupakan salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan mempunyai tugas dan
wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana
dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).
Praperadilan dalam perwujutannya tetap satu dan berada pada Pengadilan
Negeri baik organisatoris maupun administratif, personal, material, dan finansial
berada dalam tubuh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Praperadilan ini tunduk
dan berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedudukannya
pun berada dan bersatu dengan pengadilan Negeri setempat.
Di Indonesia, lembaga praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal
1 butir 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yang pada pokoknya tujuan dasar dari
praperadilan adalah satu cerminan pelaksanaan dari asas presumption of innocent
(praduga tidak bersalah) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah
melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat
manusianya.13 Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah
melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparatur penyidik secara sah
menurut undang-undang atau satu penahanan dan atau penangkapan yang
mengandung cacat.
12
HMA KUFFAL, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), halaman 252.
13
Subyek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Objek
praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang
berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu
untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan
secara horizontal.14
Fungsi dan peranan peradilan di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model Het Herziene Inlandsch
Reglement (HIR) yang diberlakukan sejak tahun 1941-1942. HIR harus dapat
memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya,
dimana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti
lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan
penyalahgunaan wewenang pemeriksaan dalam beberapa kasus tindak pidana.15
Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan
keadilan dan menaruh harapan. Namun, realitanya jauh dari harapan. Justru,
pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat
dari keadilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan keadilanpun pupus ketika
ditemukan adanya permainan sistematis yang diperankan oleh segerombolan orang
yang bernama mafia peradilan. Maka dari itu untuk memperoleh lembaga peradilan
14
Irma Hermawati, ”Sekilas tentang praperadilan”, http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.htm, diakses tanggal 20 April 2010.
15
yang baik, diperlukan pendekatan terpadu (integrated justice system) dan
kemandirian Mahkamah Agung sebagai peradilan 1 (satu) atap, juga mesti
memperhatikan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat, seperti nilai ketuhanan,
keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodrenan, musyawarah,
perlindungan hak asasi dan sebagainya. Sehingga lembaga peradilan tersebut dapat
sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.16
Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan, dan ia
berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah yaitu
tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka
tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan yaitu penasehat
hukumnya, dapat mengajukan keberatan pada pengadilan negeri melalui praperadilan
untuk meminta putusan hakim mengenai sah/tidaknya penangkapan/penahanan atas
dirinya. Suatu penahanan dan atau penangkapan yang tidak sah oleh aparatur
penyidik berkonsekuensi seorang tersangka dapat menuntut ganti kerugian atau
merehabilitasi namanya.
Realitas yang demikian dapat dilihat antara lain terhadap tiga orang dokter
yang mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait
penahanan ketiganya atas tuduhan dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di
Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Adapun yang mendasari sah tidaknya penahanan
ketiganya yaitu Pertama, bahwa tidak didasari bukti yang cukup karena Kejaksaan
16
melakukan penahanan tanggal 16 November 2009, Sedangkan pihak kejaksaan baru
mendapatkan bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penahanan tanggal 2 Desember
2009 sesuai berita acara penyitaan tanggal 2 Desember 2009. Kedua, bahwa selain
penahanan dinilai tidak sah, juga penyitaan pada tanggal 2 Desember 2009 yang
dilakukan Kejaksaan merupakan pelanggaran terhadap KUHAP, Sebab termohon
mengajukan persetujuan penyitaan kepada ketua PN Kabanjahe tanggal 24 November
2009 sebelum penyitaan dilakukan.17
Lembaga praperadilan walaupun berfungsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan upaya paksa, namun fungsi pengawasan lembaga yang diberikan
undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena
adanya hambatan-hambatan yang muncul karena maksud dan tujuan pemberlakuan
praperadilan itu tidak tercapai dengan baik dan benar, sehingga hak-hak tersangka
untuk memperoleh perlindungan hukum masih terabaikan. Adapun
hambatan-hambatan yang timbul salah satunya yaitu bolak-baliknya perkara pidana dari
penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum
telah terabaikan; bahkan sering terjadi bolak baliknya perkara pidana dilatarbelakangi
oleh kepentingan pribadi atau kelompok atau politik.
Masyarakat yang mengajukan praperadilan atas sah tidaknya suatu penahanan
atau penangkapan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh
17
aparat penegak hukum jarang sekali menang atau bahkan sampai ke pengadilan. Hal
ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai
pencari keadilan.
Realita ini dapat dilihat dalam beberapa kasus praperadilan dimana hampir
semuanya dimenangkan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan, salah satunya
seperti halnya dalam putusan No. 14/Pra.Pid/2009/PN.Mdn antara Drs. Torkis P.
Siahaan melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait perihal menahan
atau menghentikan berkas perkara secara diam-diam, dimana kasus tersebut
dimenangkan oleh pihak kepolisian. Bukan hanya itu putusan No.
29/Pra.Pid/2007/PN.Mdn antara M. Richard Manik, SH melawan Direktur Narkoba
Polda Sumatera Utara, terkait perihal penagkapan secara paksa dimana tidak adanya
bukti pemula yang cukup serta tidak adanya surat perintah penahanaan serta
penggeledahan dari Pengadilan Negeri.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian
dalam bentuk tesis dengan judul “Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum
Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan”.
B. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses
2. Bagaimana Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam
proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan
3. Bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum perkara pidana.
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam
proses hukum perkara pidana.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam
proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji putusan praperadilan dalam praktek hukum perkara pidana.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di
bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya
hukum pidana.
2. Secara Praktis
Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar yang
dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah
ada.
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada disekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara Khususnya Fakultas Ilmu Hukum, ternyata belum
ditemukan judul mengenai Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum
Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, penulis
berkeyakinan bahwa judul tesis ini dan permasalahan yang diajukan belum pernah
diteliti dan dibahas, sehingga dapat dikatakan asli.
F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,
thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan
perbandingan, pegangan teoritis.18 Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai
beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut19 :
1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan
fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
18
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), halaman 27.
19
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta,
membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui
serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena
telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin
faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada
pengetahuan peneliti.
Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah teori sistem hukum
(Legal System) dan teori sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Dalam
teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum
dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki
sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (legal structure), komponen
substansi hukum (legal substance), dan komponen budaya hukum (legal culture).
Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga
saling berpengaruh satu sama lainnya.20 Ketiga komponen dimaksud, diuraikan
sebagai berikut21 :
1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak
dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga
20
Lawrence M. Friedman, American Law, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), halaman 7.
21
pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk
menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan
penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil
ini dapat terwujud hukum in concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah
hukum in abstracto atau kaidah hukum umum.
3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang
mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini
untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang
sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.
Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu
merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari
bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama
untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap
kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian
hukum.22
Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan
perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah
22
satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) c. Yurisprudensi Tetap (Case Law)
d. Hukum Kebiasaan
e. Konvensi-Konvensi Internasional f. Asas-Asas Hukum Internasional
3. SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum 4. Pranata-Pranata Hukum
5. Lembaga-Lembaga Hukum
6. Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
a. Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
b. Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi) c. Kendaraan
d. Gaji
e. Kesejahteraan pegawai / karyawan
7. Budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.
Dari uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut diatas apabila salah satu unsur
saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem
juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan
membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan,
23
rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan
mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan prilaku hukum masyarakat.
Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara
Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas
unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling
bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa
dipisahkan dari yang lain.24
Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) tidak dapat dipisahkan dari
sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin
dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka
mesin mengalami kepincangan.25 Struktur hukum yang terkait dengan sistem
peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi
polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.
Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun
sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak
berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih,
berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat
mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.
24
Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 39.
25
Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum
merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika
diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.
26
Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana menunjukkan
mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar
pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa:
”criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem
Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian
kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.
27
terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”
28
26
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), halaman 5.
27
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Binacipta, 1996), halaman 14.
28
Adapun ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli
Atmasasmita,29 yaitu:
a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen
peradilan pidana.
c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi
penyelesaian perkara.
d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration
of justice.
Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana yang mengatur tata cara
menegakkan hukum pidana material. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum
pidana material, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang
mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat (yang terpaksa
berurusan pidana) beracara di muka pengadilan.30
Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas presumption
of innocent (praduga tidak bersalah). Asas praduga tidak bersalah yaitu bahwa dalam
proses peradilan pidana tersangka/terdakwa wajib mendapat hak-haknya yaitu setiap
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan
29
Romli Atmasasmita, Op. Cit., halaman 10.
30
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai
seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak
untuk segera mendapat pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapat
pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk
diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang
dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru
bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan
kunjungan keluarganya.31
Seseorang apabila dikenakan penangkapan dan atau penahanan, dan ia
berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah yaitu
tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka
tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan yaitu penasehat
hukumnya, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri melalui
praperadilan untuk meminta putusan hakim mengenai sah/tidaknya
penangkapan/penahanan atas dirinya. Selain itu, pihak pelapor dapat mengajukan
keberatan kepada pengadilan negeri melalui praperadilan, bila perkara tindak pidana
yang dilaporkan dihentikan penyidikan atau penuntutan untuk mendapatkan putusan
hakim mengenai sah/tidaknya penhentian penyidikan atau penuntutan.
Praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan,
31
atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan
dapat dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat
pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan, atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai
akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut
hukum.32
Sejauh ini kita kenal praperadilan sering dilakukan oleh tersangka atau
keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan
gugatan/permohonan praperadilan terhadap pihak kepolisian atau terhadap pihak
kejaksaan ke pengadilan negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan
tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau sah tidaknya
penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun sesungguhnya praperadilan secara
hukum dapat juga dilakukan pihak kepolisian terhadap kejaksaan, begitu juga
sebaliknya, dimana tertuang dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP yang mengatur
tentang praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya
untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun pasal tersebut juga
memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan
memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian.33
32
M. Sofyan Lubis, “Praperadilan Dalam KUHAP”, http://www.Kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=5, diakses tanggal 20 April 2010.
33
Realita yang demikian dapat dilihat antara lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Selatan mempraperadilankan Polda Kalimantan Selatan terkait penangkapan,
penahanan serta penggeledahan atas 0,56 gram sabu-sabu yang semula diamankan
Polda Kalimantan Selatan sebagai barang bukti di pengadilan. Dimana barang bukti
tersebut dibawa pulang ke rumah oleh jaksa mukhyar dengan alasan tidak ada tempat
penitipan barang bukti. Padahal menurut ketentuan, benda sitaan harus disimpan
dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggung jawab atas benda sitaan
tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan, sehingga benda yang menjadi barang bukti tersebut dilarang
dipergunakan oleh siapapun juga dan dengan alasan apapun tidak diperkenankan
disimpan dirumah karena apabila barang bukti tersebut sampai disimpan dirumah
maka yang harus bertanggung jawab adalah instansi Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Selatan.34
Praperadilan juga dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika
suatu perkara telah dinyatakan cukup bukti oleh pihak kejaksaan dan/atau suatu
perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah
jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian
Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat
mempraperadilankan pihak kejaksaan ke pengadilan negeri. Namun, realita yang
demikian jarang sekali terjadi, dimana masing-masing pihak berusaha saling menjaga
34
hubungan baik atas dasar pertimbangan rasa segan sesama aparat dan/atau adanya
rasa saling membutuhkan dalam sistem kerja dan/atau adanya rasa saling
pengertian.35
Apabila kondisi ini dibiarkan terus tanpa adanya upaya untuk memperbaiki
antar sesama penegak hukum agar tercipta budaya saling kontrol, maka hal ini dapat
menganggu upaya penegakan supremasi hukum di negara kita ini.
Dalam era supremasi hukum ini kepolisian harus berani mempraperadilankan
pihak kejaksaan jika suatu perkara yang telah dinyatakan cukup bukti ternyata
perkara tersebut tidak jadi dilimpahkan ke pengadilan, begitu juga sebaliknya,
kejaksaan harus berani mempraperadilankan pihak kepolisian jika secara tiba-tiba
pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Pengehentian Penuntutan)
terhadap suatu perkara yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan
penuntutan.
Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang
pengadilan negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa proses acara praperadilan
bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak
pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan
fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan
memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Dengan
35
demikian, putusan praperadilan walaupun mencakup sah atau tidaknya suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat
digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding.36
Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada pengadilan tinggi. Oleh
karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan
mempunyai karakter sendiri, sebab hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang
sebagai sarana pengawasan secara horizontal demi penegakan hukum, keadilan dan
kebenaran. Sifat ataupun fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik
tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum
seseorang diputus oleh pengadilan, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak
asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung
sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai
dengan aturan main.
2. Kerangka Konsepsi
Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara
konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan
tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk
menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan
dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
36
a. Eksistensi adalah Keberadaan.
b. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan
demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
c. Perkara Pidana adalah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan
pidana.
d. Pengadilan Negeri adalah badan yang berwenang mengadili perkara pada tingkat
pertama.
e. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
f. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta
G. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian mengenai Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara
Pidana Di Pengadilan Negeri Medan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu
lebih menitikberatkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi terdapat peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, apakah telah
sejalan dengan undang-undang atau tidak.
2. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan Kasus (Case Approach),37 dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach),38 dilakukan dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan
menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.
37
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 94.
38
3. Sumber Data
Penelitian ini mempunyai sumber data yang terdiri atas:
a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan.39
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks,
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil
simposium mutahir yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.40
c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya
kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.41
4. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,
dilaksanakan dua tahap penelitian :
a. Studi Kepustakaan.
Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori,
pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok
permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.
39
Jhony Ibrahim, Teori Dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publising, 2006), halaman 295.
40
Ibid
41
b. Studi Lapangan.
Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan
diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab
(wawancara) dengan penegak hukum. Pada wawancara ini yang akan dijadikan
sumber informan akan dipilih dari institusi kepolisian, kejaksaan, hakim pada
wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Lembaga Profesi Advokat, serta pakar
hukum sebagai kelompok masyarakat yang berdasarkan profesi yang terdapat di
Kota Medan.
5. Analisis Data
Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara
kualitatif42 yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan
maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
42
BAB II
PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG
PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM
PERKARA PIDANA
A. Sejarah Pengaturan Praperadilan
Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak
Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan
fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.43 Habeas
Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah
pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya
(polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak
melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun
pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar
telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak
asasi manusia.
Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak
yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung
dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah Habeas
43
Corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam
penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta
wajib menunjukan alasan yang menyebabkan penahanannya”.
Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak
hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana
saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar
hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.44 Dalam
perkembangannya surat perintah Habeas Corpus menjadi salah satu alat pengawasan
serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingakat federal maupun di negara
bagian di Amerika Serikat.
Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspirasi untuk
menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang
yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk
mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan
kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang
diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya.
Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang
44
memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang
dilakukan aparat penegak hukum. 45
Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada
kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga
melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung
saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama
syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.
Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal
77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu:
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan
pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.
Penjabaran Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal
83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam KUHAP,
45
praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pada pokoknya mengatur
sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal
77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak
mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya
paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.
Ada beberapa perbedaan mendasar antara habeas corpus dengan lembaga
praperadilan, yaitu:46
1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa
sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan habeas corpus, hakim yang
memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu
penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa
46
dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas corpus, lebih luas dalam arti
permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus ditujukan kepada
instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.
B. Praperadilan Menurut HIR
Secara historis, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) atau dikenal dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, maka hukum acara pidana
sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (Het Herziene Indonesisch
Reglement) Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa
kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, dimana didalamnya terdapat
beberapa kendala, kelemahan, kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa,
bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian
hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam
proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan,
hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian
dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.
HIR diciptakan dalam suasana kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk
hukum serta perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa sehingga
menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini penjajah. Berhubungan dengan
perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin moderen serta didasari pada
perkembangan era kemerdekaan negara RI, sistem yang dianut HIR dirasakan telah
dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan
unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.47
Pada masa HIR, pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dan
penuntutan sama sekali tidak ada. Pada masa itu yang ada hanya pengawasan oleh
hakim, dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus disetujui
hakim.48 Namun, dalam kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan
manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh
hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi.
C. Praperadilan Menurut KUHAP
Ditinjau dari aspek historis yuridis, Sejak berdirinya Negara Hukum Republik
Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia
adalah hukum acara pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda yang terkenal
dengan nama HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement).
Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai
dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang
merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan
dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara
Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat/constitusional/state) yang
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara
47
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 7.
48
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dirasakan kurang
menghargai hak asasi manusia yang diatur dalam HIR, maka Pemerintah RI
bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan
mencabut HIR dan menggantikannya dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana
dengan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian KUHAP hadir menggantikan Het
Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. 49
Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk
“mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan
penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak
asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam
proses hukum. 50
KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga
diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah
kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri
mereka, dimana merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan
sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau
49
HMA Kuffal, Op.Cit., halaman 253
50
A. Samsan Nganro, Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM,
http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/, diakses
terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun
putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum”
pemeriksaan pengadilan.
Terhadap “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari
tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara
limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap
penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga
mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan
mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan
tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak
melenyapkan kesengsaraan masa lalu.
Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan
oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan
optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan
hukum.
Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut
dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur
lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan
kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang
penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut
umum.51
Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan
bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai
instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas
suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan
eksistensinya: 52
a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri,
dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri
sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang
bersangkutan.
b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun
sejajar dengan pengadilan negeri.
c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan
bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta
pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial
pengadilan negeri itu sendiri.
51
HMA Kuffal, Op.Cit, halaman 253.
52