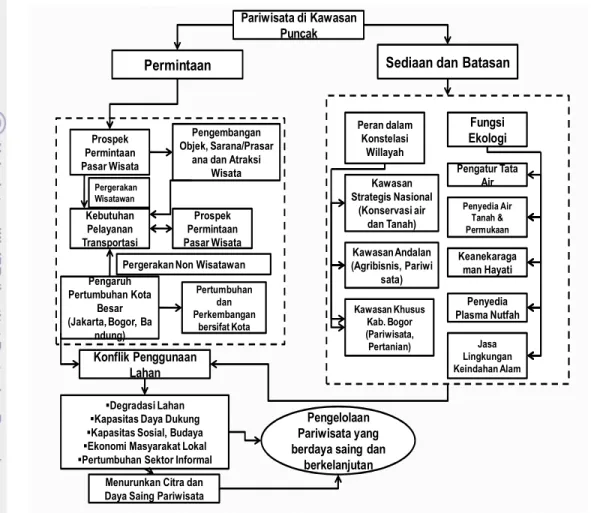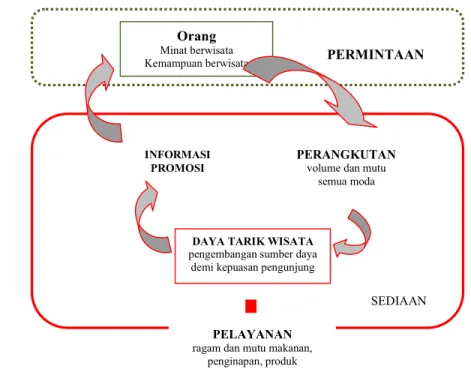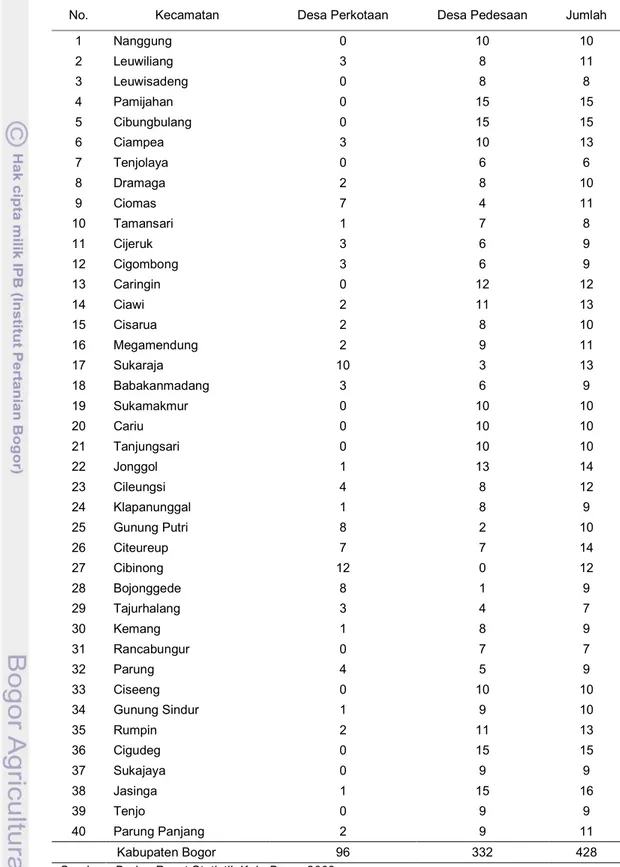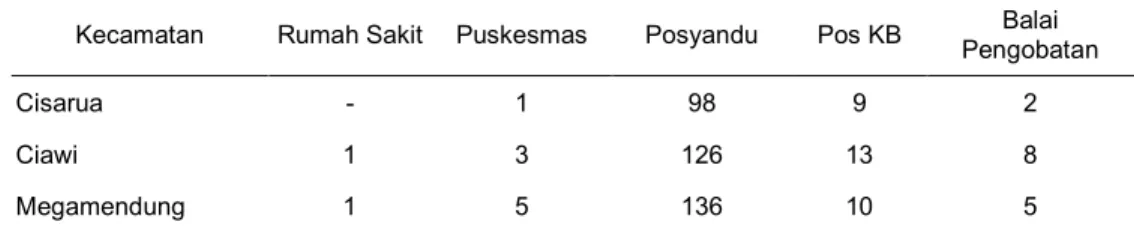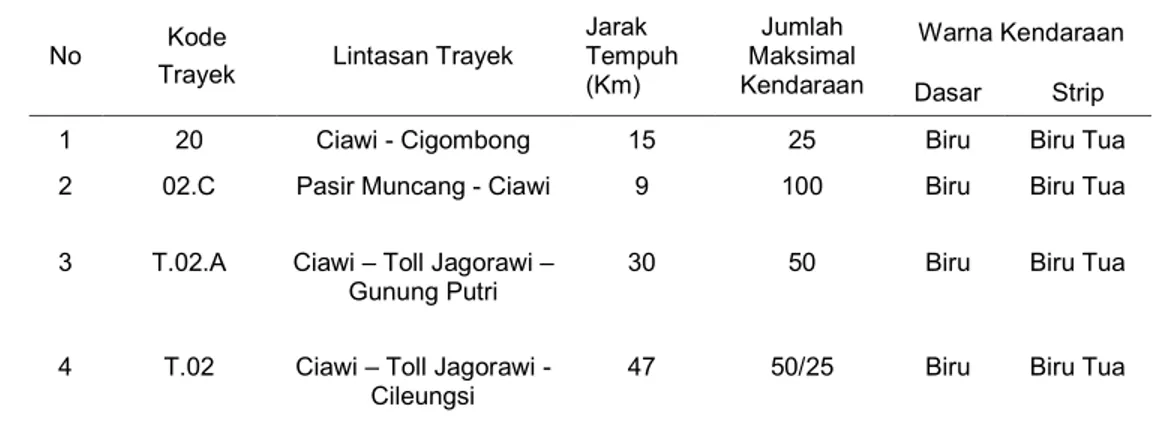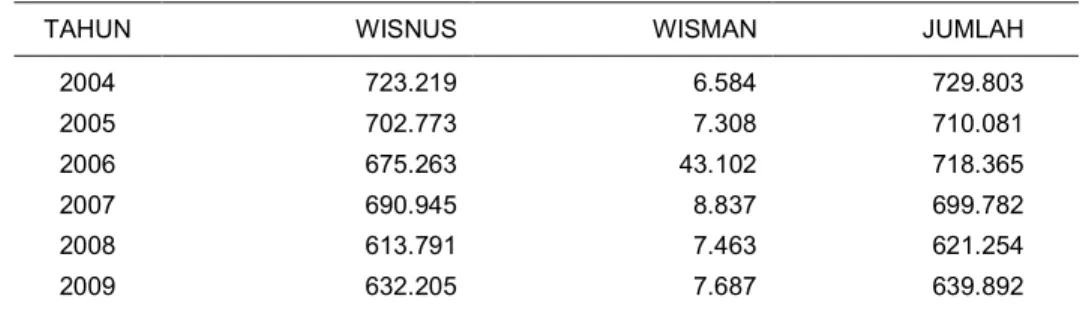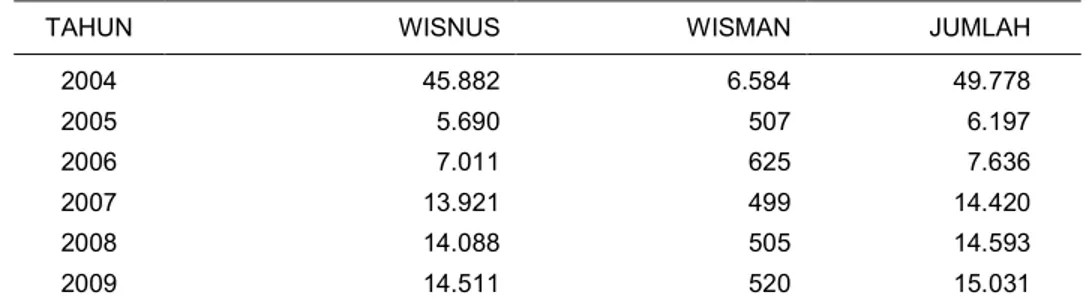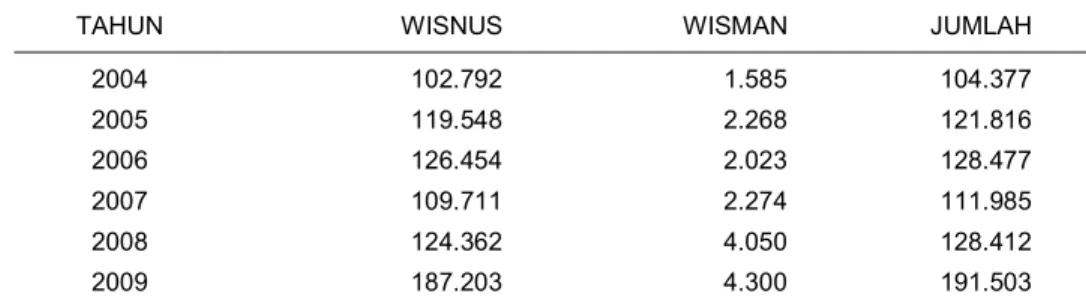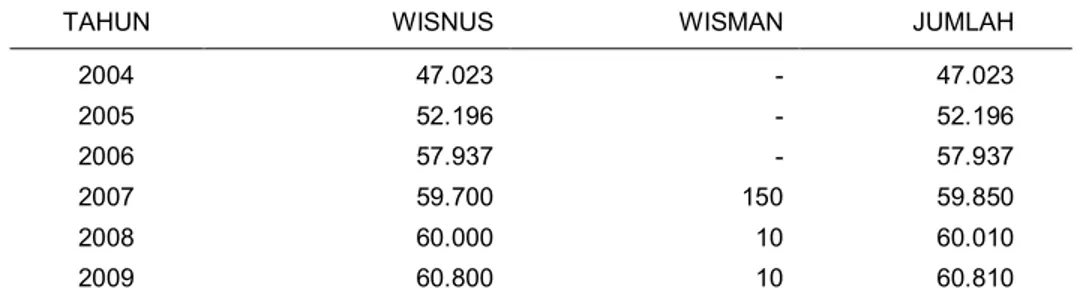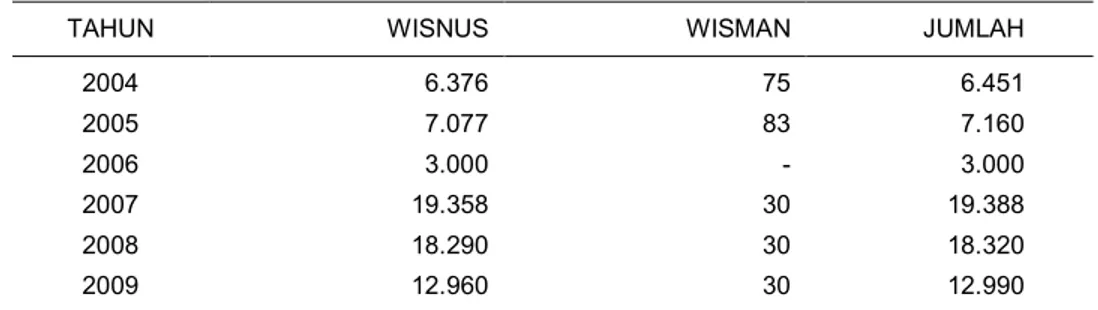* $
*
0 * $ *
* *
3 * 1 * $
*
$
-* $ 1
4 * $ +
* * * $
+ , 5 * 6
4 *
$ + 1 6 * * $
" '7! 6 * * 8 1
, 3 6 * " '9! 8
$ :' &' $ *
: $
3 - * ;1-< = * $ ;,$< + * ;+ < 1
* $ +
* $ *
*
* >
*
-? $
+ ? $
$
7 ?
$ ? " '7! ? 8
? " '9! $ 0
8 ? $
8
? $
? ;255< ? $
5 5
.
;,55<
? $
:' &' ? $
:# 7% :# :7
%& 7& :! ':
!& &: $
$ 1 + A
8 0 ? 0 *
; <
; ! < ! (D +E2
; ! " < 7 9D
*
!""9 !"!9
;#< 1 - * ;1-<
@ ;!< ,$ ;, $ <
@
4 @ ;:< + ;+ <
4
$
? $ !""9
% #'' """
* ,$ +
? $
? $ 88+ #" """ C
#! 7"! #:# +
C $
* +
!"!9 #! ##" 99' 1- ,$
$ ? $
*
? $ ?
# '#% """ !
!""9
% ''( !(% ! 1 *
4
!"!9 9 (7! ":! ! & 'D
? $ ;#!9 &7" """ !<
,$ +
1- 9 !%% 7:9 7 ! 9 !!& %7' !
$ !""9 ? $
#: #7% :((
C $ !"!9
#" &7( &:' 1- ## '!' "&(
,$ ## 79: #:9 + $
? ? $
+ ? $
?
$ $+
#$ ! % & %
& ! % ! & $ & % % % '
' % & ' & ' % % (
) ! % % % & * (
+$
,$ % ! & % ! - &
.
. $ 0 12 32
$ "!% &#)&"(" # %!.&', / " ! , # #) %#) #
$ ( (' 4 56
$& %7% * (! $ &!. !. #)
'8 '8 ' $ %# #, '*
& %
'(98 '8 '8 %'7(#( , % 7 +7(* '8 % &, * 8 ,* $
#))( #))(
&#)& +% *
& % '()' ! %, & # & (" + $: $ '7 # *
"!% &#)&"(" # %!.&', / " !
, # #) %#) #*
'(98 '8 '8 &:& %$! # * '8 '8 +'%" / +* $:8 )'
? $ ?
$
- $
$
# - + $
-0 $
*
! $ - 5 ? ? $ - $
+ 8 ;$ 8< $
: - + $ -$
' $ - $ 2 - 0
- , 2
- 2 ,
( $ ?
: $ -$
% 8 %
&
* 7
$
$
0 + , ; < 0 1 ; < $
- 0 F 0 ?
$ - - $
$ A $ - $ #977
$ #99' ! $ $
+ 8 - $ $ !""&
: $ $ +
8 $ - $
$ $ . #99"
$ $ ; < ?
$ 4 1 $ ?
? ? $ $
? $ ?
- A $ -$ * :( # !"#! +
? $ $ ? $
? - $ .
!"#! + ? $
$ ? $ ?
. G+,-A+0 /A-+0
3-?/,+3+1-. $ $ "%!"&'#('
$ - $ + 8
$ ; :<
$
# $ - $ 2
! - 0
$
# - , 2
Daftar Isi ... i
ii
4.1.1 Aspek Geografis dan Administratif ... 70
4.1.2 Aspek Geomorfologis ... 72
4.1.3 Aspek Klimatologi ... 73
4.1.4 Aspek Demografi dan Sosial Budaya ... 73
4.1.5 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... 77
4.1.6 Aspek Pelayanan Umum ... 78
4.2.10 Kondisi Aksesibiltas dan Transportasi ... 94
4.2.10.1 Aksesibilitas ... 94
4.2.10.2 Transportasi ... 95
4.2.11 Kondisi Obyek Wisata ... 98
... 107
5.1 Analisis Situasi Wisatawan dan Obyek Tujuan Wisata (OTW) ... 106
iii
6.3 Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi ... 147
6.4 Status Keberlanjutan Dimensi Sosial Budaya ... 151
6.5 Status Keberlanjutan Dimensi Sarana Prasarana ... 154
6.6 Analisis Multi Dimensi Satus Keberlanjutan ... 158
... 162
7.1 Metode Analisis Strukturisasi Kelembagaan, Permasalahan, Tujuan dan Aktivitas/Program yang diperlukan di Kawasan Puncak ... 162
7.1.1 Elemen Lembaga yang Terkait dalam Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak ... 164
7.1.2 Elemen Kendala Kelembagaan yang dihadapi dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 170
7.1.3 Elemen Tujuan yang diinginkan dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 176
7.1.4 Elemen Aktivitas/Program yang diharapkan dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 181
7.2 Pembahasan ... 187
... 191
8.1 Peraturan Perundang>Undangan Penataan Ruang dan Pariwisata ... 191
8.2.5 Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama antar Daerah ... 211
9.3.2 Submodel Transportasi dan Akomodasi ... 229
9.3.3 Submodel Fisik Lingkungan ... 232
9.3.4 Submodel Hukum dan Kelembagaan ... 235
9.4. Validasi Model .... ... 238
9.4.1 Uji Validasi Struktur dan kinerja ... 239
9.5 Simulasi Skenario Model Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak ... 241
iv
meningkatkan frekuensi penertiban bangunan liar... . 244
9.5.3 Skenario Alternatif (Alt) :Kebijakan Pengendalian penduduk, Membatasi jumlah kendaraan, Meningkatkan perekonomian wilayah, meningkatkan frekuensi penertiban bangunan tidak berizin, serta internalisasi biaya lingkungan ... 247
9.6 Perbandingan antara Ketiga Skenario ... 247
9.7 Kebijakan dan Pendekatan Program ... 253
9.7.1 Kebijakan Pengendalian Penduduk ... 254
9.7.1.1 Program KB dan Operasi Yustisi ... 255
9.7.1.2 Program Pembatasan Kawasan Permukiman ... 257
9.7.2 Kebijakan Peningkatan Perekonomian Kawasan ... 260
9.7.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja yang Siap Pakai ... 261
9.7.2.2 Peningkatan UKM di Bidang Pertanian dan Industri Rumah tangga (Home Industry) ... 261
9.7.2.3 Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi ... 262
9.7.3 Kebijakan Pengendalian Bangunan Tidak Berizin ... 264
9.7.4 Kebijakan Pembatasan Jumlah Kendaraan ... 265
9.7.5 Pembiayaan Lingkungan Kawasan Puncak ... 269
9.8. Simulasi Peningkatan Nilai Keberlanjutan Multi Dimensi Kawasan Puncak ... 269
... 282
10.1 Kesimpulan ... 282
10.2 Saran ... 283
Daftar Pustaka ... 284
v
Tabel 1. Jumlah bangunan ber>IMB dan tidak ber>IMB ... 4
Tabel 2. Dampak positif dan negatif pariwisata ... 26
Tabel 3. Resiko akibat kegiatan kepariwisataan ... 27
Tabel 4. Prinsip>prinsip panduan kepariwisataan dalam agenda 21 ... 31
Tabel 5. Dimensi dalam pariwisata ... 32
Tabel 6. Jumlah pengunjung di DTW Kawasan Puncak Tahun 2009 ... 37
Tabel 7. Tujuan, jenis data, sumber, metode analisis dan output ... 39
Tabel 8. Parameter, sumber data dan kegunaan ... 43
Tabel 9. % (SSIM) awal elemen ... 53
Tabel 10. Hasil & % (RM) final elemen ... 56
Tabel 11. Elemen dan sub elemen dalam kajian pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 56
Tabel 12. Analisis kebutuhan ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 61 Tabel 13. Uraian komponen sistem kotak gelap (& ' & %) ... 65
Tabel 14. Simbol>simbol diagram alir (Muhammadi $ 2001) ... 67
Tabel 15. Banyaknya desa menurut desa perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bogor Tahun 2008 ... 71
Tabel 16. Pembagian wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan ketinggian tempat ... 72
Tabel 17. Kemiringan lahan di Kabupaten Bogor ... 73
Tabel 18. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2010 ... 76
Tabel 19. Banyaknya sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2007>2008 ... 78
Tabel 20. Luas wilayah di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 84
Tabel 21. Luas DAS yang terdapat di Kawasan Puncak ... 91
Tabel 22. Persentase tutupan lahan Tahun 1992, 1995, 2000 dan 2006 ... 92
Tabel 23. Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Cisarua, Ciawi dan Megamendung ... 93
Tabel 24. Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Cisarua, Ciawi dan Megamendung ... 93
Tabel 25. Panjang jalan di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 97
Tabel 26. Trayek, jurusan, jarak tempuh, jumlah maksimal kendaraan dan warna kendaraan angkutan umum yang melintasi Kawasan Puncak ... 98
Tabel 27. Tipologi jenis dan atraksi wisata Kawasan Puncak ... 99
Tabel 28. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Taman Safari Indonesia Tahun 2004 – 2009 ... 101
Tabel 29. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Telaga Warna Tahun 2004 – 2009 ... 102
vi
Tabel 32. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan
mancanegara ke Objek Wisata Taman Melrimba Tahun
2004 – 2009 ... 104
Tabel 33. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Curug Panjang Tahun 2004 – 2009 ... 104
Tabel 34. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Objek Wisata Taman Wisata Matahari tahun 2004 – 2009 ... 105
Tabel 35. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Taman Wisata Riung Gunung tahun 2004 – 2009 ... 105
Tabel 36. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Objek Wisata Curug Cisuren tahun 2004 – 2009 ... 106
Tabel 37. Jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek tujuan wisata dari tahun 2004 sampai dengan 2009 ... 107
Tabel 38. Rata>rata biaya yang dikeluarkan pengunjung pada kawasan wisata Puncak Bogor (BPTi) ... 112
Tabel 39. Hasil uji parsial (Uji t) frekuensi kunjungan ... 115
Tabel 40. Hasil Pengujian Serentak (Uji>F) pada Frekuensi Kunjungan ... 116
Tabel 41. Hasil pengujian statistik deskriptif ... 116
Tabel 42. Hasil uji multikolinearitas ... 117
Tabel 43. Keputusan uji autokorelasi ... 118
Tabel 44. Hasil uji autokorelasi (n=168, k=5, α=0.05) ... 119
Tabel 45. Hasil uji heteroskedastisitas ... 119
Tabel 46. Perbandingan daya saing antara Kawasan Pariwisata Puncak dan Lembang ... 121
Tabel 47. Daya dukung fisik (PCC) untuk kendaraan dan wisatawan berdasarkan lokasi objek tujuan wisata di Kawasan Puncak ... 128
Tabel 48. Curah hujan dan Hari hujan di Kawasan Puncak ... 130
Tabel 49. Faktor koreksi curah hujan di lokasi objek wisata tahun 2009 ... 131
Tabel 50. Kondisi PCC dan RCC pada setiap lokasi objek tempat wisata ... 131
Tabel 51. Kondisi PCC, RCC, ECC dan kunjungan wisatawan pada setiap lokasi objek tempat wisata ... 132
Tabel 52. Luas dan presentase Lahan Kritis di Kecamatan Ciawi,Cisarua dan Megamendung ... 146
Tabel 53. Bencana Longsor di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 146
Tabel 54. Luas Kerentanan Tanah di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 147
Tabel 55. Rasio KUKM berdasarkan data KUKM (Koperasi, UMKM dan IKM) dan jumlah penduduk ... 149
vii
Tabel 59. Jumlah Fasilitas Peribadatan Kecamatan Ciawi, Cisarua,
Megamendung Tahun 2009 ... 158
Tabel 60. Nilai indeks keberlanjutan kawasan puncak Kabupaten Bogor tahun 2010 ... 158
Tabel 61. Perbedaan nilai indeks keberlanjutan analisis dengan analisis Rap>Tourism Kawasan Puncak ... 159
Tabel 62. Hasil Analisis RAP>TOURISM untuk nilai dan koefisien determinasi (R2) ... 160
Tabel 63. Faktor pengungkit per>dimensi keberlanjutan Kawasan Puncak ... 161
Tabel 64. Matriks jawaban pakar untuk elemen lembaga yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 165
Tabel 65. & matriks elemen lembaga yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 165
Tabel 66. Matriks jawaban pakar untuk elemen kendala yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 170
Tabel 67. Matriks & elemen kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 171
Tabel 68. Elemen Tujuan yang diinginkan dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 177
Tabel 69. Matriks jawaban pakar untuk elemen tujuan yang diinginkan yang terkait dengan pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 177
Tabel 70. Matriks & elemen tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 178
Tabel 71. Elemen aktivitas/program yang diharapkan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 182
Tabel 72. Matriks Jawaban Pakar untuk Elemen Aktivitas/Program yang Diharapkan yang Terkait dengan Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak ... 182
Tabel 73. Matriks & elemen aktivitas/program yang diharapkan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 183
TabeI 74. Identifikasi hierarki dan klasifikasi subelemen pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. ... 188
Tabel 75. Peraturan berkaitan dengan penataan Kawasan Puncak ... 192
Tabel 76. Peraturan Perundang>undangan berdasarkan tujuan dan pokok>pokok yang diatur ... 196
Tabel 77. Aspek kunci pada berbagai peraturan perundang> undangan ... 199
Tabel 78. Aspek kunci kelembagaan dan koodinasi pada peraturan perundang>undangan ... 209
Tabel 79. Perbandingan Pengendalian dan Pemberian Perizinan di Kawasan Puncak berdasarkan UU 26/2007 dan Perpres 54/2008 ... 215
Tabel 80. Keterkaitan tujuan, alat analisis dan hasil analisis dengan rumusan black box ... 216
Tabel 81. Simulasi sub model penduduk ... 228
Tabel 82. Simulasi sub model transportasi dan akomodasi ... 231
viii
Tabel 86. Data validasi model berdasarkan perubahan jumlah
kendaraan... 241 Tabel 87. Hubungan antara Output dalam Black Box dan Pemilihan
Skenario ... 243 Tabel 88. Perbandingan berdasarkan skenario TI, RP dan Alt pada
tahun 2009 dan 2029 ... 248 Tabel 89. Rekomendasi kebijakan dan program pengelolaan
ix
Gambar 1. Kerangka pemikiran pengelolaan pariwisata yang
berdaya saing dan berkelanjutan di Kawasan Puncak
Kabupaten Bogor ... 5
Gambar 2. Perumusan masalah penelitian ... 7
Gambar 3. Model komponen fungsional kunci yang membentuk dinamika dan sistem hubungan kepariwisataan ... 14
Gambar 4. Indeks daya saing pariwisata (Gooroochurn dan Sugiyarto 2004). ... 20
Gambar 5 Peta wilayah penelitian ... 35
Gambar 6. Ilustrasi penentuan indeks keberlanjutan pengembangan kawasan pariwisata dalam skala ordinasi ... 49
Gambar 7. Ilustrasi indeks keberlanjutan setiap dimensi ... 50
Gambar 8. Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor ... 55
Gambar 9. Tahapan analisis sistem (Eriyatno 1999) ... 59
Gambar 10. Tahapan penelitian dan metode analisis ... 69
Gambar 11. ( ) (pintu masuk) ke Kawasan Puncak ... 95
Gambar 12. Prosentase wisatawan berdasarkan daerah asal ... 109
Gambar 13. Prosentase alasan wisatawan mengunjungi objek tujuan wisata di Kawasan Puncak ... 109
Gambar 14. Prosentase keluhan wisatawan di Kawasan Puncak ... 110
Gambar 15. Prosentase saran wisatawan untuk perbaikan kinerja pariwisata Kawasan Puncak ... 110
Gambar 16. Prosentase usulan penanganan kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak ... 111
Gambar 17. Prosentase biaya yang dikeluarkan pengunjung pada kawasan wisata puncak Bogor ... 112
Gambar 18 Perbandingan biaya yang dikeluarkan pengunjung pada kawasan wisata Puncak Bogor ... 113
Gambar 19. Grafik uji normalitas untuk model frekuensi kunjungan ... 117
Gambar 20. Bagan keputusan uji autokorelasi ... 118
Gambar 21. Kondisi perbandingan antara, RCC dan kunjungan wisatawan pada setiap lokasi objek tempat wisata ... 133
Gambar 22. Kondisi perbandingan antara, ECC dan kunjungan ... 133
Gambar 23. Indeks keberlanjutan dimensi hukum dan kelembagaan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 140
Gambar 24. Atribut pengungkit dimensi hukum dan kelembagaan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 142
Gambar 25. Indeks keberlanjutan dimensi ekologi kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 143
Gambar 26. Atribut pengungkit dimensi ekologi di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 144
Gambar 27. Indeks keberlanjutan dimensi ekonomi kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 148
Gambar 28. Atribut pengungkit dimensi ekonomi di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 150
x
Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 154 Gambar 32 Atribut pengungkit dimensi sarana prasarana
pariwisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 155 Gambar 33. Diagram layang>layang nilai keberlanjutan kawasan
Puncak ... 159
Gambar 34. Matriks driver ) * elemen lembaga
pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 166
Gambar 35. Strukturisasi & pengelola pariwisata
di Kawasan Puncak ... 168
Gambar 36. Matriks ) * elemen kendala
kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan
pariwisata di Kawasan Puncak ... 172
Gambar 37. Strukturisasi kendala kelembagaan yang dihadapi
dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 175
Gambar 38. Matriks ) * elemen tujuan yang
diinginkan dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan
Puncak ... 178 Gambar 39. Strukturisasi tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan
pariwisata di Kawasan Puncak ... 181
Gambar 40. Matriks ) * elemen aktivitas/
program yang diharapkan dalam pengelolaan
pariwisata di Kawasan Puncak ... 184 Gambar 41. Strukturisasi aktivitas/program yang diharapkan dalam
pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 186 Gambar 42. Hubungan Hierarkhi Rencana Tata Ruang ... 201 Gambar 43. Diagram input>output (black box) pengelolaan
pariwisata di Kawasan Puncak ... 220 Gambar 44. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop)
pengembangan pariwisata di Kawasan Puncak
Kabupaten Bogor ... 222 Gambar 45. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model
penduduk ... 226 Gambar 46. Struktur Model Dinamik sub model penduduk ... 226 Gambar 47. Grafik hasil simulasi jumlah penduduk periode 2009>
2029 ... 229 Gambar 48. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model
transportasi dan akomodasi. ... 229 Gambar 49. Struktur model dinamik sub model transportasi dan
akomodasi ... 230 Gambar 50. Grafik hasil simulasi jumlah kendaraan dan luas
akomodasi periode 2009>2029 ... 232 Gambar 51. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model
fisik lingkungan ... 233 Gambar 52. Struktur Model Dinamik sub model fisik dan
lingkungan ... 234 Gambar 53. Grafik hasil simulasi jumlah wisatawan, dan jumlah
sampah periode 2009>2029 ... 235 Gambar 54. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub
xi
2009>2029. ... 237 Gambar 57. Model pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. ... 238 Gambar 58. Grafik perbandingan penduduk aktual dan penduduk
hasil simulasi. ... 240 Gambar 59. Grafik perbandingan jumlah kendaraan aktual dan
jumlah kendaraan hasil simulasi. ... 241 Gambar 60. Ruas Jalan alternatif wisata di Kawasan Puncak ... 246 Gambar 61. Perbandingan hasil simulasi pada ketiga skenario
untuk Jml Penduduk, Jml wisatawan, Jml kendaraan, Kapasitas ECC, Biaya Lingkungan, Luas Akomodasi,
Luas Tutupan Lahan, dan jml sampah. ... 249 Gambar 62. Titik Rawan Macet di Wilayah Puncak ... 266
Gambar 63. Sketsa konsep pengaturan jalur angkutan wisata. ... 267
Gambar 64. Dimensi Hukum dan Kelembagaan Hasil Simulasi ... 271 Gambar 65. Analisis Monte Carlo Dimensi Hukum Kelembagaan
Hasil Simulasi ... 272 Gambar 66. Dimensi Ekologi Hasil Simulasi ... 273 Gambar 67. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekologi Hasil Simulasi ... 274 Gambar 68. Dimensi Sarana Prasarana Hasil Simulasi ... 275 Gambar 69. Analisis Monte Carlo Dimensi Sarana Prasarana Hasil
Simulasi ... 275 Gambar 70. Dimensi Sosial Budaya Hasil Simulasi ... 278 Gambar 71. Analisis Monte Carlo Dimensi Sosial Budaya Hasil
xii
Lampiran 1. GLOSSARY ... 290 Lampiran 2. Jenis dan Sumber Data ... 293 Lampiran 3. Hotel/Vila/Wisma di Kawasan Puncak ... 297 Lampiran 4 Nama Obyek Wisata di Kabupaten Bogor ... 301
Lampiran 5 Data kunjungan wisatawan ke Hotel Bintang dan
Melati ... 302 Lampiran 6 Seni Tradisional di Kabupaten Bogor ... 303 Lampiran 7. Rekapitulasi Sumber Data Daya Dukung OTW ... 304 Lampiran 8. Rekapitulasi sumber data Daya Dukung OTW ... 304
Lampiran 9 Hasil Pengolahan Analisis Regresi ... 305
Lampiran 10. Data Pajak dan Retribusi dari Sektor Pariwisata 2004 –
2010 ... 306 Lampiran 11. Hasil Pengolahan Data Faktor yang Berpengaruh pada
Kunjungan Wisatawan ... 307 Lampiran 12. Hasil Pengolahan Data Analisis Daya Saing Kawasan
Puncak ... 312 Lampiran 13. Hasil Pengolahan Ranking Daya Saing Kawasan
(GDP) suatu negara dan bagi daerah sebagai penyumbang
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut mengakibatkan daerah berlomba
lomba untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimilikinya, sehingga
dapat menarik kunjungan wisata (turis), baik lokal maupun mancanegara.
Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak yang cukup besar pada
industri industri yang terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel dan Usaha
Kecil Menengah (UKM) di daerah daerah kunjungan pariwisata.
Dampak positif yang ditimbulkan pariwisata terhadap perekonomian bukan
hanya dari pengeluaran/konsumsi wisatawan mancanegara, tetapi juga berasal
dari pengeluaran wisatawan nusantara dan pengeluaran wisatawan
(wisatawan Indonesia keluar negeri). Investasi yang dilakukan industri pariwisata
seperti hotel dan restoran serta pengeluaran pemerintah pusat dan daerah di
sektor pariwisata turut memberi dampak yang besar terhadap perekonomian
Indonesia. Pertumbuhan sektor pariwisata juga mendorong laju pertumbuhan
sektor sektor lain termasuk pertanian, perdagangan dan jasa. Dampak pariwisata
terhadap ekonomi dapat berupa pembentukan output nasional, Produk Domestik
Bruto (PDB), pembayaran upah/gaji, penerimaan pajak dan penyerapan tenaga
kerja.
Kepariwisataan Kabupaten Bogor dalam perwilayahan pariwisata Provinsi
Jawa Barat ditetapkan sebagai wilayah yang termasuk dalam satu dari sembilan
kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat, yaitu kawasan wisata alam
pegunungan puncak (Disbudpar 2008). Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan
Puncak, ditentukan struktur pengembangannya yaitu: (a) Kawasan Puncak
didominasi fungsi lindung; (b) Pengembangan prasarana wilayah khususnya
jalan raya, relatif terbatas dengan maksud tidak merangsang perkembangan
budidaya yang ada; (c) Pola pengelolaan kawasan pariwisata, pengaturan
alokasi kawasan wisata harus menunjang fungsi utama Kawasan Puncak
sebagai kawasan konservasi air dan alam serta sosial budaya, adat istiadat dan
karakteristik fungsi lingkungan setempat; (d) Bangunan yang diperkenankan di
penunjang kawasan tersebut dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimum 5% (Disparsenibud 2003).
Persoalan lingkungan utama dalam pengembangan pariwisata Puncak
adalah telah terjadinya degradasi DAS Ciliwung Hulu yang diperlihatkan dengan
penambahan lahan kritis (Sabar 2004) dan peningkatan erosi serta
(Qodariah . 2004, Sawiyo 2005). Hal ini disebabkan antara lain karena
peningkatan luas tutupan lahan oleh bangunan. Sebelum tahun 2000 kenaikan
tutupan lahan permukiman relatif lambat yaitu dari 3,96% (1992) menjadi 8,49%
(2000) atau meningkat sebesar 4,53%. Selanjutnya setelah tahun 2000 kenaikan
tutupan lahan relatif lebih cepat selama kurun waktu 6 tahun (2000 2006) dimana
tutupan lahan meningkat sebesar 12% (Dewi 2010). Perubahan tutupan lahan
tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh daya tarik kawasan sebagai
daerah pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap APBD Kabupaten
Bogor, berupa pajak dan retribusi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.
Nilai pajak dan retribusi yang disumbangkan dari sektor pariwisata meningkat
menjadi Rp. 35.509.323.990 pada tahun 2009, dari Rp.17.873.667.000 pada
tahun 2005.
Dampak aktivitas pariwisata yang nampak terlihat jelas adalah terjadinya
kemacetan lalu lintas terutama pada saat saat akhir minggu atau hari libur.
Berdasarkan survey data primer ( /TC) yang dilakukan oleh DLLAJ
pada tahun 2001, volume lalu lintas di jalan raya Puncak rata rata adalah 28.800
kendaraan per hari atau sekitar 1.200 kendaraan per jam. Pada tahun 2009
dilakukan kembali survey data primer di pos pengamatan Ciawi dengan hasil
rata rata jumlah kendaraan yang melintas adalah sebanyak 39.564 kendaraan
per hari atau 1.649 kendaraan per jam. Sebagian besar kendaraan adalah
kendaraan ringan (kendaraan penumpang pribadi dan angkutan kota), rata rata
setiap harinya 21.531 kendaraan per hari atau 897 kendaraan per jam,
sedangkan bus atau truk jumlahnya 2.094 kendaraan per hari atau 87 kendaraan
per jam. Akibat kondisi kemacetan lalu lintas tersebut, 46,67% wisatawan
menyatakan tidak menyukai kemacetan dan kondisi ini dapat menurunkan minat
wisatawan untuk mengunjungi Kawasan Puncak (Disparsenibud 2003).
Peran multifungsi Kawasan Puncak sebagai kawasan konservasi dan
pariwisata memerlukan suatu penanganan yang terpadu dan komprehensif antar
dan mengelola Kawasan Puncak dengan baik. Pengelolaan lingkungan tersebut
meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan,
pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009).
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian diarahkan pada topik “Model
Kebijakan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di
Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, melalui penelitian ini diharapkan pariwisata
di Kawasan Puncak dapat berkembang dengan baik, memiliki daya saing dan
berkelanjutan sebagai output dari penanganan yang terintegrasi dengan
mempertimbangkan unsur unsur ekonomi, ekologi, sosial budaya, sarana
prasarana, kelembagaan dan hukum.
Pembangunan pariwisata di Kawasan Puncak tidak terlepas dari
permintaan, sediaan dan batasan. Prospek permintaan pasar wisata di Kawasan
Puncak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Kawasan Puncak pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.102.680
orang, meningkat menjadi 1.347.625 orang pada tahun 2009 (Disbudpar 2009).
Penambahan wisatawan dan aktivitas wisata memiliki konsekuensi terhadap
penambahan dan pengembangan objek/sarana/prasarana dan atraksi wisata.
Selain itu diperlukan pula ketersediaan dan kesiapan pelayanan transportasi bagi
wisatawan maupun non wisatawan pengguna akses transportasi tersebut.
Pengembangan Kawasan Puncak selain akibat aktivitas wisata juga dipengaruhi
oleh pertumbuhan kota besar seperti Jakarta, Bogor dan Bandung, sehingga
mempercepat pertumbuhan daerah daerah di Kawasan Puncak menjadi bersifat
kota (Kabupaten Bogor 2003).
Kawasan Puncak berdasarkan hidrologis/tata air berada pada hulu Daerah
Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, seluruh aliran sungai akan mengalir ke arah Utara
dan bermuara pada Sungai Ciliwung melewati ke arah Teluk Jakarta, dengan
demikian kawasan Puncak mempunyai fungsi eksternal untuk menjaga tata air
Kota Jakarta sebagai wilayah hilirnya. Selain itu berdasarkan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah didasari
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2006, kawasan wisata
alam pegunungan Puncak yang mencakup areal wilayah Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Cianjur, ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Unggulan (KWU)
Walaupun pengembangan struktur tata ruang untuk Kawasan Puncak
sudah dibatasi secara maksimal, namun masih banyaknya bangunan bangunan
fisik yang baru, baik berizin maupun tidak berizin. Sampai dengan tahun 2006
jumlah bangunan yang memiliki IMB dan tidak ber IMB di Kawasan Puncak
(Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung) dapat dilihat pada tabel 1
berikut:
Tabel 1. Jumlah bangunan ber IMB dan tidak ber IMB
Uraian Jumlah
Bangunan Ber IMB Tidak ber IMB
1. Kecamatan Ciawi 634 580 54
2. Kecamatan Megamendung 704 402 302
3. Kecamatan Cisarua 1.901 1.335 566
2.749 2.749
! " 446 446
Jumlah 6.434 5.066 1.368
!!"#
Berdasarkan jumlah bangunan tersebut, banyak bangunan yang berdiri di
atas tanah negara dan tanah perkebunan serta eks perkebunan sulit untuk
dikendalikan. Selain itu banyak bangunan yang melebihi ketentuan teknis
tutupan bangunan, melanggar garis sempadan atau bangunan yang berubah
fungsi dari rumah tinggal menjadi villa, wisma dan hotel. Permasalahan lain
adalah bermunculannya PKL di sepanjang jalan Ciawi sampai dengan Cisarua.
Permasalahan munculnya bangunan bangunan tidak berizin tersebut sebagai
akibat kurang intensifnya pengendalian dan pengawasan pembangunan fisik di
kawasan puncak dalam kaitannya dengan fungsi Kawasan Puncak sebagai
kawasan lindung (Kabupaten Bogor 2008).
Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan pariwisata Puncak,
pertambahan jumlah bangunan, berkurangnya tutupan lahan, peningkatan
timbulan sampah, pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, berkurangnya
estetika karena lingkungan kumuh, peningkatan resiko kejadian longsor
merupakan beberapa kondisi yang terjadi di kawasan pariwisata Puncak. Jika
kondisi ini tidak ditangani, maka diduga akan mengakibatkan penurunan citra
dan daya saing kawasan puncak sebagai kawasan pariwisata andalan. Ciri
daerah daerah disekitarnya seperti Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan
Sukabumi. Kerangka pikir penelitian ini disajikan pada gambar 1.
" #
Gambar 1. Kerangka pemikiran pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.
4 " " 3 )
Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip
prinsipnya. Prinsip prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para
pelaku ( $ ), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan, mewadahi tujuan tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya
dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.
Berdasarkan hal tersebut maka kondisi Kawasan Puncak perlu ditinjau dari sisi
lingkungan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, tata ruang, hukum dan
kelembagaan. Serangkaian kajian yang dilakukan tersebut dibuat suatu model
pembangunan pariwisata di Kawasan Puncak yang berdaya saing dan
berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rumusan permasalahan
yang perlu dipecahkan adalah:
a) Kinerja pembangunan di suatu kawasan atau wilayah akan ditentukan oleh
arahan pemanfaatan ruang serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah
daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk mengevaluasi kembali
bentuk bentuk regulasi pemanfaatan ruang dan perizinan pariwisata yang
sudah dilaksanakan di Kawasan Puncak;
b) Kawasan Puncak dengan potensi alamnya menjadi andalan bagi Kabupaten
Bogor dan Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan pariwisata alam
pegunungan. Kegiatan pariwisata tersebut dapat berlangsung terus jika
dikelola secara berkelanjutan, karenanya perlu dilakukan analisis untuk
mengetahui status keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kawasan Puncak;
c) Pengelolaan pariwisata yang baik, akan memberikan rasa aman dan nyaman
bagi para wisatawan serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial,
budaya dan ekonomi masyarakat lokal maka akan meningkatkan daya saing
wisata di kawasan tersebut. Berdasarkan hal tersbut perlu dilakukan kajian
untuk mengukur tingkat daya saing pariwisata di Kawasan Puncak;
d) Kelembagaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang
keberhasilan suatu program. Pengelolaan pariwisata di suatu kawasan akan
dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan yang terkait didalamnya. Koordinasi,
konsistensi dan tumpang tindih kewenangan sering menjadi permasalahan
didalam pengelolaan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan
kajian untuk mengetahui kondisi kelembagaan pengelolaan pariwisata di
Kawasan Puncak;
e) Pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak agar berdaya saing dan
berkelanjutan harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, ekologi,
ekonomi, hukum dan kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui
bagaimana rancangan model pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.
Rumusan permasalahan pengelolaan pariwisata disajikan dalam gambar 2.
Pariwisata di Kawasan Puncak
Gambar 2. Perumusan masalah penelitian.
5 +" "
Tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan
pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak agar memiliki daya saing dan dapat
dilaksanakan atau dikelola secara berkelanjutan. Guna mencapai tujuan utama
maka dirancang beberapa sub tujuan sebagai berikut:
a) Mengetahui performansi wisatawan di Kawasan Puncak;
b) Menghasilkan analisis terhadap kebijakan yang mengatur penataan ruang dan
pariwisata di Kawasan Puncak;
c) Menghasilkan analisis tingkat daya saing pariwisata di Kawasan Puncak;
d) Menghasilkan analisis daya dukung lingkungan di Kawasan Puncak;
e) Menghasilkan analisis status keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kawasan
f) Menghasilkan analisis kondisi kelembagaan pengelola pariwisata di Kawasan
Puncak;
g) Menghasilkan model kebijakan pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.
6 3 /
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk:
a) Memberikan kontribusi positif sebagai koreksi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pariwisata;
b) Sebagai acuan bagi para pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan
usaha yang berkelanjutan;
c) Sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di
bidang pariwisata;
d) Sebagai alternatif model bagi pengelolaan pariwisata terutama dalam
memadukan unsur konservasi dan pengembangan pariwisata;
e) Sebagai acuan untuk penyempurnaan kebijakan penataan ruang, perizinan,
pengelolaan lingkungan, pembinaan sosial budaya, hukum dan kelembagaan,
ekonomi serta sarana dan prasarana, agar dalam implementasinya dapat
berkelanjutan.
7 ! " , .
Penelitian ini dilakukan di sebuah kawasan wisata yang merupakan Daerah
Tujuan Wisata (DTW) yang dikenal secara nasional. Masalah yang diteliti
merupakan masalah aktual dan strategis yaitu tentang kebijakan pembangunan
pariwisata di kawasan puncak yang merupakan daerah konservasi penting bagi
Propinsi DKI Jakarta selaku ibukota Negara Republik Indonesia. Rekomendasi
kebijakan pariwisata yang dihasilkan mempertimbangkan unsur daya saing dan
berkelanjutan, sehingga metode yang digunakan harus mampu mengakomodasi
dua tujuan tersebut.
Berkenaan dengan hal tersebut maka kebaruan penelitian ( % ) terletak
pada upaya untuk memadukan beberapa metode analisis secara komprehensif,
yaitu metode pengukuran indeks daya saing dengan memperhitungkan 8
indikator, indeks keberlanjutan (MDS), daya dukung, % & (TCM),
analisis kelembagaan, ' (FGD) dan analisis sistem
dinamik, untuk mendapatkan arahan kebijakan agar pariwisata di Kawasan
+ - $+
Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang komponen
komponennya terdiri atas: (1) Pari = penuh, lengkap, berkeliling; (2) Wis (man)=
rumah, kampong, komunitas; (3) Ata = pergi terus menerus,
mengembara ( ), bila dirangkai menjadi satu kata berarti pergi
secara lengkap meninggalkan rumah (kampong), berkeliling terus menerus
(Pendit 2002).
Yoeti (1988) dan Pendit (2002), mengutip berbagai pengertian pariwisata
seperti tertera dibawah ini:
1. Pariwisata adalah gabungan berbagai kegiatan, pada umumnya bidang
ekonomi yang langsung berkaitan dengan kedatangan dan tinggal serta
kegiatan pendatang di negara tertentu atau daerah tertentu (Schulaland,
1910);
2. Pariwisata adalah kepergian orang orang sementara dalam jangka waktu
pendek ke tempat tempat tujuan diluar tempat tinggal dan pekerjaan sehari
harinya serta kegiatan kegiatan mereka selama berada di tempat tujuan
tersebut ( in Britain 1976);
3. Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antar orang,
baik dari negara yang sama atau antar negara atau hanya dari daerah
geografis yang terbatas, didalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu
di daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai
kebutuhan, kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan (Wahab 1992);
4. Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi
wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah
dalam proses menarik dan melayani wisatawan wisatawan serta para
pengunjung lainnya (Robert McIntosh dan Gupta 1980);
5. Pariwisata adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari
seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan
yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga lembaga yang
digunakan untuk maksud tersebut (Hans Buchli);
6. Pariwisata adalah lalu lintas orang orang yang meninggalkan tempat
mata sebagai konsumen dari bu ah hasil perekonomian dan kebudayaan,
guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang
beranekaragam dari pribadinya (Kurt Morgenroth);
7. Pariwisata adalah keseluruhan hubungan antara manusia yang hanya berada
untuk sementara waktu dalam suatu tempat kediaman dan berhubungan
dengan manusia manusia yang tinggal di tempat itu (Gluckmann 1998);
8. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal di tempat lain
di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari satu tahun terus
menerus dengan maksud bersenang senang, berniaga dan keperluan
keperluan lainnya (Santoso 2000);
Berdasarkan Undang Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
Berbagai definisi yang dikutip menunjukkan beragam aspek yang menjadi
titik tolak pandangan masing masing ahli dalam mendefinisikan pengertian
pariwisata. Terdapat kesamaan yang dapat ditangkap dari definisi definisi
tersebut, sehingga Yoeti (1988), mengemukakan empat faktor yang menjadi
dasar pengertian pariwisata yakni:
1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu, sekurang kurangnya 24 jam
dan kurang dari satu tahun;
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain;
3. Perjalanan itu, apapun bentuknya harus selalu dikaitkan dengan
pertamasyaan atau rekreasi;
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat
yang dikunjunginya dan semata mata sebagai konsumen di tempat itu.
Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh kegiatan
perjalanan ( % ) sebagai salah satu bentuk kegiatan manusia yang digunakan
untuk memenuhi keinginan (rasa ingin tahu) yang bersifat rekreatif dan edukatif.
Adapun dalam melakukan kegiatan pariwisata seseorang mempunyai motivasi
sendiri yang akan diwujudkan dalam bentuk wisata yang dipilihnya.
Piknik dapat menjadi bagian dari pariwisata atau menjadi salah satu
kegiatan dalam pariwisata, sedangkan rekreasi biasanya dilakukan dengan
Warpani 2007). Menurut Banapon (2008), motivasi berpariwisata dapat dibagi
kedalam empat kategori yaitu: motivasi fisik, motivasi budaya, motivasi antar
pribadi, motivasi status dan martabat.
STIPAR (2006), menguraikan 8 (delapan) tipologi pariwisata berdasarkan
produk pariwisata, yaitu:
1. ( (ekowisata): wisata yang bertujuan untuk menikmati kondisi alam
yang unik maupun keindahan alam yang ada juga kehidupan tanaman dan
binatang liar yang ada didalamnya;
2. (wisata budaya): wisata untuk mendapatkan pengalaman
mengenai suatu cara/gaya hidup yang sedang mengalami kepunahan atau
bahkan turut serta hidup dalam cara/gaya hidup dimaksud;
3. ) * (agrowisata): wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai
objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman
rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro;
4. ) % (wisata petualangan): wisata yang terkait dengan alam dan
lingkungan seperti gunung, sungai, hutan dan sebagainya. Wisata petualang
membawa wisatawan berinteraksi sangat dekat dengan alam dan merasakan
tantangan alam;
5. + (wisata kesehatan): wisata yang memiliki fasilitas
penyembuhan kesehatan atau manfaat yang berkaitan dengan kesehatan
atau dipercaya dapat memulihkan kondisi kesehatan kembali seperti semula;
6. (wisata religi): wisata yang dikaitkan dengan acara
keagamaan, misalnya kunjungan/ziarah ke fasilitas fasilitas peribadatan atau
tempat tempat religius lainnya;
7. ( (wisata pendidikan): wisata yang lebih mengutamakan
kepada perjalanan yang memiliki kegiatan kegiatan formal yang berkaitan
dengan pelajaran atau dunia pendidikan;
8. (wisata belanja): wisata ke suatu destinasi wisata untuk
memenuhi kebutuhan berbelanja.
Tingkatan daur hidup produk sangat penting diketahui untuk mengukur
posisi produk pariwisata saat ini. Konsep daur hidup produk dijelaskan STIPAR
(2006) sebagai berikut:
1. : Pada tahap ini, produk masih berupa daya tarik atau atraksi saja,
umumnya wisatawan telah mengenal dan mengetahui tentang produk ini
tetapi jumlahnya masih sedikit. Produk yang ditawarkan masih belum
dikembangkan dan belum memiliki banyak pesaing;
2. , : Pada tahap ini, pesaing sudah mulai tertarik pada pasar yang serupa
dengan produk yang ditawarkan dan keuntungan dari produk yang ditawarkan
sudah mulai meningkat. Produk sudah cukup berkembang dan sudah
mempunyai sarana dan prasarana pendukung. Pasar sudah mengenal produk
tersebut meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Produk tersebut sudah
mempunyai pasar yang tetap dan ada kemungkinan terus bertambah jumlah
peminatnya (wisatawan);
3. & : Pada tahap ini, produk telah berkembang dan telah mempunyai
posisi yang baik di mata pasar. Sarana dan prasarana pendukung telah
lengkap, sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Produk ini telah
mempunyai pasar yang tetap dan akan terus bertambah, sehingga pengelola
harus dapat melakukan inovasi inovasi agar wisatawan tidak jenuh;
4. : Pada tahap ini, posisi produk di pasar mengalami penurunan. Pasar
telah berkurang dan cenderung sedikit. Hal ini terjadi karena atraksi yang
ditawarkan produk tersebut kurang menarik atau kurang memenuhi selera dan
ekspektasi wisatawan, atau terjadinya persaingan dengan produk lain yang
memiliki tipologi serupa.
$
Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang
sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti
komponen ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Sebagai sebuah sistem,
antarkomponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi yang
berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem juga akan menyebabkan
terjadinya perubahan pada subsistem yang lain, sampai akhirnya kembali
ditemukan harmoni yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Mill dan Morrison
(1985) dalam Pitana dan Gayatri (2005), bahwa pariwisata adalah sistem dari
berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba laba.
Pitana dan Gayatri (2005), mengemukakan beberapa model sistem
1. Sistem pariwisata terdiri dari tiga komponen utama yaitu: (1) daerah asal
( ); (2) daerah tujuan ( ); dan (3) daerah antara ( /
perjalanan) (Leiper 1979);
2. Sistem pariwisata terdiri dari empat komponen yaitu: (1) $ ; (2). % ; (3)
destinasi; dan ( 4) pemasaran ( Mill dan Morrison 1985);
3. Sistem pariwisata terdiri atas tiga elemen yaitu: (1) elemen dinamis yaitu
perjalanan wisatawan; (2) elemen statis, yaitu: keberadaan destinasi dan
elemen konsekuensial yaitu berbagai dampak yang timbul (Mathiesen dan
Wall 1982);
4. Sistem pariwisata berdasarkan aspek pemasaran pariwisata terdiri dari: (1)
subsistem produksi; (2) subsistem % ; (3) subsistem manajemen; dan
(4) subsistem distribusi dan penjualan (Poon 1993).
Aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem pariwisata
dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat; (2) swasta; dan (3)
pemerintah. Kelompok masyarakat terdiri dari masyarakat umum yang ada pada
destinasi seperti tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media masa.
Kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha,
sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi
mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (Pitana
dan Gayatri 2005).
Warpani dan Warpani (2007), memandang pariwisata sebagai suatu sistem
dan memilahnya dalam sisi permintaan dan sediaan. Komponen permintaan
terdiri atas elemen orang, ditengarai oleh hasrat orang melakukan perjalanan
dan kemampuan melakukannya, sedangkan komponen sediaan adalah daya
tarik wisata serta perangkutan, informasi dan promosi dan pelayanan. Hubungan
antar elemen digambarkan sebagai suatu sistem kepariwisataan sebagaimana
Gambar 3. Model komponen fungsional kunci yang membentuk dinamika dan sistem hubungan kepariwisataan (Gunn 1988).
Elemen kepariwisataan dikelompokkan menjadi elemen: (1) Utama, yakni
daya tarik yang mengandung arti objek yang menjadi sasaran dan destinasi
kunjungan wisata; (2) Prasyarat, yakni elemen yang merupakan prasyarat proses
berlangsungnya kegiatan pariwisata, yakni perangkutan; (3) Penunjang, misalnya
informasi dan promosi yang membangun dan mendorong minat berwisata; dan
(4) Sarana pelayanan, yakni elemen yang membuat proses kegiatan pariwisata
menjadi lebih mudah, nyaman, aman dan menyenangkan berupa hotel, motel,
penginapan, rumah makan dan lain lain (Gunn 1988).
4 %
Menurut Pitana dan Diarta (2009), pengelolaan pariwisata harus
memperhatikan prinsip prinsip berikut:
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kearifan
lokal dan yang merefleksikan keunikan peninggalan
budaya dan keunikan lingkungan;
2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi
basis pengembangan kawasan pariwisata;
Minat berwisata Kemampuan berwisata
pengembangan sumber daya demi kepuasan pengunjung
volume dan mutu semua moda
SEDIAAN
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah
budaya lokal;
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan
lokal;
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan
pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi
sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata
tersebut jika melampaui ambang batas ( ) lingkungan alam
atau akseptibilitas sosial, walaupun di sisi lain mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat.
) % ) (PATA) menyusun petunjuk pengembangan
( ) pariwisata yang berisi tiga substansi pokok mengenai etika
pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab, yaitu: (1) keuntungan dan
kemanfaatan jangka panjang ( ); (2) keberlanjutan produk
pariwisata ( ); dan (3) keadilan antargenerasi (
-.) (Pitana dan Diarta 2009).
Metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan sebagai
berikut: (1) konsultasi dengan semua pemangku kepentingan; (2) identifikasi isu;
(3) penyusunan kebijakan; (4) pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas
khusus; (5) penyediaan fasilitas dan operasi; (6) penyediaan kebijakan fiskal,
regulasi dan lingkungan sosial yang kondusif; dan (7) penyelesaian konflik
kepentingan dalam masyarakat (Richardson dan Fluker 2004).
5 + 8"
Menurut Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
ruang adalah meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang
adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
Secara umum perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan
rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia,
kualitas pemanfaatan ruang, yang secara struktural menggambarkan keterikatan
fungsi lokasi yang terbagi dalam berbagai kegiatan. Perencanaan tata ruang
tata ruang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta
mengikat semua pihak (Sugandhy 1999).
Dalam menata ruang wilayah tempat kehidupan dan penghidupan,
Indonesia menganut konsep ruang wilayah yang terdiri atas elemen wisma,
karya, marga, suka dan penyempurna; disingkat WKMSP. Wisma adalah ruang
wilayah permukiman, karya adalah ruang wilayah pekerjaan, marga adalah ruang
wilayah pergerakan/mobilitas, suka adalah ruang wilayah bagi fasilitas yang
mencakup rekreasi dan pariwisata dan penyempurna adalah ruang wilayah bagi
fasilitas sosial budaya lainnya termasuk tempat ibadah (Warpani dan Warpani
2007).
Daerah/kota tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan daerah/kota
lainnya dalam jaringan kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Elemen WKMSP di
daerah/kota membentuk suatu jaringan saling ketergantungan, karena itu harus
ditata secara terkoordinasi dalam satu satuan tata ruang wilayah. Daerah/kota
bukan wilayah tertutup melainkan berhubungan satu sama lain secara fisik
geografis dan juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan. Koordinasi tata ruang wilayah diperlukan agar terjadi keseimbangan
pembangunan dan perkembangan antar daerah.
Kegiatan pariwisata menempati ruang di suatu wilayah (administrasi) atau
bahkan ruang kegiatannya lebih dari satu wilayah administrasi daerah sehingga
keberadaanya sangat bermakna sebagai bagian tata ruang wilayah dan
sebaliknya pengembangan pariwisata pun harus mengacu kepada tata ruang
wilayah. Jadi harus tercipta hubungan timbal balik antara pengembangan
pariwisata dan rencana tata ruang wilayah.
Jarak geografis antara lokasi daya tarik wisata dengan asal wisatawan
adalah salah satu aspek keruangan yang tidak dapat diabaikan. Akibat jarak
geografis tersebut maka diperlukan prasarana dan sarana perangkutan untuk
menunjang kegiatan pariwisata seperti, jaringan perangkutan, perhotelan, dan
pelayanan lainnya, pada aspek inilah sering terjadi tumpang tindih dan konflik
kepentingan atas ruang wilayah. Selain jarak antara daerah tujuan wisata dan
wisatawan yang berjauhan, juga jarak antar daerah tujuan wisata sendiri yang
tidak terkonsentrasi dalam satu lokasi tetapi terpencar pada wilayah yang cukup
luas. Kondisi ini harus diperhitungkan dalam rencana tata ruang wilayah, tidak
dasarnya akan terjadi “pengaruh rambatan” ( $ , ) yang biasa
terjadi di wilayah yang terdapat kegiatan pariwisata (Warpani dan Warpani
2007).
Pemanfaatan ruang di setiap daerah tujuan wisata harus dilaksanakan
secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dikembangkan
pola tata ruang yang menyerasikan tata guna tanah, air serta sumberdaya alam
lainnya dalam satu kesatuan tatanan lingkungan yang harmonis dan dinamis
serta ditunjang dengan pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi.
Pendekatan perencanaan tata ruang melalui perencanaan tata guna lahan dapat
dilakukan dengan cara penilaian terhadap komponen komponennya, seperti
tanah, iklim dan lain lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu
berubah menurut waktu dan ruang (Sugandhy 1999).
Sebaran lokasi DTW pada skala nasional dan/atau daya tarik wisata pada
skala regional, memicu terjadinya interaksi antardaerah sebagai manifestasi
hubungan sediaan permintaan. Hubungan antara daerah asal wisatawan dengan
DTW adalah dalam bentuk mobilitas orang, sedangkan hubungan antar daerah
dapat menyangkut mobilitas orang dan/atau barang. Selain arus mobilitas orang
dan barang, sektor kepariwisataan berdampak terhadap peredaran uang.
Berkenaan dengan pariwisata mancanegara, maka arus valuta asing mempunyai
makna berarti bagi perekonomian suatu negara (Warpani dan Warpani 2007).
Santoso (2001), menguraikan masalah masalah tata ruang dari mulai
perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian ruang sebagai berikut:
1. Permasalahan perencanaan tata ruang meliputi: (1) penggunaan peta dasar,
tingkat ketelitian peta dan data/informasi yang tidak seragam antar
instansi/lembaga terkait; (2) penerapan kriteria teknis sektoral versus kriteria
teknis ruang yang menimbulkan konflik antar instansi/lembaga dalam alokasi
fungsi ruang; (3) penyusunan rencana tata ruang wilayah yang kurang
mengakomodir perkembangan data/informasi sektor sektor pengguna ruang;
(4) pemahaman yang berbeda terhadap peraturan perundang undangan; (5)
pemahaman yang berbeda terhadap deliniasi fungsi ruang yang tergambar
pada peta rencana tata ruang wilayah; (6) pemahaman yang berbeda
masa berlaku izinnya versus masa berlakunya arahan fungsi ruang didalam
rencana tata ruang wilayah;
2. Masalah dalam pemanfaatan ruang meliputi: (1) belum tuntasnya
penyelesaian masalah masalah pertanahan, sehingga potensial
menyebabkan kekeliruan dan/atau tumpang tindih hak atas pemanfaatan
ruang wilayah; (2) kurang lengkap dan kurang jelasnya rencana tata ruang
wilayah sehingga sulit menjadi acuan pembangunan, karena tidak berbasis
pada evaluasi kemampuan/kesesuaian lahan serta kurang antisipatif terhadap
kebutuhan pembangunan; (3) rendahnya kemampuan sektoral dan
masyarakat dalam penjabaran rencana tata ruang wilayah, karena kurangnya
sosialisasi dan diseminasi; (4) inkonsistensi dalam implementasi rencana tata
ruang wilayah dengan pelaksanaan pembangunan prasarana wilayah,
sehingga pemanfaatan ruang wilayah menjadi tidak terkendali;
3. Masalah masalah dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: (1) tidak
adanya kejelasan, wewenang dan prosedur pengawasan yang meliputi
, pelaporan dan evaluasi serta penertiban dalam pemanfaatan
ruang wilayah; (2) lemahnya pencatatan atau tidak tersedianya data/informasi
adanya perubahan rencana tata ruang wilayah; (3) kurang tersedianya
anggaran untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; (4) tidak adanya
tindak lanjut hasil pengendalian oleh pihak pihak yang kompeten; (5)
kelemahan aparat dalam penerapan peraturan perundang undangan.
6 * $
Aspek daya saing merupakan cerminan kesiapan dan kemampuan produk
wisata serta penguasaan terhadap pasar dan informasi yang diformulasikan
secara tepat pada strategi dan program pengembangan pariwisata. Faktor faktor
yang memperlihatkan daya saing kepariwisataan Indonesia antara lain
(Suwantoro 2004):
1. Pendapatan: selama kurun waktu lima tahun terakhir peringkat pertama
pendapatan negara negara Asean diraih oleh Singapura, yaitu sebesar
32,73% dari total pengeluaran wisatawan di Asean. Posisi Indonesia pada
2. Jumlah wisatawan: jumlah wisatawan tertinggi ditempati oleh Malaysia
sebesar 29,5% sedangkan Indonesia berada di urutan keempat sebesar
9,98%;
3. Lama tinggal: Filipina menduduki peringkat pertama dengan rata rata lama
tinggal 11,5 hari sedangkan Indonesia berada di urutan kedua dengan rata
rata lama tinggal 10,5 hari.
Posisi daya saing pariwisata Indonesia menempati peringkat ke 60 indeks
daya saing perjalanan dan wisata (TTCI) dari 124 negara yang disurvei oleh
forum ekonomi dunia (WEF) yang berbasis di Jenewa, Swiss. Guna mengukur
daya saing tersebut digunakan 13 indikator, antara lain kebijakan peraturan dan
regulasi, keselamatan dan keamanan, regulasi lingkungan, kesehatan dan
, privatisasi perjalanan dan wisata serta infrastruktur transportasi. WEF
(1993), menyebutkan daya saing perjalanan dan wisata nasional telah menjadi
sebuah sektor kunci dalam ekonomi dunia dan menjadi sumber dari
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di banyak negara.
Karakteristik jasa pariwisata dapat digunakan sebagai acuan pengukuran
daya saing. Mihalic (2000) menyatakan terdapat lima karakteristik jasa pariwisata
yaitu: (1) , dimana karakteristik ini terkait dengan konsistensi dan
kesesuaian pelayanan; (2) % karakteristik ini berhubungan
dengan kemampuan merespon secara cepat keluhan pelanggan; (3) ) ,
yaitu kemampuan meyakinkan pelanggan serta memenuhi janji kepada
pelangan; (4) ( , yaitu terkait dengan kepedulian kepada pelanggan; dan
(5) , yaitu karakteristik yang terkait dengan penampilan fisik, peralatan
dan berbagai media komunikasi.
Studi yang dilakukan Dwyer . (2000) menggunakan
% untuk mengukur daya saing . Studi ini
membedakan dua katagori harga yaitu % dan . %
berkaitan dengan yang dikeluarkan dari dan ke suatu destinasi dan
berkaitan dengan komoditi pada suatu tujuan destinasi. Studi lain
dilakukan oleh Inskeep (1991) dan Middleton (1997) menyatakan bahwa
-% sebagai indikator yang penting dalam pengukuran daya saing. Studi
ini juga konsisten dengan studi yang dilakukan Ritchie dan Crough (1993) dan
Mihalic (2000) yang memasukkan faktor lingkungan sebagai indikator penentu
Ritchie dan Crough (1993) memperluas penelitian sebelumnya dengan
mendasarkan pada teori % % yang menyatakan bahwa
kepemilikan dan penggunaan sumber sumber daya yang dimiliki oleh suatu
negara (destinasi) akan mengakibatkan destinasi tersebut unggul bersaing
dibandingkan dengan destinasi lainnya. Peneliti memasukkan katagori yang lebih
luas $ ,
#
Gooroochurn dan Sugiyarto (2004) serta Trisnawati # (2007) dalam
penelitiannya menggunakan index daya saing pariwisata yang dibentuk dari 8
indikator penentu daya saing pariwisata. Kedelapan indikator tersebut seperti
tercantum dalam gambar 4 berikut.
Gambar 4. Indeks daya saing pariwisata (Gooroochurn dan Sugiyarto 2004).
1. .9 indikator ini menunjukkan pencapaian
perkembangan ekonomi daerah akibat kedatangan turis pada daerah
tersebut. Pengukuran yang digunakan adalah . yaitu rasio
antara penerimaan pariwisata dengan GDP. Ukuran lainnya adalah
. yaitu rasio antara jumlah aktivitas turis (datang dan pergi)
dengan jumlah penduduk daerah destinasi;
2. : indikator ini menunjukkan harga
komoditi yang dikonsumsi oleh turis selama berwisata seperti biaya
digunakan adalah , sebagai proksi dari harga adalah
rata rata tarif minimum hotel yang merupakan hotel , , /
3. Indikator ini menunjukkan
perkembangan jalan raya, perbaikan fasilitas sanitasi dan peningkatan akses
penduduk terhadap fasilitas air bersih. Guna mengukur IDI terdapat kesulitan
sehingga CM memproksikan IDI dengan perkapita penduduk;
4. indikator ini menunjukkan kualitas lingkungan
dan kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungannya. Pengukuran
yang digunakan adalah indeks kepadatan penduduk (rasio antara jumlah
penduduk dengan luas daerah) dan indeks emisi CO2. Data Indeks emisi CO2
dapat diperoleh dari informasi tingkat pencemaran udara pada jalan jalan
utama;
5. indikator ini menunjukkan
perkembangan infrastruktur dan teknologi modern yang ditunjukkan dengan
meluasnya penggunaan internet, dan ekspor produk produk
berteknologi tinggi. Pengukuran yang digunakan adalah .
(rasio penggunaan dengan jumlah penduduk) dan . .
(rasio ekspor produk produk berteknologi tinggi: komputer, produk farmasi,
mesin mesin industri dan elektronik dengan jumlah ekspor keseluruhan);
6. ! ! indikator ini menunjukkan kualitas
sumber daya manusia daerah tersebut sehingga dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada turis. Pengukuran HRI menggunakan indek
pendidikan yang terdiri dari rasio penduduk yang bebas buta huruf dan rasio
penduduk yang berpendidikan SD, SMP, SMU, diploma dan sarjana;
7. " " : indikator ini menunjukkan tingkat keterbukaan
destinasi terhadap perdagangan internasional dan turis internasional.
Pengukurannya menggunakan rasio jumlah penerimaan dari turis
internasional dengan total PAD dan rasio penerimaan pajak ekspor impor
dengan jumlah seluruh penerimaan;
8. # # : indikator ini menunjukkan kenyamanan
dan keamanan turis untuk berwisata di daerah destinasi. Ukuran SDI adalah
7 * " "
Mathieson dan Wall (1982), mendefinisikan daya dukung sebagai
“maksimum jumlah manusia yang dapat ditampung di suatu lokasi tanpa
mengakibatkan penurunan kualitas fisik lingkungan, tanpa mengakibatkan
penurunan kualitas kenyamanan pengunjung wisata dan tanpa mengakibatkan
dampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di sekitar areal
wisata”. Hal serupa disampaikan oleh WTO (1995), bahwa daya dukung wilayah
wisata adalah daya dukung lingkungan spesifik, sehingga secara relatif
wisatawan dapat menikmati kesenangan dan memperoleh kepuasan yang
diinginkan, tanpa menghilangkan kesenangan orang lain.
Batasan daya dukung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: (1) faktor
pemasaran berkaitan dengan karakteristik wisatawan seperti usia, jenis kelamin,
pendapatan, motivasi, sikap dan harapan. Faktor lainnya berupa level pemakaian
dari fasilitas, kepadatan wisatawan, lamanya menginap, tipe/jenis aktivitas dan
level kepuasan wisatawan; (2) faktor yang berkaitan dengan atribut destinasi,
seperti kondisi lingkungan dan alam, struktur ekonomi dan pembangunan,
struktur sosial dan organisasi, organisasi politik dan level pengembangan
pariwisata (O’Reilly 1991 dalam Pitana dan Diarta 2009).
WTO (1995), menyebutkan pula bahwa daya dukung wilayah wisata
dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan, yaitu: (1) lingkungan fisik, misalnya
ukuran ruang yang dibutuhkan. Secara fisik, jika daya dukung terlewati, akan
berpengaruh terhadap kerentanan aset sumberdaya alam, karena muncul
masalah seperti meningkatnya jumlah limbah dan sampah, pencemaran serta
gangguan terhadap proses ekologi yang penting; (2) lingkungan sosial, misalnya
ketersediaan fasilitas yang diperlukan. Secara sosial dampak negatif dari
terlampauinya daya dukung akan muncul gangguan sosial dan budaya,
produktivitas masyarakat turun, misalnya karena kepadatan wisatawan timbul
kemacetan lalu lintas yang menghambat mobilitas masyarakat dalam
beraktivitas. Terlampauinya daya dukung sosial berakibat pada perubahan sosial
budaya masyarakat lokal yang rentan terhadap dampak yang merugikan.
Menurut Pitana dan Diarta (2009), terdapat tiga tipe daya dukung yang
1.
Merupakan kemampuan suatu kawasan alam atau destinasi wisata untuk
menampung pengunjung/wisatawan, penduduk asli, aktivitas/kegiatan wisata
dan fasilitas penunjang wisata. Konsep ini sangat penting mengingat
sumberdaya alam dan infrastruktur yang sangat terbatas sehingga sering
mengalami % # Pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung
fisiknya dapat menyebabkan degradasi sumberdaya alam, penurunan kualitas
hidup komunitas disekitarnya, % , dan sebagainya;
2. 0
Konsep ini merefleksikan interaksi destinasi pariwisata dengan ekosistem flora
dan fauna, seperti halnya pada kegiatan ekowisata. Konsekuensinya sangat
penting untuk melindungi dan menjaga ekosistem agar sedapat mungkin tetap
seperti kehidupan habitat aslinya. Diperlukan peran pemerintah untuk
membuat kawasan lindung dan konservasi serta pemberlakuan peraturan
yang melarang perilaku destruktif seperti perburuan, penebangan hutan,
pengeboman ikan, peracunan biota laut dan sebagainya;
3. 1
Merefleksikan dampak pengunjung/wisatawan pada gaya hidup komunitas
lokal. Kemampuan sebuah komunitas untuk mengakomodasi keberadaan
wisatawan beserta gaya hidupnya di komunitas tertentu sangat bervariasi dari
suatu budaya dengan budaya lain dan dari suatu wilayah dengan wilayah lain.
Wisatawan umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dan ingin
mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan penduduk lokal dengan adat
atau kebiasaan uniknya.
Pitana dan Diarta (2009) mengemukakan pentingnya mengukur RCC
( ) yang didefinisikan sebagai “suatu metoda
manajemen yang didasarkan atas pemanfaatan suatu destinasi oleh aktivitas
pariwisata yang tidak merusak lingkungan fisik atau menurunkan kualitas
rekreasi. Dampak dari pembangunan dan pengembangan destinasi wisata pada
lingkungan diteliti dan diidentifikasi tingkat kritisnya. Tingkat kritis suatu destinasi
wisata mengacu pada jumlah orang yang mengunjungi kawasan tersebut per
tahun atau per hari atau per sekali kunjungan. Umumnya nilai optimum