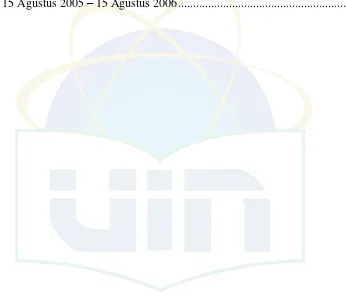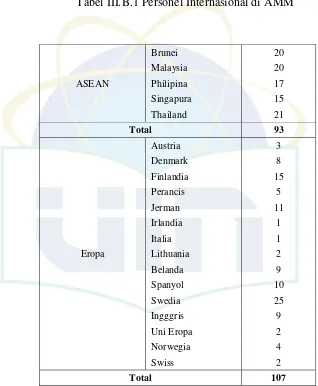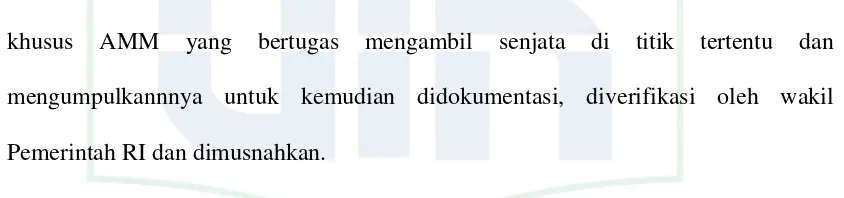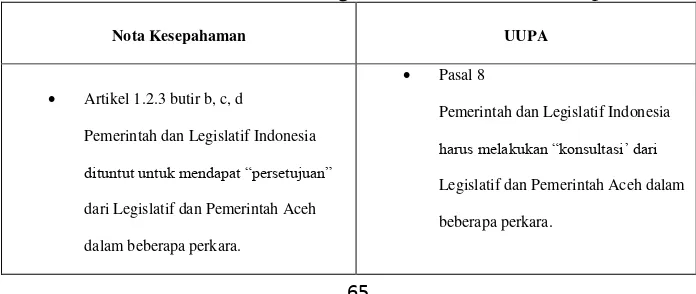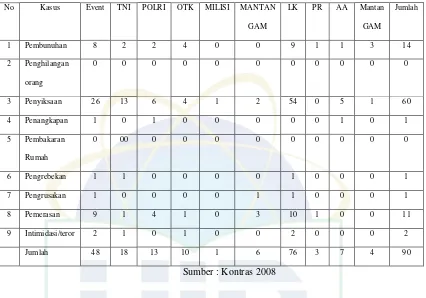Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Citra Dea Gemala
NIM 208083000023
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
PERAN ACEH MONITORING MISSION DALAM UPAYA
PEACE BUILDING DI ACEH PADA TAHUN 2005 – 2006
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 8 Desember 2013
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Utnuk Memenuthi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
CITRA DEA GEMALA
NIM 208083000023
Dosen Pembimbing
Teguh Santosa MA,
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PEACE BUILDING DI ACEH TAHUN 2005-2006
Oleh
CITRA DEA GEMALA NIM 208083000023
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.
Ketua, Sekretaris,
Agus Nilmada Azmi, M.Si Agus Nilmada Azmi, M.Si
NIP.197808042009121002 NIP.197808042009121002
Penguji I, Penguji II,
Drs. Aiyub Mochsin, MA, Agus Nilmada Azmi, M.Si
02001540 NIP.197808042009121002
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 16 Januari 2014.
Ketua Pogram Studi Hubungan Internasional
Kiky Rizky, M.Si
Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinski, Finlandia, Pemerintah Republik Indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman Untuk mengakhiri konflik
bersenjata yang telah berlangsung selama 30 tahun di Aceh. Perjanjian ini juga menjadi dasar
bagi Uni Eropa dan ASEAN untuk membentuk sebuah lembaga pemantau untuk mengawasi
implementasi Nota Kesepahaman di Aceh.
Aceh Monitoring Mission (AMM) menjalankan misi di Aceh selama 15 bulan. AMM
memainkan peran yang sangat penting bagi proses implementasi damai di Aceh. Diantara
beberapa keberhasilan peran dan tugas AMM, juga terdapat berbagai kelemahan atau
kegagalan. Kunci keberhasilan AMM sendiri adalah komposisi anggota-anggotanya yang
merupakan representasi dari dua organisasi regional yang sangat kredibel dan berpengaruh,
baik bagi GAM dan Pemerintah RI, yaitu Uni Eropa dan ASEAN.
Skripsi ini menganalisa tentang peran yang dilakukan Aceh Monitoring Mission
dalam upaya peacebuilding di Aceh pada periode tahun 2005-2006, melalui usaha-usahanya
sebagai mediator dan tim pemantau pelaksanaan MoU Helsinki dengan menggunakan
beberapa konsep yakni peranan, peace building, organisasi internasional dan teori resolusi
konflik. Dari hasil analisa yang menggunakan beberapa teori dan konsep dapat disimpulkan
bahwa lembaga pemantau dalam proses implementasi perjanjian perdamaian memang
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta, atas segala bimbingan-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "Peranan Aceh
Monitoring Mission dalam Upaya Peace Building di Aceh tahun 2005-2006".
Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)
utnuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 30 tahun di Aceh.
MoU ini juga menjadi dasar bagi Uni Eropa dan ASEAN utnuk membentuk lembaga
pemantau untuk mengawasi implementasi MoU di Aceh. Aceh Monitoring Mission
menjalanan misi di Aceh selama 15 bulan, banyak kalangan mulai dari sipil hingga
pengamat politik menilai bahwa AMM berhasil membawa kedua belah pihak unt
mengimplementasikan dengan baik MoU Helsinki. Namun, tidak sedikit juga yang
menilai bahwa faktor-faktor yang dapat menggangu jalannya perdamaian ini belum
seluruhnya dapat dihilangkan dan memiliki kemungkinan untuk muncul kembali pasca
kepergian AMM. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian ini.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi
ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama Kepada bapak Teguh
Santosa MA selaku pembimbing, yang sangat sabar meluangkan waktunya untuk
berbagi pengetahuan dan juga saran serta koreksi kepada penulis; kepada seluruh staf
pengajar program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta; dan juga kepada dosen penguji skripsi bapak Agus Nilmada Azmi
Msi dan bapak Drs. Aiyub Mochsin MA yang telah meluangkan waktunya untuk
Erdiana beserta onah, Sandi Banta Hidayat S.Kom dan Nabilla Intan Medina atas
dukungan, canda tawanya. Kepada calon anakku dan suami terimakasih atas cinta kasih,
kesabaran , dukungan, dan pengertiannya selama penyelesaian skripsi ini.
Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan
di program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta ; HI2008c, HMI KomFISIP serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak
dapat disebutkan satu per satu, pada program studi Hubungan Internasional Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 14 Januari 2014
vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii
LEMBAR PENGESAHAN ... iv
ABSTRAK ... v
KATA PENGANTAR ... vi
DAFTAR ISI ... vii
DAFTAR TABEL ... ix
BAB I Pendahuluan ... 1
A. Latar belakang masalah ... 1
B. Pertanyaan penelitian... 7
C. Kerangka pemikiran ... 7
D. Metode penelitian ... 14
E. Sistematika penulisan ... 15
BAB II Konflik Aceh ... 17
A. Identitas keacehan ... 17
B. Latar belakang konflik ... 20
C. Perlawanan kaum nasionalis Aceh ... 22
1. Pemberontakan Daud Beureureh... 23
2. Pemberontakan Hasan Tiro dan lahirnya GAM ... 29
D. Resolusi konflik oleh pemerintah RI ... 32
viii
BAB IV Analisa peran Aceh Monitoring Mission dalam Peace Building Process di
Aceh ... 48
A. Demobilisasi dan Decommissioning persenjataan GAM... 48
B. Redeployment TNI dan Polri... 53
C. Amnesti ... 54
D. Reintegrasi GAM ... 58
E. Undang-undang Pemerintahan Aceh ... 63
F. Pengaturan keamanan dan hak asasi manusia ... 69
G. Hambatan dan tantangan AMM ... 73
BAB V Kesimpulan dan saran ... 78
A.Kesimpulan ... 78
B. Saran ... 79
DAFTAR PUSTAKA ... x
Tabel IV.A.1 Statistik perlucutan senjata GAM ... 50
Tabel IV.B.1 Statistik penarikan Pasukan Non-organik TNI/POLRI ... 53
Tabel IV.E.1 Perbandingan UUPA dan Nota Kesepahaman... 65
Tabel IV.F.1 Rekapitulasi tabel kekerasan satu tahun perjanjian damai RI
Sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an, isu keamanan
non-tradisional menjadi fokus utama dalam sistem perpolitikan internasional. Menurut
data yang ada, peperangan yang terjadi pasca Perang Dunia II tercatat dari awal tahun
1949 hingga 2001 terdapat sekitar 143 negara dunia diguncang 761 konflik di mana
diantaranya terdapat 457 kasus konflik yang melibatkan kekerasan. Dari 457 kasus
tersebut, 73.5% merupakan konflik internal yang sebagian besar terjadi di
negara-negara berkembang (the Post-Conflict Fund, 2003).
Isu-isu keamanan tradisional memang masih menyisakan masalah hingga kini
(Steans & Pettiford, 2009:436). meskipun isu keamanan non-tradisional seperti
masalah lingkungan, kemiskinan, populasi, migrasi, terorisme, intervensi
kemanusiaan, kejahatan yang terorganisir dan konflik separatis dapat mempengaruhi
keamanan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini pula
yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Beragam konflik internal
(intra-state conflict) yang terjadi di negeri ini banyak dilatarbelakangi oleh isu-isu etnis,
agama ataupun gerakan separatisme (Abdullah, 2011:87). Hal ini juga menjadi isu
yang menimbulkan konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia hingga memunculkan
pada gerakan separatisme Aceh yang bernama GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
Jika dirunut ke belakang, sebetulnya gerakan separatisme Aceh telah
Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh pada tahun 1957. Pemberontakan ini
didasari oleh rasa kekecewaan rakyat Aceh atas sikap sentralisasi pemerintah pusat
dengan menghapus provinsi Aceh dan memasukkan Aceh menjadi bagian dari
provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut bertolak belakang dengan janji Presiden
Soekarno pasca perang kemerdekaan akan menjadikan Aceh menjadi daerah otonomi
khusus. Namun sebelum hal itu terjadi, pergolakan serta pemberontakan terhadap
gerakan separatis kembali mencuat. Gejolak yang kian memanas antara pemerintah
pusat dengan Aceh, maka cara praktis untuk melunakkan hati rakyat Aceh,
pemerintah pusat kemudian memberikan Aceh dengan status Daerah Istimewa pada
26 Mei 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 (Kawilarang,
2010:159). Pemberontakan Daud Beureureh berakhir pada 9 Mei 1962, ketika
Kolonel M. Jasin Panglima Kodam Iskandar Muda berhasil membujuk Daud
Beureureh untuk turun gunung.
Pada tahun 1976 rakyat Aceh kembali bergolak dengan diproklamirkannya
kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember oleh Hasan Di Tiro. Gerakan serta
perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan yang disebut dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) ini muncul akibat akumulasi ketidakpuasan Aceh terhadap
pemerintah pusat yang dianggap telah berlaku tidak adil disetiap sektor kehidupan
pada masyarakat Aceh, terutama dalam sektor ekonomi (Fahri Ali dkk, 2008:112).
Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landasan ideologi keacehan oleh
Hasan Tiro. Ideologi keacehan ini adalah hasil dari pertautan antara fakta sejarah
agama Islam pertama di Asia Tenggara. Keyakinan Hasan Tiro dengan sejarah
kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri dan didukung oleh melimpahnya
sumber daya alam tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.
Dari awal berdirinya, GAM telah mengalami tekanan dari pemerintah Orde
Baru dengan dilakukannya Daerah Operasi Militer (DOM), keadaan ini membuat
perjuangan serta kekuatan GAM melemah. Sekitar tahun 1980-an GAM mulai
kembali menemukan kekuatannya. Hal ini disebabkan sepanjang tahun 1986 hingga
1989 sebanyak 5000 personil GAM telah mendapat latihan militer di Libya. Aksi-aksi
militer anggota GAM dari alumni Libya ternyata lebih kuat dan lebih variatif (Fahri
Ali dkk, 2008:163). Keadaan ini membuat pemerintah pusat melancaran operasi
militer yang lebih keras dan ofensif, yang dikenal sebagai Operasi Jaring Merah dan
memjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer.
Seiring berjalannya waktu, penanganan konflik yang mengedepankan
pendekatan militer telah menyisakan pelanggaran HAM dalam skala besar, hal
demikian pula perlawanan GAM yang semain ofensif terhadap pemerintah pusat.
Pada akhirnya Pemerintah RI berinisiatif melakukan usaha untuk mewujudkan
perdamaian yakni dengan cara melakukan perudingan. Perundingan yang ditempuh
oleh RI dan GAM tergolong sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi
di Aceh.
Upaya menghadirkan pihak ketiga dalam bentuk perundingan belum pernah
dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Upaya penyelesaian konflik antara
Wahid (1999-2001) dan diteruskan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri
(2001-2005). Dari upaya keseriusan tersebut hadirlah NGO Hendry Dunant Centre
(HDC) sebagai pihak ketiga dan mediator. Hasil dari perundingan ini adalah Jeda
Kemanusiaan (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh). Jeda
kemanusiaan ini adalah usaha untuk mencapai perdamaian dengan rentang waktu
penghentian konflik fisik. Dalam hal ini, Jeda Kemanusiaan I dimulai pada 2 Juni
hingga September 2000, namun dapat diperpanjang hingga 27 September 2000.
Asumsinya adalah bahwa rentang waktu itu cukup untuk mengambil langkah yang
lebih konstruktif dalam perdamaian. Ini dibuktikan dengan munculnya pelaksanaan
Jeda Kemanusiaan II yang berlangsung dari 16 September 2000 hingga 15 Januari
2001. (Hamid, 2008:61-64)
Setelah Jeda Kemanusiaan berlangsung kemudian diteruskan oleh Perjanjian
Penghentian Permusuhan atau yang dikenal sebagai Cessation of Hostilities
Agreement (CoHA) yang ditandatangani pada 9 Desember 2002. Akan tetapi,
perjanjian ini tidak berlangsung lama dikarenakan selama proses perjanjian
diterapkan berbagai kekerasan dan bentrokan antara Tentara RI dan GAM tidak
mengalami penurunan (Hamid; 141). Maka, melalui Keputusan Presiden Nomor 28
tahun 2003 yang ditandatangani pada 19 Mei, Presiden Megawati memberlakukan
Darurat Militer di Aceh dengan mengirimkan 40.000 pasukan Tentara Nasional
Indonesia dan 14.000 personel Polisi (Kawilarang, 2008;169)
Sejak berlangsungnya pernyataan Keadaan Bahaya oleh Megawati, pada
menggemparkan dunia internasional yang menyebabkan sekitar 230.000 jiwa
meninggal dunia, 36.786 jiwa hilang, dan 174.000 jiwa tinggal di tenda pengungsian.
Sekitar 120.000 rumah hancur, 800 km jalan dan 260 jembatan rusak, 639 fasilitas
kesehatan hancur serta 2.224 sekolah hancur. Sejak peristiwa itu pula
organisasi-organisasi international mulai masuk ke Aceh untuk memberikan bantuan kepada
korban Tsunami. Walaupun pada awalnya perhatian dunia internasional lebih tertuju
kepada bantuan kemanusiaan, akan tetapi lama kelamaan bantuan secara politik juga
menjadi sorotan dunia internasional, yaitu mengusahakan perdamaian antara RI dan
GAM yang berkonflik selama kurang lebih 30 tahun (Kawilarang, 2010:177).
Adapun salah satu organisasi internasional yang turut memberikan bantuan
baik sosial ataupun politik di Aceh adalah Uni Eropa. Kontribusi Uni Eropa terhadap
proses perdamaian Aceh, telah dimulai sejak terjadinya bencana Tsunami. Program
bantuan kemanusiaan ini dilanjutkan dengan komitmen Komisi Eropa dan negara
anggota Uni Eropa untuk mendukung terciptanya perdamaian dan pembangunan
Aceh setelah konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yaitu dengan
menghadirkan Crisis Management Initiative (CMI) sebagai mediator antara
pemerintah RI dan GAM untuk mencapai kesepakatan damai.
Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, pada 15 Agustus
ditandatanganilah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di
Helsinski yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ; a) Penyelenggaraan
Amnesti dan Reintegrasi Mantan Kombatan ke dalam Masyarakat, d) Pengaturan
Keamanan, e) Pembentukan Misi Monitoring Aceh, f) Penyelesaian Perselisihan.
Salah satu langkah mendesak yang dilaksanakan seusai ditandatanganinya
MoU Helsinski adalah pembentuan Aceh Monitoring Mission (AMM) atau Misi
Pemantau Aceh. AMM mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan komitmen
para pihak yang bersepakat dalam MoU Helsinski. Dalam MoU Helsinski pasal 5
ayat 1 disebutkan : “Misi Pemantau Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan
Negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan
komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.”.
Ada beberapa Mandat yang harus dijalankan oleh AMM sesuai dengan Nota
Kesepahaman yaitu memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan
daerah Aceh, reintegrasi mantan kombatan GAM, mengadakan pemilu daerah di
Aceh, penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI, memberikan
bantuan dalam penangananhak asasi manusia, memutuskan kasus amnesty yang
disengketakan dan membentuk serta memelihara hubungan baik dengan pihak yang
bertikai.
Untuk lebih jauh dalam menganalisis beberapa peran AMM lainnya, maka
diperlukan analisis komprehensif terhadap peran AMM. Yaitu dengan menganalisa
mandatnya sesuai yang dituangkan dalam Nota kesepahaman (Mou) Helsinki. Di lain
pihak juga penelitian ini bertujuan untuk mengalisa peran AMM selama melakukan
menjadikan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mematuhi Nota Nesepahaman
Helsinski.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah pokok
permasalahan yaitu :
Bagaimana peranan yang dilakukan Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam
upaya Peace building di Aceh pada tahun 2005-2006 ?
C. Kerangka pemikiran
Pada penelitian ini, analisa mengenai peran Aceh Monitoring Mission dalam
upaya peace building di Aceh tahun 2005-2006 akan menggunakan dua teori dan dua
konsep. Teori yang akan menjadi dasar penelitian ini adalah resolusi konflik dan
organisasi internasional. Sedangkan dua konsep yang akan menjadi pisau analisis
dalam penelitian ini adalah peranan dan peace building.
Konflik adalah situasi dan kondisi dimana terjadi pertentangan dan kekerasan
dalam menyelesaikan masalah antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat
dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan organisasi etnis di suatu
wilayah. Berakhirnya Perang Dingin, telah mengakibatkan perubahan dalam peta
konflik dunia, dimana konflik lebih banyak terjadi dalam negara (intrastate) daripada
antar negara (interstate).
Tipologi konflik di Indonesia dapat dilihat dalam realitas konflik yang cukup
a) Konflik Horisontal, merupakan konflik yang terjadi antar kelompok agama,
kelompok pendatang dengan penduduk asli, kelompok etnis atau suku dan
organisasi bisnis yang berada di lokasi setempat.
b) Konflik Vertikal, merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dan
kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Asumsinya, konflik terjadi
karena merupakan akibat dari proses pembuatan kebijakan (policy)
pemerintah yang tidak partisipatif dan pada tahap berikutnya memunculkan
perbedaan pendapat, pertentangan, kekerasan serta separatisme (Hadi dkk
2005).
Dalam rangka mencari penyelesaian yang efektif dari sebuah konflik internal
maka perlu mengidentifikasikan sebab-sebab fundamental suatu konflik. Levy (Hadi
dkk 2007:24) berupaya menemukan variabel independen dari suatu konflik dengan
mengkaji sumber-sumber konflik dari empat level analisa yaitu level sistemik, sosial
kemasyarakatan, organisasi birokrasi dan individual. Penyelesaian konflik dapat
tercapai apabila sumber-sumber konflik disetiap level analisa yang berbeda dapat
ditangani secara optimal. Di pihak lain Burton melihat bahwa sumber-sumber utama
konflik berhubungan dengan keterkaitan yang berkesinambungan antara struktur
sosial, institusi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarmanusia. Identifikasi dari
kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik adalah hal yang
sangat penting. Berbagai macam sebab terjadinya konflik internal termasuk gerakan
separatisme, seperti perbedaan etnis, faktor historis, perbedaan agama dan
Resolusi konflik merupakan suatu proses penyelesaian masalah dalam
konflik. Pengambilan keputusan adalah bagian yang penting dalam resolusi konflik.
Sebelum meyimpulkan analisis pengambilan keputusan, ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan, seperti mengenai perbedaan persepsi pihak yang bertikai,
perselisihan yang dinegosiasikan, isu-isu yang krusial untuk mencari penyelesaian.
Resolusi konflik sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam konflik
dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengkontrol konflik (Bavly,
2002:6)
Tujuan paling mendasar dari resolusi konflik (Sukma, 2009) adalah
tercapainya perdamaian yang bukan hanya menyangkut masalah militer, politik dan
ekonomi saja, tetapi juga harus menyangkut pemenuhan dari berbagai kebutuhan
ekonomi, aspirasi dan hak dari pihak-pihak yang bertikai. Usaha menciptakan
perdamaian berarti usaha mengurangi tingkat permusuhan dan kekerasan,
memanusiakan pihak lain, membangun rasa saling percaya dan merespon kebutuhan
dan kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai. J.Galtung menyatakan bahwa usaha
perdamaian terdiri dari, membuat perdamaian (peace making), memelihara
perdamaian (peacekeeping) dan membangun perdamaian (peacebuilding) (Bavly,
2002)
Peace building adalah kegiatan menciptakan perdamaian mulai dari bawah
sampai ketingkat para pemimpin (bottom up). Menurut Fisher, Peace Building
menyangkut usaha-usaha meningkatkan hubungan dari pihak-pihak yang bertikai
persepsi yanglebih akurat, menciptakan iklim yang lebih positif dan menciptakan
keinginan politik yang tidak bertahan lama karena perdamaian yang lebih kuat untuk
dapat melakukan perundingan-perundingan yang konstruktif ditengah adanya
perbedaan-perbedaan (Bavly 2002:8). Peace Making adalah usaha-usaha yang
dilakukan oleh negara-negara atau perwakilan-perwakilan resmi melalui kegiatan
diplomasi untukmencapai suatu penyelesaian dari pihak-pihak yang bertikai.
Sedangkan Peace Keeping adalah kegiatan intervensi dari pihak ketiga untuk
memisahkan pihak-pihakyang berperang dan menjaga agar tidak terjadi tindakan
kekerasan.
Konsep peace building mulai banyak digunakan setelah Sekretaris Jenderal
PBB Boutros Boutros-Ghali (1992: 11) mengeluarkan laporannya, An Agenda for
Peace, pada tahun 1992. Dalam laporan tersebut, peace building dipahami sebagai
serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk “mengidentifikasikan dan mendukung
berbagai struktur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian
sehingga dapat mencegah terulangnya kembali konflik”. Namun, dalam
perkembangannya, definisi peace building yang dikembangkan Boutros-Ghali
kemudian mencakup juga berbagai upaya untuk menanggulangi akibat-akibat yang
ditimbulkan oleh konflik, menghilangkan akar penyebab konflik (root causes of
conflict), dan membuat negative peace atau ketiadaan kekerasan berubah menjadi
positive peace dimana masyarakat merasakan keadilan social, kesejahteraan ekonomi
Upaya penyelesaian suatu konflik dapat dapat dilihat dalam kerangka studi
mengenai resolusi konflik yang bertujuan untuk menelaah berbagai macam situasi,
pemerintahan atau kegiatan organisasi internasional yang dapat mencegah krisis
menjadi perang, atau jika perang sudah terjadi akan berupaya mengakhiri perang dan
melakukan upaya perdamaian hingga keakarnya.
Secara sederhana, Organisasi internasional adalah pihak yang berada di luar
konflik antara dua pihak atau lebih yang bertikai mencoba untuk membantu mereka
mencapai penyelesaian masalah melalui berbagai kesepakatan (Pruit dan Rubin,
2004:374). Tujuan masuknya organisasi internasional adalah merubah situasi konflik
destruktif dan menurunkan tingkat eskalasinya, mengalihkan para pelaku onflik
menuju ke arah penyelesaian konflik dan mendamaikannya.
Hal utama yang dituntut dari keterlibatan organisasi internasional adalah sikap
nertal untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai. Pada awalnya, netralitas
atau impartial ini menjadi syarat mutlak keberhasilan resolusi konflik. Dalam
perjalanannnya kemudian, hal tersebut justru melahirkan dilema dan berjalan serba
salah. Di satu sisi diperlukan demi terlaksananya program secara fair, tetapi di sisi
lain tidak jarang netralitas itu sendiri justru membantu agresor atau pihak yang kuat
dalam memerangi pihak yang lemah. Netralitas organisasi internasional dituntut
dalam persoalan identitasi saja (Stedman, 1996:363). Keberpihakan terhadap
kelompok lemah dituntut dalam segala atifitas resolusi konflik, baik sejak pencegahan
sampai pada postconflict building, tidak hanya pada aktifitas militer tetapi juga
Titik paling krusial dalam menjalankan perdamaian yang berkelanjutan tahap
implementasi dari kesepakatan damai. Dari sekian banyak perjanjian damai yang
berhasil dilaksanakan, sebagian besar juga gagal dalam tahap ini. Ini menunjukkan
bahwa tahap implementasi jauh lebih sulit daripada menghasilkan sebuah
kesepakatan. Keberhasilan implementasi menjadi suatu keharusan dari suksesnya
sebuah resolusi konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan semua penyebab konflik
dan juga sangat tergantung dari kemampuan institusi-institusi yang ada dalam negara
dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik (Rasmussen, 1997:40). Institusi
tersebut adalah lembaga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan monitoring
perdamaian yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat konflik
atau melibatkan organisasi internasional.
Menurut Kriesberg (1998), implementasi akan berhasil manakala ada sebuah
organisasi internasional kuat yang bertugas mengontrol jalannya kesepakatan damai
dengan mengkombinasikan berbagai metode baik kekuatan militer maupun ekonomi
dan politik (h. 99). Dengan catatan, metode kekerasan atau penggunaan kekuatan
militer harus dibatasi dan tidak bersifat berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat
konflik (Kriesberg, 1998:100). Hal ini menjelaskan bahwa sebelum perdamaian
benar-benar tercipta dengan baik dan stabil perlu ada lembaga monitor di area
konflik.
Dalam kaitanya dengan proses perdamaian yang terjadi di Aceh, NGO seperti
Aceh Monitoring Mission (AMM) merupakan sebuah organisasi internasional yang
Aceh Darussalam. Peranan AMM dalam penyelesaian konflik tersebut merupakan
perilaku politik yang diharapakan dari pihak lain. Peran AMM dalam proses
perdamaian di Aceh merupakan peran yang di dapat karena permintaan dari kedua
belah pihak, yaitu GAM-RI. Dengan kata lain peran didapat karena diundang oleh
pihak lain bukan inisiatif sendiri.
Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran adalah seperangkat
tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental (Perwita
dan Yani, 2005:29).
Peranan (role) dapat didefinisikan sebagai berikut: Perilaku yang di harapkan
dari seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:132). Peranan dapat
dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu
posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan.
Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (action), tetapi juga termasuk
harapan mengenai motivasi (motivation), kepercayaan (beliefs), perasaan (feelings),
sikap (attitudes) dan nilai-nilai (values) (Perwita dan Yani, 2005:30).
Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam
menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku
politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan
akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan (Mas’oed,
1989:45).
Mengenai sumber munculnya harapan tersebut dapat berasal dari dua sumber,
yaitu:
1. Harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik.
2. Harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan
yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa
yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan
(Mas’oed, 1989:46-47).
Jadi, peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh
struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur-struktur itu
dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga di pengaruhi oleh
situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran.
D. Metode Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian pustaka berupa studi
literatur dengan memilih data yang relevan untuk mendukung penelitian yang diambil
dari buku referensi, artikel, jurnal, buku-buku ilmiah, internet, media massa dan
majalah.
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif.Cara pengumpulan data
dilakukan melalui teknik pengumpulan data sekunder atau library research. Dalam
hal ini, data yang diperlukan akan dihimpun dari berbagai buku bacaaan/literatur,
lembaga penelitian bidang konflik, artikel media baik dari surat kabar maupun
majalah dan dari laman internet.
Dalam menganalisa data, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai
berikut : pertama, menghimpun literatur dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai
sumber data dan informasi yang diperlukan. Kedua, memilah atau mengklasifikasikan
data atau informasi secara sistematis. Ketiga, mengadakan analisis dengan metode
dan teknik pengumpulan data yang tepat untuk dikaji berdasarkan kerangka dasar
teori. Keempat, pencapaian kesimpulan dari penelitian.
E. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah penulisan, skripsi ini membagi pembahasan menjadi
beberapa BAB, Sub Bab, dan Sub-sub Bab yang diuraikan secara singkat dalam
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Kerangka Teori
D. Metode Penelitian
E. Sistematika Penulisan
Bab II Konflik Aceh
A. Identitas Keacehan
B. Latar Belakang Konflik Aceh
1) Pemberontakan Daud Beureureh
2) Pemberontakan Hasan Tiro dan Lahirnya GAM
D. Resolusi Konflik Aceh Oleh Pemerintah RI
E. Upaya Perdamaian Dari Crisis Management Initiative
Bab III Profil Aceh Monitoring Mission
A. Profil AMM
B. Struktur dan Mekanisme kerja AMM
C. Tugas dan Mandat AMM
Bab IV Analis Peran Aceh Monitoring Mission dalam Peace Building Process di
Aceh
A. Demobilisasi dan Decommisioning persenjataan GAM
B. Redeployment TNI dan POLRI
C. Amnesti
D. Reintegrasi GAM
E. Undang-Undang Pemerintahan Aceh
F. Pengaturan keamanan dan Hak Asasi Manusia
G. Hambatan dan Tantangan AMM
Bab V Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar Pustaka
BAB II
KONFLIK ACEH
Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik Aceh sangatlah penting
dipaparkan terlebih mengenai identitas keacehan, guna mendapatkan pemahaman
menyeluruh (holistic) dari apa yang melatar-belakangi terjadinya konflik Aceh.
Untuk itu penting menelusuri identitas keacehan sebagai variable penelusuran guna
mengetahui Latar Belakang Konfilk Aceh. Setelah itu barulah menjelaskan
perlawanan Kaum Nasionalis Aceh serta upaya Pemerintah dalam Resolusi Konflik
dalam konflik Aceh yang menghasilkan Nota Kesepahaman Helsinski sebagai
landasan terbentuknya Aceh Monitoring Mission dalam membangun perdamaian di
Aceh.
A. Identitas Keacehan
Aceh merupakan sebuah provinsi di Indonesia, lebih tepatnya Aceh terletak di
ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu
kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa.
Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan
oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah
utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera
Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan
memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad
ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di
kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan
keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah
Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah
yang sangat menjunjung tinggi nilai agama (Time Magazine, 15 Februari 2007).
Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka
hidup sesuai syariah Islam (Islamic studies: 2013).
Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak
bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah
yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di
sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane diAceh Tenggara sampai Ulu
Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung
Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.
Identitas daerah yang tersebar di Indonesia mempunyai ciri dan khas
tersendiri di setiap wilayahnya, salah satunya yaitu Aceh. Aceh merupakan suku
bangsa Indonesia yang dikenal memiliki identitas dan sejarah yang khas. Sebutan
sebagai Serambi Mekah bagi Aceh tidak hanya berarti sebagai pintu masuk pertama
penyebaran agama Islam di Indonesia, tetapi juga mempunyai konotasi tentang
tingginya pengaruh nilai-nilai Islam dalam adat istiadat dan semangat juang
dalam memaknai istilah Serambi Mekkah (Reid, 2006: 38-39). Pertama, pengertian
tersebut terindikasi pada naskah kuno karya Ar-Raniri, terminologi Serambi Mekkah
yang pertama ini merujuk dengan pengertian Aceh merupakan Mekkah-nya kawasan
Timur (Mecca of the East). Kedua, pengertian ini yang merujuk pada pandangan
Snouck Hurgronje (ICG 2001:17) , yang mengartikan istilah Serambi Mekkah
Sebagai “gerbang ke Tanah Suci” (The Gate to the Holy Land). Penyebutan ini
disebaban terdapatnya fakta bahwa daerah Aceh sering digunakan oleh para calon
jemaah haji dari kepulauan di Timur sebagai tempat persinggahan sebelum mereka
melanjutkan perjalanannya ke Mekkah.
Dari pengertian di atas, terdapat pemahaman yang sangat khas antara
pengertian Aceh dengan Serambi Mekkah yaitu identitas keislaman (Islamic Identity).
Pada akhirnya ketika kita mengucapkan istilah Aceh dengan Serambi Mekkah maka
timbul pula pemahaman bahwa Aceh merupakan kawasan Islam di wilayah timur. Di
lain pihak, julukan Serambi Mekkah yang melekat pada wilayah Aceh dengan mudah
pula diasosiasikan dengan identitas keislaman Aceh. Identitas Islam yang sudah
melekat jauh sebelum Indonesia merdeka inilah dalam perjalanannya ternyata
menjadi pemicu konflik antara Aceh dan Republik Indonesia. Identitas keislaman
Aceh tidak hanya digunakan oleh para elit politik aceh untuk membangun sentimen
kolektif masyarakat ketika berhadapan dengan kelompok lain, tetapi juga
dimanfaatkan pemerintah pusat sebagai pilihan bagi Aceh dalam kerangka kebijakan
B. Latar Belakang Konflk Aceh
Sejak berlangsungnya konflik Aceh melalui pemberontakan yang dipimpin
oleh Daud Beureueh pada tahun 1957 (Kawilarang, 2010:159), beragam dampak
yang ditimbulkan amatlah parah pada masyarakat sipil Aceh. Ribuan rakyat sipil tak
berdosa telah gugur, mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim.
Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan
pekerjaan dan mata pencaharian. Ratusan sekolah terbakar, sehingga mengganggu
proses pendidikan. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses
terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.
Kekecewaan masyarakat Aceh diawali ketika Teungku Daud Beureuh masuk
dalam “Daftar Hitam” yang ingin disingkirkan oleh Pemerintah Pusat. Seperti kita
ketahui Teungku Daud merupakan salah satu tokoh rakyat Aceh dalam mengusir
penjajah dengan ikut sertanya Teungku Daud bersama Republik dengan cara
mengumpulkan dana untuk melawan penjajah. Janji dari Presiden Soekarno untuk
memberikan kebebasan rakyat Aceh menerapkan syariat Islam tidak ditepati, semakin
membuat pedih rakyat Aceh. Kekecewaan rakyat Aceh yang tidak terbendung
akhirnya menimbulkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Pada tahun 1953. pemberontakan ini dapat ditumpas pada tanggal 26 Mei 1959 ketika
Aceh diberikan otonomi luas, terutama dalam bidang agama, adat dan pendidikan.
Konflik yang terjadi di Aceh khususnya Gerakan Separatisme Aceh berlatar belakang
tentang perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Aceh pada tahun 1819 dan
merdeka, hal inilah yang membuat GAM berusaha mengembalikan kedaulatan
tersebut kepada Kesultanan Aceh.
Aceh yang kita ketahui merupakan provinsi yang mempunyai ciri khas yakni
rakyat Aceh mempunyai identitas social-kultural dan religi yang kuat. Salah satu
alasan terjadinya pemberontakan Teungku Daud adalah keinginan Teungku Daud
untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, yang pada saat itu disetujui oleh pemerintah
pada saat penumpasan pemberontakan DI/TII. Namun rezim Orde Baru membuat
sebuah keputusan yang lagi-lagi membuat kekecewaan di hati rakyat Aceh (Reid:
2006, 23).
Keputusan yang diambil oleh Rezim Orde Baru dengan model politik
sentralisme adalah melalui UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan
Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, Orde
membuat penyeragaman di semua daerah tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal (Tim
Peneliti LIPI, 2007, 54-55).
Akibat kedua UU tersebut, secara otomatis keistemewaan Aceh akan
tereliminasi. Syariat Islam yang sudah menjadi ciri khas dari rakyat Aceh menjadi
hilang karena lembaga-lembaga adapt yang ada sejak lama di Aceh harus digantikan
oleh struktur pemerintahan modern yang diinginkan oleh pemerintahan Orde Baru.
Hal inilah yang membuat kekcewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat
semakin besar.
Faktor ekonomi juga turut serta menjadi penyebab terjadinya konflik yang
Pemerintah ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas politik. Aset sumber daya alam di Aceh dieksploitasi dalam
konteks pembangunan ini. Pabrik LNG dan pupuk Iskandar Muda yang dibangun di
Aceh maju pesat. Bahkan Indonesia menjadi salah satu eksportir LNG terbesar dan
90% dari produksi pupuk ditujukan bagi ekspor.
Namun, berdasarkan kebijakan yang diambil pada masa rezim Orde Baru
yang sentralisasi, ekonomi Aceh terkonsentrasi oleh power dan otoritas yang berpusat
di Jakarta, maka pembangunan di Aceh tidak mengalami kemajuan yang signifikan
bila dibandingkan keuntungan pusat yang diperoleh dari wilayah Aceh. Akibat dari
pembangunan yang terlalu banyak di Jakarta adalah rakyat Aceh mengalami
kesengsaraan dan kesusahan dimana di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur tercatat
2.275 desa miskin pada tahun 1993 (Hadi 2007:50-51).
Hal itu semua membuat rakyat Aceh sadar bahwa yang seharusnya menikmati
hasil dari sumber daya alam adalah masyarakat Aceh sendiri bukan pusat. Hal inilah
yang membuat rakyat Aceh semakin kecewa dengan pemerintah pusat. Kesadaran
rakyat Aceh tentang ketidakadilan pusat terhadap Aceh dimanfaatkan oleh GAM,
dimana GAM memperoleh kekuatan setelah industri gas dan minyak di Aceh Utara
berdiri pada tahun 1970.
C. Perlawanan Kaum Nasionalis Aceh
Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh telah tercatat sebanyak dua kali
kepada Pemerintah Pusat. Pertama, pemberontakan yang dipimpin oleh Teuku M.
Beureueh merupakan tokoh ulama terkemuka di Aceh yang mendirikan dan menjadi
ketua PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 (Reid, 2005:275).
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, PUSA berhadapan dengan kelompok
Uleebalang dalam upaya mereka menguasai setiap sektor kekuasaan dan
pemerintahan di Aceh.
Pertentangan kaum ulama dengan kaum Uleebalang tersebut menimbulkan
konflik yang belangsung dari 22 Desember 1945 sampai dengan 13 Januari 1946
yang dikenal dengan insiden Cumbok.
1. Pemberontakan Daud Beureueh
Setidaknya ada tiga alasan utama pemberontakan yang dipimpin oleh Daud
Beureueh ini. Pertama, terkait dengan konsep dasar kenegaraan, terutama yang
berhubungan dengan dasar dan bentuk negara, sebelum kemerdekaan 17 Agustus
1945, wacana politik yang berkembang di kalangan para tokoh pejuang kemerdekaan
saat itu adalah mengenai dasar negara yang akan didirikan (Latif, 2011:65). Para
tokoh yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia), yang juga diwakili oleh kelompok Islam, pada 18 Agustus
1945 akhirnya menyetujui Pancasila sebagai Dasar Negara (Latif, 2011: 67-95).
Dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 yang dalam Mukadimah
tidak memuat tujuh kata dalam sila pertama seperti yang terdapat pada Piagam
Jakarta, yaitu “ dengan kewajiban menjalanan syariat Islam bagi pemeluknya” pada
baik dalam hal yang sangat prinsipil, yaitu dasar negara. Hal inilah yang menjadi
awal mula kekecewaan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari kelompok Islam.
Daud Beureueh sendiri pada mulanya dapat menerima realitas politik bahwa
Indonesia yang baru didirikan berdasarkan Pancasila. Sekalipun rakyat Aceh
menginginkan Negara yang berdasarkan Islam, para pemimpin Aceh mampu
meyakinkan rakyatnya bahwa untuk saat itu, ketika Indonesia yang baru lahir masih
menghadapi perjuangan fisik melawan Belanda, sebaiknya untuk sementara
menerima dahulu dan mendukung Indonesia yang berdasarkan Pancasila sampai nanti
diadakan pemilihan umum (Ibrahimy, 2001: 43).
Selain itu, kesediaan Daud Beureueh menerima konsep Negara Indonesia
yang berasaskan Pancasila lebih disebabkan oleh janji Presiden Soekarno yang
diucapkan pada kunjungannya yang pertamakali ke Aceh yakni memberikan
kebebasan kepada Aceh dalam menjalankan syariat Islam dan otonomi khusus sesuai
dengan syariat Islam (Santosa, 2006:142). Untuk menindaklanjuti janji Presiden
Soekarno tersebut, pada 1949 beberapa tokoh Aceh menghadap Wakil Perdana
Menteri Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu juga menjadi Kepala Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia/PDRI guna mendesak Pemerintah Pusat guna
membentuk Provinsi Aceh yang otonom dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
Akhirnya permintaan ini dikabulkan dengan dikeluarkannya Peraturan Wakil Perdana
Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.
8/Des/WKPM 17 Desember 1949 yang menyataan Aceh sebagai Provinsi dan Daud
Keadaan berubah setelah Hindia Belanda resmi membubarkan diri pada 27
Desember 1945 dan RI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam
pertemuan Dewan Menteri RIS pada 8 Agustus 1950 disepakati Indonesia terdiri dari
10 Provinsi hal ini menjadikan Aceh dan Sumatera Utara dijadikan 1 Provinsi. Pada
akhir tahun 1950, Mohammad Natsir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana
Menteri mengumumkan Provinsi Aceh dilebur menjadi satu dengan Provinsi
Sumatera Utara, sedangkan Daud Beureueh diangkat menjadi pejabat tinggi di
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Keputusan ini sangat mengecewakan
masyarakat Aceh karena pusat pemerintahan daerah Aceh berubah bahkan peralatan
kantor dan mobil-mobil dinas pemerintahan yang berada di Banda Aceh dibawa ke
Medan. Padahal semua inventaris tersebut dibeli secara swadaya oleh masyarakat
Aceh.
Kekecewaan Daud Beureueh terhadap Pemerintah Pusat mencapai puncaknya
ketika Presiden Soekarno pada 27 Januari 1953 berpidato di Amuntai, Kalimantan
Selatan, yang menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin menggunakan Islam
sebagai dasar Negara. Pernyataan ini sekaligus menyatakan bahwa Negara Indonesia
berdasarkan pada Pancasila, bukan Islam. Dengan pernyataan Soekarno ini semakin
jelas bagi para tokoh Aceh bahwa Indonesia tidak memberikan peluang bagi Negara
untuk menggunakan Islam sebagai dasar Negara dan pupus juga harapan rakyat Aceh
utnuk menerapkan syariat Islam di Aceh. Hal ini telah membuat Daud Beureueh
kecewa, sehingga pada 21 September 1953 Daud Beureueh menyatakan Aceh
(NII) mengikuti Kartosoewirjo lalu membubarkan Divisi X TNI yang berada di Aceh.
Pernyataan ini terjadi setelah kongres ulama di Titeue Pidie. Setelah membubarkan
Divisi X TNI, sejumlah pasukan TNI bergabung menjadi tentara Islam di bawah
komando Daud Beureueh.
Kedua, terkait dengan politik sentralisasi yang dijalankan oleh Pemerintah
Pusat pada masa-masa awal Republik berdiri. Kebijakan setralisasi yang membawa
kembali Indonesia menjadi negara kesatuan ini dapat dipahami dalam konteks situasi
politik nasional saat itu, yaitu selama periode 1949 sampai 1950. Pada saat itu
Indonesia sedang menghadapi masa perjuangan fisik dalam mempertahankan
kemerdekaan. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, Belanda
menjalankan politik pecah belah dengan membentuk negara-negara yang berdiri
sendiri dan tidak tergabung dalam federasi yaitu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,
Dayak Besar, Daerah Banjar, Federasi Kalimantan Tenggara, Negara Kalimantan
Timur, Bangka, Belitung, dan Riau (Awaludin 2009).
Di tengah situasi politik yang masih labil dan eksistensi RI yang sangat rapuh
itu menjadikan RI lebih mementingkan upaya konsolidasi nasional dan memperkuat
kesatuan wilayah RI ke dalam sistem kenegaraan yang solid. Di tengah situasi yang
penuh dengan semangat perjuangan mempertahanan kemerdekaan dan ditambah
dengan dominasi kaum nasionalis dalam percaturan politik saat itu, maka muncul
desakan membubaran Negara federasi dan membentuk Negara kesatuan. Namun,
harus dibayar mahal dengan hilangnya Provinsi Aceh yang dinilai sebagai
representatif identitas keislaman.
Alasan ketiga yang mendorong pemberontakan Daud Beureueh adalah tidak
terakomodasinya nilai Islam dalam pemerintahan di Aceh. Nilai-nilai Islam memang
telah lama berakar dalam kehidupan rayat Aceh dan mereka tetap mengharapkan
bahwa suatu saat Islam dapat kembali menjadi dasar dalam hidup berpemerintahan di
Aceh.
Aspirasi dan identitas Islam yang begitu mengakar di kalangan rakyat sejak
ratusan tahun, dan mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar
Muda (1607-1636), menemukan momentum baru untuk dimanifestasikan kembali
dalam tatanan kehidupan masyaraat Aceh ketika Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 (Ibrahimy, 2001:43). Namun, ketika
Soekarno menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara nasional yang berasaskan
Pancasila bukan Islam, Daud Beureueh semakin yain bahwa pemimpin pusat telah
menyimpang dari jalan yang benar. Republik Indonesia tidak berkembang menjadi
Negara yang berdasarkan Islam, satu-satunya kemungkinan yang terkandung dalam
prinsip Ketuhanan Yang Masa Esa, sila pertama Pancasila (Santosa, 2006:152).
Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa ide Islam yang diyakini oleh Daud
Beureueh tidak hanya pas dalam lingkup Aceh, namun lebih jauh dari itu. Daud
Beureueh menilai bahwa Indonesia pun secara keseluruhan mestinya berdasarkan
Islam. Pada titik inilah Daud Beureueh membentur kenyataan politik bahwa aspirasi
Indonesia tidak mungkin akan mengakomodasi aspirasi Islam yang selama ini
menjadi identitas Aceh.
Dengan adanya kepastian bahwa Indonesia tidak akan menolerir bentuk
pemerintahan daerah yang berlandaskan Islam, pemimpin Aceh sudah dapat
memperkirakan bahwa pemerintah pusat akan menekan Aceh, baik dalam urusan
syariat Islam maupun dalam hal kepemerintahan. Kekhawatiran itulah yang akhirnya
memaksa banyak tokoh Islam di Aceh ikut mendukung pemberontakan Daud
Beureueh (Aguswandi & Large, 2009:3).
Pemberontakan Daud Beureueh tidak berhenti meski Pemerintah Pusat
akhirnya mengembalikan Aceh sebagai tersendiri yang terpisah dari Provinsi
Sumatera Utara dengan Undang-undang No. 24/1956. Undang-undang tersebut sama
sekali tidak menyebut pemberian otonomi Aceh dalam pemberlakuan syariat Islam
(Syukriy, 2009:3).
Seiring berjalannya waktu, tiga tahun setelah itu barulah perubahan status
mulai diberikan. Status “Daerah Istimewa” baru diberikan untuk Aceh pada 26 Mei
1959 melalui Keputusan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959, yang isinya antara lain
Daerah Istimewa Aceh dapat melaksakan otonomi daerah yang seluas-luasnya
terutama dalam bidang agama, pendidikan, dan peribadatan (Nurrohman, 2006:4).
Pemberontakan Daud Beureueh baru berakhir pada 9 Mei 1962, ketika Kolonel M.
Jasin, Panglima Kodam Iskandar Muda berhasil membujuk Daud Beureuh untuk
2. Pemberontakan Hasan Tiro dan Lahirnya GAM
Perbedaan kedua terkait tujuan pemberontakan. Berbeda dengan
pemberontakan Daud Beureueh yang mulanya hanya menginginkan otonomi di
bidang pendidikan dan penerapan syariat Islam tetapi masih dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemberontakan Hasan Tiro sejak awal
memang bertujuan untuk membentukan Negara Aceh yang merdeka dan terpisahkan
Republik Indonesia (Schulze, 2004:1).
Dalam ungkapan Sukma (2003:149), tujuan pemberontakan Daud Beureueh
sama dengan pemberontakan Darul Islam Aceh yang menginginkan Indonesia
menjadi Negara Islam dan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam. Sedangkan
pemberontakan Hasan Tiro bertujuan untuk memisahkan diri secara utuh dari
Indonesia. Aspirasi untuk merdeka yang memotivasi pemberontakan Hasan Tiro ini
diperkuat juga oleh adanya sentimen nasionalisme Aceh, terkait dengan konstruksi
identitas Aceh yang berdasarkan pada etnik, bahasa, kultur, sejarah dan geografi
(Miller, 2008:12).
Pemberontakan Hasan Tiro ini dipicu oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh
rakyat Aceh dalam hal pengelolaan sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Pusat, di
samping didorong pula oleh sentimen nasionalisme etnik (ethno nasionalism) yang
bertumpu pada kekhasan Aceh dalam hal sejarah, etnisitas, kultur, dan geografi.
Sentiment nasionalisme etnik ini tercermin dari bagaimana Hasan Tiro menarik garis
perbedaan tegas antara Indonesia dan Aceh dengan cara menyebut rakyat Aceh
memperkenalkan konsep bangsa Aceh sebagai lawan dari bangsa Indonesia
(Kawilarang, 2008:157).
Pemberontakan Hasan Tiro ini terjadi pada saat Pemerintahan Soeharto, yang
mana rezim ini terfokus pada masalah pembangunan ekonomi yang membutuhan
stabilitas politik, sehingga Pemerintah Pusat tidak pernah menolerir adanya aspirasi
daerah yang menuntut otonomi, apalagi memisahkan diri. Oleh karena itu, tidak lama
setelah Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah
Pusat mengambil langkah tegas, yaitu dengan melancarkan tindakan militer atau hard
power.
Sejak Hasan Tiro melancarkan pemberontakan terhadap Pemerintahan Pusat
dengan mendeklasikan GAM dan sebelum tercapai perdamaian pada tahun 2005, ada
fase-fase penting yang dialami oleh GAM (Schulze, 2004:4).
Pertama, periode kelahiran (1976-1989), ketika GAM masih merupakan
sebuah kelompok kecil yang beranggotakan kira-kira 70 orang tetapi memiliki ikatan
ideologi yang kuat. Anggota GAM saat itu terdiri dari orang-orang terdidik, seperti
dokter, insinyur, akademi, dan pengusaha. Untuk mematahkan pemberontakan ini,
Soeharto melancarkan operasi militer, sehingga banyak anggota organisasi ini yang
tewas dan pemimpinnya banyak yang dipenjara atau melarikan diri. Pada periode ini,
akibat oprasi militer yang keras dari Pemerintah Pusat, pengikut GAM tercerai-berai
ke berbagai tempat dan mulai melakukan gerakan bawah tanah. Pada tahun 1986
banyak pemuda Aceh yang dikirim oleh Hasan Tiro untuk mengikuti pelatihan militer
Pemerintah Pusat mengirimkan ribuan pasukan ke Aceh dan tidak ada dukungan
internasional terhadap GAM, hingga pada akhirnya Hasan Tiro pindah ke Swedia dan
menjadi warganegara disana.
Kedua, periode kebangkitan GAM (1989-1998). Pada tahun 1989 banyak
pemuda Aceh yang telah mengikuti pelatihan militer di Libya kembali ke Aceh dan
bergabung dengan GAM. Dengan kembalinya pejuang-pejuang yang terampil secara
militer ini GAM mulai mengkonsolidasikan organisasinya, terutama penentuan
struktur dan garis komando organisasi di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh
Timur. Para alumni Libya ini juga merekrut dan melatih ratusan anggota baru
mengenai kemiliteran, sehingga jumlah pengikut GAM bertambah banyak. Pada
tahun inilah perlawanan GAM secara militer menunjukkan peningkatan, sehingga
Pemerintah Pusat melancarkan Operasi Jaring Merah dan menjadikan Aceh sebagai
Daerah Operasi Militer (DOM). Selama DOM ini militer Indonesia menjalankan
operasi pembersihan terhadap penduduk atau desa yagn dicurigai memberikan
bantuan logistic dan tempat perlindungan bagi para gerilyawan GAM. Operasi seperti
ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi penduduk desa, agar tidak
memberikan dukungan kepada GAM (Schulze, 2004:4).
Ketiga, Periode kematangan GAM (1998-2005). Pada periode ini perlawanan
GAM berkurang secara signifikan pada 1991. Pada tahun ini, akibat operasi militer
Pemerintahan Pusat yang keras, dapat dikatakan GAM sebenarnya sudah habis.
Namun demikian, GAM masih bias eksis karena GAM masih memiliki
Di samping itu, GAM masih bias menyuarakan kemerdekaan Aceh karena beberapa
pemimpin mereka melancarkan perjuangan dari Negara tetangga, Malaysiam dengan
dukungan orang Aceh yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri. Sekalipun
secara fisik keberadaan GAM di Aceh jauh berjurang, tindak kekerasan yang
dilakukan tentara justru melahirkan generasi baru di Aceh yang bersimpati terhadap
GAM. Generasi baru inilah yang kelak, ketika Soeharto jatuh pada 1998, menjadi
motor penggerak bagi gerakan massa yang mendesak Pemerintah Pusat untuk
menyelesaikan konflik Aceh.
D. Resolusi Konflik Aceh Oleh Pemerintah RI
Resolusi konflik pada era Soeharto lebih banyak ditangani dengan pendekatan
keamanan (security approach) atau hard power daripada soft power. Pada era
Soeharto tidak pernah ada keinginan untuk menyelesaikan konflik Aceh melalui
cara-cara negosiasi atau soft power. Pemerintah Pusat juga berusaha untuk mencoba
mencari simpati rakyat (winning hearts and minds). Program simpatik seperti ini
dilakukan hanya dalam konteks untuk mencegah agar rakyat Aceh tidak ikut
bergabung dengan GAM. Aspinal dan Crouch (2003:3) mengungkapkan bahwa
hanya sebagian kecil dari elit TNI yang benar-benar memahami konsep
“memenangkan hati rakyat” itu. Bagi sebagian besar elit TNI, pemberian konsesi
kepada rakyat Aceh yang menginginkan merdeka hanya memicu perlawanan yang
lebih kuat.
Pasca jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, gelombang arus reformasi
otoriter menjadi rezim demokratis. Perubahan sistem politik demokratis disertai juga
dengan tuntutan untuk penegakan hukum telah mengubah cara pandang pemerintah
baru. Presiden Habibie melihat bahwa Aceh tidak lagi dianggap sebagai musuh
bangsa Indonesia, melainkan saudara kandung Bangsa Indonesia (Ali, 2008:197).
Pada Mei 1998, muncul gerakan anti-militer dan anti-Jakarta. Di tengah
situasi politik yang tidak berpihak pada TNI dan di tengah derasnya tuntutan
pengungkapan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di Aceh selama era
Soeharto, Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jendral
Wiranto berusaha untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat dengan mencabut
status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998. Di samping pencabutan status DOM,
Jendral Wiranto juga meminta maaf atas perilaku individu TNI selama masa DOM.
Lalu setelah itu Presiden Habibie pun ketika berkunjung ke Aceh pada Maret 1999
juga meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh TNI (Aspinal & Crouch,
2003:6). Perubahan dalam pendekatan untuk menyelesaikan konflik pada era Habibie
mengubah pendekatan penyelesaian konflik yang dilakukan pada Orde Baru yakni
security approach menjadi prosperity approach.
Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada sejumlah tahanan politik
yang terkait dengan GAM, menyalurkan bantuan dana untuk anak yatim dan janda
korban konflik serta memberikan kesempatan kepada anak-anak mantan anggota
GAM untuk menjadi pegawai negeri. Pada masa pemerintahan Habibie juga disahkan
Undang-undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
kewenangan khusus kepada Aceh hanya di bidang pendidikan, agama, adat, dan
peran ulama. Pada masa pemerintahan Habibie inilah titik kebijakan soft power dalam
resolusi konflik di Aceh berawal yang kelak juga akan digunakan pada pemerintahan
setelah Habibie. Namun demikian, Habibie sendiri tidak pernah sempat
menindaklanjuti kebijakannya yang lebih menekankan pada kesejahteraan karena
masa kepemimpinannya yang singkat.
Pada Oktober 1999, Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid
atau yang akrab disapa Gus Dur, yang dikenal sebagai orang yang memiliki
komitmen kuat terhadap demokrasi dan pluralisme. Pada masa kepemimpinannya
Gus Dur menawarkan kepada Aceh tiga opsi, yakni otonomi total (total autonomy) ,
pembagian pendapatan 75% dan 25% antara Aceh dan Jakarta, dan status provinsi
istimewa (Aspinal & Crouch, 2003:9). Pada masa kepemimpinan Gus Dur untuk
pertama kalinya sejak konflik Aceh dimulai pada tahun 1976, Indonesia bersedia
mengadakan dialog dan perundingan dengan GAM yang difasilitasi oleh Henry
Dunant Center (HDC), sebuah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan di
Jenewa, Swiss. Hasil dari perundingan tersebut berakhir dengan ditandatanganinya
dokumen Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh pada 12 Mei 2000
yang berisi antara lain kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan
di Aceh.
Terjadinya perundingan Jeda Kemanusiaan ini menghadirkan perkembangan
penting dalam konflik Aceh, baik bagi Indonesia maupun GAM. Bagi Indonesia
dengan jalan militer. Karena adanya paradigm baru dalam resolusi konflik di Aceh
yakni melalui jalan perundingan, bagi Indonesia sendiri adalah pilihan politik yang
terbaik. Sementara bagi GAM, perundingan Jeda Kemanusiaan memberi tiga arti
penting bagi profil gerakan mereka. Pertama, dari tataran kelembagaan, perundingan
tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam konteks perlawanan terhadap
Pemerintah Pusat. Kenyataan GAM duduk satu meja dengan Pemerintah Indonesia
secara resmi menyodorkan suatu realitas politik baru yaitu eksistensi GAM sebagai
“entitas politik” diakui oleh pemerintah Indonesia. Kedua, dari tataran internasional.
GAM berharap perundingan Jeda Kemanusiaan dapat membangaun citra GAM di
mata dunia. Terlebih perundingan ini difasilitasi oleh lembaga internasional, GAM
berharap bahwa perundingan ini dapat dijadikan sebgai kendaraan untuk membuat isu
aceh mendunia, dengan harapan masyarakat internasional memberikan dukungannya
kepada GAM. Ketiga, dari tataran taktis. Jeda Kemanusiaan digunaan oleh GAM
untuk memperluas pengaruhnya di Aceh. Dengan diberhentikannya kekerasan, GAM
yang secara militer jauh lebih lemah dari TNI justru mendapat kesempatan untuk
memperluas basis dukungan di kalangan penduduk local dan mengkonsolidasikan
kekuatan militernya. (Huber, 2008 dalam Aguswandi & Large, 2008:17).
Ketika GAM memanfaatkan Jeda Kemanusiaan untuk konsolidasi organisasi
dan perluasan pengaruhnya, TNI dan Polri malah diimbau untuk tidak melakukan
tindakan ofensif. Sikap TNI dan Polri yang tidak ofensif sesuai dengan imbauan itu
dimanfaatkan GAM untuk meningkatkan kegiatan militernya. Hal inilah yang pada
pada akhir Jeda Kemanusiaan pada Januari 2001, kekerasan tetap saja terjadi. Dapat
dikatakan selama tahun 2000 implementasi Jeda Kemanusiaan mengalami kegagalan.
Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan gagalnya Jeda Kemanusiaan ini.
Pertama, karena tidak adanya kepercayaan dari kedua belah pihak yang berkonflik.
Kedua, Jeda Kemanusiaan ini hanya mengatur tentang aspek keamanan dari konflik
Aceh, yaitu penghentian kekerasan dan operasi militer. Dan ketiga, tidak adanya
komitmen pada level aparat di lapangan terhadap kesepakatan penghentian kekerasan.
Gagalnya implementasi Jeda Kemanusiaan meberikan indikasi bahwa perundingan
damai dengan GAM tidak aan berjalan baik tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.
Naiknya Megawati Soekarnoputri ke kursi Presiden pada Juli 2001
merupakan titik balik peran TNI dalam pentas politik nasional dalam konteks resolusi
konflik Aceh. Komitmen politik Presiden Megawati yang nasionalis dan sangat
menekankan pada integritas wilayah menjadikan resolusi konflik di Aceh pun
bergeser kembali menjadi hard power (operasi militer) dan soft power (pemberi
otonomi luas) secara bersamaan dalam periode yang sama. Kedua kebijakan itu
dijalankan secara berbarengan untuk menekan GAM mau menerima otonomi luas
seperti yang ditawarkan oleh pusat (Aspinal & Crouch, 2003:26).
Strategi pemerintah yang mengkombinasikan hard power dan soft power
dalam waktu yang bersamaan ternyata memang membuahkan hasil. Dapat dikatakan,
pendekatan kombinasi seperti ini, pada tingkat tertentu, telah “memaksa” GAM untuk
mau berunding lagi. Hal ini terlihat dari kesediaan GAM untuk berunding kembali
kesepakatan Cessation of Hostilities Agreementi/COHA, yang isinya antara lain
mengatur tentang demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan
dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang. Namun, kesepakatan
COHA ini juga tidak bertahan lama dikarenakan kedua belah pihak masing-masing
memiliki interpretasi tersendiri terhadap COHA.
Perbedaan interpretasi seperti ini membuat pelaksanaan di lapangan menjadi
sulit, sehingga mudah memancing kedua belah pihak kembali melakukan kekerasan.
Kesulitan implementasi ini diperparah lagi oleh tidak singkronnya sikap antara aparat
di lapangan dan elit TNI/Polri maupun antar petinggi TNI/Polri sendiri serta
minimnya dukungan politik dari militer (Tempo, 5 Juli 2009:66).
Presiden Megawati akhirnya menandatangani darurat militer di Aceh pada 19
Mei 2003. Hal ini yang mengawali hard power dalam resolusi konflik Aceh.
Keberanian Presiden Megawati dalam menerapkan darurat militer ini disebabkan oleh
dua hal. Pertama, pemerintahannya merasa sudah menunjukkan kepada khalayak
Indonesia dan dunia internasional bahwa Pemerintah sudah cukup banyak member
kesempatan kepada GAM untuk merundingkan kembali tuntutan merdeka dengan
menerima otonomi yang sudah sangat luas, namun GAM tidak menunjukkan
tanda-tanda untuk melepas tuntutan kemerdekaannya. Kedua, Megawati merasa “aman”
secara politik dengan keputusan darurat militernya karena keputusan tersebut
didukung oleh TNI/Polri, DPR, serta opini publik dan media massa (Aspinal &