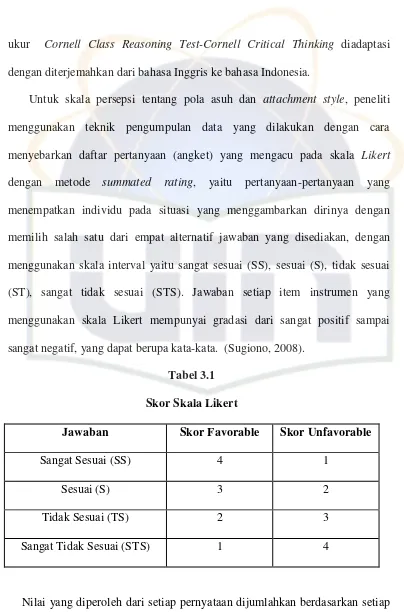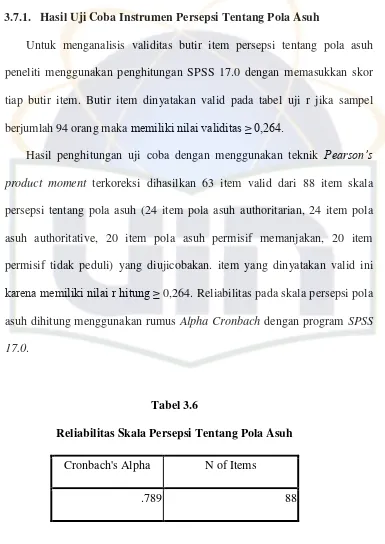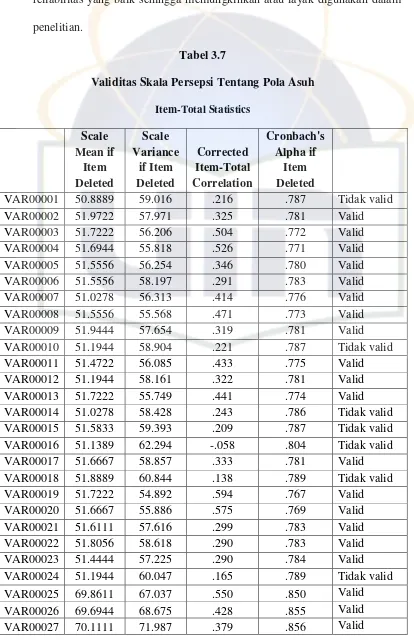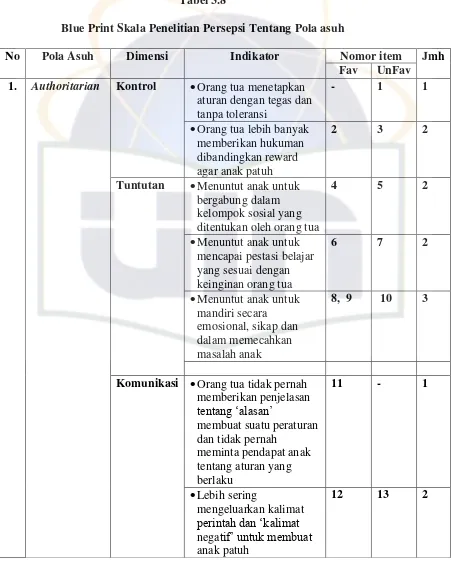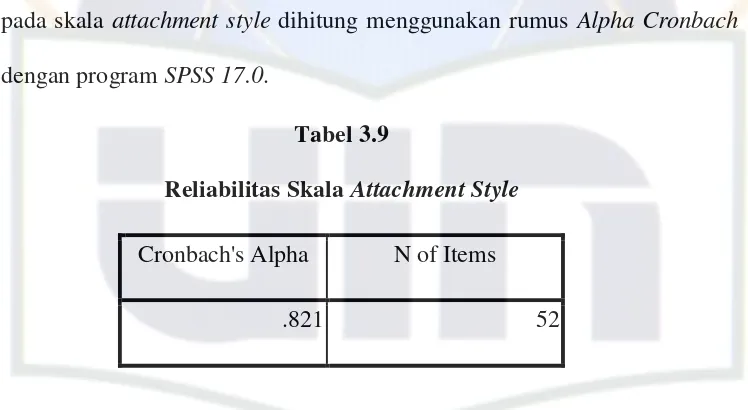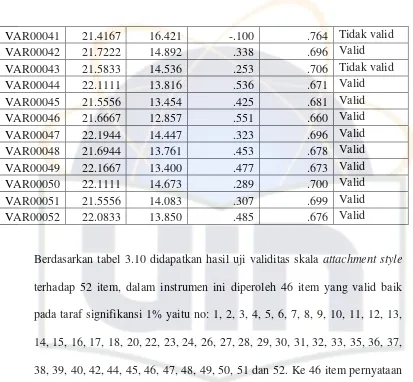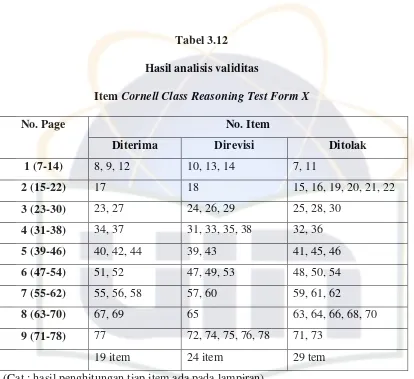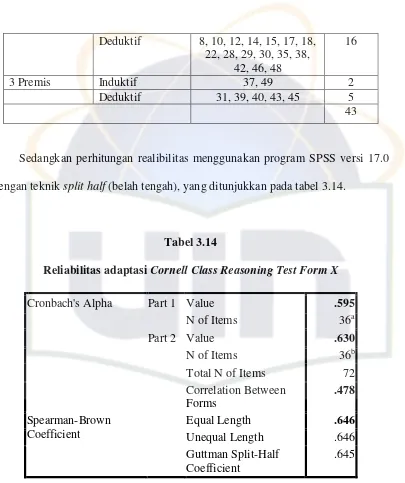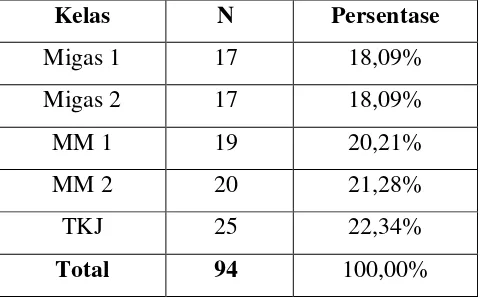SISWA SMK KARYA PUTRA BANGSA DEPOK
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Psikologi untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Psikologi
Disusun oleh :
RATIH NUR SYAFITRI
105070002300
FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
ii
SISWA SMK KARYA PUTRA BANGSA DEPOK
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Psikologi untuk memenuhi syarat-syarat
memperoleh gelar Sarjana Psikologi
Oleh :
RATIH NUR SYAFITRI
NIM : 105070002300
Di bawah bimbingan :
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. Rachmat Mulyono, M.Psi., Psi Yufi Adriani, M.Psi
NIP.19650220 199903 1 003 NIP.19820918 200901 2006
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
iii
KRITIS SISWA SMK KARYA PUTRA BANGSA DEPOK”initelah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011. Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) Fakultas Psikologi.
Jakarta, 11 Oktober 2011
Sidang Munaqasyah
Dekan / Ketua Pembantu Dekan/Sekretaris
Jahja Umar, Ph.D Dra. Fadhilah Suralaga, M.Si NIP. 130 885 522 NIP.19561223 198303 2 001
Anggota :
Dra. Netty Hartati, M.Si Drs. Rachmat Mulyono, M.Si, Psi. NIP. 1953 10021983032 NIP. 19650220 199903 1 003
iv NIM : 105070002300
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH PERSEPSI
TENTANG POLA ASUH DAN ATTACHMENT STYLE TERHADAP
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMK KARYA PUTRA
BANGSA DEPOK” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam menyusun karya tersebut. Adapun
kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber
pengutipannya dalam skripsi. Saya bersedia untuk melakukan proses yang
semestinya sesuai dengan undang-undang jika ternyata skripsi ini secara prinsip
merupakan plagiat atau ciplakan dari orang lain.
Demikian pernyataan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.
Jakarta, 11 Oktober 2011
Yang Menyatakan
Ratih Nur Syafitri
v
Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang
berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada
(buhul) tali yang amat kokoh.
Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan
(Q.S. Luqman : 22)
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Q.S. Al-Insyirah : 5-8)
Ku Dedikasikan Skripsi ini
vi (C)Ratih Nur Syafitri
(D)Pengaruh persepsi tentang pola asuh dan attachment style terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok
(E)Halaman : xi + 136
(F) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi anak tentang pola asuh orang tua (authoritarian, authoritative, permisif memanjakan dan permisif tidal peduli) dan attachment style (secure, anxious resistant, anxious avoidant) terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK
Karya Putra Bangsa Depok. Diduga jenis-jenis pola asuh dan attachment style
memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depoki,dikarenakan pola asuh dan
attachment style berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berjumlah 155 dan sampel sejumlah 94 siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok dari kelas X1-X5, sampel diambil dengan menggunakan teknik purposif sampling.
Untuk instrumen pengumpulan data, digunakan skala persepsi anak tentang pola asuh orang tua yang terdiri dari 63 item, skala attachment style
yang terdiri dari 46 item dan alat tes berpikir kritis yang merupakan adaptasi
“Cornell Class Reasoning Test Form X” terdiri dari 43 item. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda, dengan program SPSS versi 17.0. Pengujian validitas konstruk, untuk skala persepsi pola asuh dan attachment style menggunakan program SPSS versi 17.0, sedangkan uji validitas item untuk alat tes adaptasi “Cornell Class Reasoning Test Form X” menggunakan program ITEMAN versi 3.0.
vii
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan informasi positif bagi siswa, orang tua, pendidik, dan instansi pendidikan yang terkait khususnya SMK Karya Putra Bangsa dalam penelitian ini. Dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan
pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh orang tua dan attachment
style terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti merekomendasikan untuk membangun persepsi tentang pola asuh dan attachment style siswa melalui program bimbingan dan konseling bekerja sama dengan orang tua
siswa sehingga persepsi tentang pola asuh dan attachment style yang dibangun
oleh siswa lebih baik (positif) sehingga kemampuan berpikir kritisnya akan meningkat. Disamping itu kendala dalam penelitian ini masih ada 76,8% faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Saran metodologis dalam penelitian ini salah satunya adalah ada baiknya penelitian selanjutnya menggunakan alat tes berpikir kritis yang berbeda agar dapat dilakukan perbandingan.
viii
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari
zaman yang gelap gulita hingga alam yang terang benderang dengan ilmu
pengetahuan.
Peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua
pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah berjasa dalam
penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Jahja Umar, Phd, Dekan Fakultas Psikologi UIN syarif Hidayatullah
Jakarta
2. Dra. Fadhillah Suralaga, M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Dra. Netty Hartati, M.Si, selaku penguji I atas bimbingan dan saran yang
diberikan
4. Drs. Rachmat Mulyono, M.Si, Psi, Dosen pembimbing I dan penguji II
yang dengan sabar dan penuh pengertian membantu, membimbing dan
memberikan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi
5. Yufi Adriani, M.Psi, Dosen pembimbing II yang dengan sabar dan penuh
pengertian membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada
penulis selama penulisan skripsi
6. Ikhwan Luthfi, M.Si, Dosen pembimbing akademik yang telah
mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh studi di
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
7. Seluruh dosen, staff akademik dan administrasi yang telah membantu
penulis selama menempuh studi dan memberikan kontribusi baik secara
ix
9. Bapak dan Ummi tercinta atas segala limpahan kasih sayang, bimbingan
dan juga bantuannya selama hidup penulis. Maafkan jika persembahan ini
tertunda dari waktu yang seharusnya. Semoga Allah memaafkan dosa dan
menyayangi kalian berdua sebagaimana kalian menyayangi penulis sejak
kecil
10.Bapak, Mamah (Alm) mertua, dan nenek atas segala limpahan kasih
sayang, pengertian dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini
11.Suamiku tercinta, yang telah menjadi telaga semangat dan kasih sayang
yang tak pernah kering, tanpanya mungkin penulis tidak dapat
menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Semoga Allah menjadikan kita
sebagai keluarga penghuni surga
12.Kakak dan adikku, Aa Gugum, Mba Okti, Teteh Nenden, Aa Hendi, Aa
Anto, Teteh Lisda, Aa Dawa, dan Opi atas semangat dan bantuannya
selama ini kepada penulis
13.Saudara-saudariku di LDK KOMDA Psikologi angkatan 2005 (Rofiqo
(Alm), Novi, Eva, Iyung, Arizka, Evi, Via, Nia, Yunita, Yulistin, Yunita S,
Desti, Mila, Fillah, Arif, Hari, Rusydi, Didit) atas kebersamaan,
kekeluargaan dan semangatnya
14.Kakak-kakak dan adik-adik seperjuangan angkatan 2003-2004 LDK
KOMDA Psikologi dan keluarga Besar LDK SYAHID UIN Jakarta atas
ukhuwah dan kebersamaannya
15.Keluarga Besar PIM dan DPMU (2007-2008) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta atas kerjasamanya
16.Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu, mendukung, dan
x
18.Semua saudara, sahabat dan rekan-rekan penulis lain yang tidak bisa
disebutkan satu persatu
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan menfaat khususnya
bagi peneliti dan umumnya bagi siapa saja yang membaca.
Ciputat, 11 Oktober 2011
xi
LEMBAR PENGESAHAN ... iii
LEMBAR PERNYATAAN ... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
ABSTRAK ... vi
KATA PENGANTAR ... viii
DAFTAR ISI ... xi
DAFTAR BAGAN ... xv
DAFTAR TABEL ... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ... xviii
BAB 1 PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2. Pembatasan dan perumusan masalah ... 11
1.3.1. Batasan Masalah... 11
1.3.2. Peruumusan Masalah ... 13
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ... 15
1.4.1. Tujuan Penelitian ... 15
1.4.2. Manfaat Penelitian ... 17
1.4. Sitematika Penulisan ... 19
BAB 2 KAJIAN TEORI ... 20
xii
dalam berpikir kritis ... 25
2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis ... 28
2.2. Persepsi ... 32
2.2.1. Pengertian persepsi... 32
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ... 33
2.2.3. Proses persepsi ... 35
2.3. Pola asuh ... 36
2.3.1. Pengertian pola asuh ... 37
2.3.2. Aspek-aspek dalam pola asuh ... 38
2.3.3. Jenis-jenis pola asuh ... 39
2.3.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh ... 43
2.4. Attachment style ... 45
2.4.1. Pengertian attachment ... 45
2.4.2. Attachment style ... 47
2.4.3. Internal working model ... 50
2.4.4. Pengukuran kualitas attachment ... 51
2.4.5. Figur attachment ... 54
2.4.6. Attachment pada remaja ... 56
2.4.7. Stabilitas attachment style ... 57
xiii
2.5.4. Perkembangan berpikir kritis pada remaja ... 66
2.6. Kerangka berpikir... 68
2.7. Hipotesa penelitian ... 73
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN ... 76
3.1. Pendekatan dan jenis penelitian ... 76
3.2. Variabel penelitian ... 77
3.3. Definisi operasional variabel ... 78
3.4. Populasi, sampel, dan teknik sampling ... 79
3.2.1. Populasi ... 79
3.2.2. Sampel dan teknik sampling ... 80
3.5. Pengumpulan data ... 80
3.4.1. Teknik pengumpulan data... 80
3.4.2. Instrumen penelitian ... 82
3.6. Uji instrumen penelitian ... 91
3.6.1. Uji validitas ... 91
3.6.2. Uji realibilitas ... 92
3.6.3. Uji hipotesis ... 93
3.7. Hasil uji coba instrumen penelitian ... 95
3.7.1. Hasil uji coba instrumen persepsi tentang pola asuh .... 96
xiv
4.1. Gambaran subjek/objek penelitian ... 114
4.2. Presentasi data ... 119
4.2.1. Deskripsi statistik... 119
4.2.2. Deskripsi skor subjek ... 119
4.3. Deskripsi data ... 121
4.3.1. Analisis regresi berganda ... 121
4.3.2. Uji hipotesis ... 127
4.3.3. Analisis regresi sederhana dan one way ANOVA ... 129
4.4. Proporsi varians ... 135
BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN ... 140
5.1. Kesimpulan ... 140
5.2. Diskusi ... 142
5.3. Saran ... 145
5.3.1. Saran metodelogis ... 145
5.3.2. Saran praktis ... 147
DAFTAR PUSTAKA ... 148
xv
xvi
Tabel 3.2 Skala persepsi tentang pola asuh ... 83
Tabel 3.3 Skala attachment style ... 87
Tabel 3.4 Cornell Class Reasoning Test Form X ... 90
Tabel 3.5 Kriteria realibilitas ... 92
Tabel 3.6 Realibilitas skala persepsi tentang pol asuh ... 96
Tabel 3.7 Validitas skala persepsi tentang pola asuh ... 97
Tabel 3.8 Blue print skala penelitian persepsi tentang pola asuh ...100
Tabel 3.9 Realibilitas skala attachment style ...104
Tabel 3.10 Validitas skala attachment style ...104
Tabel 3.11 Blue print skala penelitian attachment style ...106
Tabel 3.12 Hasil analisis validitas item Cornell Class Reasoning Test Form X ...110
Tabel 3.13 Blue Print penelitian Cornell Class Reasoning Test Form X ...110
Tabel 3.14 Reliabilitas adaptasi Cornell Class Reasoning Test Form X ...111
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelas ...114
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin ...115
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan suku bangsa ...115
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan Ayah ...116
Tabel 4.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu ...117
Tabel 4.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan perbedaan status ibu bekerja ...117
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi responden berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan orang tua per-bulan ...118
xvii
Tabel 4.11 ANOVAb Analisis regresi dari 7 IV ...122
Tabel 4.12 Model Summary analisis regresi dari 7 IV ...123
Tabel 4.13 Coefficientsa 7 IV terhadap DV ...124
Tabel 4.14 ANOVAb regresi sederhana tingkat prestasi belajar ...129
Tabel 4.15 Model Summary tingkat prestasi belajar di kelas ...130
Tabel 4.16 ANOVA jenis kelamin (jender) ...130
Tabel 4.17 ANOVA suku bangsa ...130
Tabel 4.18 ANOVA tingkat pendidikan Ayah ...131
Tabel 4.19 ANOVA tingkat pendidikan Ibu ...131
Tabel 4.20 ANOVA status ibu bekerja ...132
Tabel 4.21 ANOVA tingkat pendapatan orang tua ...132
Tabel 4.22 ANOVA figur pengasuh dominan ...133
xviii Lampiran 2 Data uji validitas dan realibilitas
Lampiran 3 Data instrumen penelitian
Lampiran 4 Data input penelitian
Lampiran 5 Data hasil analisis regresi ganda
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Informasi biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan. Setiap orang
bisa salah dalam mengambil kesimpulan, karena menerima dan menggunakan
informasi dari satu perspektif tertentu saja tanpa membandingkannya dengan
infomasi yang lain. Para ilmuwan, psikolog dan dokter bisa memberi saran yang
salah karena tidak cermat menimbang informasi. Akibatnya, para pengguna jasa
mereka sering dirugikan karena terlalu cepat percaya pada informasi dari satu
perspektif tertentu saja.
Manusia memerlukan informasi dalam kehidupannya untuk membantu
menjalani kehidupan, terutama untuk mengenali mengetahui masalah-masalah
sehari-hari. Kemudian manusia berusaha memenuhi kebutuhan dan
menyelesaikan permasalahan-permasalahannya melalui usaha kreatif dan
kemampuannya memecahkan masalah (problem solving). Usaha manusia untuk
bertahan hidup berkaitan langsung dengan aspek kognitif manusia yaitu
kemampuan berpikir. Berpikir merupakan proses internal yang di dalamnya
terjadi pengubahan informasi sehingga memungkinkan untuk diarahkan menuju
pemecahan masalah yang menghasilkan gambaran mental baru. Permasalahan
yang kompleks dan tingginya tuntutan kehidupan yang dihadapi manusia seiring
berpikir yang „biasa‟ saja, yaitu suatu proses berpikir yang kurang sistematis
ataupun analitis. Proses berpikir semacam ini sulit menghasilkan kesimpulan atau
solusi yang mengena bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.
Manusia membutuhkan suatu usaha yang lebih aktif lagi dalam menerima dan
mengolah informasi baru yang masuk dalam memorinya (Prabandari, 2004).
Moore dan Parker (2007) mengemukakan satu cara untuk menghindari
kerugian atau kecelakaan yang disebabkan kesalahan penggunaan informasi yaitu
dengan berpikir kritis. Menurut mereka, berpikir kritis memperbesar kemungkinan
manusia memperoleh informasi yang benar. Informasi yang benar sangat
membantu manusia mengambil tindakan yang tepat. Inti dari berpikir kritis adalah
tidak begitu saja menerima atau menolak informasi yang dihadapi. Dengan kata
lain tidak begitu saja membuat keputusan tentang sesuatu. Berpikir kritis
merupakan suatu perilaku yang bisa dipelajari. Dengan melatih berpikir kritis,
seseorang dapat melakukan pertimbangan yang hati-hati dan cermat sebelum
memberi penilaian atau judgment, seseorang bisa terhindar dari penggunaan
infomasi yang menyesatkan (Moore & Parker, 2007).
Dalam perkembangan berpikir kritis, sebuah periode transisi yang penting
terjadi pada masa remaja (Keating dalam Santrock, 2007). Hal itu karena pada
periode ini terjadi perubahan-perubahan kognitif yang memungkinkan
peningkatan berpikir kritis. Peningkatan tersebut antara lain: pertama,
meningkatnya kecepatan, otomotisasi, dan kapasitas pemrosesan informasi, yang
mencapai berbagai tujuan lain; kedua, meningkatnya cakupan isi pengetahuan di
berbagai bidang; ketiga, meningkatnya kemampuan untuk menyusun
kombinasi-kombinasi baru dari pengetahuan; lalu keempat, meningkatnya rentang dan
spontanitas dalam menggunakan strategi-strategi dan prosedur-prosedur yang
diperlukan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, seperti
merencanakan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan melakukan monitor
kognitif (Santrock, 2007).
Meskipun masa remaja merupakan suatu periode penting dalam
perkembangan berpikir kritis, pada kenyataannya banyak fakta yang menunjukkan
kurangnya kemampuan berpikir kritis pada remaja. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa kasus, salah satu di antaranya, pada masa ujian nasional, banyak siswa
yang melakukan kecurangan dengan mencari „bocoran‟ soal bahkan menjualnya
kepada siswa yang lain. Apabila ia mempunyai sikap kritis, ia tidak akan
melakukan hal tersebut. Karena salah satu karakteristik pemikir kritis adalah
mempunyai kejujuran intelektual (Bassham, 2005). Peneliti mendapati kasus
tersebut dari siaran banyak televisi swasta mulai dari tahun 2005, sampai tahun ini
pun peneliti masih mendengar kasus tersebut masih terjadi. Lalu kurangnya
kemampuan berpikir kritis ditunjukkan dengan banyaknya remaja yang terjerumus
dengan kasus narkoba, walaupun pengaruh kawan sebaya sangat mempengaruhi
masalah remaja ini, tetapi apabila ia mempunyai kemampuan untuk menentukan
mana yang baik dan yang salah dengan berpikir kritis, semua masalah tersebut
Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya budaya kritis pada masyarakat
terutama remaja. Menurut Nugroho (1994) kualitas interaksi antara “neorological
system” dan lingkungan (pendidikan dan budaya) dimana individu berada,
berpengaruh terhadap perkembangan berpikir kritis seseorang. “Neorological
system” yang dimaksud adalah funsi otak (brain function). Menurut Clark
(Nugroho, 1994), otak manusia berisi lebih dari 100-200 trilyun sel otak. Setiap
neural sel siap untuk dikembangkan untuk mengaktualisasikan potensi manusia
pada tingkat yang lebih tinggi. Setiap neuron sel siap untuk memproses beberapa
trilyun informasi yang diterima. Cara untuk mengaktualisasikan potensi tersebut
juga bergantung pada keadaan emosi dan motivasi individu untuk mengaktifkan
potensi tersebut. Salah satunya adalah memproses informasi yang masuk ke dalam
otak dengan berpikir. Potensi-potensi tersebut juga tidak akan berkembang tanpa
bantuan lingkungan baik lingkungan pendidikan dan budaya di mana individu
tersebut tinggal (Nugroho, 1994).
Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (dalam Prabandari, 2004)
menemukan bahwa budaya Indonesia juga dapat menghambat kemampuan
berpikir kritis, karena adanya keharusan untuk mengikuti budaya. Jika seseorang
tidak mengikuti budayanya maka ia akan menerima sanksi yang berupa
pengucilan dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan di tiga suku bangsa (Batak
Toba, Jawa dan Minangkabau) menggunakan pemuka adat dan pendidik sebagai
narasumbernya. Pendidik di Indonesia juga lebih aktif sementara peserta didik
hanya pasif dan membeo saja, akibatnya peserta didik tidak dapat
diri dan tidak mampu untuk mengekspresikan diri. Padahal menurut Vygotsky,
seorang anak akan mencapai perkembangan kognitif yang maksimal jika ia
mendapatkan bimbingan yang tepat, dalam hal ini interaksi dengan guru, yang
dalam pendidikan dapat mempengaruhi kreativitas, kecerdasan, mutu dan kualitas
yang dihasilkan. Hal ini juga ditekankan oleh Yumarma (dalam Prabandari, 2004)
bahwa “70% keberhasilan pendidikan lebih ditentukan oleh atmosfer pendidikan
daripada isi yang diajarkan “. Peserta didik mungkin tidak mampu untuk
mengingat seluruh materi yang diajarkan tetapi pola pikir, metode, pola afeksi,
rasa merasa dan kreativitas yang tumbuh selama masa bimbingan akan selalu
melekat dalam diri anak dan lama kelamaan menyatu dengan kehidupan anak
(Prabandari, 2004). Selain itu, kurangnya usaha pembentukan dan penanaman
kebiasaan bersikap dan berpikir kritis sejak dini ikut mempengaruhi kemampuan
berpikir kritis remaja. Keluarga dan sekolah sebagai institusi pendidikan utama
dan mendasar bagi perkembangan individu kurang mengkondisikan sikap dan
pemikiran kritis secara optimal sehingga lahirlah individu-individu yang pasif,
tidak cepat tanggap dan tidak mampu menyelesaikan persoalan atau menyikapi
kondisi aktual masyarakat secara kritis (Rini, 2008).
Kemampuan berpikir kritis, mulai tumbuh sejak kecil. Anak pada dasarnya
memiliki kebutuhan untuk menemukan atau membuat sebuah runtutan pengertian
berdasar pengalaman hidup. Mereka ingin dapat bernalar secara baik atau paling
tidak ia bisa teliti tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting, tentang
apa yang benar dan apa yang salah, mana yang menenuhi syarat dan mana yang
mengkonfirmasikan dengan pengalaman. Namun, anak adalah individu yang
egosentris yang pertumbuhan pengertiannya tergantung padanya, meningkat
secara perlahan dan tersembunyi sangat dalam (tak terlihat). “Apakah saya
berpikir harus benar...”, jika belum maka orang tua yang membimbingnya untuk
membenarkan arah berpikir anak itu dan ini adalah implementasi bahwa anak itu
bergantung pada orang lain dalam menumbuhkan segala aspek pada diri anak itu.
Mendorong anak untuk membuat dan berusaha dalam menalar, dan kita perlu
mendemonstrasikan penalaran yang benar dan penalaran yang salah, tentu dalam
kealamiahan. Menurut Vygotsky, dalam konsep ZPD (Zone of Proximal
Development) yang ia kemukakan, ada batas kemampuan yang tidak dapat dicapai
anak tanpa bantuan orang lain yang lebih terampil (Santrock, 2003). Karena orang
tua adalah orang yang paling dekat dengan anak, maka pendidikan orang tua pun
ikut mempengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya dalam
berpikir kritis. Dengan alasan tersebut, dapat dikatakan pola asuh orang tua ikut
mempengaruhi kemampuan berpikir kritis anak dan remaja.
Pola asuh orangtua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua
yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian,
dan lain sebagainya) dan kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga
norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan
lingkungan (Gunarsa dalam Pratiwi, 2007). Terdapat 3 jenis pengasuhan, yaitu
authoritarian (otoriter), authoritative, dan permisif (Baumrind dalam Santrock,
2003). Baru-baru ini para ahli perkembangan berpendapat bahwa pengasuhan
tidak peduli (Santrock, 2003). Sejak dilahirkan, anak sudah mulai menjalani
proses berpikirnya, stimulasi-stimulasi yang diberikan seperti warna dan suara
untuk merangsang respons juga salah satu upaya melatih kemampuan berpikirnya.
Untuk membentuk anak mampu berpikir kritis diperlukan suasana dialogis dalam
keluarga, dengan mengungkapkan pertanyaan, isi hati dan pendapat anak kepada
orang tua. Pemilihan jenis mainan juga bisa berpengaruh kepada proses berpikir
anak, kemampuan berpikir kritis anak tidak akan terlalu berkembang bila hanya
diberikan mainan instan seperti play station. Anak sebaiknya sering diberikan
permainan seperti lego atau puzzle yang merangsangnya untuk berpikir dan
bekerja. Situasi dialogis keluarga dan orang tua yang selektif memilih mainan
anak seperti ini, hanya dimungkinkan terjadi pada pola asuh orang tua tipe
autoritatif, dimana orang tua memberikan aturan yang jelas tetapi juga
memberikan perhatian dan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan
kehendak mereka (Vidiyanto, 2010). Alpay dkk dalam penelitiannya terhadap
1.026 remaja Turki (usia 12-22 tahun) dengan menggunakan metode Watson
Glaser Scale of Critical Thinking Appraisal (WGSCTA) mengatakan bahwa sikap
orang tua yang otoriter (terutama ibu) berpengaruh negatif terhadap kemampuan
berpikir kritis anak remajanya, sedangkan perilaku ibu yang lebih toleran, empati
dan lebih kooperatif memberikan kontribusi positif untuk kemampuan berpikir
anak remajanya (Alpay & Ozkan, 2005). Keterampilan dasar seperti keterampilan
membaca dan matematika bila dikembangkan sepanjang masa kanak-kanak
selanjutnya (remaja) potensi pemikiran kritisnya akan mengalami pematangan
(Santrock, 2003).
Pola asuh yang baik dapat menghasilkan hubungan timbal balik yang baik
antara orang tua dan anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh yang tepat dapat
menumbuhkan ikatan emosional atau kelekatan yang secure (Rini, 2008). Ikatan
ini disebut attachment. Lebih lengkapnya attachment adalah suatu hubungan
emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan
individu lainnya yang mempunyai arti khusus, dalam hal ini biasanya hubungan
ditujukan pada ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang dibina bersifat timbal balik,
bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak
tampak dalam pandangan anak (Bowlby dalam Harre & Roger, 1996). Faktor
kualitas dari pengasuhan meliputi kepekaan orang tua untuk merespon secara
konsisten, tepat dan penuh dengan kehangatan, berkaitan dengan terbentuknya
secure attachment yang termasuk salah satu attachment style.Secure attachment
juga dihasilkan dari pengasuh yang membangun komunikasi penuh kenyamanan,
menggunakan cara yang fleksibel yaitu dengan adanya sikap penerimaan dalam
membantu mengatasi pemasalahan anak. Sedangkan insecure attachment
terbentuk dari interaksi pengasuh yang ditunjukkan dengan sedikitnya kontak
fisik, mengatasi permasalahan anak dengan buruk dan kaku, menunjukkan
kemarahan dan benci, serta penolakan (Berk dalam Mamay, 2006). Adanya
hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kritis anak dengan attachment
juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabandari (2004).
secara khusus mempengaruhi proses belajar keterampilan berpikir kritis pada
anak, dan kemampuan berpikir kritis anak secara umum. Banyak jurnal yang
membahas tentang attachment dan manfaatnya dalam kemampuan sosial anak
tetapi tidak banyak jurnal yang membahas attachment dengan kemampuan
kognitif anak. Padahal jika anak memiliki kualitas attachment yang secure dengan
ibu, maka anak mampu untuk mencari jalan atau strategi-strategi untuk
memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari (Meins dalam Prabandari,
2004). Hal ini mungkin tidak banyak disadari oleh para ibu, sehingga ketika
mereka berinteraksi dengan anak, ibu cenderung memanjakan sehingga
seakan-akan „lupa‟ untuk mendidik anak, meskipun ibu menyadari bahwa keluarga
merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Atau terkadang
seorang ibu yang bekerja, karena terlalu sibuk, ibu menitipkan anaknya pada
seorang pengasuh atau pembantu rumah tangga, sehingga pendidikan yang
diberikan oleh seorang pengasuh atau pembantu rumah tangga bisa jadi tidak
sama dengan pendidikan yang diberikan oleh ibu kandung, dalam hal ini bisa
keluarga atau orang lain. Sementara pendidikan di sekolah, masyarakat dan
pemerintah merupakan pelengkap bagi pendidikan di rumah, sehingga ketika
seorang ibu melakukan interaksi, ibu tidak hanya sekedar berinteraksi saja, seperti
bermain, mencium pipi dan lain sebagainya, tetapi ibu juga dapat mengarahkan
anak menjadi seorang pemikir yang kritis (Prabandari, 2004).
Pengalaman penulis sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar swasta,
banyak melihat anak yang terkesan „cerewet‟, karena bertanya tentang segala
penulis menganggap bahwa sikap anak-anak yang seperti itu menandakan bahwa
anak-anak tersebut punya rasa ingin tahu yang besar, dan ketika mereka berani
bertanya tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui kepada guru mereka, atau
mereka berusaha mencari tahu dengan membaca buku, maka mereka
mendapatkan sebuah „ilmu‟ yang mungkin saja tidak mereka dapatkan dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan rasa ingin tahu, anak-anak tersebut
sedang mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, karena menurut asumsi
peneliti, kemampuan berpikir kritis pada anak terlihat ketika mereka mau
berusaha untuk mencari tahu kejelasan (clarity) tentang pengetahuan yang mereka
dapat dalam proses pembelajaran, tidak hanya dari guru mereka, tetapi juga dari
beberapa sumber yang lain, contohnya orang tua dan buku-buku perpustakaan.
Tidak semua anak terlihat „cerewet‟ atau penuh rasa ingin tahu, ada juga
anak yang terlihat „cuek‟ dan tidak peduli ketika ada pelajaran yang mereka tidak
pahami, penulis melihat perbedaan tersebut terjadi antara anak yang ibunya selalu
bertanya tentang keadaan anaknya di sekolah atau bertanya tentang tugas sekolah
serta selalu menemani ketika mengerjakan pekerjaan rumah, dengan anak yang
ibunya tidak pernah berkomunikasi dengan guru di kelas dan tidak pernah
menemani atau mengontrol pekerjaan rumah anaknya. Variasi „kemampuan
berpikir kritis‟ juga terlihat antara anak yang ibunya selalu mengantar dan
menjemputnya di sekolah (tidak bekerja) dengan anak yang diantar dan jemput
oleh pembantu rumah tangga (karena ibunya bekerja). Penulis lantas bertanya,
mengapa perbedaan ibu yang responsif dengan yang tidak, dibarengi dengan
kedekatan ibu dengan anak ikut mempengaruhi hal tersebut? atau seperti apakah
pola asuh orang tua yang anaknya mampu bersikap kritis di kelas tersebut?
Apakah pola asuh ikut mempengaruhi variasi yang ada? peneliti sangat tertarik
meneliti semua itu. Tetapi peneliti lebih tertarik meneliti bila anak-anak yang
mempunyai sikap kritis itu sudah beranjak dewasa. Selain itu, berpikir kritis
remaja lebih mudah untuk di teliti, karena masa remaja ada pada tahap operasional
formal, di mana pada tahap ini individu mampu untuk menganalisis masalah.
Penulis juga belum menemukan penelitian yang mengaitkan antara kemampuan
berpikir kritis remaja di tingkat SMA/sederajat dengan pola asuh orang tua dan
attachment style. Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penulis memfokuskan
kepada kemampuan berpikir kritis remaja tingkat SMA/sederajat dan ingin
meneliti apakah ada pengaruh persepsi anak tentang pola asuh orang tua dan
attachment style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking)?
1.2. Pembatasan dan Perumusan masalah
1.2.1. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah merupakan suatu yang penting, karena dengan
pembatasan masalah dapat mengarahkan dalam pengumpulan data dan analisis.
Selain itu pembatasan masalah dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran
judul. Oleh karena itu, agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis
a. Persepsi tentang pola asuh yang digunakan adalah persepsi anak terhadap
empat jenis pola asuh yang diterapkan orang tuanya yaitu authoritarian,
authoritative, permisif memanjakan (permissive indulgent) dan permisif tidak
peduli (permissive indifferent) dengan ukuran berdasarkan empat aspek pola
asuh yaitu aspek kontrol, aspek demand for maturity (tuntutan), aspek clarity
of parent – child communication, aspek parental nurturance (Baumrind
dalam Santrock, 2003).
b. Attachment style yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada
attachment style antara ibu dan anak yang terbentuk berdasarkan teori
internal working model, yaitu merupakan representasi mental dari dimensi
perlakuan ibu terhadap anak (sensitivity – insentivity, acceptance – rejection,
cooperation – interference dan accessibility – ignoring). Dari dimensi
perlakuan ibu tersebut membentuk tiga attachment style yaitu secure
attachment, anxious resistant attachment, dan anxious avoidant attachment.
(Ainsworth dalam Santrock, 2003).
c. Berpikir kritis adalah pertimbangan (determination) yang dilakukan secara
sengaja, sistematis dan hati-hati untuk mengevaluasi sebuah claim /
pernyataan (Moore & Parker, 1986; Mayer & Goodchild, 1990).
d. Sampel penelitian ini adalah siswa siswi SMK Karya Putra Bangsa Depok
kelas X.
e. Faktor demografi yang digunakan dan analisis dalam penelitian ini adalah
pendidikan Ibu, status Ibu bekerja, tingkat pendapatan orang tua setiap bulan,
figur pengasuh dominan dan tingkat prestasi belajar di kelas.
1.2.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang dipaparkan penulis, maka
perumusan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh dan
attachment style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh
authoritarian terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa
SMK Karya Putra Bangsa Depok?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh
authoritative terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa
SMK Karya Putra Bangsa Depok?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif
memanjakan (permissive indulgent) terhadap kemampuan berpikir kritis
(critical thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok?
5. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif
tidak peduli (permissive indifferent) terhadap kemampuan berpikir kritis
6. Apakah ada pengaruh yang signifikan secure attachment style terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra
Bangsa Depok?
7. Apakah ada pengaruh yang signifikan pola anxious avoidant attachment
style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK
Karya Putra Bangsa Depok?
8. Apakah ada pengaruh yang signifikan pola anxious resistant attachment
style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK
Karya Putra Bangsa Depok?
9. Apakah ada pengaruh yang signifikan tingkat prestasi belajar di kelas
terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya
Putra Bangsa Depok?
10.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan jenis
kelamin?
11.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan suku bangsa?
12.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat
pendidikan Ayah?
13.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat
14.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan perbedaan
status ibu bekerja?
15.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat
pendapatan orang tua setiap bulan?
16.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan figur
pengasuh dominan?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menguji :
1. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh dan attachment style
terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya
Putra Bangsa Depok
2. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh authoritarian terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra
3. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh authoritative terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra
Bangsa Depok
4. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif memanjakan
(permissive indulgent) terhadap kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok
5. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif tidak peduli
(permissive indifferent) terhadap kemampuan berpikir kritis (critical
thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok
6. Pengaruh yang signifikan secure attachment style terhadap kemampuan
berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok
7. Pengaruh yang signifikan pola anxious avoidant attachment style terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra
Bangsa Depok
8. Pengaruh yang signifikan pola anxious resistant attachment style terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra
Bangsa Depok
9. Pengaruh yang signifikan tingkat prestasi belajar di kelas terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra
Bangsa Depok
10.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
11.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan suku bangsa
12.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat pendidikan
Ayah
13.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat pendidikan Ibu
14.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan perbedaan status ibu
bekerja
15.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat pendapatan
orang tua setiap bulan
16.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan figur pengasuh
dominan
1.3.2. Manfaat Penelitian
1.3.2.1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menemukan besaran
kontribusi dari masing-masing variabel persepsi tentang pola asuh dan attachment
style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking). Disamping itu juga,
psikologi bidang perkembangan remaja serta perkembangan dibidang pendidikan
pada umumnya, khususnya mengenai sejauh mana pengaruh dari masing-masing
variabel didalam persepsi tentang pola asuh dan attachment style terhadap
kemampuan berpikir kritis (critical thinking), mengingat belum banyak penelitian
yang meneliti masing-masing jenis dari persepsi tentang pola asuh maupun
attachment style kemudian diujikan dengan variabel kemampuan berpikir kritis
(critical thinking).
1.3.2.2. Manfaat praktis
Bagi para orangtua, penelitian ini dapat menambah wawasan baru
bagaimana seharusnya orang tua berperan sebagai pendidik utama, terutama
seorang ibu yang ikatan emosional paling berpengaruh terhadap kemampuan
anaknya, baik sosial maupun kognitif. Dengan bertambahnya pengetahuan ibu
mengenai pentingnya attachment dengan anak diharapkan dapat memberikan
dasar bagi pola pikir anak sehingga anak mulai belajar untuk berpikir secara kritis
melalui hal-hal yang sifatnya lebih kompleks dan abstrak. Selain itu peneliti juga
mengharapkan dengan dilaksanakan penelitian ini, maka akan menarik minat
ilmuwan untuk mengembangkan teori berpikir kritis pada anak dan remaja
dengan memperhatikan hubungan anak dengan ibu serta pengembangan alat untuk
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I : Pendahuluan
Berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan penelitian kemampuan
berpikir kritis (critical thinking), persepsi tentang pola asuh dan
attachment style, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Landasan Teori
Di dalam bab ini akan dibahas sejumlah teori yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti secara sistematis, kerangka berpikir, beserta
hipotesis penelitian.
BAB III : Metodelogi Penelitian
Bab ini meliputi pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian,
variabel penelitian, pengumpulan data penelitian, uji instrumen, uji
validitas, uji reliabilitas, metode analisis data dan prosedur penelitian.
BAB IV : Hasil Penelitian
Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai presentasi dan analisis
data. Terdiri dari gambaran umum responden, kategorisasi responden dan
hasil uji hipotesis.
BAB V : Kesimpulan, Diskusi, dan Saran
Pada bab ini, peneliti akan merangkum keseluruhan isi penelitian dan
meyimpulkan hasil penelitian. Terdiri dari kesimpulan, diskusi dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1. Berpikir kritis
Berpikir kritis sulit didefinisikan secara tepat. Belum ada kesepakatan dari
para ahli mengenai teori berpikir kritis ini. Oleh karena itu, penulis akan
mengemukakan terlebih dahulu kerangka teori mengenai berpikir yang kemudian
akan dilanjutkan dengan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini.
2.1.1. Definisi berpikir
Kesulitan mendefinisikan berpikir disebabkan tidak adanya pembatas yang
tajam antara kegiatan yang melibatkan berpikir dan tidak (Siegle, 1998). Berpikir
secara nyata melibatkan proses mental yang lebih tinggi: penyelesaian masalah,
penalaran, kreatiativitas, konseptualisasi, ingatan, klasifikasi, simbolisasi,
perencanaan, dsb. Sedangkan contoh lain dari berpikir melibatkan proses yang
lebih dasar seperti penggunaan bahasa dan penerimaan objek/peristiwa dari
lingkungan eksternal secara bersamaan.
Costa (Prabandari, 2004) menyatakan bahwa berpikir merupakan proses
internal dari stimulus eksternal.
“Thinking is the receiving of external stimuli throught the sense followed
by internal processing”
(Berpikir adalah menerima rangsangan eksternal, berpikir arti, diikuti oleh
Siegel menambahkan bahwa proses tersebut bersifat aktif karena melibatkan
operasi mental.
“Thinking is regarded as an active process involving a number of
denotable mentall operations”
(Berpikir dianggap sebagai suatu proses aktif yang melibatkan sejumlah
sistem operasi mental).
De Bono (Prabandari, 2004), seorang ahli pendidikan yang mengembangkan
program melatih kemampuan berpikir, menyebutkan berpikir sebagai eksplorasi
pengalaman yang dilakukan secara sadar dalam mencapai tujuan. Tujuan itu dapat
berupa pemahaman, pengambilan keputusan, perencanaan, pemecahan masalah,
penilaian dan tindakan.
De Bono mengelompokkan jenis-jenis berpikir menjadi enam kelompok,
yaitu:
1. Berpikir untuk mendapatkan informasi dan data
2. Berpikir mengenai perasaan terhadap sesuatu atau seseorang, termasuk
juga intuisi tentang sesuatu
3. Berpikir tentang mana yang benar dan baik, bagaimana mencapainya serta
konsekuensinya, jadi mengandung unsur penilaian
4. Berpikir tentang kemungkinan terjadinya sesuatu secara optimis, bahwa
sesuatu baik untuk dilakukan atau dicapai
5. Berpikir secara kreatif tentang-tentang hal-hal bau: eksplorasi, saran, usul,
6. Berpikir secara kritis terhadap jenis-jenis berpikir lainnya: sudah sampai
dimana, apa langkah selanjutnya, apa yang sebaiknya terjadi. Disebut juga
berpikir kritis, berpikir reflektif atau metakognisi
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
berpikir merupakan suatu proses mental sebagai respon atas stimulus eksternal
dimana proses tersebut memiliki suatu tujuan yang berupa hasil dari proses.
2.1.2. Definisi berpikir kritis
Dari berbagai literatur yang ada ternyata terdapat berbagai macam pengertian
mengenai berpikir kritis. Ini menandakan bahwa belum terdapat pemahaman
universal mengenai definisi umum berpikir.
Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa pandangan pakar mengenai
berpikir kritis sebagai acuan dalam kerangka teori ini, yaitu Moore dan Parker
(2007), Mayer dan Goodchild (1990).
Moore dan Parker (2003) mendefinisikan berpikir kritis sebagai :
“,,, the careful and deliberate determination of whether to accept, reject,
or suspend judgment about a claim”
(Penentuan secara hati-hati dan disengaja, apakah menerima, menolak atau
Mayer dan Goodchild (1990 dalam Takwin, 1997) mendefinisikan berpikir
kritis sebagai :
“... an active and systematic attempt to understand and evaluate
arguments”
(Usaha aktif dan sistematis untuk memahami dan mengevaluasi argumen).
Berpikir kritis menurut Moore dan Parker adalah pertimbangan
(determination) yang dilakukan secara sengaja dan hati-hati untuk menentukan
apakah sebuah claim diterima, ditolak, atau ditunda penilaiannya. Istilah claim
disamakan dengan istilah proposisi atau dalam bahasa Indonesia disamakan
dengan isilah pernyataan. Pernyataan didefinisikan sebagai kalimat yang dapat
betul atau dapat salah (Moore & Parker, 2007). Dalam pernyataan terkandung
informasi tentang sesuatu yang bisa dicek dan diuji benar atau salahnya.
Pertanyaan dan kalimat perintah bukan pernyataan karena tidak mengandung
informasi yang bisa diuji benar atau salahnya.
Mayer dan Goodchild (1990 dalam Takwin, 1997) mendefinisikan berpikir
kritis sebagai sebuah usaha yang aktif dan sistematis untuk mengerti dan
mengevaluasi argumen.
Definisi ini mempunyai enan bagian :
1. Berpikir kritis sebagai proses yang aktif. Ketika seseorang yang berpikir
kritis menerima informasi baik secara lisan maupun tulisan, ia tidak hanya
mendengar atau membaca setiap kata. Ia juga mencari arti dari setiap kata
2. Berpikir sebagai proses yang sistematis. Dalam mencari arti, seseorang
yang berpikir kritis menggunakan teknik-teknik yang logis. Ia menganalisa
informasi yang diterimanya dengan menggunakan proses yang sistematis.
Dalam tahap ini orang yang berpikir kritis akan bertanya “Dengan cara dan
aturan apa saya bisa mengerti apa yang ingin disampaikan si pemberi
informasi ini?”
3. Berpikir kritis didasarkan atas argumen. Unit dasar analisa dalam berpiki
kritis adalah argumen. Sebuah argumen dimulai dengan penjelasan tentang
ciri suatu objek (contohnya ingatan jangka pendek memiliki kapasitas
yang terbatas) atau hubungan di antara dua objek (contohnya makin
termotivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas, makin baik kinerjanya
dalam tugas itu). Argumen juga menunjukkan bukti untuk menunjang
dan/memperkuat penjelasan. Orang yang berpikir kritis mampu mengenali
dan menganalisa argumen sehingga ia mampu menggunakan argumen
secara tepat.
4. Berpikir kritis mencakup pengertian akan argumen. Orang berpikir kritis
mampu mengenali dan menganalisa argumen dari si pemberi informasi. Ia
mampu menemukenali bagian-bagian dai argumen dan merumuskan
argumen pemberi informasi dengan kata-kata sendiri. Ia merasa harus
menanyakan “Apakah argumen dari si pemberi informasi menunjang
informasi yang disampaikannya?”
5. Berpikir kritis mencakup pengevaluasian argumen. Orang yang berpikir
mampu memberi kritik terhadapnya. Ia mampu menentukan apakah
argumen si pemberi informasi valid atau tidak. Ia akan memberi
pertanyaan “haruskah saya menyetujui argumen ini?”
6. Berpikir kritis sebagai suatu usaha. Orang yang berpikir kritis mengetahui
bahwa tidak hanya ada satu cara yang benar untuk mengerti dan
mengevaluasi informasi yang diterimanya. Ia juga mengerti bahwa cara
yang dipilihnya tidak langsung menjamin bahwa ia akan mengerti dan
mengevaluasi secara benar informasi yang diterimanya secara aktif dan
sistematis. Berpikir kritis adalah pendekatan yang umum terhadap
masalah, bukan prosedur khusus yang selalu menghasilkan jawaban yang
benar. Orang yang berpikir kritis harus berusaha mencoba menggunakan
berbagai cara untuk mengerti dan mengevaluasi informasi yang
diterimanya.
Berdasarkan definisi dan pandangan dari tokoh tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah pertimbangan (determination) yang
dilakukan secara sengaja, sistematis dan hati-hati untuk mengevaluasi sebuah
claim (pernyataan).
2.1.3. Hukum-hukum logika dasar yang digunakan dalam berpikir kritis
Dalam bagian ini akan dikemukakan hukum-hukum logika dasar dalam
berpikir kritis. Hukum-hukum itu mencakup hukum-hukum proposisi logis seta
a. Proposisi logis
Aristoteles adalah orang yang pertama kali mengemukakan aturan logika
yang kemudian jadi tradisi dalam ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles
(Takwin, 1997) hal yang dianggap sebagai pondasi dasar dalam menemukan
pengetahuan yang benar adalah logos apophanticos, yaitu proposisi-proposisi
logis. Proposisi logis (pernyataan logis) adalah kalimat yang teruji
kebenarannya. Kalimat ini mengandung fakta dan terbukti kebenarannya.
Proposisi logis hanya bisa dibangun dengan prinsip identitas; “Bila sesuatu
itu X maka tak mungkin sekaligus bukan X”. Suatu pengetahuan baru sah
disebut episteme atau pengetahuan ilmiah atau benar-benar mewakili realita
bila dibangun atas dasar proposisi-proposisi logis.
Dalam berpikir kritis penggunaan proposisi logis sangat mutlak
diperlukan (Takwin, 1997). Seseorang yang melakukan berpikir kritis adalah
orang yang berpikir logis, ia menggunakan proposisi logis. Tetapi tidak setiap
orang yang berpikir logis adalah berpikir kritis. Ada syarat-syarat lain untuk
berpikir kritis. Proposisi logis diperoleh dan diuji dengan menggunakan
penalaran induktif dan penalaran deduktif.
b. Penalaran induktif
Penalaran induktif atau induksi secara umum merupakan proses
pembuatan kesimpulan umum yang berdasarkan dukungan fakta-fakta khusus
(Bittie, Copi & Cohen, Bierman & Assali dalam Takwin, 1997). Penalaran
premis-premisnya ditujukan untuk mendukung kesimpulan. Premis-premis itu bukan
keseluruhan dari fakta pendukung yang dibutuhkan tetapi hanya beberapa.
Dalam induksi beberapa kasus khusus saja sudah bisa digunakan untuk
membuat kesimpulan.
Pengambilan keputusan dengan cara induksi menggunakan prinsip
probabilitas sehingga induksi terjadi dalam kondisi yang tidak pasti. Prinsip
yang mendasari penalaran ini adalah keteraturan dalam alam mengijinkan (to
permit) penemuan hukum-hukum sebab akibat yang berlaku umum.
Meskipun demikian, penalaran induktif selalu mengandung resiko salah
karena fakta yang digunakan tidak sepenuhnya mewakili hal-hal yang akan
disimpulkan (Bierman & Assali dalam Takwin, 1997). Oleh karena itu,
penalaran induktif harus disertai pula dengan penalaran deduktif.
c. Penalaran deduktif
Penalaran deduktif atau deduksi adalah proses penalaran di mana
pembuatan kesimpulan khusus berdasarkan hukum yang lebih umum
(Bierman & Assali dalam Takwin, 1997). Penalaran deduktif menghasilkan
argumen deduktif, yaitu argumen yang premis-premisnya menyediakan
hukum umum yang memadai dan diakui kebenarannya untuk mendukung
kesimpulan khusus. Dalam deduksi, hukum umum yang digunakan harus
benar-benar memadai dan diakui benar untuk bisa digunakan membuat
2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis
Berpikir kritis pada dasarnya merupakan suatu tugas perkembangan yang akan
dihadapi oleh setiap individu. Artinya setiap individu telah memiliki bekal dasar
untuk dapat melakukannya (Nugroho, 1994). Namun demikian, Piaget
mengatakan (dalam Nugroho, 1994), hal itu bisa muncul atau tidak dalam pribadi
individu, masih akan ditentukan oleh kualitas interaksi antara “neorological
system” dan lingkungan (pendidikan dan budaya) dimana individu berada.
“Neorological system” yang dimaksud adalah modal dasar untuk berpikir
adalah funsi otak (brain function). Menurut Clark (Nugroho, 1994), otak manusia
berisi lebih dari 100-200 trilyun sel otak. Setiap neural sel siap untuk
dikembangkan untuk mengaktualisasikan potensi manusia pada tingkat yang lebih
tinggi. Setiap neuron sel siap untuk memproses beberapa trilyun informasi yang
diterima. Cara untuk mengaktualisasikan potensi tersebut juga bergantung pada
keadaan emosi dan motivasi individu untuk mengaktifkan potensi tersebut. Salah
satunya adalah memproses informasi yang masuk ke dalam otak dengan berpikir.
Potensi-potensi tersebut juga tidak akan berkembang tanpa bantuan lingkungan
baik lingkungan pendidikan dan budaya di mana individu tersebut tinggal
(Nugroho, 1994). Sama seperti yang diungkapkan oleh ahli perkembangan
Vygotsky, yaitu bahwa lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan
kemampuan kognitif seseorang. Vygotsky mengemukakan konsep ZPD (Zone of
Proximal Development) yang merujuk pada rentang-rentang tugas yang terlalu
sulit bagi individu untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui
jadi, batas bawah dari ZPD adalah level keterampilan yang mampu dapat diraih
anak dengan bekerja sendiri. Sementara batas atas dari ZPD adalah tingkat
tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur
yang mampu (Santrock, 2007). Sehingga denagan kata lain, “neorological system”
dan lingkungan (pendidikan dan budaya) adalah faktor yang dapat mempengaruhi
kemampuan berpikir kritis seseorang.
Menurut Takwin (1997), faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis
dibagi menjadi faktor situasional dan faktor disposisi. Faktor situasional adalah
faktor yang dapat mempengaruhi pada saat seseorang berpikir dalam membuat
penilaian terhadap informasi yang diterimanya. Sedangkan faktor disposisi adalah
faktor-faktor kebiasaan dan pengalamn masa lalu seseorang yang berpengaruh
terhadap penilaiannya.
1. Faktor-faktor situasional
1) Situasi accountable yaitu situasi dimana seseorang dituntut untuk
mempetanggungjawabkan hasil keputusannya. Faktor ini sangat penting
dalam menambil keputusan. Berpikir kritis adalah salah satu betuk
kegiatan pengambilan keputusan, oleh karena itu dipengaruhi pula oleh
situasi accountable (Fiske & Taylor dalam Takwin, 1997).
2) Keterlibatan (involvement) yaitu ketelibatan seseorang dalam
permasalahan, ikut mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan
2. Faktor-faktor disposisi
1) Pengalaman bertukar peran (role-taking). Pengalaman di mana seseorang
memiliki kesempatan untuk bertukar peran atau role-taking dengan orang
lain yang memiliki latar belakang berbeda , meningkatkan kemampuan
seseorang dalam menilai suatu hal dari berbagai sudut pandang. (Kohlberg
dalam Takwin, 1997)
2) Pembiasaan dan latihan. Berpikir kritis merupakan suatu keterampilan
yang bisa diajarkan dan dilatih. Semakin sering seseorang dilatih, semakin
mahir ia menggunakannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh tokoh-tokoh psikologi belajar dalam Morgan dkk (Takwin 1997)
3) Pola asuh. Pembiasaan dan latihan tidak akan berjalan dengan baik tanpa
didukung dengan interaksi yang baik dengan lingkungan sosial. Terutama
pembiasaan dan latihan yang diberikan oleh orang tua dan guru dengan
pola asuh yang tepat. Orang tua dan guru adalah orang-orang yang paling
membantu anak dan remaja dalam mencapai tugas perkembangan
kognitifnya (Vygotsky dalam Santrock, 2007). Hal ini lebih lanjut akan
dibahas pada penelitian ini.
4) Ekstirimitas penilaian seseorang terhadap suatu permasalahan. Tetlock
(Takwin, 1997) mengemukakan apabila dalam suatu permasalahan
seseorang mempersepsikan berbagai nilai yang saling berkonflik satu sama
lainnya maka penilainnya terhadap masalah akan menjadi moderat.
mempersepsikan adanya konflik nilai, maka penilaiannya terhadap suatu
masalah itu akan menjadi lebih ekstrim.
5) Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, lebih banyak
pengetahap perkembangan tertentu, ikut mempengaruhi kemampuan pada
tahap selanjutnya. Pendidikan yang dimaksud bisa (Takwin, 1997).
6) Nilai (value). Nilai menjadi standar bagi seseorang dalam menentukan apa
yang harus dia lakukan dalam menanggapi informasi. Nilai menentukan
apakah perlu untuk berpikir kritis atau tidak, atau apabila perlu, seberapa
kritis yang diperlukan untuk menanggapi informasi (Rokeach dan
Schwartz dalam Takwin, 1997).
7) Metode pengajaran. Berpikir kritis adalah keterampilan yang bisa dilatih
dan diajarkan (Moore & Parker, 1986; Mayer & Goodchild, 1990). Cara
penyampaian materi juga berpengaruh terhadap hasil belajar (Munandar
dalam Takwin, 1997).
8) Usia
Usia berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Menurut Piaget,
tahap kemampuan kognitif manusia berkembang sesuai dengan usianya.
Ada perbedaan kemampuan berpikir pada tiap tahap perkembangan. Orang
yang mampu melakukan berpikir kritis adalah mereka yang sudah
mencapai tahap formal operasional dimana ia sudah dapat melakukan
abstraksi, analisa sintesa dan mampu berpikir dengan menggunakan
2.2. Persepsi
2.2.1. Pengertian persepsi
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan
pesan. Persepsi juga diartikan dengan memberikan makna pada stimuli inderawi
(Rakhmat, 1994).
Atkinson (1983) juga menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses
dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam
lingkungan. Senada dengan itu, persepsi juga diartikan sebagai suatu proses yang
didahului stimulus yang diterima oleh inderawi kemudian diorganisasikan dan
dinterpretasikan, sehingga individu menyadari apa yang diinderakannya itu
(Davidoff, 1988)
Chaplin (2002) menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses mengetahui
atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Secara umum
persepsi diperlakukan sebagai variabel campur tangan (intervening variable) yang
bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat, keadaan psikis
atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Maka arti suatu objek atau satu
kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun oleh faktor
organisme. Dengan alasan demikian, persepsi mengenai dunia oleh
pribadi-pribadi yang berbeda juga akan berbeda, kaena setiap individu menanggapinya
berkenaan dengan aspek-aspek situasi tadi yang mengandung makna khusus sekali
Dari pengertian peneliti menyimpulkan bahwa apa yang dipersepsikan oleh
seseorang dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Hal tersebut
dapat disebabkan karena apa yang ada di sekitar kita yang ditangkap oleh panca
indera tidak langsung diartikan sama dengan realitasnya. Pengertian tersebut pada
orang yang mempersepsikan, objek yang dipersepsikan serta situasi sekelilingnya.
Berdasarkan persepsi atau pemberian arti dari apa yang ditangkap oleh panca
indera itulah maka seseorang melakukan aktivitas atau melakukan sikap-sikap
tertentu.
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan, dapat terjadi perbedaan
seseorang dalam memberikan makna terhadap informasi yang ditangkap oleh
panca inderanya. Menurut Robbins (2001) ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi terjadinya perbedaan persepsi seseorang, yaitu :
1. Orang yang melakukan persepsi
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, antara
lain :
a. Sikap individu yang bersangkutan terhadap objek persepsi
b. Motif atau keinginan yang belum terpenuhi yang ada dalam diri
seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi yang dimunculkan
c. Interest (ketertarikan). Fokus perhatian individu dipengaruhi oleh
ketertarikan tentang sesuatu. Hal ini menyebabkan objek persepsi yang
d. Harapan. Harapan dapat menyebabkan distorsi terhadap objek yang
dipersepsikan atau dengan kata lain seseorang akan mempersepsikan
suatu objek atau kejadian sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Target atau objek persepsi
Karakteristik dari objek yang dipersepsikan dapat mempengaruhi apa
yang dipersepsikan. Rangsang objek yang bergerak di antara objek yang diam
akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang objek yang paling
besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan
intensitas rangsangnya yang paling kuat. Karakteristik orang yang
dipersepsikan baik itu karakteristik personal sikap ataupun tingkah laku dapat
berpengaruh terhadap orang yang mempersepsikan karena manusia dapat
saling mempengaruhi persepsi satu sama lain. Orang tua yang berinteraksi
dengan anaknya dengan penuh perhatian, hangat, selalu antusias, dan
sebagainya akan berpengaruh terhadap persepsi anak tentang orang tuanya.
Sedangkan menurut Kossen (dalam Mamay, 2006) faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi persepsi seperti faktor keturunan yang mempengaruhi
persepsi secara fisik seperti kognisi, indera, dan lain sebagainya; latar belakang
lingkungan dan pengalaman, tekanan teman sejawat (peer effect); proyeksi, yaitu
kecenderungan manusia untuk melemparkan beberapa kesalahan pada orang lain
bisa menjadikan persepsi terhadap sesuatu berbeda; penilaian yang tergesa-gesa