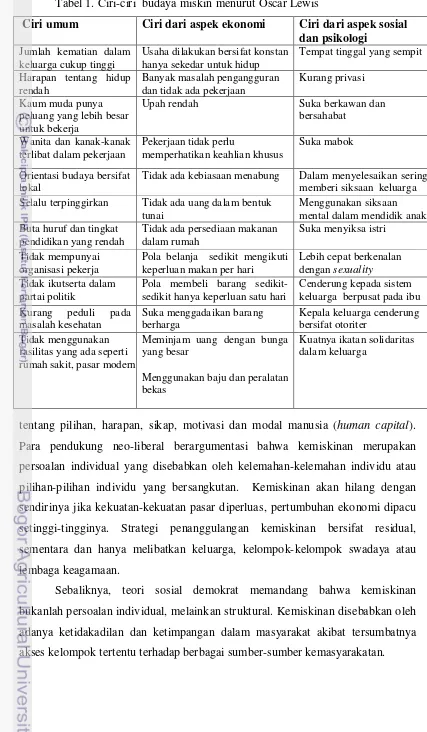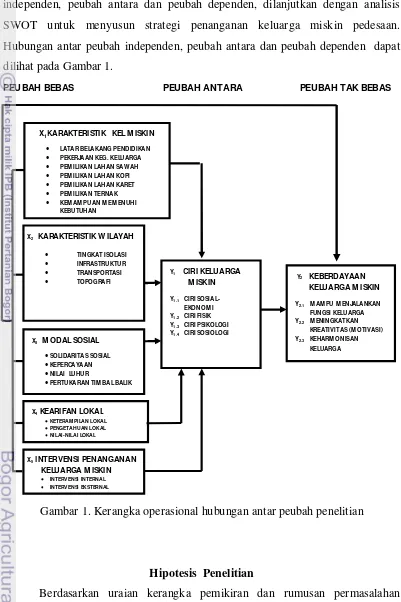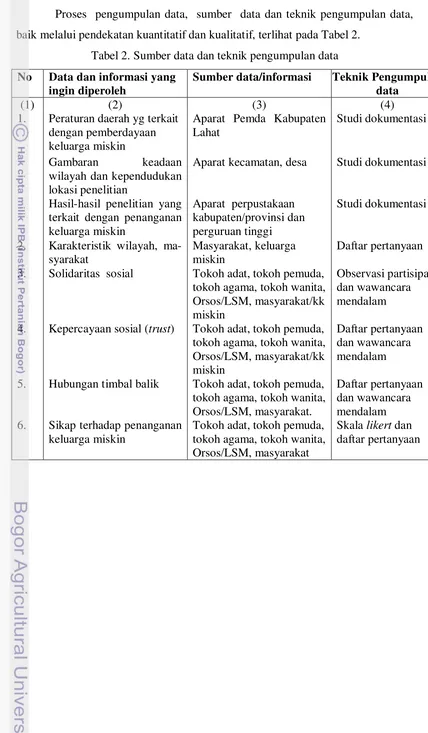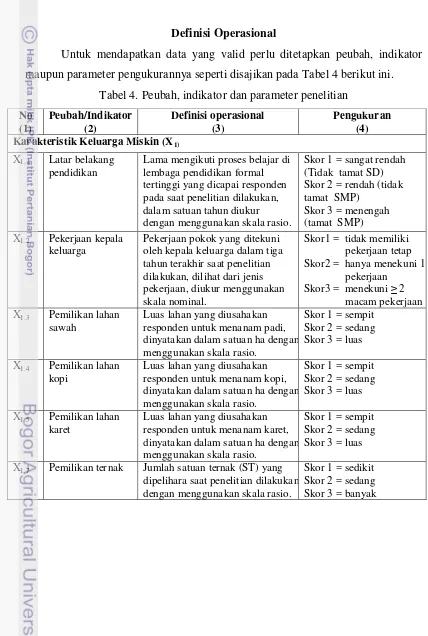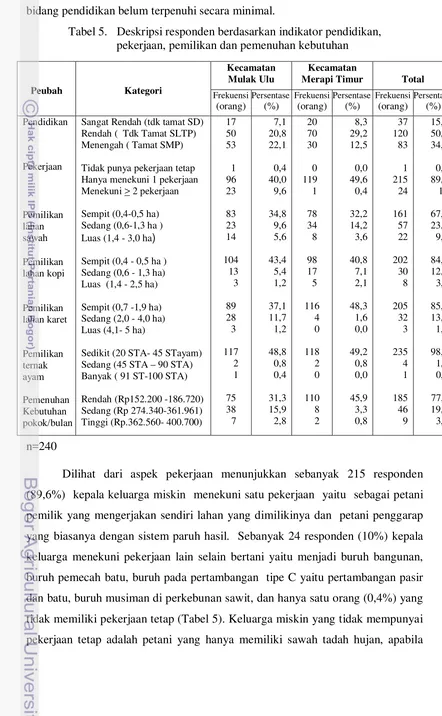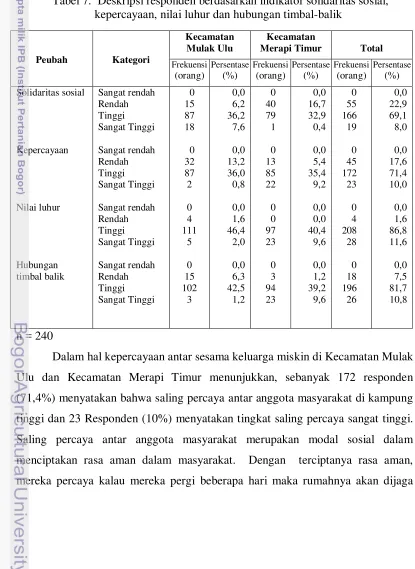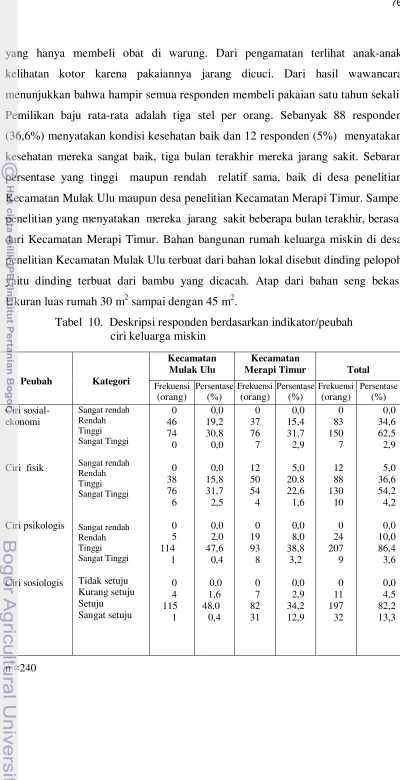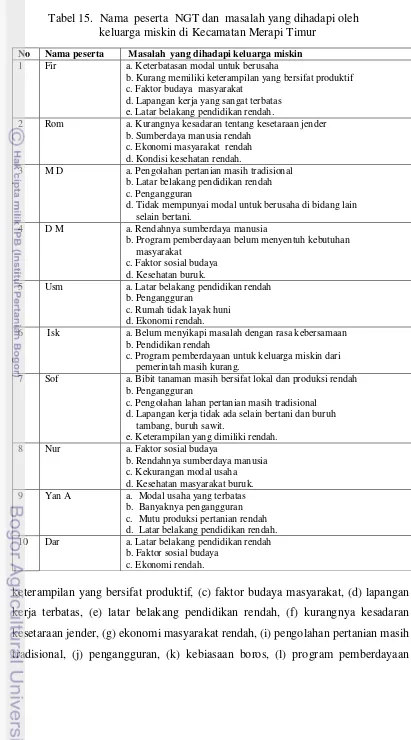STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN
KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN
LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
RAMLI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN
SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:
STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN KELUARGA
MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN.
Adalah benar merupakan karya saya dan saya buat sesuai petunjuk, arahan komisi
pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan
tinggi manapun. Semua sumber informasi yang dikutip telah dicantumkan dalam
Daftar Pustaka pada bagian akhir disertasi ini.
Bogor, Februari 2010
Ramli
NIM I.361070091
ABSTRACT
RAMLI, 2009: Strategy to promote capability of poor rural families in Lahat District South Sumatera Province (Supervised by: BASITA GINTING SUGIHEN as CHAIRMAN: DARWIS S GANI and AMIRUDDIN SALEH as MEMBERS)
Poor rural families are part of rural society which need to be improved in resources, in order that they can afford to run family function, have creativity in economy, social, physiology and sociology. Therefore poor families hopefully build harmonies in their life. This research was a descriptive correlation research which purposes are: (a) identify factors that cause poverty, (b) analyze characteristic of poor families from social economy, physical, physiology and sociology characteristic, (c) analyze dependability pattern of triggering factors and characteristic of poor families in promoting capability of poor families and (d) build strategies to promote capability of poor families according to trigger factors and characteristic of rural poor families. The Research result showed internal environment and external factors which influence capability of poor families in rural area. Trigger factor that emerge poor families which is poverty was already inherit by their elderly, because their elderly didn’t have wide farmland, low educational background (they didn’t pass the elementary school in average), didn’t have other skills besides farming. There were obvious correlation among social economy, social capital, local wisdom and capability of poor families, according to the data and information that acquired from the research. Therefore strategic concept was made and pointed, empowering competence of personal implementer of government program in sub district level, such as empowering poor families’ competence, promoting poor families participation in government and private programs that operate in rural area. Build poor families network with business world in marketing their farm products and giving them facilitation to get capital, seeds and tools that according to compete development that given to poor peoples.
Keywords: capability, poverty, family, empowerment
RINGKASAN
RAMLI. 2010. Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Di bawah bimbingan BASITA GINTING SUGIHEN, DARWIS S GANI dan AMIRUDDIN SALEH.
Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang populasinya cukup besar di Kabupaten Lahat. Penanganannya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program yang telah dilaksanakan di antaranya adalah Program Usaha Agrobisnis untuk Petani (PUAP) merupakan program/kegiatan Departemen Pertanian. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Tunai Langsung dari Departemen Sosial RI. Bantuan Bibit dari Pemerintah Daerah. Namun program tersebut baru menyentuh sebagian kecil masyarakat miskin, sehingga masih diperlukan suatu strategi yang efektif dan efisien dalam arti mampu mencapai sasaran yang lebih besar.
Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya keluarga miskin Pedesaan, (b) Mengidentifikasi karakteristik dan ciri keluarga miskin, modal sosial, kearifan lokal, dan bentuk-bentuk penanganan keluarga miskin yang telah dilaksanakan masyarakat dan pemerintah, (c) merumuskan strategi meningkatkan keberdayaan keluarga miskin pedesaan.
Dari hasil lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar (65,4%) responden mempunyai latar belakang pendidikan rendah (tidak tamat SLTP), yang tamat SLTP sebesar 34,6%. Pemilikan lahan sawah, kopi, karet kurang dari satu hektar. Potensi lain yang teridentifikasi ialah kebersamaan masyarakat termasuk keluarga miskin masih cukup baik. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keluarga miskin pedesaan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan mau bekerja keras.
hasil penelitian tersebut dirumuskan strategi penanganan keluarga miskin yang ditekankan pada penguatan kompetensi tenaga pemerintah di tingkat kecamatan, terjalinnya hubungan kerja yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kompetensi keluarga miskin melalui pendidikan nonformal, mendorong partisipasi masyarakat khususnya keluarga miskin dalam tahapan program di pedesaan, pemenuhan hak-hak dasar keluarga miskin yaitu kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, papan dan kebutuhan rasa aman.
©
Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2010
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
Tanpa mencantumkan atau menyebut sumber
a.
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan IPB.
2.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau
seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN
KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN
LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
RAMLI
Disertasi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pada
Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Disertasi : Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
Nama Mahasiswa : Ramli
Nomor Pokok : I.361070091
Program Studi : Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Menyetujui
Komisi Pembimbing
Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, MA Prof.Dr.Ir. Darwis S. Gani, MA Ketua Anggota
Dr. Ir. H. Amiruddin Saleh, MS Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana, Ilmu Penyuluhan Pembangunan,
Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
Tanggal Ujian: Tanggal Lulus:
PRAKATA
Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena
atas segala petunjuk dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan disertasi
dengan judul “Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.” Disertasi ini disusun sebagai salah
satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor pada Program Studi Ilmu
Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Keluarga miskin menjadi perhatian penulis, karena secara nasional masyarakat
miskin yang berada di pedesaan dan masalah kemiskinan kalau tidak ditangani
secara berencana dan terarah, maka akan mempunyai dampak besar yaitu
menimbulkan permasalahan sosial seperti anak terlantar, anak putus sekolah dan
kecacatan.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor
penyebab timbulnya keluarga miskin pedesaan, (b) menganalisis hubungan
karakteristik dan ciri keluarga miskin, modal sosial, kearifan lokal, intervensi
internal dan eksternal penanganan keluarga miskin dengan keberdayaan keluarga
miskin pedesaan serta (c) menyusun strategi bagaimana meningkatkan
keberdayaan keluarga miskin pedesaan. Dari hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam
merumuskan kebijaksanaan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar
masyarakat, khusus keluarga miskin. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
acuan bagi dunia usaha, organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang peduli kepada kehidupan keluarga miskin pedesaan.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:
(1) Bapak Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, MA selaku ketua Komisi Pembimbing,
Bapak Prof.Dr. Darwis S Gani, MA, Bapak Dr. H. Amiruddin Saleh MS
sebagai anggota Komisi Pembimbing, yang telah membimbing, mendorong
serta memberi masukan dalam penyusunan disertasi ini.
(2) Bapak Bupati Kabupaten Lahat beserta bapak Camat Mulak Ulu, bapak Camat
Merapi Timur yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk
mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Lahat.
(3) Kepada pimpinan jajaran Departemen Sosial RI yang telah memberikan
kesempatan untuk izin belajar mengikuti Program Strata Tiga di IPB Bogor.
(4) Kepada teman-teman Pejabat Fungsional Peneliti dan Widyaiswara
Departemen Sosial RI yang memberikan dorongan yang positif dan membuat
penulis selalu bersemangat untuk belajar.
(5) Teman-teman mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pembangunan Angkatan
2007 yang banyak membantu dalam proses penyelesaian studi.
(6) Kepada Istri penulis Ny. Indriany dan anak penulis drg Henny Kartikasari,
Dwisisca Kumala Putri SKM dan si bontot Tri Deasy Permata Hati yang selalu
memberikan semangat dan mendorong agar cepat menyelesaikan studi.
(7) Kepada teman, sahabat yang telah membantu penyelesaian disertasi ini
penulis ucapkan banyak terima kasih.
Akhirnya, penulis mengharapkan saran, kritik yang konstruktif guna
perbaikan disertasi ini dan diharapkan disertasi ini mempunyai andil dalam
penanganan keluarga miskin pedesaan.
Bogor, Februari 2010
Penulis
RAMLI
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Lembah Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera
Selatan pada tanggal 28 Januari 1954, sebagai anak kelima dari sepuluh
bersaudara, pasangan Bapak Hi. Muhammad Toha (almarhum) dan Ibu Hj
Selamah di Sukamerindu Pagar Alam.
Jenjang pendidikan yang penulis ikuti SD Negeri di Karang Caya
Kecamatan Jarai, SLTP Negeri di Kota Lahat, SPSA Negeri di Palembang tamat
tahun 1974, Akademi Administrasi Negara lulus tahun 1984, kemudian
melanjutkan Strata 1 di STIA Jakarta lulus tahun 1990. Pada tahun 2002 penulis
meneruskan studi Strata 2 Jurusan Administrasi Negara dengan konsentrasi
Otonomi Daerah di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2004.
Pada tahun 2007 penulis mendapat izin belajar ke jenjang Strata 3 program studi
Ilmu Penyuluhan Pembangunan di Institut Pertanian Bogor.
Penulis mulai bekerja di Departemen Sosial RI pada tahun 1976 dan
ditempatkan di Kantor Wilayah Departemen Sosial RI di Tanjung Ria Base-G
Jayapura Irian Jaya. Jabatan yang pernah dipangku adalah:
(1) Kepala Seksi Pembinaan Swadaya Masyarakat Bidang Bina Sosial
Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya.
(2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Sosial Departemen Sosial Jakarta.
(3) Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Sosial Jakarta.
(4) Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Sekretariat Balitbang Sosial Jakarta.
(5) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Balitbang Sosial
Jakarta.
(6) Kepala Bidang Program Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial Jakarta.
(7) Kepala Bidang Program Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial sampai dengan sekarang.
Diklat yang pernah diikuti antara lain diklat Administrasi Kepegawaian
yang diselenggarakan BAKN, Diklat Metodologi penelitian yang diselenggarakan
LIPI, Diklat Perencanaan dan Evaluasi, Diklat SEPALA, Diklat SEPAMA.
Karya ilmiah yang telah diterbitkan di antaranya (a) Partisipasi masyarakat
dan fungsinya dalam pembangunan, (b) Pengaruh teknologi terhadap perubahan
sosial, (c) Lumpur panas PT Lapindo Berantas dan permasalahan sosial
masyarakat Porong, (d) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur dan (e) Hubungan Sikap Petani terhadap Penerapan
Teknologi Panca Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Konawe Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Bogor, Februari 2010
Penulis
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL ...
DAFTAR GAMBAR ...
DAFTAR LAMPIRAN ...
PENDAHULUAN ………... Latar belakang ……….. Masalah Penelitian ……….. Tujuan penelitian ………... Manfaat penelitian ………...
TINJAUAN PUSTAKA ………. Tinjauan Penelitian Terdahulu……….. Kemiskinan ……….. Keluarga ……… Pemberdayaan ……….. Partisipasi ………. Masyarakat Pedesaan ………... Modal Sosial ………... Kearifan Lokal ………
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN …….. Kerangka Pemikiran ……….... Hipotesis Penelitian ………..
METODE PENELITIAN ………. Desain Penelitian ……….. Populasi dan Sampel ……… Pengumpulan Data ………... Skala Pengukuran ………. Definisi Operasional ………... Validitas dan Reliabilitas Instrumen ……….... Analisis Data ………
HASIL DAN PEMBAHASAN ... Gambaran Umum Kabupaten Lahat ... Kecamatan Mulak Ulu ... Kecamatan Merapi Timur ... Profil Keluarga Miskin Pedesaan ... Karakteristik Responden Keluarga Miskin ... Karakteristik Wilayah ... Modal Sosial ... Kearifan lokal ... Intervensi Penanganan Keluarga Miskin Pedesaan ...
xv
Ciri-ciri Keluarga Miskin ... Keberdayaan Keluarga Miskin ... Faktor Penyebab Timbulnya Keluarga Miskin Pedesaan ...
Hubungan Karakteristik Keluarga Miskin, Karakteristik Wilayah, Modal Sosial, Kearifan Lokal, dan Intervensi Penanganan dengan Keberdayaan Keluarga Miskin ... Hubungan Ciri Keluarga Miskin dengan Keberdayaan Keluarga Miskin ... Penyusunan Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan dengan Menggunakan Analisis SWOT ... Faktor Internal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Mulak Ulu ... Faktor Eksternal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Mulak Ulu ... Strategi Penanganan Keluarga Miskin di Kecamatan Mulak Ulu ... Faktor Internal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Merapi Timur ... Faktor Eksternal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Merapi Timur ... Strategi Penanganan Keluarga Miskin di Kecamatan Merapi Timur ... Strategi dan Program Prioritas untuk Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Lahat..
KESIMPULAN DAN SARAN ... Kesimpulan ... Saran ...
DAFTAR PUSTAKA ...
LAMPIRAN ...
75 78 79
88
93
95 96
99
103
103
106
108
108
114 114 115
116
120
DAFTAR TABEL
Halaman
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.Ciri-ciri budaya miskin menurut Oscar Lewis ...
Sumber data dan teknik pengumpulan data ...
Empat alternatif jawaban responden ...
Peubah, indikator dan parameter penelitian ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator pendidikan, pekerjaan, pemilikan dan pemenuhan kebutuhan ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator tingkat isolasi (infrastruktur, transportasi) dan topografi (tingkat kesuburan tanah) ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator solidaritas sosial, kepercayaan, nilai luhur dan hubungan timbal-balik ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator pengetahuan lokal, keterampilan lokal dan nilai-nilai lokal ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator penanganan keluarga miskin internal dan eksternal ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator/peubah ciri keluarga miskin ...
Deskripsi responden berdasarkan indikator keberdayaan keluarga ...
Peserta brainstorming dengan menggunakan teknik NGT di Kecamatan Mulak Ulu ...
Masalah keluarga miskin yang perlu diprioritaskan untuk ditangani di Kecamatan Mulak Ulu...
Peserta brainstorming dengan menggunakan teknik NGT di Kecamatan Merapi Timur ...
Nama peserta NGT dan jenis masalah yang dihadapi oleh keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...
Masalahan keluarga miskin yang perlu diprioritaskan untuk di tangani di Kecamatan Merapi Timur ...
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Nilai koefisien korelasi peubah ciri keluarga miskin dengan keberdayaan keluarga miskin pedesaan ...
Ringkasan faktor analisis internal kekuatan dan kelemahan keluarga miskin di Kecamatan Mulak Ulu ...
Ringkasan faktor analisis eksternal peluang dan ancaman keluarga miskin di Kecamatan Mulak Ulu ...
Matriks analisis SWOT untuk perumusan strategi penanganan keluarga miskin di Kecamatan Mulak Ulu ...
Ringkasan faktor analisis internal kekuatan dan kelemahan keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...
Ringkasan faktor analisis eksternal peluang dan tantangan keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...
Matriks SWOT analisis untuk perumusan strategi penanganan keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...
95
100
101
104
105
106
107
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1
2
Kerangka operasional hubungan antar peubah penelitian ...
Mekanisme strategi penanganan keluarga miskin pedesaan ...
37
112
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Peta lokasi penelitian ...
2. Kuesioner penelitian ...
3. Pedoman wawancara ...
4. Pedoman observasi ...
5. Pedoman studi dokumentasi... ...
6. Pedoman nominal group technique (NGT) ... 7. Gambar Penyelenggaraan NGT di Kecamatan Mulak Ulu ...
8. Gambar penjelasan kepada masyarakat Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu tentang maksud dan tujuan Penelitian ...
9. Gambar rumah keluarga miskin di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu ...
10.Gambar rumah keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...
11.Gambar Keluarga miskin sampel Penelitian setelah selesai mendapat penjelasan maksud dan tujuan penelitian di Kecamatan Merapi Timur ...
12.Gambar suasana penyelenggaraan NGT di Kecamatan Merapi Timur ...
13.Surat izin penelitian dari Sekolah Pascasarjana IPB Bogor ...
14.Surat izin pemberitahuan penelitian Dari Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ...
15.Surat pemberitahuan penelitin Dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ...
16.Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lahat ...
122
123
135
138
141
144
147
148
149
149
151
152
153
154
156
157
1
PENDAHULUAN
Latar belakang
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaannya melibatkan berbagai
disiplin ilmu antara lain ilmu kesejahteraan sosial, antropologi, sosiologi,
psikologi, hukum, manajemen, administrasi negara. Sasaran pembangunan
kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Penyandang masalah kesejahteraan sosial, menurut Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial (2008), meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak
nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut
usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga
binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga
berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah psikologis, komunitas adat
terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja
migran terlantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), keluarga rentan dan
keluarga fakir miskin.
Kemiskinan merupakan akar masalah dari permasalahan kesejahteraan
sosial lainnya, oleh karenanya rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat
dapat menjadi ujung tombak ekonomi, yang diharapkan dapat berkembang pada
keluarga yang lebih besar (kerabat) hingga pembentukan perkumpulan yang
bersifat ekonomi lainnya. Sebaliknya, bila keluarga miskin tidak segera ditangani
maka ia akan makin terpuruk, tidak mempunyai aset untuk produksi, tidak
mempunyai keterampilan dan cenderung menjadi pasrah. Rumah tangga miskin
seperti ini sangat rapuh dan makin terpuruk apabila kepala keluarga pencari
nafkah meninggal, sakit, terkena pemutusan hubungan kerja, terkena bencana
alam dan atau konflik sosial lainnya.
Keluarga miskin tidak mempunyai kemampuan menghadapi resiko-resiko
di atas, karena pada umumnya masyarakat/keluarga miskin tidak mempunyai
investasi atau aset. Sedangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti
organisasi sosial lokal, kearifan lokal, modal sosial dan potensi alam yang
bernilai ekonomis di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat belum
2 Modal sosial masyarakat Indonesia cukup beragam dan dapat dijadikan
pilihan atau alternatif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
khususnya keluarga miskin di pedesaan. Putnam (2000) menunjukkan bukti
bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial.
Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila ciri-ciri berikut ini
dimiliki oleh masyarakat: (1) hadirnya hubungan yang erat antar anggota
masyarakatnya dan (2) adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang
memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa.
Ada saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat.
Modal sosial memungkinkan manusia bekerjasama untuk menghasilkan
sesuatu yang besar. Akumulasi pengetahuan akan berjalan lebih cepat melalui
interaksi antar manusia. Hal tersebut menjadi kekuatan organisasi, karena dia
menciptakan berbagai inovasi. Individu yang memiliki modal sosial yang tinggi
ternyata lebih maju dalam karir jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki
modal sosial yang rendah. Konpensasi yang diperoleh pekerja juga dipengaruhi
oleh modal sosial yang dimilikinya (Burt 1997). Demikian pula suksesnya
seseorang di dalam memperoleh pekerjaan juga dipengaruhi oleh modal sosial
yang dimilikinya (Lin & Dumin 1996). Dalam penanganan kemiskinan di
pedesaan, organisasi sosial lokal, modal sosial dan kearifan lokal menjadi aspek
penting. Dengan menumbuhkan, menggerakkan potensi dan sumber-sumber yang
ada di masyarakat desa, maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial di pedesaan.
Berdasarkan buku Kabupaten Lahat dalam Angka yang dikeluarkan
Bappeda Kabupaten Lahat (2008), Kabupaten Lahat terdiri dari 21 kecamatan dan
365 kelurahan/desa. Jumlah penduduk adalah 740.217 jiwa terdiri dari 370.217
jiwa laki-laki dan 370.000 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut menurut
data Dinas Sosial Kabupaten Lahat (2009) terdapat permasalahan kesejahteraan
sosial keluarga miskin sebanyak 2.084 kepala keluarga atau lebih kurang 10.420
jiwa (1,41%). Permasalahan keluarga miskin tersebut tersebar di 21 kecamatan
yaitu Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Pulau
Pinang, Gumai Ulu, Pagar Gunung, Kota Agung, Tanjung Tebat, Mulak Ulu,
3
Barat, Kikim Selatan dan Kikim Tengah. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
Populasi keluarga miskin yang cukup besar ada di Kecamatan Lahat (867
kepala keluarga), Kecamatan Merapi Timur (288 kepala keluarga), Kecamatan
Kikim Barat (248 kepala keluarga), Kecamatan Mulak Ulu (240 kepala keluarga),
Kecamatan Pagar Agung (90 kepala keluarga) dan Kecamatan Gumay Talang (65
kepala keluarga). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada meliputi
nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat yang masih dijunjung tinggi, kegiatan
kebersamaan seperti gotong-royong masih cukup tinggi dan tokoh masyarakat
masih menjadi panutan masyarakat.
Lembaga sosial masyarakat dan organisasi sosial yang ada berupa
organisasi sosial yang menangani anak yatim piatu terlantar ada sebanyak dua
buah dengan kapasitas tampung masing-masing 50 jiwa. Organisasi sosial yang
bergerak di bidang pendidikan keagamaan sebanyak satu buah yang mengelola
pendidikan Taman Kanak-Kanak/TK, Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah
Pertama/SMP dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA.
Dalam Implementasi penanganan masalah kesejahteraan sosial belum
terjalin koordinasi antara pemerintah dengan organisasi sosial maupun dengan
masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada
belum besar. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kepedulian masyarakat
terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
Berdasarkan data di lapangan diperoleh gambaran bahwa keluarga
miskin di pedesaan tertinggal di Kabupaten Lahat belum banyak disentuh oleh
program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Pranata sosial lokal
juga belum berbuat untuk menangani keluarga miskin. Yayasan sosial pada
tingkat kecamatan dan kecenderungan masih menangani anak yatim piatu. Dalam
lingkup masyarakat secara tradisional keluarga miskin masih terbatas ditangani
oleh kerabat terdekat, seperti paman, kakek, kakak atau keluarga terdekat lainnya
(exstended family). Masyarakat dalam sistem sosial yang luas belum ikut menangani keluarga miskin.
Kondisi di atas memperlihatkan bahwa penanganan keluarga miskin yang
4 jika dalam kerabat tersebut semua tergolong keluarga miskin, maka keluarga
miskin tersebut tidak akan mendapat bantuan secara optimal dari kerabatnya.
Akibatnya timbul masalah sosial baru dalam keluarga miskin tersebut seperti anak
kurang gizi, ketidakmampuan menyekolahkan anak pada tingkatan tertentu dan
atau tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan akses modal termasuk
mendapatkan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan.
Di lain pihak banyak anggota masyarakat di desa yang secara ekonomi dan
latar belakang pendidikan cukup baik, namun belum menunjukkan kepedulian
terhadap permasalahan sosial yang ada di wilayahnya, khususnya kepedulian
terhadap keluarga miskin. Terkait dengan hal tersebut perlu suatu konsep terpadu
menyangkut penyampaian informasi melalui penyuluhan sosial, pelatihan jangka
pendek kepada masyarakat dalam upaya mengubah cara pandang (mindset) masyarakat terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya.
Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang potensi dan sumber
yang dapat digali dan dikembangkan agar masyarakat mau berpartisipasi aktif
dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat atau individu yang kurang
beruntung, khususnya kepada keluarga miskin, dipandang perlu mengadakan
penelitian secara mendalam mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan
keberdayaan keluarga miskin pedesaan dan strategi meningkatkan
keberdayaannya (Kasus di Kecamatan Mulak Ulu dan Merapi Timur Kabupaten
Lahat Provinsi Sumatera Selatan). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat
disusun strategi meningkatkan keberdayaan keluarga miskin pedesaan di
Kabupaten Lahat.
Masalah penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalahan sosial keluarga miskin di
pedesaan Kabupaten Lahat di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai
berikut:
1. Apa faktor penyebab keluarga miskin di pedesaan?
2. Bagaimana hubungan karakteristik dan ciri keluarga miskin, modal sosial,
kearifan lokal, intervensi ekternal dan internal dengan keberdayaan keluarga
5 3. Strategi seperti apa yang tepat untuk meningkatkan keberdayaan keluarga
miskin pedesaan?
Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara
umum penelitian ini bertujuan menemukan profil masyarakat miskin di pedesaan
khususnya di Kabupaten Lahat. Diharapkan dengan diketahuinya profil
masyarakat miskin di pedesaan ini dapat dirumuskan strategi mengatasinya yang
relatif lebih efektif dan efisien. Secara lebih rinci tujuan khusus yang ingin dicapai
adalah:
1. Mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya keluarga miskin di pedesaan.
2. Menganalisis hubungan karakteristik dan ciri keluarga miskin pedesaan,
karakteristik wilayah, modal sosial, kearifan lokal, intervensi internal dan
eksternal penanganan keluarga miskin dengan keberdayaan keluarga miskin.
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan keberdayaan keluarga miskin
pedesaan.
Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil-hasil penelitian ini
diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yakni:
1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan
baru yaitu hubungan keberdayaan kemiskinan dengan tingkat partisipasi
masyarakat.
2. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan atau masukan bagi
pemerintah untuk menyusun strategi meningkatkan partisipasi masyarakat,
dunia usaha dalam penanganan keluarga miskin, dan diharapkan menjadi
acuan bagi organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati
permasalahan sosial dalam melaksanakan intervensi pemecahan masalah
6
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian implementasi kebijakan program pemberdayaan keluarga
miskin di delapan provinsi di Indonesia oleh Mujiyadi et al. (2007) menyebutkan bahwa bantuan kepada nelayan miskin di Provinsi Riau Kepulauan berupa perahu
motor dan peralatan jaring untuk menangkap ikan. Bantuan ternak sapi,
kambing diberikan di tujuh provinsi yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Sebagian besar
(59,3%) responden anggota kelompok usaha merasa perkembangan usahaternak
sapi berkembang baik, sisanya (40,7%) merasa belum mengalami perkembangan.
Secara ekonomi usahaternak belum dirasakan oleh keluarga miskin, karena
sapi baru bisa berproduksi kurang lebih 1,5 tahun. Dapat dibayangkan selama 1,5
tahun keluarga miskin tersita waktunya untuk menyediakan pakan ternak sapi dan
merawat sapi. Banyak waktu tersita yang seharusnya digunakan keluarga miskin
tersebut untuk mencari nafkah, mereka gunakan untuk memelihara ternak.
Namun secara psikologis mereka senang karena menganggap ternak sapi yang
dimiliki merupakan tabungan di masa mendatang dan mereka merasakan status
(harkat dan martabat) menjadi meningkat. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut
diperoleh informasi bahwa bantuan sapi pada awalnya bukan kebutuhan yang
mendesak. Bantuan yang sangat mereka harapkan adalah bantuan usaha yang
cepat menghasilkan uang.
Bantuan kepada nelayan di Provinsi Kepulauan Riau, ditinjau dari segi
ekonomi, secara umum para anggota kelompok belum dapat merasakan hasil dari
pemberdayaan yang mereka ikuti. Hal ini mengingat pada saat evaluasi, program
baru berjalan kurang lebih tiga bulan. Namun dengan adanya bantuan motor
tempel/ketinting, maka aktivitas nelayan mencari ikan dapat menjangkau jarak
lebih jauh dan waktu yang digunakan lebih singkat. Ada beberapa anggota
kelompok belum memanfaatkan bantuan yang diberikan, karena mereka
sebenarnya telah memiliki perahu lengkap dengan motor tempel yang lebih besar.
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir
Miskin (P2FM) antara lain dalam penumbuhan kelompok dan penentuan bantuan,
7 yang diberikan tidak melibatkan seluruh calon anggota kelompok, sehingga
banyak anggota kelompok yang tidak memahami cara-cara pengelolaan usaha
bersama. Di samping itu rendahnya kualitas sumberdaya manusia pendamping
ditandai oleh pendamping tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
manajemen usaha bersama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
implementasi P2FM belum melibatkan calon sasaran garapan terutama dalam
persiapan yaitu penentuan program atau kegiatan unggulan yang secara riil
menjadi kebutuhan masyarakat.
Penelitian pekerja anak dari keluarga miskin, yang dilakukan Marwanti
(2008) menunjukkan bahwa upah yang didapatkan anak berkisar Rp. 150.000- Rp.
300.000 per minggu. Besar-kecilnya upah sangat tergantung dari borongan
pekerjaan yang ada. Upah tersebut sebagian diberikan kepada orang tua dan
dipakai sendiri untuk makan, jajan dan ditabung. Keluarga responden penelitian
termasuk keluarga luas dalam arti keluarga tidak hanya terbatas pada ayah, ibu
dan anak saja, melainkan kakek, nenek, cucu, menantu tinggal bersama dalam
satu rumah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan pekerja anak menjadi
tumpuan keluarganya dalam menopang kebutuhan hidup keluarga. Orang tua
pekerja anak lebih banyak bekerja serabutan seperti membuat kantong kertas,
kaos, topi dan bendera. Penghasilan dari pekerjaan tersebut sangat tergantung dari
pesanan, kalau lagi tidak ada pesanan berarti menganggur. Aspek penting yang
muncul dari penelitian ini adalah anak yang semestinya diarahkan untuk belajar
demi masa depannya, tapi justru menjadi tulang punggung keluarga dalam
mencari nafkah.
Pada penelitian pemberdayaan sosial keluarga pasca bencana alam di
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), hasil amatan Gunawan et al. (2007) di lapangan menunjukkan bahwa fungsi keluarga dikategorikan sebagai:
(1) Fungsi keagamaan.
Bencana tsunami yang demikian dahsyat, telah merusak berbagai sarana
ibadah seperti mesjid, musholah dan berbagai tempat ibadah lainnya. Guna
melaksanakan ibadah, masyarakat menggunakan sarana darurat apa adanya.
Pelaksanaan ibadah keagamaan ini menunjukkan kekuatan spiritual
8 berjamaah, upaya yang bersifat individual dalam keluarga tetap dijalankan.
Hal ini memperlihatkan fungsi keagamaan dalam keluarga masih merupakan
modal dasar untuk dapat dikembangkan ke arah terwujudnya ketahanan sosial
keluarga. Apabila ketahanan sosial keluarga dapat terwujud maka fungsi
keluarga juga dapat dijalankan secara optimal.
(2) Fungsi sosialisasi dan pendidikan.
Fungsi ini belum normal, karena kondisi keluarga masih mengalami masalah
sosial dan trauma akibat bencana. Tempat hunian masih darurat/sementara,
dengan sarana pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga yang masih sangat
terbatas, sehingga belum memungkinkan pelaksanaan sosialisasi dan
pendidikan dalam keluarga dan di masyarakat dapat dilaksanakan secara
wajar.
(3) Fungsi ekonomi.
Akibat bencana tsunami, banyak anggota masyarakat yang kehilangan
pekerjaan, mereka menjadi penganggur, penghidupan mereka banyak
bergantung bantuan jatah hidup (jadup). Kegiatan ekonomi masyarakat
umum, sudah mulai menampakkan perkembangan yang signifikan. Banyak
pasar tradisional mulai beroperasi, walaupun daya beli masyarakat masih
relatif rendah.
Kajian pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah
pesisir pantai oleh Mujahidin et al. (2007) menunjukkan bahwa seluruh kelompok telah menjalankan usahanya dengan memanfaatkan dana stimulan yang
diterima. Kegiatan usaha yang telah berjalan meliputi warung sembako, usaha
salon, counter hand phone (HP), usaha menjahit dan usaha penangkapan ikan. Setiap kelompok dalam menjalankan usahanya dihadapkan oleh
permasalahan di antaranya: anggota kelompok tidak aktif dalam berusaha,
kemacetan piutang, lambannya usaha dan manajemen usaha yang kurang baik. Di
samping itu, di kalangan para kelompok nelayan yang menjadi masalah adalah
pada musim ombak, nelayan tidak melaut dan terjadilah musim paceklik. Semua
permasalahan tersebut dibahas dalam kelompok dan dicarikan upaya-upaya
penyelesaiannya. Hasil kajian memperlihatkan bahwa bantuan yang diberikan
9 penelitian ini tergambar bahwa pasca bencana banyak anggota masyarakat yang
kehilangan mata pencaharian, kehilangan aset untuk mencari nafkah. Namun
dalam menghadapi cobaan tersebut tidak pasrah, mereka berusaha bangkit dari
keterpurukan dengan berupaya mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan
menggunakan sarana atau tempat apa adanya.
Kemiskinan Teori Kemiskinan
Dalam pandangan teori budaya miskin, menurut Lewis (1966), kemiskinan
itu cenderung kekal karena diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu
sistem sosial yang mereka warisi bersama. Pandangan ini mendapat dukungan
seperti yang dibicarakan Lipton (1976) bahwa kemiskinan absolut itu disebabkan
oleh dua faktor yaitu pertama faktor genetik yaitu kemiskinan yang telah ada yang
terus diwarisi sejak mereka lahir disebabkan kondisi keluarga mereka miskin,
kedua kondisi lingkungan sosial yang nyata dan mengekali nilai atau kebiasaan
yang diamalkan orang miskin juga telah menyumbang kepada kemiskinan secara
budaya.
Lewis (1966) menyatakan sekurang-kurangnya ada lima kondisi yang
menyebabkan kekalnya budaya miskin. Budaya miskin lahir dalam masyarakat
karena (1) mengamalkan sistem ekonomi tunai, upah kerja dan produksi untuk
tujuan keuntungan; (2) tingginya angka pengangguran dan pekerja tanpa skill; (3) tingkat upah yang sangat rendah; (4) berlakunya kegagalan sistem sosial, politik
dan ekonomi dalam membantu masyarakat berpendapatan rendah; dan (5) adanya
suatu sistem nilai yang diamalkan dalam kelas dominan yaitu kelompok kaya
sebagai pengaruh kelas lainnya.
Secara rinci Anthony Leeds (Balitbangda Provinsi Riau 2006) telah
meringkas beberapa ciri budaya miskin yang dirumuskan Oscar Lewis seperti
terlihat pada Tabel 1.
Cheyne, O’Nrien dan Beigrave (Suharto 2006) mengemukakan bahwa ada
dua teori utama (grand theory) tentang kemiskinan, yaitu: (1) teori neo-liberal dan (2) teori sosial demokrat. Teori neo-liberal mengatakan komponen penting dari
sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Menurut Sherraden (2006) teori
10 Tabel 1. Ciri-ciri budaya miskin menurut Oscar Lewis
Ciri umum Ciri dari aspek ekonomi Ciri dari aspek sosial dan psikologi
Jumlah kematian dalam keluarga cukup tinggi
Usaha dilakukan bersifat konstan hanya sekedar untuk hidup
Tempat tinggal yang sempit Harapan tentang hidup
rendah
Banyak masalah pengangguran dan tidak ada pekerjaan
Kurang privasi Kaum muda punya
peluang yang lebih besar untuk bekerja
Upah rendah Suka berkawan dan
bersahabat Wanita dan kanak-kanak
terlibat dalam pekerjaan
Pekerjaan tidak perlu
memperhatikan keahlian khusus
Suka mabok
Orientasi budaya bersifat lokal
Tidak ada kebiasaan menabung Dalam menyelesaikan sering memberi siksaan keluarga Selalu terpinggirkan Tidak ada uang dalam bentuk
tunai
Menggunakan siksaan mental dalam mendidik anak Buta huruf dan tingkat
pendidikan yang rendah
Tidak ada persediaan makanan dalam rumah
Suka menyiksa istri
Tidak mempunyai organisasi pekerja
Pola belanja sedikit mengikuti keperluan makan per hari
Lebih cepat berkenalan dengan sexuality
Tidak ikutserta dalam partai politik
Pola membeli barang sedikit-sedikit hanya keperluan satu hari
Cenderung kepada sistem keluarga berpusat pada ibu Kurang peduli pada
masalah kesehatan
Suka menggadaikan barang berharga
Kepala keluarga cenderung bersifat otoriter
Tidak menggunakan fasilitas yang ada seperti rumah sakit, pasar modern
Meminjam uang dengan bunga yang besar
Kuatnya ikatan solidaritas dalam keluarga
Menggunakan baju dan peralatan bekas
tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan modal manusia (human capital). Para pendukung neo-liberal berargumentasi bahwa kemiskinan merupakan
persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan individu atau
pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan
sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas, pertumbuhan ekonomi dipacu
setinggi-tingginya. Strategi penanggulangan kemiskinan bersifat residual,
sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau
lembaga keagamaan.
Sebaliknya, teori sosial demokrat memandang bahwa kemiskinan
bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh
adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya
11 Berdasarkan konsep dan teori kemiskinan tersebut maka penelitian ini
diarahkan pada pendekatan yang berkaitan dengan ciri kemiskinan dari aspek
sosial ekonomi, fisik, psikologikal dan dan sosiologis lebih banyak diarahkan
pada persoalan individu dalam keluarga.
Batasan dan Dimensi Kemiskinan
Pembicaraan tentang permasalahan sosial tentu tidak terlepas dari
permasalahan kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan merupakan masalah
multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial,
budaya dan politik. Kemiskinan dapat dianggap sebagai faktor utama
menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial.
Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan
sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya yang dimaksudkan
di sini tidak hanya aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.
Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung
dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan
standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Badan Pusat Statistik (2006) menyebutkan bahwa garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah
yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan
setara 2.100 kalori perorang perhari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri
dari perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, aneka barang dan
jasa lainnya.
Menurut Justika (1999), kemiskinan merupakan keadaan
ketidakberfung-sian individu atau kelompok atau keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialnya
yang ditandai dengan:
(1) Ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan dasar sehari-hari, seperti tidak
mampu memenuhi keperluan pangan (bahan makanan), sandang (pakaian),
papan (rumah), air bersih, kesehatan dan kebutuhan dasar pendidikan.
(2) Ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosialnya, seperti tidak
mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai
12 (3) Ketidakmampuan dalam menangani masalah sosial yang dihadapinya, karena
tidak mempunyai keahlian/keterampilan, kurang mempunyai motivasi,
kurang percaya diri, tidak mempunyai kemampuan mengambil keputusan.
Suharto (2003) mengemukakan bahwa secara konseptual, pekerja sosial
memandang kemiskinan merupakan masalah multidimensional, yang meliputi
sosial ekonomi dan struktur individual. Lebih lanjut Suharto (2003) menjelaskan
ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerja sosial yaitu:
(1) Kelompok yang paling miskin (destitute) atau sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara tetap memiliki pendapatan di bawah garis
kemiskinan dan umumnya tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan dan
tidak mempunyai akses untuk meningkatkan kesejahteraan.
(2) Kelompok miskin (poor), kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki jalan masuk terhadap peningkatan
pendapatan, seperti memiliki sumber-sumber keuangan, memiliki pendidikan
yang memadai atau tidak buta huruf.
(3) Kelompok rentan. Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari miskin,
karena memiliki tingkat kehidupan yang relatif lebih baik dibanding kelompok
paling miskin dan miskin. Namun sebenarnya kelompok ini sering disebut
near poor (mendekati miskin), karena kelompok ini masih sangat rapuh terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Bila terjadi kondisi seperti
krisis ekonomi, maka kelompok ini sangat rentan menjadi miskin bahkan bisa
menjadi kelompok paling miskin.
Hasil survei Badan Pusat Statistik (2006) dengan menggunakan garis
kemiskinan Rp. 152.847,00 perkapita per bulan, maka diketahui jumlah warga
miskin sebanyak 39,1 juta orang atau 17,75% dari total penduduk Indonesia.
Kemudian Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar USD 2 perkapita
perhari atau setara Rp. 540.000,00 perbulan, maka jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai lebih dari 60% dari total penduduk.
Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur untuk mengukur kemiskinan
yaitu pangan, pakaian, perumahan, pendidikan dan pekerjaan. Pangan dapat
dilihat secara kasat mata dari jumlah penduduk di penjuru dunia khususnya di
13 kekurangan gizi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya laju pertumbuhan
penduduk dibandingkan produksi pangan.
Ditinjau dari aspek pakaian terlihat perbedaan yang menyolok antara
negara kaya dengan negara miskin. Di negara miskin masih banyak orang
bertelanjang atau buruk pakaiannya akibat tidak mampu membeli. Ditinjau dari
aspek perumahan kondisinya dapat dilihat dari penggunaan material, tata ruang,
ukuran atau luas rumah, dibandingkan dengan kapasitas penghuni. Selanjutnya
dari aspek pendidikan terlihat dari tingkat buta huruf atau pendidikan rendah bagi
orang dewasa, sehingga dengan latar belakang pendidikan rendah tersebut, mereka
tidak mampu bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang
besar.
Menurut Sajogyo (1991), yang paling mudah menemukan ukuran
kemiskinan adalah pada tingkat ekonomi rumah tangga yaitu tingkat mencapai
kecukupan dalam hal kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan fisik
seperti pangan, perumahan, pakaian dan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan
dan jasa. Dalam hal pangan ada ukuran obyektif berdasar ilmu gizi berupa ukuran
kecukupan pangan kalori yang dibutuhkan perhari yaitu 2.100 kalori.
Lebih lanjut Sajogyo (1991) mengemukakan bahwa sebenarnya masih
dapat dibuat satu garis kemiskinan tambahan yaitu yang lebih rendah dari garis
kemiskinan Badan Pusat Statistik 1984, misalnya pada tingkat pangan yang tak
mencapai 85% dari tingkat 2.100 kalori/orang/hari yang dianjurkan. Pada tingkat
kalori seburuk itu pada satuan rumah tangga, pencari nafkah khususnya pekerja
kasar tidak cukup kuat untuk bekerja, anak balita kurang gizi.
Kemiskinan secara sosial psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan
dan struktur sosial yang mendukung dalam mengadakan kesempatan peningkatan
produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan
yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi
seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat, meliputi
faktor internal dan eksternal.
Faktor internal penyebab dari kemiskinan ketika nilai-nilai budaya yang
dianut oleh orang miskin diidentikkan dengan sikap malas, mudah menyerah pada
14 sistem atau struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan
orang miskin dapat bekerja (Suparlan 1984).
Soetrisno (2001) membagi tahap kemiskinan menjadi dua yaitu tahap
destitute (tahap kemiskinan yang terendah yaitu hidup di bawah garis kemiskinan), tahap ini disebut miskin papa dan tahap near poor (hidup relatif lebih baik), namun keadaan ini belum stabil, dalam artian sewaktu-waktu
kelompok ini menghadapi suatu krisis maka dengan cepat kelompok near poor itu akan melorot lagi statusnya menjadi kelompok destitute.
Chamber (1983) menyimpulkan bahwa inti dari kemiskinan terletak pada
deprivation trap atau jebakan kekurangan. Selanjutnya Chamber (1983) menjelaskan bahwa deprivation trap terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin. Kelima ketidakberuntungan itu adalah: (1)
kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan dan
(5) ketidakberdayaan. Kelima hal tersebut saling kait satu sama lain, sehingga
merupakan deprivation trap. Terkait dengan lima ketidakberuntungan ini Chamber (1983) menganjurkan agar dua jenis ketidakberuntungan yang dihadapi
keluarga miskin yakni kerentanan dan ketidakberdayaan menjadi perhatian utama.
Menurut Soetrisno (2001), kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu
kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu
kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan distribusi. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan
berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Artinya kondisi
kemiskinan yang terjadi antar kelompok satu dengan kelompok yang lain
mungkin saja berbeda.
Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK 2004)
menjelaskan dimensi kemiskinan:
(1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan
papan).
(2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
(3) Tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk
15 (4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
(5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.
(6) Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
(7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan.
(8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
(9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok
marjinal dan terpencil).
Midgley (1995) mengatakan tiga penyebab utama kemiskinan yaitu:
(1) Human capital deficiencies: berarti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan manusia, sehingga
mendapatkan pekerjaan yang rendah dan tentunya dengan gaji/pendapatan
yang rendah.
(2) Insufficient demand for labor: rendahnya permintaan akan tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran. Pengangguran menyebabkan orang
tidak memiliki pendapatan, daya beli rendah, akhirnya tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasar.
(3) Discrimination: adanya perlakuan berbeda terhadap golongan tertentu terutama dalam aksesibilitas sumberdaya dan adanya dominasi pihak tertentu
terhadap sumberdaya tersebut.
Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (2004) mengidentifikasi
penyebab kemiskinan, yaitu:
(1) Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan
dasar termasuk (a) modal sumberdaya manusia, pendidikan formal,
keterampilan dan kesehatan yang memadai, (b) modal produksi misalnya
lahan dan akses terhadap kredit, (c) modal sosial misalnya jaringan sosial
dan akses terhadap kebijakan, keputusan politik dan (d) sarana fisik,
termasuk hidup di daerah terpencil.
(2) Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan karena krisis
16 pekerjaan (PHK), konflik sosial dan politik, bencana alam, terserang
penyakit, sakit.
(3) Tidak ada suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di
dalam negara, tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari
kejahatan, adanya intimidasi, kebijakan publik yang tidak mendukung upaya
penanggulangan kemiskinan.
Giddens (2002) mengelompokkan teori kemiskinan ke dalam dua
perspektif. Pertama adalah perspektif yang memandang orang miskin bertanggung
jawab atas kemiskinannya. Kedua adalah perspektif yang memandang kemiskinan
adalah hasil dari kekuatan-kekuatan struktural dalam masyarakat. Menurut
Giddens (2002), perspektif yang pertama cenderung menyalahkan orang miskin.
Perspektif kedua menyalahkan sistem. Dalam perspektif pertama
dikatakan bahwa orang miskin dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk
berhasil, karena kelemahan pada tingkat individual, seperti kurangnya motivasi,
kurang keterampilan. Di sisi lain, pada perspektif kedua memandang orang
miskin disebabkan oleh kekuatan-kekuatan struktural dan orang miskin tidak
berdaya untuk mengatasinya.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Strategi, menurut McNicholas (1977) adalah suatu seni menggunakan
kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui
hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi paling menguntungkan.
Koteen (1991) mengatakan bahwa ada beberapa tipe strategi, antara lain
(1) strategi organisasi, (2) strategi program, (3) strategi pendukung sumberdaya
dan (4) strategi kelembagaan.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Bappenas (2005) telah
menetapkan lima Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yaitu:
(1) Perluasan kesempatan, yaitu untuk menciptakan kondisi dan lingkungan
ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin, baik
laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya
dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara
17 (2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yaitu memperkuat kelembagaan
sosial, ekonomi, politik, budaya dan memperluas partisipasi masyarakat
miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar.
(3) Peningkatan kapasitas yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar dan
kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan
agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
(4) Perlindungan sosial, yaitu untuk memberikan perlindungan dan rasa aman
bagi kelompok yang rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin,
orang jompo, anak terlantar, baik laki-laki maupun perempuan yang
disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik
sosial).
(5) Penataan kemitraan global, yaitu untuk mengembangkan dan menata ulang
hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan ke
empat strategi tersebut.
Menurut Ancok (1995), strategi penting dan dapat berkesinambungan
yang dapat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menggunakan
institusi lokal yakni mekanisme jaminan sosial yang hidup di dalam komunitas
tempatan. Strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis komunitas
setempat.
Ada dua strategi yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan
berbasis tempatan. Pertama strategi pemberdayaan rumah tangga, rumah tangga
miskin di pedesaan dan perkotaan yaitu mengatasi kemiskinan dengan menguasai
potensi, dengan cara mereka sendiri. Strategi utama biasanya dengan
memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga pria dan wanita, dewasa
maupun anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya
wanita berperan ganda. Selain terlibat dalam kegiatan reproduksi yang langsung
menghasilkan pendapatan. Pada rumah tangga lapisan bawah atau miskin
seringkali peranan wanita mencari nafkah lebih nyata dibandingkan pada rumah
18 Menurut Hart (1986), konsolidasi tenaga kerja dalam strategi alokatif
rumah tangga miskin itu sangat ketat. Dalam strategi ekonomi rumah tangga
miskin pedesaan misalnya, wanita seperti juga pria biasanya memiliki peranan
yang sangat penting sebagai pencari nafkah di bidang pertanian maupun non
pertanian. Hal ini berarti, memberdayakan anggota rumah tangga yang laki-laki
sama pentingnya dengan memberdayakan anggota rumah tangga yang perempuan.
Strategi yang kedua adalah yang bertumpu kepada kekuatan komunitas
desa itu sendiri, menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di dalam komunitas
pedesaan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena upaya mengatasi kemiskinan
juga dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Di kalangan rumah tangga miskin di
pedesaan maupun di perkotaan biasanya juga ada pertukaran atau konsolidasi
sumberdaya antar rumah tangga lapisan maupun antar lapisan.
Menurut Suharto (2006), salah satu strategi pemecahan masalah
kemiskinan adalah dengan pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan
dasar tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kelompok-kelompok
masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi pendekatan ini ditujukan
kepada pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk, karena sebagian
besar penduduk hidup dalam keadaan kekurangan.
Pendekatan kebutuhan dasar mengutamakan penghapusan kemiskinan
absolut tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas tingkat kelangsungan
hidup (subsistence level) dan bahkan juga menghapus kemiskinan relatif. Pendekatan kebutuhan dasar tidak hanya mengutamakan peranan pemerintah
dalam menghapus kemiskinan, tetapi terutama menghendaki adanya partisipasi
masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pemenuhan
kebutuhan dasar.
Pendekatan kebutuhan dasar berasumsi: pertumbuhan ekonomi semata
tidak mampu menghilangkan kemiskinan absolut, karena pertumbuhan ekonomi
sendiri melahirkan ketimpangan di antara bidang atau yang maju atau tradisional.
Konsep kebutuhan dasar adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk
dalam suatu negara dalam jangka tertentu. Untuk mencapai tujuan ini pendekatan
kebutuhan dasar mempunyai dua perangkat sasaran yang terpisah tetapi saling
19 consumtion items), misal kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan (2) penyediaan jasa umum dasar (basic public services) misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih.
Suharto (2006) mengatakan bahwa sejalan dengan perkembangan
teknologi kebutuhan dasar semakin meningkat. Konsep ini mencakup tiga sasaran
lain sebagai pelengkap yaitu (1) pekerjaan yang produktif yang memberikan
imbalan-imbalan yang layak termasuk memperkerjakan diri sendiri, (2) prasarana
yang mampu menghasilkan barang dan jasa dan (3) partisipasi seluruh penduduk
dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan program/
proyek pembangunan.
Menurut Suharto (2006), secara teoritik dalam penentuan paket kebutuhan
dasar masih dihadapkan pada tiga kesulitan yaitu:
(1) Kesulitan untuk menentukan standar kebutuhan dasar. Kesulitan ini
disebabkan karena sulitnya standar yang universal dan objektif. Standar
kebutuhan dasar itu berbeda berdasarkan golongan/bangsa, daerah,
kebudayaan, kelompok sosial atau golongan umur.
(2) Kesulitan untuk menentukan tingkat kebutuhan dasar. Kesulitan ini karena
tidak hanya ada satu tingkat kebutuhan dasar, yang menyangkut kebutuhan
dasar sekedar melangsungkan hidup. Makin tinggi tingkat kemajuan
masyarakat maka tingkat kebutuhan dasar berubah. Golongan ini kebutuhan
hidup lebih produktif, bermutu dan berkesinambungan.
(3) Kesulitan untuk menentukan urutan kebutuhan dasar, menentukan urutan
prioritas yang tercakup dalam barang dan jasa, salah satu cara dengan
mengidentifikasi kelompok-kelompok inti dari pada kebutuhan dasar itu.
Tipologi Komunitas Miskin
Menurut Afrizal dan Ahmadi (1997), penduduk miskin dapat dibedakan
atau dikelompokkan berdasarkan kemampuan fisiknya, jenis kelamin dan
umurnya. Mereka juga dapat dikelompokkan secara ekologis dan pekerjaan. Dari
segi karakteristik pelakunya, penduduk miskin yang umumnya dapat
dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kerakyatan itu dapat dijumpai di daerah
pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan distribusi lokalitasnya menurut variasi
20 pertanian lahan basah (persawahan) dan lahan kering (perladangan) serta nelayan
kecil yang tinggal di pinggir sungai, danau dan laut. Mereka yang bekerja di
sektor non-pertanian dan hidup di perkotaan, melakukan pekerjaan seperti
pedagang kecil, pekerja upahan dan jasa dengan status pekerjaan dan pendapatan
yang rendah.
Berdasarkan tipologi komunitas miskin tersebut maka penelitian diarahkan
kepada komunitas pedesaan yang bekerja pada lahan basah (persawahan), lahan
kering (perladangan dan perkebunan kopi), dengan fokus sasaran petani miskin
yang mempunyai lahan usaha yang sempit kurang dari 0,5 hektar.
Keluarga
Keluarga dipandang dari aspek sosiologis adalah kelompok orang yang
memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Orang yang termasuk
keluarga adalah bapak, ibu dan anak-anaknya.
Pengertian keluarga menurut Murdock (1965):
“…family as a group of person united by ties of marriage, blood or adoption constituting a single household; interacting and community with each other and their respective social role of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister creating and maintaining a common culture.”
Lebih lanjut Murdock (1965) menjelaskan bahwa keluarga sebagai suatu
kelompok manusia yang hidup bersama, yang terbentuk karena ikatan
perkawinan, darah dan adopsi. Dalam melaksanakan hidup berumahtangga, mesti
didasari oleh saling menghargai, saling menghormati setiap peran anggotanya,
sehingga dapat memelihara dan menciptakan budaya bagi kemanusiaan.
Keluarga dapat dibedakan antara keluarga inti (nucleus family) dan keluarga besar (extended family). Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum dewasa/belum menikah, sedangkan keluarga besar adalah
suatu lingkungan keluarga yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan
anak-anaknya yang belum kawin, tetapi termasuk anaknya yang sudah kawin
memisahkan diri dari orangtuanya.
Perkembangan bentuk keluarga, menurut Dubois (1992) meliputi antara
lain: (1) Keluarga campuran yaitu keluarga yang menikah setelah masing-masing
21 anak dari hasil pernikahan sebelumnya. (2) Keluarga orang tua tunggal, yaitu
keluarga yang hanya memiliki satu orangtua. Mereka biasanya terdiri dari seorang
ayah atau seorang ibu saja. Bentuk keluarga ini biasanya terjadi karena adanya
perceraian, salah satu pasangan meninggal dunia, atau orangtua yang memiliki
anak di luar pernikahan dan memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri.
(3) Keluarga multi generasi, yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa generasi
yang tinggal dalam satu rumah tangga. Dalam keluarga tersebut ada kakek atau
nenek, sampai cucu atau buyut.
Keluarga, menurut Departemen Sosial RI (2004), merupakan suatu sistem
sosial yang berunsurkan tiga subsistem yaitu: (1) Subsistem orangtua, yaitu
suami-isteri atau ibu, yaitu hubungan sosial antara suami-isteri atau
bapak-ibu. Kualitas hubungan subsistem ini akan berpengaruh terhadap kedua subsistem
lainnya; (2) Subsistem orangtua-anak, yaitu hubungan sosial antara orang tua
(suami-isteri atau bapak-ibu) dengan anak atau anak-anaknya. Kualitas hubungan
subsistem ini juga berpengaruh terhadap kedua subsistem lainnya; dan (3)
Subsistem anak, yaitu hubungan sosial antar anak. Kualitas hubungan subsistem
ini juga berpengaruh terhadap subsistem lainnya.
Yang dimaksud dengan keluarga rentan sosial-ekonomi atau keluarga
miskin adalah keluarga yang terdiri ayah dan atau ibu serta anak, namun karena
sebab tertentu memiliki keterbatasan sumberdaya keluarga yang dicirikan dengan
rendahnya pendapatan di bawah Upah Minimal Regional/UMR, yang karena tidak
dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum atau 2.100 kalori per-anggota keluarga
perhari.
Keluarga merupakan suatu jaringan sosial dengan peranan penting yaitu
(1) memenuhi kebutuhan manusia akan keterkaitan, (2) menyediakan pengakuan,
penguatan keyakinan dan perlindungan terhadap isolasi sosial, (3) menyediakan
alat untuk identifikasi dan sosialisasi norma, nilai, pengetahuan dan kepercayaan
suatu budaya tertentu dan (4) dapat berfungsi sebagai sistem gotong-royong yang
sangat diperlukan untuk penyesuaian diri (adaptasi) dan untuk mengatasi stres.
Permasalahan keluarga di Indonesia sangat bervariasi dan saling berkaitan
yaitu antara lain menyangkut kemiskinan, kemelaratan, keterbelakangan,
22 penyalahgunaan narkoba/NAPZA, pemutusan hubungan pekerjaan, tindak
kekerasan dalam rumahtangga dan perceraian.
Intensitas masalah yang dialami setiap keluarga tergantung pada: (1)
sumber-sumber yang dimiliki oleh keluarga yang memungkinkan keluarga untuk
memperoleh akses terhadap pelayanan sosial dasar yang dibutuhkannya, antara
lain kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, (2) dukungan sosial dan
kontrol sosial lingkungan sosial dan budaya terhadap keluarga serta ketersediaan
sumber yang berasal dari lingkungan fisik atau lingkungan hidup dan (3)
ketersediaan pelayanan sosial dasar yang berkualitas yang dibutuhkan oleh
keluarga bermasalah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.
Keluarga mempunyai peran dan fungsi tertentu dalam setiap masyarakat,
sebagai mana dikemukakan Horton (1987), yaitu:
(1) Fungsi biologis, keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang dapat
memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi anggotanya dalam
memenuhi kebutuhan biologis. Fungsi biologis berkaitan erat dengan
pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan seksual
suami-isteri. Kelangsungan sebuah keluarga banyak ditentukan oleh keberhasilan
dalam menjalankan fungsi biologis. Apabila terjadi gangguan fungsional
biologis salah satu pasangan, dimungkinkan menimbulkan masalah dalam
rumahtangga, seperti perceraian.
(2) Fungsi sosialisasi anak, yaitu peranan keluarga dalam membentuk
kepribadian anak. Keluarga dipandang sebaga