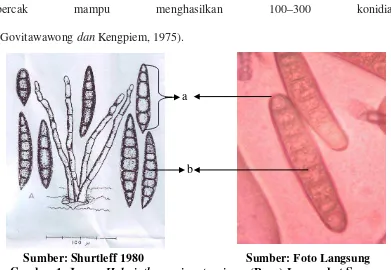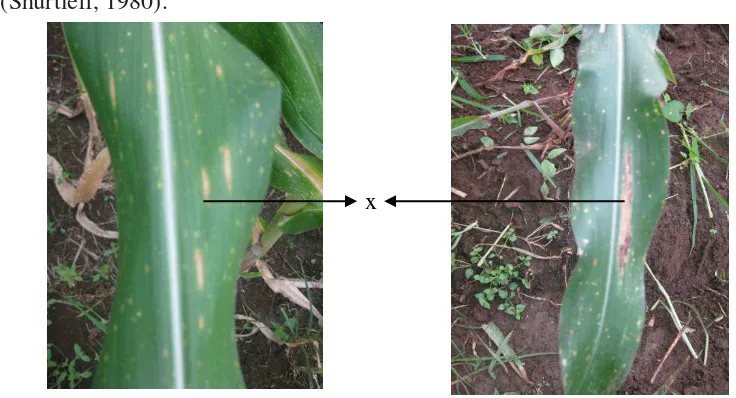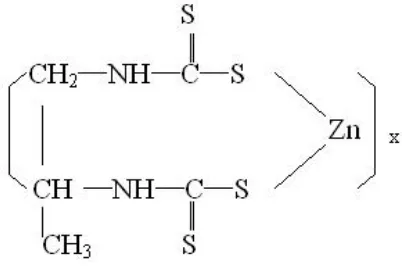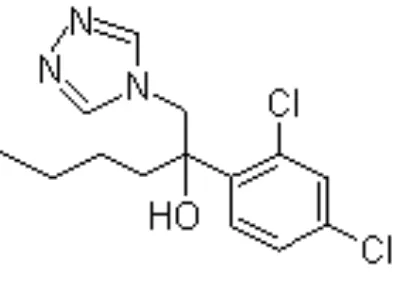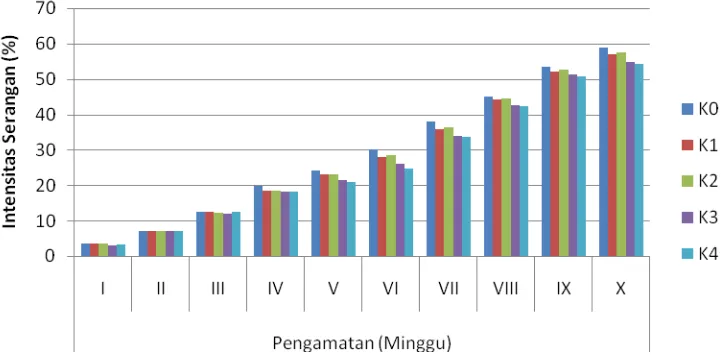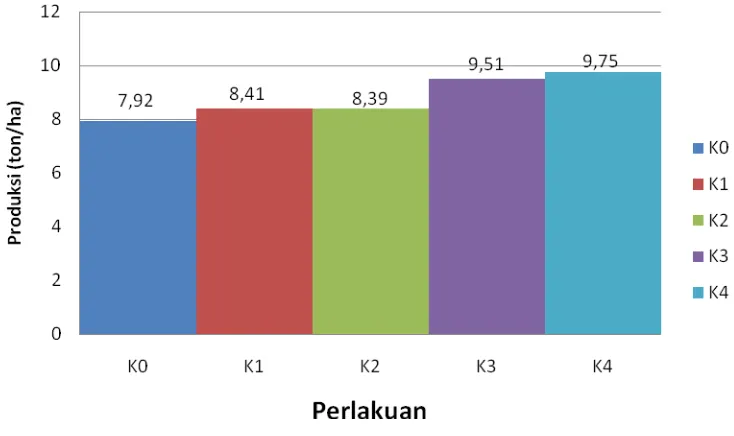UJI EFEKTIVITAS FUNGISIDA NABATI DAN FUNGISIDA KIMIA
TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN
(
Helminthosporium turcicum
(Pass.) Leonard et Suggs)
PADA TANAMAN JAGUNG (
Zea mays
L.)
DI DATARAN RENDAH
S K R I P S I
SYAWALUDDIN 050302003
HPT
DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
UJI EFEKTIVITAS FUNGISIDA NABATI DAN FUNGISIDA KIMIA
TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN
(
Helminthosporium turcicum
(Pass.) Leonard et Suggs)
PADA TANAMAN JAGUNG (
Zea mays
L.)
DI DATARAN RENDAH
S K R I P S I
SYAWALUDDIN 050302003
HPT
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Menempuh Gelar Sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
(Ir. Syamsinar Yusuf, MS) (Ir. Zulnayati Ketua Anggota
)
DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
ABSTRACT
Syawaluddin, Effectiveness Test Plant Fungicides and Chemical Fungicides against Leaf Blight Diseases (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) on Corn Plants (Zea mays L.) in the Lowlands.
This research aims to determine the effectiveness of control from chemical plant and chemical to the leaf blight disease (Helminthosporium turcicum) on maize crops in the lowlands.
This research was conducted in the UPT-BBI Crop Tanjung Selamat, Deli Serdang with the altitude ± 25 m above sea level. This research was conducted from August 2009 to November 2009.
This research used randomized block design method (RAK) non-factorial consisting of K0 (control / no treatment), K1 (piper betle leaf solution 300 gr/litre of water), K2 (fragrant grass leaves solution 300 gr/ litre of water) , K3 (the active ingredient chemical fungicides propineb 1,4 gr/ litre of water), K4 (the active ingredient chemical fungicides heksaconazol 1 ml/ litre of water). The observed parameters are intensity attacks Helminthosporium turcicum Pass .(%), and maize production (Ton / Ha).
The results showed that attack intensity of disease
ABSTRAK
Syawaluddin, Uji Efektifitas Fungisida Nabati dan Fungisida Kimia Terhadap Penyakit Hawar Daun (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) di Dataran Rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian secara nabati dan kimia terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) pada tanaman jagung di dataran rendah.
Penelitian ini dilaksanakan di UPT-BBI Palawija Tanjung Selamat, Deli Serdang dengan ketinggian tempat ± 25 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009 sampai bulan November 2009.
Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari K0 (Kontrol/tanpa perlakuan), K1 (Larutan daun sirih 300 gr/ liter air), K2 (Larutan daun sereh 300 gr/ liter air), K3 (Fungisida kimia bahan aktif propineb 1,4 gr/ liter air), K4 (Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol 1 ml/ liter air). Parameter yang diamati adalah Intensitas Serangan
Helminthosporium turcicum Pass.(%), dan produksi jagung (Ton/Ha).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas serangan penyakit
RIWAYAT HIDUP
Syawaluddin lahir tanggal 10 Juni 1987 di Gedung Johor Kecamatan
Medan Johor Kotamadya Medan dari Ayahanda Salman dan Ibunda Aguswati,
Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.
Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu Tahun 1999 lulus dari
Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemala Bhayangkari 1 Medan. Tahun 2002 lulus dari
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Medan. Tahun 2005 lulus
dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Medan. Tahun 2005 diterima di
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara melalui jalur SPMB.
Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah aktif dalam organisasi
Ikatan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (IMAPTAN) Tahun 2005- 2009.
Tahun 2005- 2009 menjadi anggota Komunikasi Muslim HPT (KOMUS HPT).
Tahun 2008-2009 menjadi asisten di Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman.
Tahun 2009 menjadi asisten koordinator di Laboratorium Dasar Perlindungan
Hutan. Tahun 2009 menjadi asisten koordinator di Laboratorium Hama Hutan.
Tahun 2008 menjadi ketua panitia seminar Peranan Pertanian Dalam
Pembangunan Sumatera Utara. Tahun 2008 menjadi ketua panitia motivation
training Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional FP USU. Tahun 2008
menjadi panitia pelaksana seminar Dies Natalis FP-USU ke- 52. Tahun 2009
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juni sampai Juli di
PTPN III (Persero) Kebun Sei Silau, Kabupaten Asahan. Tahun 2009
melaksanakan penelitian di Balai Benih Induk Tj.Selamat, Kabupaten Deli
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian
ini tepat pada waktunya.
Adapun judul dari usulan penelitian ini yaitu “UJI EFEKTIVITAS FUNGISIDA NABATI DAN FUNGISIDA KIMIA TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) PADA
TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI DATARAN RENDAH” yang
merupakan salah satu syarat syarat untuk dapat melakukan penelitian di
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih
kepada Ir. Syamsinar Yusuf, M.S dan Ir. Zulnayati, selaku dosen ketua dan dosen
anggota dalam membimbing usulan penelitian ini.
Penulis juga menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun demi penyempurnaan usulan penelitian ini. Akhir kata penulis
mengucapkan terima kasih.
Medan, Pebruari 2010
DAFTAR ISI
Biologi Penyebab Penyakit ... 4Daur Hidup Penyakit ... 5
Gejala Serangan ... 6
Faktor Yang Mempengaruhi... 7
Pengendalian Penyakit ... 8
Fungisida Nabati ... 9
Fungisida Kimiawi... 11
METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 13
Bahan dan Alat Penelitian ... 13
Metode Penelitian ... 13
Pelaksanaan Penelitian ... 15
Pengolahan Lahan ... 15
Pembuatan Pestisida Nabati ... 15
Penanaman Benih ... 16
Pemupukan ... 16
Pemeliharaan Tanaman ... 16
Panen ... 17
Parameter Pengamatan ... 17
Intensitas Serangan Penyakit ... 17
Produksi ... 18
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 20
Pembahasan ... 21
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 26
Saran ... 26
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
No Tabel Hal 1. Rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap serangan Helminthosporium turcicum (%) untuk setiap minggu pengamatan. ... 20 2. Rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap produksi
DAFTAR GAMBAR
No Gambar Hal
1. Jamur Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs. ... 6
2. Gejala serangan hawar daun turcicum ... 7
3. Rumus bangun Propineb ... 11
4. Rumus bangun Heksaconazol ... 12
5. Histogram pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap
penyakit hawar daun (helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs) (%) untuk setiap minggu pengamatan ... 22DAFTAR LAMPIRAN
No Lampiran Hal
1. Bagan Penelitian. ... 30
2. Bagan Tanaman Sampel... 32
3. Deskripsi Tanaman Jagung Varietas Bisi 16... 33
4. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan I ... 34
5. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan II ... 35
6. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan III ... 36
7. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan IV ... 37
8. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan V ... 38
9. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan VI ... 39
10. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan VII ... 40
11. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan VIII ... 41
12. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan IX... 42
13. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan X ... 43
14. Rataan Produksi Jagung (ton/ha) ... 44
ABSTRACT
Syawaluddin, Effectiveness Test Plant Fungicides and Chemical Fungicides against Leaf Blight Diseases (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) on Corn Plants (Zea mays L.) in the Lowlands.
This research aims to determine the effectiveness of control from chemical plant and chemical to the leaf blight disease (Helminthosporium turcicum) on maize crops in the lowlands.
This research was conducted in the UPT-BBI Crop Tanjung Selamat, Deli Serdang with the altitude ± 25 m above sea level. This research was conducted from August 2009 to November 2009.
This research used randomized block design method (RAK) non-factorial consisting of K0 (control / no treatment), K1 (piper betle leaf solution 300 gr/litre of water), K2 (fragrant grass leaves solution 300 gr/ litre of water) , K3 (the active ingredient chemical fungicides propineb 1,4 gr/ litre of water), K4 (the active ingredient chemical fungicides heksaconazol 1 ml/ litre of water). The observed parameters are intensity attacks Helminthosporium turcicum Pass .(%), and maize production (Ton / Ha).
The results showed that attack intensity of disease
ABSTRAK
Syawaluddin, Uji Efektifitas Fungisida Nabati dan Fungisida Kimia Terhadap Penyakit Hawar Daun (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) di Dataran Rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian secara nabati dan kimia terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) pada tanaman jagung di dataran rendah.
Penelitian ini dilaksanakan di UPT-BBI Palawija Tanjung Selamat, Deli Serdang dengan ketinggian tempat ± 25 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009 sampai bulan November 2009.
Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari K0 (Kontrol/tanpa perlakuan), K1 (Larutan daun sirih 300 gr/ liter air), K2 (Larutan daun sereh 300 gr/ liter air), K3 (Fungisida kimia bahan aktif propineb 1,4 gr/ liter air), K4 (Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol 1 ml/ liter air). Parameter yang diamati adalah Intensitas Serangan
Helminthosporium turcicum Pass.(%), dan produksi jagung (Ton/Ha).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas serangan penyakit
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian
dari keluarga rumput-rumputan. Berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan
Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Sekitar abad ke-16
orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk Indonesia. Orang Belanda
menamakannya mais dan orang Inggris menamakannya corn
(Departemen Pertanian, 2002).
Di Indonesia, jagung merupakan sumber bahan pangan penting setelah
beras. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga banyak digunakan sebagai bahan
pakan ternak. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan
jagung juga semakin meningkat, namun tidak diikuti oleh peningkatan produksi
sehingga terjadi kekurangan setiap tahunnya sebesar 1,3 juta ton yang harus
dipenuhi melalui impor. Untuk menutupi kekurangan pasokan jagung perlu
diupayakan melalui peningkatan produksi (Departemen Pertanian, 2002).
Kebutuhan akan jagung semakin bertambah seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri pakan dan pangan. Namun,
produksi jagung nasional belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga
volume dan nilai impor jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun
(Pusat Data Pertanian, 2001).
Selain untuk tanaman pangan, jagung juga banyak digunakan untuk pakan.
Data menunjukkkan sekitar 60% jagung di Indonesia digunakan sebagai bahan
sekaligus peluang bagi pengembangan jagung di dalam negeri
(Pusat Data Pertanian, 2001).
Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pakan, pangan, dan industri
lainnya semakin meningkat. Sekitar 3,5 juta ton biji jagung per tahun diserap oleh
pabrik pakan di Jawa Timur, dan sisanya sekitar 2,0 juta ton diserap oleh pabrik
pakan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Untuk pakan
ternak monogastrik (unggas dan babi) diperlukan tambahan asam amino esensial
lisin dan triptofan dari sumber lain yang sebagian besar masih diimpor. Pada
tahun 2004, di Cilegon, Banten, telah beroperasi pabrik pengolahan jagung
terpadu untuk menghasilkan tepung, protein, minyak, dan tetes jagung dengan
kapasitas 1.000 ton biji jagung per hari atau 330.000 ton jagung per tahun, di
mana 70% bahan bakunya masih diimpor (Azrai dkk, 2005).
Di Indonesia, penyakit hawar daun jagung pertama kali dilaporkan
berjangkit di dataran tinggi Sumatera Utara pada tahun 1917. Gejala penularannya
ditandai oleh munculnya bercak daun yang kemudian berkembang melebar hingga
daun jagung mengering. Jika penularan terjadi pada varietas rentan maka tanaman
akan mati (Badan Penelitian Tanaman Serealia, 2005).
Varietas tahan merupakan komponen pengendalian yang dianjurkan
hingga saat ini. Aplikasi fungisida hanya disarankan untuk pengendalian pada
pertanaman produksi benih, dengan cara menyemprotkan pada saat bercak mulai
tampak di daun. Teknik pengendalian lainnya yang pernah dianjurkan di Sumatera
Utara adalah sanitasi dan pemupukan berimbang
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui efektivitas pengendalian secara nabati dan kimia
terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) pada tanaman jagung
(Zea mays L.) di dataran rendah.
Hipotesa Penelitian
Diduga ada perbedaan keefektifan fungisida nabati dan kimia untuk
mengendalikan Helminthosporium turcicum pada tanaman jagung (Zea mays L.).
Kegunaan Penelitian
- Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan.
TINJAUAN PUSTAKA
Biologi Penyebab Penyakit
Klasifikasi jamur Helminthosporium turcicum menurut Alexopoulus and
Mims (1979) adalah :
Divisio : Amastigomyceta
Sub Divisio : Deuteromycotina
Kelas : Deuteromycetes
Sub Kelas : Hyphomycetidae
Ordo : Hyphales
Family : Dematiaceae
Genus : Helminthosporium
Spesies : Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs.
Dari Dematiaceae- Phragmospore, marga Helminthosporium kebanyakan
menyerang Graminae. Ini mempunyai konidiofor tegak dan kuat, berwarna coklat.
Konidium seperti kumparan atau seperti gada panjang, sering agak bengkok,
bersekat banyak berwarna coklat, konidium berdinding tebal. Marga
Helminthosporium dipecah menjadi beberapa marga, antara lain Drechslera,
Bipolaris, dan Exserohilum. Helminthosporium turcicum (Exserohilum turcicum)
menyerang bunga dan daun jagung (Semangun, 1996)
Penyakit hawar daun (leaf blight) turcicum disebabkan oleh jamur
Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs. Jamur membentuk
konidiofor yang keluar dari mulut daun (stomata), satu atau dua dalam kelompok,
secara umum 8-9 μm. Konidium lurus atau agak melengkung, jorong atau
berbentuk gada terbalik, pucat atau berwarna coklat jerami, halus mempunyai 4-9
sekat palsu, panjang 50-144 (115) μm, dan bagian yang paling lebar berukuran
18-33 μm, kebanyakan 20-24 μm. Konidium mempunyai hilum menonjol dengan
jelas, yang merupakan ciri dari marga Drechslera. Dalam biakan murni, D.
turcicum membentuk askus dalam peritesium. Stadium sempurna dari jamur ini
disebut Setosphaeria turcica (Luttrell) Leonard et Suggs atau
Trichometasphaeria turcica (Pass.) Luttrell (Holliday, 1980).
Penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Helminthosporium turcicum
merupakan salah satu penyakit utama pada jagung setelah bulai. Patogen ini menular melalui udara sehingga mudah menyebar. Kehilangan hasil akibat bercak daun mencapai 59%, terutama bila penyakit menginfeksi tanaman sebelum bunga betina keluar (Poy 1970).
Daur Hidup Penyakit
Jamur Helminthosporium turcicum dapat bertahan hidup pada tanaman
jagung yang masih hidup, beberapa jenis rumput-rumputan termasuk sorgum,
pada sisa-sisa tanaman jagung sakit, dan pada biji jagung. Konidium jamur ini
disebarkan melalui angin. Di udara, konidium yang terbanyak terdapat menjelang
tengah hari. Konidium berkecambah dan pembuluh kecambah mengadakan
infeksi melalui mulut kulit atau dengan mengadakan penetrasi secara langsung,
yang didahului dengan pembentukan apresorium (Semangun,1991).
b a
hinggap pada permukaan tanaman yang lain. Selanjutnya spora beradhesi, melakukan penetrasi awal, kemudian membentuk bercak dan berkembang. Siklus hidup cendawan Exserohilum turcicum berlangsung 2–3 hari. Dalam 72 jam satu
bercak mampu menghasilkan 100–300 konidia (Govitawawong dan Kengpiem, 1975).
Sumber: Shurtleff 1980 Sumber: Foto Langsung Gambar 1. Jamur Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs.
Keterangan : a = konidium b = sekat konidium
Gejala Serangan
x
hari. Bentuk konidia agak melengkung, ujungnya tumpul, bersekat 3−10 buah (Shurtleff, 1980).
Gambar 2. Gejala serangan hawar daun turcicum Sumber : Foto Langsung
Tanaman jagung yang tertular Helminthosporium turcicum, gejala awalnya
muncul bercak-bercak kecil, jorong, hijau tua/hijau kelabu kebasahan.
Selanjutnya, bercak-bercak tadi berubah warna menjadi coklat kehijauan. Bercak
kemudian membesar dan mempunyai bentuk yang khas, berupa kumparan atau
perahu. Lebar bercak 1-2 cm dan panjang 5-10 cm, tetapi lebar dapat mencapai 5
cm dan panjang 15 cm. Konidia banyak terbentuk pada kedua sisi bercak pada
kondisi banyak embun atau setelah turun hujan, yang menyebabkan bercak
berwarna hijau tua beledu, yang makin ke tepi warnanya makin muda. Beberapa
bercak dapat bersatu membentuk bercak yang lebih besar sehingga dapat
mematikan jaringan daun Pertanaman jagung yang tertular berat tampak kering
seperti habis terbakar (Semangun, 1991).
Faktor yang Mempengaruhi
Jarak tanam yang rapat menyebabkan kelembaban udara di sekitar
Helminthosporium turcicum. Suhu optimal untuk pertumbuhan, pembentukan, dan
perkecambahan konidia Helminthosporium turcicum adalah 200C- 260C
(Renfro and Ultstrup 1976).
Tanaman jagung yang terinfeksi penyakit hawar daun pada fase vegetatif
menyebabkan tingkat penularan yang lebih berat dibanding bila penularan terjadi
pada tanaman yang lebih tua dan ini akan berpengaruh terhadap kehilangan hasil
(Sumartini dan Sri Hardaningsih 1995). Namun menurut Sudjono (1988), jika
tanaman jagung tertular sebelum keluar rambut (bunga betina) dapat
menyebabkan kehilangan hasil 59%. Kehilangan hasil akibat H. turcicum dapat
mencapai 100% atau puso pada tingkat penularan yang berat (Roliyah 2000).
Perkembangan penyakit ditentukan oleh kondisi lingkungan. Suhu optimal untuk perkembangan penyakit adalah 200− 300C (Schenck and Steller 1974). Keadaan suhu tersebut umum dijumpai pada areal pertanaman jagung di Indonesia sehingga hawar daun hampir selalu ditemukan pada setiap musim tanam. Patogen dalam bentuk miselium dorman juga mampu bertahan hingga satu tahun pada sisa tanaman jagung (Shurtleff 1980; Sumartini dan Srihardiningsih 1995) sehingga penyakit bersifat laten serta mampu menyebabkan serangan secara sporadis yang serius terutama pada varietas rentan (Pakki, 2005).
Pengendalian Penyakit
Penanaman varietas tahan merupakan cara pengendalian yang mudah,
murah, dan aman bagi lingkungan (Wakman dan Burhanuddin, 2007). Menurut
Sudjono (1988) jenis Kalingga, Arjuna, dan Hibrida C1 adalah tahan terhadap
Pengendalian Helminthosporium turcicum pada daerah endemis dapat dilakukan dengan pembenaman sisa-sisa panen untuk mengurangi sumber inokulum awal. Cara ini efektif menekan intensitas serangan pada daerah endemis
H. turcicum(Summer dan Litteral, 1974)
Helminthosporium turcicum selain menginfeksi tanaman jagung, juga
dapat merusak beberapa jenis gulma atau tanaman inang alternatif. Oka (1993)
mengemukakan bahwa untuk mengendalikan penyakit tanaman, maka sumber
inokulum awal (X) harus dihilangkan/dikurangi. Pengolahan tanah yang baik dan
penyiangan yang sempurna dapat menekan/mengurangi sumber inokulum awal.
Pengendalian secara biologis dengan menggunakan mikroorganisme antagonis belum banyak dilaporkan. Cendawan antagonis Trichosporom sp. (Wang dan Wu 1987) dan bakteri Pseudomonascepacia (Upadhyal dan Jasaswal 1992) berpotensi dikembangkan di areal pertanaman jagung.
Jika diperlukan, penyakit ini dapat dikendalikan dengan fungisida dengan
bahan aktif carbendazin 6,2% + mancozeb 73,8%, mancozeb 80%,
trishloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Muis dkk, 2000).
Fungisida Nabati
Secara umum, pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang
bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat
dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Oleh karena terbuat dari
bahan alami/nabati maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (biodegerable)
di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan
Untuk menghasilkan bahan pestisida nabati dapat dilakukan beberapa
teknik, diantaranya:
1. Pengerusan, penumbukan, pembakaran, atau pengepresan untuk
menghasilkan produk berupa tepung, abu, atau pasta.
2. Rendaman untuk produk ekstrak.
3. Ekstraksi dengan menggunakan bahan kimia pelarut disertai perlakuan
khusus oleh tenaga yang terampil dan dengan peralatan khusus.
(Kardinan, 2004)
Sirih (Piper betle L.)
Dalam daun sirih terkandung beberapa senyawa seperti minyak atsiri, zat
penyamak, cineole, dan yang terpenting senyawa alkoloid. Komposisi kimia pada
tanaman sirih yaitu, saponi, flafonida dan polypenol mampu memberikan
ketahanan pada tanaman. Senyawa fenol yang terkandung pada daun sirih dapat
berfungsi sebagai penahan serangan patogen. Dengan cara menghambat sporulasi
dari patogen, sehingga tanaman dapat terlindung (Hendra dkk, 1995).
Ekstrak daun sirih telah dikembangkan dalam beberapa bentuk sediaan
misal pasta gigi, sabun, obat kumur karena daya antiseptiknya. Sediaan perasan,
infus, ekstrak air-alkohol, ekstrak heksan, ekstrak kloroform maupun ekstrak
etanol dari daun sirih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap gingivitis, plak
dan karies (Sari dan Dewi, 2006).
Sereh (Andropogon nardus L.)
Sereh dapat berfungsi sebagai insektisida dan fungisida yang mengandung
bahan aktif atsiri yang terdiri dari senyawa sintral, sitronela, geraniol, mirsena,
yang dikenal sebagai `citronella oil’ di pasaran. Minyak sitronela mengandung
dua bahan kimia penting yaitu sitronelal dan geraniol. Sitronelal dan geraniol
digunakan untuk bahan dasar pembuatan ester-ester seperti hidroksi sitronelal,
genaniol asetat dan mentol sintetik yang mempunyai sifat lebih stabil dan banyak
digunakan dalam industri wangi-wangian(Kardinan, 2004).
Fungisida Kimiawi
Propineb
Fungisida dari kelompok ditiokarbamat merupakan fungisida sintetik organik generasi pertama yang hingga kini paling banyak digunakan di seluruh dunia. Propineb ditemukan pada tahun 1963. Fungisida ini bersifat non sistemik, non spesifik, dan multisite inhibitor. Propineb digunakan sebagai protektan dengan cara disemprotkan untuk menghambat perkecambahan spora. Dengan rumus kimia C5H8N2S4Zn (Djojosumarto, 2008).
Propineb yang terdapat pada produk yang digunakan bertuliskan 70 WP, yang artinya dalam 1 Kg produk terdapat 700 gr bahan aktif propineb dengan berbentuk tepung. WP adalah formulasi bentuk tepung yang bila dicampur air akan membentuk suspensi yang penggunaannya dengan cara disemprotkan (Djojosumarto, 2000).
Heksakonazol
Merupakan fungisida golongan triazol, ditemukan pada tahun 1986, yang berspektrum luas, bersifat kuratif dan protektan mengendalikan jamur patogen. Bekerja secara sistemik ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh kayu (xylem) dengan rumus kimia C14H17Cl2N3O (Djojosumarto, 2008).
Heksaconazole yang terdapat pada produk yang digunakan bertuliskan 50EC, yang artinya dalam 1 liter produk terdapat 500 ml bahan aktif heksaconazole. EC merupakan sediaan berbentuk pekatan (konsentrat) cair dengan konsentrasi bahan aktif yang cukup tinggi. Konsentrat cair ini akan membentuk emulsi (butiran benda cair melayang dalam media cair lain) (Djojosumarto, 2000).
METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Induk Tanjung Selamat, Medan
dengan ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2009.
Bahan dan Alat Penelitian
Adapun bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: benih
jagung Bisi 16, fungisida nabati dari larutan daun sirih, larutan daun sereh wangi,
fungisida kimia dengan bahan aktif propineb, heksaconazol, air, teepol dan bahan
pendukung lainnya.
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, gembor,
ember, knapsack, tugal, meteran, tali plastik, papan nama, papan sampel, cat,
kuas, alat tulis dan alat pendukung lainnya.
Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari:
K0 = Kontrol
K1 = Larutan daun sirih dengan dosis 300 gr/ liter air
K2 = Larutan daun sereh dengan dosis 300 gr/ liter air
K3 = Fungisida kimia bahan aktif propineb dengan dosis 1,4 gr/ liter air K4 = Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol dengan dosis 1 ml/ liter air
(t-1) (r-1) ≥ 15
(4-1) (r-1) ≥ 15
4r-4 ≥ 15
4r ≥ 19
r ≥ 4,75
r = 5 (pembulatan)
Jumlah ulangan = 5
Jumlah plot : 5 x 5 = 25 plot
Jarak antar plot : 50 cm
Paret keliling : 30 cm
Ukuran plot : 270 cm x 240 cm
Luas lahan : 17,50 m x 16,00 m
Jarak tanam : 70 x 30 cm
Jumlah tanaman per plot : 28 tanaman
Jumlah seluruh tanaman : 700 tanaman
Metode linear yang digunakan adalah sebagai berikut :
Yij = µ + ρi + τj + εij
Dimana :
Yij = data percobaan
µ = efek nilai tengah
ρi = efek blok dari taraf ke-i
τj = efek perlakuan dari taraf ke-j
Jika sidik ragam menunjukkan efek yang nyata maka dilanjutkan dengan
Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT).
(Sastrosupadi, 2000).
Pelaksaan Penelitian Pengolahan Lahan
Lahan dibersihkan dari sisa- sisa gulma. Pengolahan dilakukan sebanyak 3
kali, yaitu dilakukan terlebih dahulu pencangkulan tanah sedalam 20- 30 cm
(sedalam perakaran jagung). Kemudian meratakan tanah yang telah dicangkul
sehingga bongkahan tanah menjadi halus, setelah itu tanah digemburkan kembali
dengan membalik tanah sekaligus membuat petak- petak percobaan dengan
ukuran yang telah ditentukan yaitu 2,7 m x 2,4 m.
Pembuatan Pestisida Nabati Larutan Daun Sirih
Daun sirih yang digunakan adalah daun yang masih segar yang dapat
diperoleh di tempat penjualan sirih di pasar. Daun sirih disediakan sebanyak
300 gr. Pembuatan larutan daun sirih dilakukan dengan cara di blender dengan
pelarut 1 liter air. Larutan diendapkan selama ± 1 jam kemudian disaring agar
didapat larutan yang siap diaplikasikan (Hendra dkk, 1995).
Larutan Daun sereh
Daun sereh dipilih yang bermutu baik, dengan cara memperhatikan ukuran
dan aromanya. Pembuatan larutan dari sereh wangi dapat dilakukan dengan cara;
daun sereh yang masih segar ditimbang sebanyak 300 gr kemudian
selama ± 1 jam kemudian disaring agar didapat larutan yang siap diaplikasikan
(Syamsuddin, 2003).
Penanaman Benih
Penanaman benih jagung Bisi 16 dilakukan dengan menggunakan tugal
dengan kedalaman ± 2,5- 5 cm dan jarak tanam 30 cm x 70 cm. Pada setiap
lubang dimasukkan terlebih dahulu pupuk kompos kemudian dimasukkan 2 benih
jagung dan ditutup kembali dengan pupuk kompos dan tanah yang gembur. Bila
kedua benih telah tumbuh maka dipilih satu tanaman saja yang paling bagus.
Pemilihan tanaman ini dilakukan sebelum aplikasi pertama fungisida nabati dan
kimia ke tanaman.
Pemupukan
Pupuk yang digunakan adalah Urea, SP-36 dan KCL. Dosis pupuk yang
digunakan untuk Urea adalah 350 kg/ ha untuk dua kali pemupukan, SP-36
sebanyak 200 kg/ ha dan KCL sebanyak 50 kg/ ha. Pada pemupukan pertama
sebagai pupuk dasar, Urea yang digunakan adalah 200 kg/ ha (sekitar 4,2 gr/
tanaman), SP-36 sebanyak 4,2 gr/ tanaman dan KCL sebanyak 1, 05 gr/ tanaman.
Dengan jarak pemberian 10 cm dari tanaman. Pemupukan kedua dilakukan pada
35 hst, pupuk yang diberikan hanya urea dengan dosis 150 kg/tanaman (sekitar
3,15 gr/tanaman) dengan jarak pemberian 15 cm dari tanaman
(Syafruddin dkk, 2007).
Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma, penyiraman,
Penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali pada 3 minggu setelah tanam
(MST) dan 6 MST dengan menggunakan cangkul yang bertujuan untuk
membersihkan gulma dari areal pertanaman. Penyiraman dilakukan 2 kali yaitu
pada pagi dan sore hari apabila kondisi tanah kering, tetapi apabila hujan
penyiraman tidak dilakukan. Penyiraman dilakukan cukup disekitar perakaran.
Penjarangan dilakukan pada saat umur tanaman 14 hari dengan
meninggalkan satu tanaman yang terbaik terutama tanaman sampel pada setiap
lubang tanam untuk parameter pengamatan.
Pembumbunan dilakukan dengan menimbun tanah pada batang bawah
tanaman jagung yang bertujuan untuk menutupi akar yang terbuka dan untuk
membuat pertumbuhan tanaman tetap tegak dan kokoh.
Aplikasi Fungisida
Aplikasi fungisida nabati dan kimiawi dilakukan sebanyak 1 kali dalam
seminggu yang dimulai pada saat patogen mulai menyerang tanaman (kurang dari
1%) 21 hari setelah tanam (HST) sampai 84 HST (10 kali aplikasi) dengan
menggunakan knapsack. Aplikasi dilakukan pada saat sore hari.
Panen
Kriteria panen pada jagung umumnya kira- kira setelah tanaman berumur
100 hari pada saat daun telah menguning dan kering ini pun tergantung kepada
varietas jagung yang digunakan, biji jagung telah berwarna kuning kemerahan dan
telah mengeras, klobot daun telah menguning dan kering dan rambut berwarna
Parameter Pengamatan Intensitas Serangan Penyakit
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah intensitas serangan
Helminthosporium turcicum pada daun tanaman jagung. Pengamatan pertama
dilakukan pada 15 hst (sebelum aplikasi pertama fungisida), dengan interval
waktu pengambilan data satu kali dalam seminggu. Dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
Keterangan :
IS : Intensitas Serangan Penyakit
n : Jumlah daun dari kategori serangan
v : Nilai skala dari kategori serangan
Z : Nilai skala dari kategori serangan tertinggi
N : Jumlah seluruh daun yang diamati
Kategori nilai skor serangan:
0 : Tidak ada gejala serangan
1 : Luas kerusakan pada permukaan daun 1- 5 %
3 : Luas kerusakan pada permukaan daun 6- 25%
1. : Luas kerusakan pada permukaan daun 26- 50%
7 : Luas kerusakan pada permukaan daun 51- 75%
9 : Luas kerusakan pada permukaan daun 76- 100%
Produksi
Produksi dihitung dengan menimbang berat bersih biji jagung pipilan pada
akhir masa percobaan yang dikonversikan ke dalam ton/ha, dengan menggunakan
rumus:
Keterangan:
Th = Taksasi hasil
La = Luas areal tanaman
Hs = Rata- rata hasil tanaman sampel
Pt = Persentase tumbuh tanaman
Jt = Jarak tanam
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil penelitian uji efektivitas fungisida nabati dan fungisida kimia
terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum (pass.) leonard et
suggs) pada tanaman jagung (zea mays L.) di dataran rendah adalah sebagai
berikut :
1. Intensitas Serangan Helminthosporium turcicum
Hasil pengamatan mingguan intensitas serangan (%) hawar daun jagung
(Helminthosporium turcicum) dari pengamatan 21 HST- 84 HST dapat dilihat
pada lampiran 4 sampai dengan 15. Dari hasil analisa sidik ragam dapat dilihat
adanya perbedaan yang tidak nyata pada pengamatan ke I- III, nyata pada pada
pengamatan ke IV dan sangat nyata pada pada pengamatan ke V- X, maka
dilakukan Uji Jarak Duncan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.
Rata-rata intensitas serangan (%) Helminthosporium turcicum pada
masing- masing perlakuan pada setiap minggu pengamatan dapat dilihat pada
tabel 1, berikut ini:
Tabel 1: Uji beda rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap serangan Helminthosporium turcicum (%) untuk setiap minggu pengamatan.
2. Produksi Jagung (ton/ha)
Hasil pengamatan produksi pipilan jagung kering dapat dilihat pada
lampiran 16. Dari analisis produksi jagung dapat dilihat adanya perbedaan yang
sangat nyata pada masing- masing perlakuan, maka dilakukan Uji Jarak Duncan.
Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2: Uji beda rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap produksi jagung (ton/ha)
Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata pada Uji Jarak Duncan taraf 5%.
Keterangan perlakuan: K0 = Kontrol
K1 = Larutan daun sirih dengan dosis 300 gr/ liter air K2 = Larutan daun sereh dengan dosis 300 gr/ liter air
K3 = Fungisida kimia bahan aktif propineb dengan dosis 1,4 gr/ liter air K4 = Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol dengan dosis 1 ml/ liter air
Pembahasan
1. Intensitas Serangan Helminthosporium turcicum
Intensitas serangan Helminthosporium turcicum pada tabel 1 menunjukkan
bahwa serangan penyakit ini sudah ditemukan sejak pengamatan 21 HST, kecuali
pada perlakuan K3 (propineb 1,4 gr/l.air)
Pada pengamatan I (21 HST) sampai dengan pengamatan III (35 HST)
K4. Sedangkan pada pengamatan IV (42 HST) perlakuan K0 berbeda nyata
terhadap perlakuan K1, K2, K3, K4.
Pada pengamatan V (49 HST), perlakuan K3 dan K4 berbeda sangat nyata
terhadap perlakuan K0, K1, dan K2. Perlakuan C3 tidak berbeda nyata terhadap
perlakuan C4.
Pada pengamatan VI (56 HST) sampai pengamatan X (84 HST), perlakuan
K0 berbeda sangat nyata terhadap perlakuan K1, K2, K3 dan K4. Sedangkan K1
tidak berbeda nyata pada K2 dan K3 tidak berbeda nyata pada K4.
Untuk melihat perbedaan yang nyata antara fungisida nabati dan fungisida
kimia terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum (pass.) leonard
et suggs) dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:
Gambar 5. Histogram pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap penyakit hawar daun (helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs) (%) untuk setiap minggu pengamatan.
Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa intensitas serangan pada pengamatan
IV (42HST) terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 18,05% dan tertinggi pada
pada perlakuan K4 dengan nilai 20,97% dan tertinggi pada K0 dengan nilai
24,26%. Pada 56 HST, intensitas serangan terendah pada perlakuan K4 dengan
nilai 24,72% dan tertinggi pada K0 dengan nilai 30,03%. Pada 63 HST, intensitas
serangan terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 33,56% dan tertinggi pada K0
dengan nilai 38,07%. Pada 70 HST, intensitas serangan terendah pada perlakuan
K4 dengan nilai 42,32% dan tertinggi pada K0 dengan nilai 45,10%. Pada
77 HST, intensitas serangan terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 50,80%
dan tertinggi pada K0 dengan nilai 53,56%. Pada 84 HST, intensitas serangan
terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 54,31% dan tertinggi pada K0 dengan
nilai 58,80%.
Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa intensitas serangan antara perlakuan
K3 dan K4 lebih rendah bila dibandingkan dengan perlakuan K0, K1 dan K2. Ini
menunjukkan bahwa fungisida kimia lebih efektif untuk mengendalikan penyakit
hawar daun jagung (Helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs),
terutama untuk fungisida yang bersifat sistemik (K4/ heksaconazol).
Pada perlakuan fungisida kimia, perlakuan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air)
yang bersifat sistemik lebih efektif untuk menekan perkembangan hawar daun bila
dibandingkan dengan perlakuan K3 (propineb 1,4 gr/l.air) yang bersifat kontak
pada setiap minggu pengamatan. Hal ini dikarenakan fungisida kontak tidak dapat
diserap oleh tanaman, tetapi hanya membentuk lapisan penghalang dipermukaan
daun tanaman sehingga perkecambahan spora dan miselia jamur menjadi
terhambat (Djojosumarto, 2000) dan lapisan penghalang ini dapat tercuci oleh
curah hujan yang tinggi. Sedangkan fungisida sistemik bisa diserap oleh jaringan
bagian tanaman lainnya (Djojosumarto, 2008) sehingga lebih tahan lama di dalam
jaringan tanaman dalam menghambat pertumbuhan jamur.
Pada perlakuan fungisida nabati, perlakuan K1 (larutan daun sirih
300 gr/l.air) yang mengandung fenol mampu menahan serangan patogen dengan
cara menghambat sporulasi dari patogen sehingga tanaman dapat terlindung dan
bertahan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hendra, et al (1995) bila
dibandingkan dengan perlakuan K2 (larutan daun sereh 300 gr/l.air) yang
mengandung senyawa stronella dan golongan alkohol pada setiap minggu
pengamatan. Penggunaan fungisida nabati (sirih dan sereh) berperan aktif dalam
menghambat pertumbuhan konidia maupun koloni jamur, sehingga mampu
menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit hawar daun. Penggunaan daun
sirih dan daun sereh tidak bersifat racun terhadap tanaman sehingga tidak
mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Pada lampiran dapat dilihat bahwa rataan curah hujan pada bulan Agustus
2009 – November 2009 berkisar antara 49 mm pada bulan Agustus; 229,5 mm
pada bulan September; 305,6 mm pada bulan Oktober dan 276,7 mm pada bulan
November. Dengan suhu udara berkisar antara 26,3 oC (Agustus) , 26,2 oC
(September) , 26,1 oC (Oktober) dan 25,8 oC (November) Untuk kelembaban
udara pada bulan Agustus 2009 – November 2009 berkisar antara 89%- 90%.
Faktor- fakor lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur
Helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs. Hal ini didukung oleh
pernyataan Sudjono (1989) bahwa perkembangbiakan penyakit dibantu oleh curah
yang kurang dan Semangun (1991) Kelembaban relatif untuk pertumbuhan jamur
diatas 90% dengan suhu optimum pembentukan konidium 20-26 oC.
2. Produksi jagung (ton/ha)
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa produksi jagung pada perlakuan K3 dan
K4 berpengaruh sangat nyata terhadap perlakuan K0, K1 dan K2. Dapat dilihat
pada rataan produksi tertinggi yaitu pada perlakuan K4 dengan nilai 9,75 ton/ha
dan terendah terdapat pada perlakuan K0 dengan nilai 7,92 ton/ha.
Produksi jagung berbanding terbalik dengan intensitas serangan,
maksudnya apabila intensitas serangan tinggi maka produksinya rendah, begitu
juga sebaliknya produksi yang didapat tinggi apabila intensitas serangan penyakit
rendah. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan tabel 1 dan tabel 2.
Untuk melihat pengaruh dari masing-masing perlakuan berbeda sangat
nyata terhadap produksi jagung dapat dilihat pada gambar 6.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Intensitas serangan tertinggi pada 84 HST (pengamatan X) terdapat pada
perlakuan K0 (kontrol) sebesar 58,80%, K2 (larutan daun sereh 300 gr/l.air)
: 57,42% ; K1 (larutan daun sirih 300 gr/l.air) : 57,03% , K3 (propineb 1,4
gr/l.air) 54,87% dan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air) : 54,31%.
2. Perlakuan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air) lebih efektif untuk menekan
perkembangan hawar daun bila dibandingkan dengan perlakuan K3
(propineb 1,4 gr/l.air) pada setiap minggu pengamatan.
3. Perlakuan K1 (larutan daun sirih 300 gr/l.air) lebih efektif untuk menekan
perkembangan hawar daun bila dibandingkan dengan perlakuan K2 (larutan
daun sereh 300 gr/l.air) pada setiap minggu pengamatan.
4. Produksi jagung tertinggi pada perlakuan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air)
sebesar 9,75 ton/ha, dan terendah pada perlakuan K0 (kontrol) sebesar 8,31
ton/ha.
5. Fungisida kimia lebih efektif daripada fungisida nabati dalam
mengendalikan penyakit hawar daun.
Saran
Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap intensitas serangan
hawar daun Helminthosporium turcicum dengan waktu aplikasi dan dosis
DAFTAR PUSTAKA
Alexopoulus, C. J. and C. W. Mims., 1979. Introductory Mycology. Third Edition. John Wiley & Sons, New York. Page 566-567.
Azrai, Muhammad., Made J. Mejaya, dan M.Yasin H.G., 2005. Pemuliaan Jagung Khusus. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 96.
Badan Penelitian Tanaman Serealia, 2005. Varietas Jagung Tahan Penyakit Hawar Daun. Badan Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 14-15.
Chemblink, 2008. Hexaconazole. Diakses dari
pada tanggal 2
Desember 2008.
Departemen Pertanian. 2002. Luas Tanam, Produksi Dan Produktivitas Jagung. Departemen Pertanian. Jakarta. Hal 2.
Djojosumarto, Panut. 2000. Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian. Kanisius, Yogyakarta. Hal 46.
. 2008. Pestisida dan Aplikasinya. Agromedia Pustaka, Jakarta. Hal 129, 146, 205.
Govitawawong, P. and Kengpiem. 1975. Studies on southern corn leaf blight
(Helminthosporiummaydis). Thailand National Corn and Sorgum Program.
1975. Annual Report. Kasetsart University, Thailand. Page 293−298.
Hendra, J. Firdausil dan Hasanah., 1995. Pengaruh Pemberian Dan Lama
Perendaman Kayu Manis dan Sirih Terhadap Pengendalian
Pseudomonas solancearum Pada jahe. Risalah Kongres Nasional XIII Dan Seminar Ilmiah. Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, Mataram.
Holliday, P. 1980. Fungus Disases of Tropical Crops. Cambridge Univ. Press, Cambridge. Page 607.
Kardinan, Agus., 2004. Pestisida Nabati Ramuan Dan Aplikasi. Penebar Swadaya, Jakarta. Hal 4-7.
Muis, A., S. Pakki, dan Sutjiati. 2000. Peranan Varietas Tahan dan Fungisida
Dalam Mengendalikan Penyakit Hawar Daun (Helminthosporium
maydis) Pada Tanaman Jagung. Seminar Mingguan Balitjas, tanggal, 24 Juni 2000. Hal 7.
Pakki, Syahrir., 2005. Epidemiologi Dan Pengendalian Penyakit Bercak Daun (Helminthosporium sp.) Pada Tanaman Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 101-106.
Poy, C. 1970. Corn seed production of Helminthosporium maydis and future seed prospects.Plant Dis. Rep. 54(12): 1118−1121.
Pusat Data Pertanian, 2001. Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pusat Data Pertanian, Jakarta. Hal 4.
Renfro, B. L. and A. J. Ullstrup. 1976. A comparison of maize diseases in temperate and in tropical environment. PANS 22(4):491-498.
Roliyah, Y. 2000. Laporan Perkembangan Penyakit Hawar Daun Pada Tanaman Jagung di Propinsi Sumatera Utara. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Medan. Hal 21.
Sari, Retno dan Dewi Isadiartuti., 2006. Studi Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Tangan Ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn.). Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. Hal 163-164.
Sastrosupadi, A., 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Kanisius, Jakarta. Hal. 72.
Schenck, N.C. and T.J. Steller. 1974. Southerncorn Leaf Blight Development Relative to Temperature, Moisture, and Fungicide Application. Phytopathology 64: 619−624.
Semangun, H., 1991. Penyakit-Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 42- 48.
____________, 1996. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 107-108.
Shanghai Kima Chemical, 2008. Propineb. Diakses dari http://www.tradevv.com/vp-propineb/ pada tanggal 2 Desember 2008.
Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of Corn Disease. Second Ed. The American Phytopathological Society. Page 105.
Sudjono, M. S. 1988. Penyakit Jagung dan Pengendaliannya. Dalam: Subandi, M. Syam, dan Adi Widjono, Jagung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hal 205-241.
Sujono, S. dan Sudarmadi. 1989. Teknik Pengamatan Hama dan Penyakit. Fakultas Pertanian. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 43. Sumartini dan Srihardiningsih. 1995. Penyakit Jagung dan Pengendaliannya.
Monograf Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang No. 13.
Summer, D.R. and R.H. Litteral. 1974. Influence of tillage planting date, inoculum survival and mixed population on epidemiology of southern corn leaf blight. Phytopatology 64: 168: 173.
Syamsuddin, 2003. Pengendalian Penyakit Terbawa Benih (Sedd Borne Diseases) Pada Tanaman Cabai (Capsicum annum L.) menggunakan
Agen Biocontrol dan Ekstrak Botani.
Syafruddin, Faesal, dan M. Akil., 2007. Pengelolaan Hara pada Tanaman Jagung.Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 213-214.
Tim Bimbingan Teknis BPTP/LPTP, 1999. Metodologi Pengkajian Tanaman
Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Jakarta. Hal 28- 29.
Upadhyal, R.S. and R.K. Jasaswal. 1992. Pseudomonas cepacia causes mycelial deformities and inhibition of conidiation in phytopathogenic fungi. Current Microbiol.24(4): 181−187.
Wakman, W. dan Burhanuddin., 2007. Pengelolaan Penyakit Prapanen Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 310-313.
Wang and W.S. Wu. 1987. Survivability and biological control of Bipolaris
maydis on corn. Plant Prot. Bull. Taiwan 29(1): 1−2.
Lampiran 1.
BAGAN PENELITIAN
V III
I
IV II
Keterangan:
: Plot Tanaman Jagung
K0 = Kontrol (tanpa perlakuan)
K1 = Larutan daun sirih dengan dosis 300 gr/ liter air
K2 = Larutan daun sereh dengan dosis 300 gr/ liter air
K3 = Fungisida kimia bahan aktif propineb dengan dosis 1,4 gr/ liter air K4 = Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol dengan dosis 1 ml/ liter air
Jumlah plot : 5 x 5 = 25 plot
Jarak antar plot : 50 cm
Jarak antar ulangan : 50 cm
Parit keliling : 30 cm
Ukuran plot : 270 cm x 240 cm
Luas lahan : 17,50 m x 16,00 m
Jarak tanam : 70 x 30 cm
Jumlah tanaman per plot : 28 tanaman
Lampiran 2.
BAGAN TANAMAN SAMPEL
240 cm
270 cm
Keterangan :
: Tanaman jagung
: Tanaman sampel
30 cm
30cm
70cm
U
Lampiran 3. Deskripsi Tanaman Jagung Varietas BISI-16
Tanggal dilepas : 12 Oktober 2004
Asal : Hibrida modifikasi silang ganda antara hibrida silang tunggal FS 601 dan FS 602
Daun : Medium, bergelombang, dan agak tegak Warna daun : Hijau gelap
Keragaman tanaman : Seragam Perakaran : Baik
Kerebahan : Tahan rebah
Bentuk malai : Sedikit terbuka dan agak tegak Warna sekam : Ungu
Warna anther : Ungu kekuningan Warna rambut : Ungu kemerahan Tinggi tongkol : + 111 cm
Kelobot : Menutup tongkol cukup baik Tipe biji : Semi gigi kuda
Warna biji : Oranye kekuningan Jumlah baris/tongkol : 14 - 18 baris Bobot 1000 biji : + 336 g
Rata-rata hasil : 9,2 t/ha pipilan kering Potensi hasil : 13,4 t/ha pipilan kering
Ketahanan : Tahan terhadap penyakit karat daun
Keterangan : Baik ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 1000 m dpl
Lampiran 4.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan I (3 MST)
Perlakuan
Lampiran 5.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan II (4 MST)
Perlakuan
Ulangan
Total Rataan I II III IV V
K0 7.35 7.50 6.78 7.35 6.78 35.76 7.15 K1 6.48 7.58 7.08 6.54 7.08 34.76 6.95 K2 7.35 6.75 7.08 7.17 7.48 35.83 7.17 K3 7.08 7.35 7.35 7.08 6.35 35.21 7.04 K4 7.35 6.83 7.08 7.17 7.35 35.78 7.16 Total 35.61 36.01 35.37 35.31 35.04 177.34
Rataan 7.12 7.20 7.07 7.06 7.01 7.09
Analisis Sidik ragam
SK db JK KT Fh F0,05 F0,01 Ulangan 4 0.11 0.03 0.18 tn 3.01 4.77 Perlakuan 4 0.18 0.04 0.30 tn 3.01 4.77
Galat 16 2.36 0.15
Total 24 2.64
FK 1257.98 KK 5.42 %
Ket: tn : Tidak Nyata
* : Nyata
Lampiran 6.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan III (5 MST)
Perlakuan
Ulangan
Total Rataan I II III IV V
K0 12.15 12.98 12.08 12.33 12.58 62.12 12.42 K1 12.33 12.35 12.58 12.67 12.67 62.60 12.52 K2 11.58 12.00 12.83 12.20 12.98 61.59 12.32 K3 12.15 12.08 12.33 11.58 11.78 59.92 11.98 K4 12.98 12.83 11.78 12.18 12.18 61.95 12.39 Total 61.19 62.24 61.60 60.96 62.19 308.18
Rataan 12.24 12.45 12.32 12.19 12.44 12.33
Analisis Sidik ragam
SK db JK KT Fh F0,05 F0,01 Ulangan 4 0.27 0.07 0.34 tn 3.01 4.77 Perlakuan 4 0.84 0.21 1.08 tn 3.01 4.77
Galat 16 3.11 0.19
Total 24 4.21
FK 3799.00 KK 3.57 %
Ket: tn : Tidak Nyata
* : Nyata
Lampiran 7.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan IV (6 MST)
Lampiran 8.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan V (7 MST)
Lampiran 9.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan VI (8 MST)
Lampiran 10.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan VII (9 MST)
Lampiran 11.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan VIII (10 MST)
Lampiran 12.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan IX (11 MST)
Lampiran 13.
Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan X (12 MST)