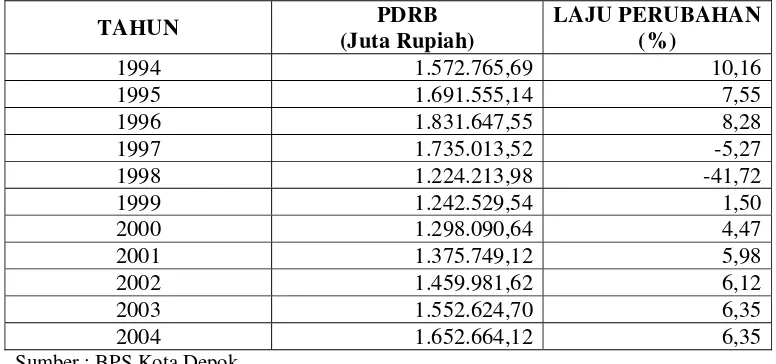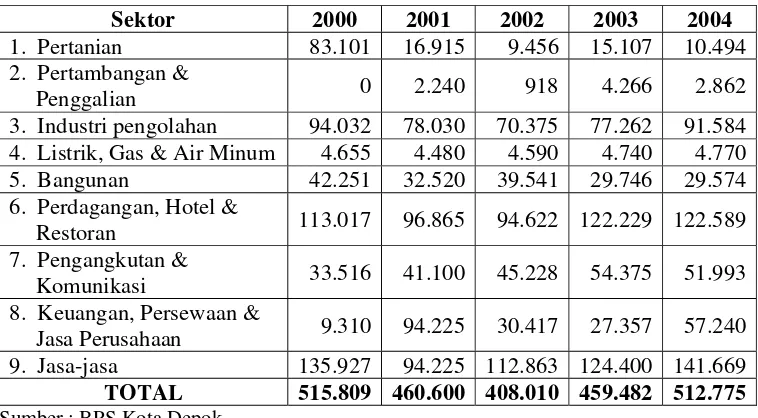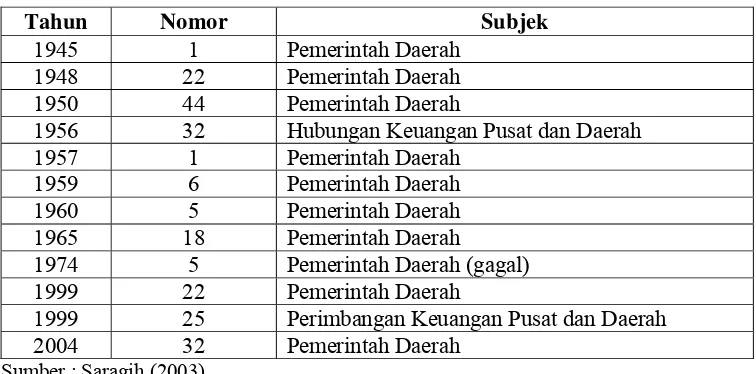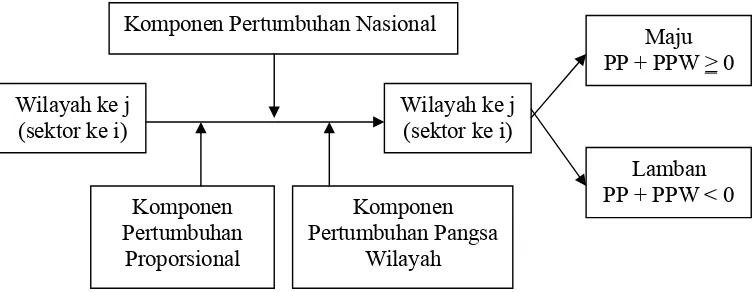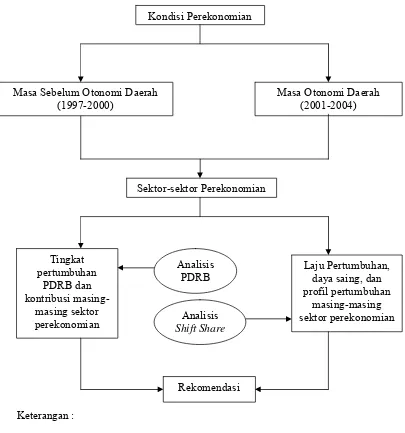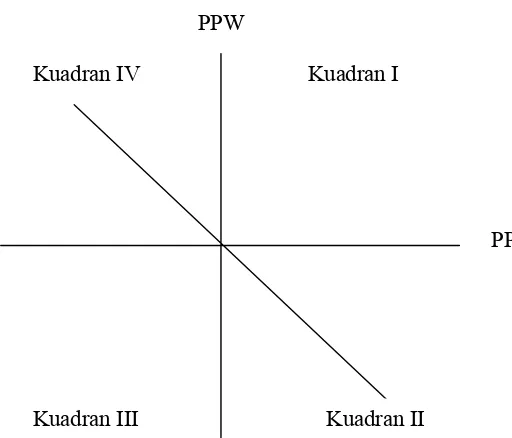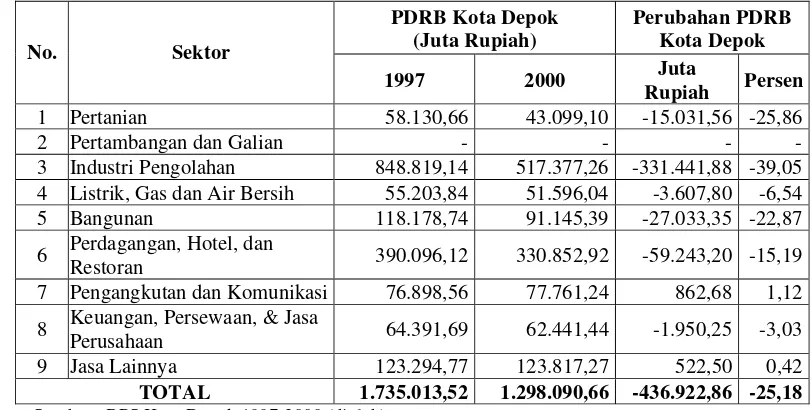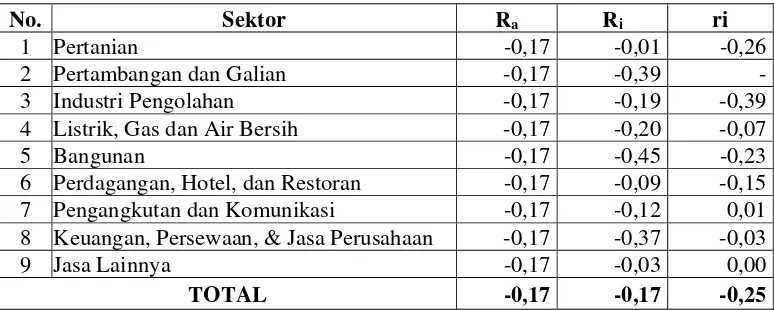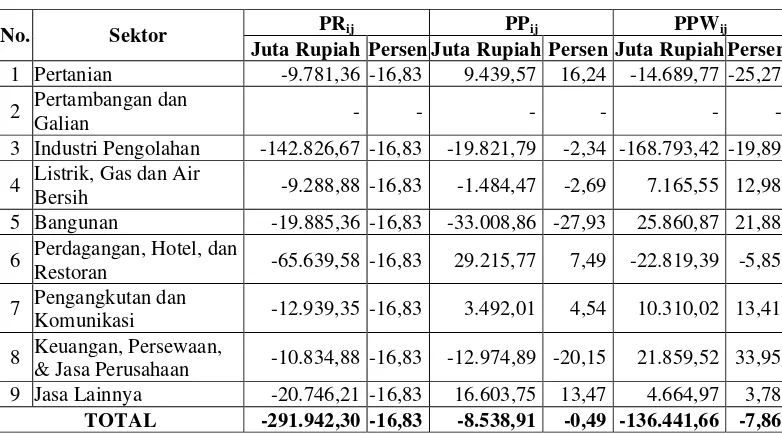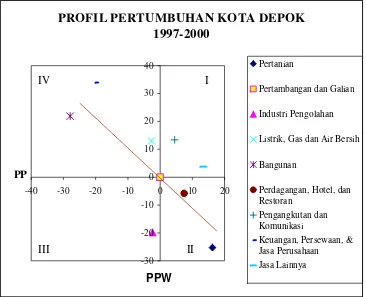Oleh ANNISA ANJANI
H14103124
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
RINGKASAN
ANNISA ANJANI. Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok) (dibawah bimbingan FIFI DIANA THAMRIN)
Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Pembangunan yang terjadi selama ini dirasa tidak menyentuh di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah pusat dengan daerah. Salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan tersebut adalah adanya struktur pemerintahan yang terpusat. Pada sistem pemerintahan yang terpusat ini pemerintah pusat berperan sebagai pengambil dan pembuat keputusan pembangunan untuk daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana.
Otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya untuk mengatur dearahnya sendiri secara mandiri dirasa akan membawa angin segar untuk mengatasi permasalahan tentang lambannya kemajuan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam realisasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang timbul pada daerah tersebut dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan segala potensi dan keragaman yang dimiliki daerah tersebut.
Menindaklanjuti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 diresmikan pula Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (dimana UU No. 15/1999 ini diimplementasikan di Kota Depok mulai 1 Januari 2001). Kota Depok memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk berkembang sebagai penyokong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok itu sendiri. Seiring dengan pembangunan di Kota Depok pula maka baik langsung maupun tak langsung akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap keadaan lingkungan di Kota Depok. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.
otonomi daerah berlangsung. Selang waktu tersebut dibagi menjadi dua selang waktu analisis, yaitu tahun 1997-2000 dan 2001-2004.
Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok selama otonomi daerah tahun 2001-2004, pertumbuhan PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar Rp 276.897,01 juta (20,13 persen). Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar (23,61 persen), sedangkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan terkecil (8,76 persen).
Laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok semasa otonomi daerah tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,07 persen. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan tercepat adalah sektor listrik, gas, dan air bersih (6,33 persen), dan yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian (-7,58 persen).
Daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,46 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum sektor-sektor perekonomian di Kota Depok memiliki daya saing cukup baik bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sektor yang memiliki daya saing yang kurang baik adalah sektor bangunan (-4,33 persen), sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang terbaik adalah sektor industri pengolahan (7,49 persen).
Pada tahun 2001-2004 secara keseluruhan nilai PB Kota Depok adalah bernilai positif (4,53 persen), artinya sektor-sektor perekonomian di Kota Depok secara keseluruhan tergolong ke dalam kelompok yang maju. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat PB terbesar (8,02 persen). Sedangkan sektor yang paling tidak progresif adalah sektor pertanian (-6,83 persen). Sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan berada di kuadran I yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang baik pula. Pada tahun 2001-2004 tidak ada sektor yang menempati kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa semasa otonomi daerah berlangsung, sektor-sektor perekonomian di Kota Depok tidak ada yang pertumbuhannya tergolong lambat.
Berdasarkan teori Rostow tentang tahapan pembangunan, maka Kota Depok dapat dikatakan berada pada tahap pra take-off menuju take-off. Hal ini dikarenakan, pada Kota Depok semasa otonomi daerah memiliki industri yang maju yang merupakan ciri pada tahapan pra take-off, namun Kota Depok belum memenuhi ciri pada tahap take-off.
adalah dengan mengembangkan pertanian perkotaan, yaitu dengan mengembangkan produk unggulan Kota Depok. Pemerintah Kota Depok hendaknya tetap menjaga kestabilan laju pertumbuhan perekonomian tersebut, terutama sektor listrik, gas, dan air bersih yang memiliki laju pertumbuhan tercepat pada masa otonomi dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dengan cara memberikan layanan prasarana air bersih yang optimal. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan harus terus dilakukan antara lain dengan meningkatkan tenaga kerja maupun pengusaha yang terlatih di bidang industri dan membina hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Sedangkan untuk sektor bangunan, harus tetap ditingkatkan kualitas bangunan di Kota Depok, terutama untuk bangunan perumahan. Perlu juga dilakukan rehabilitasi bangunan dan gedung, baik bangunan sekolah maupun peribadatan dan bangunan lainnya, yang sudah bobrok.
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa
Nomor Registrasi Pokok Program Studi
Judul Skripsi
: : : :
Annisa Anjani H14103124 Ilmu Ekonomi
Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok)
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Menyetujui, Dosen Pembimbing,
Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si NIP. 132 321 453
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, April 2007
1984 di Jakarta, hingga kini penulis berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Agus Basuki dan Erna Hernawati. Tahun 1996 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada SD Islam Yasma PB Sudirman, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada SLTP Islam Yasma PB Sudirman. Pada tahun 2002 penulis menamatkan pendidikan menengah atas pada SMU Negeri 99 Jakarta Timur.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok). Penulis tertarik menulis tentang otonomi di Kota Depok karena kian lama perkembangan Kota Depok kian pesat sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimilikinya, terutama selama otonomi berlangsung. Skripsi ini juga diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Kepada Ibu Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si dan Bapak Jaenal Effendi, MA selaku penguji dan komisi pendidikan yang telah menguji dan memberi banyak saran atas penyempurnaan skripsi ini. Kepada para Staf Departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan seminar dan sidang, penulis ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada para peserta seminar yang telah memberi kritik dan saran yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini.
Kepada seluruh sahabat dan teman-teman IE-40 (Utie, Tuti, Vivi, Yudis, Madu, Wilma, Tirani, Evi, dan semuanya), teman-teman IE-39 dan IE-41 (Teh Nita, Iyas, Heri, dan semuanya), teman-teman Hipotesa, teman-teman LabKom dan perpustakaan FEM, teman-teman KKP Dukuh Turi, teman-teman Wisma Melati dan teman-teman Pramana, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, yang telah banyak memberikan keceriaan, pemikiran, dorongan, dan semangat kepada penulis, hanya ucapan terima kasih untuk semua.
Bogor, April 2007
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kondisi tersebut memungkinkan pertumbuhan suatu wilayah sering kali tidak seimbang dengan wilayah lainnya (Gunawan, 2000). Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya (Rita, 2004).
Oleh ANNISA ANJANI
H14103124
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
RINGKASAN
ANNISA ANJANI. Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok) (dibawah bimbingan FIFI DIANA THAMRIN)
Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Pembangunan yang terjadi selama ini dirasa tidak menyentuh di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah pusat dengan daerah. Salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan tersebut adalah adanya struktur pemerintahan yang terpusat. Pada sistem pemerintahan yang terpusat ini pemerintah pusat berperan sebagai pengambil dan pembuat keputusan pembangunan untuk daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana.
Otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya untuk mengatur dearahnya sendiri secara mandiri dirasa akan membawa angin segar untuk mengatasi permasalahan tentang lambannya kemajuan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam realisasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang timbul pada daerah tersebut dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan segala potensi dan keragaman yang dimiliki daerah tersebut.
Menindaklanjuti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 diresmikan pula Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (dimana UU No. 15/1999 ini diimplementasikan di Kota Depok mulai 1 Januari 2001). Kota Depok memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk berkembang sebagai penyokong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok itu sendiri. Seiring dengan pembangunan di Kota Depok pula maka baik langsung maupun tak langsung akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap keadaan lingkungan di Kota Depok. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.
otonomi daerah berlangsung. Selang waktu tersebut dibagi menjadi dua selang waktu analisis, yaitu tahun 1997-2000 dan 2001-2004.
Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok selama otonomi daerah tahun 2001-2004, pertumbuhan PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar Rp 276.897,01 juta (20,13 persen). Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar (23,61 persen), sedangkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan terkecil (8,76 persen).
Laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok semasa otonomi daerah tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,07 persen. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan tercepat adalah sektor listrik, gas, dan air bersih (6,33 persen), dan yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian (-7,58 persen).
Daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,46 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum sektor-sektor perekonomian di Kota Depok memiliki daya saing cukup baik bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sektor yang memiliki daya saing yang kurang baik adalah sektor bangunan (-4,33 persen), sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang terbaik adalah sektor industri pengolahan (7,49 persen).
Pada tahun 2001-2004 secara keseluruhan nilai PB Kota Depok adalah bernilai positif (4,53 persen), artinya sektor-sektor perekonomian di Kota Depok secara keseluruhan tergolong ke dalam kelompok yang maju. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat PB terbesar (8,02 persen). Sedangkan sektor yang paling tidak progresif adalah sektor pertanian (-6,83 persen). Sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan berada di kuadran I yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang baik pula. Pada tahun 2001-2004 tidak ada sektor yang menempati kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa semasa otonomi daerah berlangsung, sektor-sektor perekonomian di Kota Depok tidak ada yang pertumbuhannya tergolong lambat.
Berdasarkan teori Rostow tentang tahapan pembangunan, maka Kota Depok dapat dikatakan berada pada tahap pra take-off menuju take-off. Hal ini dikarenakan, pada Kota Depok semasa otonomi daerah memiliki industri yang maju yang merupakan ciri pada tahapan pra take-off, namun Kota Depok belum memenuhi ciri pada tahap take-off.
adalah dengan mengembangkan pertanian perkotaan, yaitu dengan mengembangkan produk unggulan Kota Depok. Pemerintah Kota Depok hendaknya tetap menjaga kestabilan laju pertumbuhan perekonomian tersebut, terutama sektor listrik, gas, dan air bersih yang memiliki laju pertumbuhan tercepat pada masa otonomi dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dengan cara memberikan layanan prasarana air bersih yang optimal. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan harus terus dilakukan antara lain dengan meningkatkan tenaga kerja maupun pengusaha yang terlatih di bidang industri dan membina hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Sedangkan untuk sektor bangunan, harus tetap ditingkatkan kualitas bangunan di Kota Depok, terutama untuk bangunan perumahan. Perlu juga dilakukan rehabilitasi bangunan dan gedung, baik bangunan sekolah maupun peribadatan dan bangunan lainnya, yang sudah bobrok.
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa
Nomor Registrasi Pokok Program Studi
Judul Skripsi
: : : :
Annisa Anjani H14103124 Ilmu Ekonomi
Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok)
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Menyetujui, Dosen Pembimbing,
Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si NIP. 132 321 453
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, April 2007
1984 di Jakarta, hingga kini penulis berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Agus Basuki dan Erna Hernawati. Tahun 1996 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada SD Islam Yasma PB Sudirman, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada SLTP Islam Yasma PB Sudirman. Pada tahun 2002 penulis menamatkan pendidikan menengah atas pada SMU Negeri 99 Jakarta Timur.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok). Penulis tertarik menulis tentang otonomi di Kota Depok karena kian lama perkembangan Kota Depok kian pesat sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimilikinya, terutama selama otonomi berlangsung. Skripsi ini juga diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Kepada Ibu Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si dan Bapak Jaenal Effendi, MA selaku penguji dan komisi pendidikan yang telah menguji dan memberi banyak saran atas penyempurnaan skripsi ini. Kepada para Staf Departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan seminar dan sidang, penulis ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada para peserta seminar yang telah memberi kritik dan saran yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini.
Kepada seluruh sahabat dan teman-teman IE-40 (Utie, Tuti, Vivi, Yudis, Madu, Wilma, Tirani, Evi, dan semuanya), teman-teman IE-39 dan IE-41 (Teh Nita, Iyas, Heri, dan semuanya), teman-teman Hipotesa, teman-teman LabKom dan perpustakaan FEM, teman-teman KKP Dukuh Turi, teman-teman Wisma Melati dan teman-teman Pramana, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, yang telah banyak memberikan keceriaan, pemikiran, dorongan, dan semangat kepada penulis, hanya ucapan terima kasih untuk semua.
Bogor, April 2007
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kondisi tersebut memungkinkan pertumbuhan suatu wilayah sering kali tidak seimbang dengan wilayah lainnya (Gunawan, 2000). Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya (Rita, 2004).
Otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya untuk mengatur daerahnya sendiri secara mandiri dirasa akan membawa angin segar untuk mengatasi permasalahan tentang lambannya kemajuan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam realisasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bersama atribut-atribut lainnya. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang timbul pada daerah tersebut dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan segala potensi dan keragaman yang dimiliki daerah tersebut. Undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan pusat dengan daerah.
Namun Undang-undang per-otonomian daerah tersebut juga tidak dapat dilepaskan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Pada akhirnya pemerintah pusat akan berperan dalam kewenangan dan pengaturan keuangan daerah. Dampak yang berkembang selama otonomi daerah pun kian dirasa oleh masyarakat. Untuk menganalisis dampak otonomi daerah tersebut, penulis ingin mengangkat masalah dampak otonomi daerah terhadap sektor-sektor perekonomian di Kota Depok.
1.2. Perumusan Masalah
3
untuk memperoleh pendapatannya sendiri dari hasil pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.
Kota Depok memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk berkembang sebagai penyokong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok itu sendiri. Lokasi Kota Depok strategis karena terletak di pinggir perbatasan Provinsi Jawa Barat dan memiliki jalur yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok juga merupakan salah satu hinterland dari Kota Jakarta membuat Kota Depok mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dengan makin ramai dan semaraknya Kota Depok dan sekitarnya akibat pesatnya pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan industri.
Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok yang terus meningkat dapat menjadi indikator pesatnya pertumbuhan Kota Depok dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.1 dibawah ini.
Tabel 1.1. PDRB Kota Depok 1994-2004 Atas Dasar Harga Konstan 1993
TAHUN PDRB
Sumber : BPS Kota Depok
tahun 1997. Pada tahun 1998 PDRB Kota Depok mengalami penurunan drastis sebesar Rp 765.902,33 juta dari Rp 2.080.767,34 juta menjadi Rp 1.323.865,01 juta. Hal ini diperkirakan karena tidak stabilnya situasi politik secara nasional di Indonesia. Dampak krisis ekonomi yang terjadi akibat perubahan iklim politik tersebut turut mengguncang Kota Depok yang saat itu masih tergabung dalam kewilayahan Kabupaten Bogor. Pada tahun 2000 terjadi penurunan PDRB yang cukup besar dari Rp 1.375.749,12 juta pada tahun 1999 menjadi Rp 1.298.090,64 juta rupiah. Hal ini diperkirakan akibat dari implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di Kota Depok.
Kota Depok terus berkembang dan mengalami perubahan orientasi sebagai pusat pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan jasa. Perkembangan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 1.1 yaitu dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 1999-2004 yang mengalami peningkatan pertahunnya sebesar 1,50 persen, 4,47 persen, 5,98 persen, 6,12 persen, 6,35 persen, dan 6,44 persen. Hal tersebut memberikan tantangan bagi sektor-sektor perekonomian yang ada di dalamnya untuk lebih optimal lagi dalam memajukan sektor-sektor yang ada.
5
Seiring dengan pembangunan di Kota Depok pula maka baik langsung maupun tak langsung Kota Depok telah menyediakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Munculnya pusat hiburan dan banyaknya pembangunan yang terjadi tentu akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Berikut disajikan data ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Depok selama tahun 2000-2004.
Tabel 1.2. Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2000-2004 (Jiwa)
Sektor 2000 2001 2002 2003 2004
1. Pertanian 83.101 16.915 9.456 15.107 10.494 2. Pertambangan &
Penggalian 0 2.240 918 4.266 2.862
3. Industri pengolahan 94.032 78.030 70.375 77.262 91.584 4. Listrik, Gas & Air Minum 4.655 4.480 4.590 4.740 4.770 5. Bangunan 42.251 32.520 39.541 29.746 29.574 6. Perdagangan, Hotel &
Restoran 113.017 96.865 94.622 122.229 122.589 7. Pengangkutan &
Komunikasi 33.516 41.100 45.228 54.375 51.993 8. Keuangan, Persewaan &
Jasa Perusahaan 9.310 94.225 30.417 27.357 57.240 9. Jasa-jasa 135.927 94.225 112.863 124.400 141.669
TOTAL 515.809 460.600 408.010 459.482 512.775
Sumber : BPS Kota Depok
Besarnya peningkatan jumlah penduduk dan tenaga kerja dirasa akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap keadaan lingkungan di Kota Depok. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Hal ini tergantung dari keseimbangan dan keselarasan perkembangan yang ada di Kota Depok sendiri.
1. Bagaimana pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah?
2. Bagaimana laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah?
3. Bagaimana daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah?
4. Bagaimana profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor perekonomian Kota Depok?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah.
2. Menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah.
3. Menganalisis daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah.
4. Mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor perekonomian Kota Depok.
1.4. Manfaat Penelitian
7
1. Kegunaan bagi Pemerintah Kota Depok. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan sektor perekonomian mana yang dapat benar-benar menjadikan kota Depok sebagai unggulan.
2. Kegunaan bagi para akademisi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya atau pun hanya sebagai bacaan semata.
3. Kegunaan lainnya bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan suatu pengetahuan umum yang menarik, dan dipetik manfaatnya. Terutama pengetahuan terhadap Kota Depok dan perkembangannya.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup atau batasan dari penelitian ini adalah penelitian dengan mengamati dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok. Penelitian mengambil data tahun 1997 hingga tahun 2004, yaitu melibatkan data sebelum dan selama otonomi daerah berlangsung. Selang waktu tersebut dibagi menjadi dua selang waktu analisis, yaitu tahun 1997-2000, dan 2001-2004.
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan
pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang
selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Padahal konsep otonomi daerah sudah muncul pada saat pemerintahan orde lama,
yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah
(Pemerintah Pusat, 1999). Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan
mengenai pemerintah daerah.
Tabel 2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah sejak tahun 1945-1999
Tahun Nomor Subjek
1945 1 Pemerintah Daerah
1948 22 Pemerintah Daerah
1950 44 Pemerintah Daerah
1956 32 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
1957 1 Pemerintah Daerah
1959 6 Pemerintah Daerah
1960 5 Pemerintah Daerah
1965 18 Pemerintah Daerah
1974 5 Pemerintah Daerah (gagal)
1999 22 Pemerintah Daerah
1999 25 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
2004 32 Pemerintah Daerah
Sumber : Saragih (2003)
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah adalah
kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom, selanjutnya
daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 terdapat beberapa prinsip
tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah
(1) Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
(2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan
di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan (3) Asas tugas pembantuan yang
dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan
Desa.
Tiga asas pada prinsip pelaksanaan otonomi daerah (asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan) dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan
Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
11
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
Pada masa sebelum otonomi daerah kedudukan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah membentuk suatu hierarki, yaitu pemerintah pusat ada pada
posisi paling tinggi, kemudian provinsi, dan yang paling bawah adalah kabupaten.
Adanya otonomi daerah menyebabkan hierarki tersebut dihilangkan. Posisi
Kabupaten/Kota tidak memiliki hierarki terhadap propinsi. Hal ini menyebabkan
wewenang pemerintah daerah semakin besar. Berdasarkan Undang-undang No. 22
Tahun 1999 kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
Kewenangan bidang lain ini meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
Daerah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan dan kesejahteraan
pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Daerah berwenang mengelola sumber daya
nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara
bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
2.2. Konsep Regional dan Kewilayahan
Menurut BPS dalam buku Pendapatan Domestik Bruto Kotamadya Depok
(1998) Region dapat diartikan sebagai Daerah Tingkat I (Provinsi), Daerah
Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), dan Daerah administrasi yang lebih rendah
(kecamatan). Budiharsono (2001) menyatakan bahwa wilayah dapat diartikan
sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang
bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah tersebut dibagi menjadi empat
jenis, yaitu :
1. Wilayah Homogen
Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria
dan mempunyai sifat-sifat atau ciri yang relatif sama. Sifat-sifat atau
ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi, geografi, agama, suku,
dan sebagainya. Richardson (1975) dan Hoover (1977) mengemukakan bahwa
wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal
(internal uniformity). Contoh wilayah homogen adalah pantai utara Jawa
Barat yang merupakan wilayah yang homogen dari segi produksi padi
13
2. Wilayah Nodal
Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai
ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland).
Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi,
barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.
Dalam wilayah nodal pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam
wilayah tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Biasanya
daerah belakang akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja
kepada daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang
dalam bentuk barang jadi. Contoh wilayah nodal adalah DKI Jakarta dengan
Botabek (Bogor, Tanggerang, dan Bekasi), Jakarta yang merupakan daerah
inti dan Botabek sebagai daerah belakangnya.
3. Wilayah Administrasi
Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan
berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti
propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW. Dalam
kenyataannya, suatu pembangunan seringkali tidak hanya dalam satu kesatuan
wilayah administrasi. Sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan
daerah aliran sungai, pengelolaan lingkungan dan sebagainya, yang batasnya
bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan
seringkali lintas batas wilayah administrasi. Sehingga penanganannya
4. Wilayah Perencanaan
Boudeville dalam Glasson (1978) mendefinisikan wilayah perencanaan
sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan
keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang
cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting
dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk
memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai
suatu kesatuan (Budiharsono, 2001).
Klassen juga menyatakan ciri-ciri wilayah perencanaan adalah sebagai
berikut: (a) cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang
berskala ekonomi; (b) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga
kerja yang ada; (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (d)
mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan; (e) menggunakan
suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan; (f) masyarakat dalam
wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.
Salah satu contoh wilayah perencanaan yang ada di Indonesia adalah
BALERANG (Pulau Batam, P. Rempang, dan P. Galang). Daerah
perencanaan tersebut sudah lintas batas wilayah administrasi. (Budiharsono,
2001)
Klasifikasi wilayah dapat pula dibedakan atas dasar wilayah formal,
fungsional, dan perencanaan (Hanafiah, 1988) :
1. Wilayah Formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam
15
2. Wilayah Fungsional adalah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu
hubungan fungsional yang saling tergantung dalam kriteria tertentu, terkadang
wilayah fungsional diartikan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah
polaritas yang secara fungsional saling tergantung.
3. Perpaduan wilayah formal dengan wilayah fungsional menciptakan Wilayah
Perencanaan. Boudeville dalam Budiharsono (2001) mengemukakan bahwa
wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau
kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dirancang
sedemikian rupa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut
sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
2.3. Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Arsyad (1993) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi pada umumnya
didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita
penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan
pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang
apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan
penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun
demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua
istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi
sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah
ekonomi di negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk
menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang.
Menurut Rostow dalam Deliarnov (2005), proses pembangunan ekonomi
bisa dibedakan ke dalam lima tahap yaitu : (1) Tahap tradisional statis, yang
dicirikan oleh keadaan Iptek yang masih sangat rendah dan belum berpengaruh
terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi sektor
pertanian-pedesaan. Struktur sosial-politik juga masih bersifat kaku; (2) Tahap
transisi (pra take-off), yang dicirikan oleh Iptek yang mulai berkembang,
produktivitas yang meningkat dan industri yang makin berkembang. Tenaga kerja
pun mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri, pertumbuhan tinggi,
kaum pedagang bermunculan, dan struktur sosial-politik yang makin membaik;
(3) Tahap lepas landas, yang dicirikan oleh keadaan suatu hambatan-hambatan
sosial politik yang umumnya dapat diatasi, tingkat kebudayaan dan Iptek yang
makin maju, investasi dan pertumbuhan tetap tinggi, dan mulai terjadi ekspansi
perdagangan ke luar negeri; (4) Tahap dewasa (maturing stage), dicirikan oleh
masyarakat yang makin dewasa, dapat menggunakan Iptek sepenuhnya. Terjadi
perubahan komposisi angkatan kerja dimana jumlah tenaga kerja skilled lebih
banyak dari pada tenaga kerja unskilled. Serikat dagang dan gerakan buruh
semakin maju dan berperan, dan tingginya pendapatan perkapita; dan (5) Tahap
konsumsi massa (mass consumption) yang merupakan tahap akhir dimana
masyarakat hidup serba kecukupan, kehidupan dirasakan aman tentram, dan laju
17
Penelitian Kuznets (1966) dalam Sukirno (1985) tentang corak perubahan
persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi di 13
negara2 adalah sebagai berikut:
1. Sumbangan sektor pertanian pada produksi nasional telah menurun di 12
negara dari 13 negara. Umumnya pada awal pembangunan ekonomi, peranan
sektor pertanian mendekati setengah (hingga duapertiga) dari seluruh produksi
nasional. Pada akhir penelitian, peranan sektor pertanian dalam menghasilkan
produksi nasional hanya mencapai 20 persen atau kurang di beberapa negara,
dan di beberapa negara peranannya lebih rendah dari 10 persen.
2. Di 12 negara, peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional
meningkat. Pada awal penelitian, sumbangan sektor industri berkisar antara
20-30 persen dari seluruh produksi nasional. Pada akhir penelitian, peranan
sektor industri paling sedikit meningkat 20 persen sehingga sedikitnya
menyumbang 40 persen terhadap produksi nasional.
3. Sektor jasa-jasa sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional tidak
mengalami perubahan yang berarti dan perubahan tersebut tidak konsisten
sifatnya.
Perubahan struktur ekonomi tersebut berarti bahwa (1) sektor pertanian
produksinya mengalami perkembangan yang lebih lambat dari perkembangan
produksi nasional; sedangkan (2) tingkat pertambahan produksi sektor industri
adalah lebih cepat dari pada tingkat pertambahan produksi nasional; dan (3) tidak
adanya perubahan dalam peranan sektor jasa-jasa dalam produksi nasional berarti
2
perkembangan sektor jasa-jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan
produksi nasional.
Teori pattern of development oleh Chenery (1975) dalam Tambunan
(2001) mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan
masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan
konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain
ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik
dan manusia (SDM). Perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban
bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan
penurunan laju pertumbuhan penduduk dan family size yang semakin kecil.
Struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh
sektor pertanian dan/atau sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor
nonprimer, khususnya industri.
Irawan, Suparmoko (1999) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi
adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering
diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi pembangunan
ekonomi selain untuk meningkatkan pendapatan riil juga untuk meningkatkan
produktivitas. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu
wilayah atau daerah. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi dan faktor
nonekonomi (seperti hukum, pendidikan, agama, pemerintah, dan lainnya).
Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses
pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam
19
kemajuan material harus muncul dari warga masyarakatnya sendiri dan tidak
dapat dipengaruhi atau diidentifikasi oleh daerah luar (Jhingan, 2002).
2.4. Konsep Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Daerah
Soegijoko (1997) menyatakan bahwa suatu masyarakat dalam suatu
wilayah, tempat atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau
wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik dan sosialnya.
Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan
koordinasi proyek dan pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan
nasional. Dari segi pembangunan, perencanaan regional memberikan rangka dasar
dalam proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal dapat dipertemukan
secara balanced dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu
rangkaian pembangunan yang menyeluruh.
Sogijoko (1997) juga menyatakan bahwa adanya proses desentralisasi
menuntut dilakukannya penyediaan pelayanan, perbaikan kemampuan aparat
pemerintah daerah, dan penguatan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat
wilayah. Oleh karena itu, strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
wilayah adalah sebagai berikut :
1. Desentralisasi Kekuasaan
Pemerintah harus meningkatkan kemampuan dalam memperbesar
pendapatan daerah. Di lain pihak, pemerintah pusat tetap meneruskan
pengalihan sumber daya kepada pemerintah daerah dalam bentuk bantuan
yang tidak mengikat sehingga memberikan keleluasaan dalam membuat
2. Peningkatan Pendapatan Daerah
Dewasa ini bantuan pemerintah pusat merupakan kekuatan untuk
pemerintah daerah. Akan tetapi, dengan adanya proses desentralisasi,
pemerintah daerah perlu menyusun sejumlah kriteria untuk pemasukan
keuangan daerah. Pemerintah daerah juga harus dapat menampilkan
kemampuan administrasi dan proses budgetting yang baik, agar dianggap
mampu untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.
3. Pengembangan Kelembagaan
Kesuksesan desentralisasi pendanaan akan tergantung dari peningkatan
kemampuan kelembagaan pemerintah agar lebih efisien dan efektif.
Tantangan itu dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk
keterkaitan antar-kelembagaan agar lebih transparan dan bertanggung jawab
serta profesional.
4. Keanekaragaman Budaya
Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki kemauan dan kebutuhan
yang berbeda-beda dan dituangkan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh
sebab itu, aparat pemerintah daerah harus tanggap terhadap
perbedaan-perbedaan itu, sehingga perlu adanya penilaian sosial yang menggambarkan
pendekatan strategi kebudayaan untuk masing-masing daerah.
Tambunan (2001) menyatakan ada beberapa teori yang dapat
menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi
21
1. Teori Basis Ekonomi
Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan
permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor industri
di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal, termasuk
tenaga kerja dan bahan baku, dan output-nya di ekspor akan menghasilkan
pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan
peluang kerja di daerah tersebut.
2. Teori Lokasi
Inti pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha atau
perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan
biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha memilih lokasi usaha
yang memaksimumkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha
atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan
pasar.
3. Teori Daya Tarik Industri
Dalam upaya pengembangan ekonomi daerah di Indonesia sering
dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan. Ini
adalah masalah membangun portofolio industri suatu daerah. Dalam
menjawab pertanyaan tersebut, ada sejumlah faktor penentu pembangunan
industri di suatu daerah, yang terdiri atas (1) Faktor-faktor daya tarik industri
yang mencakup nilai tambah yang tinggi per pekerja/produktivitas,
dan prospek bagi permintaan domestik; dan (2) Faktor-faktor daya saing
daerah, meliputi penilaian kemampuan industri suatu daerah dan
pembangunan kemampuan industri suatu daerah.
2.5. Konsep Perkotaan
Berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan
Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa serta perubahan nama dan pemindahan
ibukota pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Kawasan Perkotaan memiliki status Daerah Kota, dan
adanya penetapan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :
1. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
2. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah
Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan
3. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang
berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.
Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya
berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola
Kawasan Perkotaan. Di Kawasan Pedesaan yang direncanakan dan dibangun
menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan
Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
23
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah
Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pengikutsertaan
masyarakat ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
perkotaan, dan pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
O’Sullivan (2001) menyatakan bahwa sebuah kota adalah pusat produksi
dan perdagangan. Dengan adanya dua sentra tersebut, maka munculnya kota akan
meningkatkan standar hidup masyarakat disekitarnya. Pusat kota adalah wilayah
dimana terdapat pusat pelayanan pemerintah. Sedangkan area perkotaan adalah
wilayah yang terdiri dari minimal satu pusat kota dan dikelilingi oleh area yang
memiliki kepadatan penduduk lebih dari 1000 jiwa per acre3, sehingga total
penduduknya dalam area perkotaan minimal 50 ribu jiwa. Sedangkan yang
dimaksud dengan kota metropolitan adalah area yang memiliki jumlah penduduk
yang sangat besar di pusat kotanya dan terintegrasi secara ekonomi. Karakteristik
kota metropolitan adalah memiliki kepadatan penduduk di pusat kota sebanyak 50
ribu jiwa dan ditambah lagi dengan penduduk yang ada di area perkotaan,
sehingga jumlah penduduknya akan mencapai lebih dari 50 ribu jiwa.
Tatag Wiranto dalam Soegijoko (1997) mengungkapkan bahwa ciri
masyarakat perkotaan ditandai oleh struktur masyarakat berbasis perdagangan dan
jasa, kepadatan penduduk rapat, tempat tinggal penduduk berkelompok, tenaga
3
berpendidikan relatif tinggi, dan sistem organisasi kerja yang kompleks berbasis
kegiatan formal. Kawasan perkotaan juga dianggap pusat kegiatan ekonomi dan
politik, dan dianggap sebagai tempat dimana terjadinya proses pemusatan
kekuasaan dan perubahan budaya, pusat kreativitas yang menyebabkan terjadinya
pola perkembangan kehidupan masyarakat dan lingkungan fisiknya sangat
berbeda dengan kawasan pedesaan yang biasanya disebut kawasan pinggiran.
2.6. Penelitian Terdahulu
Budiharsono (2001) melakukan penelitian tentang keadaan perekonomian
antar daerah (27 provinsi) di Indonesia dengan menggunakan metode analisis Shift
Share. Hasilnya adalah bahwa pertumbuhan Produk Domestik (PDB) Indonesia
pada tahun 1983-1987 sebesar 27,14 persen. Pertumbuhan ini tidak merata di
seluruh provinsi. Provinsi-provinsi yang pertumbuhan PDRB-nya melebihi
pertumbuhan PDB Indonesia pada kurun waktu 1983-1987 adalah Daerah
Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara,
Maluku dan Timor Timur. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya memiliki tingkat
PDRB yang lebih kecil daripada pertumbuhan PDB-nya pada kurun waktu
1983-1987. Kemudian Budiharsono melakukan penelitian kembali terhadap
pertumbuhan sektor-sektor di provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1983-1987.
Hasilnya adalah sektor-sektor Industri, Utilitas dan Jasa merupakan sektor yang
pertumbuhannya cepat. Sedangkan sektor pertanian mempunyai nilai pergeseran
25
Ardiansyah (2004) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan
sektor-sektor perekonomian di Kota Jambi sebelum dan pada masa otonomi
menyimpulkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah seluruh sektor
perekonomian di Kota Jambi pertumbuhannya pesat. Akan tetapi setelah adanya
otonomi daerah, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang lambat.
Kota Jambi kalah bersaing dengan Kabupaten yang lain. Selain itu dampak krisis
ekonomi juga secara tidak langsung masih berpengaruh terhadap perekonomian
Kota Jambi.
Restuningsih (2004) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan
sektor-sektor perekonomian di propinsi DKI Jakarta pada masa krisis ekonomi tahun
1997-2002 dengan menggunakan alat analisis Shift Share menyimpulkan bahwa
krisis ekonomi yang melanda DKI Jakarta menyebabkan sebagian besar
sektor-sektor ekonomi tidak dapat bersaing dengan baik, yaitu sektor-sektor pertanian, sektor-sektor
industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan dan sektor
jasa-jasa. Sedangkan sektor pertambangan dan galian, sektor pengangkutan dan
komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan,
perbankan, dan jasa perusaan dapat bersaing dengan baik.
Ruth Elisabeth (2006) menggunakan analisis Shift Share dalam
penelitiannya untuk menganalisis dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan
sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasilnya adalah sebelum
otonomi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara
lebih kecil dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Saat
Tapanuli Utara lebih besar dari tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
Propinsi Sumatera Utara. Pada masa otonomi daerah pertumbuhan sektor-sektor
perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara lebih kecil dari pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Sebelum otonomi daerah perekonomian
Tapanuli Utara tergolong lambat, pada tahun 1997-2000 juga masih cenderung
lambat, dan pada tahun 2001-2004 pertumbuhannya adalah progresif.
Azman (2001) menyimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten
Padang Pariaman selama tahun 1995-1999 telah terjadi pergeseran dari kelompok
sektor primer ke kelompok sektor tersier (melalui analisis Shift Share). Walaupun
demikian, sektor pertanian yang berada pada kelompok sektor primer masih tetap
mendominasi bila dibandingkan dengan sektor lainnya, baik dari segi
kontribusinya terhadap PDRB maupun dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
Sedangkan pada kelompok tersier, sektor yang memberikan kontribusi terbesar
adalah sektor jasa-jasa.
Berdasarkan penelitian terdahulu ada yang menganalisis pertumbuhan
ekonomi atau pertumbuhan wilayah pada satu kurun waktu tertentu dan ada pula
yang menganalisis pertumbuhan wilayah pada dua kurun waktu. Pada penelitian
ini menggunakan dua kurun waktu yaitu sebelum dan selama otonomi daerah, tapi
dengan kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang dipakai berbeda dengan
penelitian sebelumnya dan terbagi dalam tiga periode, yaitu periode masa sebelum
krisis ekonomi tahun 1994-1996, periode pada masa krisis ekonomi tahun
27
2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis 2.8.1. Analisis Shift Share
Analisis Shift Share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et all (1960),
yang telah menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan
ekonomi wilayah di Amerika Serikat. Lucas (1979) juga menggunakan analisis ini
untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor atau wilayah yang lamban di
Indonesia dan Amerika Serikat. Analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk
menduga dampak kebijakan wilayah ketenagakerjaan.
Analisis Shift Share merupakan suatu analisis mengenai perubahan
berbagai indikator ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik
waktu di suatu wilayah. Analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk
membandingkan laju sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan laju
pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektor dan mengamati
penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangannya
bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi dalam wilayah
tersebut memiliki keunggulan kompetitif.
Analisis Shift Share memiliki tiga kegunaan, yaitu untuk melihat
perkembangan :
1. Sektor perekonomian di suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi
wilayah yang lebih luas.
2. Sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan
3. Suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat
membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan
pertumbuhan antar wilayah. Dengan demikian, dapat ditunjukan adanya shift
(pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu
memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian
nasional.
Pada analisis Shift Share diasumsikan bahwa perubahan indikator
kegiatan ekonomi disuatu wilayah antara tahun dasar analisis dengan tahun akhir
analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan, yaitu :
1. Komponen Pertumbuhan Nasional
Komponen pertumbuhan nasional (PN) adalah perubahan
produksi/kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan
produksi/kesempatan kerja nasional secara umum, perubahan kebijakan
ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi
perekonomian semua sektor dan wilayah. Dalam hal ini, analisis pertumbuhan
ekonomi hanya difokuskan pada pembahasan daerah kabupaten. Maka, istilah
komponen PN dianalogikan menjadi komponen pertumbuhan regional (PR).
Hal ini dilakukan untuk menghindari salah penafsiran dalam pengertian
nasional (Indonesia) dengan regional (provinsi/kabupaten).
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional
Komponen pertumbuhan proposional (PP) tumbuh karena perbedaan
sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan
29
Komponen Pertumbuhan Nasional
subsidi dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman
pasar.
3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) timbul karena
peningkatan atau penurunan produksi/kesempatan kerja dalam suatu wilayah
dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu
wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan
komperatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi
serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.
Berdasarkan ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut dapat
ditentukan dan diidentifikasikan perkembangan suatu sektor ekonomi pada suatu
wilayah. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan
sektor ke i di wilayah ke j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju).
Sementara itu, PP + PPW < 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ke i pada
wilayah ke j tergolong lamban. Kerangka analisis shift share dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
Gambar 2.1. Kerangka Model Analisis Shift Share
2.8.2. Keunggulan Analisis Shift Share
Menurut Soepono (1993), keunggulan analisis Shift Share tersebut adalah:
1. Analisis Shift Share dapat melihat perkembangan produksi atau kesempatan
kerja pada suatu wilayah hanya pada dua titik waktu tertentu, yang mana satu
titik waktu dijadikan sebagai dasar analisis, sedangkan satu titik waktu
lainnya dijadikan sebagai akhir analisis.
2. Perubahan PDRB di suatu wilayah antara tahun dasar analisis dapat dilihat
melalui 3 komponen pertumbuhan wilayah, yakni komponen pertumbuhan
regional (PR), komponen pertumbuhan proposional (PP), dan komponen
pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).
3. Komponen PP dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor
perekonomian di suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa suatu wilayah dapat
mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional
dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih
cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor tersebut.
4. Komponen PPW dapat digunakan untuk melihat daya saing sektor-sektor
ekonomi dibandingkan dengan sektor ekonomi pada wilayah lainnya.
5. Jika persentase PP dan PPW dijumlahkan, maka dapat ditunjukkan adanya
shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah.
2.8.3. Kekurangan Analisis Shift Share
Kemampuan teknik analisis Shift Share untuk memberikan dua indikator
positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor
31
wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk
sektor-sektor tersebut, tidaklah lepas dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan
analisis Shift Share, yaitu :
1. Analisis Shift Share tidak lebih daripada suatu teknik pengukuran atau
prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah
menjadi komponen-komponen. Persamaan Shift Share hanyalah identity
equation dan tidak mempunyai implikasi-implikasi keprilakuan. Metode Shift
Share tidak untuk menjelaskan mengapa. Misalnya, pengaruh kenggulan
kompetitif adalah positif dibeberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah
lain. Metode Shift Share merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan
suatu sistem perhitungan semata dan tidak analitik.
2. Komponen pertumbuhan regional secara implisit mengemukakan bahwa laju
pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju regional tanpa
memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.
3. Kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) berkaitan dengan
hal-hal yang sama seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan
teknologi dan perubahan lokasi, sehingga dapat berkembang dengan baik.
4. Teknik analisis Shift Share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua
barang dijual secara nasional, padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu
wilayah bersifat lokal, maka barang itu tidak dapat bersaing dengan
wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama, sehingga tidak
2.9. Kerangka Pemikiran Konseptual
Kondisi perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh demografi, potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam
pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kekuasaan dalam pengambilan
keputusan ini termasuk didalamnya adalah pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu keputusan tersebut adalah keputusan
mengenai otonomi daerah di daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah tersebut
merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat sangat dominan
dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga daerah tidak dapat
berkreasi sendiri dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Sedangkan
pada masa otonomi daerah, daerah di tuntut untuk mengembangkan daerahnya
sendiri dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Dari kondisi daerah tersebut, terdapat sembilan sektor perekonomian yang
dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur pertumbuhan suatu perekonomian.
Kesembilan sektor tersebut adalah: (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan
Penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Minum; (5)
Bangunan; (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Pengangkutan dan
Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-jasa.
Dari kesembilan sektor tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan PDRB dan
33
dapat diketahui laju pertumbuhan, daya saing, dan profil pertumbuhan dari
masing-masing sektor perekonomian melalui analisis Shift Share. Setelah
melakukan analisis PDRB dan analisis Shift Share maka akan didapatkan sebuah
hasil dan kesimpulan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi
pemerintah setempat untuk merencanakan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di Kota Depok selanjutnya. Adapun kerangka pemikiran konseptual
Keterangan :
: Hal-hal yang dianalisis
: Analisis yang digunakan
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran konseptual Kondisi Perekonomian
Masa Otonomi Daerah (2001-2004)
Sektor-sektor Perekonomian
Laju Pertumbuhan, daya saing, dan profil pertumbuhan
masing-masing sektor perekonomian Tingkat
pertumbuhan PDRB dan kontribusi
masing-masing sektor perekonomian
Rekomendasi Analisis
PDRB
Analisis Shift Share Masa Sebelum Otonomi Daerah
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2006-Mei 2007. Lokasi
penelitian adalah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai
objek penelitian karena : (1) Kota Depok mengalami perkembangan dari tahun ke
tahun karena di dukung oleh berbagai potensi sektor perekonomian, seperti sektor
industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran; (2) Letak Kota Depok
cukup strategis, yaitu terbentang antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi DKI Jakarta; (3) Tersedianya data PDRB dan data pendukung
lainnya yang relatif lengkap; (4) Belum adanya penelitian tentang analisis
pertumbuhan sektor-sektor perekonomian pasca otonomi daerah dengan studi
kasus Kota Depok.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder yang diperoleh
dari BPS Kota Depok, BPS Kabupaten Bogor, dan instansi terkait lainnya. Data
yang dibutuhkan adalah data PDRB Kota Depok tahun 1997-2004, data PDRB
Jawa Barat tahun 1997-2004, dan data-data lainnya yang mendukung.
3.3. Metode Analisis Shift Share
Pada analisis Shift Share diasumsikan bahwa perubahan indikator
kegiatan ekonomi disuatu wilayah antara tahun dasar analisis dengan tahun akhir
pertumbuhan regional, komponen pertumbuhan proporsional, dan komponen
pertumbuhan pangsa wilayah.
3.3.1. Analisis PDRB Kota dan PDRB Provinsi
Asumsikan dalam suatu wilayah perekonomian terdapat m wilayah kota
(j=1,2,3,...,m) dan n sektor ekonomi (i=1,2,3,...,n), maka perubahan dalam PDRB
dapat dinyatakan sebagai berikut :
∆Yij = PRij + PPij + PPWij (1)
dimana :
∆Yij = Perubahan PDRB sektor i pada wilayah ke j,
PRij = Persentase perubahan PDRB Kota yang disebabkan komponen pertumbuhan regional,
PPij = Persentase perubahan PDRB Kota yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional,
PPWij = Persentase perubahan PDRB Kota yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.
Untuk memperoleh nilai PR, PP dan PPW, ada beberapa rumusan yang
harus dipenuhi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis :
Yi =
∑
=
m
j ij Y 1
dimana:
Yi = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.
37
2. PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis :
Y`i =
∑
Yi = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis.
Y`ij = PDRB kota sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis.
Sedangkan Total PDRB propinsi pada tahun dasar analisis dan tahun akhir
analisis dapat dirumuskan sebagai berikut.
3. Total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis :
Y.. =
∑∑
Y.. = Total PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.
Yij = Total PDRB kota sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.
4. Total PDRB provinsi pada tahun akhir analisis :
Y`.. =
∑∑
Y`.. = Total PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.
Y`ij = Total PDRB kota sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.
3.3.2. Rasio PDRB Kota dan PDRB Propinsi (Nilai Ra, Ri, dan ri)
Nilai Ra, Ri, dan ri digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB
Menghitung nilai Ra, Ri, dan ri menggunakan nilai PDRB yang terjadi pada dua
titik waktu, yaitu tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis.
1. Nilai Ra
Ra merupakan selisih antara total PDRB provinsi pada tahun akhir analisis
dengan total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis dibagi total PDRB provinsi
pada tahun dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut.
Ra =
Y`.. = Total PDRB Provinsi pada tahun akhir analisis,
Y.. = Total PDRB Provinsi pada tahun dasar analisis.
2. Nilai Ri
Ri adalah selisih antara PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir
analisis dengan PDRB provinsi sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDRB
propinsi sektor i pada tahun dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut.
Ri =
Y`i. = PDRB Provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis,
Yi. = PDRB Provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.
3. Nilai ri
ri adalah selisih antara PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada
tahun akhir analisis dengan PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun
39
Y`ij = PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis,
Yij = PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.
3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah
Nilai komponen PR, PP, dan PPW didapat dari perhitungan nilai Ra, Ri,
dan ri. Dari ketiga komponen tersebut apabila dijumlahkan akan didapatkan nilai
perubahan PDRB.
1. Komponen Pertumbuhan Regional (PR)
Komponen Pertumbuhan Regional adalah perubahan produksi suatu
wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi regional secara umum,
perubahan kebijakan ekonomi regional, atau perubahan dalam hal-hal yang
mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila diasumsikan bahwa
tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor dan antar wilayah, maka
adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan
wilayah. Pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat
daripada sektor dan wilayah lainnya. Komponen PR dirumuskan sebagai berikut.
PRij = (Ra) Yij (2)
dimana :
PRij = Komponen pertumbuhan regional sektor i pada wilayah ke j,