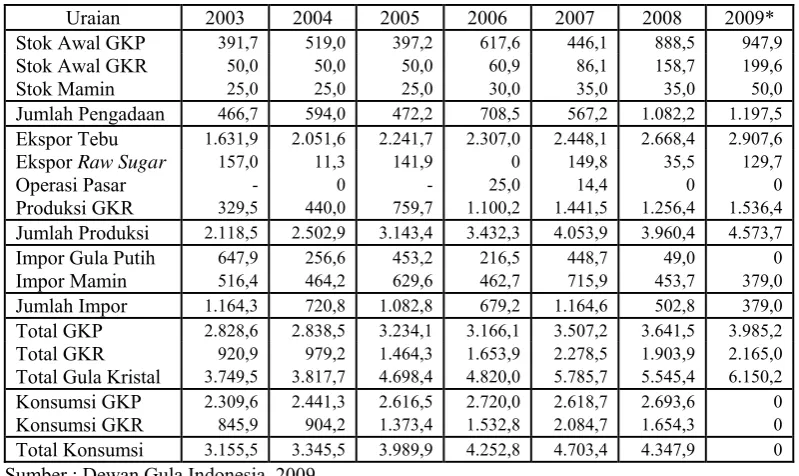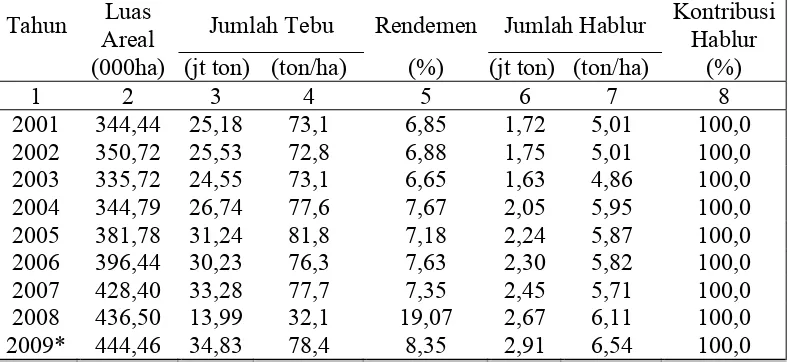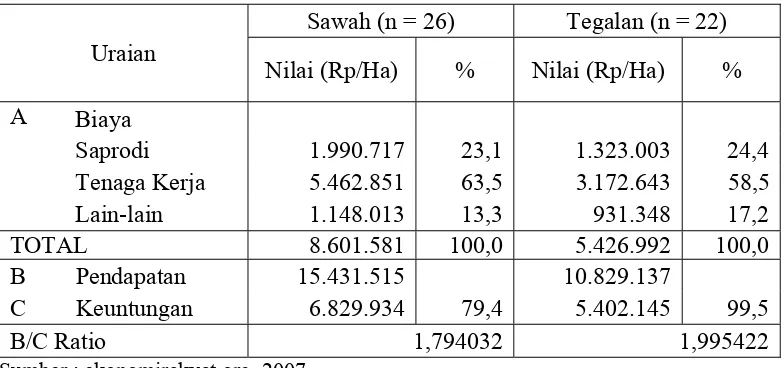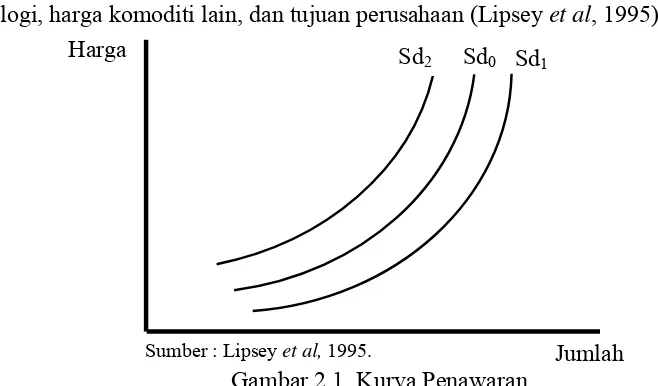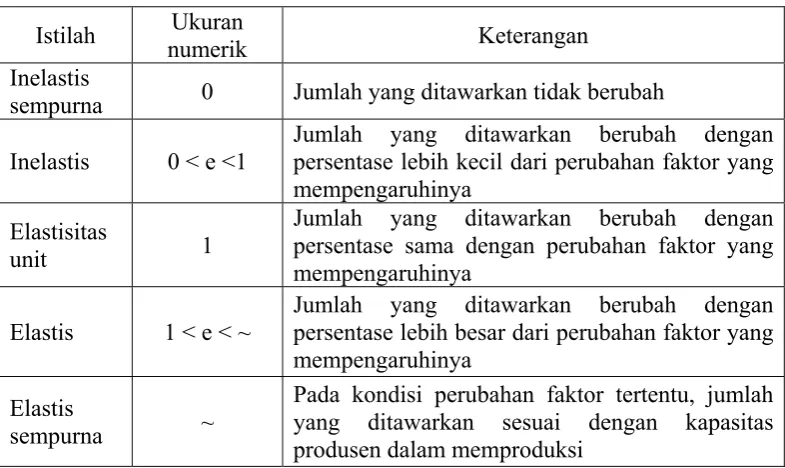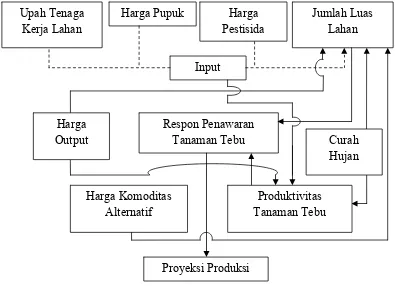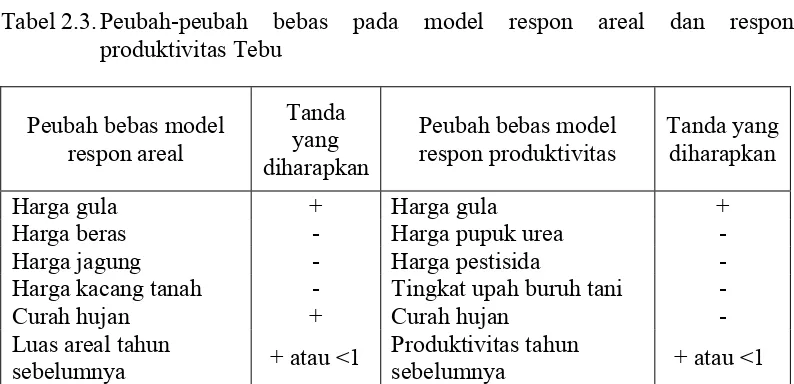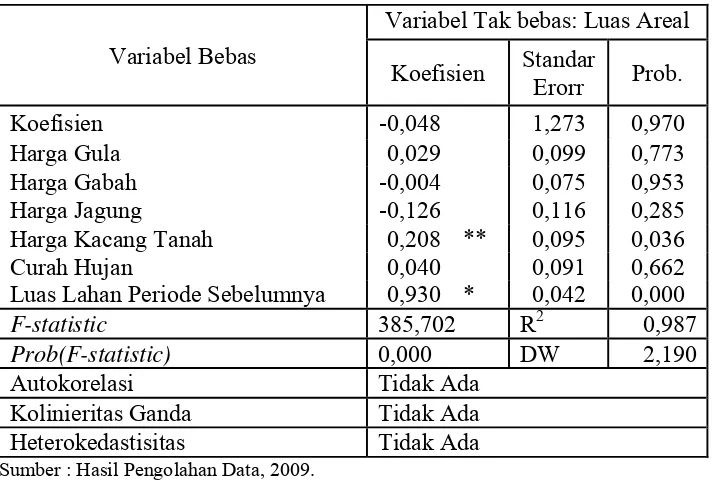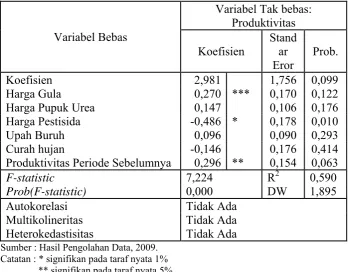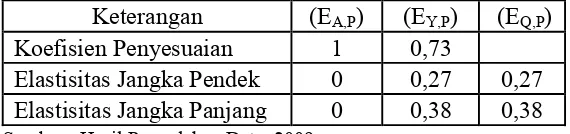F
DEP
FAKULT
INS
I MA
PARTEM
TAS EKON
STITUT P
OLEH ADE SANJ
H14053726
MEN ILMU
NOMI DA
PERTANI
2009
JAYA 6
U EKON
AN MAN
IAN BOG
OMI
NAJEMEN
GOR
RINGKASAN
I MADE SANJAYA, Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran (dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM).
Adanya isu kelangkaan minyak bumi akhir-akhir ini menyebabkan perlunya kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan energi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2006 yang kemudian direspon oleh Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan menetapkan sasaran bahwa pada tahun 2025 penggunaan energi berbahan dasar minyak bumi ditargetkan kurang dari 20 persen dari konsumsi energi total, penggunaan gas bumi sebesar 30 persen, lebih dari 33 persen berbahan baku batu bara, lebih dari 5 persen untuk masing-masing panas bumi, energi nabati (tanaman) dan energi alternatif lainnya.
Salah satu tanaman yang berpotensi diolah menjadi bahan baku penghasil energi adalah tanaman tebu. Penggunaan tanaman tebu sebagai bahan baku penghasil energi diduga akan menyebabkan trade off output tanaman tebu itu sendiri. Jika hal tersebut benar, maka pergeseran fungsi output akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran dari tanaman tebu. Untuk itu perlu dilakukan analisis respon penawaran tebu Indonesia.
Ketersedian tebu di Indonesia sebagai penghasil gula masih belum mencukupi, hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan total gula nasional yang lebih besar daripada jumlah produksi gula di dalam negeri. Akibatnya pengadaan impor gula sampai dengan tahun 2008 masih terus dilakukan. Ironisnya, lahan yang tersedia di Indonesia merupakan lahan yang sangat potensial ditanami tebu. Rendahnya produksi tebu nasional selain dikarenakan jumlah luas areal tanam yang tergolong sempit, juga disebabkan oleh produktivitas tanaman tebu yang masih rendah.
Untuk meningkatkan produksi tebu domestik diperlukan pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, baik dari segi harga output, harga input produksi, dan variabel-variabel non-market yang secara relevan mempengaruhi pergeseran produksi tanaman tebu.
Pada penelitian ini pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penawaran tebu di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data
didasarkan karena produk yang diteliti adalah produk pertanian yang mempunyai karakteristik beda kala.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif didasarkan untuk menjelaskan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan produksi tanaman tebu di Indonesia. Metode analisis kuantitatif didasarkan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini mempengaruhi variabel tak bebas yang dikaji.
Dari hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan produksi tebu Indonesia jauh lebih responsif jika dilakukan dengan pendekatan intensifikasi, artinya peningkatan penawaran dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan harga faktor-faktor input produksi produk pertanian seperti kebijakan harga pupuk, harga pestisida, dan tingkat upah buruh.
PROYEKSI PENAWARAN TEBU INDONESIA TAHUN 2025 : ANALISIS RESPON PENAWARAN
OLEH I MADE SANJAYA
H14053726
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Skripsi : Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran
Nama : I Made Sanjaya
NIM : H14053726
Menyetujui :
Dosen Pembimbing,
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M. Ec
NIP : 19641022 198903 1 003
Mengetahui :
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS
NIP : 19641023 198903 2 002
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Agustus 2009
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir pada tanggal 8 September 1987 di Depok, sebuah kota satelit yang berada di propinsi Jawa Barat. Penulis anak terakhir dari dua bersaudara pasangan I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan jenjang sekolah dasar di SD PSKD Kwitang VIII Depok, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Depok hingga lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 49 Jakarta Selatan dan berhasil lulus tanpa hambatan pada tahun 2005.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran”. Tebu merupakan komoditas yang sangat penting peranannya dalam kebutuhan pokok manusia dan merupakan satu-satunya bahan pemanis alami yang lazim digunakan manusia. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai respon penawaran tebu Indonesia dengan harapan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam meningkatkan produksi gula nasional dan mencapai swasembada gula nasional. Disamping itu skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada Dedi Budiman Hakim Ph.D, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis baik secara teknis maupun psikis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat dikerjakan dengan maksimal. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Dr. Sri Hartoyo sebagai penguji utama dan Dr. Lukytawati sebagai komisi pendidikan yang telah bersedia menguji hasil karya penulis. Semua kritikan dan saran Beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ade Holis atas kesediannya membantu penulis dalam hal perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta pada seminar hasil penelitian ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Akhirnya dengan bangga penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati serta kakak penulis Putu Damarathi. Kesabaran dan dorongan mereka sangat besar artinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.
Bogor, Agustus 2009
F
DEP
FAKULT
INS
I MA
PARTEM
TAS EKON
STITUT P
OLEH ADE SANJ
H14053726
MEN ILMU
NOMI DA
PERTANI
2009
JAYA 6
U EKON
AN MAN
IAN BOG
OMI
NAJEMEN
GOR
RINGKASAN
I MADE SANJAYA, Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran (dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM).
Adanya isu kelangkaan minyak bumi akhir-akhir ini menyebabkan perlunya kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan energi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2006 yang kemudian direspon oleh Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan menetapkan sasaran bahwa pada tahun 2025 penggunaan energi berbahan dasar minyak bumi ditargetkan kurang dari 20 persen dari konsumsi energi total, penggunaan gas bumi sebesar 30 persen, lebih dari 33 persen berbahan baku batu bara, lebih dari 5 persen untuk masing-masing panas bumi, energi nabati (tanaman) dan energi alternatif lainnya.
Salah satu tanaman yang berpotensi diolah menjadi bahan baku penghasil energi adalah tanaman tebu. Penggunaan tanaman tebu sebagai bahan baku penghasil energi diduga akan menyebabkan trade off output tanaman tebu itu sendiri. Jika hal tersebut benar, maka pergeseran fungsi output akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran dari tanaman tebu. Untuk itu perlu dilakukan analisis respon penawaran tebu Indonesia.
Ketersedian tebu di Indonesia sebagai penghasil gula masih belum mencukupi, hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan total gula nasional yang lebih besar daripada jumlah produksi gula di dalam negeri. Akibatnya pengadaan impor gula sampai dengan tahun 2008 masih terus dilakukan. Ironisnya, lahan yang tersedia di Indonesia merupakan lahan yang sangat potensial ditanami tebu. Rendahnya produksi tebu nasional selain dikarenakan jumlah luas areal tanam yang tergolong sempit, juga disebabkan oleh produktivitas tanaman tebu yang masih rendah.
Untuk meningkatkan produksi tebu domestik diperlukan pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, baik dari segi harga output, harga input produksi, dan variabel-variabel non-market yang secara relevan mempengaruhi pergeseran produksi tanaman tebu.
Pada penelitian ini pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penawaran tebu di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data
didasarkan karena produk yang diteliti adalah produk pertanian yang mempunyai karakteristik beda kala.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif didasarkan untuk menjelaskan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan produksi tanaman tebu di Indonesia. Metode analisis kuantitatif didasarkan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini mempengaruhi variabel tak bebas yang dikaji.
Dari hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan produksi tebu Indonesia jauh lebih responsif jika dilakukan dengan pendekatan intensifikasi, artinya peningkatan penawaran dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan harga faktor-faktor input produksi produk pertanian seperti kebijakan harga pupuk, harga pestisida, dan tingkat upah buruh.
PROYEKSI PENAWARAN TEBU INDONESIA TAHUN 2025 : ANALISIS RESPON PENAWARAN
OLEH I MADE SANJAYA
H14053726
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Skripsi : Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran
Nama : I Made Sanjaya
NIM : H14053726
Menyetujui :
Dosen Pembimbing,
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M. Ec
NIP : 19641022 198903 1 003
Mengetahui :
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS
NIP : 19641023 198903 2 002
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Agustus 2009
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir pada tanggal 8 September 1987 di Depok, sebuah kota satelit yang berada di propinsi Jawa Barat. Penulis anak terakhir dari dua bersaudara pasangan I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan jenjang sekolah dasar di SD PSKD Kwitang VIII Depok, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Depok hingga lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 49 Jakarta Selatan dan berhasil lulus tanpa hambatan pada tahun 2005.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran”. Tebu merupakan komoditas yang sangat penting peranannya dalam kebutuhan pokok manusia dan merupakan satu-satunya bahan pemanis alami yang lazim digunakan manusia. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai respon penawaran tebu Indonesia dengan harapan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam meningkatkan produksi gula nasional dan mencapai swasembada gula nasional. Disamping itu skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada Dedi Budiman Hakim Ph.D, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis baik secara teknis maupun psikis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat dikerjakan dengan maksimal. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Dr. Sri Hartoyo sebagai penguji utama dan Dr. Lukytawati sebagai komisi pendidikan yang telah bersedia menguji hasil karya penulis. Semua kritikan dan saran Beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ade Holis atas kesediannya membantu penulis dalam hal perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta pada seminar hasil penelitian ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Akhirnya dengan bangga penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati serta kakak penulis Putu Damarathi. Kesabaran dan dorongan mereka sangat besar artinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.
Bogor, Agustus 2009
DAFTAR ISI
2.2. Tinjauan Kebijakan Pergulaan Nasional ... 14
2.3. Teori Penawaran ... 15
2.4. Teori Respon Penawaran ... 16
2.4.1. Respon Penawaran dengan Pendekatan Respon Areal dan Produktivitas ... 17
2.5. Respon Beda Kala pada Komoditi Pertanian ... 20
2.5.1. Model Distribusi Beda Kala ... 22
2.6. Model Penyesuaian Nerlovian ... 24
2.7. Model Proyeksi Penawaran Tanaman Perkebunan ... 26
2.8. Kerangka Pemikiran Konseptual ... 28
2.9. Hipotesis Penelitian ... 30
2.10. Penelitian Terdahulu ... 33
3.1. Jenis dan Sumber Data ... 37
3.4.1. Persamaan Model Respon Areal dan Produktivitas
untuk Data Empiris ... 43 3.5. Respon Penawaran ... 44 3.6. Evaluasi Model ... 45 3.6.1. Kriteria Statistik (Uji Derajat Pertama) ... 46 3.6.2. Kriteria Ekonomi (Uji Derajat Kedua) ... 48 3.6.3. Kriteria Ekonomi (Apriori) ... 52 3.7. Model Proyeksi Penawaran Tebu Tahun 2025 ... 53 3.8. Pengukuran Peubah ... 53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 56 4.1. Hasil dan Estimasi Persamaan Respon Areal Tebu Indonesia . 56
4.1.1. Uji Ekonometrika ... 56 4.1.2. Uji Statistik dan Dasar Teoritis Respon Areal ... 58 4.2. Hasil dan Estimasi Persamaan Respon Produktivitas Tebu
Indonesia ... 60 4.2.1. Uji Ekonometrika ... 60 4.2.2. Uji Statistik dan Dasar Teoritis Respon Produktivitas . 62 4.3. Respon Penawaran Tebu Indonesia ... 64 4.4. Proyeksi Kebutuhan Tebu Indonesia Tahun 2025 ... 66 4.5. Proyeksi Penawaran Tanaman Tebu Indonesia Tahun 2025 ... 67 4.6. Implikasi Hasil Analisis Respon Penawaran ... 68
V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 70 5.1. Kesimpulan ... 70 5.2. Saran ... 71
DAFTAR PUSTAKA ... 73
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1.1. Neraca Gula Indonesia Tahun 2003-2009* (dalam ribu ton) ... 2 1.2. Kontribusi Luas Areal, Produksi, Produktivitas, Tebu dan
Hablur Indonesia ... 4 2.1. Biaya dan Pendapatan Usaha Tani Tebu di Lahan Sawah
dan Tegalan ... 13 2.2. Ukuran Elastisitas ... 18
2.3. Peubah-peubah Bebas pada Model Respon Areal dan Respon
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman 1. Hasil Regresi Model Persamaan Respon Areal
Tebu Indonesia ... 76 2. Hasil Uji Autokorelasi Model Persamaan Respon Areal Tebu
Indonesia ... 76 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Respon Areal Tebu
Indonesia ... 76 4. Hasil Uji Normalitas Model Persamaan Respon Areal Tebu
Indonesia. ... 77 5. Hasil Uji Multikolinieritas Model Persamaan Respon Areal
Tebu Indonesia ... 78 6. Hasil Regresi Model Persamaan Respon Produktivitas Tebu
Indonesia ... 79 7. Hasil Uji Autokorelasi Model Persamaan Respon
Produktivitas Tebu Indonesia ... 79 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan Respon
Produktivitas Tebu Indonesia ... 79 9. Hasil Uji Normalitas Model Persamaan Respon Produktivitas
Tebu Indonesia. ... 80 10. Hasil Uji Multikolinieritas Model Persamaan Respon
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Adanya isu kelangkaan minyak bumi akhir-akhir ini menyebabkan perlu
dilakukannya penggunaan bahan baku alternatif sebagai penghasil energi,
sehingga pada tahun 2006 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan
terkait dengan pemenuhan kebutuhan energi pada tahun-tahun mendatang.
Munculnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 terkait dengan pemenuhan
energi nasional direspon oleh Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral yang
menargetkan kurang dari 20 persen konsumsi energi total dipenuhi oleh minyak
bumi, 30 persen bersumber dari gas alam, lebih dari 33 persen bahan baku batu
bara, dan lebih dari 5 persen masing-masing bersumber dari panas bumi, energi
nabati (tanaman), dan energi alternatif lainnya.
Beberapa jenis tanaman atau komoditas yang digunakan untuk
menghasilkan energi alami di antaranya adalah tebu, jagung, ubi jalar, ubi kayu,
dan sagu. Pemenuhan kebutuhan energi bersumber dari tanaman diduga akan
menyebabkan produksi komoditas-komoditas pertanian berubah yang disebabkan
karena bahan baku alternatif yang digunakan dalam menghasilkan energi sama
dengan bahan baku yang digunakan dalam produksi pangan di Indonesia. Hal ini
menyebabkan terbaginya penggunaan output dari komoditas pertanian strategis
tersebut. Salah satu komoditas yang dianggap rawan terhadap krisis pangan adalah
Gula merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai
peran penting sebagai satu-satunya pemanis alami, baik untuk konsumsi rumah
tangga maupun industri. Dalam hal ini, peranan gula sebagai bahan pemanis
utama belum tergantikan oleh bahan pemanis lainnya seperti gula merah, madu,
sakarin, maupun bahan pemanis kimia.
Tabel 1.1. Neraca Gula Indonesia Tahun 2003-2009* (dalam ribu ton)
Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Stok Awal GKP 391,7 519,0 397,2 617,6 446,1 888,5 947,9
Stok Awal GKR 50,0 50,0 50,0 60,9 86,1 158,7 199,6
Stok Mamin 25,0 25,0 25,0 30,0 35,0 35,0 50,0
Jumlah Pengadaan 466,7 594,0 472,2 708,5 567,2 1.082,2 1.197,5
Ekspor Tebu 1.631,9 2.051,6 2.241,7 2.307,0 2.448,1 2.668,4 2.907,6
Ekspor Raw Sugar 157,0 11,3 141,9 0 149,8 35,5 129,7
Operasi Pasar - 0 - 25,0 14,4 0 0
Produksi GKR 329,5 440,0 759,7 1.100,2 1.441,5 1.256,4 1.536,4
Jumlah Produksi 2.118,5 2.502,9 3.143,4 3.432,3 4.053,9 3.960,4 4.573,7
Impor Gula Putih 647,9 256,6 453,2 216,5 448,7 49,0 0
Impor Mamin 516,4 464,2 629,6 462,7 715,9 453,7 379,0
Jumlah Impor 1.164,3 720,8 1.082,8 679,2 1.164,6 502,8 379,0
Total GKP 2.828,6 2.838,5 3.234,1 3.166,1 3.507,2 3.641,5 3.985,2
Total GKR 920,9 979,2 1.464,3 1.653,9 2.278,5 1.903,9 2.165,0
Total Gula Kristal 3.749,5 3.817,7 4.698,4 4.820,0 5.785,7 5.545,4 6.150,2
Konsumsi GKP 2.309,6 2.441,3 2.616,5 2.720,0 2.618,7 2.693,6 0
Konsumsi GKR 845,9 904,2 1.373,4 1.532,8 2.084,7 1.654,3 0
Total Konsumsi 3.155,5 3.345,5 3.989,9 4.252,8 4.703,4 4.347,9 0
Sumber : Dewan Gula Indonesia, 2009.
Catatan : Gula Kristal Putih (GKP), Gula Kristal Rafinasi (GKR), Makanan dan Minuman (Mamin), dan *) Data Sementara
Konsumsi gula di Indonesia yang besar salah satunya dikarenakan oleh
banyaknya jumlah penduduk, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk
setiap tahunnya peningkatan permintaan gula nasional juga akan meningkat.
Ironisnya permintaan masyarakat ini tidak direspon oleh jumlah produksi
domestik gula nasional. Perbedaan pada jumlah produksi dan permintaan
yang ada tahun sebelumnya. Untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat
maka pemerintah melakukan pengadaan impor gula setiap tahun.
Pengadaan impor gula yang terjadi selama ini berdampak pada
pengurangan devisa negara. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara
meningkatkan produksi gula domestik dan untuk meningkatkan produksi gula
domestik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi tebu nasional.
Tebu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di Indonesia, akan
tetapi sampai saat ini produksi gula nasional masih belum cukup tersedia di
masyarakat luas. Dengan alasan tersebut, produksi tebu nasional seharusnya
menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengingat permintaan masyarakat
akan gula yang cukup tinggi.
Salah satu cara untuk meningkatkan produksi domestik gula pasir adalah
dengan menambah jumlah produksi tebu sebagai bahan baku gula, dan salah satu
cara untuk menambah jumlah produksi tebu di Indonesia adalah dengan
menambah jumlah luas areal tanaman sehingga akan didapatkan jumlah produksi
tebu yang lebih tinggi.
Peningkatan luas areal tebu yang terjadi di Indonesia beberapa tahun
kebelakang menyebabkan jumlah produksi tebu secara keseluruhan meningkat,
akan tetapi peningkatan produksi tebu tidak sebanding dengan peningkatan jumlah
penduduk setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Tabel
1.2. yang menunjukan bahwa jumlah permintaan total gula domestik jauh lebih
Tabel 1.2. Kontribusi Luas Areal, Produksi, Produktivitas, Tebu dan Hablur Indonesia
Tahun Luas Areal (000ha)
Jumlah Tebu Rendemen Jumlah Hablur Kontribusi Hablur
Sumber : Perusahaan-perusahaan Gula, diolah Sekretariat Dewan Gula Indonesia 2009. Catatan : * Data Taksasi Produksi
1.2. Perumusan Masalah
Penggunaan tanaman sebagai bahan baku energi alami akan berdampak
besar bagi produksi tanaman yang digunakan untuk pangan itu sendiri. Untuk
memperoleh bahan bakar alami yang terbarukan, akan memunculkan suatu
permasalahan serius, yaitu trade off penggunaan output. Di satu sisi, penggunaan
komoditas tersebut untuk menghasilkan output sebagai bahan pangan merupakan
kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, di sisi lain output komoditas
yang digunakan sebagai bahan baku energi alami merupakan kebutuhan strategis
yang harus terpenuhi karena keterbatasan bahan bakar minyak bumi.
Produksi bahan bakar alami dapat diperoleh dengan cara merubah
komposisi suatu komoditas tanaman menjadi struktur rantai karbon sehingga
menghasilkan komposisi sempurna yang serupa dengan rantai karbon yang
terjadi, tetapi seperti yang telah diutarakan sebelumnya, perolehan bahan bakar
dari komoditas pertanian mempunyai trade off yang cukup besar.
Penggunaan tanaman sebagai bahan baku energi menentukan jumlah
tanaman yang harus diproduksi. Pengolahan komoditas pertanian menjadi bahan
baku energi -asumsi luas areal dan produksi tetap (konstan)- akan menyebabkan
jumlah produksi output yang digunakan sebagai bahan pangan berkurang,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi berbahan baku tanaman perlu
dilakukan perhitungan kebutuhan dan jumlah penawaran tebu Indonesia.
Peningkatan permintaan gula yang tinggi harus diimbangi dengan
peningkatan produksinya. Berdasarkan Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. dapat dilihat
bahwa kebutuhan akan gula (konsumsi gula) tahun 2008 adalah sebesar 4.347.880
ton, artinya dengan asumsi di atas, untuk memenuhi kebutuhan dengan produksi
domestik dan menghindari pengadaan impor, maka Indonesia harus memproduksi
sebanyak jumlah yang sama dengan yang dikonsumsi. Akan tetapi jumlah
produksi pada tahun 2008 hanya sebesar 1.256.435 ton yang dihasilkan dari
13.990.206 ton tebu di lahan seluas 436.504,2 hektar sehingga pada tahun 2008
pengadaan impor masih dilakukan.
Pengadaan impor tersebut dapat dihindari dengan cara meningkatkan luas
lahan atau produktivitas tanaman tebu sehingga diperoleh jumlah tebu yang lebih
banyak. Akan tetapi, baik pertumbuhan luas areal maupun peningkatan
produktivitas tanaman tebu yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan masih
penelitian ini adalah bagaimana respon produksi tebu di Indonesia dengan
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :
1. Menganalisis respon penawaran komoditas tebu terhadap perubahan
variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Memproyeksikan kebutuhan dan jumlah penawaran tebu di Indonesia pada
tahun 2025.
1.4. Cakupan Penelitian
Penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada respon penawaran
komoditi tebu Indonesia yang penulis lakukan melalui pendekatan respon luas
areal dan respon produktivitas tebu terhadap adanya perubahan faktor-faktor
penentu seperti harga komoditi sendiri, harga komoditi alternatif, harga input
produksi, dan curah hujan. Data yang digunakan merupakan data time series dari
tahun 1969 sampai dengan 2006.
Pendekatan nilai proyeksi jumlah kebutuhan tebu tidak berdasarkan nilai
elastisitas permintaan jangka panjang tanaman tebu. Nilai proyeksi jumlah tebu
yang dibutuhkan pada tahun 2025 diperoleh berdasarkan nilai pertumbuhan
konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk dengan asumsi tidak adanya
gangguan atau shock sampai tahun 2025. Khusus untuk proyeksi jumlah
dilakukan secara bersama-sama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund.
Sedangkan untuk proyeksi jumlah penawaran pada tahun 2025 mendatang
digunakan nilai elasisitas jangka panjang penawaran tebu terhadap perubahan
harga yang diperoleh dari perhitungan nilai elastisitas areal dan produktivitas
tanaman tebu.
1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan pertimbangan kepada
pihak-pihak terkait dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di industri pergulaan
nasional, sehingga dapat memajukan industri pergulaan Indonesia guna mencapai
swasembada gula nasional. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur
untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi kepentingan
konsumen dan juga petani secara bersamaan. Dan yang terakhir, diharapkan
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Aspek Strategis Tanaman Tebu
Tebu berasal dari India yang tumbuh di tepi sungai Gangga (Sawit, 1998).
Sampai saat ini tanaman tebu sudah tersebar luas khususnya di daerah sekitar
garis khatulistiwa. Tanaman tebu sampai ke Indonesia dan dikenal di Indonesia
karena tanaman ini dibawa oleh bangsa Hindu.
Tebu (Saccharum officinarum) adalah tumbuhan bermarga
rumput-rumputan (Graminae) yang tumbuh dalam rumpun dan terdiri dari sejumlah
batang serta berumur 12 bulan di daerah tropika dan 24 bulan di daerah
subtropika, tergantung jenis dan tempat serta cara menanamnya. Klasifikasi botani
tanaman tebu berasal dari divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas
Monocotyledonae, keluarga Poaceae, genus Saccharum, dan nama spesies seperti
yang telah disebutkan diatas Saccharum officinarum.
2.1.1. Fase Pertumbuhan Tebu
Tumbuhan ini memiliki beberapa fase pertumbuhan dari sejak penanaman
sampai masak. Kebutuhan bahan pembangun tubuh tanaman tebu misalnya : air,
unsur hara makro dan mikro, O2, Co2, serta sinar matahari tidak sama pada setiap
fase pertumbuhan serta dipengaruhi oleh proses metabolisme dalam tanaman tebu.
Kegiatan dan kebutuhan tiap fase pertumbuhan tersebut dapat diuraikan sebagai
1. Fase Kecambah.
a. Pra kecambah, umur 0 - 9 hari.
Stek tebu mulai menyerap air dan oksigen untuk mengubah cadangan
makanan berupa gula menjadi asam amino untuk pembelahan sel. Mata tunas
menggembung, akar sel terbentuk.
b. Perkecambahan, umur 10 - 30 hari.
Mata tunas bertambah besar dan memanjang muncul di atas permukaan tanah.
Perakaran stek bertambah banyak dan panjang. Pada fase ini dibutuhkan air,
oksigen, dan fosfat yang diperlukan untuk pembelahan sel. Untuk menujang
kegiatan fase ini, pupuk TSP sebagai sumber fosfat sudah harus tersedia di dalam
tanah.
Guna memperoleh hasil tebu yang memadai, jumlah mata tumbuh pada fase
ini harus ada 45.000 per hektar. Fase perkecambahan ini dipengaruhi oleh letak
mata pada batang tebu, dan kualitas batang stek.
2. Fase Pertunasan.
a. Pertumbuhan tunas dan akar, umur 0 - 45 hari.
Kecambah tebu terbuka daunnya dan akar baru keluar dari pangkal tunas tebu.
Pada fase ini dibutuhkan air, oksigen, zat asam arang, fosfat, nitrogen, dan sinar
matahari untuk fotosintesis. Oleh karena itu, pada saat ini sudah harus tersedia
pupuk TSP dan Za sebagai unsur fospat (P) dan nitrogen (N) di dalam tanah.
Pupuk Za yang diberikan pada fase ini sebesar 50% dari dosis anjuran, karena
tanaman belum menyerap N terlalu banyak untuk keperluan pertumbuhan sel-sel
b. Pertunasan, umur 45 hari - 3 bulan.
Tunas-tunas muda (anakan) mulai keluar dan tebu tumbuh menjadi rumpun
yang terdiri dari beberapa tunas tanaman tebu. Pada fase ini dibutuhkan air, zat
asam arang, fosfat, kalium, nitrogen, dan sinar matahari penuh. Akan tetapi
pertumbuhan anakan juga tergantung dari jenis tebu. Ada jenis tebu yang cepat
beranak banyak dan ada yang secara serempak beranak banyak. Namun demikian
beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan tunas anakan adalah
pupuk, penurunan tanah, dan jarak tanam.
3. Fase Batang Memanjang (Pemanjangan, umur 3 - 9 bulan).
Pertunasan berhenti dan batang memanjang dengan pembentukan ruas tebu.
Pada fase ini kebutuhannya sudah penuh dan stabil. Tajuk daun tebu telah
menutupi ruang di antara larikan tanaman. Uraian pertumbuhan pada fase ini
adalah sebagai berikut :
a. Daun.
Pada pertumbuhan awal terbentuk daun-daun kecil. Daun-daun ini akan
tumbuh menjadi besar sampai tercapai ukuran maksimal yang akhirnya akan
menjadi kecil lagi.
b. Batang.
Pada titik tumbuh akan terbentuk sel baru karena pada tempat tersebut sel
mempunyai kemampuan untuk membagi diri, kemudian sel baru tersebut
berkembang menjadi lebih besar. Di bagian bawah ruas, sel masih melanjutkan
pembelahan sehingga pertumbuhan batang disebabkan oleh adanya pertumbuhan
hari, karena pada malam hari jaringan sel mengandung air terbanyak dan turgor
terbesar yang menyebabkan penguapan sedikit terjadi.
c. Akar.
Akar tebu terbagi atas :
‐ Akar bibit : cincin akar pada batang stek akan tumbuh lebih cepat daripada
tunas yang keluar pada mata stek. Akar ini mula-mula berfungsi
menyerap makanan untuk keperluan pertumbuhan tunas baru
selanjutnya akar ini akan mati dan fungsinya digantikan oleh akar
biasa.
‐ Akar biasa : tumbuh dari cincin tunas anakan. Pada fase pertumbuhan tunas
memanjang, terbentuk pula akar yang tumbuh di bagian yang
lebih atas akibat pemberian tanah sebagai tempat tumbuh.
4. Fase Kemasakan.
a. Pra masak, umur 9 - 12 bulan.
Pertumbuhan vegetatif menurun, pembentukan ruas baru pada daun makin
lambat. Pada fase ini air dan oksigen semakin kurang diserap oleh tanaman,
sedangkan unsur lainnya tetap dibutuhkan. Sejalan dengan penurunan
pertumbuhan vegetatif, dimana juga akan terjadi kematian beberapa tunas anakan
yang akhirnya akan didapatkan jumlah tunas atau batang sebanyak kurang lebih
90.000 tunas per hektar. Dalam fase ini juga terjadi penimbunan gula (sakarosa) di
b. Masak, umur 12 bulan.
Tanaman berhenti tumbuh, kadar air dalam batang tebu berkurang sedangkan
kadar gula naik, daun mulai mengering. Pada fase ini hanya dibutuhkan sedikit air
untuk menjaga keseimbangan akibat penguapan melalui daun. Akhirnya pada saat
tertentu, tanaman tebu akan mengalami kematian dimana kadar sakrosa menurun.
Oleh karena itu sebelum terjadi penurunan kadar gula, tebu harus ditebang karena
sudah masak.
c. Pasca masak, umur lebih dari 12 bulan.
Pada fase ini tanaman tebu sudah menunjukan gejala kematian dan daun
mengering dimulai dari yang tertua. Pengeringan daun pada batang tebu tersebut
berangsur-angsur menjalar ke batang yang lebih muda. Sampai akhirnya mencapai
daun yang masih menggulung.
2.1.2. Analisis Usaha Tani Tebu
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti (2007), Jenis lahan
yang diusahakan untuk tebu ada dua macam yaitu lahan sawah dan lahan tegalan.
Berdasarkan kedua jenis lahan tersebut analisis usaha tani dapat secara agregat
dihitung biaya dan pendapatannya. Petani yang mengusahakan tebu di lahan
sawah mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Biaya saprodi usahatani tebu di
lahan sawah rata-rata mencapai Rp 2 juta/ha (23,1% dari total biaya), sementara
untuk tegalan rata-rata mencapai Rp 1,3 juta/ha (24,4% dari total biaya).
Biaya saprodi meliputi pembelian bibit, pupuk, dan pestisida. Pengeluaran
tegalan, yaitu Rp 5,5 juta/ha (63,5% dari total biaya) dibandingkan Rp 3,2 juta/ha
(58,5% dari total biaya). Alokasi terbesar pada biaya saprodi untuk tegalan adalah
biaya pembelian pupuk urea. Petani menggunakan urea agar tanaman menjadi
subur, sehingga menambah berat tebu. Sementara untuk biaya tenaga kerja pada
lahan sawah yang memerlukan alokasi lebih besar daripada tegalan antara lain
untuk biaya irigasi. Petani umumnya mengairi tanaman tebu di lahan sawah
sedikitnya dua kali. Berdasarkan Tabel 2.1. alokasi biaya lain-lain pada lahan
tegalan sebesar 17,2% dari total biaya. Sebanyak 16,6% dari total biaya
merupakan proporsi biaya sewa lahan sementara pada lahan sawah biaya sewa
lahan sebesar 12,7% dari total biaya.
Tabel 2.1. Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan.
Uraian
B/C Ratio 1,794032 1,995422
Sumber : ekonomirakyat.org, 2007.
Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tebu lebih banyak
diusahakan petani penyewa lahan. Sementara dengan melihat perbandingan
alokasi biaya, tersirat bahwa biaya sewa lahan sawah lebih mahal daripada
tegalan, sehingga lebih sedikit proporsi petani yang menyewa sawah daripada
dibandingkan di lahan sawah, yaitu sebesar 1,794032. Artinya usahatani tebu di
tegalan lebih menguntungkan dibandingkan di lahan sawah.
Gaol dalam Halsafah (2002) meneliti tentang kekompetitifan usahatani
tebu dengan usaha alternatif. Tanaman alternatif di lahan sawah yang digunakan
sebagai kompetitor adalah padi, jagung, dan kacang tanah. Sedangkan di lahan
kering yaitu padi, jagung, lombok, sawi, dan ubi kayu. Adapun jenis tebunya
mencakup tebu tanam dan tebu kepras.
Di lahan sawah, pendapatan usahatani dari tanaman alternatif bukan saja
lebih unggul dalam nilai absolut pendapatannya dibandingkan dengan usaha tani
tebu, tetapi juga dalam efisiensi biaya (net B/C) sehingga peluang tanaman
alternatif untuk ditanam di lahan sawah lebih besar daripada tanaman tebu. Hal
tersebut disebabkan berkembangnya teknologi tumpangsari serta semakin pastinya
dan meningkatnya harga jual hasil panen tanaman alternatif. Untuk tebu di lahan
kering, pendapatan usahatani alternatif lebih kecil daripada pendapatan usahatani
tanaman tebu. Sesungguhnya hal ini berlaku secara umum karena produktivitas
dan intensitas tanaman dari tanaman alternatif cukup rendah di lahan kering.
2.2. Tinjauan Kebijakan Pergulaan Nasional
Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka
menyejahterakan petani tebu dan memperkuat daya saing industri gula. Salah satu
kebijakan yang sangat mendasar dan mempunyai dampak terhadap industri gula
nasional adalah diberlakukannya program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)
lahan menjadi sistem Tebu Rakyat Intensifikasi, menjadikan petani sebagai tuan
diatas lahannya sendiri, dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu dengan
dukungan pendanaan, bimbingan teknis dan pengaturan distribusi dan
perdagangan gula.
2.3. Teori Penawaran
Kurva penawaran adalah penyajian penawaran dalam bentuk grafik skedul
penawaran (supply schedule) yang menggambarkan jumlah yang akan dijual para
produsen pada harga-harga alternatif komoditi tersebut. Kurva penawaran
menunjukkan hubungan antara jumlah atau kuantitas yang ditawarkan dan harga,
jika faktor lainnya tetap sama. Kemiringan positif menunjukkan bahwa kuantitas
atau jumlah yang ditawarkan bervariasi dalam arah yang sama dengan harga.
Gambar 2.1 menunjukan kurva penawaran yang menggambarkan hubungan antara
kuantitas per periode dengan harga. Pergeseran kurva penawaran terjadi ketika
faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan suatu perusahaan
selain harga komoditi itu sendiri berubah, misalnya harga input, perubahan
teknologi, harga komoditi lain, dan tujuan perusahaan (Lipsey et al, 1995).
Sumber : Lipsey et al, 1995.
Sd0
Jumlah
Harga Sd
1
Menurut Lipsey et al. (1995), jumlah yang akan dijual oleh perusahaan
disebut kuantitas yang ditawarkan untuk komoditi itu. Kuantitas atau jumlah yang
ditawarkan merupakan arus, yaitu banyaknya per satuan waktu. Satu hipotesis
ekonomi yang mendasar adalah bahwa untuk kebanyakan komoditi, harga
komoditi dan kuantitas atau jumlah yang akan ditawarkan berhubungan secara
positif, dengan faktor yang lain tetap sama. Dengan kata lain, makin tinggi harga
suatu komoditi, makin besar jumlah komoditi yang akan ditawarkan, semakin
rendah harga, semakin kecil jumlah komoditi yang ditawarkan.
2.4. Teori Respon Penawaran
Tebu termasuk golongan tanaman tahunan (perennial crop), dengan
karakteristik adanya tenggang waktu yang cukup panjang antara saat tanam
dengan pertama kali dipanen, yaitu sekitar 1-2 tahun. Oleh karena itu, berbagai
hubungan yang dirancang untuk menjelaskan perilaku tersebut, idealnya harus
mempertimbangkan tenggang waktu antara saat tanam dan saat panen pertama
kali, termasuk penanaman dan pergantian tanaman. Kendala yang dihadapi adalah
tidak tersedianya data yang memadai, terutama untuk penggantian tanaman.
Karenanya, sering dilakukan pendekatan yang lebih sederhana, namun cukup
representatif.
Respon produksi (Yt*) sebuah komoditi diasumsikan merupakan fungsi
dari harga komoditi itu sendiri, harga komoditi lain, harga input, dan faktor tetap.
Yt* = f (Pt, Pit, Wt, Zt,) (2.1)
dimana :
Yt* = tingkat produksi yang diharapkan petani pada waktu ke-t,
Pt = harga komoditi itu sendiri,
Pit = harga komoditi lain,
Wt = harga input produksi, dan
Zt = faktor tetap.
Kurva penawaran tradisional menggambarkan hubungan antara harga dan
kuantitas dengan asumsi cateris paribus atau menganggap semua faktor lain
konstan, sedangkan respon penawaran menggambarkan respon output terhadap
perubahan harga dengan tidak menahan faktor lain konstan. Di dalam ilmu
ekonomi respon penawaran berarti variasi dari output pertanian dan luas areal
dalam kaitannya dengan perubahan harga (Ghatak dan Ingersent, 1984).
2.4.1. Respon Penawaran dengan Pendekatan Respon Areal dan Produktivitas
Secara umum, hal-hal prinsipil yang dapat menyebabkan perubahan
penawaran (pergeseran kurva penawaran) adalah perubahan harga input,
perubahan harga komoditas alternatif, perubahan teknologi yang berpengaruh
terhadap biaya produksi atau efisiensinya, perubahan pada harga komoditas yang
diproduksi secara bersamaan (joint product), dan kebijakan pemerintah (Tomek
dan Robinson, 1987). Adapun pendugaan respon penawaran sederhana dapat
perkalian antara luas areal tanam dengan produktivitasnya (Ghatak dan Ingersent,
1984). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :
Q A · Y (2.2)
dimana :
Q = jumlah produksi,
A = luas areal, dan
Y = produktivitas
Dengan demikian, perubahan luas areal dan produktivitas dapat
mempengaruhi produksi dari petani tebu sehingga dapat mempengaruhi besarnya
jumlah penawaran, sedangkan luas areal dan produktivitas sendiri dipengaruhi
oleh berbagai hal.
Tabel 2.2. Ukuran Elastisitas
Istilah Ukuran
numerik Keterangan
Inelastis
sempurna 0 Jumlah yang ditawarkan tidak berubah
Inelastis 0 < e <1
Jumlah yang ditawarkan berubah dengan persentase lebih kecil dari perubahan faktor yang mempengaruhinya
Elastisitas
unit 1
Jumlah yang ditawarkan berubah dengan persentase sama dengan perubahan faktor yang mempengaruhinya
Elastis 1 < e < ~
Jumlah yang ditawarkan berubah dengan persentase lebih besar dari perubahan faktor yang mempengaruhinya
Elastis
sempurna ~
Pada kondisi perubahan faktor tertentu, jumlah yang ditawarkan sesuai dengan kapasitas produsen dalam memproduksi
Sumber : Lipsey et al, 1995.
Konsep respon penawaran tercermin dalam elastisitas penawaran.
terhadap peubah-peubah yang mempengaruhinya dengan nilai antara nol sampai
tak terhingga (Tabel 2.2).
Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar respon penawaran tebu
terhadap harga, hal tersebut didapatkan dengan mengasumsikan bahwa luas areal
dan produktivitas memiliki respon terhadap perubahan produksi sehingga apabila
persamaan (2.2) dideferensialkan total terhadap harga (P) akan dihasilkan :
Y A A (2.3)
Karena terdapat konsep mengenai unsur-unsur yang secara umum
mempengaruhi luas areal dan produktivitas yaitu A A P dan Y P, A
dimana P adalah harga maka harus dideferensialkan secara parsial sehingga
didapatkan :
dA δδA dP (2.4)
dY δδ dP δδA dA (2.5)
subsitusi persamaan (2.4) dan (2.5) ke persamaan (2.3).
Y δδA A δδ δδA· A (2.6)
Kalikan persamaan (2.6) dengan .
Y δδA A δδ δδA· A (2.7)
Karena Q A · Y sehingga
δδA A δδ δδA· A (2.8)
Kemudian persamaan (2.8) dikali dengan A
A maka didapatkan:
Jika dinyatakan dalam elastisitas maka :
E(Q,P) E(Y,P) E(A,P) E(Y,A) (2.10)
dimana :
E(Q,P) = elastisitas penawaran tebu terhadap harga,
E(A,P) = elastisitas luas areal terhadap harga,
E(Y,P) = elastisitas produktivitas tebu terhadap harga, dan
E(Y,A) = elastisitas produktivitas tebu terhadap luas areal,
Dalam penelitian ini elastisitas yang digunakan adalah terhadap harga
output atau harga sendiri. Adapun nilai elastisitas yang diperoleh dari model
merupakan elastisitas jangka pendek dengan asumsi tidak ada perubahan output
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti musim (musim hujan dan
musim kemarau) dan dengan asumsi tidak adanya gangguan hama penyakit dalam
proses produksi. Dari model yang diperoleh dengan menggunakan data deret
waktu (time series), nilai elastisitas jangka panjang dapat diduga dari nilai
elastisitas jangka pendeknya (Koutsoyiannis, 1977). Secara teoritis elastisitas
jangka panjang akan lebih besar atau lebih elastis jika dibandingkan dengan
elastisitas jangka pendeknya.
2.5. Respon Beda Kala Pada Komoditi Pertanian
Salah satu karakteristik utama produk pertanian adalah adanya tenggang
waktu antara menanam dengan memanen yang biasa disebut dengan istilah
gestation period atau beda kala (lag). Hasil yang diperoleh petani adalah
masa lalu. Apabila terjadi peningkatan harga output suatu komoditas pertanian
pada saat tertentu, maka peningkatan itu tidak akan segera diikuti oleh
peningkatan luas areal dan atau produktivitas karena keputusan alokasi
sumberdaya telah ditetapkan petani pada saat sebelumnya. Respon petani terjadi
setelah beda kala sebagai dampak perubahan harga output, input, dan kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan komoditi pertanian.
Tomek dan Robinson (1989), sumber daya yang diperuntukan bagi
pertanian cenderung tetap digunakan terutama ketika kesempatan alternatif untuk
pekerjaan terbatas, sehingga dalam jangka pendek elastisitas harga sangatlah tidak
elastis (inelastis), kondisi tersebut dikatakan sebagai kekakuan asset (asset fixity)
sedangkan menurut Nurdiana (2001), petani tidak memberikan respon pada tahun
bersamaan melainkan lebih respon terhadap harga yang diharapkan sehingga
mengakibatkan banyak dugaan elastisitas respon luas areal terhadap harga
menghasilkan nilai yang sangat rendah Gujarati (1991), disebutkan beberapa
alasan utama yang mendasari terjadinya hal tersebut, yaitu :
Alasan Psikologis. Disebabkan oleh adanya kekuatan kebiasaan atau kelembaman. Para petani biasanya enggan untuk melakukan perubahan-perubahan
karena pada umumnya terpaku pada tradisi atau kebiasaan lama.
Alasan Teknis. Proses produksi komoditas pertanian membutuhkan waktu antara saat menanam dan memanen sehingga produksi komoditas pertanian sangat
tergantung pada peubah-peubah beda kala. Demikian pula introduksi teknis
petani mahir dalam menggunakan teknik produksi baru sebelum pada akhirnya
dapat meningkatkan nilai produksi dan penawarannya.
Alasan Kelembagaan. Perubahan tidak dapat terjadi begitu saja karena ada aturan atau kelembagaan yang mengikat seperti adanya perjanjian kontrak waktu
produksi dan aturan-aturan yang bersifat kelembagaan lainnya.
2.5.1. Model Distribusi Beda Kala
Model bersebaran beda kala (distributed lag models) adalah model yang
memiliki minimal satu peubah bebas berupa peubah nilai beda kala. Menurut
Ramanathan (1998), berdasarkan jenis peubah beda kala maka model tersebut
dibagi menjadi dua yaitu :
1. Peubah bebas beda kala (lagged independent variables/exogenous lagged
variables) yang memiliki bentuk umum :
Y a b X b X b X (2.11)
2. Peubah tak bebas beda kala (lagged dependent variables/endogenous lagged
variables)
Y a b Y b Y b Y (2.12)
dimana :
Y = peubah tak bebas,
X = peubah bebas,
t = waktu ke t, dan
Estimasi atau pendugaan distribusi beda kala dapat dilakukan dalam tiga
kelompok pendekatan (Gujarati, 1991).
1. Metode Pendugaan Khusus
Pendekatan dengan menggunakan metode pendugaan khusus ini
menyarankan dengan mula-mula meregresi Yt atas Xt, kemudian meregresi Yt atas
Xt dan Xt-1, kemudian meregresi Yt atas Xt, Xt-1, dan Xt-2, dan seterusnya. Prosedur
kegiatan ini berhenti ketika koefisien regresi dari peubah beda kala mulai menjadi
tidak signifikan secara spesifik dan atau koefisien dari setidak-tidaknya satu
peubah berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya. Adapun kelemahan
dari pendekatan ini adalah tidak adanya petunjuk yang pasti mengenai jumlah
maksimum peubah beda kala yang dapat dimasukkan ke dalam model,
ketersediaan data, dan jika terlalu banyak peubah beda kala sebagai peubah bebas
maka derajat bebasnya menjadi kecil serta kecenderungan timbulnya masalah
kolinieritas ganda menjadi tinggi.
2. Metode Pembatasan Secara Apriori
Metode ini mengasumsikan suatu bentuk umum dari bentuk sebaran beda
kala dan menduga parameter yang menerangkan sebarannya dengan pasti.
Model-modelnya antara lain adalah yang dikembangkan oleh Koyck, Friedman, dan
Cagan (Partial Adjustment Model).
Dalam pendugaan metode kuadrat terkecil (least square estimates) secara
langsung, kedua model diatas memiliki kelemahan, yaitu galatnya memiliki
Dengan demikian untuk selanjutnya dipilih model ketiga yaitu model penyesuaian
Nerlovian.
2.6. Model Penyesuaian Nerlovian
Model penyesuaian parsial yang dikembangkan oleh Marc Nerlove
merupakan model yang banyak digunakan dalam studi-studi respon penawaran
dengan berbagai perbaikan yang terus dilakukan. Model Nerlovian
menghipotesiskan reaksi petani atas dasar harga yang diinginkan dan penyesuaian
parsial areal atau produktivitas (Askari dan Cummings, 1977).
Dalam Koutsoyiannis (1977) dijelaskan bahwa model ini terdiri dari
peubah tak bebas pada satu tingkat yang diinginkan pada periode ke-t (Yt*) dan
tergantung pada peubah-peubah bebas X periode ke-t (Xt). Dalam penelitian ini
dimisalkan Yt* adalah luas lahan dan produktivitas tebu yang diinginkan dan
dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas (Xt), maka persamaan menjadi :
Y a a X (2.13)
Luas lahan dan produktivitas yang diharapkan tidak dapat diamati secara langsung
sehingga untuk mengatasinya didalilkan suatu hipotesis yang merupakan hipotesis
penyesuaian parsial.
Y Y d Y Y (2.14)
dengan d
dimana :
Y Y = perubahan luas lahan atau produktivitas yang terjadi,
Y Y = perubahan luas lahan atau produktivitas yang diinginkan, dan
Jika d maka tidak ada perubahan yang terjadi
Jika d = 1 maka perubahan yang diinginkan sama dengan
perubahan yang terjadi.
Persamaan (2.14) dapat diartikan bahwa dengan adanya gestation periode
di bidang pertanian, maka perubahan luas lahan atau produktivitas yang nyata
terjadi pada suatu periode tertentu hanyalah proporsi dari perubahan yang
diinginkan. Proporsi ini disebut koefisien penyesuaian (adjustment coefficient).
Selanjutnya persamaan (2.13) disubsitusikan ke dalam persamaan (2.14) :
Y Y d a a X Y (2.15)
Y da da X d Y (2.16)
atau
Y b b X b Y (2.17)
dimana :
b da
b da
b d
Model persamaan pada persamaan (2.16) atau persamaan (2.17) inilah
yang disebut dengan model penyesuaian parsial Nerlovian. Model tersebut
menunjukan bahwa besarnya nilai peubah pada suatu periode produksi Y
sebagian dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri X dan cadangan yang
tersedia diawal periode tersebut atau cadangan hasil periode sebelumnya Y .
Dalam model ini galat tidak mengalami serial korelasi dan hal ini dapat
Bila asumsi ini benar maka metode kuadrat terkecil (OLS) dapat digunakan untuk
menduga model. Selain itu koefisien d mempunyai makna ekonomi yang
jelas karena telah mengandung koefisien penyesuaian parsial d . Sehingga model
ini cocok untuk studi respon penawaran produk-produk pertanian yang
mempunyai sifat kekakuan, kendala kelembagaan, dan kelembaman.
2.7. Model Proyeksi Penawaran Tanaman Perkebunan
Dalam memproyeksikan jumlah penawaran tanaman perkebunan dapat
dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :
1. Pendekatan Langsung.
Proyeksi jumlah penawaran dengan pendekatan langsung dilakukan melalui
nilai elastisitas jangka panjang yang didapatkan dengan menggunakan bentuk
sederhana (reduced form) fungsi penawaran komoditas perkebunan sebagai
berikut :
(2.18)
dimana :
Qst = produksi komoditas tahun t,
Pt-1 = harga riil komoditas tahun sebelumnya,
Qst-1 = produksi komoditas tahun sebelumnya, dan
= parameter elastisitas jangka pendek komoditas terhadap harga sendiri.
Dari hasil estimasi fungsi penawaran (2.18), elastisitas jangka panjang
penawaran terhadap harga sendiri (ELR) dihitung dengan persamaan berikut :
Bentuk umum persamaan untuk proyeksi penawaran komoditas
perkebunan dengan pendekatan langsung adalah seperti pada persamaan berikut :
(2.20)
dimana :
= proyeksi produksi/penawaran tahun t setelah tahun dasar,
= produksi/penawaran komoditas tahun dasar, dan
= laju pertumbuhan harga riil komoditas per tahun.
2. Pendekatan Tidak Langsung.
Proyeksi penawaran menggunakan pendekatan tidak langsung dilakukan
melalui proyeksi areal dan proyeksi produktivitas dengan menggunakan elastisitas
terhadap harga-harga yang diperoleh dari estimasi fungsi areal dan fungsi
produktivitas, serta pertumbuhan dari masing-masing variabel harga. Proyeksi
areal dan produktivitas dirumuskan pada persamaan (2.21) untuk areal tanam dan
persamaan (2.22) untuk produktivitas. Sebagai tahun dasar adalah tahun 2006.
∑ (2.21)
dan
∑ (2.22)
Selanjutnya proyeksi produksi pada tahun ke-t adalah :
(2.23)
dimana :
= proyeksi areal komoditas i pada tahun t,
= areal tanam komoditas i tahun dasar,
= elastisitas areal tanam terhadap harga komoditi alternatif ke j,
= pertumbuhan harga sendiri per tahun (desimal),
= pertumbuhan harga komoditas alternatif per tahun (desimal),
= proyeksi produktivitas komoditas i pada tahun t,
= produktivitas komoditas i tahun dasar,
= elastisitas produktivitas terhadap harga sendiri,
= elastisitas produktivitas terhadap harga komoditi alternatif ke j,
= pertumbuhan harga input per tahun (desimal), dan
= proyeksi produksi/penawaran komoditas i tahun t setelah tahun dasar.
2.8. Kerangka Pemikiran Konseptual
Secara umum, untuk menduga respon penawaran tebu di Indonesia dapat
didekati dengan menggunakan pendekatan perubahan produksi. Perubahan
produksi tanaman tebu dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan bahwa
produksi adalah hasil perkalian antara luas areal dan produktivitas (Persamaan
2.2). Untuk mengetahui besarnya perubahan produksi tebu, terlebih dahulu
dilakukan identifikasi peubah-peubah eksogen dari luas areal dan produktivitas
tanaman tebu. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa komoditas
pertanian memiliki respon beda kala (lag). Untuk itu, dalam model respon luas
areal maupun model respon produktivitas menggunakan peubah beda kala dari
masing-masing peubah endogennya.
Berdasarkan uraian di atas, maka akan dianalisis respon penawaran
menggunakan model penyesuaian Nerlovian. Model Nerlovian terdiri dari dua
model yaitu model respon luas areal dan model respon produktivitas. Setelah
kedua model terbentuk, dapat diketahui besarnya respon areal tanaman tebu dan
produktivitasnya terhadap harga gula baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Penjumlahan nilai respon luas areal dan respon produktivitas tanaman
tebu digunakan sebagai nilai respon penawaran tanaman tebu di Indonesia.
Dengan demikian, perubahan produksi dari para petani tebu dipengaruhi
oleh perubahan dari luas areal dan perubahan produktivitas yang pada akhirnya
mempengaruhi besarnya penawaran tebu, sedangkan luas areal dan produktivitas
sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
2.9. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peubah-peubah yang
diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan luas areal tanaman tebu adalah luas
areal tahun sebelumnya, harga gula tahun lalu, harga komoditas alternatif tahun
lalu, faktor cuaca (curah hujan tahun lalu). Secara matematis dapat dituliskan
sebagai berikut :
A Hrglx , Hrgbx , Hrjgx , Hrktx , Ch , A ) (2.24)
Pada produktivitas tanaman tebu, pendugaan peubah-peubah bebas yang
mempengaruhi meliputi produktivitas tahun lalu, harga gula saat ini, harga
input-input produksi, dan faktor cuaca (curah hujan tahun berjalan). Secara matematis
fungsi persamaan produktivitas tebu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan :
Y Hrgl , Hrur , Hrpes , Hrub , Ch , Y (2.25)
dimana :
A = luas areal tanaman tebu,
Y = produktivitas tanaman tebu,
Hrglx = harga riil gula domestik,
Hrgbx = harga riil gabah,
Hrjgx = harga riil jagung,
Hrktx = harga riil kacang tanah,
Hrur = harga riil pupuk urea,
Hrpes = harga riil pestisida,
Hrub = tingkat upah tenaga kerja, dan
Pengaruh luas areal tahun lalu terhadap luas areal saat ini adalah pada
hubungannya terkait kejadian yang terjadi saat selang waktu. Luas areal saat ini
dapat saja merupakan keberlanjutan, pengurangan, maupun peningkatan luas areal
tahun sebelumnya. Komoditas alternatif dapat bersifat sebagai pesaing atau
pelengkap. Semakin tinggi harga komoditas yang berkompetitif maka akan
semakin sempit luas areal tanam komoditas yang diteliti. Dalam penelitian ini,
digunakan peubah bebas berupa harga komoditi alternatif yang paling umum
diusahakan, baik di lahan sawah maupun di lahan kering, yaitu padi, jagung,
kedelai, dan kacang tanah.
Tanaman-tanaman alternatif tersebut diduga sebagai tanaman subsitusi
karena kedudukannya sebagai bahan pangan. Di sisi lain, dapat diduga sebagai
tanaman komplementer karena waktu tanam yang relatif singkat (± 3 bulan)
terutama untuk tanaman kacang tanah, dan jagung, sehingga dugaan hubungan
komoditas alternatif mempunyai dua kemungkinan yaitu searah dan terbalik.
Luas areal dan produktivitas suatu komoditas dapat meningkat apabila
harga komoditas tersebut meningkat. Hal ini didasarkan pada alasan rasional
apabila laba yang diberikan suatu komoditas lebih besar dari laba yang diberikan
dari komoditas lain, maka petani akan mengalokasikan sumberdaya produksi yang
dimiliki lebih besar untuk komoditas tersebut.
Pemilihan harga gula sebagai peubah bebas yang mewakili harga
komoditas tebu karena pada dasarnya usaha tani tebu yang ada ditujukan untuk
mendukung industri gula sebagai bahan baku utamanya dan pola pengusahaan
menurut Soentoro et al (1998), respon perubahan gula terhadap perubahan jumlah
luas areal panen tebu paling sedikit berselang satu tahun. Perubahan harga
provenue gula biasanya diumumkan pada bulan April, untuk pembelian musim
panen tebu bulan Juni sampai Oktober tahun yang sama. Sedangkan musim
penanaman tebu dimulai bulan Mei sampai Juli untuk tebu tanam dan untuk tebu
kepras dimulai bulan Juni sampai Agustus. Oleh karena itu, kenaikan harga gula
baru terlihat dampaknya pada musim berikutnya.
Harga provenue gula yang ada termasuk kebijakan pemerintah, yaitu
pengendalian kebijakan harga atau kebijakan pengembangan suatu komoditas
yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap harga.
Pada penelitian ini, harga provenue yang digunakan hanya sampai tahun 1998
karena pada tahun 1998 kebijakan tersebut dihentikan, selanjutnya untuk tahun
1999 sampai 2000 digunakan harga dasar gula yang ditetapkan oleh pemerintah,
dan untuk harga gula tahun 2001 sampai dengan 2006 digunakan harga dasar gula
rata-rata tingkat produsen di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya perubahan harga
berpengaruh searah terhadap kenaikan luas areal dan produktivitas tanaman tebu.
Produktivitas tahun lalu berpengaruh terhadap respon produktivitas. Hal
ini disebabkan karena produktivitas saat ini merupakan keberlanjutan,
peningkatan, ataupun penurunan dari tahun sebelumnya. Selain produktivitas
tahun lalu, luas areal saat ini juga berpengaruh positif terhadap perubahan
produktivitas saat ini.
Harga input-input produksi yang mempunyai pengaruh terhadap
upah buruh. Semakin tinggi harga input maka akan mengurangi jumlah
penggunaannya sehinga berpotensi untuk mengurangi produktivitas tanaman.
Tabel 2.3. Peubah-peubah bebas pada model respon areal dan respon produktivitas Tebu
2.10. Penelitian Terdahulu
Haryanto (1999) melakukan penelitian penawaran dan permintaan gula
pasir di Indonesia dengan menggunakan data deret waktu periode 1976-1997.
Dalam penelitian ini model persamaan simultan dikembangkan menjadi lima
persamaan, yaitu persamaan luas areal tebu di Indonesia, persamaan harga
provenue, persamaan produksi gula pasir di Indonesia, impor gula pasir Indonesia,
dan permintaan gula pasir Indonesia. Empat persamaan pertama menggunakan
peubah beda kala. Persamaan luas areal tebu terdiri dari harga provenue tahun
sebelumnya, harga dasar gabah tahun sebelumnya, luas areal tebu giling tahun
sebelumnya, dan trend waktu. Dalam persamaan struktural produksi gula pasir
terdapat lima peubah penjelas, yaitu luas areal tebu, harga pupuk tahun
sebelumnya, upah tenaga kerja tahun sebelumnya, harga gula merah, dan produksi
dan tingkatan serta metode penggunaan model menggunakan metode Ordinary
Least Square (OLS) dan Two Stage Least Square (2SLS). Hasil dari kedua
metode tersebut baik OLS maupun 2SLS cukup baik untuk menduga model
penawaran dan permintaan gula pasir di Indonesia. Kesimpulan dari sisi
penawaran dan persamaan luas areal adalah bahwa hanya harga provenue tahun
sebelumnya, luas areal tahun sebelumnya, dan trend waktu yang berpengaruh
nyata terhadap respon penawaran gula. Selain itu luas areal tebu tidak responsif
terhadap semua peubah penjelasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang
kecuali terhadap harga provenue jangka panjang. Pada persamaan produksi, luas
areal tebu, dan harga gula merah berpengaruh nyata dan produksi gula pasir tidak
responsif terhadap semua peubah ekonominya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
Ernawati (1997), melakukan kajian keragaan pasar gula Indonesia dan
simulasi dampak kebijakan liberalisasi perdagangan gula dunia dengan
menggunakan deret waktu periode 1965-1995. Dalam penelitian tersebut,
Ernawati menggunakan model linier persamaan simultan yang terdiri dari tiga
belas persamaan, yaitu tujuh persamaan identitas dan enam persamaan struktural
untuk menggambarkan pasar gula Indonesia. Keenam persamaan struktural
tersebut, yaitu persamaan luas areal tebu, produktivitas tebu, stok gula nasional,
impor gula pasir, permintaan gula rumah tangga, dan permintaan gula industri.
Persamaan luas areal tebu dapat dijelaskan dengan baik oleh rasio harga provenue
tahun sebelumnya dengan harga dasar gabah tahun sebelumnya, luas areal tanam
luar Jawa. Namun dari keempat peubah tersebut, hanya luas areal tanam tahun
sebelumnya yang berpengaruh nyata. Produktivitas tebu dapat dijelaskan dengan
baik oleh rasio harga provenue tahun sebelumnya dengan harga dasar gabah tahun
sebelumnya, teknologi, musim, produkitivitas tahun sebelumnya, rasio luas lahan
tebu di Jawa dengan luas areal tanam total, dan rasio luas lahan kering terhadap
luas areal tanam tebu total. Namun dari keenam peubah di atas, hanya peubah
musim dan produktivitas tahun sebelumnya yang berpengaruh nyata. Adapun
saran yang diberikan oleh Ernawati diantaranya adalah bahwa model luas areal
tanam perlu memasukan peubah-peubah harga tanaman yang mungkin menjadi
kompetitor tanaman tebu di lahan kering dan lahan sawah. Di samping itu pada
persamaan produktivitas mungkin sebaiknya dipisahkan antara produktivitas tebu
di lahan kering dan di lahan sawah dengan memasukan tanaman tebu kepras dan
tebu tanam.
Santika (2004) meneliti tentang analisis respon penawaran dan
keberlanjutan produksi tebu di Jawa dan luar Jawa. Variabel bebas yang
digunakan untuk menduga respon areal adalah luas areal tebu tahun sebelumnya,
harga padi tahun sebelumnya, harga jagung tahun sebelumnya, dan harga gula
tahun sebelumnya. Sedangkan untuk respon produktivitas tebu, variabel bebas
yang digunakan antara lain produktivitas sebelumnya, luas areal tahun
bersangkutan, harga urea tahun sebelumnya, dan harga gula tahun sebelumnya.
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa respon penawaran tebu terhadap
harga sendiri di pulau Jawa, dan luar Jawa bersifat inelastis baik dalam jangka
bahwa perkembangan produksi tebu di Indonesia dipengaruhi oleh sifat lokalitas
dari Jawa dan luar Jawa. Adapun beberapa saran yang diajukan antara lain, perlu
dilakukannya keberlanjutan produksi tebu di luar Jawa melalui pendekatan luas
III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder
yang berbentuk data deret waktu dengan observasi sebanyak 38 buah dari tahun
1969 sampai dengan tahun 2006. Penentuan jangka waktu ini didasarkan atas
keterbatasan data yang dapat diakses oleh penulis. Data yang digunakan dalam
penelitian ini mencakup data luas areal tanaman tebu, data produktivitas tanaman
tebu, data harga gula domestik, data perkembangan harga domestik komoditas
alternatif seperti padi, jagung, dan kacang tanah, data harga input-input produksi
seperti pupuk, pestisida, dan biaya upah tenaga kerja dan data rata-rata curah
hujan Indonesia.
Semua data yang digunakan diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan
tema penulisan skripsi ini seperti Departemen Pertanian Republik Indonesia
(Deptan RI), Dewan Gula Indonesia Departemen Pertanian Republik Indonesia
(DGI), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), Pusat Penelitian Sosial
Ekonomi Pertanian (PSE), lembaga-lembaga penelitian terkait, dan berbagai
sumber pustaka lainnya.
3.2. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan
deskriptif kuantitatif. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif didasarkan untuk