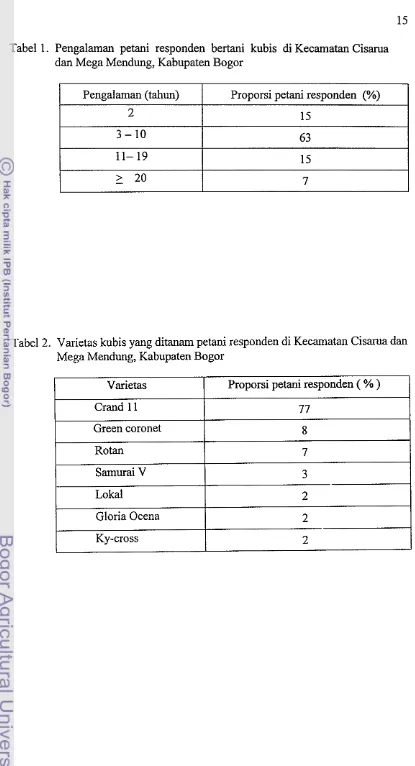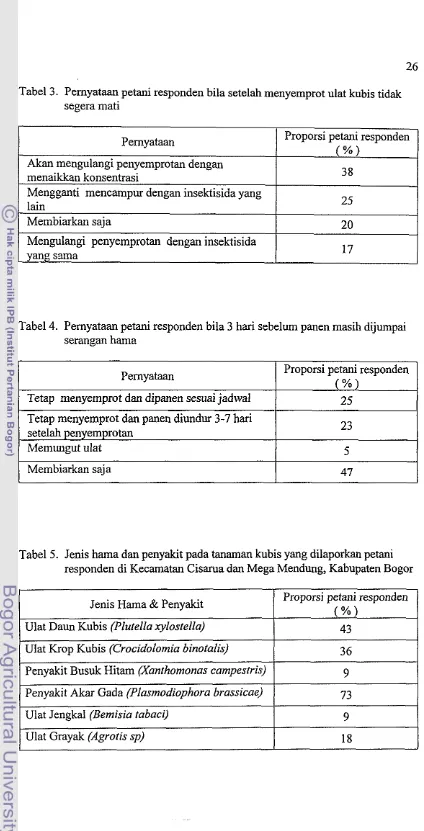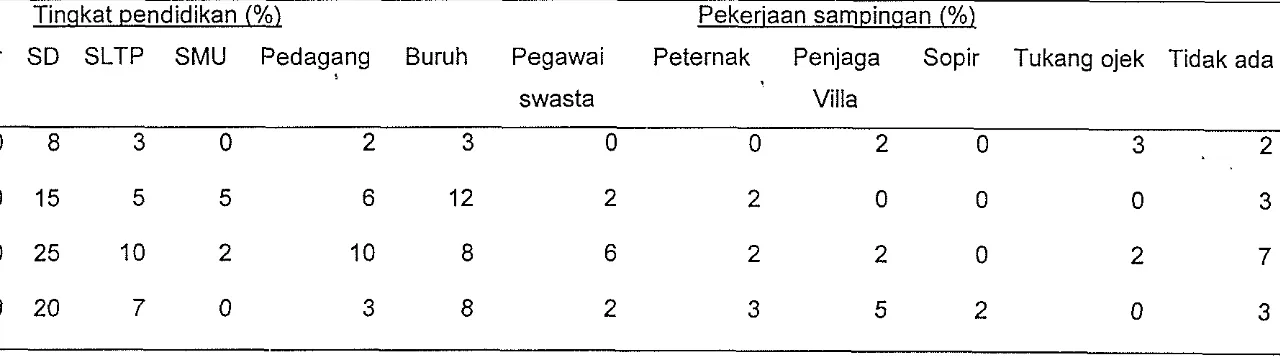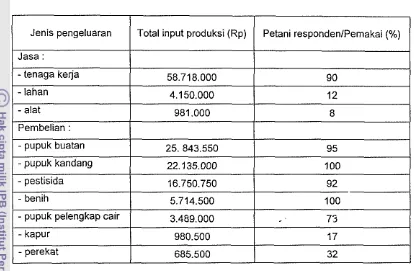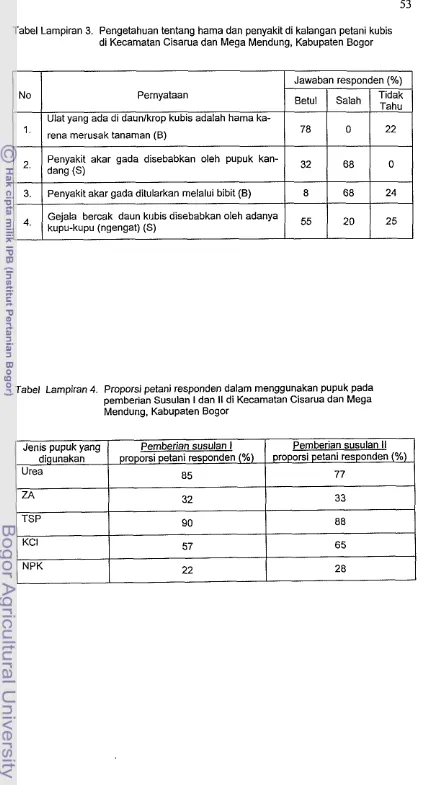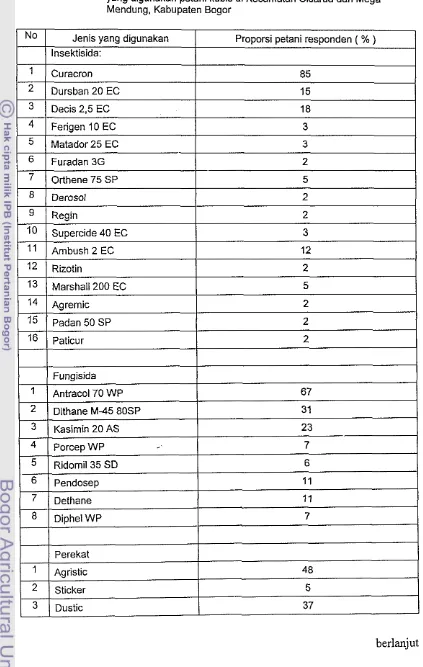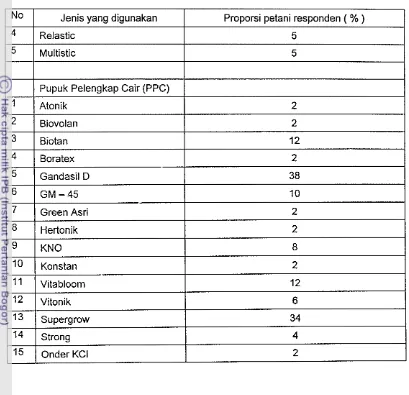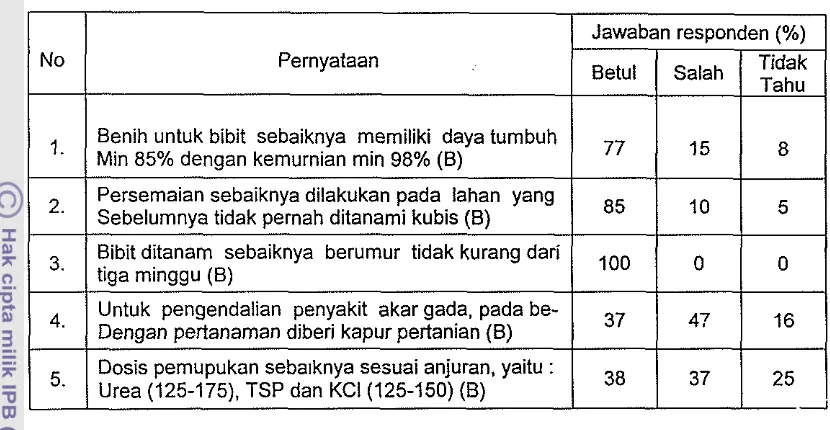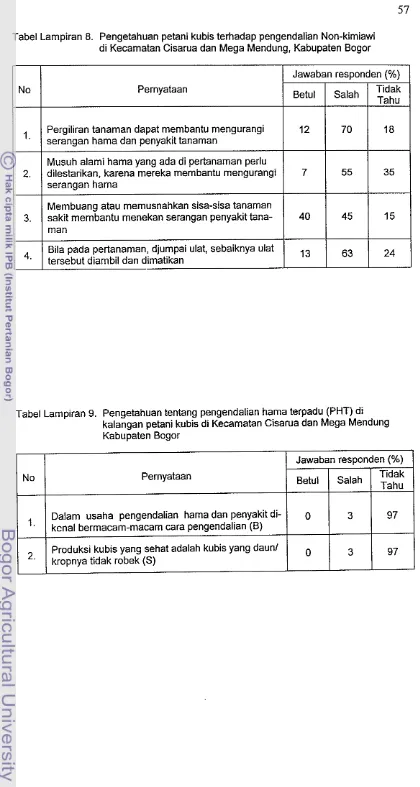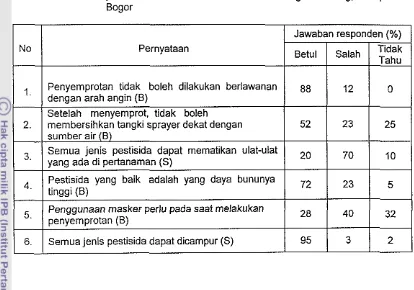PERMASALAHAN PENGUTAMAAN
PENGGUNAAN PESTISIDA DALAM USAHATANI KUBIS
DI KECAMATAN CISARUA DAN MEGA MENDUNG
KABUPATEN BOGOR
OLEH
:SUDIRMAN TUTU
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
ABSTRAK
SUDIRMAN TUTU. Permasalahan Pengutamaan Penggunaan Pestisida Dalam
Usahatani Kubis. Dibimbing oleh HERMANU TRIWIDODO dan BAMBANG S.
UTOMO.
Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari cara yang terbaik u n a pemasya-.&atan penerapan PHT pada pertanaman kubis dengan melihat pola penggunaan dan alasan pengutamaan penggunaan pestisida dalam budidaya kubis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei Pengetahuan, Sikap d m Tindakan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, pada awal bulan September sampai dengan Nopember 2000.
Enam puluh (60) petani responden diwawancarai d&ngan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Pertanyaan mengenai keadaan sosial-ekonomi, pengetahuan terhadap hama pefiyakit tanaman kubis dan musuh alaminya, sikap petani terhadap pengelolaan hama penyakit dan budidaya tanaman.
Kondisi wilayah Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung cukup baik untuk budidaya kubis termasuk jenis tanaman sayuran lainnya. Hanya saja Program PHT di wilayah tersebut belurn pemah dimasyarakatkan. Petani yang umumnya berpzndidikan Sekolah Dasar dan mempunyai tanggungan keluarga 3-5
orang serta mengusahakan lahan yang relatif sempit masih tetap melakukan sistim tanam secara monokultur. Mereka masih mengutamakan pula penggunaan pestisida dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Pengetahuan mereka terhadap hama penyakit dan musuh alaminya serta dampak negatif penggunaan pestisida masih rendah.
Pengetahuan mereka mengenai budidaya tanaman kubis secara mum
sudah baik, seperti pemilihan benih bermutu, pemindahan bibit tepat waktu pemeliharaan tanaman di persemaian maupun di pertanaman. Sedangkan untuk penggunaan pupuk padat dan pupuk cair maupun penggunaan kapur umumnya belum sesuai dengan dosis anjuran.
Petani mengutamakan pestisida dalam mengendalikan hama penyakit kubis karena petani belum menemukan pengendalian hama penyakit selain pestsida. tekanan biologis mendorong petani melakukan penyemprotan secara berjadwal, kelompok tani tidak aktif dan kelembagaan petani yang tidak berfungsi, optimalisasi penyuluh lapangan rendah, tersedia banyak pestisida di pasaran termasuk pestisida yang sudah dilarang penggunaannya serta informasi distributor yang tidak obyektif.
Sikap petani dalam melakukan penyemprotan secara bejadwal dan mengutamakan pestisida menunjukkan rendahnya pengetahuan mereka dalam ha1 pengelolaan hama penyakit tanaman kubis maupun terhadap musuh alaminya.
SURAT PEFNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul :
Pennasalahan Pengutamaan -Penggunaan Pestisida Dalam Usahatani
Kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung Kabupten Bogor
adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pemah dipublikasikan.
Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas
d m dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, 13 Mei 2002
PERMASALAHAN PENGUTARlAAN PENGGUNAAN
PESTISIDA DALAM USAHATAN1 KUBIS
DI KECAMATAN CISARUA DAN MEGA MENDUNG
KABUPATEN BOGOR
OLEH :
SUDIRMAN TUTU
Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Tesis : Permasalahan Pengutamaan Penggunaan Pestisida Dalam
Usahatani Kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung
Kabupaten Bogor
Nama : Sudirman Tutu
NRP : 98135PHT
Program Studi : Entomologi - Fitopatologi
Menyetujui : 1. Komisi Pembimbing
Dr. Ir. I-Iermanu Triwidodo, MSc. Ketua
Ir. Bambang S. Utomo. MDS Anggota
Mengetahui,
2. Ketun Program Studi Program Paseasarjana Entomologi - Fitopatologi
frida Manuwoto, M.Sc
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1955 di Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sebagai anak kesembilan dari sembilan bersaudara
dari Ibu Hj. H. Daeng Intang (Alm.) dan Ayahanda Haji P. Daeng Tutu.
Penulis setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Pertanian Menengah
Atas di Ujung Pandang pada tahun 1974, bekerja sebagai tenaga honorer selama
lebih kurang 2 tahun. Melanjutkan studi di Fakultas 'Pertanian (Program Diploma
- Pendidikan Ahli Penyuluhan Pertanian = PAPP) Universitas Hasanuddin Ujung Pandang tahun ajaran 197711978 dan menyelesaikan studi pada tahun 1980. Pada
tahun 1981-1985, penulis bekerja sebagai penyuluh pertanian di Sulawesi Selatan.
Penulis melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Jurusan Hama dan Penyakit
Tumbuhan di Universitas yang sama pada tahun 1983 dan memperoleh gelar
Sarjana Pertanian tahun 1986.
Sejak tahun 1987 sampai sekarang, penulis bekeja sebagai staf di Badan
Sumberdaya Manusia Pertanian Jakarta yang sebelum reorganisasi dikenal dengan
Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian.
Pada tahun ajaran 199811999, penulis mendapat beasiswa dari Departemen
Pertanian melalui Proyek Sumberdaya Sarana dan Prasarana Badan DIKLAT
Pertanian Jakarta untuk mengikuti Program Magister Sains di Program
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Penulis menikah dengan Hasrawati Tola dan dikaruniai 3 orang anak
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Komisi Pembimbing :
Bapak Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc., sebagai ketua; Bapak Ir. Bambang S.
Utomo, MDS sebagai anggota serta kepada Bapak Didin, atas segala bimbingan,
petunjuk dan saran-saran sejak perencanaan dan pelaksanaan penelitian hingga
penulisan tesis ini.
Kepada Bapak Badri dan keluarganya di Caarua, penulis menyampaikan
terima kasih atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penelitian di
lapangan. Kepada Penyuluh, PHP, Mantri Tani, staf unsur terkait dan segenap
pihak yang turut membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat saya
sebutkan satu per satu, diucapkan pula terima kasih atas bantuan morilnya dalam
pelayanan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Badan Sumberdaya
Manusia Pertanian Departemen Pertanian, penulis mengucapkan terima kasih atas
dorongan moril sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima
kasih yang sama juga disampaikan kepada Pemimpin Proyek Sumberdaya Sarana
dan Prasarana Badan DIKLAT Pertanian dan segenap staf atas kesempatan dan
dukungan biaya sehingga proses penyelesaian studi penulis dapat be jalan lancar.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB, Direktur Program
Pascasarjana dan staf, Ketua Program Studi Entomologi-Fitopatologi, serta
IPB, atas kesempatan, ilmu pengetahuan, bimbingan serta bantuan yang telah
penulis dapatkan di IPB.
Dorongan, bantuan dan petunjuk yang sangat berarti dari Bapak Dr. Ir.
Baharuddin Baso Tika, MS. (Bupati KDH Tk I1 Jeneponto, Sulawesi Selatan) d m
Bapak Abdul Gani Sarro (Kapten KM SINABUNG), Ibu (Mertua) Hj. Hafsjah Karaeng Bola serta Ibu asuh Hj. M. Daeng Tjaya, yang untuk semua itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besamya.
Akhimya kepada istriku dan anak-anakku tercinta yang telah merelakan
waktunya, pengertian dan dorongannya selarna masa studi penulis serta selumh
keluarga dan saudari-saudaraku diucapkan terima kasih yang sebesar-besamya.
Lebih dari itu, kepada Ibundaku yang sangat kucintai yang telah meninggal
sebelum penulis mengikuti studi "semoga ketekunan hati Ibunda mendoakan
penulis semasa hidupnya", mendapat pahala dan limpahan rahrnat Allah Yang
Maha Kuasa. Kepada Ayahanda, penulis menghaturkan sembah sujud atas doa
dan dorongan yang diberikan.
Bogor, Mei 2002
DAFTAR
IS1
Halaman DAFTAR TABEL
...
xiDAFTAR LAMPIRAN
...
xiPENDAHULUAN
...
1 Latar Belakang...
1. .
Tujuan Penelltlan
...
2 TINJAUAN PUSTAKA...
3METODOLOGI
...
10...
HASIL DAN PEMBAHASAN 12
Hasil
...
12...
Keadaan Umum Wilayah 12
. .
...
Karakterlstlk Petani 13
...
Karakteristik Usahatani 13
...
Pengetahuan Petani...
. Budidaya Kubis. Hama dan Penyakit (Ulat Kubis, Bercak Daun. dan Akar
...
Gada)
...
.
Musuh Alami Ulat KubisPengendalian Akar Gada
...
.
...
.
Pengendalian Ulat Kubis dan Bercak Daun...
.
Pengendalian Dengan Cara Non.Kimiawi...
. Pengendalian Hama Terpadu
...
. Pestisida dan Penyemprotan 23
...
. Dampak Penggunaan Pestisida 23
...
Sikap Petani 24
...
.
Kerasionalan Penggunaan Pestisida 24. . ...
.
Pencampuran Pest~slda 25...
.
Kepeduliaan Dalam Penggunaan Pestisida 25Halaman
Pembahasan
...
...
Pengetahuan...
Sikap...
Tindakan...
Faktor-faktor Penyebab Pengutamaan Penggunaan Pestisida
...
Faktor-faktor Lain Sebagai Penyebab Penggunaan Pestisida
KESIMPULAN DAN SARAN
...
...
Kesimpulan
...
Saran
DAFTAR PUSTAKA
...
...
DAFTAR
TABEL
Nomor Teks Halaman
1. Pengalaman petani responden dalam bertani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor..
...
152. Varietas kubis yang ditanam petani responden di Kecamatan Cisama dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
153. Pemyataan petani responden bila setelah menyemprot ulat kubis tidak
segera mati
...
264. Pemyataan petani responden bila 3 hari sebelum panen masih dijumpai serangan hama
...
265. Jenis hama dan penyakit pada tanaman kubis yang dilaporkan petani responden di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten
Bogor
...
26Nomor Lampiran Halaman
1. Karakteristik petani kubis di tinjau dari segi Umur, Tingkat pendidikan dan Pekerjaan sampingan di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung,
Kabupaten Bogor..
...
5 12. Total input produksi yang dikeluarkan petani responden selama musim
tanam 2000
...
52 3. Pengetahuan tentang hama dan penyakit di kalangan petani kubisdi Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
53 4. Proporsi petani responden dalam menggunakan pupuk pada pemberianSusulan I dan I1 di Kecamatan Cisarua dan Mega Mndung, Kabupaten
Bogor
...
535. Jenis insektisida, fingisida, perekat dan pupuk pelengkap cair (PPC) yang digunakan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mndung,
...
Kabupaten Bogor 54
6. Pengetahuan tentang budidaya tanaman di kalangan petani kubis
Nomor Lampiran Halaman 7. Pengetahuan tentang musuh alami di kalangan petani kubis
di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
56 8. Pengetahuan petani kubis terhadap pengendalian Non-kimiawidi Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
579. Pengetahuan tentang pengendalian hama terpadu di kalangan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten
Bogor
...
5710. Pengetahuan tentang pestisida dan penyemprotan di kalangan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten
Bogor
...
5811. Pengetahuan petani kubis terhadap darnpak penggunaan pestisida di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten
Bogor
...
58 12. Sikap kerasionalan petani kubis pada penggunaan pestisidadi Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
5913. Sikap petani kubis terhadap kecenderungan mencampur pestisida
di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
5914. Sikap kepeduliaan petani kubis pada penggunaan pestisida
di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
...
6015. Tindakan pengelolaan organisme pengganggu tanaman (OPT) di kalangan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung,
...
Kabupaten Bogor 60
16 .Jenis pestisida yang digunakan petani kubis di Kecamatan Cisarua
...
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kubis mempakan tanaman hortikultura yang penting bagi manusia dan
dimanfaatkan sebagai pelengkap makanan pokok serta salah satu sumber mineral
dan vitamin. Umurnnya kubis dikonsumsi setelah diolah, namun sebagian
masyarakat mengkonsumsi langsung tanpa direbus. Oleh karenanya perlu
'diupayakan agar produksi kubis sehat dan tidak mengandung racun yang
membahayakan manusia, termasuk adanya residu pestisida.
Hanya disayangkan bahwa penggunaan pestisida pada tanaman kubis
masih tinggi (Rauf A. dkk. 1994). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (1994), bahwa biaya penggunaan pestisida yang dikeluarkan oleh petani
kubis mencapai 30% dari biaya produksi total. Meskipun demikian, petani masih
tetap mengutamakan penggunaan pestisida dalam pengendalian hama. Cara
aplikasi berjadwal yang dilakukan oleh petani di pedesaan dan meningkatnya
penggunaan pestisida pada sayuran temtama kubis, pada giliran berikutnya akan
menimbulkan dampak yang lebih serius, yaitu terhadap kesehatan, hama semakin
resisten terhadap insektisida, dan pencemaran lingkungan hidup pada umumnya.
Penggunaan pestisida menurut Flint dan van den Bosh (1981) dapat mempakan
altematif terakhir apabila dilakukan suatu sistem pengendalian harna melalui
pendekatan ekonomi dan ekologi yang dikenal sebagai pengendalian hama terpadu
2
PHT merupakan salah satu upaya untuk mengurangi bahkan kalau
mungkin meniadakan penggunaan pestisida. Hanya dalam penerapannya
seringkali menemukan banyak hambatan.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari cara yang terbaik untuk
pemasyarakatan penerapan PHT pada pertanaman kubis dengan melihat pola
penggunaan dan alasan pengutamaan penggunaan pestisida dalam budidaya
kubis.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumhangan
TINJAUAN PUSTAKA
Kubis
Kubis banyak diusahakan di daerah pegunungan dan dataran tinggi
seperti Lembang, Pangalengan dan Pacet (Jawa Barat), Wonosobo d m
Tawangmangu (Jawa Tengah), Tengger dan Pujon (Jawa Timur), serta Tanah
Karo (Sumatera Utara) (Sunarjono 1980).
Kubis bunga diperbanyak dengan biji, dan untuk luasan 1 ha diperlukan i
400 g biji, dengan jarak tanam 70 cm
x
50 cm. Pupuk kandang digunakan 1 kgllubang tanam sedangkan pupuk buatan yang terdiri dari pupuk Nitrogen (2 gUrea
+
4,5 g ZA), pup& Fosfor (9 g TSP) dan Kalium (7 g KCL) diberikan sebelum tanam pada tiap lubang tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada umurtanarnan di lapangan i 4 minggu yang terdiri dari 2 g Urea dan 4,5 g ZA per
tanaman. Total dosis pupuk yang diperlukan untuk lahan seluas 1 ha adalah 30 ton pupuk kandang, 100 kg Urea, 250 kg ZA, 250 kg TSP dan 200 kg KCL
(Satrosiswojo dkk. 1993).
Hama dan Penyakit
Hama-hama utama pada tanaman kubis adalah Agrotis ipsilon Hufn
(Ulat tanah hitarn), Plutella xylostella (L) (Lepidoptera: Yponomeutidae, dan Crocidolomia binotalis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) (Anonim 1981).
Sudarmo (1994) mengemukakan bahwa Agrotis ipsilon (Hufn)
(Lepidoptera: Noctuidae) atau dikenal dengan uret atau ulat tanah adalah ulat
pemakan daun pada kubis. Ulat biasanya merusak dengan cara memotong bagian
4
tanaman yang berumur 1-2 minggu. Apabila terjadi serangan hama dengan
intensitas yang tinggi dan meliputi areal yang luas maka perlu dikendalikan secara
kimiawi dengan insektisida (Suyanto 1994).
Ngengat Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae),
mempakan hama penting tanaman Curcifera di Indonesia temtama di dataran
tinggi. Pengendalian hama ini dapat dilakukan secara kultur teknis yaitu dengan
penanaman tumpangsari antara wortel dengan kubis. Sedangkan cara kimiawi
dilakukan dengan menggunakm insektisida Bacillus thuringiensis.
Crocidolomia binotalis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) adalah ngengat
kubis yang ulatnya memsak daun dan menyebabkan gulungan daun kubis menjadi
tidak sempurna (Sudarmo 1994).
Penyakit-penyakit utama pada tanaman kubis adalah : Busuk Hitam
(Xanthomonas campestris), Akar Gada (Plasmodiophora brassica), Bercak Daun
(Alternaria sp.) dan Penyakit Rebah Kecambah (Rhizoctonia sp.) (Anonim 1981).
Xanthomonas campestris (Penyakit Busuk Hitam : Black rot). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris pv. Campestris (Pamm.)
Dye. Sinonim:
X.
campestris pv. Campestris (Pamm.) Dowson, BacillusCampesbis Pamm. Pseudomonas Campestris (Pamm.) E.F.Sm., Bacterium
Campestris (Pamm.) E.F.Sm, B. Campestris (Pamm.) Chester, dan Phytomonas Campeslris (Pamm.) Bergey et al. (Anonim 1997).
Pengendaliannya adalah dengan pergiliran tanaman, menanam benih
sehat, perlakuan benih dengan air panas, perlakuan tanah persemaian
(desinfektan), eradikasi tanaman terserang, penggunaan mulsa, serta menanam
5
Plasmodiophora brassica (Penyakit Akar BengkakIAkar GadaIAkar
Pekuk : Club root). Patogennya adalah Plasmodiophora brassicae Wor. (Anonim
1997).
Pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan aplikasi fungisida yang
efektif.
Menund Sudarmo (1992) bahwa ha1 teknis yang perlu diperhatikan
dalam penggunaan pestisida adalah ketepatan penentuan dosis. Dosis adalah
jumlah pestisida daIam liter atau kilogram yang digunakan untuk mengendalikan
hama atau penyakit tiap satuan luas tertentu atau tiap tanaman yang dilakukan
dalam satu kali aplikasi atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dosis bahan aktif
adalah jumlah bahan aktif pestisida yang dibutuhkan untuk keperluan satuan luas
atau satuan volume larutan.
Ada tiga macam konsentrasi yang perlu diperhatikan dalam ha1
penggunaan pestisida yaitu : (1) konsentrasi bahan aktif, yaitu persentase bahan
aktif suatu pestisida dalam larutan yang sudah dicampur dengan air, (2)
konsentrasi formulasi, yaitu banyaknya pestisida dalam cc atau gram setiap liter air, (3) konsentrasi laiitan atau konsentrasi pestisida, adalah persentase
kandungan pestisida dalam suatu larutan jadi.
Insektisida untuk hama tanaman kubis menurut Baehaki (1994), terdiri
atas 4 golongan, yaitu : Insektisida Organofosfat, Insektisida Karbamat, Insektisida Organik Campwan, dan Insektisida Botani. Sedangkan cara kerja
insektisida yang dikemukakan oleh Oka (1995) ialah bagaimana efeknya dan
6
masuk ke dalam tubuh serangga hama ia akan mempengaruhi proses hidup hama
itu. Efek-efek yang terlihat adalah mati, sakit, perubahan perilaku, pertumbuhan,
metabolisme atau kapasitas reproduksinya. Misalnya : 1) racun-racun perut masuk
ke dalam perut serangga hama melalui mulut, diabsorpsi ke dalam tubuh melalui
saluran pencemaan, 2 ) racun kontak pada umumnya masuk ke dalam tubuh hama
melalui kontak tubuh serangga dengan permukaan daun yang mengandung racun
tersebut sehingga merusak sistim syaraf dan pemafasan hama, 3) fumigan, mudah
sekali menguap dan masuk ke dalam tubuh serangga hama dalam bentuk gas
melalui sistim pemafasannya, 4 ) racun sistemik diaplikasikan pada daun, batang,
buah-buahan atau akar diabsorpsi oleh tanaman kemudian racun tersebut bergerak
meialui sistim vaskuler menuju bagian-bagian yang tidak terkena perlakuan racun
itu. Selma hama memakan, racun itu juga akan ikut termakan, 5 ) racun penyebab
mati lemas (suffocation) adalah racun yang menyurnbat saluran pemafasan
sehingga tidak dapat bemafas akhimya hama tersebut mati.
Akibat Samping Penggunaan Pestisida
Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi
hama, resujensi hama, timbulnya hama sekunder, terdapatnya residu pestisida
dalam bahan makanan dan pencemaran lingkungan (Untung 1992; Oka 1995).
Pemantauan residu sipermetrin, etrin, delatametrin dan profenofos pada tanaman
kubis yang dilakukan oleh Soeriaatmadja dan Sastrosiswojo (1988) (dalam Oka
1995) di Kabupaten Bandung dan Garut menunjukkan kadar yang dapat
membahayakan konsurnen. Asefat (konsentrasi formulasi 0,2 - 0,4%) yang
diaplikasikan pada tanaman kubis meninggalkan residu dalam tanaman tersebut
7
Salah satu sifat insektisida yang penting untuk diperhatikan adalah residu
insektisida baik residu yang ada pada produk maupun residu yang tertinggal pada
lingkungan. Residu insektisida dalam bahan makanan khususnya sayuran, selain
berasal dari insektisida yang langsung diaplikasikan pada tanaman dapat juga
karena kontaminasi atau karena tanarnan ditanam pada tanah yang mengandung
residu insektisida yang persisten.
Rata-rata konsentrasi residu insektisida pada tanaman kubis di Lembang
adalah 6,05 m a g , di Pengalengan 3,53 mgkg dan di Kertasari 8,06 mgkg. Dari hasil penelitian tersebut ternyata kadar residu yang terkandung dalam tanaman
kubis relatif tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai upaya agar tanaman sayuran
yang ditanam oleh para petani bebas dari residu insektisida (Nurmala 1992).
Pengendalian HamaTerpadu (PHT)
Penerapan PHT pada tanaman kubis bertujuan untuk mengurangi
pemakaian pestisida dan residu pestisida yang tertinggal sehingga tanaman kubis
bebas dari senyawa-senyawa beracun yang dapat membahayakan manusia.
Menurut Oka (1995) PHT adalah suatu teknologi pengendalian hama
yang memanfaatkan berbagai cabang ilmu dalam satu rarnuan yang serasi yang
satu memperkuat yang lain. Falsafah PHT menghendaki agar penerapannya di
lapangan lentur, fleksibel sesuai dengan kondisi ekologi setempat dan keadaan
sosial/budaya masyarakat yang hidup di suatu daerah. Jadi bukan merupakan
"paket" teknologi yang h a s dapat dilaksanakan sama di semua kondisi. PHT
mengembalikan fungsi petani ke kedudukannya yang sebenamya, karena PHT
sifatnya lentur dan dinamis dalam penerapannya di lapangan maka petani hams
8
hams rnampu untuk menjadi pengamat, penganalisis ekosistem, pengambil
keputusan pengendalian, dan sebagai pelaksana teknologi pengendalian yang
sesuai dengan prinsip-prinsip PHT.
Petani dan Organisasinya
Organisasi petani merupakan kelembagaan yang perlu ada dalam
lingkungan masyarakat petani. Petani selaku pengelola usahatani, secara individu
tampaknya tidak banyak yang dapat diiarapkan dari hasil usahatani mereka
sehingga perlu ada organisasi petani. Organisasi petani menghimpun petani dan
anggota kelompok tani dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu
yang telah mereka tetapkan (Anonim 2002).
Di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung kelompok tani yang pernah
dibentuk tidak berfungsi. Salah satu faktor penyebabnya karena kelompok tani
tersebut dibentuk. Artinya terbentuknya kelompok tani bukan atas kesadaran
petani itu sendiri.
Penyuluhan dan Agribisnis
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian akan beijalan dengan produktif,
efektif dan efisien apabila didukung oleh kelembagaan, sarana dan prasarana serta
anggaran yang memadai.
Berkaitan dengan itu pula, menurut Saragih (2000) bahwa pertanian
hanyalah salah satu bagian dari agribisnis yakni hanya production operation on the farm, sedangkan agribisnis mencakup 3 (tiga) sektor yaitu :
9
manufacture and distribution of farm supplies) seperti industri ago-kimia
(industri pupuk, industri pestisida, industri obat-obatan hewan), industri agro-
otomotif (industri alat dan mesin pertanian, industri peralatan pertanian, industri
mesin dan peralatan industri pengolahan hasil pertanian) dan industri
pembibitanlperbenihan tanamanfhewan.
Kedua, sektor pertanian dalam arti luas @reduction operations on the
farm) disebut juga on-farm agribisnis, yaitu pertanian tanaman pangan, tanaman
hortikultura, tanaman obat-obatan, perkebunan, petemakan, perikanan lzut dan air
tawar serta kehutanan.
Ketiga, sektor industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir
yakni kegiatan industri yang mengolah hasil hilir yakni kegiatan industri yang
mengolah hasil pertanian menjadi produk-produk olahan baik produk antaia
(intermediate product) maupun produk akhir (storage, processing and distribution
offarm commodities and items made for them).
Dengan perkataan lain pembangunan Agribisnis merupakan
pembangunan industri dan pertanian serta jasa sekaligus. Keberhasilan agribisnis
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu Kecamatan C i s m a d m
Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor pada awal bulan September 2000
sampai dengan akhir bulan Nopember 2000. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan metode survei yang dilakukan dengan dua tahap kegiatan, yaitu
pertama tahap persiapan yang m e m u s k a n topik permasalahan yang akan
digunakan dalam wawancara, kedua tahap survei dengan menggmakzn metode
Pengetahuan, Sikap cian Tindakan. Pemilihan petani responden dilakukan
berkaitan dengan informasi dzri Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Bogor Tahun 2000. Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung merupakan sentra
pertanaman kubis selain pertanaman hortikultura lainnya. Petani di lokasi tersebut
urnumnya menggunakan pestisida dalam kegiatan usahatani sayuran termasuk
untuk budidaya kubis. Di lokasi penelitian belum pemah dimasyarakatkan
penerapan PHT.
Penyebaran lokasi responden dilakukan berdasarkan domisili petani,
dengan pertimbangan mudah menemukan petani dan tersedia cukup waktu.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan
kuesioner yang terstruktur. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup keadaan
sosial-ekonomi, pengetahuan terhadap hama penyakit tanaman kubis dan musuh
alaminya, sikap petani terhadap pengelolaan hama penyakit dan budidaya
tanaman. Untuk melengkapi data lainnya dilakukan juga wawancara tidak
terstruktur selain petani kubis, juga terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),
11
dinas terkait. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Untuk kelancaran komunikasi dalam mewawancarai 60 orang petani responden,
dibantu oleh satu orang kontak tani sebagai asisten lapangan. Untuk merekam
pemahaman dan persepsi responden tentang hama, penyakit dan musuh alami,
wawancara dilengkapi dengan alat peraga berupa spesimen hama atau foto gejala
serangan penyakit, dan dilakukan di lapangan dan di rumah. Diharapkan dari
wawancara dapat meliput informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Analisis Data
Data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis secara deskriptif dan
disajikan dalam bentuk tabulasi, sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Keadaan Umum Wilayah
Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung yang dipilih sebagai lokasi
sampel memiliki topografi bergelombang sampai pegunungan. Berdasarkan data
BPS dan Departemen Pertanian tahun 1998, lokasi tersebut terletak pada ketinggian 700 -1 100 m dpl., dengan derajat kemasaman @H) berkisar antara 5-8.
Jenis tanah umumnya latosol coklat, dengan tekstur tanah remah (gembur). Curah
hujan 3524 mm selarna satu ta!!un (199912000). Suhu rata-rata harian berkisar
20°C
-
35"C, serta kelembaban nisbi udara (RH) berkisar antara 7&90%.Lahan usahatani di lokasi penelitian sebagian besar diusahakan untuk
komoditas yang cocok untuk dataran tinggi termasuk sayuran dataran tinggi. Jenis
sayuran yang banyak diusahakan selain kubis dan wortel, juga terdapat kentang,
cabe, caisin, tomat, bawang dam, sawi, brocoli, kacang merah, tales, buncis,
ditanam secara tumpangsari.
Penerapan PHT di lokasi penelitian tersebut belum pemah
dimasyarakatkan. Petani mengenal istilah PHT melalui televisi, sesama petani
dan ada juga dari petugas pertanian. Oleh karenanya pengetahuan petani
responden tentang musuh alami dan cara pengendalian secara PHT di lokasi
13
Karakteristik Petani
Petani responden di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung umumnya
mempunyai pekerjaan sarnpingan. Umur petani berkisar 21-59 tahun dengan
tingkat pendidikan sebagian besar Sekolah Dasar (Tabel Lampiran 1).
Jumlah tanggungan keluarga para petani umumnya berkisar 3-5 orang
(68%), 6-8 orang (27%) dan 1-2 orang (5%). Status pemilikan lahan adalah milik
sendiri (72%) atau menyewa lahan (17%) dan bagi hasil (1 1%). Luas lahan yang diusahakan untuk pertanaman kubis relatif sempit, umumnya berkisar 0,l-0,5 ha
(72%), di bawah 0,l ha
(7%)
dan yang mengusahakan di ztas 0,5-1,5 ha hanya (5%). Pengalaman bertani kubis cukup beragam, tetapi umumnya 3-10 tahun(63%) (TabeI 1).
Karakteristik Usahatani
Untuk mencapai hasil produksi kubis yang tinggi, petani harus
menyediakan berbagai input mulai dari penanaman sampai panen. Input produksi
tertinggi dikeluarkan oleh umumnya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega
Mendung adalah tenaga ke rja, pupuk dan pestisida (Tabel Lampiran 2).
Sekitar 93% tanaman kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung
ditanam secara monokultur dan 7% ditanam secara tumpangsari. Tanaman
tumpangsari dengan kentang (3%), caisin (2%) dan cabe (2%). Petani yang melakukan penanaman secara tumpangsari ini terutama yang memiliki lahan
garapan kurang dari 0,l ha. Hasil yang diperoleh dari tanaman tumpangsari
dipergunakan untuk membeli pupuk dan pestisida. Belum ada petani responden
yang melakukan sistem tanam sacara tumpangsari antara kubis dengan tomat
14
penelitian. Sebagian petani (52%) menanam wortel secara turnpangsari dengan
tanaman sayuran lain seperti cabe, tomat, bawang dam, kentang, caisin, dll.
Rotasi tanaman yang dilakukan masih berkisar pada tanaman yang memiliki famili
yang sama seperti sawi, dan caisin. Varietas kubis yang ditanam oleh urnumnya
petani adalah Grand 11 (77%) (Tabel 2), karena Grand 1 1 mudah diperoleh dan
memiliki daya tumbuh baik serta produksi memadai.
Petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung melakukan penyemaian
sendiri, dengan cara langsung yaitu benih kubis disebar setelah direndam terlebih
dahvlu ke dalam air panas. Sebagian besar petani menempatkan persemaian pada
lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami kubis (85%) dan pada lahan bekas
pertanaman kubis (5%). Ada pula menempatkan di halaman nunah dengan
maksud lebih mudah melakukan perawatan (10%).
Sekitar 84% petani responden pernah mendengar tentang pengapuran
pada lahan pertanaman kubis yang bersurnber dari penyuluh (22%), sesama petani
kubis (33%), media massa (12%) dan dari petugas kios saprotan (17%). Dari
kelompok yang pemah mendengar tentang pengapuran, 5% selalu melakukannya,
32% kadang-kadang melakukan dan 47% yang tidak pernah melakukan. Kapur yang diberikan urnumnya 86% dibawah dosis yang dianjurkan. Hal ini pula
mungkin yang menyebabkan 12% petani responden menjawab salah dan 31%
ragu-ragu atas pernyataan bahwa penyakit akar gada dapat berkurang apabila lahan
pertanaman diberi kapur. Sekitar 57% yang memberikan jawaban betul atas
Tabel 1. Pengalaman petani responden bertani kubis di Kecamatan Cisama dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
Tabel 2. Varietas kubis yang ditanam petani responden di Kecamatan Cisama dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
Pengalaman (tahun)
2 3 - 10 11- 19 >
- 20
Proporsi petani responden (%)
15 63 15 7 Varietas Crand 11 Green coronet Rotan Samurai V - Lokal Gloria Ocena Ky-cross
[image:111.577.79.494.46.812.2]16
Pupuk kandang yang paling urnurn di,-akan di Kecamatan Cisarua maupun Mega Mendung adalah kotoran ayam (go%), karena jenis pupuk kandang
ini lebih mudah diperoleh. Sisanya menggunakan kotoran domba dengan alasan
untuk merangsang pertumbuhan lebih cepat. Hanya saja tidak banyak tersedia
sehingga kurang yang menggunakan.
Pencampwan pupuk kandang dengan pupuk buatan pada pemupukan
dasar sering dilakukan oleh petani (12%), yang mencampur pupuk kandang
dengan furadan (8%) dan yang mencampur pupuk kandang dengan kapw (13%). Pupuk buatan yang digunakan pada pemupukan dasar tersebut adalah TSP dan
KCL. Sedangkan jenis pupuk buatan yang digunakan oleh petani terdiri atas Urea,
ZA, TSP dan KCL karena mereka telah mengetahui bahwa pemupukan yang
lengkap adalah campuran UreaIZA, TSP, dan KC].
Penggunaan pupuk Urea dan ZA umurnnya dilakukan oleh petani pada
pemupukan susulan I dan I1 (Tabel Lampiran 4), temasuk penggunaan pupuk pelengkap cair (PPC) yang diberikan disekitar pekarangan dengan alasan agar
dapat merangsang pertumbuhan lebih cepat.
Sekitar 66% petani yang menggunakan PPC dengan alasan bahwa PPC
dapat meningkatkan hasil panen, 17% beranggapan bahwa penggunaan PPC
adalah pemborosan, dan sebagian petani lain tidak menggunakannya karena tidak
yakin dengan manfaatnya. PPC ini diapiikasikan bersamaan dengan
penyemprotan pestisida yang diaplikasikan tersendiri (tidak mencampur). PPC
yang umum digunakan adalah Gandasii D (38%) dan Supergrow (34%) (Tabel
Pengetahuan Petani
Budidaya Kubis
Pengetahuan petani tentang budidaya kubis secara umum cukup baik.
Mereka (100%) memindahkan bibit sesuai dengan petunjuk teknis pertanian yaitu
tidak kurang dari 3 minggu, begitu pula dalam memilih benih dan tempat
persemaian sudah baik. Hanya saja dalam penggunaan kapur dan pupuk belum
sesuai dengan dosis yang dianjurkan (Tabel Lampiran 6). Hama dan Penyakit (Ular Kubis, Bercak Daun dan Akar Gada)
Pengetahan petani responden tentang ulat kubis dan akar gada sudah
baik, kecuali gejala bercak daun masih rendah. Petani sudah mengetahui bahwa
kerusakan dam adalah sebagai akibat dari serangan ulat kubis. Mereka juga
mengetahui bahwa ngengat adalah induk dari ulat kubis. Dari pengalaman,
mereka berpendapat bahwa apabila banyak ngengat di pertanaman, ulat daunpun
semakin banyak dan kerusakan daun bertambah. Bahkan mereka juga
berpendapat, kecuali penyakit akar gada, semua kerusakan daun pada tanaman
adalah akibat serangan hama.
Mengenai gejala bercak daun, hanya 20% petani yang menjawab salah
atas pemyataan bahwa gejala bercak daun disebabkan oleh kupu-kupulngengat
(Tabel Lampiran 3).
Di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung penyakit akar gada oleh
petani disebutnya penyakit gondok. Penyakit ini menghambat pertumbuhan
bahkan apabila seluruh tanaman terserang, menyebabkan gaga1 panen. Walaupun
18
memahami penyakit ini. Hanya 13% petani yang mengetahui bahwa penyakit akar
gada disebabkan oleh microorganisme, 55% yang berpendapat penyebabnya
adalah tanah yang kurang subur dan 32% beranggapan sebagai akibat pupuk
kandang yang tidak baik. Mereka juga berpendapat bahwa akar gada dapat
ditularkan melalui tanah (68%), melalui pupuk kandang atau benihhibit 15%
(masing-masing) dan hanya 1 orang yang berpendapat melalui angin (2%).
Sebanyak 40% petani menyatakan bahwa serangan penyakit akar gada sudah ada sejak 3 tahun laiu, 33% bahwa lzbih 5 tahun lalu, dan yang menyatakan belurn
sampai 5 tahun (27%). Sebagian besar petani (83%) menyatakan tanamannya
pemah terserang penyakit akar gada dan 17% tidak pemah terserang.
Berdasarkan pengalaman petani penyakit akar gada menimbulkan
gangguan perakaran sehingga mengakibatkan kelainan pada pertumbuhan
tanaman. Menurut Semangun (1991) penyakit ini dapat tersebar setempat oleh air
drainase, alat-alat pertanian, tanah yang tertiup angin, hewan dan bibit-bibit.
Berbeda yang dilaporkan Suryaningsih (1481) bahwa penyakit akar gada dapat
disebarkan oleh pupuk kandang.
Musuh Alami Ulat Kubis
Istilah musuh alami atau musuh hama oleh petani di Kecamatan Cisarua
dan Mega Mendung beium dikenal. Petani beranggapan bahwa semua serangga
yang ada di pertanaman adalah perusak tanarnan, kecuali laba-laba karena mereka
sering melihat memangsa serangga lainnya. Sekitar 28% petani yang menjawab
betul atas pemyataan bahwa laba-laba adalah musuh alami hama dan hanya 22%
yang meyakini bahwa bila tanaman kubis disemprot dengan pestisida, musuh
19
bahwa apabila musuh alami terbunuh karena penyemprotan, maka serangga ulat
meningkat.
Dalam kaitan dengan Diadegma, semua petani responden belum pernah
melihatnya sehingga mereka tidak yakin atas pemyataan bahwa serangga
Diadegma adalah musuh alami ulat kubis (15%) dan yang menjawab tidak tahu
atas pemyataan tersebut (85%) (Tabel Lampiran 7).
Pzngendalian Akar Gada
Petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung dalam pengendalian
penyakit akar gada sudah baik. Mereka menggunakan kapur (dolomit) yang dilakukan sebelum tanam atau pada saat selesai mengolah tanah. Hanya saja di
bawah dosis yang dianjurkan. Selain penggunaan kapur, mereka juga melakukan
pengendalian secara kultur teknis atau mekanis yaitu pada saat masih muda,
tanaman dicabut dan kemudian disulam. Setelah tua, tanaman yang terserang akar
gada biasanya dibiarkan saja. Dilakukan juga pembenaman sisa-sisa tanaman
kubis di lahan kubis sampai membusuk, sehingga dapat menjadi sumber inokulum
bagi musim tanam berikutnya (Rauf A. dkk. 1994). Sisanya melakukan
pembongkaran dan pemusnahan sisa-sisa tanaman kubis atau tindakan lainnya.
Sekitar 57% petani memberikan pemyataan betul dengan pendapat bahwa
penyakit akar gada dapat berkurang apabila lahan pertanaman diberi kapur, 12%
tidak yakin dan 31% tidak tahu.
Pengendalian Ulat Kubis dun Bercak Daun
Pada umumnya pengetahuan petani terhadap pengendalian ulat kubis dan
20
saja mereka melakukan secara kimiawi. Sebanyak 87% menggunakan pestisida
dalam mengendalikan ulat kubis dan bercak daun, dan ada pula yang
mengkombinasikan dengan cara mekanis (memungut ulat) yaitu bila terdapat
serangan hama setempat-setempat (13%).
Jenis pestisida yang umurn digunakan oleh petani dalam mengendalikan
hama dan penyakit adalah Curacron 500 EC (Insektisida) (85%), Antracol 70 WP
(fungisida) (55%), sedangkan perekat menggunakan Agristic. Insektisida,
fungisida, maupun perekat yang digunakan oleh petani adalah lebih dari satu
macam. Dalam aplikasi penyemprotan, pencampuran pestisida sering dilakukan
oleh petani. Alasan dari pencampuran adalah
untuk
efisiensi waktu, menghemat biaya dan untuk mengendalikan beberapa hama dan penyakit sekaligus (TabelLampiran 13). Alasan efisiensi ini biasanya berlaku untuk pericampuran berbagai
jenis pestisida (fungisida, insektisida, dan perekat). Ada beberapa petani
mencampur insektisida dengan fungisida dengan anggapan bahwa dapat berfungsi
sebagai perekat. Dari 34 merk pestisida yang digunakan umumnya didasarkan
pada pengalaman sendiri (72%). Sisanya berdasarkan saran dari petani lainnya dan petugas pertanian atau harganya relatif lebih murah. Untuk kegiatan
penyemprotan ini, umumnya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung
(73%) melakukan sendiri atau mengupahkan kepada orang lain (27%).
Penyemprotan pestisida yang dilakukan oleh petani responden umumnya
berjadwal (68%), yang melakukan penyemprotan apabila terlihat ada daun yang
rusak (18%), dan bila petani melihat ada kupu-kupu keciungengat di pertanaman
(14%). Sedangkan bila petani melihat ada serangan hama setempat-setempat,
21
dilakukan untuk mencegah meluasnya serangan hama. Hanya 8% yang
menyemprot pada tanaman yang ada ulatnya atau memungut ulat (14%). Bila
setelah disemprot ulat kubis tidak segera mati, petani menyatakan akan
mengulangi penyemprotan dengan menaikkan konsentrasi atau dengan mengganti
mencampur dengan insektisida yang lain. Kadang-kadang membiarkan saja atau
mengulangi penyemprotan (Tabel 3).
Bila 3 hari sebelum panen masih dijumpai serangan hama, petani tetap
menyemprot dan dipanen sesuai jadwal, atau diundur 3-7 hari setelah penyenprotan. Beberapa petani responden melakukan secara mekanik
(memungut ulat) dan sebagian tetap membiarkan saja (Tabel 4).
Pengendalian Dengan Cara Non-Kimiawi
Pengendalian dengan cara non-kimiawi, secara umum petani responden
belum menunjukkan sikap yang mendukung terhadap cara pengendalian tersebut.
Meskipun diantara mereka ada yang meldrukan rotasi tanaman tetapi maksud
mereka bukan bertujuan untuk mengurangi serangan hama dan penyakit
melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik
(Tabel Lampiran 8).
Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
Pengetahuan petani tentang PHT di kalangan petani kubis di Kecamatan
22
Dari yang pernah mendengar hanya ada 2 orang yang mengaku pernah
mengenal dan mengikuti SL-PHT untuk komoditi kubis secara swadaya. Dari hasil wawancara dengan petani, menyatakan tidak tahu dengan pendapat bahwa
produksi kubis yang sehat adalah kubis yang daunikropnya tidak robek serta ada
bermacam-macam cara pengendalian hamalpenyakit dalam PHT (97%) (masing-
masing) (Tabel Lampiran 9).
Setelah dijelaskan kepada responden bahwa melalui PHT, jumlah
penyemprotan dapat berkurang dari 12x menjadi 3x, sebanyak 98% petani
responden menyatakan tertarik dengan PHT. Salah satu pertimbangan mereka
karena faktor ekonomi, karena program PHT adalah salah satu diantaranya
t bertujuan mengurangi penggunaan pestisida dalam usaha pengendalian hama
penyakit. Hanya 1 orang memsa tidak yakin dengan PHT.
Hanya disayangkan karena dalam usaha perlindungan tanaman dengan
menerapkan konsepsi PHT masih terbatas pada tanaman pangan, khususnya
tanaman padi. Penerapan PHT pada komoditas lainnya masih banyak menghadapi
kendala baik teknis maupun sosial ekonomi (Wardoyo 1991).
Menurut Rauf A. dkk. (1994), permasalahan yang mernbentang dalam penerapan PHT hams mampu kita artikan sebagai tantangan, dan peluang untuk
mengatasi tantangan itu sebagian telah melekat pada petani. Rendahnya tingkat
pengenalan PHT disebabkan rendahnya dinamika kelompok dan dukungan
kelembagaan petani di lokasi tersebut. Disamping itu juga karena belum di
23
Pestisida dun Penyemprotan
Pengetahuan petani responden tentang pestisida dan penyemprotan cukup
baik. Sebagian besar petani (88%) menyatakan betul atas pendapat bahwa
penyemprotan tidak boleh dilakukan berlawanan dengan arah angin, dan 72%
yang setuju bahwa pestisida yang baik adalah yang daya bunuhnya tinggi. Akan
tetapi 95% berpendapat bahwa semua jenis pestisida dapat dicampur dan 20% yang berpendapat, semua jenis pestisida dapat mematikan ulat-ulat yang ada di
pertanaman. Sebagian pula petani berpendapat bahwa perlu menggunakan
masker pada saat melakukan penyemprotan (28%) dan tidak boleh membersihkan
tangki sprayer dekat dengan sumber air setelah menyemprot (52%) (Tabel
Lampiran 10).
Alasan ~ e t a n i tidak mengenakan masker pada saat melakukan
penyemprotan, karena tidak praktis dan bahkan berpendapat bahwa pestisida
berbahaya hanya pada serangga hama saja dan terhadap manusia tidak (40%).
Dampak Penggunaan Pestisida
Pengetahuan petani tentang dampak penggunaan pestisida rendah. Petani
kurang memahami adanya dampak residu pestisida terhadap tanaman dan
pengar& residu pestisida sistemik yang bisa tertinggal di dalam jaringan tanaman.
Sekitar 30% petani responden yang setuju dengan pendapat bahwa
tanaman yang sering disemprot pestisida dapat mengandung racun sehingga
berbahaya bagi konsumen, dan 33% yang setuju dengan pemyataan bahwa berkurangnya udang dan berbagai jenis ikan yang hidup di sungai berkaitan
24
dengan pendapat bahwa penyemprotan yang terlalu sering dapat menyebabkan
hama dan penyakit resisten terhadap pestisida (Tabel Lampiran 11).
Sikap Petani
Kerasionalan Penggunaan Pesfisida
Sikap petani dalam penggunaan pestisida kurang rasional. Diketahui darj
hasil wawancara dengan responden yang urnurnnya (95%) setuju atas pernyataan
bahwa penyemprotan pestisida dilakukan seawal mungkin begitu terlihat gejala
serangan hama dan penyakit. Hanya 45% responden yang menyatakan tidak
setuju bila setelah penyeinprotan turun hujan, keesokan harinya pertanaman perlu
disemprot lagi. Sebagian besar pula (87%) yang setuju dengan pernyataan hanya
dengan melakukan penyemprotan secara berjadwal, kita dapat menyelamatkan
h a i l panen. Terdapat 78% petani setuju dengan pernyataan bila harga hasil panen meningkat penyemprotan perlu dilakukan lebih sering, dan sekitar 72% setuju
dengan pemyataan bila tetangga menyemprot, menunjukkan kita juga perlu
melakukan penyemprotan. Hanya sebagian (53%) yang setuju dengan pernyataan
bila tersedia cukup uang untuk membeli pestisida penyemprotan sebaiknya
dilakukan secara berjadwal (Tabel Lampiran 12).
Penyemprotan berjadwal dimaksudkan petani adalah untuk mencegah
kehilangan hasil yang lebih besar. Menurut Suyanto (1994) dapat berakibat
meningkatnya biaya produksi yang dapat mempengaruhi m e n m y a keuntungan
nyata yang diperoleh, dan dapat menimbulkan pencemaran Iingkungan dimana-
25
Pencampuran Pestisida
Semua petani responden mempunyai kecenderungan untuk melakukan
pencampuran pestisida. Kecendemgan ini dapat dilihat dari sikap petani yang
menyatakan setuju bahwa pencampuran pestisida menghemat waktu (88%),
menghemat biaya pelaksanam penyemprotan (65%). Ada pula yang berpendapat
bahwa dengan mencampur pestisida beberapa jenis hama dan penyakit dapat
dikendalikan sekaligus (27%).
Faktor lain yang mendorong petani untuk melakukan pencampuran
pestisida adalah kurangnya pengetahuan petani tsntang kelemahan dari
pencampuran pestisida yang dapat menurunkan daya bunuhnya (22%) (Tabel
Lampiran 13). Meskipun pencampuran tersebut mempertimbangkan tentang
waktu, akan tetapi telah menunjukkan ketidzkefisienan dalam menggunakan
sumberdaya yang ada (RauCA. dkk. 1994).
Kepedulian Dalam Penggunaan Pestisida
Kepedulian petani dalam menggunakan pestisida masih kurang.
Sebanyak 68% petani setuju dengan pernyataan bahwa pestisida yang sering
digunakan telah mempunyai izin dari pemerintah sehingga dianggap tidak
berbahaya bagi konsumen. Akan tetapi mereka juga tidak setuju dengan
pemyataan bahwa penyemprotan pestisida dapat juga menyebabkan serangga lain
ikut terbunuh (58%) (Tabel Lampiran 14). Pendapat ini tampaknya berkaitan
dengan pengetahuan petani yang tidak mengetahui tentang dampak negatif dari
pestisida. Sebagai contoh, ketika mereka mencampur pestisida ataupun
Tabel 3. Pemyataan petani responden bila setelah menyemprot ulat kubis tidak segera mati
Tabel 4. Pemyataan petani responden bila 3 hari sebelum panen masih dijumpai serangan hama
Pemyataan
Akan mengulangi penyemprotan dengan menaikkan konsentrasi
Mengganti mencampur dengan insektisida yang lain
Membiarkan saja
Mengulangi penyemprotan dengan insektisida yang s m a
Proporsi petani responden
( % )
38
25 20 17
Tabel 5. Jenis hama dan penyakit pada tanaman kubis yang dilaporkan petani responden di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
Pemyataan
Tetap menyernprot dan dipanen sesuai jadwal
Tetap menyemprot dan panen diundur 3-7 hari setelah penyemprotan
Memungut ulat
Membiarkan saja
Proporsi petani responden
( % ) 25 23 5 47
Jenis Hama & Penyakit Ulat Daun Kubis (Plutella xylostella)
Ulat Krop Kubis (Crocidolomia binotalis)
Penyakit Busuk Hitam (Xanrhomonas campestris)
Penyakit Akar Gada (Plasmodiophora brassicae)
Ulat Jengkal (Bemisia (abaci)
Ulat Grayak (Agroris sp)
Proporsi petani responden
27
Sikap kepedulian petani terhadap dampak pestisida pada dirinya,
konsumen, ikan yang hidup di perairan serta mahluk lain yang ber,wa yang ada
di pertanaman masih kurang (TabeI Larnpiran 11).
Tindakan Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman
Tindakan pengelolaan OPT oleh petani di Kecamatan Cisarua dan Mega
Mendung masih rendah. Petani yang melakukan pengamatan dengan frekuensi
pengamatan lebih dari 8x dalam sebulan tetapi tidak be rjadwal(20%), 5-8x (38%)
dan kurang dari 5x (42%). Mereka melakukan pengamatan denga? maksud hanya
ingin mengetahui ada atau tidaknya serangan hamalpenyakit. Apabila ada
serangan mereka memutuskan untuk melakukan penyemprotan. Hanya sebagian
petani responden yang menyatakan setuju bila tanaman terserang ulat 3 hari
menjelang panen, penyemprotan tetap dilakukan dan dipanen sesuai jadwal(25%),
dan bila setelah penyemprotan temyata ulat kubis tidak mati, penyemprotan
diulangi dengan konsentrasi dinaikkan (38%) (Tabel Lampiran 15). Umurnnya
mereka setuju dengan pernyataan bahwa seandainya ditemukan ulat pada
pertanaman maka seluruh tanaman disemprot dengan segera (78%), dan
penyemprotan dilakukan secara be rjadwaI(68%).
Hama dan penyakit penting yang ada di pertanaman kubis yang
dilaporkan petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung (Tabel 5).
.
. Usahatani sayuran di lokasi tersebut merupakan sumber pendapatanutama bagi petani sehingga mereka tidak mau menanggung resiko kehilangan
hasil yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup keluarganya. Untuk itu
28
masih menitik beratkan pada penggunaan pestisida dalam mencegah tejadinya
kerugian akibat jasad pengganggu tanaman tersebut.
Berdasarkan pengalaman di lahan petani, serangan beberapa hama dan
penyakit yang disebutkan di atas tidak begitu tinggi. Keadaan ini antara lain
disebabkan semua petani melakukan pengendalian intensif dengan pestisida.
Mereka melakukan penyemprotan pada tanamannya selama satu musim tanam
cukup beragam. Yang terbanyak antara 11- 20x sebanyak (50 %), dan dibawah 5-
PEMBAHASAN
Seperti disebutkan dalam metode bahwa data survei PST dapat digunakan
untuk identifikasi masalah. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk
mengungkapkan permasalahan yang tampak dan ada kaitannya dengan PHT.
Dengan demikian, titik tolak untuk mengidentifikasi masalah adalah memahami
apa yang seharusnya diketahui dan dilaksanakan oleh petani kubis dan apa yang
mereka ketahui dan laksanakan (Rauf A. clkk. 1994). Berdasarkan hasil suwei, pennasalahan tersebut diungkapkan dibawah ini.
Pengetahuan
Pengetahuan petani tentang budidaya kubis di Kecamatan Cisarua dan
Mega Mendung secara m u m cukup baik, seperti : waktu pemindahan bibit,
pemilihan benih dan penempatan persemaian. Hanya ada beberapa ha1 yang
memerlukan perbaikan, seperti : sistem tanam, pengapuran dan dosis
pemberiannya. Penanaman secara monokultur masih mendominasi. Kurangnya
petani yang melakukan penanaman secara tumpangsari tampaknya mereka
beranggapan bahwa produksi kubis tidak dapat maksimal. Mereka sebsnarnya
belum mengetahui bahwa penanaman kubis secara turnpangsari dapat menekan
serangan hama dan penyakit. Sedangkan pemberian kapur pada lahan pertanaman
kubis hanya berkisar 37%. Dari jumlah yang sering mengapur umumnya
...
memberikan dibawah dosis anjuran (86%). Kecuali pupuk padat dan PPC digunakan secara berlebihan. Penggunaan yang berlebihan ini, diduga kurangnya
infonnasi dari penyuluh tentang hal tersebut sehingga mereka menggunakan hanya
30
Ketidakefisienan penggunaan pupuk dan PPC sebagai akibat masih
rendahnya pengetahuan mereka tentang ha1 tersebut. Hal ini dapat mendukung
perkembangan hama dan penyakit (Oka 1995).
Sebagian besar petani yang belurn mau melakukan pengapuran,
tampaknya berkaitan dengan persepsi mereka bahwa pengapuran tidak dapat
mengurangi serangan penyakit tersebut. Persepsi ini lahir karena dosis
pengapuran yang diberikan oleh umumnya petani yang telah mengapur masih
lebih rendah dari pada yang dianjurkan. Salah satu penyebab timbulnya penyakit
akar gada adalah kondisi tanah yang kurang bagus (kemasaman tanah tinggi).
Untuk menetralisir kondisi tanah semacam itu dapat diatasi dengan pemberian
kapur pertanian pada lahan pertanaman sekitar 2 - 4 ton per hektar. Pemberian ini bertujuan mengurangi gangguan penyakit akar gada (Suyanto 1994).
Kurangnya pengetahuan petani tentang penyebab timbulnya akar gada
dan penyebab tertularnya, juga disebabkan kurang aktifnya penyuluh dalam
menyampaikan informasi kepada petani berkaitan dengan penyakit tersebut.
Dari pengalaman yang diperoleh selama bertani tampaknya menambah
pengetahuan mereka tentang kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hama dan
penyakit. Mereka mengetahui bahwa kerusakan tanma11 kubis disebabkan oleh
ulat daun. Petani mengetahui juga bahwa keberadaan ulat daun, apabila ngengat
banyak di pertanaman. Juga mereka memahami bahwa penyebab bercak daun
bukan karena ngengat. Menurut Oka (1995) kerusakan dam pada tanaman kubis
umumnya di sebabkan larva Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis.
Gejala bercak daun disebabkan oleh jamur Alternaria brassica (Berk.)
31
spora jamur dapat disebarkan oleh agensia-agensia seperti angin, air, burung,
serangga, hewan lain serta manusia (Agrios 1996).
Ketidaktahuan petani tentang musuh alami hama (Diadegma), selain karena tidak yakin dengan adanya musuh alami di pertanaman, juga tidak
mengenal tentang serangga tersebut. Hanyalah laba-laba yang mereka golongkan
sebagai serangga yang ada di pertanaman tidak merusak tanaman. Pengenalan
musuh alami diperlukan ketekunan melihat di lapangan. Hal ini tidak mudah
dilakukan oleh umumnya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung mengingat kegiatan mereka di luar usahatani memerlukan cukup waktu. Bahkan
kadang-kadang melebihi waktu dari kegiatan usahataninya itu sendiri. Hal ini
pula bersamaan dengan belum adanya kegiatan SL-PHT di lokasi penelitian.
Pengendalian ulat kubis yang
di!akukan
oleh petani responden masihmenitik beratkan pada penggunaan pestisida dengan cara berjadwal. Penggunaan
pestisida secara berlebihan oleh hampir semua petani responden telah menyita
sebagian besar dari biaya produksi (Suyanto 1994). Juga dapat menciptakan dosis
subletal yang dapat memacu timbulnya resistensi (Oka 1995). Selain secara
ekonomis tidak menguntungkan, penggunaan pestisida yang berlebihan juga tidak
layak secara ekologis dan sosial (Darmawan 1994).
Pengendalian akar gada yang dilakukan oleh sebagian petani responden
di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung adalah dengan menggunakan kapur.
Ada pula yang memilih menempatkan persemaian di lahan yang belum pemah
ditanami kubis dengan tujuan menekan perkembangan penyakit akar gada.
Tindakan ini menunjukkan adanya perhatian sebagian petani dalam ha1
32
pengapuran dengan pertimbangan faktor sosial dan ekonomi. Mereka memilih
lebih kepada pengendalian secara kultur teknis dan mekanis dari pada mengapur.
Rendahnya pengetahuan petani responden tentang konsep PHT, selain
masih kurangnya informasi tentang ha1 tersebut juga karena belum dilakukan
pemasyarakatannya. Konsekuensinya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega
Mendung tetap mengutamakan penggunaan pestisida dalam melakukan
pengendalian hama penyakit.
Meskipun penggunaan pestisida merupakan salah satu faktor yang tidak
dapat ditinggalkan dalam mempertahankan produksi, nanlun petani responden
belum mempertimbangkan segi ekonomi dan lingkungan. Pengendalian hama
penyakit kubis yang dilakukan petani dengan menggunakan pestisida, tampaknya
terkait dengan faktor psikologis, yaitu sikap kekhawatiran petani terhadap resiko
kegagalan panen bila pertanaman tidak disemprot.
Penggunaan satu jenis pestisida kadang-kadang dilakukan petani
responden untuk mengendalikan hama penyakit. Alasan mereka, pestisida mampu
membunuh semua serangga hama. Pendapat ini berkaitan dengan kurangnya
pengetahuan mereka tentang komposisi bahan aktif dari setiap jenis pestisida. Hal
yang dapat memacu timbulnya resistensi pada Plutella xylostella yaitu dengan
penaggunaan satu jenis pestisida secara terus menerus (Oka 1995).
Pengendalian dengan cara Non-kimiawi maupun rotasi tanaman belurn
banyak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pemasyarakatan PHT yang sampai
sekarang belum diterapkan di daerah tersebut. Namun demikian ketika mendapat
33
Hanya saja informasi atau teknologi pengendalian yang dibutuhkan petani di
Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung sampai sekarang belum ada.
Untuk itu PHT melalui kegiatan SL-PHT perlu dimasyarakatkan di
kalangan petani sayuran. Meskipun dalam penerapan PHT kadang-kadang
menemui kendala, namun untuk mengatasi kendala itu diperlukan "konsep" yang
tepat. Menurut Wardoyo (1991) penerapan PHT, selain komoditi padi masih
banyak menghadapi kendala teknis dan sosial ekonomi.
Sikap
Sikap kerasionalan petani dalam penggunaan pestisida masih kurang.
Seringnya petani melakukan penyemprotan secara berjadwal menunjukkan sikap
kurang rasional. Tampaknya sikap seperti ini sudah melekat pada din petani
kubis. Secara ekonomi penyemprotan bejadwal kurang menguntungkan
(Sunarjono 1971). Sedangkan dari aspek ekologi dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan yang dapat berakibat negatif terhadap musuh alami maupun terhadap
mahluk hidup lainnya (Tnharso 1994). Untuk memperbaiki sikap petani
diperlukan pendekatan persuasif dan intensif kepada petani dan keluarganya.
Hanya sekarang ini kelompok tani yang pemah dibentuk di Kecamatan Cisarua
dan Mega Mendung, tidak iagi berfungsi. Penyuluhpun yang jumlahnya terbatas
di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung kesulitan dalam pelaksanaan tugas
penyuluhan secara mcrata kepada petani.
Kecenderungan petani responden untuk mencampur pestisida juga
menunjukkan sikap yang kelim. Mereka umurnnya berpendapat bahwa semua
jenis pestisida dapat