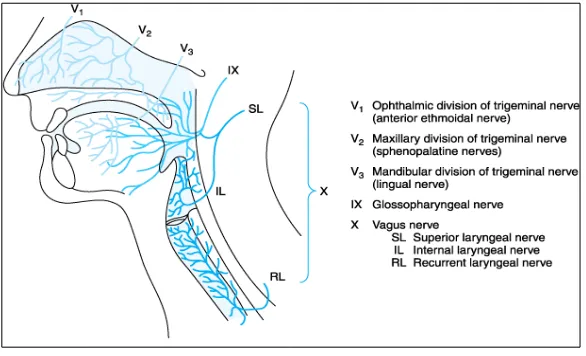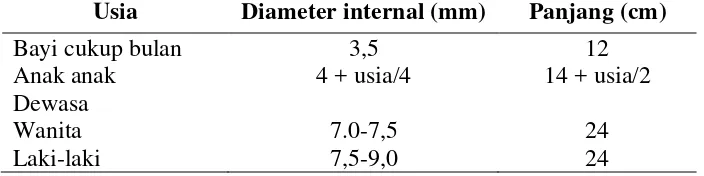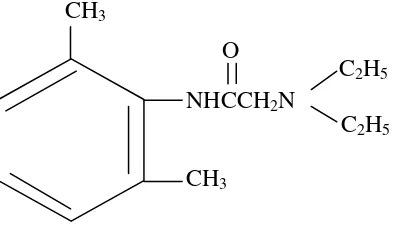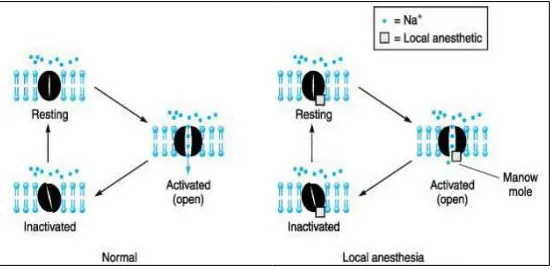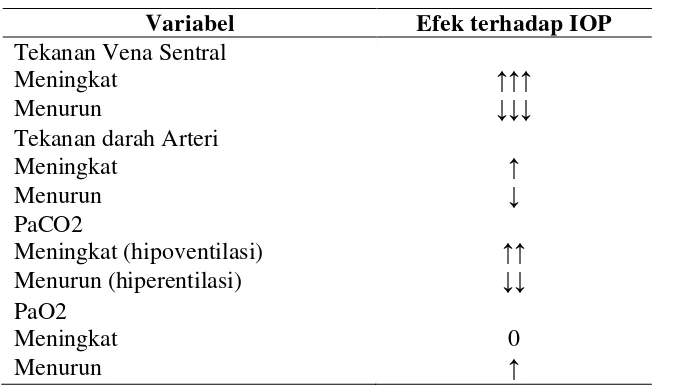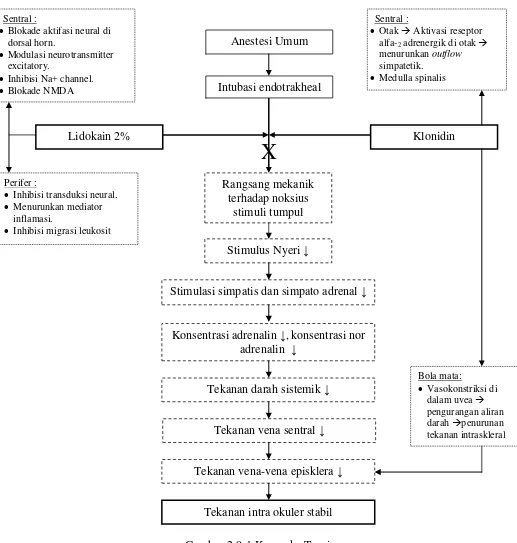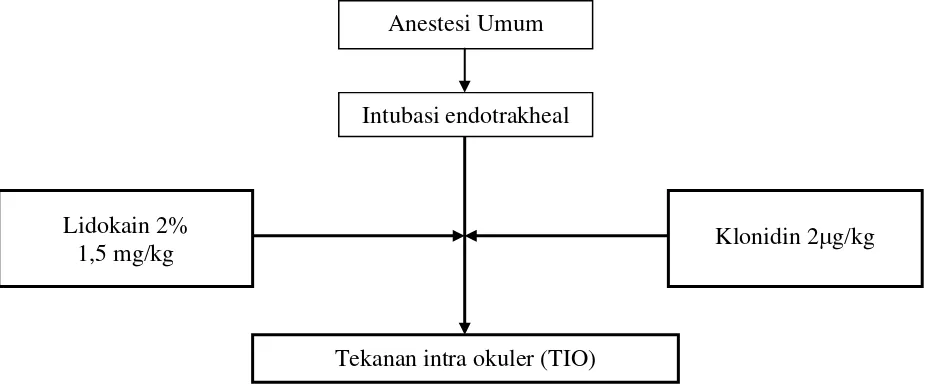TESIS
OLEH:
dr. MUHAMMAD JALALUDDIN ASSUYUTHI CHALIL
NIM: 087114013
PERBANDINGAN EFEK KLONIDIN 2
µ
g/Kg INTRAVENA DAN
LIDOKAIN 2% 1.5 mg/Kg INTRAVENA UNTUK MENCEGAH
KENAIKAN TEKANAN INTRA OKULER (TIO) SELAMA
TINDAKAN INTUBASI ENDOTRAKHEAL
PROGRAM MAGISTER KLINIK – SPESIALIS
DEPARTEMEN/SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA/
Judul : Perbandingan Efek Klonidin 2µg/Kg Intravena dan Lidokain 2% 1.5 mg/Kg Intravena untuk Mencegah Kenaikan Tekanan Intra Okuler (TIO) selama Tindakan Intubasi Endotrakheal
Nama : dr. Muhammad Jalaluddin Assuyuthi Chalil
Program Megister : Magister Kedokteran Klinik
Konsentrasi : Anestesiologi dan Terapi Intensif
Menyetujui,
Ketua Program Megister
(dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC) NIP: 19510423 197902 1 003
Ketua TKP – PPDS
(dr. H. Zainuddin Amir, SpP(K)) NIP: 19540620 198011 1 001 Pembimbing III
(Prof.dr. Aslim Sihotang, SpM (K)) NIP: 130 521 828
Pembimbing I
(Dr.dr. Nazaruddin Umar, SpAN, KNA) NIP: 19510712 198103 1 002
Pembimbing II
Telah diuji pada Tanggal : 04 Februari 2012
PANITIA PENGUJI TESIS
1. dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC NIP: 19510423 197902 1 003
2. dr. Asmin Lubis, DAF, SpAn, KAP, KMN NIP: 19530121 197902 1 001
TESIS
OLEH
dr. MUHAMMAD JALALUDDIN ASSUYUTHI CHALIL
Pembimbing I : Dr. dr. NAZARUDDIN UMAR, SpAn, KNA Pembimbing II : dr. DADIK WAHYU WIJAYA, SpAn Pembimbing III : Prof. dr. ASLIM SIHOTANG, SpM(K)
PERBANDINGAN EFEK KLONIDIN 2
µ
g/Kg INTRAVENA DAN
LIDOKAIN 2% 1.5 mg/Kg INTRAVENA UNTUK MENCEGAH
KENAIKAN TEKANAN INTRA OKULER (TIO) SELAMA
TINDAKAN INTUBASI ENDOTRAKHEAL
Tesis Ini Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kedokteran Klinik
di Bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara
PROGRAM MAGISTER KLINIK – SPESIALIS
DEPARTEMEN/SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA/
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrah maanir raahiim,
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT karena atas ridho, rahmat
dan karunia– Nya kepada saya sehingga dapat mengikuti Program Pendidikan
Dokter Spesialis I Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara serta menyusun dan menyelesaikan penelitian ini
sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan keahlian dibidang
Anestesiologi dan Terapi Intensif . Shalawat dan salam saya sampaikan kepada
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-nya Radhiallahu’anhum
ajma’in yang telah membawa perubahan dari zaman kejahiliyahan ke zaman
berilmu pengetahuan seperti saat ini.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan
penghargaan kepada:
Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahril Pasaribu, dr., DTM&H,
MSc., SpA(K), Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara,
Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, SpPD-KGEH, yang telah memberikan
kesempatan untuk mengikuti Program Pendidkan Dokter Spesialis I Anestesiologi
dan Terapi Intensif di Universitas Sumatera Utara ini. Bapak Direktur RSUP.H.
Adam Malik Medan, Direktur RSUD. Dr. Pirngadi Medan, serta Direktur RS.
Haji Medan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar dan
bekerja di lingkungan rumah sakit ini.
Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Prof.dr.Achsanuddin
Hanafie, SpAn KIC sebagai ketua Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif
FK USU/RSUP H Adam Malik Medan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada
dan Terapi Intensif. Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn KNA sebagai sekretaris
Departemen, dr. Akhyar H. Nasution, SpAn, KAKV sebagai sekretaris Program
Studi, serta dr.Ade Veronica HY, SpAn, KIC sebagai Kepala Instalasi
Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP. H. Adam Malik Medan.
Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn,
KNA sebagai pembimbing I, dr. Dadik Wahyu Wijaya, SpAn sebagai
pembimbing II, Prof. dr. Aslim Sihotang, SpM (K) sebagai pembimbing III, Dr.
Ir. Erna Mutiara, M.Kes sebagai pembimbing statistik yang banyak membantu
dalam penelitian ini khususnya dalam hal metodologi penelitian dan analisa
statistik.
Rasa hormat dan terima kasih kepada semua guru-guru kami, dr. A. Sani
P. Nasution, SpAn KIC, dr. Chairul M. Mursin, SpAn, Prof. dr. Achsanuddin
Hanafie, SpAn KIC, dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC, Dr. dr. Nazaruddin
Umar, SpAn, KNA, dr. Asmin Lubis, DAF, SpAn, KAP, KMN, dr. Akhyar H.
Nasution, SpAn KAKV, dr. Yutu Solihat, SpAn KAKV, dr. Nadi Zaini, SpAn,
Dr. Soejat Harto, SpAn, KAP, dr. Muhammad AR, SpAn, dr. Syamsul Bahri,
SpAn, dr. Walman Sitohang, SpAn, dr. Tumbur, SpAn, dr. Ade Veronica HY,
SpAn KIC, dr Tjahaya Indra Utama, dr. Nugroho K.S, SpAn, SpAn, dr. Dadik
Wahyu Wijaya, SpAn, dr. M. Ihsan, SpAn, dr. Guido M. Solihin, SpAn, dr. Qodri
FT, SpAn, KAKV, dr. Romy F Nadeak, SpAn.
Terima kasih kepada seluruh teman-teman residen Anestesiologi dan
Terapi Intensif FKUSU, terutama kepada: dr. Ferdinand AC, dr. Andri Faizal, dr.
Raka JP, dr. Mumia, dr. M. Teguh P dan dr. Haryo atas kerja sama dan bantuan
serta dorongannya selama ini. Terima kasih kepada teman-teman residen Ilmu
Bedah, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, THT, Penyakit Mata dan bidang ilmu
kedokteran lainnya yang banyak berhubungan dengan bidang Anestesiologi dan
Anestesiologi, perawat ICU dan perawat lainnya yang banyak berhubungan
dengan kami. Terima kasih juga kepada seluruh pasien dan keluarganya sebagai
“guru” kedua kami dalam menempuh pendidikan spesialis ini
Terima kasih yang tak terhingga kepada keempat orang tua saya, ayahanda
H. Chaliluddin Usman Batubara – Hj. Rahmah Tanjung, H. M. Yunus Rasiman –
Hj. Zuharni atas doa’-doa’ yang telah dipanjatkan kehadirat Allah demi
keberhasilan, keselamatan dan kemudahan saya dalam menjalani pendidikan ini,
atas kasih sayang yang tidak berkesudahan, pengorbanan yang tidak terkira, jerih
payah yang tidak terbalaskan. Semoga Allah memberikan mereka umur yang
berkah, kesehatan yang sempurna dan ketenangan di dalam hatinya. Terima
kasihku jua teruntuk istriku tercinta, dr. Yunnie Trisnawati, M.Ked (Ped), SpA
atas pengorbanan, kesabaran, kesetiaannya kepadaku selama pendidikan ini.
Semoga Allah menganugrahkan anak-anak yang sholeh kepada kami. Demikian
juga kepada adik-adikku: Ahmad Almunawar Abror, Abdul Hafiz Alkhairi, SPi,
M.Sholahuddin Al aiyubi, Am.Komp, Raudhatul Marhamah, Am.Keb, Raudhatul
Inayah, Am.Keb, Raudhatul Jannah, Yudhie Dhamanhuri, SE dan Gunawan
Pradana, SH yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil
selama saya mengikuti program pendidikan ini.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita
berserah diri dan memohon rahmat dan pengampunan. Mudah-mudahan ilmu
yang didapat, bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, agama,bangsa
dan negara.
Wassalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Medan, 04 Februari 2012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iv
DAFTAR GAMBAR ... xi
DAFTAR GRAFIK ... xiv
ABSTRAK ... xvi
ABSTRACT ... xvii
BAB 1 ... 1
PENDAHULUAN ... 1
1.1 LATAR BELAKANG ... 1
1.2 RUMUSAN MASALAH ... 8
1.3 HIPOTESIS ... 8
1.4 TUJUAN PENELITIAN ... 8
1.4.1 Tujuan umum ... 8
1.4.2 Tujuan khusus ... 8
1.5.1 Manfaat akademis ... 9
1.5.2 Manfaat praktis ... 9
BAB 2 ... 10
TINJAUAN PUSTAKA ... 10
2.1. JALAN NAFAS ... 10
2.1.1. Anatomi ... 10
2.1.2. Pipa endotrakhea (ETT) ... 12
2.1.3. Laringoskop rigid ... 13
2.1.4. Teknik laringoskopi dan intubasi ... 14
2.2. Mekanisme respon hemodinamik terhadap laringoskopi dan intubasi endotrakheal ... 18
2.3. STRESS RESPONSE ... 21
2.4. STRESS HORMONE ... 23
2.5. LIDOKAIN ... 24
2.5.1. Struktur, rumus bangun ... 24
2.5.2. Famakokinetik ... 25
2.5.4. Toksisitas Lidokain ... 27
2.6. KLONIDIN ... 29
2.6.1. Struktur,rumus bangun ... 29
2.6.2. Farmakokinetik ... 30
2.6.3. Mekanisme kerja ... 30
2.6.4. Efek samping ... 34
2.6.5. Hipertensi rebound ... 35
2.7. FISIOLOGI HUMOUR AKUEUS DAN TEKANAN INTRAOKULER (TIO) ... 36
2.7.1. Humor akueus ... 36
2.7.2. Tekanan vena episkleral ... 37
2.8. TEKANAN INTRAOKULER (TIO) ... 38
2.9. TONOMETER ... 39
2.9.1. Jenis ... 39
2.9.2. Klasifikasi ... 40
2.9.3. Tonometer schiotz ... 41
KERANGKA TEORI ... 44
BAB 3 ... 46
METODOLOGI PENELITIAN ... 46
3.1. DESAIN PENELITIAN ... 46
3.2. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN ... 46
3.2.1. Tempat ... 46
3.2.2. Waktu ... 46
3.3. POPULASI DAN SAMPEL ... 46
3.3.1. Populasi ... 46
3.3.2. Sampel ... 46
3.4. KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI ... 47
3.4.1. Kriteria Inklusi ... 47
3.4.2. Kriteria Eksklusi ... 47
3.4.3. Kreiteria drop out ... 47
3.5. BESAR SAMPEL ... 47
3.6. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA ... 48
3.6.1. Alat dan Bahan ... 48
3.7. IDENTIFIKASI VARIABEL ... 51
3.7.1. Variabel Independent ... 51
3.7.2. Variabel Dependent ... 51
3.8. RENCANA MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA ... 51
3.9. DEFINISI OPERASIONAL ... 52
3.10. MASALAH ETIKA ... 53
3.11. ALUR PENELITIAN ... 54
BAB 4 ... 55
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 55
4.1. HASIL ... 55
4.1.1. Karekteristik Pasien ... 55
4.1.2. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler Pre anesthesia antar Kelompok ... 56
4.1.3. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 1 Menit sebelum Intubasi (T-0) antar Kelompok ... 57
4.1.5. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 2 Menit
setelah Intubasi (T-2) antar Kelompok ... 58
4.1.6. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 3 Menit
setelah Intubasi (T-3) antar Kelompok ... 58
4.1.7. Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler
(TIO) antara T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan T-3 di dalam Kelompok A .. 59
4.1.8. Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler
(TIO) antara T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan T-3 di dalam Kelompok B .. 60
4.1.9. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Sitolik antar
Kelompok ... 62
4.1.10. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Diastolik antar
Kelompok ... 62
4.1.11. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan MAP antar Kelompok .... 63
4.1.12. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Laju Nadi antar Kelompok
63
4.1.13. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Intra Okuler (TIO)
antar Kelompok ... 64
BAB 5 ... 71
KESIMPULAN DAN SARAN ... 71
5.1. KESIMPULAN ... 71
5.2. SARAN ... 72
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1-1 Anatomi jalann nafas ... 10
Gambar 2.1-2 Susunan cartilago yang menyusun laring ... 11
Gambar 2.1-3 Saraf simpatis pada jalan nafas ... 12
Gambar 2.1-7 ETT dengan mandren yang dibentuk mirip stik hoki ... 15
Gambar 2.1-8 Posisi aman dan intubasi dengan blade macinthos ... 16
Gambar 2.1-9 Gambaran glotis selama laringoscopi dengan blade ... 17
Gambar 2.5-1 Rumus bangun lidokain ... 25
Gambar 2.5-2 Mekanisme kerja anestesi lokal ... 26
Gambar 2.5-3 Hubungan tanda dan gejala anestesi lokal dengan ... 28
Gambar 2.6-1 Rumus bangun klonidin ... 29
Gambar 2.6-2 Respon yang dapat dimediasi oleh reseptor –reseptor ... 31
Gambar 2.9-1 Tonometer Schiotz ... 41
Gambar 2.9-1 Kerangka Teori ... 44
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1-1. Prosedur operasi mata terbuka ... 3
Tabel 2.1-2 Patokan ukuran ETT ... 13
Tabel 2.1-3 Komplikasi dari intubasi ... 18
Tabel 2.8-1 Efek kardiopulmonal terhadap TIO ... 38
Tabel 2.9-1 Konversi tonometer Schiotz ... 43
Tabel 4.1-1 Karekteristik Data Penelitian ... 55
Tabel 4.1-2 Uji Shapiro-Wilk ... 56
Tabel 4.1-3 Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler Pre Anesthesia ... 56
Tabel 4.1-4 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 1 Menit sebelum Intubasi (T-0) antar Kelompok ... 57
Tabel 4.1-5 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 1 Menit setelah Intubasi (T-1) antar Kelompok ... 57
Tabel 4.1-6 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 2 Menit setelah Intubasi (T-2) antar Kelompok ... 58
Tabel 4.1-7 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 3 Menit setelah Intubasi (T-3) antar Kelompok ... 58
Tabel 4.1-8 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-0, dan T-1 di dalam Kelompok A .. 59
Tabel 4.1-9 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-2, dan T-3 di dalam Kelompok A .. 60
Tabel 4.1-10 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-2, dan T-3 di dalam Kelompok B .. 60
Tabel 4.1-11 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-2, dan T-3 di dalam Kelompok B .. 61
Tabel 4.1-12 Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Sitolik antar Kelompok ... 62
Tabel 4.1-14 Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan MAP antar Kelompok ... 63
Tabel 4.1-15 Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Laju Nadi antar Kelompok ... 63
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI ... 80
LAMPIRAN 2 : JADWAL TAHAPAN PENELITIAN ... 81
LAMPIRAN 3 : PENJELASAN MENGENAI PENELITIAN ... 82
LAMPIRAN 4 : LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN . 84 LAMPIRAN 5 : LEMBARAN OBSERVASI PERIOPERATIF PASIEN ... 85
LAMPIRAN 6 : RANDOMISASI BLOK SAMPEL DAN DAFTAR SAMPEL ... 86
LAMPIRAN 7 : SURAT PERSETUJUAN KOMISI ETIK ... 87
ABSTRAK
Latar Belakang. Intubasi endotrakheal merupakan tindakan yang rutin dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani operasi intra okuler dengan anestesi umum untuk menjaga patensi jalan nafas, memberikan akses pembedahan yang lebih baik dan memfasilitasi
ventilasi paru untuk mengendalikan PaCO2
Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan obat alternatif dalam upaya pencegahan kenaikan TIO selama tindakan intubasi endotrakheal.
. Akan tetapi, tindakan intubasi itu sendiri dapat menimbulkan takikardi, hipertensi, dan peningkatan tekanan intra okuler (TIO). Keadaan ini dapat membahayakan pasien-pasien yang disertai hipertensi dan penyakit
kardiovaskular, glaukoma dan penetrating eye injury. Setiap faktor yang dapat
meningkatkan TIO akan menyebabkan drainase humor aqueous atau pengeluaran humor
vitreous melalui luka dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius berupa kerusakan fungsi penglihatan secara permanen.
Metode. Setelah mendapat persetujuan dari komite etik penelitian bidang kesehatan Fakultas Kedokteran USU, penelitian dilakukan dengan desain uji klinis acak tersamar ganda terhadap 40 pasien bedah elektif dengan intubasi endotrakheal, berusia antara 18-40 tahun, dengan status fisik ASA 1 atau 2. Pasien dibagi menjadi 2 kelompok (A dan B), masing-masing 20 orang. Kelompok A diberikan Klonidin 2µg/kgBB intravena 30 menit sebelum intubasi endotrakheal, sedangkan kelompok B diberikan Lidokain 2% 1,5 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum tindakan. Semua pasien dipremedikasi dengan midazolam 0,1 mg/kgBB intravena dan pethidin 1 mg/kgBB intravena 5 menit sebelum intubasi. Induksi dilakukan dengan menggunakan propofol 2 mg/kgBB intravena dan rokuronium 1 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum intubasi. Pengukuran profil hemodinamik (tekanan darah sistolik dan diastolik, tekanan arteri rata-rata, laju nadi) dan TIO dilakukan dalam 4 urutan waktu, yaitu sebelum tindakan anestesi (T-pre), 1 menit sebelum intubasi (T-0), 1 menit setelah intubasi (T-1), serta pada menit ke-2 dan ke-3 setelah intubasi (T-2 dan T-3). Pengukuran TIO dilakukan pada mata kanan dengan
Tonometri Schiotz. Uji hipotesis dilakukan dengan Mann whitney test dengan p<0,05
dianggap bermakna.
Hasil. Data karekteristik pasien tidak didapatkan perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok penelitian. Baik pada kelompok A maupun B, didapatkan penurunan profil hemodinamik dan TIO yang bermakna antara saat T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan
T-3 (p<0,05). Namun secara statistik, penurunan tersebut tidak menunjukkan perbedaan
yang bermakna antara kedua kelompok penelitian (p>0,05).
Kesimpulan. Kedua obat ini mempunyai kemampuan yang sama dalam menumpulkan respon hemodinamik dan menurunkan TIO, serta mencegah kenaikan TIO akibat tindakan intubasi endotrakheal.
ABSTRACT
Background. Endotracheal intubation is routinely performed during general anaesthesia in patients undergoing intraocular surgery to secure a clear airway, allowing good
surgical access and facilitating ventilation of the lungs to control of PaCO2
Aim. The aim of this study is to found alternative medicine in order to prevent the increase of intraocular pressure (IOP) during endotracheal intubation.
. However,
intubation is associated with tachycardia, hypertension and an increase in intraocular
pressure (IOP). Such situations are likely to be harmful to the patients with hypertension,
cardiovascular disease, glaucoma, and penetrating eye injury. Any factor that may increases IOP will tend to cause drainage of aqueous humour or extrusion of the vitreous humour through the wound. The latter is a serious complication that can permanently damage vision.
Method. After approval by the local ethics committee, a double blind and randomized clinical trial on 40 patients of ASA 1 or 2 aged 18-40 years who had undergone elective surgery using endotracheal intubation was conducted. The patients were divided into two groups (group A, n=20, and group B, n=20). Group A was administered clonidine
2µg.kg-1 IV 30 minute prior to endotracheal intubation, meanwhile group B was
administered lidocain 2% 1,5 mg.kg-1 IV 2 minutes before intubation. All of the patients
had received midazolam 0,1 mg.kg-1 IV and pethidine 1 mg.kg-1 IV as pre-medication 5
minutes before intubation. General anaesthesia was induced 2 minutes before intubation
with propofol 2 mg.kg-1 IV followed by rocuronium 1 mg.kg-1
Result. Patient characteristics data showed no differences between two groups. Hemodynamic profile and IOP within both groups A and B was showed significance
reduction between T-pre and T-0, T-1, T-2 and T-3 (p<0,05). But statistically, the decline
did not show significant differences between treatment groups (p>0,05).
IV to facilitate tracheal intubation. Hemodynamic profile (systolic and diastolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate) and IOP were measured on the right eye using the Schioetz tonometer in 4 sequences of time, before pre-medication (T-pre), 1 minute before intubation (0), and 1, 2, and 3 minutes after endotracheal intubation (1, 2, and T-3). Non-parametric data was compared between group by Mann Whitney test. Statistical significance was assumed if p<0,05.
Conclusion. Both drugs have the same ability in blunting the hemodynamic response and lowering the IOP, and preventing the increase in IOP caused by endotracheal intubation.
ABSTRAK
Latar Belakang. Intubasi endotrakheal merupakan tindakan yang rutin dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani operasi intra okuler dengan anestesi umum untuk menjaga patensi jalan nafas, memberikan akses pembedahan yang lebih baik dan memfasilitasi
ventilasi paru untuk mengendalikan PaCO2
Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan obat alternatif dalam upaya pencegahan kenaikan TIO selama tindakan intubasi endotrakheal.
. Akan tetapi, tindakan intubasi itu sendiri dapat menimbulkan takikardi, hipertensi, dan peningkatan tekanan intra okuler (TIO). Keadaan ini dapat membahayakan pasien-pasien yang disertai hipertensi dan penyakit
kardiovaskular, glaukoma dan penetrating eye injury. Setiap faktor yang dapat
meningkatkan TIO akan menyebabkan drainase humor aqueous atau pengeluaran humor
vitreous melalui luka dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius berupa kerusakan fungsi penglihatan secara permanen.
Metode. Setelah mendapat persetujuan dari komite etik penelitian bidang kesehatan Fakultas Kedokteran USU, penelitian dilakukan dengan desain uji klinis acak tersamar ganda terhadap 40 pasien bedah elektif dengan intubasi endotrakheal, berusia antara 18-40 tahun, dengan status fisik ASA 1 atau 2. Pasien dibagi menjadi 2 kelompok (A dan B), masing-masing 20 orang. Kelompok A diberikan Klonidin 2µg/kgBB intravena 30 menit sebelum intubasi endotrakheal, sedangkan kelompok B diberikan Lidokain 2% 1,5 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum tindakan. Semua pasien dipremedikasi dengan midazolam 0,1 mg/kgBB intravena dan pethidin 1 mg/kgBB intravena 5 menit sebelum intubasi. Induksi dilakukan dengan menggunakan propofol 2 mg/kgBB intravena dan rokuronium 1 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum intubasi. Pengukuran profil hemodinamik (tekanan darah sistolik dan diastolik, tekanan arteri rata-rata, laju nadi) dan TIO dilakukan dalam 4 urutan waktu, yaitu sebelum tindakan anestesi (T-pre), 1 menit sebelum intubasi (T-0), 1 menit setelah intubasi (T-1), serta pada menit ke-2 dan ke-3 setelah intubasi (T-2 dan T-3). Pengukuran TIO dilakukan pada mata kanan dengan
Tonometri Schiotz. Uji hipotesis dilakukan dengan Mann whitney test dengan p<0,05
dianggap bermakna.
Hasil. Data karekteristik pasien tidak didapatkan perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok penelitian. Baik pada kelompok A maupun B, didapatkan penurunan profil hemodinamik dan TIO yang bermakna antara saat T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan
T-3 (p<0,05). Namun secara statistik, penurunan tersebut tidak menunjukkan perbedaan
yang bermakna antara kedua kelompok penelitian (p>0,05).
Kesimpulan. Kedua obat ini mempunyai kemampuan yang sama dalam menumpulkan respon hemodinamik dan menurunkan TIO, serta mencegah kenaikan TIO akibat tindakan intubasi endotrakheal.
ABSTRACT
Background. Endotracheal intubation is routinely performed during general anaesthesia in patients undergoing intraocular surgery to secure a clear airway, allowing good
surgical access and facilitating ventilation of the lungs to control of PaCO2
Aim. The aim of this study is to found alternative medicine in order to prevent the increase of intraocular pressure (IOP) during endotracheal intubation.
. However,
intubation is associated with tachycardia, hypertension and an increase in intraocular
pressure (IOP). Such situations are likely to be harmful to the patients with hypertension,
cardiovascular disease, glaucoma, and penetrating eye injury. Any factor that may increases IOP will tend to cause drainage of aqueous humour or extrusion of the vitreous humour through the wound. The latter is a serious complication that can permanently damage vision.
Method. After approval by the local ethics committee, a double blind and randomized clinical trial on 40 patients of ASA 1 or 2 aged 18-40 years who had undergone elective surgery using endotracheal intubation was conducted. The patients were divided into two groups (group A, n=20, and group B, n=20). Group A was administered clonidine
2µg.kg-1 IV 30 minute prior to endotracheal intubation, meanwhile group B was
administered lidocain 2% 1,5 mg.kg-1 IV 2 minutes before intubation. All of the patients
had received midazolam 0,1 mg.kg-1 IV and pethidine 1 mg.kg-1 IV as pre-medication 5
minutes before intubation. General anaesthesia was induced 2 minutes before intubation
with propofol 2 mg.kg-1 IV followed by rocuronium 1 mg.kg-1
Result. Patient characteristics data showed no differences between two groups. Hemodynamic profile and IOP within both groups A and B was showed significance
reduction between T-pre and T-0, T-1, T-2 and T-3 (p<0,05). But statistically, the decline
did not show significant differences between treatment groups (p>0,05).
IV to facilitate tracheal intubation. Hemodynamic profile (systolic and diastolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate) and IOP were measured on the right eye using the Schioetz tonometer in 4 sequences of time, before pre-medication (T-pre), 1 minute before intubation (0), and 1, 2, and 3 minutes after endotracheal intubation (1, 2, and T-3). Non-parametric data was compared between group by Mann Whitney test. Statistical significance was assumed if p<0,05.
Conclusion. Both drugs have the same ability in blunting the hemodynamic response and lowering the IOP, and preventing the increase in IOP caused by endotracheal intubation.
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pasien-pasien mata umumnya memiliki risiko khusus terhadap tindakan
anestesi. Pasien biasanya datang dengan umur yang ekstrim, sangat muda atau
justru sangat tua. Oleh karenanya, kondisi medis yang mendasari keadaan pasien
tersebut dapat memperberat risiko anestesi, demikian juga halnya respon pasien
terhadap obat-obat anestesi yang diberikan. Seringnya, pasien-pasien mata yang
mendapat pengobatan sehubugan dengan penyakit mata yang mereka derita dapat
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatalaksana anestesi. Terdapat
variasi data mortalitas yang berkaitan dengan tindakan anestesi pada
operasi-operasi mata sejak tahun 1960 sampai 1970-an, yaitu berkisar antara 0.06% –
0.16% tanpa membedakan apakah pasien mendapat tindakan anestesi lokal atau
umum.1 Quigley pada tahun 1974 menyatakan bahwa morbiditas yang berkaitan
dengan tindakan anestesi pada pembedahan mata termasuk di dalamnya mual,
muntah, perdarahan retrobulbar, perforasi dan hilangnya humor vitreous.
Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi mata merupakan hal yang
penting bagi seorang dokter anestesi, diantaranya adalah pemahaman tentang
tekanan intra okuler (TIO) serta bagaimana tekanan tersebut dapat dipengaruhi
oleh beberapa penyakit dan obat-obatan, termasuk obat-obat yang digunakan
dalam tindakan anestesi.
2
3
Karena, salah satu tujuan penting dalam tatalaksana
anestesi selama tindakan pembedahan mata adalah mengupayakan agar TIO tetap
terkendali. Terutama sekali pada tindakan pembedahan mata sistem terbuka,
dimana variasi perubahan TIO yang besar selama pembedahan dapat berakibat
terjadinya kerusakan pada fungsi penglihatan paska operasi. Pada pasien-pasien
seperti ini, tindakan-tindakan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya suatu
peningkatan TIO, termasuk stres mekanik ataupun farmakologik, haruslah
Usaha-usaha untuk mengendalikan TIO dalam rentang nilai yang fisiologis
(berkisar antara 10-20 mmHg) merupakan suatu keharusan untuk
mempertahankan kondisi anatomis yang diperlukan untuk fungsi refraksi dan
penglihatan yang optimal. Pentingnya TIO pada seorang dokter anestesi adalah
sebagai berikut:
1) Pasien dengan peningkatan TIO yang terjadi secara akut atau kronis
yang menjalani tindakan pembedahan korektif.
2) Pasien dengan peningkatan TIO kronik yang menjalani tindakan
pembedahan non-ophthalmic.
3) Pasien dengan tindakan pembedahan bola mata terbuka akibat adanya
penetrating eye injury.
4) Beberpa obat dan tindakan yang digunakan dalam anestesi yang dapat
mempengaruhi TIO.
Tekanan intra okuler membantu untuk menjaga bentuk dan organel di dalam
bola mata. Variasi tekanan yang temporer umumnya dapat ditoleransi oleh mata
normal. Kedipan mata meningkatkan tekanan intra okuler sebanyak 5 mmHg
hingga dapat mencapai 26 mmHg. Ketika bola mata terbuka selama tindakan
operasi (tabel1.1-1) atau setelah perforasi traumatik, tekanan intra okuler akan
mendekati tekanan atmosfer. Beberapa faktor yang normalnya meningkatkan
tekanan intra okuler dapat mengakibatkan terjadinya penurunan volume intra
okuler yang disebabkan oleh mengalirnya humor aqueous atau keluarnya humor
vitreous melalui luka yang ada. Penyebab terakhir merupakan komplikasi serius
yang dapat memperburuk penglihatan secara permanent. 5
Intubasi trakhea, merupakan tindakan yang rutin dilakukan pada
pasien-pasien yang menjalani operasi intra okuler dengan anestesi umum untuk menjaga
patensi jalan nafas, memberikan akses pembedahan yang lebih baik dan
memfasilitasi ventilasi paru untuk mengendalikan PaCO 6
intubasi itu sendiri mempunyai efek terhadap terjadinya takikardia, hipertensi,
peningkatan TIO, dan tekanan intra kranial.8,9
Tabel 1.1-1. Prosedur operasi mata terbuka
Ekstraksi Katarak
6
Perbaikan laserasi kornea
Transplantasi kornea (penetrasi keratoplasti) Iridektomi perifer
Pengambilan benda asing Perbaikan ruptur bola mata
Implantasi lensa intraokuler sekunder
Trabekulektomi (dan prosedur penyaringan lain) Vitrektomi (anterior dan posterior)
Perbaikan kebocoran dari luka
Keadaan tersebut dapat membahayakan pasien-pasien yang disertai
hipertensi dan penyakit kardiovaskuler10, space-occupying lesion (SOL) di intra
kranial, glaukoma, dan penetrating eye injury.1,9,11 Setiap faktor yang dapat
meningkatkan TIO akan menyebabkan drainase humor aqueous atau pengeluaran
humor vitreous melalui luka dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius
berupa kerusakan fungsi penglihatan secara permanen.12
Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa peningkatan TIO yang
signifikan dapat terjadi sebagai akibat tindakan laringoskopi dan intubasi.13
Respon hemodinamik terhadap tindakan laringoskopi dan intubasi tampaknya
mempunyai efek yang lebih signifikan terhadap peningkatan TIO dari pada akibat
pemberian suksinilkolin.12-18 Laringoskopi dan intubasi akan menyebabkan
kenaikan TIO sebesar 10-20 mmHg.5,19 Muntah, batuk dan bucking pada tindakan
intubasi endotrakheal menyebabkan peningkatan TIO yang dramatis mencapai
30-40 mmHg.13,20 Hal ini mungkin berkaitan dengan respon simpatis kardiovaskuler
akibat intubasi trakhea.19 Fluktuasi yang kecil dari tekanan darah arteri juga
ketika terjadi hipertensi dan akan turun secara signifikan apabila terjadi hipotensi.
Di lain pihak, perubahan tekanan vena juga memiliki pengaruh yang besar
terhadap TIO. Muntah, batuk, bucking dan maneuver valsava, dapat
mengakibatkan terbendungnya sistem vena, yang akan mengganggu outflow
humor aqueous dan meningkatkan volume darah koroidal.13 Peningkatan TIO
terjadi segera setelah intubasi trakhea (dalam 20 detik)21 dan akan menghilang
setelah 1 atau 2 menit.21- 23
Dikatakan bahwa, respon hemodinamik akibat laringoskopi dan intubasi
trakhea mencerminkan suatu peningkatan aktivitas simpatoadrenal akibat
stimulasi pada orofaringeal dan laringotrakheal.24,25 Reaksi ini tidak dapat dicegah
dengan pemberian premedikasi rutin.26,27 Shribman et al, telah menunjukkan
bahwa ujung afferent utama terhadap stimulus yang bertanggung jawab pada
respon adrenergik mungkin adalah struktur supraglotik.28 Stimulasi adrenergik
dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang berakibat pada
peningkatan tekanan vena sentral (hubungannya lebih dekat terhadap kenaikan
TIO dari pada terhadap tekanan darah arteri). Stimulasi adrenergik juga
meningkatkan tahanan aliran humor aqueous antara bilik depan dan kanal
Schlemm’s.29
Bharti N dkk (2008), melakukan penelitian terhadap 60 pasien ASA 1 atau
2, membandingkan perubahan TIO antara pasien yang diintubasi dengan ILMA
(intubating laryngeal mask airway) dengan yang diintubasi secara konvensional
menggunakan laringoskop. Pada akhir penelitian diperoleh bahwa terjadi
peningkatan TIO yang bermakna dari nilai baseline dibandingkan setelah tindakan
intubasi trakhea, yaitu dari 7,2+1,4 menjadi 16,8+5,3 mmHg (p<0,01) dan tidak
kembali ke level preintubasi selama 5 menit. Tekanan arteri rata-rata juga
menunjukkan peningkatan yang bermakna setelah intubasi trakhea, yaitu dari nilai
preintubasi selama 5 menit. Sedangkan laju jantung pada kedua kelompok
sama-sama mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai preintubasi (p<0,05).9
Banyak cara telah dicoba untuk mengurangi insidensi dan keparahan yang
ditimbul akibat respon hemodinamik selama tindakan intubasi trakhea, seperti
penggunaan opioid30, zat anestesi lokal baik secara topikal31 ataupun diberikan
secara intravena32-34, obat penghambat α- atau β-adrenergik35,36,
angiotensin-converting enzyme inhibitor, klonidin, obat-obat vasodilator seperti sodium
nitroprusside, prostaglandin E1
Mahajan RP et al (1988)14, melaporkan dalam hasil penelitiannya tentang
nitrogliserin (NTG) intranasal dan TIO selama anestesi umum. Mereka melakukan
dua penelitian yang terpisah mengenai efek NTG terhadap TIO. Dalam penelitian
pertama, 12 orang dewasa PS-ASA 1 mendapat 3 ml larutan NTG (2mg/3ml)
yang diberikan secara intranasal selama steady-state anestesi umum, diperoleh
penurunan TIO yang bermakna bersama dengan turunnya tekanan darah arteri dan
vena sentral. Pada penelitian kedua, terhadap 30 orang pasien yang terbagi
menjadi 2 kelompok secara random tersamar ganda. Kelompok 1 mendapat
normal salin 3 ml dan kelompok 2 mendapat NTG 2mg/3ml, keduanya diberikan
secara intranasal 2 menit sebelum induksi. Induksi anestesi dilakukan dengan
thiopental lalu diikuti pemberian suksinilkolin 1,5mg/kgBB. Diakhir penelitian
didapat bahwa pasien pada kelompok 1 mengalami kenaikan TIO yang bermakna
setelah pemberian suksinilkolin. Sedangkan pada kelompok 2, peningkatan TIO
setelh pemberian suksinilkolin dan setelah intubasi trakhea secara signifikan lebih
rendah dibandingkan dengan kelompok 1.
dan obat-obat calcium channel-blocking.37
Warner et al (1989)38, melakukan penelitian tentang efek lidokain,
suksinilkolin dan intubasi trakhea terhadap TIO pada anak-anak dengan PS-ASA
1 berusia antara 18 bulan sampai 7 tahun yang menjalani koreksi strabismus yang
dianestesi dengan halotan dan nitrous oksid (NO). Dalam penelitian tersebut
sebelum laringoskopi, menyebabkan kenaikan TIO yang tidak bermakna antara
saat segera sebelum dengan saat setelah intubasi trakhea.
Zimmerman AA et al (1996)39, melakukan penelitian terhadap 60 orang
pasien PS-ASA I atau II yang dirandom, bertujuan untuk menilai apakah
kombinasi propofol dan alfentanil dapat mencegah peningkatan TIO akibat
pemberian suksinilkolin dan intubasi endotrakhea selama tindakan rapid sequence induction (RSI). Mereka menyimpulkan bahwa kombinasi propofol dan alfentanil
mencegah kenaikan TIO akibat pemberian suksinilkolin dan RSI.
Mowafi HA et al (2003)40, melaporkan hasil penelitiannya tentang
perubahan TIO selama tindakan laparoskopi pada pasien-pasien yang dianestesi
dengan propofol total intravenous anesthesia (TIVA) dibandingkan dengan
anestesi inhalasi isofluran. Setelah melakukan penelitian terhadap 40 orang wanita
dewasa PS-ASA I atau II untuk operasi laparoskopi ginekologi elektif, mereka
menyimpulkan bahwa propofol TIVA dapat menurunkan TIO selama laparoskopi
dan mungkin merupakan obat pilihan bila pengendalian TIO selama operasi
diperlukan.
Georgiou M et al (2002)12, telah melakukan penelitian tentang sufentanil
atau klonidin untuk meredam kenaikan TIO selama RSI. Sebanyak 32 orang
pasien dengan PS-ASA I-III yang telah terjadwal untuk tindakan operasi
non-ophthalmik ikut dalam penelitian yang bersifat prospektif, tersamar ganda dan
teracak. Diakhir peneltian mereka menyimpulkan bahwa sufentanil 0,05µg/kgBB
intravena dapat menghambat kenaikan TIO yang berhubungan dengan pemberian
suksinilkolin selama RSI. Dilain pihak, klonidin gagal menunjukkan efek yang
sama. Hal ini mungkin disebabkan efek puncak klonidin (tercapai setelah 30-60
menit) yang belum adekuat saat dilakukannya RSI.
pada pasien-pasien yang menjalani operasi non-ophthalmic. Tiga puluh dua pasien
usia 16-60 tahun, PS-ASA I-II yang telah terjadwal untuk tindakan operasi
non-ophthalmic ikut dalam penelitian ini. Mereka menyimpulkan bahwa anestesi
umum dengan remifentanil sebagai analgetik akan menurunkan TIO.
Moeini HA et al (2006)19, telah melaporkan hasil peneltiannya mengenai
efek lidokain dan sufentanil dalam mencegah kenaikan tekanan intra okuluer
akibat suksinilkolin dan intubasi endotrakhea. Sebanyak 210 pasien ikut
berpartisipasi dalam penelitian yang bersifat uji klinis tersamar ganda ini. Dari
hasil penelitian disimpulkan bahwa premedikasi dengan lidokain dan sufentanil
tidak hanya mencegah kenaikan TIO akibat pemberian suksinilkolin, laringoskopi
dan intubasi trakhea, akan tetapi juga menurunkan TIO, sehingga memberikan
kondisi yang lebih baik selama pembedahan.
Yavascaoglu B et al (2007)41, telah melakukan penelitian tentang
perbandingan esmolol dan deksmedetomidin untuk melemahkan TIO dan respon
hemodinamik terhadap laringoskopi dan intubasi trakhea, yang melibatkan 60
pasien PS-ASA I-II, berusia 18-60 tahun, yang menjalani tindakan pembedahan
non-ophthalmic elektif. Pada akhir penelitian mereka menyimpulkan bahwa
deksmedetomidin lebih efektif dari pada esmolol dalam mencegah respon
hemodinamik dan kenaikan TIO pada saat intubasi trakhea.
Dari uraian latar belakang penelitian tadi, maka dapat ditarik beberapa
permasalahan yang menyebabkan peneltian ini penting untuk dilakukan, yaitu:
a) Sebagai seorang ahli anestesi harus mampu melakukan managemen
anestesia terhadap pasien-pasien dengan trauma okuli terbuka,
pasien-pasien yang memerlukan pencegahan kenaikan TIO selama
pembedahan mata, pasien dengan gangguan TIO yang akan
menjalani tindakan pembedahan non-ophthalmic dengan anestesi
b) Tindakan laringoskopi dan intubasi trakhea dapat menyebabkan
teraktivasinya simpatoadrenal akibat stimulasi pada orofaringeal dan
laringotrakheal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan
TIO
c) Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, belum ada
yang membandingkan efek antara klonidin dosis 0,2µg/kgBB
intravena dengan lidokain 2% dosis 1,5mg/kgBB intravena dalam
upaya pencegahan kenaikan TIO saat laringoskopi dan intubasi
trakhea.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Apakah ada perbedaan efek klonidin 2µg/kg intravena dan lidokain 2% 1.5
mg/kg intravena untuk mencegah kenaikan tekanan intra okuler selama tindakan
intubasi endotrakheal.
1.3 HIPOTESIS
Ada perbedaan efek klonidin 2µg/kg intravena dan lidokain 2% 1.5 mg/kg
intravena untuk mencegah kenaikan tekanan intra okuler selama tindakan intubasi
endotrakheal.
1.4 TUJUAN PENELITIAN
1.4.1 Tujuan umum
Untuk memperoleh obat alternatif dalam mencegah kenaikan tekanan intra
okuler selama tindakan intubasi endotrakheal.
1.4.2 Tujuan khusus
a. Untuk mengetahui efek klonidin 2µg/kg intravena dalam mencegah
b. Untuk mengetahui efek lidokain 2% 1.5 mg/kg intravena dalam mencegah
kenaikan tekanan intra okuler selama tindakan intubasi endotrakheal
c. Untuk mengetahui perbandingan efek kedua obat, sehingga diketahui obat
mana yang lebih efektif dalam mencegah kenaikan tekanan intra okuler
selama tindakan intubasi endotrakheal
1.5 MANFAAT PENELITIAN
1.5.1 Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan
tambahan dalam penelitian lanjutan tentang usaha-usaha pencegahan kenaikan
tekanan intra okuler selama tindakan intubasi endotrakheal.
1.5.2 Manfaat praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam
pemberian adjuvan sebagai usaha pencegahan kenaikan tekanan intra okuler
selama tindakan intubasi endotrakheal pada keadaan berikut:
a. Pasien-pasien dengan tekanan intra okuler tinggi yang akan menjalani
tindakan pembedahan non-ophthalmik
b. Pasien-pasien dengan cedera bola mata terbuka yang memerlukan
tindakan intubasi endotrakheal selama pembedahan
c. Pasien-pasien yang memerlukan tindakan intubasi endotrakheal selama
pembedahan bola mata, baik elektif maupun emergensi, yang
memerlukan pengendalian tekanan intra okuler.
d. Pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi yang memerlukan tindakan
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.JALAN NAFAS
2.1.1. Anatomi
Ada dua gerbang untuk masuk ke jalan nafas pada manusia yaitu hidung
yang menuju nasofaring (pars nasalis), dan mulut yang menuju orofaring (pars
oralis). Kedua bagian ini di pisahkan oleh palatum pada bagian anteriornya, tapi
kemudian bergabung di bagian posterior dalam faring (gambar 2.1.1-1).
Gambar 2.1-1 Anatomi jalann nafas6
Faring berbentuk U dengan struktur fibromuskuler yang memanjang dari
dasar tengkorak menuju kartilago krikoid pada jalan masuk ke esofagus. Bagian
depannya terbuka ke dalam rongga hidung, mulut, laring, nasofaring, orofaring
dan laringofaring (pars laryngeal). Nasofaring dipisahkan dari orofaring oleh garis
imaginasi mengarah ke posterior. Pada dasar lidah, secara fungsional epiglotis
memisahkan orofaring dari laringofaring (atau hipofaring). Epiglotis mencegah
Laring adalah suatu rangka kartilago yang diikat oleh ligamen dan otot. Laring
disusun oleh 9 kartilago (gambar 2.1-2) : tiroid, krikoid, epiglotis, dan (sepasang)
aritenoid, kornikulata dan kuneiforme.
Gambar 2.1-2 Susunan cartilago yang menyusun laring6
Saraf sensoris dari saluran nafas atas berasal dari saraf kranial (gambar
2.1-3). Membran mukosa dari hidung bagian anterior dipersarafi oleh divisi
ophthalmic (V1) saraf trigeminal (saraf ethmoidalis anterior) dan di bagian
posterior oleh divisi maxila (V2) (saraf sphenopalatina). Saraf palatinus mendapat
serabut saraf sensori dari saraf trigeminus (V) untuk mempersarafi permukaan
superior dan inferior dari palatum molle dan palatum durum. Saraf lingual
(cabang dari saraf divisi mandibula [V3
Cabang dari saraf fasialis (VII) dan saraf glosofaringeal untuk sensasi rasa
di daerah tersebut. Saraf glosofaringeal juga mempersarafi atap dari faring, tonsil
dan bagian dalam palatum molle. Saraf vagus (saraf kranial ke 10) untuk sensasi
jalan nafas dibawah epiglotis. Saraf laringeal superior yang merupakan cabang
dari saraf vagus dibagi menjadi saraf laringeus eksternal yang bersifat motoris dan ] saraf trigeminal) dan saraf glosofaringeal
(saraf kranial yang ke 9) untuk sensasi umum pada dua pertiga bagian anterior dan
saraf laringeus internal yang bersifat sensoris untuk laring antara epiglotis dan pita
suara. Cabang vagus yang lainnya yaitu saraf laringeal rekuren, mempersarafi
laring dibawah pita suara dan trakhea6
Gambar 2.1-3 Saraf simpatis pada jalan nafas6
2.1.2. Pipa endotrakhea (ETT)
Endotracheal tube (ETT) digunakan untuk mengalirkan gas anestesi
langsung ke dalam trakhea dan mengizinkan untuk kontrol ventilasi dan
oksigenasi. Pabrik menentukan standar ETT (American National Standards for
Anesthetic Equipment; ANSI Z-79). ETT kebanyakan terbuat dari
polyvinylchloride. Pada masa lalu, ETT diberi tanda “IT” atau “Z-79” untuk
indikasi ini telah dicoba untuk memastikan tidak beracun. Bentuk dan kekakuan
dari ETT dapat dirubah dengan pemasangan mandren. Ujung pipa diruncingkan
untuk membantu penglihatan dan pemasangan melalui pita suara. Pipa Murphy
memiliki sebuah lubang (mata Murphy) untuk mengurangi resiko sumbatan pada
bagian distal tube bila menempel dengan carina atau trakhea. Tahanan aliran
udara terutama tergantung dari diameter pipa, tapi ini juga dipengaruhi oleh
panjang pipa dan lengkungannya. Ukuran ETT biasanya dipola dalam milimeter
untuk diameter internal atau yang tidak umum dalam scala Prancis (diameter
kompromi antara memaksimalkan flow dengan pipa ukuran besar dan
meminimalkan trauma jalan nafas dengan ukuran pipa yang kecil.6
Kebanyakan ETT dewasa memiliki sistem pengembungan balon yang terdiri
dari katup, balon petunjuk (pilot balloon), pipa pengembangkan balon, dan balon
(cuff). Katup mencegah udara keluar setelah balon dikembungkan. Balon petunjuk
memberikan petunjuk kasar dari balon yang digembungkan. Inflating tube
dihubungkan dengan klep. Dengan membuat trakhea yang rapat, balon ETT
mengijinkan dilakukannya ventilasi tekanan positif dan mengurangi kemungkinan
aspirasi. Pipa yang tidak berbalon biasanya digunakan untuk anak-anak untuk
meminimalkan resiko dari cedera karena tekanan dan post intubation croup.6
Tabel 2.1-1 Patokan ukuran ETT
Usia Diameter internal (mm) Panjang (cm)
Bayi cukup bulan 3,5 12
Anak anak 4 + usia/4 14 + usia/2
Dewasa
Wanita 7.0-7,5 24
Laki-laki 7,5-9,0 24
2.1.3. Laringoskop rigid
Laringoskop adalah instrumen untuk pemeriksaan laring dan untuk fasilitas intubasi trachea. Handle biasanya berisi batre untuk cahaya bola lampu pada
ujung blade, atau untuk energi fiberoptic bundle yang berakhir pada ujung blade.
Cahaya dari bundle fiberoptik tertuju langsung dan tidak tersebar. Laringoskop
dengan lampu fiberoptic bundle dapat cocok digunakan diruang MRI. Blade
Macintosh dan Miller ada yang melengkung dan bentuk lurus. Pemilihan dari
blade tergantung dari kebiasaan seseorang dan anatomi pasien. Disebabkan karena
tidak ada blade yang cocok untuk semua situasi, klinisi harus familier dan ahli
2.1.4. Teknik laringoskopi dan intubasi
2.1.4.1. Indikasi Intubasi
Pamasangan TT merupakan bagian rutin dari pemberian anestasi umum.
Intubasi bukan prosedur bebas resiko, bagaimanapun, tidak semua pasien dengan
anestesi umum memerlukan intubasi, tetapi TT dipasang untuk proteksi, dan
untuk akses jalan nafas. Secara umum, intubasi adalah indikasi untuk pasien yang
memiliki resiko untuk aspirasi dan untuk prosedur operasi meliputi rongga perut
atau kepala dan leher. Ventilasi dengan face mask atau LMA biasanya digunakan
untuk prosedur operasi pendek seperti cytoskopi, pemeriksaan dibawah anestesi,
perbaikan hernia inguinal dan lain lain.6
2.1.4.2. Persiapan untuk laringoskopi rigid
Persiapan untuk intubasi termasuk memeriksa perlengkapan dan posisi
pasien. ETT harus diperiksa. Sistem inflasi cuff pipa dapat diuji dengan
menggembungkan balon dengan menggunakan spuit 10 ml. Pemeliharaan tekanan
balon menjamin balon tidak mengalami kebocoran dan katup berfungsi.6
Beberapa dokter anestesi memotong ETT untuk mengurangi panjangnya
dengan tujuan untuk mengurangi resiko dari intubasi bronkhial atau sumbatan
akibat dari pipa kinking. Konektor harus ditekan sedalam mungkin untuk
menurunkan kemungkinan terlepas. Jika mandren digunakan ini harus dimasukan
ke dalam ETT dan ini ditekuk menyerupai stik hoki. Bentuk ini untuk intubasi
dengan posisi laring ke anterior. Blade harus terkunci di atas handle laringoskop
dan bola lampu dicoba berfungsi atau tidak. Intensitas cahanya harus tetap
walaupun bola lampu bergoyang. Sinyal cahaya yang berkedap kedip karena
lemahnya hubungan listrik, perlu diingat untuk mengganti batre. Extra blade,
handle, ETT (1 ukuran lebih kecil atau lebih besar) dan mandren harus
disediakan. Suction diperlukan untuk membersihkan jalan nafas pada kasus
Keberhasilan intubasi tergantung dari posisi pasien yang benar. Kepala
pasien harus sejajar atau lebih tinggi dengan pinggang dokter anestesi untuk
mencegah ketegangan bagian belakang yang tidak perlu selama laringoskopi.
Rigid laringoskop memindahkan jaringan lunak faring untuk membentuk garis
langsung untuk melihat dari mulut ke glotis yang terbuka. Elevasi kepala sedang
(sekitar 5-10 cm diatas meja operasi) dan ekstensi dari atlantoocipito joint
menempatkan pasien pada posisi sniffing yang diinginkan. Bagian bawah dari
tulang leher adalah fleksi dengan menepatkan kepala diatas bantal.6
Gambar 2.1-4 ETT dengan mandren yang dibentuk mirip stik hoki6
Persiapan untuk induksi dan intubasi juga meliputi preoksigenasi rutin.
Preoksigenasi dengan beberapa (4 dari total kapasitas paru paru) kali nafas dalam
dengan 100% oksigen memberikan ekstra margin of safety pada pasien yang tidak
mudah diventilasi setelah induksi. Preoksigenasi dapat dihilangkan pada pasien
yang mau di face mask, yang bebas dari penyakit paru, dan yang tidak memiliki
Gambar 2.1-5 Posisi aman dan intubasi dengan blade macinthos6
2.1.4.3. Intubasi Orotrakheal
Laringoskop dipegang oleh tangan kiri. Dengan mulut pasien terbuka lebar,
blade dimasukan pada sisi kanan dari orofaring dengan hati-hati untuk
menghindari gigi. Geserkan lidah ke kiri dan masuk menuju dasar dari faring
dengan pinggir blade. Puncak dari lengkung blade biasanya di masukan ke dalam
vallecula, dan ujung blade lurus menutupi epiglotis. Dengan blade lain, handle
diangkat dan jauh dari pasien secara tegak lurus dari mandibula pasien untuk
melihat pita suara. Terperangkapnya lidah antara gigi dan blade dan pengungkitan
dari gigi harus dihindari. ETT diambil dengan tangan kanan, dan ujungnya
dilewatkan melalui pita suara yang terbuka (abduksi). Balon ETT harus berada
dalam trakhea bagian atas tapi diluar laring. Langingoskop ditarik dengan hati-
hati untuk menghindari kerusakan gigi. Balon dikembungkan dengan sedikit udara
yang dibutuhkan untuk tidak adanya kebocoran selama ventilasi tekanan positif,
untuk meminimalkan tekanan yang ditransmisikan pada mukosa trakhea.
Merasakan pilot balon bukan metode yang dapat dipercaya untuk menentukan
Setelah intubasi, dada dan epigastrium dengan segera diauskultasi dan
capnogragraf dimonitor untuk memastikan ETT ada di intratrakheal. Jika ada
keragu-raguan tentang apakah pipa dalam esophagus atau trakhea, cabut lagi ETT
dan ventilasi pasien dengan face mask. Sebaliknya, pipa diplester atau diikat untuk
mengamankan posisi.6
Gambar 2.1-6 Gambaran glotiss selama laringoscopi dengan blade yang melengkung.
Lokasi pipa yang tepat dapat dikonfirmasi dengan palpasi balon pada sternal
notch sambil menekan pilot balon dengan tangan lainnya. Balon jangan ada diatas
level kartilago cricoid, karena lokasi intralaringeal yang lama dapat menyebabkan
suara serak pada paska operasi dan meningkatkan resiko ekstubasi yang tidak
disengaja. Posisi pipa dapat dilihat dengan radiografi dada, tapi ini jarang
diperlukan kecuali dalam ICU.6
2.1.4.4. Komplikasi laringoskopi dan intubasi
Komplikasi laringoskopi dan intubasi termasuk hipoksia, hiperkarbia,
malfungsi ETT. Komplikasi-komplikasi ini dapat terjadi slama laringoskopi atau
intubasi, saat ETT dimasukkan, dan setelah ekstubasi.6
Tabel 2.1-2 Komplikasi dari intubasi
Selama laringoskopi dan intubasi Malposisi
Intubasi esophagus Intubasi bronchial Trauma jalan nafas Gigi rusak
Lacerelasi lidah, bibir dan mucosa Dislokasi mandibula
2.2.Mekanisme respon hemodinamik terhadap laringoskopi dan intubasi endotrakheal
King et al27, merupakan salah satu dari beberapa kelompok studi awal
yang melakukan pengamatan pada respon hemodinamik terhadap tindakan
laringoskopi dan intubasi endotrakheal (LETI). Mereka mengusulkan bahwa
disritmia jantung, hipertensi, dan takikardia berhubungan dengan LETI sebagai
akibat dari penurunan tonus vagal ataupun peningkatan aktivitas simpatoadrenal.
Mereka berdalil bahwa penigkatan tekanan darah arteri lebih disebabkan karena
pengikatan curah jantung (CO) daripada peningkatan tahanan pembuluh darah
sistemik (SVR). Mereka mencatat bahwa respon tekanan darah tampaknya lebih
mudah diblok secara komplet dengan lebih mendalamkan level anesthesia dari
pada meningkatkan laju jantung (HR). Mereka juga mencatat bahwa laringoskopi
sendiri dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, sedangkan intubasi akan
Bedford42 telah menggambarkan suatu saling ketrekaitan antara sistem
saraf pusat (CNS) dan respon kardiovaskuler. Selama LETI, peingkatan respon
hemodinamik terjadi karena jalan nafas atas (laring, trakhea, dan karina) memiliki
refleks sistem saraf simpatetis yang dapat bereaksi tidak hanya dengan substansi
atau subjek yang berkontak langsung padanya, tetapi juga terhadap faktor lain,
seperti level anestesi yang ringan (light level of anesthesia). Refleks penutupan
glottis (laringospasme) adalah respon motorik jalan nafas atas terhadap light
anesthesia. Nervus glossopharyngeal berada di superior permukaan anterior
epiglottis. Nervus glossopharyngeal dan vagus, keduanya merupakan jalur afferen
untuk terjadinya refleks laringospasme dan respon hemodinamik pada tindakan
LETI. Nervus vagus memiliki jalur sensorik yang berasal dari daerah setentang
bagian distal epiglottis posterior sampai ke jalan nafas bagian bawah. Karena
terjadinya laringospasme dimediasi oleh jalur vagal efferen ke glottis, maka
refleks ini dapat timbul selama light anesthesia, yaitu ketika ujung-ujung saraf
sensorik yang diinervasi oleh vagal di jalan nafas atas terstimulasi.
Respons kardiovaskuler pada saat tindakan LETI dimediasi oleh sistem
saraf simpatis dan parasimpatis. Respon saraf parasimpatis adalah adalah
terjadinya sinus bradikardi, yang sering sekali terinduksi pada infan dan
anak-anak kecil, akan tetapi terkadang dapat juga terjadi pada orang dewasa. Karena
refleks ini dimediasi oleh peningkatan tonus vagal pada nodus sinoatrial, hal ini
menunjukkan adanya suatu respon monosinaptik terhadap stimulus noksius yang
terjadi.42
Respon simpatis pada tindakan LETI berupa sinus takikardia. Derbyshire
et al43,44 melaporkan bahwa pada saat intubasi endotrakheal tidak hanya disertai
peningkatan aktivitas simpatetik, akan tetapi juga disertai meningkatnya aktivitas
katekolamin adrenomedullari. Respon hipertensi dan takikardi yang biasa terjadi
pada tindakan intubasi endotrakheal dihasilkan oleh aktifitas jalur-jalur efferen
dan glossopharyngeus ke sistem saraf simpatetik, melalui batang otak dan medulla
spinalis, meyakinkan adanya suatu respons otonomik yang diffus, termasuk
peningkatan letupan dari serabut-serabut cardioaccelerator, pelepasan
norpeineprin dari terminal saraf adrenergik pada vascular beds, dan pelepasan
epinefrin dari medulla adrenal. Karena pelepasan rennin dari apparatus
juxtaglomerular ginjal diaktivasi oleh beta-adrenergik, maka aktivasi sistem
rennin-angiotensin juga turut ambil bagian dalam mencetuskan respon hipertensi
pada LETI.42,45
Dalam suatu penelitian tentang respon kardiovaskuler terhadap LETI,
dilakukan evaluasi terhadap respon laringoskopi dan intubasi trakheal secara
terpisah. Dengan menggunakan intubasi nasotrakheal serat optik secara sadar
sehingga stimulus akibat laringoskopi rigid dan suksinilkolin dapat dihindari,
Ovassapian et al46, telah melaporkan bahwa peningkatan maksimum pada
tekanan darah terjadi selama insersi pipa endotrakheal melalui hidung. Sedangkan
peningkatan laju jantung maksimum terjadi selama penempatan pipa endotrakheal
di dalam trakhea. Hal ini hampir sama dengan penelitian Shribman et al28, yang
meneliti tentang respon kardiovaskluer dan katekolamin terhadap laringoskopi
dengan dan tanpa intubasi endotrakheal. Mereka mendapati bahwa terjadi
peningkatan tekanan darah dan konsentrasi katekolamin yang bersirkulasi secara
signifikan pada saat tindakan laringoskopi dengan atau tanpa intubasi. Akan
tetapi, intubasi berkaitan dengan peningkatan laju jantung yang bermakna,
sementara hal ini tidak terjadi jika hanya dilakukan laringoskopi saja. Finfer et
al47, membandingkan laringoskopi langsung dengan intubasi menggunakan serat
optik. Mereka mendapatkan bahwa, baik intubasi dengan laringoskopi dan
bronkhoskopi menghasilkan kenaikan tekanan darah dan laju jantung yang
signifikan. Sehingga tampak bahwa peningkatan maksimum pada tekanan darah
terjadi pada saat laringoskopi, sedangkan laju jantung akan maksimum meningkat
2.3.STRESS RESPONSE
Tubuh kita akan beraksi terhadap stimulus eksternal, mulai dari cedera
ringan sampai yang bersifat massif, baik lokal maupun umum (general). Respon
yang bersifat umum dapat berupa aktivasi sistem endokrin, reaksi metabolik serta
reaksi biokimia di seluruh tubuh. Besarnya respon sangat bergantung pada
keparahan, intensitas dan durasi stimulus. Pemicu terjadinya refleks respon
tersebut, serta pemicu bekerjanya beberapa substansi yang saling mempengaruhi
yaitu antara aksis pituitari-hipothalamus, sistem hormon neuro-endokrin klasik
dan sistem saraf otonomik disebut dengan stress response atau alarm reaction.48,49
Respon lokal meruapakan hal yang penting untuk proses penyembuhan dan
pertahanan melawan infeksi. Respon ini melibatkan mediator-mediator, produk
sel endothelial pembuluh darah dan bahkan produk intraseluler dari sel tunggal.49
Stress response menyebabkan sekresi dari beberapa hormon anabolik dan
katabolik yang menghasilkan suatu hipermetabolisme disertai akselerasi pada
hampir seluruh reaksi biokimiawi. Efek dari Stress response (The
neuro-endocrinal outflow) dapat berupa:
• Perubahan pada sistem kardiovaskuler: peningkatan curah jantung, laju jantung, tekanan darah, peningkatan kontraktilitas miokardium
dan meningkatnya kebutuhan oksigen
• Distribusi volume darah: vasokonstriksi perifer dan splanchnic,
vasodilatasi pembuluh darah koroner dan serebral
• Perubahan pada respiratori: peningkatan laju nafas
• Perubahan pada cairan dan elektrolit: retensi garam dan air
• Koagulasi: terjadi hiperkoagubiliti dan fibrinolisis
• Immunosuppression: infeksi luka
• Perubahan pada metabolik: mobilisasi substrat, hiperglikemia
Stimuli utama untuk terjadinya refleks neuroendokrin di dalam tubuh
adalah:
1) Hipotensi: berkurangnya volume darah yang bersirkulasi efektif
yang disebabkan oleh suatu alasan apapun (seperti trauma,
perdarahan, luka bakar, infark miokard, tamponade jantung, sepsis,
kolaps neurogenik, dan lain sebagainya), akan diindera oleh
baroreseptor di aorta, karotis dan arteri renalis, sesuai dengan
seberapa besar kehilangan volum yang terjadi. Terjadi baik secara
langsung, yaitu melalui jalur otonom sentral untuk mengaktivasi
pelepasan hormon pituitari seperti ACTH, vasopressin, growth
hormone, beta endorphin, maupun secara tidak langsung melalui
sistem saraf simpatetik untuk mengaktivasi pelepasan katekolamin,
glucagon, mencegah pelepasan insulin dan pada akhirnya
menyebabkan retensi natrium dan air serta peningkatan laju
jantung, tekanan darah dan gula darah.48,50
2) Oksigen, karbondioksida dan ion hydrogen
Perubahan pada konsentrasi oksigen, CO2
3) Ansietas dan emosional
dan ion hydrogen dalam
darah akan mencetuskan respon kardiovaskuler, pulmonal dan
neuroendokrin melalui aktivasi kemoreseptor di perifer, aorta dan
carotid bodies.49
Ketakutan, ansietas, emosional, serta ketegangan secara signifikan
dapat menurunkan toleransi terhadap nyeri. Stimulus ini melalui
sistem limbik terutama pada region amigdala hipokampus dan
nukleus batang otak bagian bawah yang kemudian sinyal akan
ditransmisi hipothalamus posterior, selanjutnya akan diteruskan ke
pituitari.49
4) Temperatur
a. Obat anestesi: siklopropan, eter dapat menyebabkan
pelepasan katekolamin
b. Laringoskopi dan intubasi
Stimulasi mekanis pada saluran pernafsan atas melalui
hidung, epifaring, laringofaring, dengan jalur afferen
dibawah oleh nervus glossopharyngeus dan yang berasal
dari pohon trakheobronkhial melalui nervus vagus.
c. Light anaesthesia
d. Nyeri
6) Sensitisasi perifer
7) Sensitisasi sentral
8) Pembedahan, dan
9) Luka49
2.4.STRESS HORMONE
Respon refleks neuroendokrin terhadap suatu cedera terdiri dari:
1) Autokrin (respon otonomik), terdiri dari:
a. Katekolamin
Katekolamin plasma akan meningkat segera setelah cedera
dan mencapai konsentrasi puncak dalam 24 sampai 48 jam
tergantung pada keparahannya. Hormon ini akan memicu
aktifitas metabolik, hemodinamik dan modulasi hormon.
Epineprin akan menyebabkan glikogenolisis hepatik,
glukoneogenesis, lipolisis pada jaringan adipose, ketogenesis
meningkatkan resistensi insulin, mencegah ambilan glukosa
oleh sel. Sedangkan efek langsung pada sistem
kardio-respiratori adalah meningkatnya laju jantung, kontraktilitas
miokard, tekanan darah dan laju nafas.
c. Insulin49
2) Endokrin, yaitu hormon-hormon yang berada dibawah kendali
hipothalamus-pituitari
a. Kortisol
b. Growth hormone
c. Arginin vasopressin
d. Aldosteron
e. Rennin-angiotensin
3) Parakrin, terdiri dari: jaringan lokal yang teraktivasi, sistem sel
endothelial pembuluh darah, dan sel tunggal. Semuanya memicu
respon selama terjadinya perdarahan, inflamasi, sepsis dan bentuk
lain dari cedera sel.50 Keadaan ini akan melepaskan sel-sel mediator
seperti: sitokin, leukotrin, prostaglandin, histamine, serotonin, TNF,
interleukin I, II, VI, plasminogen aktifator, ekisanoid,
kallikrein-kinin dan mediator-mediator lainnya.49
2.5.LIDOKAIN
2.5.1. Struktur, rumus bangun
Lidokain merupakan obat anestesi lokal dari golongan amide. Di sintesa
pertama sekali dengan nama dagang xylocaine oleh Nils Lofgren tahun 1943.
Rekan kerjanya Bengt Lundqvist melakukan ekperimen pertama sekali tahun
1948. Lidokain terdiri dari satu gugus lipofilik (biasanya merupakan suatu cincin
aromatik) yang dihubungkan suatu rantai perantara (jenis amida) dengan suatu
gugus yang mudah mengion (amine tersier). Anestesi lokal merupakan basa
lemah. Dalam penerapan terapeutik, mereka umumnya disediakan dalam bentuk
garam agar lebih mudah larut dan stabil. Di dalam tubuh mereka biasanya dalam
bentuk basa tak bermuatan atau sebagai suatu kation. Perbandingan relatif dari
dua bentuk ini ditentukan oleh harga pKa-nya dan pH cairan tubuh, sesuai dengan
2.5.2. Famakokinetik
Lidokain efektif bila diberikan secara intra vena. Pada pemberian intra vena
mula kerja 45-90 detik. Kadar Puncak plasma dicapai dalam waktu 1-2 menit dan
waktu paruh 30-120 menit. Lidokain hampir semuanya dimetabolisme dihepar
menjadi monoethylglcinexcylidide melalui oksidatif dealkylation, kemudian
diikuti dengan hidrolisis menjadi xylidide. Monoethylglcinexcylidide mempunyai
aktivitas sekitar 80% dari lidokain sebagai antidisritmia sedangkan xylidide hanya
mempunyai aktifitas antidisritmia 10%. Xylidide dieksresi dalam urin sekitar 75%
dalam bentuk 4-hydroxy-2,6-dimethylaniline. Lidokain dalam plasma 50% terikat
oleh albumin.
2.5.3. Mekanisme kerja
Ada dua pendapat kerja lidokain sebagai analgesi, meskipun efek analgesi
ini tidak jelas. Mekanisme lidokain sebagai analgesik menghambat suatu enzim
yang mensekresi kinin atau memblok C nosiseptor lokal secara langsung.
Penghambatan saluran ion natrium dan blokade yang bersifat reversible sepanjang
konduksi akson periferal dari serabut saraf Aδ dan digambarkan oleh Carlton
1997 dengan tujuan target analgesik pada dorsal horn medulla spinalis.52
Sebagai anestesi lokal, lidokain menstabilisasi membran saraf dengan cara
mencegah depolarisasi pada membran saraf melalui penghambatan masuknya ion CH3
NHCCH2N
CH3 O
C2H5
C2H5
natrium. Obat anestesi lokal mencegah transmisi impuls saraf (blokade konduksi)
dengan menghambat perjalanan ion sodium (Na+) melalui saluran ion selektif Na+
dalam membran saraf (butterworth dan stricharrtz 1990). Saluran Na+ sendiri
merupakan reseptor spesifik untuk molekul anestesi lokal. Kemacetan pembukaan
saluran Na+ oleh molekul anestesi lokal sedikit memperbesar hambatan
keseluruhan permeabilitas Na+. Kegagalan permeabilitas saluran ion terhadap Na+,
memperlambat peningkatan kecepatan depolarisasi sehingga ambang potensial
tidak dicapai dan dengan demikian potensial aksi tidak disebarkan.
Saluran Na+ ada dalam keadaan diaktivasi-terbuka, tidak diaktivasi tertutup
dan istirahat- tertutup selama berbagai fase aksi potensial. Pada membran saraf
istirahat, saluran Na+ di distribusi dalam keseimbangan diantara keadaan istirahat–
tertutup dan tidak diaktivasi-tertutup.
Gambar 2.5-2 Mekanisme kerja anestesi lokal
Dengan ikatan yang selektif terhadap saluran Na+ dalam keadaan tidak
diaktivasi-tertutup, molekul anestesi lokal menstabilisasi saluran dalam
konfigurasi ini dan mencegah perubahan mereka menjadi dalam keadaan
istirahat-tertutup dan diaktivasi-terbuka terhadap respon impuls saraf. Saluran Na+ dalam
keadaan tidak diaktivasi-tertutup tidak permeable terhadap Na+ sehingga konduksi
impuls saraf dalam bentuk penyebaran potensial aksi tidak dapat terjadi. Hal ini
diartikan bahwa ikatan obat anestesi lokal pada sisi yang spesifik yang terletak