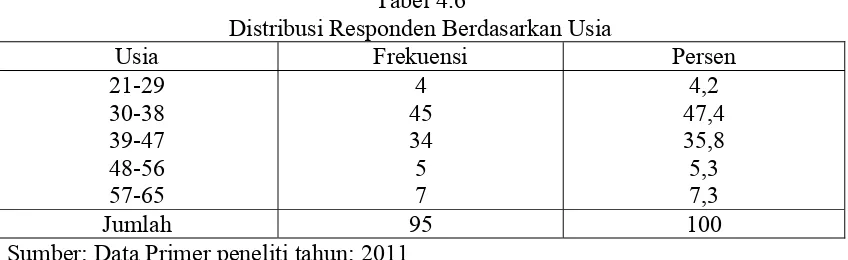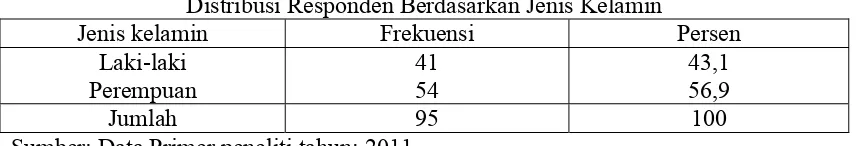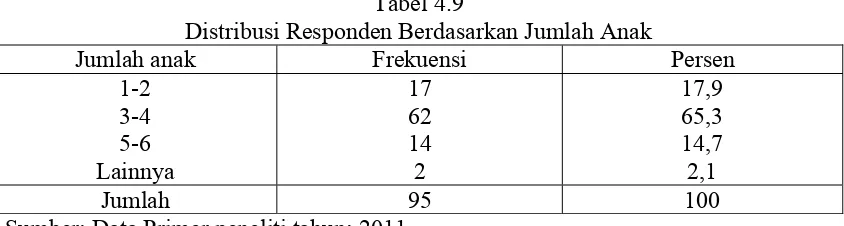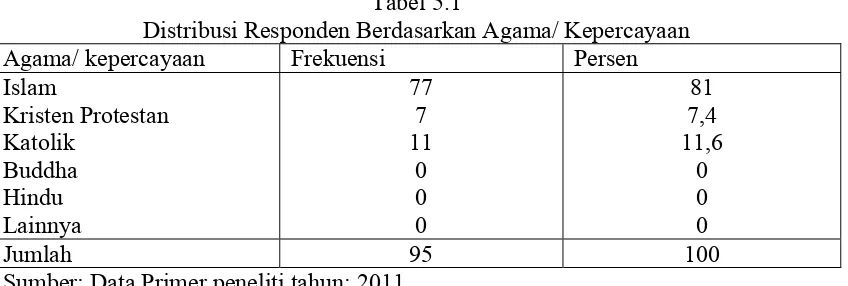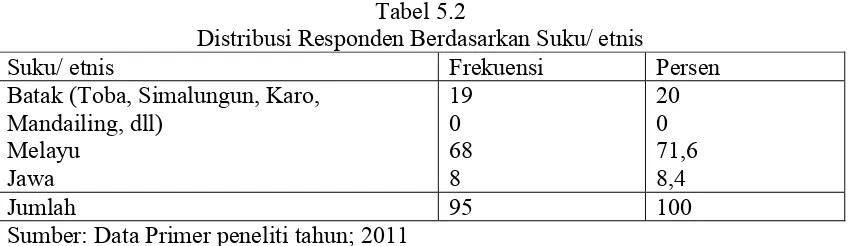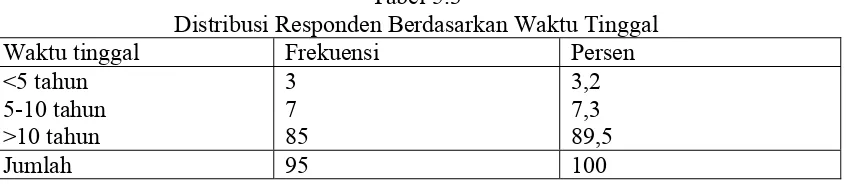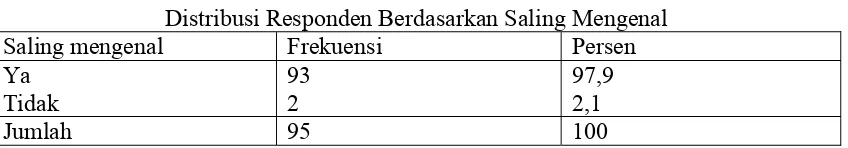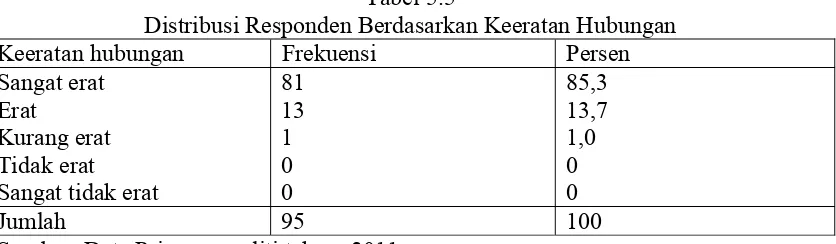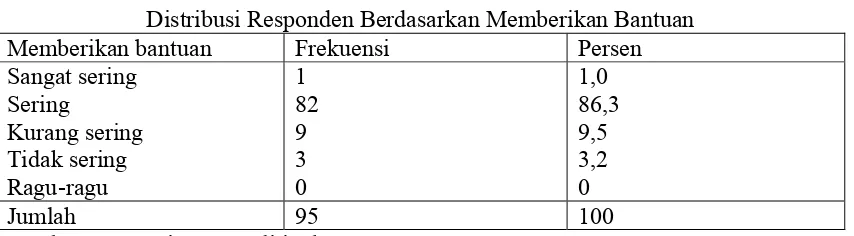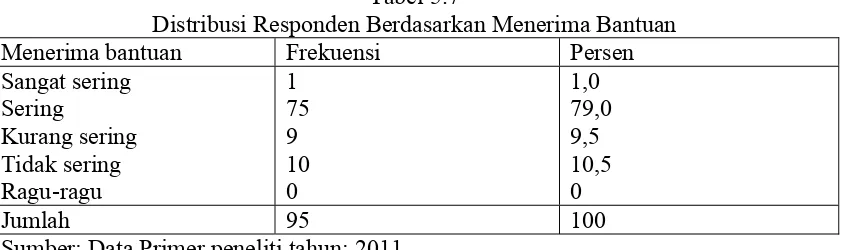Skripsi
POLA INTERAKSI INTERNAL MASYARAKAT PEMUKIMAN KUMUH (Studi deskriptif: Jl. Juanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun)
Di susun
Oleh :
Ester Verawaty Pasaribu 070901018
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LEMBAR PERSETUJUAN
Skripsi ini disetujui oleh :
Nama : Ester Verawaty Pasaribu
NIM : 070901018
Departemen : Sosiologi
Judul : POLA INTERAKSI INTERNAL MASYARAKAT
PEMUKIMAN KUMUH
(STUDI DESKRIPTIF : JL. JUANDA KELURAHAN JATI
KECAMATAN MEDAN MAIMUN)
Dosen Pembimbing Ketua Departemen
(Dra. Linda Elida, M.Si) (Dra. Lina Sudarwati, M.Si) NIP. 131967683 NIP. 19660318 198903 2 001
Dekan
ABSTRAK
Kota Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia tidak terlepas dari masalah kebutuhan dan permukiman. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ditambah dengan jumlah rumah yang dianggap belum layak dan arus urbanisasi menyebabkan kota Medan semakin kekurangan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertumbuhan kota yang cenderung cepat mengakibatkan kota tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana yang layak dan memadai bagi kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan, penerangan, terutama perumahan. Ketidakmampuan menyediakan sarana perumahan yang memadai ini menimbulkan adanya pemukiman-pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh banyak ditemukan di kota Medan salah satu diantaranya adalah pemukiman yang dekat dengan bantaran sungai Deli yaitu pemukiman yang berada pada kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Interaksi dapat ditemukan pada masyarakat ini adalah ketika berada di bantaran sungai. Aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan seperti mandi di air sungai, memberihkan peralatan dapur. Ketika melakukan aktifitas tersebut mereka saling berinteraksi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Adapun yang menjadi lokasi penelitiannya adalah di Jl. Juanda kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Adapun yang menjadi popoulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada pemukiman kumuh di kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner dan observasi (pengamatan).
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus , karena
berkat, rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul “Pola Interaksi Internal Masyarakat Pemukiman Kumuh (Studi Deskriptif : Jl. Juanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun)”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Departemen Sosiologi Universitas Sumatera Utara. Dalam proses
penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan baik berupa waktu,
tenaga, pemikiran, kritikan, saran, kerjasama dalam penelitian ini.
Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis baik secara
material maupun spiritual terutama kepada :
1. Kedua orangtua yang saya sangat sayangi dan sangat saya cintai. Terimakasih
buat Ayahanda St. Tumpal Pasaribu, SP.d dan Ibunda Debora Sitorus, SP.d
yang selalu memberikan motivasi, semangat kepada ananda dan doa-doa yang
selalu kalian panjatkan. Terimakasih buat cinta dan kasih yang selalu kalian
berikan. Ananda berharap Tuhan yang akan memberikan kasih dan berkat yang
terus melimpah buat keluarga kita.
2. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
3. Ibu Dra. Lina Sudarwati, M.Si sebagai Ketua Departemen Sosiologi sekaligus
Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis
selama kuliah di Departemen Sosiologi.
4. Ibu Dra. Linda Elida, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak
meluangkan waktu untuk memberikan dan menyumbangkan ide-ide serta saran
dan kritikan dari awal penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen dan staf di Departemen Sosiologi yang telah mendidik dan
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sumatera Utara.
6. Untuk Kak Feni dan Kak Bety, terima kasih karena selalu memberikan
kemudahan dalam urusan administrasi kuliah.
7. Kepada seluruh responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat kelurahan
Jati.
8. Untuk Kakak, abang dan adikku tersayang, Martha Junita Pasaribu, SP.d,
Daniel Fresly Pasaribu, Amd, Josua Fransen Pasaribu dan Marthin Fernando
Pasaribu terima kasih telah memberikan nasehat dan doanya.
9. Buat Ayu Wulandari dan Rini Syahfitri terima kasih atas waktu yang telah kita
lewati bersama dalam suka dan duka tetap setia walaupun berbeda.
10.Buat teman-teman stambuk 2007 terimakasih buat semangat dan dukungan
kalian.
11.Buat senior dan junior Departemen Sosiologi terimakasih buat motivasi dan doa
12.Untuk teman-teman Naposo Bulung HKBP Perumnas Batu Onom yang selalu
memberikan motivasi, semangat dan selalu mendoakan penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini masih
terdapat ketidaksempurnaan. Namun penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat
bermanfaat bagi pembaca. Semoga penelitian ini dapat pula menjadi pedoman pada
penelitian-penelitian selanjutnya.
Medan, September 2011
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAKSI ... i
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI... v
DAFTAR TABEL... viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...1
1.2. Perumusan Masalah ...8
1.3. Tujuan Penelitian ...8
1.4. Manfaat Penelitian ...8
1.5. Kerangka Teori ...9
1.6. Defenisi Konsep ...11
1.7. Operasional Variabel...13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Interaksi sosial... 17
2.2. Interaksionisme Simbolik ... 18
2.3. Kerjasama... 20
2.4. Assimilasi... 22
2.5. Akulturasi ... 26
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ...32
3.2. Lokasi Penelitian...32
3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 3.3.1. Populasi ...33
3.3.2. Sampel ...34
3.3.3. Purposive Sampling ...35
3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.4.1. Data primer ...36
3.4.2. Data sekunder...36
3.5. Teknik Analisis Data ...37
3.6. Jadwal Kegiatan ...38
3.7. Keterbatasan Penelitian...38
BAB IV HASIL DAN ANALISA DATA PENELITIAN 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ...40
4.2. Penyajian Data Penelitian ... 45
4.2.1. Karakteristik Responden ... 50
4.2.2. Keadaan sosial Responden... 58
4.3. Analisa Data ... 100
5.1. Kesimpulan ... 104
5.2. Saran... 105
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian ... 38
Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan agama... 45
Tabel 4.2. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir... 46
Tabel 4.3. Jumlah penduduk berdasarkan suku... 47
Tabel 4.4. Jumlah Lembaga Pendidikan ... 48
Tabel 4.5. Jumlah rumah ibadah ... 49
Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Usia... 51
Tabel 4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ... 52
Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan... 53
Tabel 4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak ... 54
Tabel 5.0. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ... 55
Tabel 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Agama/Kepercayaan... 56
Tabel 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Suku/Etnis... 57
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Tinggal ... 58
Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Saling Mengenal ... 59
Tabel 5.5. Distribusi Responden Berdasarkan Keeratan Hubungan ... 61
Tabel 5.6. Distribusi Responden Berdasarkan Memberikan Bantuan ... 62
Tabel 5.7. Distribusi Responden Berdasarkan Menerima Bantuan ... 63
Tabel 5.8. Distribusi Responden Berdasarkan Intensitas Mengunjungi ... 64
Tabel 6.0. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan Jenis
Kelamin... 66
Tabel 6.1. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan Usia ... 67
Tabel 6.2. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan
pendidikan ... 68
Tabel 6.3. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan
suku bangsa ... 70
Tabel 6.4. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan status
perkawinan... 71
Tabel 6.5. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan
agama ... 72
Tabel 6.6. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan status sosial
ekonomi ... 73
Tabel 6.7. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi
Menurut Jenis Kelamin ... 74
Tabel 6.8. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi
Menurut Usia ... 75
Tabel 6.9. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi
Menurut Pendidikan... 76
Tabel 7.0. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi
Menurut Suku Bangsa... 78
Tabel 7.1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi
Tabel 7.2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi
Menurut Pendapatan ... 80
Tabel 7.3. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara
Perkawinan... 81
Tabel 7.4. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara
Kematian ... 82
Tabel 7.5. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara
Adat... 84
Tabel 7.6. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara
Keagamaan... 85
Tabel 7.7. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara
Kebersihan Lingkungan ... 86
Tabel 7.8. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara
Keamanan Lingkungan ... 87
Tabel 7.9. Distribusi Responden Berdasarkan Mempelajari Budaya ... 88
Tabel 8.0. Distribusi Responden Berdasarkan Kebebasan Berbudaya ... 89
Tabel 8.1. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Setelah Kebebasan
Berbudaya ... 90
Tabel 8.2. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Internal (dalam rumah
tangga) ... 91
Tabel 8.3. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik antara warga ... 92
Tabel 8.5. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Antara
Kelompok Tertentu ... 93
Tabel 8.6. Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki Anak... 94
Tabel 8.7. Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki Anak... 95
Tabel 8.8. Distribusi Responden Berdasarkan Mendampingi
Anak Dalam Bepergian ... 96
Tabel 8.9. Distribusi Responden Berdasarkan Mengantar
Anak Kesekolah Dan Menjemput Anak Dari Sekolah ... 97
Tabel 9.0. Distribusi Responden Berdasarkan Mendampingi
Anak Sewaktu Belajar (Mengerjakan Pekerjaan Rumah)... 98
Tabel 9.1. Distribusi Responden Berdasarkan Memberikan Motivasi
ABSTRAK
Kota Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia tidak terlepas dari masalah kebutuhan dan permukiman. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ditambah dengan jumlah rumah yang dianggap belum layak dan arus urbanisasi menyebabkan kota Medan semakin kekurangan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertumbuhan kota yang cenderung cepat mengakibatkan kota tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana yang layak dan memadai bagi kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan, penerangan, terutama perumahan. Ketidakmampuan menyediakan sarana perumahan yang memadai ini menimbulkan adanya pemukiman-pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh banyak ditemukan di kota Medan salah satu diantaranya adalah pemukiman yang dekat dengan bantaran sungai Deli yaitu pemukiman yang berada pada kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Interaksi dapat ditemukan pada masyarakat ini adalah ketika berada di bantaran sungai. Aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan seperti mandi di air sungai, memberihkan peralatan dapur. Ketika melakukan aktifitas tersebut mereka saling berinteraksi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Adapun yang menjadi lokasi penelitiannya adalah di Jl. Juanda kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Adapun yang menjadi popoulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada pemukiman kumuh di kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner dan observasi (pengamatan).
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Perumahan dan pemukiman adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh
kota-kota besar pada negara yang sedang berkembang. Kota Medan sebagai kota
terbesar ke tiga di Indonesia tidak terlepas dari masalah kebutuhan perumahan dan
permukiman ini. Kota Medan dengan luas wilayah 265,10 km2 mempunyai jumlah
penduduk 2.097.610 jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,28%
pertahun. Menurut Data Sumatera Utara Dalam Angka tahun 2010 dari jumlah
penduduk tersebut 7,17 % diantaranya adalah penduduk miskin dengan kondisi
rumah yang masih belum dianggap layak adalah sebesar 24,28 %. Tingginya tingkat
pertumbuhan penduduk ditambah dengan jumlah rumah yang dianggap belum layak
dan arus urbanisasi menyebabkan Kota Medan semakin kekurangan perumahan dan
permukiman terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Medan memiliki
gedung-gedung yang bertingkat, memiliki mall yang megah. Dibalik hal tersebut
terdapat juga pemukiman kumuh yang letaknya tidak berjauhan dari gedung-gedung
dan mall tersebut. Pertumbuhan kota yang cenderung cepat mengakibatkan kota tidak
mampu menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi kehidupan
masyarakat, seperti sarana kesehatan, penerangan, terutama perumahan.
Ketidakmampuan menyediakan sarana perumahan yang memadai ini menimbulkan
Daerah-Departemen Dalam Negeri, suatu permukiman atau daerah perkampungan
dinyatakan kumuh dan miskin memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :
1. Kriteria sosial ekonomi
Kriteria sosial ekonomi dapat dilihat dari sebagian besar penduduknya
berpenghasilan dan berpendidikan rendah, sebagian besar penduduknya
bekerja di sektor informal kota, lingkungan pemukiman, rumah, fasilitas dan
prasarana dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim misalnya
kepadatan penduduk yang tinggi >200 jiwa/ha, kepadatan bangunan >110
bangunan/ha, kondisi fasilitas lingkungan terbatas, kawasan permukiman
rawan terhadap banjir.
2. Kriteria dari letak lokasi
Kriteria dari letak lokasinya seperti lokasi pemukiman kumuh berada di lokasi
sangat strategis dalam mendukung fungsi kota yang direncanakan sebagai
bangunan komersial, lokasi pemukiman kumuh yang kurang strategis
mendukung fungsi kota yang dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat kota dan lingkungan pemukiman kumuh yang terletak di loksi
berbahaya menurut rencana induk kota areal diperuntukkan bagi jalur
pengaman seperti bantaran sungai, jalan kereta api, jalur listrik tegangan
tinggi .
3. Kriteria berdasarkan jenis dan aktifitas pekerjaan penduduk permukiman
Jenis dan aktifitas pekerjaan pemukiman kumuh dilakukan umumnya tidak
terorganisir, tidak menentu jumlah jam kerjanya, tidak ada perlindungan/
peraturan dari pemerintah, jenis usaha umumnya berskala kecil yang sangat
tergantung pada teknologi sederhana, usaha merupakan milik keluarga, lokasi
umumnya bersifat sementara yang menyatu dengan tempat tinggal,
kualifikasi/ keterampilan diperoleh di luar pendidikan formal dan dalam
pelaksanaan usaha belum menggunakan sistem manajemen. (Error! Hyperlink reference not valid. diakses pada tanggal 21 september 2010, pukul 10.52 wib).
Masyarakat yang tinggal di kelurahan Jati memiliki tingkat pendidikan
rata-rata hanya sampai sekolah menengah atas, kemudian rata-rata-rata-rata dari masyarakat
memiliki pekerjaan hanya sebagai tukang becak dengan pendapatan yang tidak
menentu. Apabila dilihat dari jenis usaha dikategorikan sebagai usaha berskala kecil
dan menyatu dengan tempat tinggal seperti menjual makanan ringan ataupun kedai
kopi. Hal ini sangat tidak layak apabila dilihat dari segi lokasi dimana masyarakat
yang juga bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai Deli yang sudah tercemar oleh
sampah rumah tangga dan kotoran lainnya.
Pemukiman kumuh yang berada di Jl. Juanda merupakan salah satu
pemukiman kumuh yang berada di kota Medan. Pemukiman ini letaknya dekat
dengan sungai yang sebenarnya tidak layak digunakan oleh masyarakat sekitar.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, sungai ini tetap digunakan oleh
masyarakat tersebut. Masyarakat menggunakan air sungai tersebut untuk mandi yang
dapur yang dilakukan oleh kaum ibu. Masyarakat saling berinteraksi di sungai
tersebut, misalnya hal yang dilakukan ibu-ibu sewaktu berada di sungai tersebut yaitu
bercerita hal-hal yang sederhana seperti masakan apa yang hendak dimasak, bercerita
mengenai kehidupan keluarga mereka. Di bantaran sungai merupakan salah satu
tempat masyarakat Kelurahan Jati berinteraksi. Bukan hanya itu yang terdapat pada
pemukiman kumuh ini, terdapat juga banyak tumpukan sampah di ujung jalan yang
sangat bau dan kotor. Di tempat tumpukan sampah ini juga masyarakat Kelurahan Jati
berinteraksi. Hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di tempat tumpukan sampah
ini adalah mengumpulkan barang-barang bekas yang masih dapat dipergunakan dan
juga dapat dijual. Sewaktu mengumpulkan barang-barang bekas tersebut, masyarakat
tesebut berinteraksi baik itu berkompetisi untuk memperoleh barang bekas dan juga
saling bersenda gurau.
Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan–
kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari
dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia semenjak dilahirkan.
Lingkungan hidup merupakan sarana di mana manusia berada sekaligus menyediakan
kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan.
Oleh karena itu, antara manusia dengan lingkungan hidup terdapat hubungan yang
saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi secara dinamis yang
menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok,
atau kelompok dengan kelompok dan berhubungan satu dengan yang lain disebut
Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktifitas sosial dan
hadirnya kenyataan sosial, kenyataan sosial didasarkan pada motivasi individu dan
tindakan-tindakan sosialnya. Ketika berinteraksi seorang individu atau kelompok
sosial sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial
seorang individu atau kelompok sosial lain. Interaksi sosial akan berjalan dengan
tertib dan teratur dan anggota masyarakat bisa berfungsi secara normal, yang
diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks
sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku
pribadinya dipandang dari sudut sosial masyarakatnya. Manusia telah mempunyai
naluri untuk bergaul dengan sesamanya semenjak dia dilahirkan di dunia. Hubungan
dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, oleh karena
dengan pemenuhan kebutuhan tersebut dia akan mendapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanpa berhubungan atau melakukan interaksi dengan manusia
lain tidak akan bertahan hidup.
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu,
individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial
merupakan proses komunikasi diantara orang-orang untuk saling mempengaruhi
perasaan, pikiran dan tindakan. Interaksi sosial akan berlangsung apabila seorang
individu melakukan tindakan dan dari tindakan tersebut menimbulkan reaksi individu
yang lain. Interaksi sosial terjadi jika dua orang atau lebih saling berhadapan, bekerja
sama, berbicara, berjabat tangan atau bahkan terjadi persaingan dan
pertikaian.Interaksi sosial merupakan hubungan tersusun dalam bentuk tindakan
dapat kita amati atau rasakan bahwa apabila sesuai dengan norma dan nilai dalam
masyarakat, interaksi tersebut akan berlangsung secara baik, begitu pula sebaliknya,
manakala interaksi sosial yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam
masyarakat, interaksi yang terjadi kurang berlangsung dengan baik. ( Soekanto,
2009;67)
Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada dua syarat bagi terjadinya suatu
interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu
kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung
kepada adanya anggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek terpenting dari
komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau
perikelakuan orang lain. Dalam komunikasi sering kali muncul berbagai macam
penafsiran terhadap makna sesuatu atau tingkahlaku orang lain yang mana itu semua
ditentukan oleh perbedaan konteks sosialnya. Komunikasi melalui isyarat-isyarat
sederhana adalah paling elementer dan yang paling pokok dalam komunikasi. Tetapi,
pada masyarakat manusia “isyarat” komunikasi yang dipakai tidaklah terbatas pada
bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi objek
untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subjek yang bertindak) dan melihat
tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat
membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandang orang
lain. Sebagai akibatnya, mereka dapat mengonsentrasikan perilakunya dengan
sengaja untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain. . ( Bagong, 2004;
Faktor-faktor yang mendasari proses terbentuknya interaksi sosial adalah
imitasi yaitu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik
sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya; indentifikasi
yaitu adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama
(identik) dengan individu lain yang ditirunya; sugesti adalah rangsangan, pengaruh,
stimulus yang diberikan sesorang individu kepada individu lain sehingga orang yang
diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional; motivasi
yaitu rangsangan pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada
individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti tahu melaksanakan apa
yang dimotivasikan; simpati adalah proses kejiwaan, dimana seorang individu merasa
tertarik kepada seseorang atau kelompok orang, karena sikapnya, penampilannya,
wibawanya atau perbuatannya yang sedemikian rupa dan empati yaitu mirip dengan
simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati dibarengi
dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens/dalam. ( Soekanto, 2009; 70)
Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan melakukan yang namanya
interaksi. Sama seperti masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh juga
melakukan interaksi terhadap sesamanya di lingkungan sekitar dimana dia hidup.
Untuk itu, peneliti ingin meneliti bagaimana interaksi yang terjadi pada masyarakat
1.2. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah
tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Faktor sosial apa saja yang kontributif pada pola interaksi sosial
masyarakat pemukiman kumuh ?
2. Bagaimana pola interaksi yang terjadi pada masyarakat pemukiman
kumuh tersebut?
1.3. Tujuan Penelitian
Didalam sebuah penelitian, memang membutuhkan cara pandang tujuan.
Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui faktor sosial yang kontributif pada pola interaksi sosial
masyarakat pemukiman kumuh tersebut.
2. untuk mengetahui bagaimana pola interaksi yang terjadi di pemukiman
kumuh tersebut.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori, menambah
wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pola interaksi
b. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan
kajian ilmiah bagi penulis dan mampu juga sebagai referensi dan rujukan
penelitian yang terkait dalam penitian ini.
1.5. Kerangka Teori
Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal
balik antara individu dengan individu,individu dengan suatu kelompok, suatu
kelompok dengan kelompok lain. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan.
Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi, interaksi
sosial adalah proses dimana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi
saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi terjadi antara
individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok
dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam
interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik. Interaksi tidak mungkin terjadi apabila
tidak memenuhi syarat yaitu kontak dan komunikasi. Interaksi sosial dapat kita lihat
secara nyata diinstitusi keluarga. (
http://www.scribd.com/doc/12892816/Interaksi-Sosial diakses pada tanggal 10 Mei 2011, pukul 13.05 wib).
Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga
dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap
keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan
darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah
tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan
menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga diakses pada tanggal 10 Mei 2011, pukul
12.59). Fungsi keluarga beberapa diantaranya adalah untuk mengatur penyaluran
dorongan seks; reproduksi berupa pengembangan keturunan pun selalu dibatasi
dengan aturan yang menempatkan kegiatan ini dalam keluarga; keluarga berfungsi
untuk menyosialisasikan anggota baru masyarakat sehingga dapat memerankan apa
yang diharapkan darinya,keluarga mempunyai fungsi afeksi yaitu keluarga
memberikan cinta kasih kepada seorang anak; keluarga memberikan status kepada
seorang anak bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan
jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan tetapi juga termasuk di
dalamnya status yang diperoleh orang tua yaitu status kelas sosial tertentu; keluarga
memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang
bersifat kejiwaan. ( Sunarto 2004: 64). Intitusi keluarga merupakan ruang lingkup
yang dapat kita lihat terjadinya interaksi sosial. Selain itu, ruang lingkup lain yang
dapat kita lihat terjadinya interaksi sosial adalah masyarakat.
Marion Levy mengemukakan empat kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat
disebut masyarakat yaitu kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang
individu, rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, kesetiaan pada
swasembada. Inkeles mengemukakan suatu kelompok hanya dapat kita namakan
masyarakat bila kelompok tersebut memenuhi kriteria tersebut atau bila kelompok
tersebut dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak
ada orang atau kelompok lain di luar kelompok tersebut.
Seseorang tokoh sosiologi modern, Talcott Parsons pun merumuskan kriteria
adanya masyarakat. Menurutnya masyarakat ialah suatu sistem sosial yang
swasembada, melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara
reproduksi biologis dan serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.
Seorang tokoh sosiologi modern Edward Shils, pun menekankan pada aspek
pemenuhan keperluan sendirin dibaginya dalam tiga komponen: pengaturan diri,
reproduksi sendiri, dan penciptaan diri. Dari berbagai rumusan ini Nampak bahwa
konsep masyarakat mempunyai makna khusus, dan bahwa berbeda dengan
penggunaan kata masyarakat dalam bahasa sehari-hari, dalam sosiologi tidak semua
kelompok dapat disebut masyarakat. ( Sunarto 2004: 54)
1.6. Defenisi Konsep
Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara
abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian.
Konsep sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjadi masalah dan
menghindari timbulnya kekacauan ataupun kesalahan-kesalahan yang dapat
a. Interaksi sosial
Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan
individu, individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok.
Interaksi sosial merupakan proses komunikasi diantara orang-orang untuk saling
mempengaruhi perasaan, pikiran dan tindakan. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan
tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi.
b. Pemukiman kumuh
Permukiman kumuh mengandung dua pengertian, yaitu ; daerah slumsdan
daerah squatter. Sekilas secara fisik antara daerah "slum" dan "squatter" hampir sama, namun sesungguhnya berbeda dalam cara pengertiannya. Jika daerah slums
merupakan daerah-daerah permukiman yang diakui, tetapi karena kemiskinan yang
diderita penghuninya sehingga tidak dapat membiayai pembangunan lingkungannya.
Sedangkan daerah squatter adalah permukiman kumuh dan miskin yang diperoleh
dengan cara melanggar hukum, yaitu dengan cara menempati ruang-ruang publik
terbuka yang semestinya tidak diperuntukkan bagi permukiman dan penghunian.
Pemukiman kumuh Kelurahan Jati merupakan pemukiman kumuh slum. 1.7. Operasionalisasi Variabel
Defenisi operasional melekatkan arti pada suatu konstruk dengan cara
menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk
spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau
memanipulasikannya. Suatu defenisi operasional merupakan semacam buku
pegangan yang berisi petunjuk bagi peneliti. ( Silalahi 2009: 119).
Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:
Faktor-faktor sosial yang kontributif dalam interaksi:
a. Jenis Kelamin
Jenis kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu
spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual
untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu.Jenis kelamin merupakan suatu
akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan
perempuan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin diakses pada tanggal 18 Mei
2011 pukul 11.39 wib)
b. Usia
Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan
suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Umur diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 11.43
wib). Age adalah tingkat usia yang ditandai perkembangan sosial tertentu ( usia sosial
(Soekanto 1985 : 14)
c. Pendidikan
Pendidikan berasal dari kata pedagogi (paedagogie, Bahasa Latin) yang
berarti pendidikan dan kata pedagogia (paedagogik) yang berarti ilmu pendidikan
yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu ‘Paedos’
paedagogos ialah seorang pelayan atau bujang (pemuda, pen) pada zaman Yunani
Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa, pen) ke dan
dari sekolah. Perkataan paedagogos yang semula berkonotasi rendah (pelayan,
pembantu) ini, kemudian sekarang dipakai untuk nama pekerjaan yang mulia yakni
paedagoog (pendidik atau ahli didik atau guru).
Dari sudut pandang ini pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan
seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan
perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.
Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan
perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran,
perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini
mengacu kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia
meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan
bermoral(http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2043347-pengertian
pendidikan/#ixzz1MfzNgKI8 diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 11.45 wib).
d. Suku bangsa
Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang
anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya
berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh
pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan
(http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa diakses pada tanggal 18 Mei 2011
pukul11.49 wib)
e. Status perkawinan
Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat
pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka
yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga
mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai
suami istri. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami
istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai mati adalah status dari mereka yang
suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.
(http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/928/950/ diakses pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 12.20
wib)
f. Agama
Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya
dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan
kepercayaan tersebut. Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta āgama yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang
berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya
kepada Tuhan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Agama diakses pada tanggal 18 mei 2011
g. Status sosial ekonomi
Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam
masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau
suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat
pendidikan, pendapatan dan sebagainya.
(http://drsuparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-dasar-status ekonomi diakses pada
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Interaksi sosial
Interaksi sosial adalah sebagai atau merupakan dasar dari proses-proses sosial,
sebab tanpa adanya interaksi tidak mungkin kehidupan bersama akan terjalin.
(Wiyarti, 2008; 95). Bentuk proses sosial adalah interaksi sosial karena interaksi
sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial
adalah merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut
hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun
antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu,
interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling
berbicara atau bahkan saling berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan
bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut
tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah
terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan
perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang yang bersangkutan, yang
disebabkan oleh minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semuanya itu
menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan
tindakan apa yang akan dilakukan.
Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua
syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kata kontak berasal dari bahasa
terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti
terjadi hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak
lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya cara berbicara dengan pihak lain tersebut.
Komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran perilaku orang lain ( yang
berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang
ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian
memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain
tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan-perasaan
suatu kelompok manusia atau orang-perseorangan dapat diketahui oleh
kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Dalam komunikasi kemungkinan sekali
terjadi pelbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Dengan
komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau antara
kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat
terjadinya kerja sama. Akan tetapi, tidak selalu komunikasi menghasilkan kerjasama
bahkan suatu pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akibat salah paham atau karena
masing-masing tidak mau mengalah. (Bagong, 2004;16)
2.2. Interaksi Simbolik
Untuk mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu, yang
dikenal dengan interaksionisme simbolik. Diantara berbagai pendetan yang
digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal
dengan nama interaksi simbolik. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George
ini adalah interaksi sosial, kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol
dalam interaksi.
Menurut Leslie White, simbol merupakan suatu nilai atau maknanya diberikan
kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Menurut white makna atau nilai
tersebut tidak berasal dari atau ditentukan oleh sifat-sifatyang secara instrinsik
terdapat dalam bentuk fisiknya. Makna suatu simbol menurut White hanya dapat
ditangkap melalui cara nonsensoris yaitu melalui cara simbolik.
Herbet Blumer, salah seorang penganut pemikiran mead, berusaha
menjabarkan pemikiran Mead mengenai interaksionisme simbolik. Menurut Blumer
pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga, yang pertama ialah bahwa manusia
bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang dipunyai
sesuatu tersebut baginya. Blumer selanjutnya mengemukakan bahwa makna yang
dipunyai sesuatu berasal atau muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan
sesamanya. Pokok pikiran ketiga yang dikemukakan Blumer ialah bahwa makan
diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan orang
dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang hendak ditekankan Blumer di
sini adalah bahwa makna muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima
oleh seseorang melainkan ditafsirkan terlebih dahulu. ( Sunarto 2000 : 38)
2.3. Kerja sama (Kooperasi)
Kooperasi berasal dari dua kata latin, co yang berarti bersama-sama dan
operani yang berarti bekerja. Kooperasi merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman, sekalipun motifnya
dapat kita jumpai dalam kelompok dan masyarakat manusia mana pun, baik pada
kelompok-kelompok yang kecil maupun pada satuan-satuan kehidupan yang besar.
Pada dasarnya, proses sosial yang namanya kooperasi ini selalu sudah diperkenalkan
kepada setiap anak manusia sejak kecil, ketika dia masih hidup di dalam keluarga
orang tuanya. Dalam keluarga-keluarga dan juga di dalam komunitas-komunitas
tradisional yang kecil, bentuk-bentuk usaha kooperasi itu mungkin masih sederhana
saja. Akan tetapi, di dalam masyarakat nasional atau kota yang serbakompleks,
jalinan kooperasi itu tidak bisa lagi dibilang sederhana.
Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan
komunitas-komunitas tradisional. Proses sosial yang namanya kooperasi ini cenderung bersifat
spontan. Inilah kooperasi yang terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok
yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu
cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan
masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam
kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka seperti ini, orang perorangan
cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja
sendiri sebagai perorangan.
Berbeda halnya dengan kooperasi yang terjadi di dalam kelompok-kelompok
primer, kooperasi yang ada di dalam kelompok sekunder itu lebih bersifat
direncanakan secara rasional dan sengaja daripada bersifat spontan atau berlandaskan
emosi solidaritas. Kelompok-kelompok yang sedikit banyak bersifat terencana dan
Dalam kenyataannya, realisasi kooperasi itu diusahakan melalui berbagai
macam usaha. Setidak-tidaknya ada empat macam bentuk usaha kooperasi:
1. Tawar-menawar (bargaining) yang merupakan bagian dari proses pencapaian
kesepakatan untuk pertukaran barang atau jasa.
2. Kooptasi (cooptation) yaitu usaha ke arah kerja sama yang dilakukan dengan
jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan
jalannya organisasi atau kelompok.
3. Koalisi (coalition) yaitu usaha dua organisasi atau lebih yang sekalipun
mempunyai struktur berbeda-beda hendak mengajar tujuan yang sama dengan
cara kooperatif.
4. Patungan (joint-venture), yaitu usaha bersama untuk mengusahakan suatu
kegiatan, demi keuntungan bersama yang akan dibagi nanti, secara
proporsional dengan cara saling mengisi kekurangan masing-masing partner.
(Bagong, 2004;59).
2.4. Asimilasi
Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan
adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara
orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk
mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila
tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut lakukan asimilasi ke dalam
suatu kelompok manusia atau masyarakat, dia tidak lagi membedakan dirinya dengan
kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing.
Dalam proses asimilasi, mereka mengindentifikasikan dirinya dengan
kepntingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok
manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan
hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat, proses asimilasi
ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat
emosional dengan tujuan-tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit
mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan.
Proses-proses asimilasi akan timbul apabila :
1. Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang hidup
pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama.
2. Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu di dalam
kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang cukup
lama.
3. Demi pergaulan mereka yang berlangsung secara intensif itu, masing-masing
pihak menyesuaikan kebudayaan mereka msing-masing sehingga terjadilah
proses saling penyesuaian kebudayaan diantara kelompok-kelompok itu,
Sementara itu, beberapa factor yang diketahui dapat mempermudah terjadinya
1. Sikap dan kesediaan menenggang. Apabila toleransi dapat dihidupkan
diantara kelompok-kelompok manusia yang berbeda budaya itu, maka proses
asimilasi akan mudah dilangsungkan tanpa banyak hambatan yang berarti .
2. Sikap menghadapi orang asing berikut kebudayaannya. Sikap demikian ini
akan memudahkan pendekatan-pendekatan warga dari kelompok-kelompok
yang saling berbeda itu.
3. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Kesempatan di bidang
ekonomi yang seimbang begini akan memberikan kemungkinan pada setiap
pihak untuk mencapai kedudukan tertentu berkat kemampuannya. Hal yang
demikian jelas akan menetralisir perbedaan-perbedaan kesempatan yang
terjadi akibat kebudayaan yang berlainan dan berbeda-beda, yang oleh karena
itu akan memudahkan asimilasi.
4. Sikap terbuka golongan penguasa. Sikap terbuka golongan penguasa akan
meniadakan kemungkinan diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap
kelompok minoritas, dan tiadanya diskriminasi antar kelompok akan
memudahkan asimilasi.
5. Kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Sekalipun kebudayaan
masing-masing kelompok itu tidak sepenuhnya sama, namun sering kita saksikan
bahwa dalam hal-hal atau unsur-unsur tertentu terdapat kesamaan. Kian
6. Perkawinan campuran. Misalnya antara warga kelompok mayoritas dan warga
kelompok minoritas, atau antara anggota golongan penjajah dan golongan
anggota terjjah sering pula merupakan langkah penting di dalam usaha-usaha
penyelenggaraan asimilasi.
7. Musuh bersama dari luar. Ancaman musuh bersama dari luar sering pula
diperkirakan akan memperkuat rasa persatuan di dalam masyarakat. Sadar
akan adanya ancaman musuh bersama, golongan di dalam masyarakat sering
melupakan perbedaan-perbedannya dan karenanya lalu mudah berasimilasi.
Proses asimilasi tidaklah akan terjadi apabila antarkelompok tidak tumbuh
sikap toleransi dan saling berempati. Faktor-faktor yang disebutkan di atas
kiranya akan mendorong lahirnya kedua sikap yang diprasyaratkan itu. Selain
faktor-faktor yang mempercepat asimilasi, ada pula beberapa faktor yang
justru menghambat terjadinya asimilasi. Faktor-faktor tersebut antara lain
adalah:
1. Terisolasinya kebudayaan sesuai golongan tertentu di dalam masyarakat
2. Kurangnya pengetahuan suatu golongan tertentu mnegenai kebudayaan yang
dipunyai oleh golongan lain di dalam masyarakat.
4. Perasaan superior yang bercokol di hati para warga golongan pendukung
kebudayaan tertentu yang mengakibatkan sikap meremehkan oleh mereka
yang berperasaan superior ini terhadap kebudayaan kelompok lain
5. Perbedaan ciri badaniah antarkelompok, seperti misalnya warna kulit yang
menandakan bahwa perbedaan antarkelompok yang ada itu tak hanya bersifat
budayawi, tetapi juga rasial.
6. Perasaan in-group yang kuat, artinya bahwa para warga kelompok yang ada
itu merasa sangat terikat kepada kelompok dan kebudayaannya
masing-masing.
7. Gangguan-gangguan diskriminatif yang dilancarkan oleh golongan-golongan
yang berkuasa terhadap golongan minoritas.
8. Perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi antara para warga kelompok
yang akhirnya bisa membawa-bawa pertentangan antarkelompok.( Bagong,
2004;62)
2.5. Akulturasi
Telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis. Tidak jarang
manusia melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam sejarah
kebudayaan dunia, kita ketahui bahwa suku-suku bangsa di dunia sering kali
melakukan perpindahan (migrasi) ini baik akibat adanya ancaman alam maupun
karena kebutuhan untuk mencari bahan makanan. Nenek moyang bangsa Indonesia
Malaya dan Indonesia. Perpindahan seperti ini menyebabkan terjadinya pertemuan
antarkelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Akibatnya, individu
dalam kelompok itu dihadapkan dengan unsur kebudayaan para pendatang tersebut.
Interaksi antarindividu yang berbeda dengan kebudayaan ini menyebabkan
masing-masinh individu mengalami proses sosial tertentu. Diantaranya adalah akulturasi.
Akulturasi (acculturation atau culture contact) adalah proses sosial yang
timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan
unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga
unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan
sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Secara
singkat, akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk
kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi adalah
suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan
kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.
Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya
sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.
Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu Sosiologi yang berarti proses
pengambil alihan unsur-unsur (sifat) kebudayaan lain oleh sebuah kelompok atau
individu. (http://sansanice.blogspot.com/2010/08/akulturasi.html diakses pada tanggal
14 oktober 2010 pukul 13.20 wib)
menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Akulturasi adalah
fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang
mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara
langsung dan terus-menerus; yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola
kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau kedua-duanya. akulturasi
sama dengan kontak budaya yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda melebur
menjadi satu menghasilkan kebudayaan baru tetapi tidak menghilangkan kepribadian
atau sifat kebudayaan aslinya (http://ulyniamy.wordpress.com/2010/05/21/akulturasi/
diakses pada tanggal 14 oktober 2010 pukul 13.10 wib)
2.6. Konflik
Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap
dari sejarah. Selama kita masih hidup tidak akan mungkin kita menghapus konflik
dari dunia ini. Baik konflik intrapersonal dan interpersonal dan juga konflik antar
kelompok merupakan bagian konstitutif dari sejarah manusia. Berbagai macam hal
seperti perbedaan selera, perbedaan pendapat dapat mengakibatkan konflik.
Masalahnya adalah apabila konflik berlanjut hingga melahirkan kekerasaan.
Konflik sebagai proses ternyata dipraktikkan juga secara luas di dalam
masyarakat. Berbeda hal dengan kompetisi yang selalu berlangsung di dalam suasana
“damai”, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan
orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman
kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya
sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang
sebagai lawan atau saingannya.
Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik . perbedaan
pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik-konflik
antarindividu, dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan
pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Kecuali
perbedaan pendirian, perbedaan kebudayaan pun menimbulkan konflik-konflik.
Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antarindividu, akan
tetapi malahan antarkelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan
menimbulkan pola-pola kepribadian dan poal-pola perilaku yang berbeda pula di
kalangan khalayak kelompok yang luas, sehingga apabila terjadi konflik-konflik
karena alas an ini, konflik tersebut akan bersifat konflik antark lompok.
Kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda pun memudahkan terjadinya konflik. Mengajar
tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompokmakan
bersaing akan berkonflik untuk memperbutkan kesempatan dan sarana.
Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan , dan sebagainya tersebut sering
terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan-perubahan
sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya
(peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam
masyarakat akan mengakibatkan berubahnya system nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan
Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu
proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung
dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai
akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung daalam
diskusi, misalnya, jelas akan unggul,sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji
secara benar akan tersisih. Positif tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung
pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik.
Salah satu akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya
solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan
antara kelompok-kelompok, solidaritas antaranggota di dalam masing-masing
kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada
situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya
konflik dengan pihak-pihak luar. Sejalan dengan peristiwa di atas, konflik-konflik
antarkelompok pun memudahkan perubahan dan perubahan kepribadian individu.
Apabila terjadi pertentangan antara dua kelompok yang berlainan, individu-individu
akan mudah mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan dirnya secara
penuh dengan kelompoknya. Tak terbantahkan, konflik juga menerbitkan
akibat-akibatyang negatif. Dalam konflik-konflik fisik, seperti peperangan, korban-korban
akan berjatuhan dan jumlah harta benda akan hancur-luluh.(Bagong, 2004; 69)
Beberapa titik tolak konflik:
Manusia hidup selalu berkonflik. Konflik ada di alam dan hadir dalam
kehidupan manusia.
b. Konflik menciptakan perubahan
Konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas,
perusahaan, dan masyarakat berubah. Konflik juga mengubah pemahaman,
mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara yang baru.
c. Konflik selalu mempunyai dua sisi
Secara inheren konflik membawa potensi resiko dan potensi manfaat.
d. Konflik menciptakan energy
Energy dapat merusak dan juga bersifat kreatif. Konflik memiliki sifat
mengikat dan membawa sifat memisahkan.
e. Konflik dapat menjadi produktif atau non-produktif
Konflik yang produktif mengacu pada permasalahannya, kepentingan/minat,
prosedur dan nilai-nilai pemahamannya. Konflik yang paling non-produktif
mengacu pada pembentukan prasangka terhadap lawan, komunikasi
memburuk.
f. Konflik mengandung berbagai makna
Konflik adalah drama yang dapat dianalisis dengan memahami siapa, apa,
BAB III
METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan
pendekatan yang bertujuan memperoleh data dari lapangan dalam bentuk angka yang
kemudian dianalisis.
Studi deskriptif dalam hal ini adalah penelitian yang bertujuan untuk
menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel
yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang
terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang
kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut ( Bungin, 2009: 36 ).
3.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan kumuh Jl. Juanda Kelurahan
Jati Kecamatan Medan Maimun. Lokasi penelitian ini diambil berdasarkan
pertimbangan diantaranya adalah lokasi tersebut meruapakan salah satu pemukiman
kumuh, lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti, tersedianya transportasi yang
memadai dan hemat biaya.
3.3.1 Populasi
Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik
tertarik. Populasi adalah seluruh unit-unit ynag darinya sampel dipilih. Populasi dapat
berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda,
objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefenisikan
secara spesifik dan tidak secara mendua (Silalahi 2009 : 253)
Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal pada pemukiman
kumuh di Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun dengan jumlah 1791 orang
(Laki-laki 813 orang dan perempuan 978 orang).
3.3.2 Teknik Penarikan Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu,
sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi
itu sendiri (Bambang 2005 : 119). Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin
diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap
populasi dan bukan populasi itu sendiri (Bailey, 1994:83). Untuk menghitung
besarnya sampel didasarkan pada pendapat Taro Yamane (Rakhmat, 1995:99) yang
mengajukan pilihan ukuran sampel berdasarkan tingkat presisi 10% dan tingkat
kepercayaan 90%.
Rumus yang dikemukakan Taro Yamane adalah :
N
Dimana,` n : Besarnya sampel
N : Besarnya populasi
d : Presisi atau derajat kebebasan (peneliti menetapkan 10% atau d = 0,1)
Dari rumus Taro Yamane tersebut, maka besar sampel yang ditarik pada
penelitian ini adalah :
N
n =
N (d)2 + 1
1791
n =
1791 (0,1)2 + 1
1791
n =
17,91 + 1
1791
n =
18, 91
n = 94, 71
Dari proses penjumlahan melalui rumus Taro Yamane diatas maka didapat
sampel sebanyak 95 orang responden. Sedangkan teknik untuk menarik sampelnya
dilakukan dengan cara :
3.3.3 Purposive Sampling
Pemilihan sampel purposive atau bertujuan, kadang-kadang disebut juga
sebagai judgement sampling merupakan pemilihan kepada siapa subjek yang ada
dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu,
menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus
yang dimiliki sampel itu. Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas
karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan
maksud penelitian (Silalahi 2009 : 272 )
Dengan kriteria sebagai berikut :
- Pengemudi becak : 31 orang ( masyarakat yang pekerjaannya sebagai
pengemudi becak)
- Pedagang : 30 orang ( masyarakat yang pekerjaannya sebagai pedagang )
- Ibu rumah tangga : 34 orang ( masyarakat yang pekerjaannya sebagai ibu
rumah tangga)
3.4 Teknik Pengumpulan Data
penelitian yang bersangkutan secara obejektif. Dalam hal ini, teknik pengumpulan
data yang dilakukan penelitian ini dibagi menjadi dua cara yaitu:
3.4.1 Data primer
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data atau sumber responden
dilapangan. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengadakan studi lapangan yaitu:
Metode Angket
Metode ini juga disebut sebagai metode kuesioner. Metode angket berbentuk
rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah
pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket
dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau peneliti (Bungin 2001: 130)
3.4.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber
sekunder yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari beberapa
literature diantaranya adalah buku-buku referensi, dokumen majalah, jurnal, internet,
yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sumber data
sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan,
membantu member keterangan sebagai pelengkap dan bahan pembanding. ( Bungin,
2001;129)
3.5 Analisis Data
Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh, maka
model kuantitatif dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) pengolahan data; (2)
pengorganisasian data; (3) penemuan hasil. Pada analisis ini pengtetahuan dan
pengukuran yang cermat menurut ilmu statistik sangat diperlukan ( Suyanto, 2005 :
57 ).
3.6 Jadwal Penelitian
BULAN No Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pra Proposal √
2 ACC Judul √
3 Penyusunan Proposal Penelitian √ √
4 Seminar Proposal Penelitian √
5 Revisi Proposal Penelitian √
6 Penelitian Ke Lapangan √
7 Pengumpulan Data dan Analisis Data √
8 Interpretasi Data
9 Bimbingan Skripsi √ √ √ √
10 Penulisan Laporan Akhir √ √
11 Sidang Meja Hijau √
3.7. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian mencakup uraian tentang keterbatasan dan hambatan
penulisan yang digunakan maupun keterbatasan peneliti sendiri. Keterbatasan dalam
penelitian ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang
dimiliki oleh peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah.
Selain itu, peneliti juga belum menguasai secara penuh tehnik dan metode
penelitian sehingga dapat menjadi keterbatasan dalam menyajikan dan mengolah
data. Akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi melalui proses bimbingan skripsi dan
peneliti berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang mendukung penelitian
ini.
Walaupun terdapat berbagai keterbatasan, peneliti tetap berusaha semaksimal
mungkin dalam mengumpulkan informasi dari responden serta informasi yang
BAB IV
HASIL DAN ANALISA PENELITIAN
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian ini berada di wilayah kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun
Propinsi Sumatera Utara dengan ibukota adalah kota Medan. Pada zaman dahulu
Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa
kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan
semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura,
Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang
Saling/Sei Kera. http://www.pemkomedan.go.id/images/orang_payung.jpgPada
mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya
terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan
Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan
istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular.
Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang)
sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada
waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai
penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun
1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang
spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama
Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata
yang berkwalitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli
Klei.
Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni :
Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan
Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d
September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan
intensitas rata-rata 4,4 mm/jam. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih
merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi
pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya.
Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang
sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang
sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera
Utara.
Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari
keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan
kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah
penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3°
cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas
permukaan laut.
Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
Kota Medan memiliki beberapa kecamatan, salah satu diantaranya adalah
Kecamatan Medan Maimun. Sebelum pemekaran Kecamatan Medan Maimun dahulu
bergabung dengan Kecamatan Medan Baru. Tahun 1988 terjadi pemekaran di
Kotamadya Medan. Maka berdirilah Kecamatan Medan Maimun. Kecamatan Medan
Maimun ini terdapat bangunan peninggalan sejarah kejayaan Kesultanan Deli masa
dahulu yaitu Istana Maimun yang terletak di Kelurahan Sukaraja.Walaupun bukan
sebagai daerah pusat industri di Kecamatan Medan Maimun ini juga terdapat
beberapa Industri sebagai Potensi dan Produk Unggulan, seperti Konveksi Pakaian
Jadi, Roti Bika Ambon, Anyaman Rotan, Perabot rumah tangga dari kayu, Sepatu,
Syrup marquisa, Kerupuk.
Kecamatan Medan Maimun terletak di wilayah Selatan Kota Medan dengan
batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor
- Sebelah Baratberbatasan denganKecamatan Medan Polonia
- Sebelah Timurberbatasan denganKecamatan Medan Kota
Kecamatan Medan Maimun mempunyai beberapa kelurahan diantaranya adalah
Kelurahan Sukaraja, Kelurahan AUR, Kelurahan Jati, Kelurahan Hamdan, Kelurahan
Sei Mati, dan Kelurahan Kampung Baru. Kelurahan Jati pada awalnya adalah sebuah
kebun sayur yang juga ditumbuhi oleh pepohonan jati yang rimbun sehingga
melindungi tanaman sayur warga dari sinar matahari secara langsung yang dapat
merusak tanaman sayur tersebut. Menurut pengakuan ibu Masni, salah seorang warga
kelurahan Jati yang telah tinggal sejak tahun 1950 sampai sekarang, kelurahan jati
memang dahulunya banyak ditanamani pohon jati. Namun seiring dengan
perkembangan zaman yang semakin modern kelurahan jati pun dimekarkan sehingga
kelurahan jati yang cukup luas dipecah menjadi dua dengan kelurahan yang sekarang
dikenal orang-orang dengan kelurahan Hamdan. Kelurahan Jati yang awalnya kebun
sayur warga yang ditanami pohon jati dengan semakin banyaknya pendatang di
kelurahan Jati maka semakin lama pepohonan jati sudah tidak dapat ditemukan di
daerah kelurahan Jati. Banyak pula warga yang sudah tidak mengetahui asal mula
dari kelurahan Jati tersebut.
Kelurahan Jati ini dapat dikatakan pemukiman kumuh atau slum area karena pemukiman kumuh ini merupakan pemukiman kumuh yang mendukung apabila
dilihat dari kriteria sosial ekonomi, kriteria letak lokasi dan kriteria berdasarkan jenis