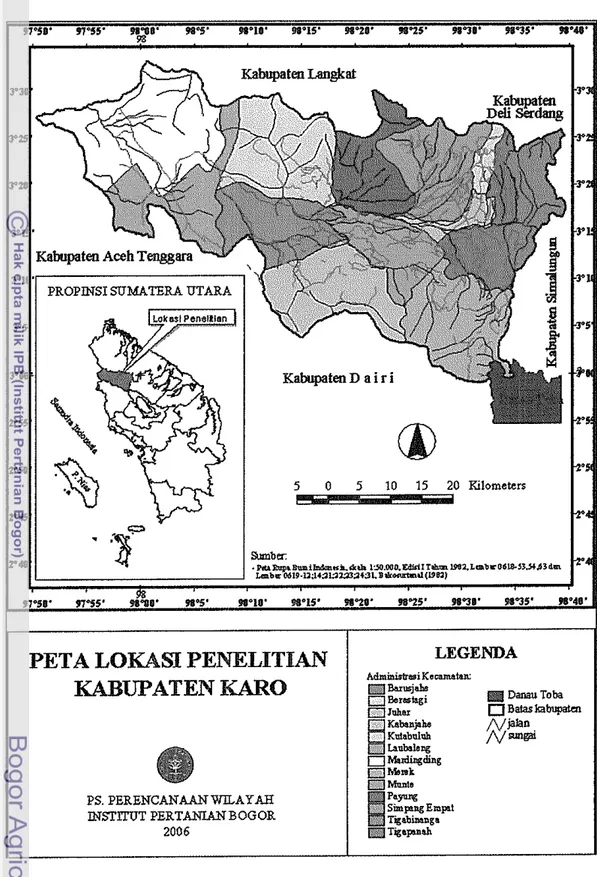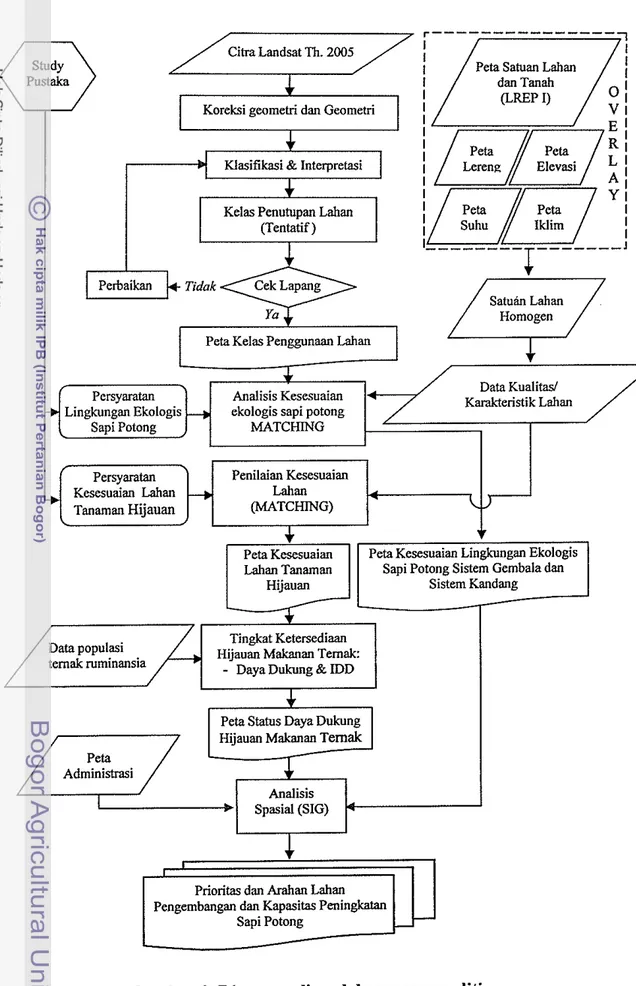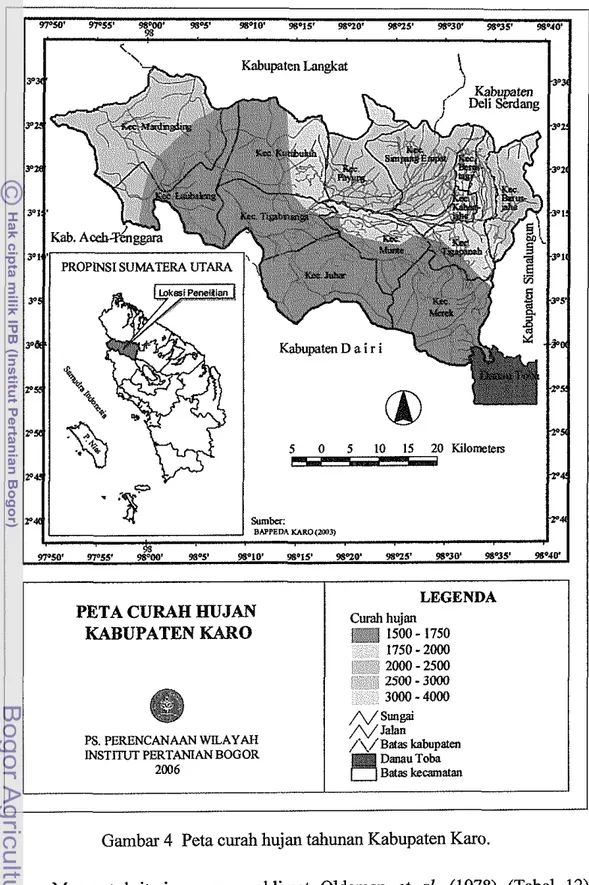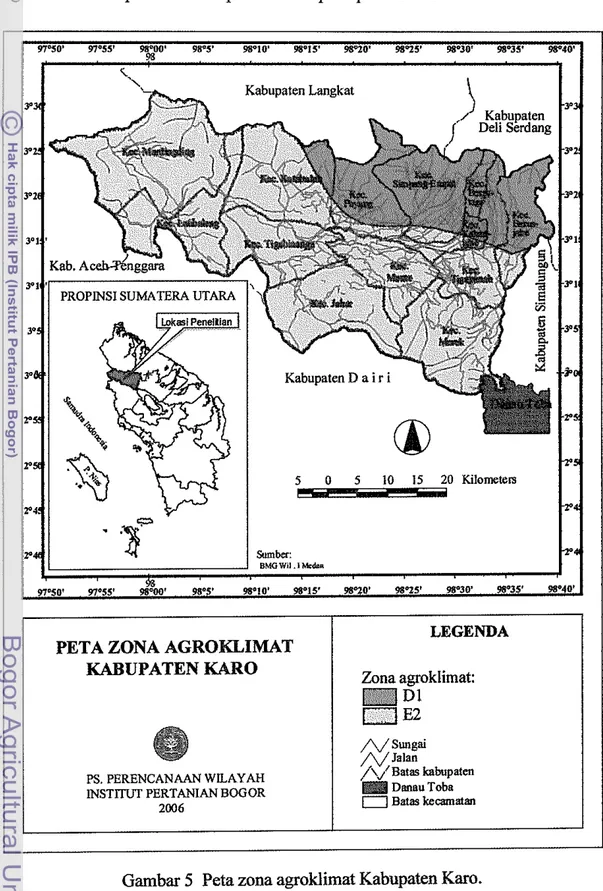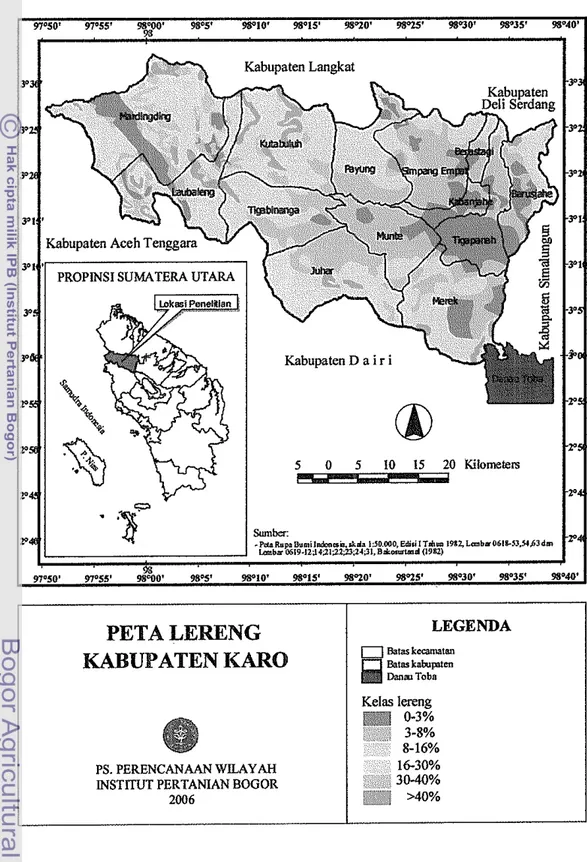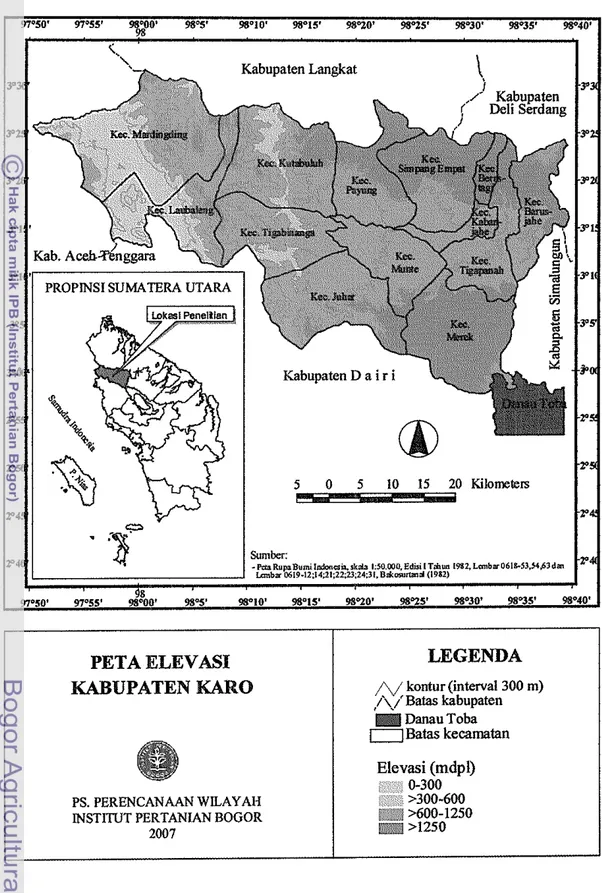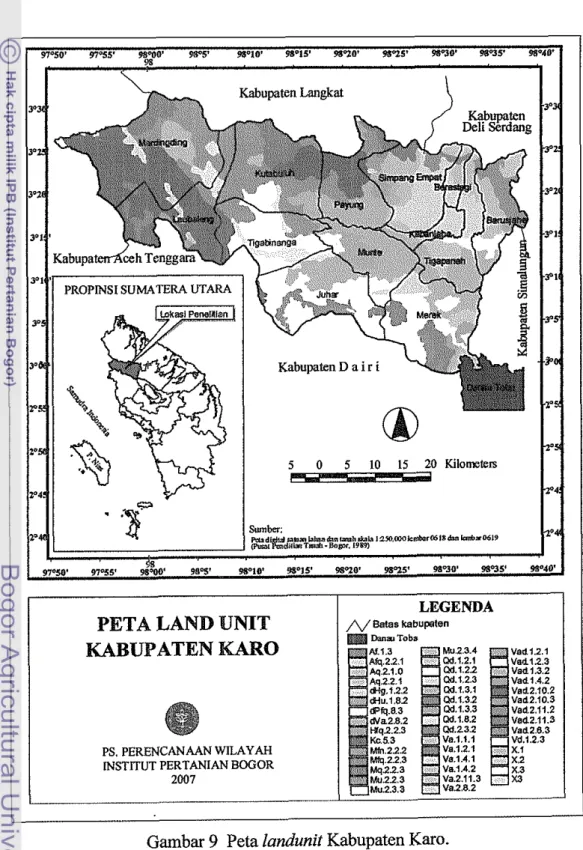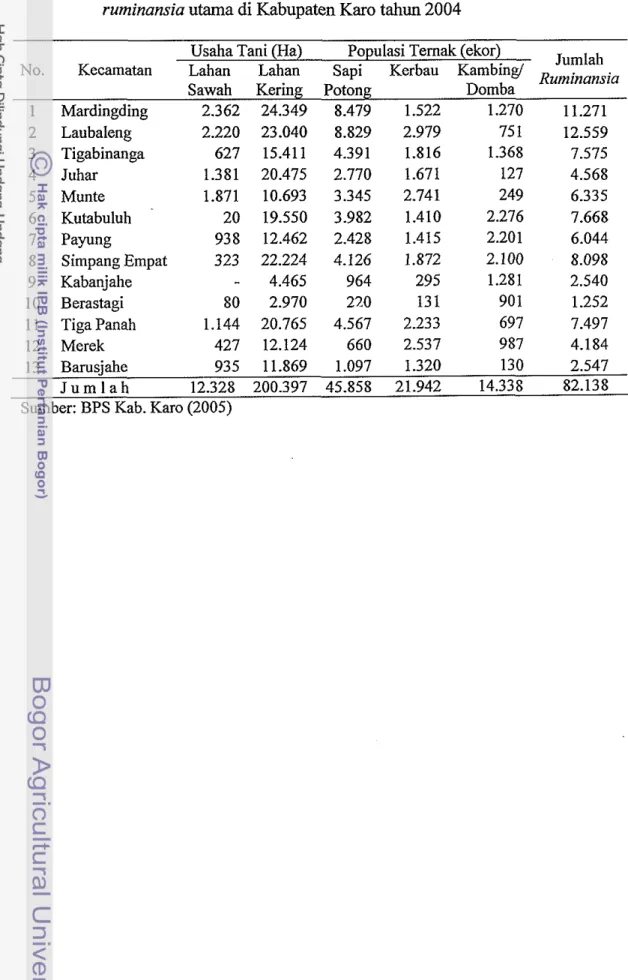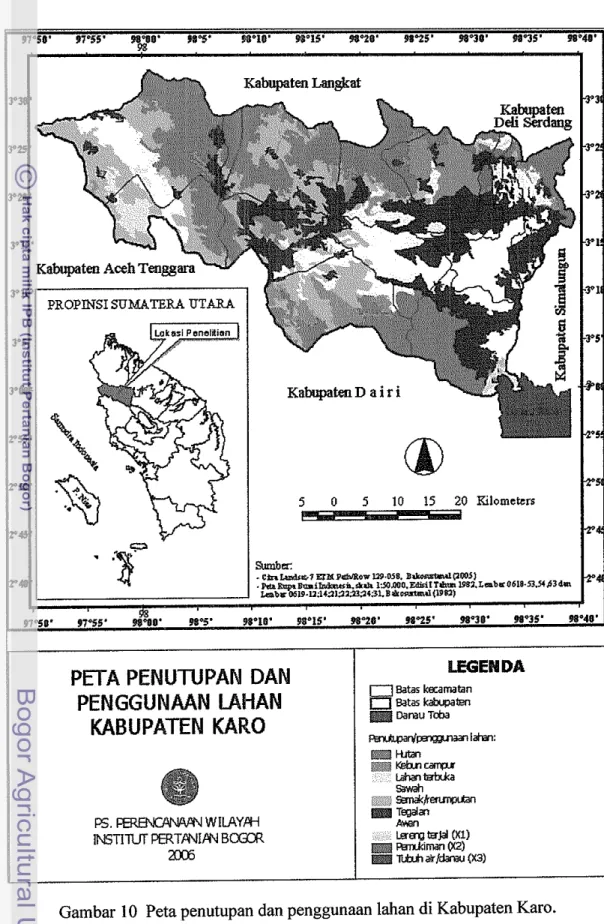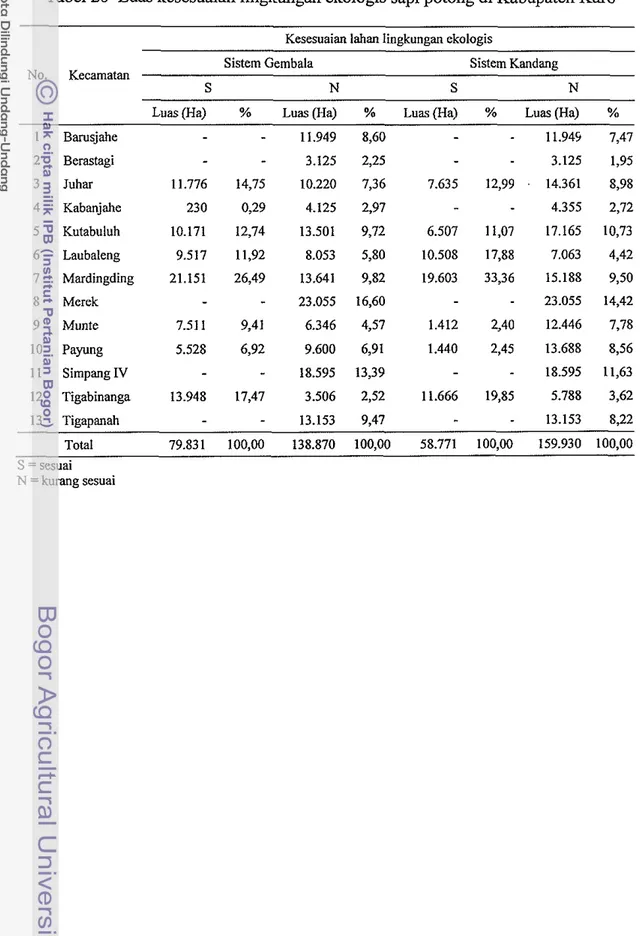ANALISIS POTENSI SUMBERDAYA LAHAN UNTUK
PENGEMBANGAN SAP1 POTONG
DI KABUPATEN KARO
MARKUS MALAU
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis "Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Karo" adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Februari 2007
Markus Malau
ABSTRAK
MARKUS MALAU. Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan
Sapi Potong di Kabupaten Karo (Potential Analysis of Land Resources for Beef
Cattle Development in Karo Regency). Dibimbiig oleh ATANG SUTANDI, UUP S. WIRADISASTRA.
Sumberdaya lahan, temak dan hijauan makanan temak (HMT) merupakan komponen yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan sapi potong. Lahan yang optimal untuk pengembangan sapi potong adalah yang sesuai lingkungan ekologis dan mampu menghasilkan makanan temak yang cukup, berkualitas dan kontinyu. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi jenis-jenis penggunaan lahan untuk pengembangan sapi potong; (2) menentukan kesesuaian lahan sebagai lingkungan ekologis sapi potong; (3)
menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman HMT yang dorninan dan potensi
untuk dikembangkan serta bagaimana tingkat ketersediaannya (daya dukung); serta (5) menentukan prioritas dan arahan lahan pengembangan sapi potong. Analisis yang digunakan melalui pendekatan penginderaan jauh (inderaja), Sistem
Informasi Geografis (SIG) dan Microsoft Excel.
Melalui analisis dan pengolahan citra satelit Landsat TM7 diidentifikasi jenis-jenis penggunaan lahan yang berpotensi untuk pengembangan sapi potong,
yakni lahan-lahan usahatani yang mendukung penyediaaan pakan HMT antara lain: sawah, tegalan, kebun campwan, semak/rerumputan, dan lahan terbuka
dengan luas 135.000 Ha (62% dari luas wilayah penelitian). Hasil analisis
menunjukkan bahwa sebahagian besar wilayah Kabupaten Karo kwang sesuai sebagai lingkungan ekologis sapi potong baik sistem gembala maupun kandang,
dengan faktor pembatas utama adalah terrain (lereng dan elevasi) serta
temperature humidity index (THI). Lahan yang sesuai lingkungan ekologis sapi potong pada pemeliharaan sistem gembala mencapai 79.831 Ha (36,50%) sedangkan sistem kandang 58.771 Ha (26,87%).
Total daya dukung @D) HMT pada kesesuaian lahan aktual mencapai
93.567 satuan temak (ST) sehingga mampu menampung tarnbahan temak sapi
potong sebesar 43.585 ST sedangkan pada keadaan kesesuaian lahan potensial
mencapai 133.371 ST dengan kapasitas peningkatan (KP) sapi potong sebesar
83.388 ST. Berdasarkan tingkat ketersediaan HMT pada keadaan kesesuaian lahan
aktual, sebagian besar lahan berada pada status rawan sampai sangat kritis
mencapai 75.908 Ha (34.71% dari luas wilayah kabupaten) dengan rata-rata DD
hijauan sebesar 1,32 ST/Ha sedangkan pada kesesuaian lahan potensial, tingkat
ketersediaan HMT pada status aman sebanding dengan status rawan sampai
sangat kritis.
Berdasarkan landuse, lahan tegalan dan sawah mempunyai kemampuan
menyediakan HMT yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lahan-lahan lainnya. Pada keadaan kesesuaian lahan aktual rata-rata DD hijauan pada lahan tegalan dan sawah masing-masing 1,30 dan 0,96 ST/Ha, sedangkan pada keadaan kesesuaian lahan potensial 1.79 dan 1,36 ST/Ha.
51.403 ST atau rata-rata 1,41 ST/Ha sedangkan pada sistem kandang, lahan
prioritas I mempunyai total DD sebesar 46.984 ST sehingga marnpu menerima
tarnbahan sapi potong sebanyak 3 1.304 ST atau rata-rata 1,37 ST/Ha.
Arahan lahan untuk pengembangan sapi potong di Kabupaten Karo adalah sistem diversifikasi pada lahan tegalan dan sawah. Untuk sistem gembala, luas areal dengan diversifikasi lahan sawah pada keadaan kesesuaian lahan potensial
mencapai 20.422 Ha (9,34% dari luas kabupaten) dengan KP sapi potong 27.000
ST (1,32 ST/Ha) sedangkan pada sistem diversifikasi lahan tegalan 15.932 Ha
(7,28%) dengan KP sapi potong 24.403 ST (4,39 ST/Ha). Sedangkan untuk sistem
kandang luas areal dengan diversifikasi lahan sawah pada keadaan kesesuaian
O
Hak
cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007
Hak cipta dilindungi
ANALISIS POTENSI SUMBERDAYA LAHAN
UNTUK
PENGEMBANGAN SAP1 POTONG
DI KABUPATEN KARO
MARMUS MALAU
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi
Ilmu
Perencanaan Wilayah
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
Judul Tesis : Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Karo
Narna : Markus Malau
NRP : A253050134
Disetujui
Komisi Pembimbing
Ketua
Diketahui
yang tercinta Fran.sisf&a
BSitumorang, Stefani rihn Patric&Hanison
atas doa, fiarapan rihn du&ungan k a h n sehma ini
...
Ucapan syu(ur:
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga atas segala rahrnat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul "Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Karo".
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak, maka perkenankan penulis menyampaikan ucapan terirna kasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Ir. Atang Sutandi, M.Si, Ph.D dan Bapak Prof. Dr. Ir. Uup S.
Wiradisastra, M.Sc selaku pembimbing serta Bapak Prof. Dr. Ir. Junaidi A. Rachim selaku penguji luar komisi, yang telah banyak memberikan biibingan dan saran;
2. Ketua Program Studi Dr. Ir. Eman Rustiadi, M.Agr dan segenap dosen pengajar serta asisten pada program studi Ilmu Perencanaan Wilayah, atas bimbingan dan dukungannya.
3. Pimpinan Pusbindiklati-en-Bappenas yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk mengikuti program studi dan memberikan beasiswa tugas belajar ini.
4. Kepala Kantor PDE (Bapak Ir. Mulia Barus, M.Si) beserta staf dan
Pemerintah Kabupaten Karo atas dukungan, bantuan dan ijin yang telah diberikan selama melaksanakan tugas belajar di Institut Pertanian Bogor
5. Segenap staf Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah yang telah membantu
kelancaran penulis selama studi.
6. Bapak Ir. Suratman, peneliti pada Puslittanak Bogor yang telah memberikan referensi, konsultasi dan masukan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah
Pascasarjana IPB tahun 200512006 atas bantuan, kerjasama dan dukungannya.
8. Kedua orangtua dan mertua, ifo dan lae J. Simatupang (Padang) serta adek-
adekku atas doa, motivasi dan dukungannya.
9. Lae Daniel, Shanty, Men-Eko (Jakarta) atas bantuan dan dorongan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara moril maupun matenl dalam penyelesaian tulisan ini.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan keiemahan, namun penulis berharap tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Kisaran pada tanggal 23 September 1969 dari bapak
3.R Malau dan ibu H br. Sitanggang. Penulis merupakan putra kedua dari tujuh
bersaudara.
Sekolah dasar hingga menengah atas diselesaikan di Bukittinggi Sumatera
Barat. Tahun 1988 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Bukittinggi dan pada tahun
yang sama lulus seleksi mas& pada jurusan Produksi Temak Fakultas Petemakan Universitas Andalas Padang melalui jalur undangan PMDK dan tarnat tahun 1995. Kesempatan untuk melanjutkan ke Sekolah Pascasarjana IPB pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah diperoleh pada tahun 2005 atas ijin tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Karo dan beasiswa pendidikan dari Pusat Pembinaan, P e n d i d i dan Pelatihan Perencana (PusbiidiMatren) Bappenas.
Saat ini penulis bekerja pada Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Karo Provinsi Surnatera Utara, dengan tugas utama antara lain membantu dalam perencanaan dan penerapan teknologi informasi dalam rangka
DAFTAR IS1
Hataman
DAFTAR TABEL
...
xi...
DAFTAR GAMBAR xii DAFTAR LAMPIRAN...
xiiiPENDAHULUAN Latar Belakang
...
1Perumusan Masalah
...
3Tujuan Penelitian
...
3...
Manfaat Penelitian 3...
Keterbatasan Penelitian 4 TINJAUAN PUSTAKA...
Sapi Potong Evaluasi Sumberdaya Lahan...
Karakteristik dan Kualitas Lahan...
Kesesuaian Lahan...
Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Ternak Ruminansia...
Hijauan Makanan Ternak...
...
Daya Dukung Hijauan Makanan Ternak Pola Pengembangan dan Bentuk Usaha Sapi Potong...
...
Sistem Informasi Geografis Penginderaan Jauh untuk Penutupan/Penggunaan Lahan...
BAHAN DAN METODE...
Lokasi dan Waktu Penelitian 23 Bahan...
.
.
Kerangka Pem~hran...
Metode dan Analisis...
...
Identifikasi Jenis Penutupank'enggunaan Lahan...
Penilaian Kesesuaian Lingkungan Ekologis Sapi Potong Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Hijauan Ternak..
Identifikasi Tingkat Ketersediaan Hijauan Makanan...
Ternak Prioritas dan Arahan Lahan Pengembangan Ternak Sapi Potong...
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN Penutupan dan Penggunaan Lahan...
38Penduduk
...
39Iklim
...
40Topografi
...
46...
Satuan Lahan dan Tanah
Hidrologi
...
...
Keadaan dan Kesuburan Tanah
. .
...
Kondisi Umum Petemakan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penutupan dan Penggunaan Lahan
...
Kesesuaian Lingkungan Ekologis Sapi Potong...
Kesesuaian Lahan Tanaman Hiiauan Makanan Temak .,...
Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah (Olyza sativa)
...
Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Gogo .
...
Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung...
Kesesuaian Lahan Tanaman Ubi Jalar...
Kesesuaian Lahan Tanaman Kacang Hijau...
...
Kesesuaian Lahan Tanaman Rurnput Gajah
Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Setaria
...
...
Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Alam
Kesesuaian Lahan Tanaman Leguminosa
...
...
Ketersediaan Hijauan Makanan Temak
...
Prioritas dan Arahan Lahan
...
Prioritas Arahan Lahan
Arahan Lahan Pengembangan
...
...
SIMPULAN DAN SARAN
...
DAFTAR PUSTAKA
...
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Jenis dan sumber peta dan data sekunder
...
232 Kriteria penilaian kesesuaian lingkungan ekologis untuk sapi
gembala
...
303 Kriteria penilaian kesesuaian lingkungan ekologis untuk sapi
kandang
...
30 4 Kriteria status daya dukung hijauan makanan temak berdasarkan indeksdaya dukung
...
335 Karakterisasi pakan limbah tanaman pangan
...
336 Karakterisasi potensi sumber pakan alami pada tiap penggunaan
lahan
...
337 Nilai satuan temak (ST) ruminansia utama di Kabupaten Karo tahun
2005
...
348 Matrik prioritas arahan lahan pengembangan sapi potong
...
349 Luas wilayah dan penutupanlpenggunaan lahan Kabupaten Karo
...
menurut data BPS (2005) dan peta digital RBI 38
10 Luas wilayah. jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten
tahun 2005
...
39 1 1 Rata-rata curah hujan di Kabupaten Karo di sembilan stasiunpengamatan tahun 1985 . 2005
...
4012 Zona agroklimat berdasarkan jumlah bulan basah dan kering di
Kabupaten di 9 stasiun pengamatan tahun 1985-2005
...
4313 Rata-rata suhu udara di stasiun Kutagadung tahun 19962005 dan
stasiun tongkoh tahun 2000-2005
...
4314 Rata-rata persentase kelembaban nisbi di stasiun Kutagadung tahun
1996-2005 dan stasiun Tongkoh tahun 2000-2005
...
4415 Bentuk wilayah dan luas lahan berdasarkan kelerengan di
Kabupaten Karo
...
4616 Ketinggian dan luas wilayah di Kabupaten Karo
...
4617 Jenis-jenis tanah dominan yang dijumpai di Kabupaten Karo
...
5518 Jenis tanah yang dijumpai di Kabupaten Karo menurut Taksonomi Tanah (1975) dan Dudal & Soepraptohardjo (1960)
...
56 19 Perkembangan populasi sapi potong di Kabupaten Karo tahun2000-2005
...
5920 Luas penggunaan lahan sawah dan lahan kering serta populasi temak
...
21 Jenis penutupan dan pengggunaan lahan di Kabupaten Karo tahun 2005 berdasarkan interpretasi citra Landsat TM7
...
22 Luasan dan jenis penggunaan lahan per kecamatan di Kabupaten Karo(Ha)
.. . .. . . .. . . .. . .
.
.
..
..
... .
.
.
..
.. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .
.. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . ..
.
.
.
..
.. .. . . .. . .
23 Persentase luasan dan jenis penggunaan lahan per kecamatan di Kabupaten Karo
...
24 Kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong di Kabupaten Karo
...
25 Sebaran lahan sesuai lingkungan ekologis sapi potong berdasarkan
Ianduse
. ... . .. . .. . .. .. .... ... .. ... ..
....
.
.. .. .. . . .. .. ... ...
...
..
.. ...
.. ... .. ... . ...
..
... .. .. .. ..
...
26 Luas kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong di Kabupaten Karo
...
27 Kesesuaian lahan tanaman padi sawah di Kabupaten Karo
...
28 Kesesuaian lahan tanaman padi gogo di Kabupaten Karo...
29 Kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Karo...
30 Kesesuaian lahan tanaman ubi jalar di Kabupaten Karo
...
3 1 Kesesuaian lahan tanaman kacang hijau di Kabupaten Karo...
32 Kesesuaian lahan tanaman rumput gajah di Kabupaten Karo...
33 Kesesuaian lahan tanaman rumput setaria di Kabupaten Karo
...
34 Kesesuaian lahan tanaman rumput dam di Kabupaten Karo
...
35 Kesesuaian lahan tanaman legurninosa di Kabupaten Karo
...
36 Tingkat kepadatan usaha temak ruminansia di Kabupaten Karo tahun
2005
..
.
.
. . .
. .
. . . .
. . .
.
.
. . .
. . .
. .
. . .
. . .
. .
.
. . .
.
. . .
. .
. .
.
. . .
. . .
. . .
.
. . .
.
..
.
..
.
37 Status daya dukung hijauan makanan ternak di Kabupaten Karo tahun
2005
...
38 Daya dukung hijauan makanan temak dan kapasitas peningkatan sapi potong menurut kecamatan di Kabupaten Karo
...
39 Sebaran status daya dukung potensial pada lahan usahatani di Kabupaten Karo
...
40 Daya dukung hijauan makanan temak berdasarkan landuse di
Kabupaten Karo
...
41 Jenis tanaman sumber hijauan menurut musim tanam pada lahansawah dan tegalan di Kabupaten Karo
...
42 Daya dukung hijauan makanan temak berdasarkan musim tanarn pada lahan sawah dan tegalan di Kabupaten Karo
...
43 Prioritas arahan lahan dan kapasitas peningkatan sapi potong sistemgembala di Kabupaten Karo
...
45 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem gembala di
Kabupaten Karo
...
I07 46 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem kandang diKabupaten Karo
...
10747 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem GEMBALA menurut kecamatan di Kabupaten Karo pada keadaan kesesuaian
lahan AKTUAL
...
109 48 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem KANDANGmenurut kecarnatan di Kabupaten Karo pada keadaan kesesuaian
lahan AKTUAL
...
109 49. Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem GEMBALAmenurut kecamatan di Kabupaten Karo pada kesesuaian lahan
POTENSIAL
...
10850 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem KANDANG
menurut kecamatan di Kabupaten Karo pada kesesuaian lahan
DAFTAR
GAMBAR
Halaman
1 Peta lokasi penelitian Kabupaten Karo Provinsi Surnatera Utara
...
2 Diagram alir kerangka pemikiran
...
3 Diagram alir pelaksanaan penelitian
...
4 Peta curah hujan Kabupaten Karo
...
:
...
5 Peta zona agroklimat Kabupaten Karo
...
6 Peta estirnasi suhu berdasarkan elevasi diKabupaten Karo
...
7 Peta lereng Kabupaten Karo
...
8 Peta elevasi Kabupaten Karo
...
9 Peta landunit Kabupaten Karo
...
10 Peta penutupan dan pengggunaan lahan di Kabupaten Karo
...
11 Peta kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong sistem gembala di
Kabupaten Karo
...
12 Peta kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong sistem kandang di Kabupaten Karo...
...
13 Peta kesesuaian lahan tanaman padi sawah di Kabupaten Karo
...
14 Peta kesesuaian lahan tanaman padi gogo di Kabupaten Karo
...
15 Peta kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Karo
...
16 Peta kesesuaian lahan tanaman ubi jalar di Kabupaten Karo
...
17 Peta kesesuaian lahan tanaman kacang hijau di Kabupaten Karo
...
18 Peta kesesuaian lahan tanaman rumput gajah di Kabupaten Karo
...
19 Peta kesesuaian lahan tanaman rumput setaria di Kabupaten Karo
...
20 Peta kesesuaian lahan tanaman rumput alam di Kabupaten Karo
...
21 Peta kesesuaian lahan tanaman legurninosa di Kabupaten Karo
...
22 Peta status daya dukung hijauan makanan temak di Kabupaten Karo
23 Peta prioritas arahan lahan pengembangan sapi potong sistem
gembala di Kabupaten Karo
...
24 Peta prioritas arahan lahan pengembangan sapi potong sistem
...
kandang di Kabupaten Karo
25 Peta arahan lahan pengembangan sapi potong sistem gembala di Kabupaten Karo
...
DAFTAR LAMPIRAN
1. Asumsi tingkat perbaikan kualitas lahan aktual untuk menjadi potensial
menurut tingkat pengelolaannya
...
1202 Legenda satuan lahan dan tanah Kabupaten Karo
...
1213 Kualitas dan karakteristik Lahan di Kabupaten Karo
...
1224 Analisis kimia tanah di beberapa kecamatan di Kabupaten Karo
...
1335
Kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong di Kabupaten Karo dan faktor penghambat...
134Latar Belakang
Pembangunan subsektor petemakan memegang peranan penting dan
menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional
dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani, menyediakan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan
serta penghasil pupuk organik. Pertambahan penduduk dan tingkat pendapatan
yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan bergizi asal remak. Untuk
menjamin ketersediaan pangan tersebut perlu upaya peningkatan produksi dan
populasi ternak, salah satunya melahi pengembangan temak ruminansia sesuai
dengan daya dukung dan potensi surnberdaya lahan di suatu wilayah.
Dalam usaha peningkatan produksi temak ruminansia terdapat hubungan
yang erat antara aspek lahan, hijauan makanan temak dan ternak yang tak
terpisahkan satu sarna lain dalam usaha tani. Apabila salah satu aspek tersebut
tidak ada maka produksi yang akan dihasilkan tidak akan memuaskan dan
mungkin akan menyebabkan kegagalan dalam usaha. Lahan merupakan modal
utama sebagai tempat hidup temak ruminansia sekaligus sebagai penghasil
hijauan makanan temak. Oleh karena itu, agar dapat tercapai peningkatan
produksi temak yang optimal diperlukan lahan yang sesuai sebagai lingkungan
ekologis ternak dan mampu menghasilkan hijauan makanan temak dalarn jurnlah
dan kualitas yang cukup dan kontinyu.
Kontribusi subsektor petemakan terhadap perekonomian Kabupaten Karo
cukup besar. S t m k h u perekonomian Kabupaten Karo pada tahun 2004 didorninasi
sektor pertanian yang menyumbang 62,58 % dari total PDRB Kabupaten Karo.
dimana subsektor peternakan memberikan kontribusi sebesar 8,42 % menempati
urutan ketiga setelah tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat
(BPS, 2005). Jumlah sapi potong di Kabupaten Karo tahun 2004 sebanyak 45.858
ekor merupakan populasi yang paling banyak dipelihara dibandingkan dengan
temak besar lainnya.
Pengembangan temak sapi potong di Kabupaten Karo mempunyai prospek
lahan yang masih cukup luas, potensi sumberdaya petani peternak, dan permintaan terhadap daging sapi yang tems meningkat. Aspek pemasaran temak
sapi juga belum menjadi kendala. Di samping itu, sapi potong potensial
dikembangkan di Kabupaten Karo, di samping untuk kebutuhan daging dan
sumber tenaga kerja temtama pengolahan tanah dan penarik barang, juga mengingat hasil sampingan berupa kotoran ternak, sebagai sumber bahan organik
dan sumber hara potensial bagi tanaman. Sebaliknya bahan limbah pertanian dapat
digunakan sebagai masukan untuk usaha petemakan. Adanya keterkaitan antara
usaha tani dengan peternakan ini dapat meningkatkan pendapatan petani.
Kabupaten Karo merupakan daerah pertanian utama khususnya tanaman
pangan dan hortikultura di Sumatera Utara. Pola pengembangan sapi potong di
Kabupaten Karo tidak terlepas dari penggunaan lahan dan perkembangan usaha
pertanian terutama sawah dan tegaladadang. Di daerah pertanian intensif seperti
Kabupaten Karo, jenis pakan yang diberikan pada temak ruminansia seperti sapi
potong terdiri atas hijauan dan konsentrat, namun sebagian besar berupa pakan
hijauan. Pakan hijauan yang mempakan sumber serat kasar, berasal dari rumput
segar yang ditanam pada pematang sawah, tegalan dan lahan lainnya serta dari
limbah pertanian seperti jerami padi, jerami jagung atau jerami kacang-kacangan.
Fluktuasi pakan hijauan dipengaruhi oleh tataguna lahan dan pola tmam dan
musim panen komoditi pertanian untuk menghasilkan limbah pertanian seperti
jerami padi, jagung, ubi jalar, kacang-kacangan dan lain-lain.
Luasnya lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Karo sangat
memungkinkan dilakukan pengembangan pola integrasi temak-tanaman.
Keterpaduan antara temak dan tanaman pertanian
ini
dapat saling menunjang dansaling menguntungkan melalui pemanfaatan tenaga sapi untuk mengolah tanah
dan kotoran sapi untuk pupuk organik sementara lahan sawah dan ladang
menghasilkan limbah untuk pakan temak seperti jerami padi, jagung dan kacang-
kacangan. Pola integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pakan
temak. Dengan demikian, peluang potensi pengembangan peternakan khususnya
temak ruminansia cukup terbuka lebar dengan mengoptimalkan pemanfaatan
Perumusan Masalah
Pengembangan usaha sapi potong di Kabupaten Karo tidak berjalan
sebagaimana diharapkan karena usaha tersebut belum sepenuhnya didasarkan
pada potensi sumberdaya wilayah yang ada, baik potensi sumberdaya lahan
sebagai penyedia pakan ternak maupun lingkungan yang optimal untuk kehidupan
temak sapi itu sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan jumlah populasi dan
produksi lambat berkembang. Oleh sebab itu diperlukan kajian tentang potensi
sumberdaya lahan yang menyeluruh -untuk kepentingan perencanaan
pembangunan khususnya dalam pengembangan usaha sapi potong di Kabupaten
Karo agar optimal dan lebih terarah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dirumuskan pernasalahan sebagai berikut:
a. Belurn adanya penelitianlkajian tentang kesesuaian lahan untuk li~lgkungan
ekologis sapi potong dan kesesuaian lahan untuk hijauan makanan temak serta
daya dukungnya.
b. Potensi lahan di Kabupaten Karo belum dirnanfaatkan secara optimal bagi
pengembangan sapi potong.
c. Ketersediaan hijauan makanan temak belum terpenuhi dan dinilai secara
kualitas bagi pengembangan sapi potong.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Mengidentifikasi jenis penggunaan lahan untuk pengembangan temak sapi
potong.
2. Menentukan kesesuaian lahan sebagai lingkungan ekologis sapi potong.
3. Menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman hijauan makanan temak sapi
potong yang dominan dan potensi untuk dikembangkan serta tingkat
ketersediaannya.
4. Menentukan arahan pengembangan temak sapi potong berdasarkan potensi
sumberdaya lahan dan kelayakan usahatemak.
Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan
pembangunan, khususnya untuk pengembangan petemakan sapi potong.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan swasta yang bergerak dalam
usaha pengembangan sapi potong di Kabupaten Karo.
3. Tersedianya sistem informasi meldui analisis potensi lahanlwilayah untuk
pengembangan petemakan khususnya temak sapi potong di Kabupaten Karo.
Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan yang ada daIam penelitian ini antara lain:
1. Peta satuan tanah yang digunakan terbatas pada informasi dari peta satuan
tanah skala tingkat tinjau yang dikeluarkan Puslitanah (1982).
2. Evaluasi lahan hanya dilaksanakan lebih bersifat kualitatif sehingga hanya
memadai untuk arahan pengembangan pada tingkat awal.
3. Perhitungan produksi bahan kering hijauan makanan temak untuk setiap kelas
kesesuaian lahan didasarkan pada asumsi hasil penelitian dari tempat lain
(data sekunder).
TINJAUAN
PUSTAKA
Sapi Potong
Temak sapi merupakan temak ruminansia besar yang memiliki kemampuan
tinggi untuk mengubah hijauan yang berkualitas rendah menjadi produk yang
bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam bentuk daging. Temak ini juga dapat
memanfaatkan hasil sampingdimbah pertanian dan industri sebagai pakan pokok
hidup dan produksi (Muljadi et al., 1992). Kegunaan temak dalam kehidupan
petani meliputi antara lain: (a) sebagai sumber tenaga kerja; (b) pengubah hasil
limbah pertanian dan rumput dam; (c) sebagai tabungan dan cadangan uang tunai;
dan (d) sebagai sumber pupuk organik (Natasasmita dan Mudikdjo, 1980).
Pemilihan suatu bangsa sapi menurut Blakely (1985), tergantung pada
kesukaan petemak, keadaan lingkungan, kemampuan adaptasi, efisiensi produksi,
kemampuan memelihara dan menyusui anak, ukuran badan, pertambahan berat
badan, dan sifat-sifat lain yang cocok dengan keinginan petemak yang
bersangkutan. Jenis sapi yang dipelihara dan sudah lama ada di Indonesia serta
sudah dianggap sebagai sapi lokal adalah sapi Bali (termasuk Bos indicus), sapi
Ongole (Bos indicus) serta Peranakan Ongole (PO), sapi Madura, sapi Jawa, sapi
Sumatera dan sapi Aceh yang semuanya dianggap sebagai k e t m a n sapi Bos
sondaicus dan Bos indicus. Di antara bangsa sapi yang besar populasinya adalah
sapi Bali, sapi Ongole serta Peranakan OngoIe dan sapi Madura (Natasasmita dan
Mudikdjo, 1980).
Faktor iklim sebagai salah satu faktor lingkungan memiliki pengaruh besar
terhadap kehidupan temak sapi potong. Menurut Sugeng (1998) faktor lingkungan
tersebut meliputi: suhu, kelembaban, curah hujan. Faktor lingkungan yang tidak
sesuai akan mejadi beban berat bagi kehidupan sapi. Sifat iklim di daerah tropis di
Indonesia tergolong panas dan lembab ditandai oleh kelembaban udara rata-rata di
atas 60%, curah hujan rata-rata di atas 1.800 d t a h u n dan perbedaan antara suhu
siang dan malarn hari tidak begitu mencolok yakni sekitar 2-5°C.
Temperature humidity index (THI) merupakan faktor yang mempengaruhi
produksi dan perkembangbiakan sapi. Temperature humidity index (THI) yang
lingkungan terhadap kenyamanan suatu makhluk hidup yang mengkombinasikan
temperatur dan kelembaban (AMS, 2006). Faktor THI berhubungan dengan
kemampuan sapi potong dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya
sehingga dapat mengganggu produksi. Amundson et al. (2006) mengungkapkan
pengaruh lingkungan terhadap tingkat kebuntingan pada sapi potong diiana
untuk hari ke 0-60 periode breeding, nilai THI optimum adalah 68,O sedangkan
ambang batas THI di mana sapi akan beradaptasi adalah 72,9. Pengurangan
tingkat kebuntingan kemungkinan besar ketika rata-raia THI sama atau melebihi
dan 72,9. Selanjjutnya, Berman (2005) menyatakan, temperature humidity index
(THI) digunakan untuk menaksir tekanan (stress) yang berkaitan dengan panas
termasuk sensasi kenyamanan dengan lingkungan berbeda yakni kelembaban
udara dan temperatur pada kecepatan udara rendah
.
Ketersediaan air harus diperlctungkan dalam usaha petemakan sapi potong.
Sapi yang kekurangan air menyebabkan aktivitas sel-sel tubuhnya
akan
terganggusehingga tubuh sakit dan perturnbuhannya akan terganggu. Kebutuhan air bagi
tiap ekor sapi dewasa diperhitungkan rata-rata 40 liter sehari dan dalam kondisi di
padang penggembalaan diusahakan jarak untuk mencapai sumber air tidak lebih
dari 1,6
km
agar sapi tidak terlalu letih.Evaluasi Sumberdaya Lahan
Lahan mempakan bagian dari bentang lahan (landscape) yang mencakup
pengertian lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan
vegetasi dimana faktor-faktor tersebut secara potensial akan berpengaruh terhadap
penggunaannya (FAO, 1976). Lahanddam pengertian yang lebih luas termasuk
yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik
dimasa lalu maupun saat sekarang.
Evaluasi lahan mempakan penilaian keragaan (performance) lahan bila
digunakan untuk tujuan yang spesifik. Hal ini termasuk pelaksanaan dan
interpretasi dari survei dasar seperti iklii, tanah, vegetasi dan aspek-aspek
lainnya dari lahai~ dalam hal persyaratan dari bentuk-bentuk 'pilihan dari
penggunaan lahan (FAO, 1976). Agar bernilai dalam perencanaan, cakupan
dalam konteks fisik, ekonomi dan sosial daerah yang dipertimbangkan dan
perbandingannya h a s mengikutsertakan pula pertimbangan ekonomi.
Djaenuddin et al. (2003a) mengemukakan bahwa evaluasi lahan adalah
proses dalam menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk
penggunaan tertentu, baik untuk pertanian maupun non pertanian. Kelas
kesesuaian lahan suatu wilayah untuk suatu pengembangan pertanian pada
dasamya ditentukan oleh kecocokan sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim,
tanah, terrain mencakup lereng, topografirelief, batuan di permukaan dan di
dalam penampang tanah serta singkapan batuan (rock outcrop), hidrologi, dan
persyaratan penggunaan lahan atau persyaratan turnbuh tanaman. Kecocokan
antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayah dengan persyaratan penggunaan
atau komoditas yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa
lahan tersebut potensial dikembangkan untuk komoditas tersebut. Hal ini
memberikan pengertian bahwa jika lahan tersebut digunakan untuk penggunaan
tertentu dengan mempertimbangkan berbagai asumsi mencakup masukan yang
diperlukan, akan mampu memberikan hasil (keluaran) sesuai yang diharapkan.
Evaluasi lahan perlu untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya lahan untuk
penggunaan tertentu. Pada dasamya evaluasi sumberdaya lahan membutuhkan
keterangan-keterangan yang menyangkut 3 (tiga) aspek utama, yaitu: lahan,
penggunaan lahan dan ekonomis. Data tentang lahan dapat diperoleh dari kegiatan
survey tanah. FA0 (1976) menyatakan bahwa satuan peta lahan dalam survey
biasanya digambarkan dengan sifat lahan. Sifat lahan yang diidentifikasi dan
diinterpretasi antara lain: landform, litologi, relief dan lereng, tingkat torehan,
elevasi, pola drainase, dan landuse yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Landform atau bentuk permukaan bumi adalah bentukan alam mengenai
permukaan bumi yang terjadi melalui serangkaian proses yang disebut proses
geomorfii (geomorphic process). Landform mempunyai hubungan erat dengan
fisiografi, litologi, topografi, mineralogi, tanah dan lain-lain. Dengan demikian
dalam penelitian tanah, khususnya survei tanah, pemahaman dan penelaahan
fisiografi dan landform sangat penting. Satuan fisiografilandform merupakan
Litologi atau bahan induk adalah massa lunak bersusunan anorganik atau
organik yang menjadi awal pembentukan tanah. Bahan induk bersusunan an-
organik berasal dari pelapukan batuan induk sedangkan bahan induk bersusunan
organik berasal dari bahan induk organik. Informasi geologi dan pengetahuan
tentang litologi setempat bertujuan menentukan penetapan nama bahan induk dan
sifat-sifatnya. Bahan induk dibedakan dalarn dua grup yaitu bahan lepasnunak dan
bahan
kukuh.
Bahan lepasl lunak sebagian besar berbahan sedimen atau bahanlapukan yang terdapat di atas batuan keras. Sedangkan bahan kukuh berupa
batuan yang keras seperti batuan beku serta sebagian batuan sedimen dan
metamorfik.
Tingkat torehan, diindikasikan dengan kerapatan drainase (drainage
density) atau kerapatan lembah (valley density). Informasi tentang tingkat torehan
bertujuan menentukan tingkat erosi yang telah terjadi, baik pada masa lampau
maupun pada masa sekarang. Informasi ini dapat diperoleh dari hasil interpretasi
peta rupabumi, foto udara atau citra lainnya dan dari pengamatan lapangan.
Relief dan lereng, m e ~ p a k a n aspek topografi yang berguna untuk
mengetahui bentuk wilayah &bat adanya perbedaan ketinggian alami ataupun
buatan dan besarnya lereng yang dominan, misalnya bentuk wilayah datar sampai
agak datar mempunyai kelerengan 0-3% dengan perbedaan tinggi <5 meter,
berombak mempunyai kelerengan 3-8% dengan perbedaan ketinggian 5-15 meter,
dan seterusnya.
Elevasi, menyatakan ketinggian tempat dari permukaan laut (diiyatakan
dalam meter). Data ketinggian ini dapat diperoleh dari hasil pengukman langsung
dengan altimeter, Global Positioning System (GPS) atau data yang ada pada peta
rupa bumi/topogrd.
Drainase dan pola drainase. Drainase menyatakan mudah tidaknya air
hilang dar tanah. Berdasarkan klas drainasenya, tanah dibedakan menjadi klas
drainase terhambat (tergenang) sampai sangat cepat (air sangat cepat hilang dari
tanah. Pola drainase adalah bentukan jaringan sungai dan-anak-anak sungai yang
bempa alur-alur, proses dan bentukannya sangat dipengaruhi oleh jenis batuan
induk yang menyusun suatu lanskap. Pola drainase dapat diintepretasi dari peta
daerah kerucut volkan muda), braided (daerah yang mempunyai aliran sungai deras karena lereng curam seperti pegunungan, kipas aluvial), dendritik (daerah
datar-bergelombang dari batuan induk homogen dan tidak kukuh (tuf volkan,
batuliat), dan lain-lain.
Landuse atau penggunaan lahan, secara umum dipengaruhi oleh keadaan
tanah dan ketersediaan air. Tipe penggunaan lahan atau Land Utilization Types
(LUT) yang dapat dikembangkan disuatu wilayah akan sangat ditentukan oleh
keadaan sifat tanah dan fisik lmgkungannya. Kriteria utama yang digunakan
dalam menentukan klasifikasi penggunaan lahan dan vegetasi diutamakan pada
jenis dan vegetasi permanen yang terdapat di daerah bersangkutan. informasi ini
bertujuan mendapatkan gambaran tentang keadaan penggunaan lahan yang telah
ada pada saat kegitan dilakukan (present landuse).
Karakteristik dan Kualitas Lahan
Karakteristik lahan adalah sifat atau atribut lahan yang dapat diukurl
diestimasi, contohnya: sudut lereng, curah hujan, tekstur tanah, kapasitas air
tersedia, biomassa vegetasi dan sebagainya (FAO, 1976). Setiap satuan peta
lahanftanah yang dihasilkan dari kegiatan survei atau pemetaan sumberdaya lahan,
karakteristiknya dirinci dan diuraikan yang mencakup keadaan fisik lingkungan
dan tanahnya. Data tersebut digunakan untuk keperluan interpretasi dan evaluasi
lahan bagi komoditas tertentu.
Setiap karakteristik lahan yang digunakan secara langsung dalam evaluasi
biasanya mempunyai interaksi satu sama lain. Karenanya F A 0 (1976)
mengemukakan bahwa dalam interpretasi perlu mempertimbangkan atau
memperbdmgkan antara lahan dengan penggunaan lahan hendaknya
menggunakan kualitas lahan. Namun dalam praktek, karakteristik lahan sering
juga digunakan dalam evaluasi lahan.
Kualitas lahan (land quality) adalah sifat-sifat atau atribut yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan
(performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu. Kualitas lahan ada yang bisa diestirnasi atau diukur secara langsung di
Kualitas lahan kemungkiian berperan positif dan negatif terhadap penggunaan
lahan tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitas lahan yang berperan positif adalah
sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan, sebaliknya kualitas lahan yang
bersifat negatif karena keberadaannya akan merugikan (merupakan kendala)
terhadap penggunaan tertentu, sehingga merupakan faktor penghambat atau
pembatas. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas lahan yang sama bisa
berpengaruh terhadap lebih dari satu penggunaan. Demikian pula satu jenis
penggunaan lahan tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai kualitas lahan.
Contoh kualitas lahan untuk produksi temak, menurut FA0 (1976) dalam
Hardjowigeno dan Widiatmaka (2001) meliputi:
Semua kualitas lahan yang mempengaruhi pertumbuhan tanamanihijauanl
rumput temak, antara lain: ketersediaan air, ketersediaan hara, ketersediaan
oksigen di perakaran, daya memegang unsur hara, kondisi untuk
perkecambahan, mudah tidaknya diolah, kadar gararn, WUI-unsur beracun,
kepekaan erosi, hama dan, penyakit tanaman, bahaya banjir, suhu, sinar
matahari dan periode fotosintesis, iklim, kelembaban udara dan masa kering
untuk pematangan tanaman.
*
Kesulitan-kesulitan Hiyang mempengamhi tern&,*
Ketersediaan air minum untuk temak*
Penyakit-penyakit tern&,Nilai nutrisi dari rumput;
Sifat racun dari rumput;
*
Ketahanan terhadap kerusakan rumput;*
Ketahanan terhadap erosi akibat penggembalaan;Menurut Djaenudin et al. (2003a), karena jumlah karakteristik lahan cukt~p
banyak maka untuk kepentingan evaluasi lahan bisa dipilih dan ditentukan sesuai
dengan keperluan dan kondisi lokal di wilayah yang akan dievaluasi. Untuk
evaluasi lahan pada skala kecil (tingkat tinjau skala 1:250.000) dengan skala besar
(tingkat detil skala 1: 10.000) perlu dipertimbangkan mengenai jumlah dan macam
kualitas serta karakteristik lahan sebagai parameter yang akan digunakan. Sebagai
contoh, parameter untuk evaluasi lahan yang digunakan pada tingkat tinjau, tentu
ketersediaan dan kualitas data pada masing-masing tingkat pemetaan tanah
tersebut.
Kesesuaian Lahan
Kesesuaian lahan adalah kecocokan dari suatu tipe lahan tertentu bagi
penggunaan yang direncanakan (FAO, 1976). Sebagai contoh, lahan sesuai untuk
irigasi, tambak, pertanian tanaman semusim, tanaman hijauan pakan ternak, dan
lain-lain. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan dapat ditinjau dari sifat-sifat fisik
lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi dan atau
drainase yang sesuai untuk suatu usahatani atau komoditas tertentu yang produktif.
Menurut Djaenudi et al. (2003a), dalam menilai kesesuaian lahan ada
beberapa cara, antara lain: dengan perkalian parameter, penjumlahan, atau
menggunakan hukum minimum y a h memperbandingkan (matching) antara
kualitasl karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas kesesuaian
lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau persyaratan
tumbuh tanaman atau komoditas lainnya yang dievaluasi.
Proses klasifikasi kesesuaian lahan adalah penilaian dan pengelompokan
lahan dari area tertentu dengan menentukan kesesuaiannya bagi penggunaan
tertentu. Penilaian kesesuaian lahan tersebut dibedakan menurut kategori sebagai
berikut (FAO, 1976):
Ordo. Kelas kesesuaian lahan menunjukkan apakah lahan dinilai sebagai
sesuai (S) atau tidak sesuai (N) bagi penggunaan yang dipertimbangkan. Ordo S
mempakan lahan dimana penggunaan yang lestari dengan jenis yang
dipertimbangkan diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang mendukung
pemberian input, tanpa resiko kemsakan yang tidak dapat diterima terhadap
sumberdaya lahan. Ordo N merupakan lahan yang mempunyai kualitas yang tidak
memungkinkan penggunaan yang lestari dalam bentuk penggunaan yang
dipertimbangkan.
Kelas. Kelas mencerminkan derajat kesesuaian. Umtan kelas diyatakan
dengan angka, yang makin rendah kesesuaiannya makin besar angkanya pada
-
Kelas S1 (san~at sesuai): Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktorpembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan
secara nyata
-
Kelas S2 (cukuu sesuai]: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktorpembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan
input (masukan). Pembatas tersebut biasanya dapat di atas oleh petani sendiri.
-
Kelas S3 (sesuai marginal): Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat,dan faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan
tambahan input yang lebii banyak daripada lahan yang tergolohg S2. Untuk
mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu
adanya bantuan atau campur tangan pemerintah atau pihak s w a s h
-
Kelas N1 (tidak sesuai pada saat ini). Lahan yang mempunyai faktor pembatasyang berat tetapi masih memungkinkan diatasi, tetapi tidak dapat diperbaiki
dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal. Keadaan pembatas
sedemikian besamya, sehingga mencegah penggunaan lahan yang lestari
dalam jangka panjang.
- Kelas N2 (tidak sesuai selamanya). W a n yang mempunyai faktor pembatas
pemlanen yang mencegah segala kemungkinan penggunaan lahan yang lestari
dalam jangka panjang.
Subkelas. Subkelas mencerminkan macam hambatan, misalnya kelembaban,
bahaya erosi, dan lain-lain. Subkelas dinyatakan dengan humf kecil, misalnya
S2n1, S2e, S3me, dimana m = moisture (kelembaban); e = erosion (erosi). Pada
kelas S1 tidak ada subkelas.
Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Ternak Ruminansia
Faktor sumberdaya lahan berkaitan sangat erat dengan usaha pengembangm
tenlak rrrminnnsin, sebagai tempat hidup dan sebagai penghasil hijauan pakan
temak. Menurut Suratrnan el al. (198) W a s a r k a n kehutuhan lahan, txsaha
pctcrnakan dapat dibedakan nlenjadi dua, yaitu: usaha petemakan yang berbasis
Iahan dan usaha petemakan yang tidak behasis 1ah.m. Menrmrt Dinktomt
peternakan didasarkan pada posisi bahwa: (a) lahan adalah sumber pakan untuk
ternak (b) semua jenis lahan cocok sebagai sumber pakan (c) pemanfaatan lahan
untuk peternakan diartikan sebagai usaha penyerasian antara peruntukan lahan
dengan sistem pertanian, (d) hubungan antara lahan dengan ternak bersifat
dinamis.
Dalam usaha peningkatan produksi, terdapat hubungan segitiga antara lahan
dengan ternak dan hijauan makanan ternak yang merupakan satu kesatuan organis
yang tak terpisahkan dalam usaha tani. Bila salah satu tidak ada maka produksi
yang dihasikan tidak akan memuaskan dan mungkin akan menyebabkan
kegagalan dalam usaha (Susetyo, 1980). Jenis penggunaan l a h k yang dapat
dimanfaatkan oleh peternak antara lain: lahan sawah, tegalan, padang
penggembalaan, dan lahan perkebunan dengan tingkat kepadatan tergantung pada
keragaman dan intensitas tanaman, ketersediaan air, jenis sapi potong yang
dipelihara. Lahan-lahan tersebut memungkinkan pengembangan pola integrasi
ternak-tanaman yang mempakan proses yang saling menunjag dan saling
menguntungkan melalui pemanfaatan tenaga sapi untuk mengolah tanah dan
kotoran sapi untuk pupuk organik sementara lahan sawah dan ladang
menghasilkan l i b a h unsuk pakan ternak seperti jerami padi, jagung dan kacang-
kacangan. Pola integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pakan
ternak, sedangkan kebun dan hutan memberikan sumbangan rumput lapaugan dan
jenis tanaman lain. Pemanfaatan pola integrasi ini diiarapkan dapat meningkatkan
ketersediaan pakan sepanjang tahun, sehingga dapat meningkatkan produksi dan
produktivitas ternak (Ryadi, 2004)
Kelompok ternak ruminansia lebih banyak terpaut pada sumberdaya lahan
dibandingkan dengan kelompok unggas yang pasokan input produksinya dapat
b e d dari luar wilayah bersangkutan sepanjang sarana transportasi dan
pendukung tersedia dengan baik (Lembaga Penelitian IPB, 2001). Lebii lanjut
dinyatakan bahwa penyebaran temak mrninmia akan lebih baik kalau didasarkan
atas faktor-faktor sumberdaya lahan (seperti pola penggunaan lahanlkapasitas
tampung ternak) dan ketersediaan sumberdaya manusia khususnya tenaga keja
Menurut Natasasmita dan Mudikdjo (1980), untuk memperhitungkan potensi
suatu wilayah untuk mengembangkan temak secara teknik, maka perlu dilihat
populasi temak yang ada di wilayah tersebut dihubungkan dengan potensi
makanan ternak yang dihasilkan oleh wilayah yang bersangkutan. Untuk
memperhitungkan potensi wilayah mtuk produksi ternak herbivora @emakan
hijauan) maka perhitungan kepadatan temak teknis yang diperlukan adalah jurnlah
satuan temak (ST) temak herbivora saja. Semakin rendah angka kepadatan
teknisnya, maka berarti kemungkinan wilayah tersebut mempunyai potensi yang
tinggi untuk pengembangan temak. Dari angka kepadatan teknis maka
akan
didapatkan gambaran kasar tentang potensi suatu wilayah untuk pdngembangan
temak. Potensi yang sesungguhnya akan ditentukan oleh tingkat produksi hijauan
makanan temak di wilayah bersangkutan. Kemampuan produksi hijauan makanan
temak akan bergantung kepada: (1) Derajat kesuburan tanah, (2) Iklim, (3)
Tataguna tanah, dan (4). Topografi. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk
memperhitungkan potensi yang sesungguhnya, maka hanya tanah-tanah yang
potensial untuk menghasilkan hijauan makanan ternak saja yang diperhitungkan,
misalnya tanah pertanian, perkebunan, padang penggembalaan dan sebahagian
dari kehutanan.
Hijauan Makanan Ternak
Hijauan makanan temak (Hh4T) merupakan semua bahan yang berasal
dari tanaman dalam bentuk dam-daunan. Kelompok hijauan makanan temak
meliputi bangsa rumput (gramineae), leguminosa, dan hijauan dari tumbuhan lain
seperti daun nangka, waru, dan lain-lain. Hijauan sebagai bahan makanan temak
dapat diberikan dalam dua macam bentuk, yaitu hijauan segar dan hijauan kering.
Hijauan segar berasal dari hijauan segar seperti rumput segar, leguminosa segar
dan silase, sedangkan hijaun kering berasal dari hijauan yang sengaja diieringkan
(hay) ataupun jerarni kering (AAK, 2005).
Khususnya di Indonesia, bahan hijauan memegang peranan penting karena
diberikan dalam jumlah besar. Temak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing
dan domba yang diberi hijauan sebagai bahan tunggal, masih dapat
2005). Bulo (2004) menyatakan, dalam pengembangan temak ruminansia di Indonesia, hijauan makanan temak adalah faktor yang sangat penting dengan
komposisi yang terbesar yakni 70-80% dari total biaya pemeliharaan.
Menurut Reksohadiprojo 1984, jenis tanaman budidaya maupun alami
yang m u m dipergunakan sebagai hijauan makanan temak terdii atas: (1) jenis
rumput-rumputan (gramineae); (2) peperduan/semak (herba); dan (3) pepohonan.
Ada banyak pilihan tersedia bagi spesies hijauan yang berpotensi tinggi,
diantaranya adalah: (a) rumput aladapangan antara lain, rumput para
(Brachiaria mutica), rumput benggala (Panicum maximum), rumput kolonjono
(Panicum muticum), rumput buflel (Cenchrus ciliaris) dan lain-lain; @) peperduan,
baik berupa legum seperti kacang gude (Cajanus cajan), komak (Dolochos lablab)
dan lain-lain; dan peperduan lainnya dari limbah tanaman pangan pertanian antara
lain: jerami padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, daun ubi kayu dan lain-
lain; (c) legum pohon antara lain: sengon laut (Albazia falcataria), lamtoro
(Leucaena leucocephala), kaliandra (Calliandra calothyrsus), turi (Sesbania sp)
dan lainlain. Menurut Manurung (1996), hijauan leguminosa mempakan sumber
protein yang penting untuk temak ruminansia. Keberadaannya dalam ransum
temak akan meningkatkan kualitas pakan.
Limbah Pertanian adalah hasil ikutan dari pengolahan tanaman pangan
yang produksinya sangat tergantung pada jenis dan jumlah areal penanaman atau
pola tanam dari tanaman pangan disuatu wilayah (Makkar, 2002). Menurut
Natasasmita dan Mudikdjo (1980) produksi l i i b a h pertanian yang dapat
dimanfaatkan sebagai hijauan makanan ternak akan sangat tergantung kepada tata
guna tanah dan pola pertaniannya. Beberapa macam jenis liibah pertanian yang
dapat diianfaatkan antara lain: jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah,
pucuk tebu, dan lain-lain. Hasil limbah tanaman palawija pada umumnya bernilai
gizi lebih tinggi daripada jerami padi atau jerami jagung. Pemanfaatan limbah
pertanian untuk temak tersebut akan mendukung integrasi usaha peternakan
dengan usaha pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.
Menurut Preston dan Willis (1974), pemberian limbah padi pada ransum
sapi penggemukan sangat menentukan dalam p e r t a m b b bobot badan dan
dapat digunakan tanaman leguminosa, dengan perbandingan 75 persen konsentrat
dan 25 persen leguminosa (Nasrullah et al., 1996). Cara ini selain dapat
meningkatkan kualitas ransum, juga akan memberikan keuntungan, terutama pada
penggemukan sapi lokal.
Batubara et al. (2002) mengatakan sebahagian besar daerah petemakan
ruminansia (sapi, kerbau, domba dan kambing) di Asia Tenggara memanfaatkan
limbah pertanian (crop residue) seperti jerami pa&, jerami jagung dan pucuk tebu
untuk pakan temak pada musim kering. Demikian pula di daerah pertanian
tanaman pangan yang intensif diiana sumber hijauan pakan temak ruminansia
sangat terbatas, sehingga limbah tanaman pangan mempakan altematif
yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi temak ruminansia.
Produksi limbah pertanian dapat diestimasi berdasarkan asumsi dari
perbandingan antara produk utama dengan limbahnya. OIeh karena itu, estimasi
produksi limbah pertanian dapat menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh
perbedaan angka konversi (rasio) yang digunakan. Produksi limbah pertanian
disuatu wilayah, dapat diperkirakan berdasarkan luas areal panen dari tanaman
pangan tersebut (Jayasuriya, 2002).
Daya Dukung Hijauan Makanan Ternak
Daya dukung digunakan sebagai b a n dari jumlah individu dari spesies
yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu. Secara m u m , daya dukung
berkaitan dengan produktifitas ekosistem. Daya dukung sifatnya tidak tetap, daya
dukung bervariasi bergantung pada faktor dam seperti fluktuasi cuaca dan
i
k
l
i
m
,
dan ini juga secara kontinyu dimodifikasi oleh kegiatiin manusia dan level
teknologi. (Conant, 1983). Daya ddcmg dapat digunakan sebagai alat dalam suatu
kegiatan pembangunan berkelanjutan.
Pengertian daya dukung sudah diienal di kalangan pakar biologi, petemak
sapi dan pengelola satwa liar. Pada spesies hewan, daya dukung dapat
didefinisikan sebagai populasi maksirnum yang dapat didukung dalam suatu
habitat (Khanna et al., 1999).
Produktifitas suatu daerah dalam penyediaan hijauan makanan temak
terhadap temak yang dipelihara khususnya sapi potong. Daya dukung atau daya
tampung temak ruminansia dalam suatu wilayah menunjukkan populasi
maksimum suatu jenis ternak ruminansia yang bisa ditopang di wilayah tersebut
berkenaan dengan kemampuan wilayah dalam menyediakan pakan hijauan.
Populasi temak suatu wilayah yang sudah melebihi daya tampungnya
menunjukkan adanya kebutuhan introduksi teknologi untuk meningkatkan
produktifitas wilayah dalam memproduksi pakan hijauan. Daya tampung ternak
ditentukan melalui perhitungan luas dan daya tampung masing-masing jenis
penggunaan lahan. (Lembaga Penelitian IPB, 200 1).
Menurut Sumanto dan Juarini (2006), daya dukung hijauan makanan
ternak adalah kemampuan suatu wilayah menghasilkan pakan terutama hijauan
yang dapat menampung kebutuhan bagi sejumlah populasi ternak ruminansia
dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tanpa tambahan
khusus. Nilai daya dukung tersebut diperoleh dari total hijauan pakan tercerna
yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan pakan tercerna sejumlah populasi ternak di
wilayah tersebut. Daya dukung hijauan dihitung berdasarkan kebutuhan 1 satuan
temak (ST) sapi potong dalam satu tahun, C i a kebutuhan pakan = populasi
temak (ST)
x
1,14 ton Berat Kering Cerna (BKC)/tahun (umumnya ST dewasa=
250 kg).
Produksi hijauan merupakan produksi relatif untuk masing-masing kelas
kesesuaian yang dikuantifikasikan dalam bentuk perkiraan persentase
produktifitas terhadap tingkat produktifitas maksirnum dengan selang dimana S1
= 80-loo%, S2 = 60-SO%, S3 = 41-60% dari produksi rata-rata masing-masing
hijauan atau daya dukung lahan, sedangkan kelas
N
tidak diperhitungkan(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001).
Indeks Daya dukung (IDD) merupakan perbandingan antara total produksi
hijauan pakan temak dengan kebutuhan ternak ruminansia yang ada pada suatu
wilayah. Nilai indeks ini memberikan gambaran apakah suatu jenis hijauan
makanan temak cukup atau tidak dalam memenuhi kebutuhan ternak pada suatu
/
wilayah. Indeks daya dukung hijauan makanan ternak d i t u n g dari total pakan
dari masing-masing limbah pertanian yang tersedia terhadap jumlah kebutuhan
Juarini (2006), IDD mempunyai 4 (empat) kriteria yaitu: (1) wilayah sangat kritis,
dengan IDD 5 1;
(2)
wilayah kritis, dengan IDD >1-2; (3) wilayah rawan, denganIDD > 1,5-2; dan (4) wilayah aman, dengan IDD > 2. Masing-masing nilai IDD
tersebut mempunyai makna sebagai berikut:
Nilai 5 1 : Temak tidak mempunyai pilihan dalam memanfaatkan sumber
yang tersedia, terjadi pengurasan sumberdaya dalam agro-
ekosistemnya, d m tidak ada hijauan alami maupun limbah
yang kembali melakukan siklus haranya;
Nilai 21- 1,5 : Temak telah mempunyai pilihan untuk memanfaatkan
sumberdaya tetapi belum terpenuhi aspek konsewasi;
Nilai > 1,5
-
2 : Pengembangan bahan organik ke alam pas-pasan;Nilai
>
2 : Ketersediaan sumberdaya pakan secara fimgsional mencukupikebutuhan lingkungan secara efisien.
Pola Pengembangan dan Bentuk Usaha Sapi Potong
Menurut Yusdja dan Ilham (2004), Indonesia memiliki tiga pola
pengembangan sapi potong rakyat dimana ketiga pola ini dapat diembangkan
pada suatu daerah berdasarkan potensi sumberdaya lahan dan pakan. Pertama,
pengembangan sapi potong yang tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan
usaha pertanian terutama sawah dan ladang. Artinya disetiap wilayah persawahan
dan perladangan yang luas maka di sana banyak ditemukan temak sapi. Petemak
memelihara sapi dengan tujuan sebagai sumber tenaga k e j a terutarna pengolahan
tanah dan penarik barang. Oleh karena itu pertumbuhan pertanian akan
mendongkrak pertumbuhan jumlah sapi. Pada sisi lain, perkembangan usaha
pertanian berhubungan erat dengan perkembangan penduduk. Penduduk akan
semakin padat di wilayah yang mempunyai lahan yang subur. Keadaan
i
n
i
menciptakan struktur usaha petemakan berskala kecil. Pola kedua, adalah
pengembangan sapi yang tidak terkait dengan pengembangan usaha pertanian.
Pola ini te jadi di wilayah yang tidak subur, sulit air, temperatur tinggi, dan sangat
jarang penduduk seperti NIT, NTB dan sebagian Sulawesi. Pada umumnya, pada
wilayah seperti ini terdapat padang-padang yang luas yang tidak dapat digunakan
sapi potong yang benar-benar padat modal, dalam usaha skala besar, namun usaha
ini hanya terbatas pada pembesaran sapi bakalan menjadi sapi potong. Perusahaan
penggemukan ini yang dikenal dengan feedlotiers menggunakan sapi bakalan
impor untuk usaha penggemukan. Menurut Sugeng (1998), mengingat kondisi
Indonesia yang mempakan negara agraris maka sektor pertanian tidak dapat
terlepas dari berbagai sektor yang lain diantaranya sub sektor petemakan. Faktor
pertanian dan penyebaran penduduk di Indonesia ini menentukan penyebaran
usaha temak sapi. Masyarakat petemak yang bermata pencaharian bertani tidak
bisa lepas dari usaha temak sapi, baik untuk tenaga, pupuk dan sebagainya
sehingga maju berarti rnenunjang produksi pakan ternak bempa hijauan, hasil
ikutan pertanian berupa biji-bijian atau pakan penguat.
Untuk membuat strategi pengembangan temak ruminansia sesuai dengan
karakteristik dan potensi lahannya, menurut Suratman et al. (1998) pola
pengembangan peternakan dapat mengacu pada pola sebagai berikut:
- IntensiJikasi/diversiJikasi: pengembangan petemakan dilakukan secara intensif,
temak dikandangkan atau digembalakan secara terkendali, diaritkan, disuplai
pakan. Umumnya pola ini dilakukan bersamaan dengan usaha pertanian
lainnya, temak digembalakan bergiliran dengan lahan- tanaman pangan atau
bersamaan disatu lahan yang sama (bagi tanaman yang tidak mudah terganggu
oleh temak);
-
Ektens@kasi: pola pengembangan ternak dengan cara digembalakan pada lahan yang bukan sebagai lahan usaha budidaya pertanian.Sedangkan bentuk usaha petemakan di Indonesia menurut Natasasmita dan
Mudikdjo (1980) pada umumnya dilakukan secara tradisional yang ditandai
dengan: (1) motivasinya berhubungan dengan kedudukan sosial, agruna, sebagai
kesenangan (hobby), sebagai tabungan atau sehubungan dengan usaha
pertaniannya, yaitu sebagai sumber tenaga kerja dalam pengolahan lahan atau
sebagai surnber pup&, (2) diusahakan secara kecil-kecilan sebagai usaha
sambilan dan perhitungan rugi laba tidak menonjol; (3) dilakukan dengan
Sistem Informasi Geografis (SIG)
Sistem informasi geografis (SIG) dapat diartikan secara harafiah sebagai
suatu komponen yang terdiri atas perangkat keras, pemngkat lunak, data geografis
dan surnberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap,
menyimpan, memperbaiki, memperbahami, mengelola, memanipulasi,
mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi
berbasis geografis (F'untodewo et al., 2003). Secara spesifik SIG didefinisikan
sebagai suatu sistem berdasarkan komputer yang mempunyai kemampuan untuk
menangani data yang bereferensi geografi yang mencakup (a) pemasukan, @)
manajemen data (penyimpanan data dan pemanggilan lagi), (c) manipulasi dan
analisis, dan (d) pengembangan produk dan pencetakan (Aronoff, 1989 dalam
Barus d m Wiradisastra, 2000).
Berdasarkan operasinya, Sistem informasi geografi dapat dibedakan menjadi
dua kelompok yaitu: (1) SIG secara manual, dan (2) SIG secara terkomputer atau
SIG otomatis. SIG manual beroperasi memanfaatkan peta cetak ( k e r n /
transparan), bersifat data analog dan biasanya terdii atas beberapa unsur data
termasuk peta-peta, lembar material transparansi untuk tumpang tindii, foto u d ~ a
dan foto lapangan, laporan-laporan statistik dan laporan-laporan survei lapangan.
Sedangkan SIG terkomputer beroperasi sudah dengan menggunakan komputer
sehingga datanya merupakan data dijital namun memerlukan peralatan-peralatan
khusus yang membutuhkan keterarnpilan khusus pula dan membutuhkan biaya
yang besar terutama pada tahap awal pembentukannya. Keuntungan SIG otomatis
dibandingkan dengan SIG manual adalah pada tahap analisis dari penggunaan
data yang berulang-ulang, kompleks dan menggunakan data yang sangat besar
jumlahnya (Barus dan Wiradisastra, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa, salah
satu contoh penggunaan SIG manual adalah dalam perencanaan penggunaan lahan
seperti perencanaan penentuan wilayah pengembangan komoditas tertentu dalam
proses evaluasi kesesuaian lahan yakni dengan membandingkan antara kualitas
lahan dengan persyaratan turnbuh komoditas yang bersangkutan (crop
requirement). Data sumberdaya lahan yang diperlukan adalah (1) data iklim
yang relevan dengan keperluan tanaman, (3) data penggunaan lahan, (4) data
peruntukan lahan, dan (5) data sosial ekonomi.
Wiradisastra (1989) mengemukakan bahwa sistem informasi sumberdaya
a l d l a h a n dikembangkan dengan tujuau agar dalam menjawab kebutuhan
informasi dan analisis dapat lebih fleksibel sehingga kemajuan-kemajuan dan
perubahan-perubahan baru dapat selalu dipertimbangkan untuk meningkatkan
ketelitian dan updating sesuai dengan berkembangnya waktu. Salah satu tujuan
adalah dalam menjawab kebutuhan analisis kelayakan lahan bagi usaha pertanian
dalam hubungan penatagunaan lahan atau evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah
proses yang merupakan penghubung antara sistem infomasi dengan pengguna
informasi yang pada umumnya para perencana.
Sistem infomasi geografis (SIG) mempunyai ciri utarna yakni
kemampuannya mengintegrasikan data, baik yang sejenis maupun gabungan data
spasial seperti data penginderaan jauh dengan data non-spasial (atribut) seperti
data perpustakaan dan data lapangan. Oleh sebab itu, integrasi SIG dengan
teknologi GPS (Global Positioning System) dan inderaja benginderaan jauh)
sebagai surnber input data, akan sangat bemanfaat untuk mendapatkan h a i l yang
lebih baik, akurat dan up to date. Salah satu bentuk data GPS adalah berbentuk
titik tinggi dan koordiiat, yang selanjutnya dapat diinterpolaszkan pada SIG.
Bentuk integrasi SIG dan inderaja misalnya adalah pemanfaatan foto udara atau
citra satelit diiana hasil interpreiasi foto udara atau citra dipindahkan kesuatu
peta. Tahap selanjutnya, peta tersebut dapat didigitasi untuk diiasukkan ke dalam
SIG.
Penginderaan Jauh untuk PenutupadPenggunaan Lahan
Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi
tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh
dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau daerah yang
dikaji. Pada berbagai hal, penginderaan jauh dapat diartikan sebagai suatu proses
membaca. Dengan menggunakan sensor kita mengumpulkan data dari jarak jauh
yang dapat dianalisis untuk medapatkan infomasi tentang objek, daerah atau
Perkembangan teknologi satelit penginderaan jauh dewasa ini
memungkinkan dilakukannya pemetaan sumberdaya aladahan. Untuk maksud
identifikasi dan pemetaan jenis tanaman dari citra Landsat, cara yang paling
efektif adalah dengan mengamati pada dua saluran atau lebii secara bersama-
sarna dengan bantuan alat pengamat wama aditif atau melakukan interpretasi pada
citra paduan wama. Menurut Hanggono (1999), analisis jenis penutupant
penggunaan lahan dilakukan melalui pengolahan citra dengan tahapan yakni: (1)
penyiapan citra asli, dan (2) analisis dan interpretasi citra. Tahap penyiapan
dilakukan ketika akan menggunakan sebuah citra satelit, yakni dengan melakukan
koreksi geometri (akibat pengaruh rotasi dan bentuk bumi, efek panoramik,
perubahan kecepatan dan variasi ketinggian satelit) dan koreksi radiometri, untuk
mengurangi kesalahan perekaman nilai pixel yang diakibatkan adanya pengaruh
azimut matahari dan kondisi atmosfer seperti kabut aerosol, dan sebagainya.
Sedangkan tahap analisis dan interpretasi citra dilakukan dengan klasifikasi dan
interpretasi visual citra. Interpretasi citra secara visual dapat dilakukan dengan dua
metode, yaitu penajaman citra (image enhancement) dan visualisasi dalam warna
semu (color composite). Penajaman citra bertujuan meningkatkan kontras objek-
objek geografis yang tergambar pada citra Sedangkan penampilan dalam
komposisi wama semu, seringkali lebih mempermudah pengenalan objek melalui
perbedaan wama.
Tujuan dari suatu prosedur analisis citra adalah untuk mendapatkan
deskripsi dan kelas penutupan dan penggunaan lahan secara menyeluruh
mengenai lokasi penelitian. Salah satu penerapan yang sering dilakukan adalah
segmentasi atau klasifikasi citra dengan tujuan men&asilkan informasi tutupan
lahan. Klasifikasi citra dilakukan secara terbimbiig (supervised classz~cation)
dengan metode kemiripan maksimum (maximum likehood classification atau
BAHAN
DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
(Gambar 1) terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan. Secara geografis
terletak antara 2'50' - 3'19' Lintang Utara dan 97'55' - 98'38' Bujur Timur
dengan batas-batas wilayah adalah:
- SebelahUtara : Kabupaten Langkat dan Deli Serdang
-
Sebelah Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir '- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun
-
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi NAD)Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan September 2006.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan
data primer yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data tersebut berupa peta,
citra satelit dan data tabular, seperti ditunjukkan pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Jenis dan sumber peta dan data sekunder
No. Jenis Data Skala Tahun Bentuk Sumber Data
Peta dan citra satelit
Peta satuan lahan dan tanah
Lembar Medan (0619) dan
Lembar Sidikalang (0618) Peta Rupabumi Kabupaten Karo Peta administrasi Kabupaten Ka