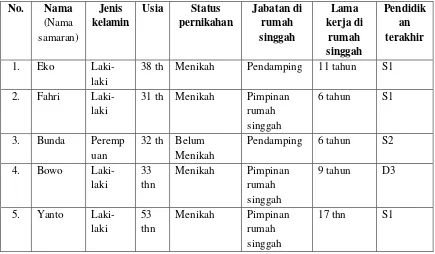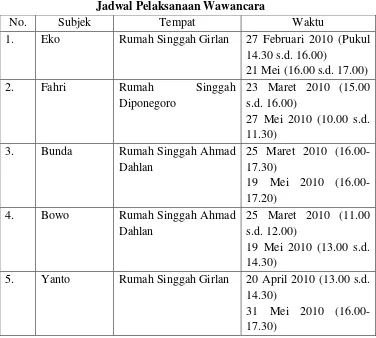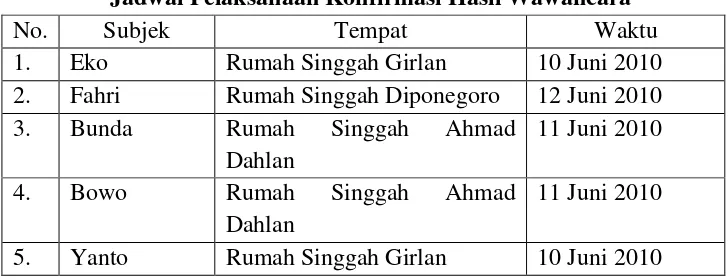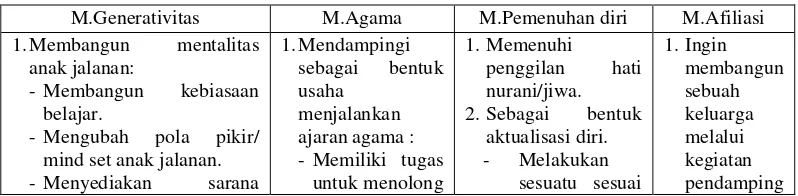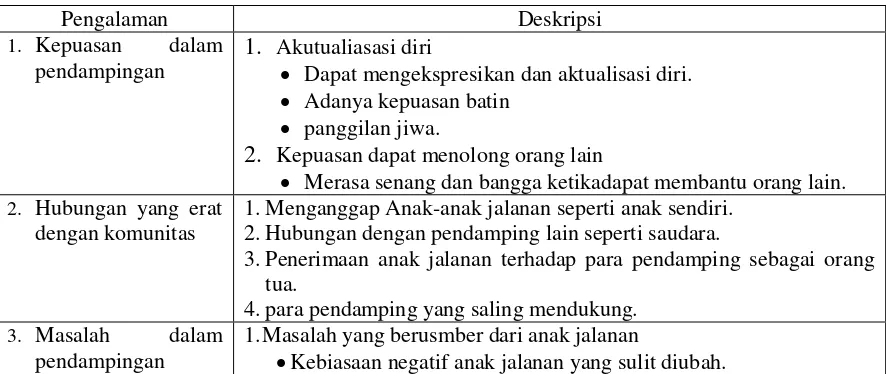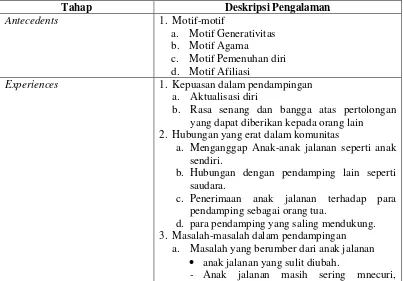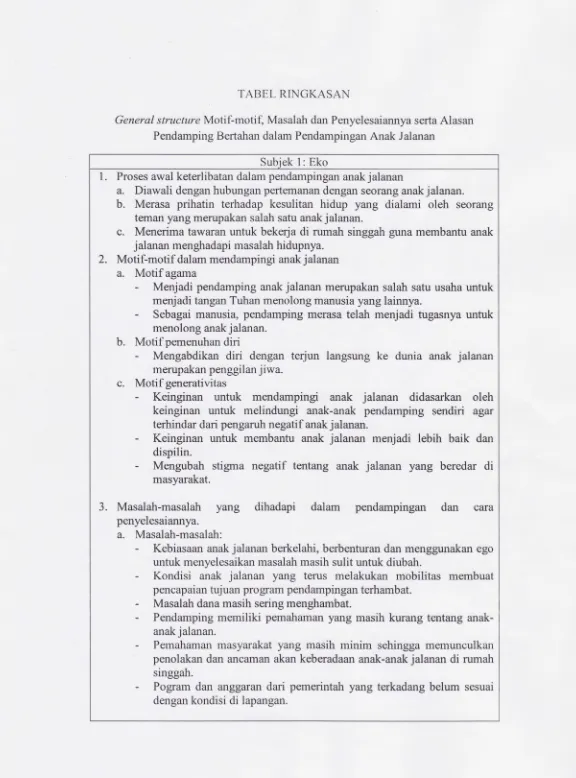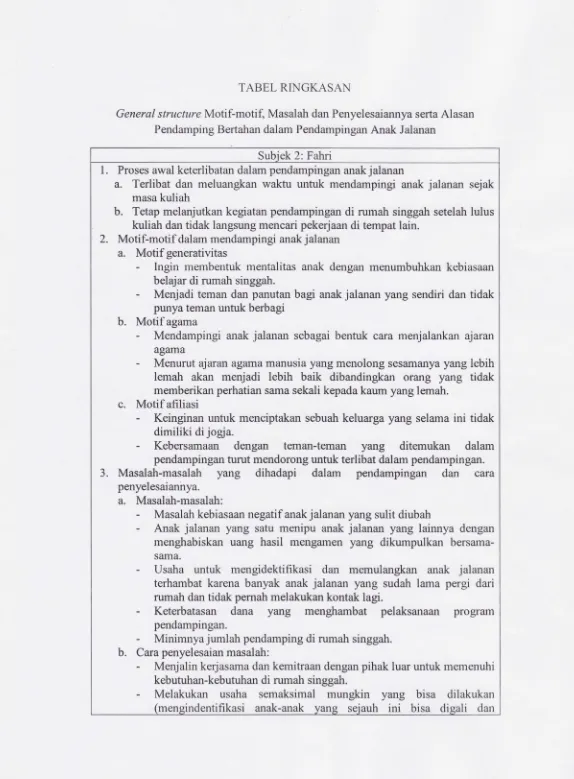Skripsi
Diajukan untuk Menenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi
Disusun oleh:
Elycia Widiastuti
069114084
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JALANAN DENGAN VOLTTNTEER
PROCESS
MODEL
Dosen Pembimbing
ll B BEC
zolo
JALANAN DENGAN VOLTINTEER
PROCESS
MODEL
Dipersipkan dan ditulis oleh: Elycia Widiastuti
069114084
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji adatanggal 15 November 2010 dan dinyatakan memenuhi syarat
Susunan Panitia Penguji
Tanda Tangan Nama Lengkap
I
1. V. Didik Suryo Hartoko, S.Psi., M.Si 2. Drs. Hadrianus Watryudi, M.Si 3. MM. Nimas Eki. S, S.Psi, Psi., M.Si
0 gmc ?0I0
Y o g y a k a r t a q o . o r. o . . o o . . . o . . o . . . o .'Fal:ultas Psikologr niversitas Sanata Dharma
Dekan
Dr. Ctristina Siwi Hand-tt* S. psi., M. Si.
a a o
iv
v
Tuhanku “Yesus Kristus”
Bapak dan Mama tercinta
Abang dan Adik-adikku
Yang bertanda tangan ali bawah ini, saya Elycia Widiastuti menlatakan bahwa shipsi saya yang berjudul *studi Deskripstif Te,rrtang pendamping Anak Jalanan dengran Yolunteer Process Mode|'ini tidak menruat karya orang lain kecuali yang telah saya sebut dalam kotipatr dan daftar pustaka sebagaimana layaknyakar5la ilmiah
Yogyakarta
t. .q
.ry?.
. lTlo
Penulis
Elycia Widiastuti
vii ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman para pendamping dalam mendampingi anak jalanan dengan menggunakan model volunteer process. Model volunteer process merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan pengalaman pendamping dalam tiga tahap yaitu tahap antecedents, experiences, danconsequences. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan 1 orang pendamping dari Rumah singgah Diponegoro, 2 orang pendamping dari Rumah singgah Ahmad Dahlan, dan 2 orang pendamping Rumah singgah Girlan Nusantara. Analisis data dilakukan dengan cara organisasi data dan koding hingga ditemukan tema-tema hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pada tahap Antecendents motif-motif para pendamping dalam mendamping anak jalanan adalah motif generativitas, motif agama, motif pemenuhan diri, dan motif afiliasi. Pada tahap Experiences,
pendamping memperoleh kepuasan, hubungan yang erat dengan komunitas serta pengalaman mengahadapi masalah. Masalah yang dihadapi oleh para pendamping meliputi masalah yang bersumber dari anak jalanan, masalah struktural rumah singgah, dan masalah yang bersumber dari luar rumah singgah. Para pendamping melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara bekerjasama dengan pihak lain, melakukan usaha mandiri, menentukan sikap terhadap anak jalanan, menyakinkan diri untuk mampu menghadapi masalah, dan berserah kepada Tuhan. Pada tahap Consequences,Para pendamping memperoleh hasil adanya perubahan yang lebih baik pada anak jalanan serta masyarakat. para pendamping juga tetap bertahan dalam pendampingan anak jalanan didorong oleh rasa tanggung jawab.
viii
ABSTRACT
This reserach aims at describing the experiences of counselors in the process of street children guidance using volunteer process model. This model is a conceptual framework which describes the experiences of the counselors in three stages; antecedents, experiences, and consequences. Data sampling are done by doing in depth interview with a counselor from rumah singgah Diponegoro, two counselors from rumah singgah Ahmad Dahlan, and two counselors from rumah singgah Girlan Nusantara. Data analysis is done by organizing the data and coding until the themes of research are found. Based on the data analysis, it is found that on the Antecedents strage, the motives of the counselors are generativity, religion, self fulfillment, and afiliation. On the Experiences stage, councelors received satisfation, relation with community and also the experience face the problems. The common problems of the counselors are problem from the street children themselves, problem from inside and/or outside rumah singgah. The counselors did some efforts to solve the problems by making a cooperation with other parties, independent efforts, decide the attitude for the children, convince themselves that they can do this, and surrender to the God. On the Consequences stage, the councelors found tha positif changes with the street children and society. The counselors still survive in the process of the guidance because they feel it is their responsibility.
bertanda tangan di bawah ini:
mernberikan karya sa),a yang berjudul "Studt Deskriptif Tentang Pendamping Anak Jalanan dengan Yolunteer Process ModeP' kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.
Oleh karena itu, Perpustakaan Sanata Dharma berhak menyimpan, mengalitrkan dalam Bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari sa)ra maupun mernberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebeirarnya. Nama
NIM
Yogyak arta,*.. Penulis
Elycia Widiastuti
: Elycia Widiastuti : 069114084
ffiil
il ?fr'f$
x
menyelesaikan kuliah ataupun mendapatkan gelar Sarjana tetapi juga merupakan
sebuah proses yang membuat penulis semakin mengenal kekuatan dan kelamahan
di dalam diri. Banyak sekali pengalaman yang penulis peroleh selama
menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Mulai dari semangat yang
menggebu-gebu untuk mengerjakan skripsi hingga upaya memotivasi diri sendiri ketika
semangat mulai pudar. Pengalaman bertemu dengan para subjek dan anak jalanan
juga telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi penulis tentang kehidupan.
Tentunya ini merupakan sepenggal pengalaman hidup yang akan memberikan
senyum dan tawa haru ketika mengenangnya.
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak
terlepas dari campur tangan Dia yang tak terlihat namun selalu ada dalam lubuk
jiwa. Terima kasih kepada My Super Hero “Yesus Kristus” yang selalu
memberikan kekuatan dalam pengharapan. Semua tak kan berarti apa-apa tanpa
penyertaanMu.
Penyertaan Tuhan sangat penulis rasakan dalam diri setiap pribadi yang
telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh bantuan kalian
tentunya sangat berharga bagi penulis, untuk itu penulis ingin mengucapkan
xi
2. Ibu Dr. Ch. Siwi Handayani, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi yang telah
membantu dalam proses perijinan.
3. Bapak Minta Istono, S. Psi, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang
telah banyak memberikan dorongan agar segera lulus.
4. Segenap staf Fakultas, Mas Gandung, yang sudah sangat membantu dalam
proses surat menyurat, kroscek nilai serta pendaftaran ujian, Bu Nanik, atas
kerjasamanya saat mengurusi LPJ-LPJ ketika penulis mengikuti kegiatan
kepanitiaan di kampus, Mas Doni, yang telah memberikan palayanan yang
menyenangkan saat mencari buku-buku referensi, Mas Muji, yang telah
membantu penulis saat mengambil mata kuliah praktikum, maaf ya Mas gak
bisa bantu jadi asisten saya mau cepat lulus hehehe, Pak Gie, yang baik hati
dan selalu memberikan senyum tulus ketika berpapasan di kampus.
5. Bang “Eko”, Pak “Fahri”, Mba “Bunda”, Pak “Bowo”, dan Om “Yanto, yang
telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman untuk membantu proses
penulisan skripsi ini.
6. Bapak Priyono, SH, selaku pimpinan Rumah singga Girlan Nusantara, Bapak
Fauzan Setianegara, selaku pimpinan Rumah singga Diponegoro, dan Bapak
xii
7. Bapak C.Siswa Widyatmoko, S.Psi, M.Si yang telah memberikan kesempatan
untuk menjadi asisten di kelas MPP dan kesempatan bekerjasama di Tim PBB.
8. Bapak “C. Ayan Dihin”, atas doa dan cinta yang tak henti-hentinya untukku
“Anda adalah inspirator saya”, Mama “Filisitas”, yang telah mendidikku
untuk mandiri sejak kecil “Sekarang saya sudah dewasa ma, terima kasih
sudah melahirkan saya ke dunia ini”, Adik-adikku “Maria Vieany Pariani” dan
“Diki Ferdinand”, atas canda tawa dan air mata ketika kita berantem, jangan
bosan-bosan mendengar nasihatku ya, Abangku “Merryo Andreas Chrismana”,
yang telah menemaniku saat pertama kali di Jogja. cepatlah kau menikah.
9. Keluarga keduaku di Kost Palem: Miranda, Noby, Atha, Mba Adel, Mba
Babay, Mbandoels, Aprina, Mba Nana, Mba Wening, Mba Lusi, Mba Puput,
Wene, dan Lia; di Kost Welcome: Karla, Eka, Widya, Mami, Dika, Mba Lily,
Shinta, Shelly, dan Tyas; di Kost Puri liberty: Mida, Ani, Dinar, Irna, Afgred,
dll. Terima kasih telah menjadi rumah dan keluarga bagiku ketika beada di
Jogja, semoga kita masih bisa saling kontak dan maaf kalau aku ada salah ya.
10. Teman-teman yang pernah menyebut diri sebagai BBF “Best Friend
Forever”, Eurike “Ike” Christiani Hutauruk, Lenny Lolita “Zippo” Ginting,
Yohana “Jojo” Yuliastuti Sihombing, terima kasih karena pernah menjadi
rumah untukku, rumah itu sepertinya sekarang sedang sepi kapan-kapan
xiii
11. Teman-teman di Great tim PBB : Pak Siswo, Mba Haksi, Mba Devi, Mba
Via, Mba Astuti, Corry, Budi, Pudji, Nita, dan anggota tim yang sebelumnya,
terima kasih ya atas kebersamaan kita selama ini, banyak pengalaman luar
biasa yang aku dapatkan bersama kalian mulai dari pengalaman meneliti,
bekerja dalam tim, jalan-jalan ke Malang, jalan-jalan ke Bantul serta
persahabatan yang telah kita bina. Sangat senang bertemu dengan kalian
semua.
12. Teman-teman angkatan 2006 : Ari, Timo, Abe, Christ, Yoga, Yupha, Hermin,
Thea, Andien, Nita, Bhekti, Jenny, Riana, Yaya, Emak, Viany, Erisa, Mia,
Lolita, Yesica, serta teman-teman yang lainnya atas kebersamaan kita di
xiv
HALAMAN PERSETUJUAN ………... ii
HALAMAN PENGESAHAN ………... iii
HALAMAN MOTTO ……… iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ……… v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ……… vi
ABSTRAK ………. vii
ABSTRACT ………... viii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ……….. ix
KATA PENGANTAR ………... x
DAFTAR ISI ……….. xiv
DAFTAR SKEMA ………. xviii
DAFTAR TABEL ……….. xix
DAFTAR LAMPIRAN ……….. xx
BAB I. PENDAHULUAN ………. 1
A. Latar Belakang Masalah ……….... 1
B. Rumusan Masalah………... 7
C. Tujuan Penelitian ……….. 8
D. Manfaat Penelitian ……… 8
BAB II. LANDASAN TEORI ………. 9
xv
4. Pendampingan anak jalanan ………. 13
B. Pendamping Anak Jalanan ………... 15
1. Sukarelawan ……… 17
a. Definisi ………... 17
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin menjadi sukarelawan ……….. 19
c. Sukarelawan dan perilaku prososial ………... 21
C. ModelVolunteerr Process………..……... 22
1. TahapAntecedents………..……..……..……..…… 22
2. TahapExperiences…………..……..……..……..…….. 25
3. TahapConsequences….……..……..……..……..…….. 29
C. Pendamping dan Tahap Perkembangan Generativitas vs Stagnasi ……….. 31
BAB III. METODE PENELITIAN ………... 33
A. Jenis Penelitian ………. 33
B. Subjek Penelitian ………..…….... 34
1. Teknik pengambilan data ……….. 34
2. Karakteristik subjek ……….. 35
C. Pengambilan Data ……..……..……..……..……..……….. 36
1. Metode pengambilan data ……… 36
xvi
2. Dependability ………... 41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………. 43
A. Para Pendamping dan Pertemuannya dengan Anak Jalanan .. 43
1. Latar belakang pendamping anak jalanan ………. 43
2. Pertemuan pendamping dengan anak jalanan …………... 48
B. Pengalaman Pendamping Pada TahapAntecendents……… 50
1. Motif-motif dalam mendampingi anak jalanan ……….... 50
C. Pengalaman Pendamping Pada TahapExperiences……….. 56
1. Kepuasan yang diperoleh dalam mendampingi anak jalanan ……….. 56
2. Hubungan yang erat dengan komunitas pendampingan.... 57
3. Masalah dan cara penyelesaiannya ……….. 58
D. Pengalaman Pendamping Pada TahapConsequences……... 70
1. Perubahan anak jalanan ke arah yang lebih baik ………... 70
2. Perubahan pandangan masyarakat terhadap anak jalanan.. 71
3. Keberlanjutan dalam pendampingan ………. 71
E. Pembahasan Umum ……… 75
BABV. KESIMPULAN DAN SARAN ……….. 83
A. Kesimpulan ……….... 83
xviii
Volunteer Process Model………. 30
Skema 2: Skema Pengalaman Pendamping Anak Jalanan Menurut
xix
Tabel 2: Panduan Wawancara ……… 36
Tabel 3: Jadwal Pelaksanaan Wawancara ………... 38
Tabel 4: Jadwal Pelaksanaan Konfirmasi Hasil Wawancara ………. 41
Tabel 5:General SummaryPengalaman Pendamping Pada Tahap
Antecedents ………. 55
Tabel 6:General SummaryPengalaman Pendamping Pada Tahap
Experiences ………. 68
Tabel 7:General SummaryPengalaman Pendamping Pada Tahap
Consequences ………. 73
Tabel 8:General SummaryPengalaman Pendamping Anak Jalanan
xx
Koding hasil wawancara subjek 2 ……… 101
Koding hasil wawancara subjek 3 ………...…….. 109
Koding hasil wawancara subjek 4 ……….……… 117
Koding hasil wawancara subjek 5 ……… 124
Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 1 ………... 126
Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 2 ………... 128
Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 3………... 130
Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 4 ………... 132
Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 5 ………... 134
Surat ijin penelitian 1 ……… 135
Surat ijin penelitian 2 ……… 136
Surat ijin penelitian 3 ……… 137
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jumlah anak-anak yang berkeliaran di jalanan dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan. Khusus di kota Yogyakarta, jumlah anak jalanan
pada tahun 2009 meningkat sebanyak 50% dari tahun 2008. Sebagian besar
anak-anak jalanan ini bukanlah penduduk asli Yogyakarta. Dari 1.363 anak
jalanan yang ada, hanya 312 anak jalanan (22,18%) yang merupakan
penduduk asli kota Yogyakarta, 967 anak jalanan (70,98%) berasal dari luar
Yogyakarta, dan sisanya tidak jelas asalnya (“Jumlah Anak Jalanan”, 2009).
Rata-rata anak jalanan ini merupakan anak-anak di bawah umur dan ketika
berada di jalanan, berprofesi sebagai pengamen, pemulung, penyemir sepatu,
peminta-minta, tukang parkir tidak resmi, pembantu di warung lesehan dan
kerajinan kaki lima serta pekerja serabutan. Ada pula anak jalanan yang
bekerja sebagaistreet guideatauThethekyaitu pemberi jasa pengantaran bagi
wisatawan yang datang ke Yogyakarta (Surjono, 2000)
Masalah anak jalanan ini sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian
pemerintah. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2000 pemerintah telah melakukan
berbagai tindakan untuk menangani masalah anak jalanan (Surjono, 2000).
Mulai dari melakukan upaya yang bersifat represif, pembinaan dan kemudian
pendampingan. Mulanya pemerintah memandang anak jalanan sebagai
komunitas yang harus diminimalisasi keberadaannya, kemudian anak jalanan
dipandang sebagai komunitas yang perlu didampingi hingga diberikan
pembinaan.
Pendampingan anak jalanan merupakan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan anak jalanan. Pendampingan anak jalanan bukan
hanya sekedar upaya menghapus anak-anak dari jalanan melainkan juga
meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan (Tomy, 2010). Tujuan utama
dari sebuah pendampingan yang diberikan kepada anak jalanan pada intinya
adalah agar anak-anak jalanan tidak lagi kembali ke jalanan dan
mengkondisikan mereka agar tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan tanpa
menimbulkan suatu pola keterikatan kepada para pendamping (Petter Coping
dalam Surjono, 2000).
Pendampingan anak jalanan dapat dilakukan dengan membentuk pos-pos
atau basis-basis yang dijadikan sebagai pusat pelayanan. Secara umum,
terdapat lima basis pendampingan anak jalanan, yaitu Basis Jalanan, Basis
Rumah Singgah, Basis Panti, Basis Masyarakat dan Basis Keluarga (Astutik,
2001). Basis pendampingan yang paling banyak dilaksanakan di Yogyakarta
adalah Basis Rumah Singgah, mengingat karakteristik anak jalanan yang ada
di Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta. Hal ini pulalah
yang mendorong peneliti melakukan penelitian di Rumah Singgah.
Pendampingan di Rumah Singgah bertujuan untuk mengkaji kondisi anak
Di rumah singgah, para pendamping berusaha memberikan sarana-sarana
bagi anak jalanan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Mulai dari
kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pembinaan moral
juga diberikan kepada anak jalanan agar mereka dapat memiliki sikap dan
perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat
(Setiawati, 2005). Proses pendampingan tentunya tidak berhenti sampai di
situ saja, mengingat kemiskinan merupakan faktor yang paling banyak
menyebabkan munculnya anak jalanan maka di rumah singgah, para
pendamping berusaha untuk memberikan alternatif solusi dengan
mengadakan program keterampilan usaha dan memberikan modal (Hartanti,
2008). Pembekalan keterampilan usaha kepada anak jalanan, diharapkan
dapat membantu anak-anak jalanan mendapatkan penghidupan yang layak.
Upaya pendampingan anak jalanan ini dilaksanakan oleh tenaga kerja
yang disebut dengan pendamping anak jalanan. Tenaga kerja tersebut ada dua
macam yaitu yang disebut pekerja sosial profesional dan relawan sosial anak.
Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga
pemerintaha maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan
sosial (Keputusan MenSos RI, 2010). Pekerja sosial dalam kerangka birokrasi
merupakan salah satu saluran pembinaan karir PNS melalui jalur jabatan
fungsional (Hidayat, 2000). Sedangkan Relawan sosial anak adalah seseorang
dan atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial
kesejahteraan sosial anak bukan dari instansi sosial pemerintah atas kehendak
sendiri dengan atau tanpa imbalan (Keputusan MenSos RI, 2010).
Pendamping pada dasarnya memiliki peran besar dalam menentukan
keberhasilan program penanganan anak jalanan. Peran pendamping dalam
pendampingan anak jalanan umumnya mencakup empat peran utama, yaitu
sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis
bagi anak jalanan yang didampinginya (Tomy, 2010).
Peran pendamping sebagai fasilitator merupakan peran yang berkaitan
dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi anak jalanan.
Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model
dan memberi dukungan bagi anak jalanan. Sebagai pendidik, pendamping
berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif
berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bagi anak jalanan.
Peran pendamping sebagai perwakilan masyarakat dilakukan
berhubungan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga
eksternal atas nama dan demi kepentingan anak jalanan yang didampinginya.
pendamping dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan,
menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan jaringan
kerja. Para pendamping dituntut pula untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis
sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, dan
Pada kenyataannya usaha para pendamping untuk menjalankan perannya
dalam mengatasi permasalahan anak jalanan melalui pendampingan di rumah
singgah bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak kendala yang dialami
oleh para pendamping yang terjun secara langsung dalam mendampingi anak
jalanan. Pertama-tama, para pendamping dihadapkan pada permasalahan dari
dalam rumah singgah seperti keterbatasan dana untuk menjalankan
program-program pendampingan Dana yang terbatas membuat para pendamping tidak
bisa menjalankan program yang telah disiapkan untuk mendampingi anak
jalanan. Hal ini hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Harmaini (2008) mengenai masalah dana, para pendamping kesulitan untuk
menjalankan program-program bagi anak jalanan karena biaya yang
dibutuhkan sangat banyak sedangkan dana yang dimiliki sangat minim.
Kondisi yang demikian membuat para pendamping mau tidak mau harus
menentukan skala prioritas untuk menjalankan program yang paling
dibutuhkan anak jalanan terlebih dahulu, seperti program pelatihan untuk
peningkatan ekonomi anak jalanan.
Permasalahan lain yang juga dihadapi para pendamping dalam rumah
singgah meliputi lingkungan kerja dan kebijakan seperti imbalan yang tidak
memadai untuk mencukupi kebutuhan. Terbatasnya fasilitas kerja seperti
transportasi dan jaminan kesehatan, serta kurangnya penghargaan dari
lembaga terhadap para pendamping (Moeliono dan Dananto, 2004).
Permasalahan selanjutnya yang dihadapi para pendamping adalah masalah
anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima
keberadaan anak jalanan sebagai bagian dari masyarakat. Di lingkungan
sosial, stigma-stigma negatif masih menempel pada anak jalanan (Astutik,
2001). Harmaini (2008) menemukan bahwa anak jalanan masih dipandang
sebelah mata dan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat.
Begitu kompleksnya permasalahan dalam pendampingan anak jalanan
telah menghadapkan para pendamping kepada permasalahan baru yang
berpengaruh pada kinerja pendamping. Para pendamping dihadapkan pada
masalah-masalah internal seperti menurunnya motivasi kerja, kejenuhan
dengan pola kerja, dan kehilangan kesabaran karena berbagai masalah pribadi
dan pekerjaan (Moeliono dan Dananto, 2004). Permasalahan ini berpengaruh
pada kelanjutan keterlibatan pendamping dalam pendamping. Dengan adanya
permasalahan-permasalahan tersebut banyak pendamping hanya bertahan
kurang dari dua tahun. Hanya ada segelintir yang tetap bertahan untuk
mendampingi anak-anak jalanan lebih dari lima tahun.
Walaupun usaha pendampingan anak jalanan kerap diwarnai dengan
berbagai masalah, namun pendampingan di rumah singgah juga memberikan
pengalaman yang menyenangkan tersendiri bagi para pendamping.
Sebagaimana yang dialami oleh salah seorang pendamping bernama
Muhammad Yunus, seorang pendamping anak jalanan di Makasar.
Keterlibatannya sebagai pendamping memberikan kebahagiaan tersendiri
baginya. Pendamping merasa bahagia ketika dapat menolong anak-anak
memberikan pendidikan kepada anak jalanan dengan mengajari anak-anak
jalanan membaca dan menulis, pengetahuan umum dan berbagai
keterampilan. Hal ini terus dilakukan Yunus bahkan setelah program Lakzis
selesai (“Di jalanan”, 2009).
Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, peneliti tertarik untuk
mengungkap pengalaman para relawan pendamping yang mendedikasikan
hidupnya untuk membantu dan mendampingi anak jalanan di rumah singgah.
Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap perjalanan karir
pendamping anak jalanan dengan menggunakan kerangka konseptual model
volunteer process tersebut. Menurut model Volunteer process, secara
konseptual perjalanan karir seorang relawan termasuk pendamping anak
jalanan meliputi tiga tahap yaitu antecedents, experiences, danconsequenses
(Omoto dan Snyder, 1995). Tahap antecedents merupakan tahap awal
keterlibatan relawan yang berusaha menggambarkan mengenai hal-hal yang
membuat seseorang dapat terlibat sebagai sukarelawan. Tahap experiences
merupakan tahap yang berisi berbagai pengalaman yang dirasakan oleh
sukarelawan saat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendamping anak
jalanan. Tahap yang terakhir yaitu consequenses merupakan tahap terakhir
dari perjalanan karir sukarelawan yang berusaha mengungkap konsekuensi
apa yang akan diterima atau dilakukan oleh relawan selanjutnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah:
Bagaimanakah pengalaman pendamping dalam mendampingi anak jalanan?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
Mengetahui pengalaman pendamping dalam mendampingi anak jalanan
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan
pengetahuan dalam ilmu psikologi sosial tentang perilaku menolong
khususnya perilaku menolong sebagai seorang sukarelawan.
2. Manfaat praktis
Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai informasi tambahan bagi
Rumah singgah, Organisasi sosial dan Yayasan sosial tentang pengalaman
pendamping anak jalanan yang sanggup bertahan dalam kurun waktu
yang cukup lama sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk merekruit
pendamping baru. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai
materi penyuluhan tentang pengalaman mendampingi anak jalanan
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Anak Jalanan 1. Definisi
Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, yang
menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan
kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya
(Shalahuddin, 2004). Agustin (2002) dalam studi kualitatifnya mendefinisikan
anak jalanan sebagai anak berusia 5 sampai dengan 15 tahun yang tidak
bersekolah lagi, tidak tinggal bersama orang tua mereka, serta bekerja di
jalanan dan tempat-tempat umum untuk memperoleh penghasilan.
Secara garis besar anak jalanan dikelompokan dalam tiga kategori
(Surbakti, 1997), yaitu sebagai berikut:
a. Children on the street
Adalah anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai pekerja
anak di jalan dan masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua
mereka. Anak-anak jalanan ini bekerja dengan tujuan untuk membantu
perekonomian keluarga karenan tekanan kemiskinan yang tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh orang tua.
b. Children of the street
Adalah anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara
sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara anak jalanan ini masih
menjalin hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuannya
tidak menentu. Anak-anak ini turun ke jalanan didorong oleh suatu
penyebab, misalnya seperti lari dari rumah.
c. Children from families of the street
Yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.
Anak-anak ini hidup bersama-sama orang tuanya dengan gaya hidup yang
berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kelompok
anak jalanan ini dapat ditemui dengan mudah di sekitar kolong jembatan,
rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan bantaran sungai. Salah satu
ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak
anak masih bayi dan bahkan sejak masih dalam kandungan.
2. Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan
Literatur menunjukkan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab
anak-anak di bawah umur turun ke jalan. Menurut Departemen sosial secara umum
ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan, yaitu:
a. Tingkat mikro
Pada tingkat mikro faktor penyebab anak turun ke jalan berkaitan
dengan anak dan keluarganya. Biasanya anak turun ke jalan dapat
dikarenakan anak lari dari rumah, disuruh bekerja, ingin berpetualang,
bermain-main atau diajak teman.
Dari sisi keluarga, dapat pula dikarenakan anak terlantar dan
jarang pula anak jalanan mengalami penolakan dari orangtua dan menjadi
korban kekerasan di rumah.
b. Tingkat meso
Pada tingkat meso, faktor keberadaan anak di jalanan terkait dengan
faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Faktor pertama adalah
kemiskinan, anak-anak merupakan aset dalam masyarakat miskin untuk
membantu meningkatkan kondisi keluarga. Sehingga banyak anak-anak
yang diajarkan untuk bekerja yang berakibat keluar dari sekolah.
Kedua, urbanisasi yang sering terjadi dalam masyarakat turut diikuti
oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini kemudian
menyebabkan semakin banyaknya anak-anak yang berada di kota dan
akhirny harus bekerja untuk mempertahankan hidup.
Ketiga, faktor penolakan masyarakan terhadap anak jalanan yang
dianggap sebagai calon kriminal. Hal ini membuat anak-anak yang telah
turun ke jalan mengalami kesulitan untuk kembali ke masyarakat.
c. Tingkat makro
Tingkat macro merupakan faktor yang berhungan dengan struktur
makro. Beberapa diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan dan
keterbatasan cara penanganan anak jalanan.
Faktor ekonomi meliputi adanya peluang pekerjaan sektor informal
yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian. Sehingga anak-anak lebih
memilih berada di jalan dibanding di bangku sekolah. Hal ini ditambah
yang diskriminatif. Anak jalanan juga dihadapkan pada
ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.
3. Kehidupan anak jalanan
Paparan mengenai kategori anak jalanan sebelumnya menunjukkan bahwa
terdapat beberapa anak jalanan yang masih berhubungan dengan orangtua dan
keluarganya serta ada pula yang tidak. Sebagian besar anak jalanan telah putus
sekolah dan harus bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata
anak jalanan ini bekerja sebagai pengamen, pemulung, penyemir sepatu, dan
peminta-minta. Selain itu ada pula yang bekerja sebagai tukang parkir tidak
resmi, pembantu di warung lesehan dan kerajinan kaki lima serta perkeja
serabutan. Profesi lainnya yang dimiliki anak jalanan di Yogyakarta adalah
street guide atau Thetek, yaitu pemberi jasa pengantaran bagi wisatawan
(Surjono, 2000).
Kaminsky (dalam Harmaini, 2008) menyebutkan bahwa kondisi kehidupan
di jalan dan bekerja di sektor informal bagi anak jalanan memiliki risiko yang
tinggi. Beberapa masalah dan risiko yang biasa menimpa anak jalanan tersebut
adalah gangguan lalu lintas dapat berupa kecelakaan atau gangguan kesehatan,
gangguan preman dan pelacur, tindak kenakalan bahkan kriminalitas. Anak
jalanan kerap menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama anak
jalanan yang lebih tua, preman, masyarkat serta aparat (Surjono, 2000). Tindak
kekerasan yang dialami anak jalanan meliputi kekerasan secara mental, fisik
mental yang paling sering dialami anak. Bentuknya seperti makian, ancaman
dan pemerasan. Kekerasan fisik yang dialami anak jalanan seperti dipukul,
ditendang, dikeroyok hingga ditusuk dengan penda tajam.
Risiko lainnya yang dialami anak-anak jalanan adalah pelecehan seksual
terutama pada anak jalanan perempuan (Shalahuddin, 2010). Risiko ini
merupakan salah satu bentuk kekerasan sesual yang dialami anak jalanan.
Anak jalanan perempuan kerap menjadi korban pelecahan bahkan perkosaan.
Anak jalanan sering dipaksa untuk melayani hawa nafsu orang-orang jalanan
yang lebih tua bahkan ada pula yang menjadi korban pelecehan aparat
keamanan. Perilaku seks bebas pun tidak dapat terhindarkan pada anak jalanan.
Irwanto (1998) pernah melakukan penelitian tentang perilaku seksual anak
jalanan. Hasil penelitiannya menemukan banyak anak jalanan yang telah
melakukan aktivitas seksual sejak usia yang masih sangat dini dengan
berganti-ganti pasangan. Akibatnya penularan HIV/AIDS tidak dapat terhindarkan.
4. Pendampingan anak jalanan
Mengingat tingginya risiko yang dihadapi anak jalanan di lingkungan
kehidupannya, maka diperlukan suatu usaha untuk melindungi anak jalanan
dari risiko tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah
pendampingan. Pendampingan anak jalanan merupakan upaya yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Pendampingan anak jalanan
bukan hanya sekedar usaha menghapus keberadaan anak-anak dari jalanan
Tujuan utama dari sebuah pendampingan yang diberikan kepada anak
jalanan pada intinya adalah agar anak-anak jalanan tidak lagi kembali ke
jalanan dan mengkondisikan mereka agar tetap memiliki nilai-nilai
kemanusiaan tanpa menimbulkan suatu pola keterikatan kepada para
pendamping (Petter Coping dalam Surjono, 2000). Untuk itu, kesejahteraan
anak jalanan tentunya menjadi fokus yang utama dalam pendampingan anak
jalanan. Para pendamping berupaya untuk memfasilitasi anak-anak jalanan
dengan sarana-sarana berupa modal dan peltihan keterampilan usaha sehingga
dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Harmaini, 2008; Astutik,
2001).
Pendampingan anak jalanan dapat dilakukan dengan membentuk pos-pos
atau basis-basis yang dijadikan sebagai pusat pelayanan. Secara umum,
terdapat lima basis pendampingan anak jalanan, yaitu Basis Jalanan, Basis
Rumah Singgah, Basis Panti, Basis Masyarakat dan Basis Keluarga (Astutik,
2001).
Pendampingan anak jalanan pada Basis Jalanan merupakan pendampingan
yang dipusatkan di jalanan yang bertujuan sebagai tahap awal penjangkauan
anak jalanan dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka. Pendampingan
di Rumah Singgah merupakan pendampingan anak jalanan yang dipusatkan
pada sebuah panti dan bersifat sementara.
Pendampingan berbasis panti merupakan kelanjutan dari pendampingan di
Rumah Singgah dan lebih ditujukan kepada anak-anak jalanan yang tidak
pendampingan yang mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dan lembaga
sosial terutama aparat keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan anak
jalanan. Selanjutnya, pendampingan berbasis keluarga merupakan
pendampingan yang menekankan pada pemberdayaan dan peningkatan
keluarga, khususnya orang tua melalui usaha ekonomi produktif serta
peningkatan pemahaman fungsi keluarga dan peran orang tua terhadap anak.
Penelitian mengenai pengalaman pendamping anak jalanan ini berfokus
pada pendampingan yang dilakukan di rumah singgah. Pendampingan di rumah
singgah bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang berkeliaran di jalanan
serta memberi keterampilan yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian
(Harmaini, 2008). Di rumah singgah, kebutuhan anak jalanan akan makanan,
kesehatan dan pendidikan berusaha terpenuhi sehingga kelak anak-anak jalanan
ini dapat menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka selanjutnya
(Astutik, 2001). Nilai-nilai dan norma dalam berelasi dengan sesama dan orang
tua turut ditanamkan oleh para pendamping kepada anak-anak jalanan melalui
pendampingan di rumah singgah (Saripudin dan Ahmad, 2006).
B. Pendamping Anak Jalanan
Pendamping anak jalanan merupakan orang-orang yang mendedikasikan
hidupnya untuk membantu, mendampingi dan menyelamatkan kehidupan
anak-anak jalanan (Moeliono dan Dananto, 2004). Pada dasarnya, pendamping anak-anak
jalanan dibedakan menjadi dua macam yaitu pendamping yang merupakan
Pendamping yang merupakan pekerja sosial profesional adalah seseorang yang
bekerja baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki
kompetensi dan profesi pekerjaan sosial (Keputusan Mensos RI, 2010).
Sedangkan pendamping yang merupakan relawan sosial anak adalah seseorang
atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial
maupun bukan, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang
kesejahteraan sosial anak atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan
(Keputusan Mensos RI, 2010).
Pendamping pada dasarnya memiliki peran besar dalam menentukan
keberhasilan program penanganan anak jalanan. Peran pendamping dalam
pendampingan anak jalanan umumnya mencakup empat peran utama, yaitu
sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis
bagi anak jalanan yang didampinginya (Tomy, 2010).
Peran pendamping sebagai fasilitator merupakan peran yang berkaitan
dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi anak jalanan.
Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model dan
memberi dukungan bagi anak jalanan. Para pendamping juga bertugas untuk
melakukan mediasi, negosiasi, pengorganisasian serta pemanfaatan sumber
bagi kepentingan anak jalanan.
Sebagai pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi
masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bagi
menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi serta menyelenggarakan
pelatihan bagi anak jalanan.
Peran pendamping sebagai perwakilan masyarakat dilakukan berhubungan
dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas
nama dan demi kepentingan anak jalanan yang didampinginya. pendamping
dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan
media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan jaringan kerja. Mengacu
pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, para pendamping memiliki
peran teknis untuk tidak hanya mampu menjadi “manager perubahan” yang
mengorganisasikan kelompok. Para pendamping dituntut pula untuk dapat
melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar,
seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin
relasi, bernegosiasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
Pada penelitian kali ini, pendamping anak jalanan yang dilibatkan adalah
pendamping yang merupakan relawan sosial. Untuk itu, kerangka teoritis
tentang pendamping anak jalanan diawali dengan definisi pekerja sukarelawan
dan faktor-faktornya.
1. Sukarelawan a. Definisi
Wilson dan Musick (1997) mendefinisikan sukarelawan sebagai
seseorang yang bekerja secara sukarela dalam sebuah komunitas dengan
cara memberikan waktu dan tenaga demi kebaikan komunitas dan
sebagai sukarelawan formal (Formal volunteer). Sukarelawan formal ini
seperti pekerja di bidang yang lainnya, berada di bawah suatu wadah
organisasi dan untuk bergabung dalan organisasi tersebut perlu melewati
tahap kualifikasi atau seleksi. Para sukarelawan akan mendapatkan imbalan
berupa uang atas tugas yang mereka kerjakan walaupun ada pula relawan
yang sama sekali tidak dibayar atas pekerjaannya.
Bekerja secara sukarela berbeda dengan aktivitas menolong pada
umunya. Perbedaannya terletak pada konteks kedua aktivitas tersebut. Pada
aktivitas bekerja secara sukarela konteksnya adalah organisasi sehingga
biasanya dilakukan oleh beberapa orang secara bersama. Biasanya pekerjaan
ini dilakukan bukan karena adanya relasi yang dekat sebelumnya antara
relawan dan orang yang ditolong. Sedangkan menolong secara umum
merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk tindakan
menolong sehari-hari seperti menolong orang yang mengalami kecelakaan,
menyeberangkan orang yang sudah tua. Pemberian pertolongan biasanya
didasarkan oleh adanya perasaan wajib untuk menolong karena adanya
hubungan yang erat sebelumnya antara orang yang menolong dan ditolong
(D.H. Smith dan Mcaulay, 1980).
Menurut Sweifach (2008) sukarelawan diartikan sebagai seseorang
yang memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, kemampuan dan waktu
kepada orang lain, kelompok, komunitas atau organisasi secara suka rela
tanpa mengharapkan imbalan. Hall (1997) menambahkan menolong secara
Penner (2002) menyebutkan bahwa menjadi sukarelawan merupakan
sebagai salah satu bentuk perilaku menolong yang dilakukan dalam konteks
organisasi, yang telah direncanakan sebelumnya dan berlangsung dalam
periode waktu tertentu. Penner (2004) menyebutkan empat karakteristik
yang membedakan antara menolong sebagai sukarelawan dan perilaku
menolong lainnya, yaitu:
a. Merupakan tindakan telah direncanakan sebelumnya.
b. Merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam jangka waktu
yang panjang.
c. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan bukan karena adanya
kewajiban.
d. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam konteks organisasi.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sukarelawan
merupakan orang-orang yang bekerja secara sukarela untuk menolong orang
lain tanpa mengharapkan imbalan dan dilakukan dalam konteks organisasi,
dimana kesejahteraan orang lain merupakan tujuan dari upaya yang
dilakukan.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin menjadi sukarelawan
Penner (2004) mengajukan model Konseptual untuk menggambarkan
faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga berkeinginan untuk
(1) Karakteristik demografik :Pendidikan
Berbagai literatur secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara karakteristik demografik tertentu dengan aktivitas bekerja
secara sukarela. Penelitian di Amerika kebanyakan menunjukkan adanya
kesamaan karakteristik demografis para sukarelawan yaitu karakteristik
pendidikan. Omoto dan Snyder (1995) menemukan bahwa 50% relawan
AIDS di Amerika memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan memiliki
pekerjaan yang tetap. John Wilson (2000 dalam Penner 2004) menyebutkan
bahwa faktor pendidikan turut mempengaruhi kepekaan seseorang terhadap
masalah sekitar, meningkatkan rasa empati dan membangun kepercayaan
diri. Ditambah lagi, mereka tidak mengharapkan imbalan atas apa yang
mereka kerjakan sebagai sukarelawan.
(2) Personal atribut : empati
Personal atribut dalam bentuk keyakinan, sikap, kebutuhan atua
dorongan, motif-motif dan karakteristik kepribadian merupakan
faktor-faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menjadi
sukarelawan.Salah satu bentuk personal atribut adalah empati. Atkins et al.
(1999) menemukan adanya hubungan antara peran empati dan keinginan
untuk bekerja secara sukarela.
(3) Tekanan sosial
Tekanan sosial yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi
seseorang untuk menjadi sukarelawan adalah faktor sosial yang berupa
sosial secara langsung contohnya adalah adanya permintaan langusng dan
faktor sosial tidak langsung misalnya seperti masalah sosial, bencana alam
dan lain sebagainya.
(4) Volunteer activator
Volunteer activatoradalah cakupan luas berbagai stimulus yang menjadi
berbagai alasan yang kemudian mengaktifkan hasrat atau dorongan untuk
menjadi sukarelawan. Volunteer activator dapat berupa pengalaman hidup
seseorang secara personal yang kemudian menimbulkan pemikiran atau
perasaan tertentu.
c. Sukarelawan dan perilaku prososial
Selain keempat hal diatas, keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan
terkait pula dengan perilaku prososial seseorang. Bekerja secara sukarela
merupakan salah satu bentuk perilaku prososial dalam konteks organisasi
yang direncanakan dan berlanjut dalam durasi waktu tertentu (Penner,
2004). Perilaku prososial sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan yang
bertujuan untuk membantu orang lain terlepas dari motif menolong.
Pengalaman para pendamping anak jalanan juga menunjukkan bahwa alasan
mereka untuk berkomitmen menjadi pendamping anak jalanan tidak hanya
terbatas karena adanya keinginan untuk menolong. Terdapat motif lain yang
turut menyertai para pendamping untuk mendampingi anak jalanan.
Penelitian tentang motif untuk bekerja sukarela pernah dilakukan oleh
Devi Damayanti pada mahasiswa yang menjadi sukarelawan di sebuah LSM
mendorong seseorang untuk terlibat sebagai sukarelawan adalah motif
pengembangan diri, altruistik, aktualisasi diri, keinginan untuk memperoleh
pengalaman dan mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki (Damayanti,
2001)
C. ModelVolunteer Process
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model volunteer process untuk
menggambarkan pengalaman para relawan pendamping dalam mendampingi
anak jalanan. Menurut model ini pengalaman menjadi seorang sukarelawan
dapat dijelaskan dalam tiga tahap, yaitu tahap antecedents. experiences dan
consequences(Omoto dan Snyder, 1995).
1. TahapAntecedents
Tahap Antecedent (permulaan) merupakan tahap yang menggambarkan
tentang proses awal keterlibatan seseorang sebagi sukarelawan. Menurut teori
ini, beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan seorang sukarelawan.
Pertama, personal tribut yang mencakup sifat dan watak penolong yang
dimiliki seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada
perbedaan sifat dan watak antara sukarelawan dan yang bukan sukarelawan.
Atkins et al. (1999) menemukan sukarelawan memiliki empati yang tinggi,
kepedulian kepada orang lain serta memiliki kebutuhan untuk menolong orang
lain yang cukup tinggi. Hal inilah yang pertama-tama muncul dan mendorng
Kedua, keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan disebabkan adanya
kebutuhan sosial dan personal serta motivasi untuk menjadi sukarelawan.
Penelitian tentang motif-motif para sukarelawan yang pernah dilakukan oleh
Gidron (1978) terhadap 317 suka relawan pada 4 institusi kesehatan dan
mental. Hasilnya menggambarkan bahwa keinginan untuk bekerja secara
sukarela didorong oleh adanyarewardyang dapat diperoleh dengan melakukan
pekerjaan tersebut. Reward tersebut adalah kesempatan untuk menjalin relasi
dengan orang lain (sosial), kesempatan untuk memperoleh pemenuhan diri
(personal) serta kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi
(ekonomi). Penelitian yang dilakukan oleh Omoto dan Snyder (2002)
menemukan bahwa para suka relawan mengajukan dirinya sebagian besar
didorong oleh orientasi pada orang lain (other-oriented) atau motif-motif
prososial. Data-data lainnya juga menunjukkan bahwa aktivitas suka relawan
dapat pula didorong oleh adanya rasa yang tidak mementingkan diri sendiri
seperti menguntungkan karir seseorang atau mengembangkan relasi sosial
(Clary & Snyder 1999).
Faktor terakhir adalah dukungan sosial dari lingkungan yang dimiliki
seseorang. Omoto dan Snyder (1995) menemukan bahwa seseorang yang
menjadi sukarelawan sebagian besar memiliki lingkungan yang sama dan
mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Kebanyakan sukarelawan berasal
dari keluarga yang juga sukarelawan.
Pada penelitian ini, tahap antecedents yang dilalui seorang relawan
berkaitan dengan motif-motif yang mendorong pendamping dalam
mendampingi anak jalanan. Terkait dengan motif-motif menjadi pendamping
anak jalanan, Clary dan Snyder (1998) menggunakan pendekatan fungsional
untuk melihat motif-motif yang mendorong seseorang menjadi pekerja
sukarelawan. Pendekatan fungsional merupakan perspektif motivasional yang
menekankan pada proses personal sosial yang memungkinkan munculnya
keinginan hingga terlibat sebagai seorang sukarelawan. Menurut pendekatan
fungsional terdapat enam fungsi yang menjadi motif seseorang untuk mnejadi
sukarelawan yaitu:
a. Value(Nilai)
Seseorang ingin menjadi sukarelawan didorong oleh nilai-nilai penting
yang dianut seperti nilai altruisme dan nilai kemanusiaan. Nilai altruisme
mendorong seseorang menolong sesama manusia. Pada penelitian terdahulu
ditemukan bahwa para relawan memiliki kepedulian yang lebih kepada orang
lain dibandingkan dengan non relawan.
b. Understanding(Pemahaman)
Keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan didorong oleh keinginan untuk
belajar dan mengetahui hal yang baru serta untuk mengasah keterampilan dan
kemampuan yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Gidron (1978)
menunjukkan bahwa para relawan di Institusi kesehatan dan mental memiliki
motifunderstandingdalam menjalankan tugasnya.
Motif seseorang untuk bekerja secara sukarela didorong oleh keinginan
untuk menjalin relasi dengan orang lain. Menjadi sukarelawan dapat
memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat menjalin relasi dengan
orang lain. Kebersamaan dengan orang lain menjadi pendorong yang kuat bagi
seseorang untuk bekerja sebagai seorang sukarelawan.
d. Career(Karir)
Seseorang terlibat dalam suatu aktivitas volunteerism didorong oleh
keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman yang
diperoleh selama menjadi relawan.
e. Protective(Perlindungan)
Motif ini merupakan motif yang berkaitan dengan fungsi ego, dimana
seseorang terlibat sebagai sukarelawan dikarekan adanya dorongan untuk
megurangi perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri seperti kecemasan,
perasaan bersalah serta masalah-masalah pribadi.
f. Enhancement(Peningkatan)
Motif seseorang untuk terlibat sbegai sukarelawan didorong oleh
keinginan untuk berkembang secara psikologis misalnya seperti meningkatnya
pemahaman tentang diri sendiri dan penerimaan diri.
2. TahapExperiences
Tahap experiences merupakan tahap yang menjelaskan tentang berbagai
pengalaman yang dirasakan setelah seseorang menjadi sukarelawan khususnya
aktivitasnya sebagai sukarelawan. Omoto dan Snyder menyebutkan ada banyak
tolak ukur yang dapat digunakan untuk menggambarkan
pengalaman-pengalaman sebagai sukarelawan.
Pada penelitiannya terdahulu, Omoto dan Snyder (1995) melakukan
penelitian yang berfokus pada kepuasan yang diperoleh para sukarelawan
selama menjalankan tugas dan integrasinya terhadap organisasi yang
menaunginya. Hasilnya menunjukkan bahwa para sukarelawan memperoleh
kepuasan atas apa yang mereka lakukan. Kepuasan para sukarelawan dapat
terpenuhi dikarenakan motif-motif yang pada awalnya mendorong menjadi
sukarelawan terpenuhi dengan katerlibatan sebagai sukarelawan. Integrasi
dengan komunitas juga turut tercapai dengan adanya kesamaan visi dan misi
antara para pendamping dan komunitas yang menaunginya. Hal ini kemudian
mempengaruhi keputusan sukarelawan untuk melajutkan keterlibatannya.
Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengalaman-pengalaman
relawan pendamping selama mendampingi anak jalanan. Pengalaman tersebut
meliputi suka duka yang dirasakan pendamping, termasuk pengalaman
menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pendampingan serta hal-hal
yang membuat para pendamping bertahan dalam mendampingi anak jalanan.
Bekerja sebagai seorang pendamping anak jalanan di rumah singgah
bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Pada proses pendampingan, para
pendamping dihadapkan pada beragamnya karakteristik anak jalanan, mulai
dari pendapatan, umur, profesi, pola hubungan dengan keluarga dan masalah
pendamping anak jalanan dimulai dengan menjangkau anak jalanan untuk
dibina di rumah singgah, serta membangun kepercayaan dengan anak-anak
maupun orang tua (Astutik, 2001).
Kompleksnya tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pendamping
anak jalanan mengantarkan para pendamping ke berbagai permasalahan yang
kompleks pula. Permasalahan muncul dimulai dengan banyaknya tanggapan
yang negatif terhadap adanya kegiatan pendampingan anak jalanan. Harmaini
(2008) menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang negatif
dan berperilaku diskriminatif terhadap anak-anak jalanan. Odhi Shalahudin
(2001) juga menyebutkan bahwa upaya pendampingan yang bertujuan untuk
mensejahterakan anak jalanan ini sering dituduh sebagai organisasi yang
menggerakkan anak jalanan secara liar sehingga upaya semacam ini sering
tidak mendapatkan perhatian. Pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh
para rewalan pendamping juga sering terbentur permasalahan dana. Banyak
program intervensi yang disusun tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan
dana (Moeliono dan Dananto, 2004). Dari sisi pendamping sebagai pribadi,
kejenuhan dan hilangnya kesabaran juga pernah terjadi sehingga turut
menurunkan motivasi kerja sebagai pendamping anak jalanan (Moeliono dan
Dananto, 2004).
Secara naluriah manusia akan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah
yang dihadapi dalam hidupnya termasuk juga para pendamping anak jalanan.
Usaha atau cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini disebut dengan
kognitif dan behavioral yang dilakukan seseorang untuk memodifikasi,
menahan atau menghilangkan stressor yang mengancam (Folkman dan
Lazarus, 1984). Kemampuan coping yang dimiliki seseorang memampukan
seseorang berpikir dan berperilaku secara khusus untuk menghadapi tantangan
atau tekanan yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan,
khususnya yang berkaitan dengan kesejateraannya (Folkman dan Lazarus,
1984).
Selanjutnya Folkaman dan Lazarus (1986), secara garis besar strategi
coping dibedakan atas dua fungsi utama yaitu:
a. Problem focused coping
Strategi coping ini merupakan strategi coping yang berberorientasi
pada masalah yang menjadi stressor. Usaha-usaha yang dilakukan lebih
diarahkan pada penyelesaian masalah. Ciri-ciri strategi coping yang
berorientasi pada masalah adalah adanya usaha yang dilakukan secara aktif
untuk mengatasi masalah, perencanaan, mengesampingkan kegiatan lain,
penundaan perilaku mengatasi masalah serta usaha mencari dukungan
sosial berupa bantuan (Carver, 1989).
b. Emotion focused coping
Strategi coping ini merupakan strategi coping yang lebih beorientasi
pada emosi. Usaha yang dilakukan lebih diarahkan pada usaha untuk
mengurangi atau menghilangkan stress yang dirasakan. Pada strategi ini
seseorang berusaha mengahadapi masalah secara tidak langsung.
dapat berupa pencarian dukungan sosial untuk alasan emosional,
pemaknaan secara positif dan pendewasaan diri, penerimaan, kembali
kepada agama atau dapat pula berupa pengingkaran (Carver, 1989)
Kedua strategi coping ini, biasanya juga dilakukan oleh pendamping ketika
menghadapi berbagai masalah dalam mendampingi anak jalanan. Para
pendamping merasa pertemuan informal antar pendamping, kerjasama antar
LSM serta berekreasi merupakan trategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi
berbagai masalah dalam pendampingan Moeliono dan Dananto, 2003). Para
pendamping juga perlu bersikap lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan
keadaan ketika permasalahan dana menjadi penghambat dalam melaksanakan
program-program pendampingan sehingga menyusun ulang program dengan
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan anak jalanan yang paling mendesak
dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dana yang muncul dalam
pendampingan (Harmaini,2000).
3. Tahap Consequences
Tahap consequences merupakan tahap yang membahas tentang hal-hal apa
saja yang diperoleh seseorang setelah menjadi sukarelawan. Konsekuensi ini
meliputi dampak dari keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan baik bagi diri
sendiri maupun orang lain. Konsekuensi ini dapat berupa pengetahuan,
perubahan sikap diri sendiri maupun orang lain, relasi dan lain sebagainya.
sukarelawan. Para relawan mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka
mengalami banyak perubahan sikap dan perilaku terhadap orang-orang yang
mereka layani dan dalam konteks ini adalah anak-anak jalanan. Para relawan
pun dapat semakin mengenal dan mengetahui orang-orang yang mereka layani
(Omoto dan Snyder, 1995).
Menurut Odi Shalahudin (2001) pendampingan terhadap anak jalanan
bukanlah hal yang mudah tetapi mereka tetap mebutuhkan uluran tangan untuk
mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih baik. Sejak tahun 1993 hingga
tahun 2000 semakin banyak orang-orang yang memberikan perhatian kepada
anak-anak jalanan. Seperti yang terjadi di Semarang, tujuh LSM luar negeri
turut memberikan perhatian terhadap upaya pengentasan anak jalanan.
Skema 1. Skema Pengalaman Pendamping Anak Jalanan Menurut
Volunteer Process Model
Volunteer Process Model
TahapExperiences
TahapAntecedents
TahapCosequences
Personal Atribut Motivasi Dukungan Sosial
Personal Atribut Personal Atribut Personal Atribut
D. Pendamping dan Tahap Perkembangan Generativity vs Stagnasi
Salah satu faktor pendorong keberadaan anak-anak di jalanan adalahnya
hubungan antara orangtua dan anak yang tidak harmonis. Hasil penelitian yang
dilakukan Surjono (2000) menunjukkan bahwa sekitar 29,5 persen anak jalanan
hanya bertemu dan berkomunikasi dengan orangtuanya sekitar seminggu
hingga sebulan sekali. Bahkan, sekitar 13 persen anak jalanan di Yogyakarta
sama sekali tidak lagi bertemu dan berkomunikasi dengan orang tuanya.
Melihat kondisi yang demikian tujuan keberadaan pendamping di rumah
singgah salah satunya adalah menggantikan keberadaan orangtua untuk
membimbing dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak jalanan yang belum
terpenuhi.
Para pendamping yang berusia antara 30 hingga 60 tahun dihadapkan pada
tugas perkembangan generativitas versus stagnasi (Cremers, 1989; Boeree,
2006). Pada tahap ini, pendamping dihadapkan pada tugas untuk mengabdikan
diri sehingga dapat menyeimbangkan generativitas dan stagnasi. Generativitas
merupakan perluasan cinta kepada masa depan yang tidak mengharapkan
balasan. Perluasan cinta kepada masa depan menyebabkan berkurangnya rasa
mementingkan diri sendiri dan menjadikan para pendamping semakin
produktif. Produktif yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada
menghasilkan keturunan atau melakukan suatu tugas melainkan lebih kepada
membina, membimbing dan melindungi anak-anaknya atau generasi
selanjutnya (Cremers, 1989). McAdams (1992) menambahkan bahwa
pada relasi yang ada di luar keluarga seperti relasi pertemanan, komunitas atau
organisasi kesukarelawanan seperti pendamping sukarelawan anak jalanan ini.
Orang-orang dewasa termasuk pendamping anak jalanan yang berada
ditahap perkembangan ini ada pula yang tidak bisa produktif untuk melakukan
generativitas atau dengan kata lain mengalami stagnasi. Seseorang yang
mengalami stagnasi merasa dirinya tidak dapat berperan dan memberikan
sumbangan kepada orang-orang di sekitarnya termasuk generasi muda (Boeree,
2006). Bentuk lain dari stagnasi yang dialami individu adalah tidak dapat
memaknai hidup yang dijalani sehingga hidup yang dijalani terasa
membosankan. Hal inilah yang membuat seseorang lari kepada kesenangan
semu seperti kesenangan akan materi (Cremers, 1989). Hal ini dapat pula
terjadi pada para pendamping anak jalanan sehingga mereka hanya memikirkan
kesenangan sendiri dan tidak memperdulikan anak jalanan.
Berdasarkan paparan teori di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengalaman pendamping pada tahapantecedents?
2. Bagaimanakah pengalaman pendamping pada tahapexperiences?
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
bertujuan untuk menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi,
keadaan sosial atau hubungan (Neuman, 2000). Pada penelitian ini, peneliti
akan mendeskripsikan motif-motif para pendamping dalam mendampingi
anak jalanan, masalah-masalah yang dihadapi serta cara-cara yang dilakukan
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendampingan anak
jalanan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan proses
penyelidikan untuk memahami suatu masalah-masalah sosial atau manusia
dengan menggunakan tradisi metodologi pemeriksaan yang berbeda.
Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang
kompleks, menyeluruh, serta informasi yang detail dalam setting penelitian
yang natural (Creswell, 2003). Mack et.al. (2005) mengemukakan bahwa
pendekatan kualitatif efektif digunakan dalam menggali data yang berupa
informasi spesifik tentang nilai-nilai, opini, perilaku, dan konteks sosial
budaya dari sebuah populasi.
B. Subjek Penelitian
1. Teknik pemilihan subjek
Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposif
sampling yaitu subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan
dengan pertanyaan penelitian. Kriteria subjek penelitian yang dilibatkan
adalah pendamping anak jalanan yang bekerja secara sukarela, bukan
merupakan pekerja sosial profesional, dan telah melakukan
pendampingan lebih dari lima tahun. Jumlah subjek yang dilibatkan
disesuaikan dengan data yang diperoleh. Biasanya hingga data yang
diperoleh jenuh yaitu hingga tidak ada lagi data-data baru yang muncul.
Selain itu jumlah subjek juga tergantung pada ketersediaan waktu dan
sumber data yang sesuai dengan kriteria (Mack, 2005).
Pada penelitian ini, jumlah subjek yang dilibatkan sebanyak lima
orang. Teknik pengambilan subjek dilakukan dengan cara:
a. Mencari subjek sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan di
sebuah rumah singgah. Peneliti turut berpartisipasi sebagai relawan
pada sebuah rumah singgah.
b. Mengingat data mengenai rumah singgah yang peneliti ketahui
jumlahnya terbatas, peneliti mencari informasi mengenai rumah
singgah di Dinas Sosial Yogyakarta.
c. Berdasarkan informasi yang dimiliki, peneliti mencari subjek di
beberapa rumah singgah sesuai dengan karakteristik yang telah
menanyakan kesediaan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian
ini.
2. Karakteristik subjek
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang
bekerja sebagai pendamping anak jalanan di rumah singgah, dan telah
melakukan pendampingan kepada anak jalanan di rumah singgah
minimal lima tahun. Pendamping anak jalanan ini terdiri dari empat
laki-laki dan satu perempuan. Tiga di antaranya merupakan pimpinan rumah
singgah.
Tabel 1
Data Demografik Subjek Penelitian
No. Nama (Nama samaran) Jenis kelamin Usia Status pernikahan Jabatan di rumah singgah Lama kerja di rumah singgah Pendidik an terakhir
1. Eko
Laki-laki
38 th Menikah Pendamping 11 tahun S1
2. Fahri
Laki-laki
31 th Menikah Pimpinan
rumah singgah
6 tahun S1
3. Bunda Peremp
uan
32 th Belum
Menikah
Pendamping 6 tahun S2
4. Bowo
Laki-laki 33 thn Menikah Pimpinan rumah singgah
9 tahun D3
5. Yanto
Laki-laki 53 thn Menikah Pimpinan rumah singgah
C. Pengambilan Data
1. Metode pengambilan data
Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara. Banister et.al. (dalam Poerwandari, 2005)
mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara merupakan suatu
teknik pengambilan data yang didesain untuk memperoleh gambaran
yang jelas dari perspektif partisipan (Mack, 2005). Model wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur
dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.
Pedoman wawancara digunakan untuk menjaga agar wawancara terfokus
pada permasalahan penelitian dan memastikan tidak ada hal-hal yang
belum terungkap dalam wawancara.
Wawancara dalam penelitian ini mengungkap data-data mengenai
identitas subjek, latar belakang keterlibatan dalam rumah singgah,
motif-motif yang mendorong untuk mendampingi anak jalanan, masalah yang
dihadapi dan cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan
masalah-masalah dalam pendampingan serta alasan bertahan sebagai pendamping
anak jalanan.
Tabel 2
Panduan Wawancara
No. Aspek Deskripsi Pertanyaan
1. Identitas subjek. Nama, usia, status pernikahan,pendidikan, lama kerja dan jabatan di rumah singgah.
1. Siapa nama Anda? 2. Berapa usia Anda
sekarang?
belum?
4. Apa pendidikan terakhir Anda?
5. Berapa lama Anda bekerja di rumah singgah?
6. Apa jabatan Anda di rumah singgah? 2. Tahap Antecedents Proses awal keterlibatan dalam pendampingan, motif-motif untuk menjadi
pendamping anak
jalanan
1. Bagaimana cerita awalnya sehingga Anda bisa terlibat dalam pendampingan di rumah singgah?
2. Hal apa yang
mendorong Anda
untuk mendampingi anak-anak jalanan? 3. Tahap
Experiences
Suka duka dalam
pendampingan,
masalah yang
dihadapi, penyelesaian
masalah yang
dilakukan.
1. Apa suka duka yang Anda alami selama mendampingi anak jalanan?
2. Adakah masalah Anda
hadapi dalam
pendampingan?
3. Masalah apa yang Anda alami?
4. Apa yang Anda
lakukan untuk
mengatasi masalah yang Anda hadapi? 5. Apa yang membuat
Anda bertahan sebagai pendamping anak jalanan hingga saat ini?
4. Tahap
Consequences
1. Bagaimana dengan
hasil dari
2. Pelaksanaan pengambilan data
Pengambilan data dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai
berikut:
Tabel 3
Jadwal Pelaksanaan Wawancara
No. Subjek Tempat Waktu
1. Eko Rumah Singgah Girlan 27 Februari 2010 (Pukul 14.30 s.d. 16.00)
21 Mei (16.00 s.d. 17.00)
2. Fahri Rumah Singgah
Diponegoro
23 Maret 2010 (15.00 s.d. 16.00)
27 Mei 2010 (10.00 s.d. 11.30)
3. Bunda Rumah Singgah Ahmad
Dahlan
25 Maret 2010 (16.00-17.30)
19 Mei 2010 (16.00-17.20)
4. Bowo Rumah Singgah Ahmad
Dahlan
25 Maret 2010 (11.00 s.d. 12.00)
19 Mei 2010 (13.00 s.d. 14.30)
5. Yanto Rumah Singgah Girlan 20 April 2010 (13.00 s.d. 14.30)
31 Mei 2010 (16.00-17.30)
D. Analisis Data
Tahap-tahap analisis data dimulai dengan melakukan organisasi data,
pengkodean dan analisis. Organisasi data dilakukan agar peneliti dapat
memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan analisis yang
dilakukan serta menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalam
Organisasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyimpan
rekaman wawancara, verbatim wawancara, data hasil pengkodean,
data-data yang sudah dikategorisasi dalam tema-tema.
Pengkodean data dilakukan sebelum analisis data. Pengkodean data
dilakukan dengan tujuan data dapat menggambarkan topik yang diteliti
secara lengkap dan detil sehingga peneliti dapat menemukan makna dari data
yang telah dikumpulkan. Peneliti dapat melakukan pengkodean data dengan
cara yang berbeda-beda sesuia dengan apa yang dirasa paling efektif bagi data
yang diperoleh (Poerwandari, 2005). Pada penelitian ini, pengkodean data
dilakukan secara deduktif dan induktif. Pengkodean secara deduktif dilakukan
dengan menggolongkan data berdasarkan tema-tema umum yang tertera
dalam teori. Pengkodean induktif yaitu berdasarkan makna dari sebuah data.
Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Boyatzis (dalam
Poerwandari, 2005) menyebutkan bahwa analisis tematik adalah proses
mengkode informasi sehingga menghasilkan daftar tema, model tema atau
indikator yang kompleks, kualifikasi yang terkait dengan tema atau
penggabungannya. Tema yang dihasilkan memungkinkan diperolehnya
deskripsi mengenai fenomena bahkan interpretasinya.
Poerwandari (2005) menyebutkan secara umum banyak peneliti
menyarankan analisis tematik dapat dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Membaca transkrip sesegera mungkin setelah transkrip dibuat untuk
2. Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan pengkodean
untuk memperoleh ide umum tentang tema. Hal ini perlu dilakukan untuk
menghindari kesulitan dalam pengambilan keputusan.
3. Mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang muncul sewaktu-waktu
secara spontan.
4. Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur. Peneliti juga
perlu mencatat secara disiplin tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan
daninsightyang muncul.
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 1. Kredibilitas
Kredibilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengganti konsep
validitas yang dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas penelitian
kualitatif. Kredibilitas penelitian kualitatif ditentukan oleh berhasil
tidaknya sebuah penelitian mengeksplorasi masalah atau
mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial at