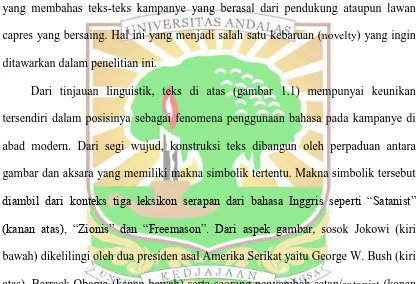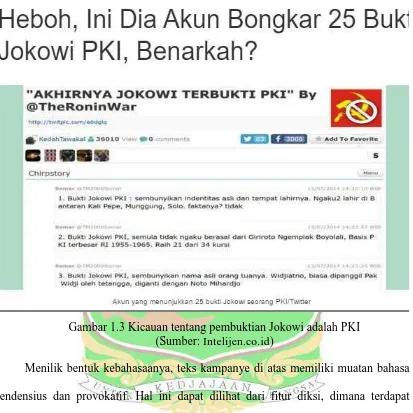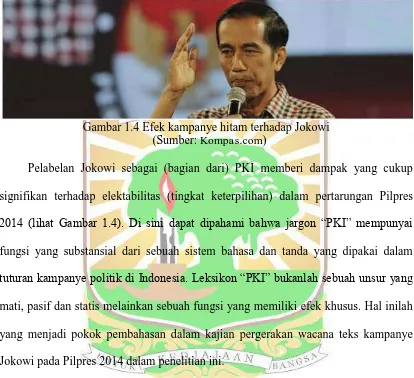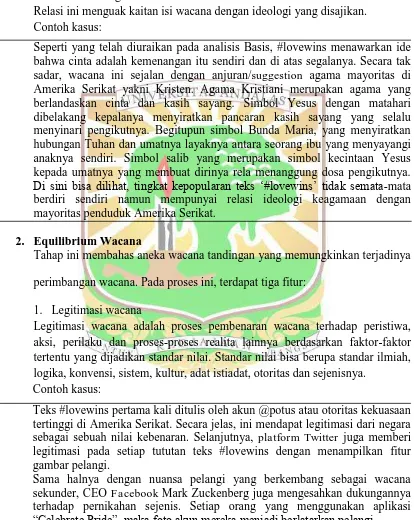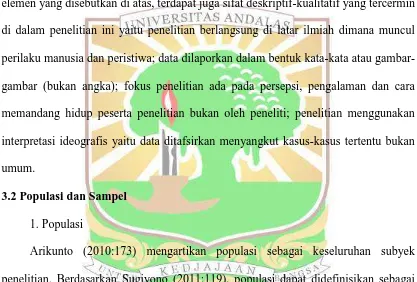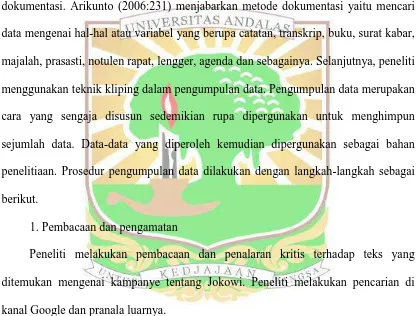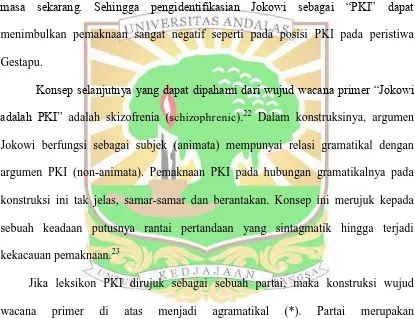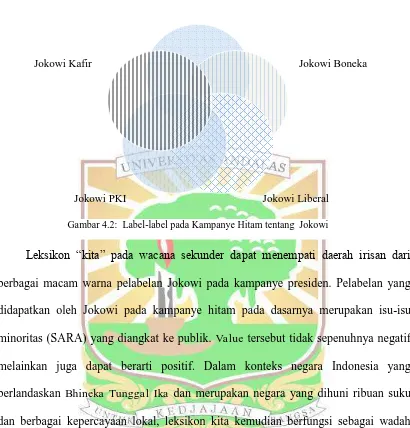ANALISIS PERBANDINGAN WACANA KAMPANYE HITAM DAN PUTIH TENTANG JOKOWI PADA PILPRES 2014 DAN
PERGERAKAN WACANANYA
TESIS
Tesis ini Ditulis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Humaniora pada Program Pascasarjana Universitas Andalas
Oleh:
MUHAMMAD ADEK
1420722018
PROGRAM STUDI LINGUISTIK PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
ANALISIS PERBANDINGAN WACANA KAMPANYE HITAM DAN PUTIH TENTANG JOKOWI PADA PILPRES 2014 DAN PERGERAKAN
WACANANYA Oleh: Muhammad Adek
Pembimbing I: Dr. Sawirman, M.Hum Pembimbing II: Dr. Fajri Usman, M.Hum
ABSTRAK
Penelitian ini membahas konfigurasi dan pergerakan wacana kampanye tentang Jokowi pada Pilpres 2014. Studi didasarkan atas teori perbandingan wacana (BREAK), dengan tujuan melakukan analisis mendalam terhadap dialektika teks dan konteks melalui pendekatan analisis wacana kritis. Permasalahan dalam studi ini dijawab dan dijelaskan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedua wacana mengusung pola konstruksi dan pergerakan yang identik. Perbedaan antara kedua wacana terjadi di tataran muatan ideologis-historis. Wacana primer mengandung muatan ideologi anti-komunis, memuat pesan nostalgia pemimpin militeristik dan fanatisme agamawi serta mengemukakan spirit manipulatif, diskriminatif dan intimidatif. Di sisi lain, wacana sekunder mengusung ideologi egaliter/demokratis, mengandung gagasan pluralisme, serta mengusulkan spirit kebersamaan dan penerimaan.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian
Fenomena penggunaan bahasa dalam situasi kampanye presiden merupakan
salah satu topik yang banyak didiskusikan oleh peneliti bahasa. Hal ini disebabkan
oleh adanya anggapan umum di masyarakat bahwa kemampuan berbahasa
berbanding lurus dengan kemampuan intelektual seseorang. Penelitian terbaru
dilakukan oleh Eskenazi dan Schumacher (2016) dalam rangka memberi pandangan
dan mengkritisi kemampuan berbahasa capres dan eks presiden Amerika Serikat.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelima bakal capres yang bersaing pada
pemilu 2016: Donald Trump, Hillary Clinton, Ted Cruz, Mark Rubio dan Bernie
Sanders, mempunyai rataan kemampuan kosakata dan tata bahasa yang setara dengan
siswa kelas menengah (middle-school student level). Kemampuan terendah dimiliki
oleh capres Trump yaitu berada di bawah level siswa kelas menengah (below sixth
grade).
Di Indonesia, beberapa peneliti juga giat mengkaji hubungan antara fenomena
penggunaan bahasa dalam kampanye presiden. Beberapa penelitian tersebut antara
lain; Andyani (2011) membahas wacana politik dari sudut pandang media massa
ternama pada Pilpres 2009. Selanjutnya adalah Kholila (2016) yang menelaah
fitur-fitur kebahasaan yang digunakan capres Jokowi dalam pidato kampanye Pilpres 2014.
Seterusnya, Afifah (2014) mengkaji penggunaan simbol-simbol dan unsur warna
Namun demikian, penelitian mengenai bahasa dan kampanye yang dihasilkan
oleh pendukung-pendukung salah satu capres di media massa dan sosial masih belum
banyak diperhatikan dan diteliti secara mendalam. Dalam tataran ini, para penyuara
dukungan kepada masing-masing capres ikut serta dan berperan aktif dalam
menyampaikan dukungannya di berbagai jenis media berbasis tulisan (massa dan
sosial). Perkembangan pesat dari teknologi terutama internet dan sarana
pendukungnya seperti gawai, notebook, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya
membuat hal tersebut demikian mudah untuk diwujudkan. Ada pun contoh kampanye
yang dipraktikkan di media sebagai berikut:
Gambar 1.1 Kampanye Tentang Capres Jokowi sebagai Zionis/Freemason (sumber: votreesprit.wordpress.com)
Cuplikan di atas adalah contoh teks kampanye pada Pilpres 2014 yang
ditemukan di media massa daring (online). Teks ini bertebaran secara luas pada
rentang waktu kampanye Pilpres 2014. Pada gambar di atas, terlihat capres Jokowi
Teks di atas merupakan kampanye yang biasanya disebarkan oleh pihak-pihak
yang kabur identitasnya (anonim). Teks jenis ini bisa muncul kapan saja, di mana saja
dan dibuat oleh siapa saja. Teks seperti ini mempunyai sifat kemunculan yang bebas,
dinamis dan sporadis. Faktor-faktor inilah yang kemudian membuat kemunculannya
menjadi fenomena kebahasaan tersendiri. Berbeda dengan penelitian-penelitian
bahasa kampanye yang telah disebutkan sebelumnya (lihat hal. 1), hampir tidak ada
yang membahas teks-teks kampanye yang berasal dari pendukung ataupun lawan
capres yang bersaing. Hal ini yang menjadi salah satu kebaruan (novelty) yang ingin
ditawarkan dalam penelitian ini.
Dari tinjauan linguistik, teks di atas (gambar 1.1) mempunyai keunikan
tersendiri dalam posisinya sebagai fenomena penggunaan bahasa pada kampanye di
abad modern. Dari segi wujud, konstruksi teks dibangun oleh perpaduan antara
gambar dan aksara yang memiliki makna simbolik tertentu. Makna simbolik tersebut
diambil dari konteks tiga leksikon serapan dari bahasa Inggris seperti “Satanist”
(kanan atas), “Zionis” dan “Freemason”. Dari aspek gambar, sosok Jokowi (kiri
bawah) dikelilingi oleh dua presiden asal Amerika Serikat yaitu George W. Bush (kiri
atas), Barrack Obama (kanan bawah) serta seorang penyembah setan/satanist (kanan
atas) yang menunjukkan isyarat tangan serupa (membentuk tanda seperti tanduk).
Kesamaan tersebut kemudian diretorikakan dalam ujaran Kebetulan atau “By Design?” Pada akhirnya, keseluruhan narasi dari teks ini disimpulkan dengan Jokowi
Zionis/Freemason (lihat judul di bawah gambar).
Di bagian bawah teks (gambar 1.1), sebuah klausa Jokowi Zionis/Freemason
beberapa pengertian yang dapat ditimbulkan oleh konstruksi tersebut. Berikut contoh
model analisisnya:
Jokowi Zionis/Freemason (a)
Jokowi (adalah) Zionis/Freemason (a1)
Jokowi (adalah) Zionis dan Freemason (a2)
Jokowi Zionis (a3)
Jokowi Freemason (a4)
Dalam konstruksi (a1) dan (a2), terdapat pelesapan pemarkah klausa relasional
yaitu ‘adalah’ (atau verba relasional dalam bahasa Inggris seperti to be). Di dalam
bahasa Indonesia, hal ini lazim digunakan dalam penggunaan sehari-hari terutama
penggunaan bahasa informal. Pada konstruksi (a1), leksikon Zionis dan Freemason
dibatasi oleh tanda garis miring (/) yang menandakan penggantian kata yang setara.
Tanda (/) dapat juga menunjukkan penambahan elemen yang dapat diwakili oleh
pemarkah dan (lihat a2). Data (a3) dan (a4), konstruksi ini dapat membuat dua klausa
baru dengan menempatkan Zionis maupun Freemason sebagaiatribut (ciri khas) dari
nomina Jokowi.
Beragam pemaknaan yang muncul pada analisis di atas dapat menimbulkan
kerancuan pemahaman keseluruhan dari teks tersebut. Namun demikian, jika
ditelusuri pemaknaan secara emik, kedua leksikon tersebut mempunyai benang merah
dari fitur semantis seperti yang tergambar dalam tabel berikut:
Leksikon Perspektif Etik Perspektif Emik
Zionis [+tempat,+suci,+yahudi] [+ras, +monopoli, +jahat]
Freemason [+ahli, +kayu, +pahat] [+golongan,+monopoli,+jahat]
Dari uraian di atas, leksikon Zionis dan Freemason memiliki keterkaitan
semantis dalam hal kelompok, yang bersifat monopoli dan berperilaku jahat. Indikasi
keberadaan Jokowi sebagai bagian dari kelompok yang jahat dan ingin melakukan
monopoli di Indonesia.
Selanjutnya, penggabungan wacana fotografi dan unsur lingual (pada gambar
1.1) adalah salah satu ciri utama perwajahan berita dan informasi di era digital.
Berlimpahnya penggunaan teknik ini ditandai dengan maraknya tren dan kebudayaan
di dunia digital seperti: infografik, meme, komik sepotong (comic-strip), lecturing
video, dan lain-lain. Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan dan keluwesan
informasinya. Namun di sisi lain, hal ini juga mengandung bahaya laten mengenai
ketidaklengkapan dan ketidakpastian informasi.
Dalam perspektif kajian wacana, bahasa kampanye di atas (lihat data a) dapat
dipahami sebagai sebuah semiotika sosial (social semotics). Setiap bagian yang
menyusun kerangka teks tersebut dikonfigurasikan dalam bentuk kode-kode yang
mengandung pengalaman-pengalaman sosial. Leksikon seperti ‘Satanist’, ‘Zionis’
dan ‘Freemason’ mempunyai efek empiris yang khusus juga kepada pembaca teks
tersebut. Hingga akhirnya, teks tersebut mempunyai makna strategis oleh masyarakat
tuturnya (speech community).
Pada momentum Pilpres 2014, kehadiran contoh kampanye di atas (data a)
merupakan salah satu fenomena kebahasaan dalam kegiatan politik praktis. Berbagai
macam bentuk pernyataan, pertanyaan, retorika, tuduhan hingga klaim-klaim muluk
tercipta dengan tujuan menjatuhkan citra lawan politik. Dari sisi wacana, pengutuban
dua calon yang bersaing (capres Jokowi dan Prabowo), membuat perang ide antara
pihak-pihak yang bertarung semakin jelas arah dan tujuannya. Saling serang dan
kampanye. Pengemasan ragam ide dan intensitas menjadi kunci dari kesuksesan
kampanye-kampanye tersebut.
Salah satu jenis kampanye yang banyak tercipta pada Pilpres 2014 adalah
kampanye hitam. Kampanye hitam dipandang sebagai corong utama lahirnya
berita-berita mengejutkan dan bersifat menjatuhkan citra lawan politik. Kampanye jenis ini
adalah satu bentuk medium pembentuk cetakan wacana negatif. Menurut pakar kajian
hukum dari Universitas Indonesia, Wirdyaningsih (2014), kampanye hitam bisa
dipahami sebagai “salah satu metode kampanye kotor untuk menjatuhkan lawan
dengan menggunakan isu negatif tidak berdasar” (dalam Permasalahan Black
Campaign).
Isu negatif dan tak berdasar adalah dua hal yang mudah ditemui di era
informasi sekarang. Dengan menjunjung semangat jurnalisme publik (citizen
journalism) dan keterbukaan informasi (open-access information), maka setiap orang
dapat bertindak sebagai wartawan dadakan, ilmuan politik, ahli hukum, sejarawan
ataupun pakar forensik. Setiap orang mempunyai hak seluas-luasnya menggunakan
gawai mereka untuk menghasilkan teks-teks dalam kepentingan mereka berpolitik
dan berwacana. Praktik-praktik berbahasa mereka muncul dalam beragam wujud
seperti; opini, kecurigaan, tinjauan kritis, surat terbuka dan lain-lain.
Dalam peta perpolitikan Indonesia, tahun 2014 dapat disebut sebagai ‘tahun
politik’ dan ‘tahun pesta demokrasi’ (Wibowo dalam Skenario). Pilpres Indonesia
2014 adalah salah satu acara puncak dari rentetan kegiatan berpolitik dan bernegara.
Ini ditandai dengan kehebohan yang masif dan popularitas pemberitaan politik yang
mengenai Piplres (peta persaingan calon, nama figur, suhu politik, hasil survei, dan
lainnya) dapat dijumpai di kolom jagad pemberitaan. Pemberitaan dan informasi
berbau politik pun akhirnya menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia.
Mengerucut lagi, gelora Pilpres 2014 menelurkan satu nama dan disebut
sebagai calon terkuat, yakni Jokowi (55 tahun). Nama Jokowi dengan segera
mendominasi saluran pemberitaan sebagai figur pemimpin nasional semenjak
prestasinya menjabat Walikota Surakarta (Solo) selama dua periode berturut-turut
(2005-2010) dan (2010-2012). Namun, batu loncatan karir politiknya adalah ketika
Jokowi mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta 2012 bersama Basuki Tjahja
Purnama.
Menilik dari aspek geografis dan demografis, DKI Jakarta merupakan miniatur
Indonesia. Menurut logika umum, memenangkan suara provinsi DKI Jakarta maka
akan berpeluang besar juga menjadi pemenang di seluruh Indonesia. Keberhasilan
Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta menjadi peristiwa monumental dalam kiprah
politik Jokowi sebagai figur pemimpin nasional. Oleh sebab-sebab di atas,
pemberitaan Jokowi sebagai fenomena dan anomali politik tidak terhalangi lagi.
Pilpres 2014 merupakan salah satu momentum paling signifikan dalam
pembentukan berbagai ragam wacana. Hal ini disebabkan presiden merupakan sosok
penting dalam sebuah negara. Maka dari itu, pemilu presiden menjadi ajang jual-beli
wacana para calon yang berpartisipasi. Wacana yang muncul tersebut tidak hanya
sebatas ruang lingkup pemilu saja. Bisa jadi, wacana dihadirkan dari sisi personal
Wacana yang ada mempunyai rantai dengan wacana lain sehingga membentuk
kompleksitas informasi dan opini.
Pilpres 2014 menjadi bukti bagaimana wacana demikian mudah dibentuk,
dipelintir, dibengkokkan dan kemudian disebarluaskan. Keberpihakan media di awal
karir politik Jokowi hingga menjadi tokoh kesayangan (media darling), seketika
berbalik arah menjadi penyalur informasi-informasi negatif yang menjatuhkannya.
Berikut ini adalah beberapa tuduhan yang berhaluan negatif yang ditudingkan kepada
Jokowi selama kampanye Pilpres 2014:
Gambar 1.2 Pengidentifikasian Capres Jokowi pada Pilpres 2014
(Sumber: asliusul.blogspot.com)
Dari teks kampanye hitam di atas, salah satu yang layak diperhatikan adalah
pengindentifikan Jokowi sebagai PKI. Sumber yang pertama kali menuturkan
informasi tersebut adalah akun @TM2000semar di media sosial Twitter. Akun ini menulis kicauan bersambung (atau lazim disebut “kultwit”) pada tanggal 13 Juni
2014 pada pukul 14.22 WIB. Di dalam kicauannya, akun @TM2000semar
dari PKI. Berikut adalah tampilan kicauan akun @TM2000semar yang dikumpulkan
dalam satu berkas:
Gambar 1.3 Kicauan tentang pembuktian Jokowi adalah PKI (Sumber: Intelijen.co.id)
Menilik bentuk kebahasaanya, teks kampanye di atas memiliki muatan bahasa
tendensius dan provokatif. Hal ini dapat dilihat dari fitur diksi, dimana terdapat
pemilihan kata-kata yang menyiratkan terkuaknya sebuah rahasia gelap seperti:
“Heboh”, “Bongkar”, “Benarkah”, “AKHIRNYA”, “TERBUKTI.” Dari segi
kejelasan pesan dan informasi, leksikon ‘PKI’ mengalami pereduksian makna melalui
pengakroniman. Leksikon PKI merupakan akronim dari Partai Komunis Indonesia.
Ditilik dari fitur semantis, PKI; Partai [+organisasi, +politik, +legal], Komunis
tidak mengandung satu pun elemen makna yang negatif. Namun, leksikon “PKI”
tidak diikuti penjelasan lebih lanjut sebagai sebuah partai politik yang berakibat
menimbulkan beragam potensi makna (potential meaning) yang strategis. Dari segi struktur bangunan teks, subjek “Jokowi” secara dominan (empat kali) ditulis rapat
dengan leksikon “PKI.” Klausa Jokowi PKI dikategorikan sebagai klausa atributif
tanpa pemarkah atribut seperti adalah, sebagai, dan lainnya. Hal ini juga dapat
menimbulkan efek psikologis yang menyiratkan eratnya kaitan Jokowi dengan PKI.
Selain bentuk (form) teksnya yang khas, pengidentifikasian Jokowi sebagai PKI juga menarik dari segi kontekstual. Jargon “PKI” dalam konteks politik dan
kesejarahan Indonesia dapat diposisikan sebagai hantu menakutkan. Muchlis (2015)
dalam Hantu Bernama PKI menyebutkan bahwa kehadiran PKI diilhami sebagai
teror yang menakutkan bagi siapa yang bersinggungan dengannya. Kesan PKI yang
horor, bengis, kejam, anti-tuhan, dan pengkhianat secara nyata diejawantahkan dalam
berbagai produk pemerintah Orde Baru seperti dalam film Penumpasan
Pengkhianatan G/30/S-PKI (tahun produksi 1984), Djakarta 1966 (tahun produksi
1988), Serangan Fajar (tahun produksi 1981), artefak Sumur Lubang Buaya dan
Monumen Pancasila Sakti. Juga seperti yang terlihat dari muatan bahasa di atas, PKI
dianggap sebagai sumber kejahatan yang tak dapat ditoleransi kehadirannya. Bahkan
sampai sekarang, beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan pelarangan
ajaran komunisme seperti; TAP MPPR no 25 tahun 66, UU No. 29 tahun 99, dan
KUHP pasal 107 A, B, dan C masih dijadikan senjata pamungkas untuk
Gambar 1.4 Efek kampanye hitam terhadap Jokowi
(Sumber: Kompas.com)
Pelabelan Jokowi sebagai (bagian dari) PKI memberi dampak yang cukup
signifikan terhadap elektabilitas (tingkat keterpilihan) dalam pertarungan Pilpres
2014 (lihat Gambar 1.4). Di sini dapat dipahami bahwa jargon “PKI” mempunyai
fungsi yang substansial dari sebuah sistem bahasa dan tanda yang dipakai dalam
tuturan kampanye politik di Indonesia. Leksikon “PKI” bukanlah sebuah unsur yang
mati, pasif dan statis melainkan sebuah fungsi yang memiliki efek khusus. Hal inilah
yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian pergerakan wacana teks kampanye
Jokowi pada Pilpres 2014 dalam penelitian ini.
Kedudukan wacana dalam mempengaruhi pilihan politik publik di era
keterbukaan dan kebebasan informasi terbukti sangat penting. Bahasa sebagai
medium utama aktivitas wacana, mempunyai kedudukan yang fundamental dalam hal
ini. Bahasa tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai ide yang pasif, tetapi telah
aktif berstrategi di balik konstruksi-konstruksinya. Dampak nyata utak-atik bahasa
Untuk menyimpulkan, penelitian ini berangkat dari celah postulat Saussure
mengenai sistematika bahasa yang rapuh dan renggang yang pada akhirnya
memposisikan bahasa menjadi terombang-ambing dan tak stabil. Ruang kosong dan
kegoyahan sistem bahasa membuat para penutur dan pendengar bahasa berada dalam
kebingungan. Para produsen wacana kemudian memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan-kepentingan khususnya. Pada tataran fungsi, untuk memahami sifat
bahasa terus bergejolak dan berkembang sehingga tidak hanya berkumpul pada
lingkaran positivistik namun diharapkan mencapai level strategis.
Penelitian ini berupaya menganalisis logika, filsafat dan objektivitas
kebahasaan yang menempel pada teks-teks kampanye pada Pilpres 2014. Lebih jauh,
penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap alur pergerakan wacana dengan
menguji lima elemen dasar (Basis, Relasi, Ekuilibrium, Aktualisasi dan
Keberlanjutan) penyusun wacana itu sendiri.
1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Wacana dalam pemahaman sederhana merupakan produk imajiner yang
dihadirkan lewat praktik berbahasa. Praktik berbahasa bisa terjadi dalam wujud lisan
dan tulisan. Pemakaian bahasa sudah sedemikian berkembang mencapai level yang
strategis sehingga bisa memuat kepentingan-kepentingan tertentu. Di dalam
kampanye Pilpres 2014, wacana mempunyai kedudukan penting dalam menampung
dan mengekspresikan ide-ide serta pengalaman penuturnya mengenai kehadiran
capres Jokowi. Penelitian ini selanjutnya memberikan telaah linguistik dalam
(hitam dan putih) tentang Jokowi selama masa kampanye Pilpres 2014. Telaah
tersebut memakai dasar pijakan linguistik (analisis wacana) sebagai pisau bedahnya.
1.3Rumusan Masalah
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan ketercapaian sasaran yang
diharapkan, masalah penelitian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian berikut ini:
(1) bagaimanakah basis kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada Pilpres
2014?
(2) bagaimanakah relasi kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada Pilpres
2014 dengan aspek tekstual, kontekstual, logika, ideologi dan kebenaran?
(3) bagaimanakah ekuilibrium/keseimbangan kampanye hitam dan putih
tentang Jokowi pada Pilpres 2014?
(4) bagaimanakah aktualisasi kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada
Pilpres 2014 pada kehidupan sehari-hari?
(5) bagaimanakah keberlanjutan kampanye hitam dan putih tentang Jokowi
pada Pilpres 2014 di masa depan?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan umum penelitian adalah untuk menemukan konfigurasi, signifikansi dan
pergerakan wacana dari teks kampanye Jokowi pada Pilpres 2014.
Untuk ketercapaian sasaran yang diharapkan, tujuan penelitian di atas akan
dirinci sebagai berikut:
(1) menelaah basis wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada
(2) memeriksa relasi wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada
Pilpres 2014 dari aspek tekstual, konstekstual, logika, ideologi dan
kebenaran,
(3) mengukur ekuilibrium wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi
pada Pilpres 2014,
(4) mengulas aktualisasi wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi
pada Pilpres 2014, dan
(5) memprediksi keberlanjutan wacana kampanye hitam dan putih tentang
Jokowi pada Pilpres 2014.
1.5 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis:
1) hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan objektif kepada pembaca
dalam menyikapi keabsahan wacana melalui sudut pandang linguistik,
2) untuk memperkenalkan teori BREAK sebagai salah frame terbaru dalam
analisis wacana kritis, dan
3) untuk mengembangluaskan kerja sama kajian linguistik dengan bidang
kajian ilmu lainnya (interdiciplinarylinguistics).
b. Manfaat Praktis:
1) untuk mengetahui ragam praktik wacana yang dihadirkan teks kampanye
pada selama periode Pilpres 2014.
2) untuk meningkatkan kesadaran berbahasa (language awareness) dan sejarah
1.6 Defenisi Istilah yang Digunakan
Wacana/Diskursus :jejak kebahasaan yang ditinggalkan oleh sejarah dan merupakan metode penyampaian pesan yang tertentu dan spesifik (Foucault 1972).
Kampanye :suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan (Pfau dan Parrot 1993:15).
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Kajian Pustaka
Kemunculan sebuah penelitian ilmiah pada hakikatnya tidak pernah terlepas
dari penelitian-penelitian lainnya. Penelitian tersebut merupakan missing link dari
rantai panjang penelitian yang telah ada sebelumnya dan penyambung jalan bagi
penelitian selanjutnya. Sub-bab kajian pustaka di sini bertujuan untuk menjelaskan
posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan subjek kajian
yang sama. Dengan mengkaji penelitian-penelitian wacana kebahasaan dalam kancah
politik terutama teks kampanye presiden, penulis akan mengetahui apakah penelitian
ini akan menambah khazanah baru, memperkuat klaim-klaim, menolak
hipotesis-hipotesis yang telah ada atau memberi sudut pandang baru dalam analisis wacana
kritis khususnya analisis perbandingan wacana.
Penelitian pertama yang dirujuk yaitu Kholila (2016). Kholila mendiskusikan
beberapa aspek kebahasaan yang membentuk wacana yang memnyusun satu paket
tuturan Jokowi selama periode kampanye Pilpres 2014. Dalam penelitian ini, Kholila
mengumpulkan data dari video yang diunduh dari situs berbagi video Youtube, yang
kemudian ditranskripsikan menjadi data yang dapat dianalisis. Tahap analisis data
merupakan penyeleksian data yang sudah dalam bentuk transkrip, lalu dipilah sesuai
data yang diperlukan. Dalam melakukan analisis data, Kholila menggunakan metode
padan dengan alat penentu mitra wicara yang lebih dikenal dengan metode padan
informal yakni dengan mendeskripsikan hasil pembahasan menggunakan kata-kata
yang lengkap sesuai dengan fakta yang ada (narasi).
Hasil analisis mencakup beberapa korpus kebahasaan yang diuraikan dalam
satu per satu. Dari penggunaan diksi Jokowi saat kampanye Pilpres, Jokowi dominan
menggunakan diksi denotatif daripada diksi konotatif. Penggunaan diksi denotatif ini
menyatakan bahwa Jokowi menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti
oleh masyarakat awam dalam hal penyampaian ide atau pun program-program yang
direncanakan Jokowi beserta tim suksesnya. Ketepatan diksi juga sangat berpengaruh
dalam kampanye sebab terbukti bahwa Jokowi lebih sering menggunakan kata ‘Kita’
dari pada kata ‘Saya’ untuk menumbuhkan kesan sopan dan menghindari citra
kearogansian Jokowi di hadapan masyarakat Indonesia. Gaya bahasa juga ditemukan
dalam penelitian ini. Gaya bahasa retoris yakni eufemisme, hiperbola, dan litotes.
Eufemisme digunakan Jokowi untuk menimbulkan efek sopan dalam penyebutan
hal-hal yang mungkin cederung tidak pantas disebutkan, seperti menyebut ‘TKI’ sebagai
‘pencari suaka’. Dalam penggunaan hiperbola, Jokowi cenderung menggunakannya
untuk efek-efek penegasan dalam menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat. Gaya
bahasa litotes digunakan Jokowi untuk mengisyaratkan kesederhanaan Jokowi dan
kesamaan rasa antara Jokowi dengan masyarakat Indonesia kelas bawah.
Untuk gaya bahasa kiasan, Kholia mengindentifikasi adanya penggunaan
personifikasi, ironi, dan metonimia. Gaya bahasa personifikasi digunakan untuk
menghidupkan ajakan-ajakan Jokowi pada masyarakat Indonesia. Dalam penggunaan
ironi mengisyaratkan bahwa Jokowi juga mampu menyindir lawan politiknya yakni
dengan lawan politiknya. Metonimia digunakan Jokowi untuk menyebutkan
nama-nama program yang akan dibangun Jokowi guna membuat masyarakat yakin bahwa
Jokowi tidak main-main dalam pembuatan programnya. Banyaknya penggunaan frasa
‘oleh sebab itu…’ dan penggunaan kalimat tanya di sela-sela argumen Jokowi
memberikan pengertian bahwa Jokowi memiliki idiosinkresi tersendiri sehingga ada
pembeda antara Jokowi dengan orang lain. Gaya bahasa khas ini terungkap dari
banyaknya data yang ditemukan dalam debat capres dan cawapres maupun kampanye
Jokowi.
Penelitian kedua yang ditinjau adalah Yaumul (2014). Yaumul melandasi
penelitiannya dengan aneka fungsi-fungsi bahasa dalam ranah wacana. Menurut
Yaumul, titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks
secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Pada kajian ini, Yaumul
memfokus penelitiannya kepada salah satu unsur konteks yang berperan penting pada
retorika wacana kampanye SBY yakni simbol. Penggunaan simbolisme pada
kampanye SBY seperti logo, warna yang digunakan oleh SBY dan koleganya,
maupun jargon-jargon yang identik dengan wacana kampanye, merupakan
tanda-tanda yang cukup strategis untuk menguatkan objek yang ditampilkan SBY.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumen berupa video pidato politik SBY pada kampanye Pilpres 2009. Analisis data
dilakukan dengan menghimpun dan mengklasifikasi data, memberikan kode, dan
menginterpretasikan data. Hasil analisis data menunjukkan terdapat konteks epistemis
konteks epistemis pertahanan keamanan dalam retorika wacana kampanye SBY pada
Pilpres 2009.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa warna merah, putih dan biru menjadi
dominasi simbolisme warna yang digunakan oleh SBY dalam kampanye Pilpres
2009. Terdapat lambang bintang segitiga yang merupakan filosofi partai Demokrat
yang berdiri di atas tiga unsur, yaitu ‘rakyat’, ‘pemimpin’ dan ‘Tuhan’. Selain
pemaknaan lambang bintang segitiga yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat,
lambang bintang segitiga tidak lepas dari filsafat kejawaan/javanologi. Terdapat tiga
titik sudut bintang yang identik dengan sesanti trisula wedha pada serat Jongko
Jayabaya. Makna sesanti trisula wedha bukan senjata dalam arti sebenarnya. Secara
konotatif, tiga kekuatan yang membuat seorang pemimpin disegani segenap
rakyatnya harus memiliki tiga sifat-sifat kepemimpinan seperti benar, lurus, jujur
(bener, jejeg, jujur) seperti yang diungkapkan dalam tembang-tembang ramalan
Jayabaya. Hal ini selaras dengan tiga sudut bintang yang melambangkan sifat-sifat
kepemimpinan, dalam hal ini adalah harapan akan sifat kepemimpinan yang dimiliki
oleh SBY. Analisis data ragam bahasa dalam wacana kampanye SBY pada Pilpres
2009, terbagi menjadi analisis ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa populer.
Terdapat 129 ragam bahasa ilmiah dan 85 ragam bahasa populer dalam retorika
wacana kampanye SBY pada pemilihan presiden 2009. Selain itu pada analisis data
gaya bahasa digunakan majas (gaya bahasa) asosiasi, penegasan dan pertautan,
terdapat 5 jenis gaya bahasa klimaks, 7 gaya bahasa anti-klimaks, 36 gaya bahasa
anadiplosis, epanalepsis, anafora, epistrofa, paralelisme), dan 1 gaya bahasa
antitesis.
Penelitian selanjutnya yang ditinjau adalah Adnyani (2011). Tulisan ini
membahas wacana-wacana politik yang dimunculkan oleh media massa (koran)
menjelang Pilpres 2009. Ada pun dua tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan
cara media harian nasional Kompas dalam memberitakan situasi politik jelang Pilpres
2009 dilihat dari segi kosa kata dan bentuk kalimat yang digunakan, dan 2)
mendeskripsikan cara wacana politik membentuk citra (image) figur calon presiden
dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pilpres 2009.
Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan
analisis wacana pada level teks dengan menggunakan analisis dengan mengadaptasi
model Van Dijk. Teks berita yang digunakan sebagai sumber data adalah teks berita
Kompas yang terbit pada edisi April 2009 sampai Juni 2009. Data dikumpulkan
melalui studi dokumen dengan mengkliping teks, pembuatan kartu data, tabulasi data
yang akan dianalisis serta interpretasi dan pendeskripsian data.
Pilihan kosakata yang digunakan Kompas dihiasi dengan kosakata yang
menggambarkan cara partai politik membentuk koalisi serta pilihan kata yang
menggambarkan pertentangan antara kubu partai yang berseberangan. Bentuk kalimat
yang digunakan adalah bentuk kalimat aktif, pasif dan nominalisasi. Bentuk kalimat
pasif lebih sering digunakan dalam menulis judul teks berita daripada bentuk
aktifnya. Dalam setiap teks berita yang dimuat dalam Kompas ada sebuah
pembenaran atau ideologi yang ingin disampaikan oleh Kompas melalui
peristiwa serta mengutip pernyataan-pernyataan dari pihak yang terlibat.
Pengambaran citra oleh Kompas dilakukan dengan cara mengutip slogan kampanye,
mengaitkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan atau jabatan sebelumnya, serta
dengan cara memuat komentar-komentar pakar tentang kandidat yang bersaing.
Dalam penelitian lainnya, tesis Arifiani (2015) menelaah penggunaan metafora
dalam wacana politik Pilpres 2014. Arifiani menguraikan beberapa tujuan
penelitiannya yaitu: untuk mendeskripsikan bentuk lingual metafora dalam wacana
politik di media massa cetak, mendeskripsikan jenis metafora dalam wacana politik di
media massa cetak, mendeskripsikan konseptualisasi metafora, dan mendeskripsikan
fungsi metafora dalam wacana politik di media massa cetak berbahasa Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik
kognitif. Data dikumpulkan dari media massa cetak berbahasa Indonesia, yaitu
majalah Tempo dan koran Kompas. Analisis data didasarkan pada teori metafora
konseptual Lakoff dan Johnson dan disajikan dengan metode formal dan informal.
Hasil analisis dirangkumkan dalam beberapa beberapa poin sebagai berikut: (1)
bentuk lingual metafora yang berupa kata didominasi oleh kelas kata nomina, verba,
dan ajektiva; dalam bentuk frasa, berupa frasa nomina dan perluasan frasa nomina;
dalam bentuk klausa, berupa klausa verba; dan dalam bentuk kalimat, berupa kalimat
deklaratif dan interogatif, (2) jenis metafora yang terdapat dalam wacana politik di
media massa cetak berupa metafora langsung, metafora tidak langsung, dan metafora
implisit, (3) sekurang-kurangnya dua puluh enam konseptualisasi metafora yang
ditemukan dalam wacana politik. Konseptualisasi tersebut terdiri dari konseptualisasi
kabinet, perebutan kekuasaan, partai politik, kementerian dan kabinet, pemerintahan,
dan negara dan, (4) metafora dalam wacana politik berfungsi untuk penyederhaan,
alat untuk mengkongkretkan konsep yang abstrak, untuk dramatisasi situasi, untuk
alat retorika elite politik, untuk mengkritik, untuk menyindir, dan menunjukkan
fungsi puitis.
Rujukan penelitian lainnya adalah Wulandari (2015). Penelitian tersebut
membahas wacana humor politik (WHP) di media sosial Twitter. Wulandari
menyatakan bahwa wacana humor politik (WHP) yang ditulis oleh akun Twitter
@CapresJokes merupakan bentuk reaksi publik terhadap pelaksanaan Pilpres 2014.
Substansinya berupa komentar dan didukung dengan isu-isu atau gambaran peristiwa
seputar pelaksanaan Pilpres yang dikemas secara jenaka. Kekhasan WHP dibanding
dengan wacana humor lain dapat diamati dari strukturnya, proses penciptaan
humornya, maupun fungsinya. Selain itu, dalam WHP juga terdapat figur
capres-capres, dalam hal ini Prabowo dan Jokowi, yang terepresentasi membentuk suatu citra
tertentu.
Hasil analisis data menunjukkan struktur WHP secara umum meliputi bagian
nama akun yang berfungsi sebagai identitas, bagian isi, serta waktu dan tanggal
posting. Bagian WHP yang memiliki struktur yaitu isi, terdiri atas tweet (T) dan
meme (M). Subbagian T berfungsi mengomentari M, mempertahankan topik,
mengekspresikan perasaan penulis, dan menciptakan humor. Subbagian M berfungsi
menggambarkan peristiwa, menginformasikan sesuatu, dan menciptakan humor. Jenis
WHP yang dianalisis terdiri dari WHP bertipe monolog, dialog, dan non-monolog
mempertentangkan pemetaan makna (script). Selain itu juga dapat diamati
berdasarkan penyimpangan prinsip kerja sama, prinsip kesopanan, dan parameter
pragmatik. Peserta pertuturan dalam WHP, secara tekstual melanggar maksim
kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Secara
interpersonal, peserta tutur juga menyimpangkan maksim kebijaksanaan, maksim
kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan
maksim kesimpatian. Penyimpangan juga dilakukan terhadap parameter jarak sosial,
parameter status sosial, dan parameter kedudukan tindak tutur.
Humor dalam WHP juga memanfaatkan aspek ortografis, aspek fonologis,
aspek morfologis, ketaksaan, metonimi, hiponimi, sinonimi, antonimi, eufemisme,
nama, deiksis, kata ulang, pertalian kata dalam frasa, konstruksi aktif-pasif, pertalian
antar-klausa, kalimat tanya, kalimat eliptis, ragam dan variasi bahasa, serta pertalian
antarproposisi. WHP memiliki fungsi antara lain bercanda, mengejek, memerintah,
memberi pembenaran, menyindir, mengkritik, dan menyatakan ketidaksetujuan. Citra
Prabowo yang terepresentasi dari beberapa data WHP antara lain: figur yang
dipersalahkan dalam kasus pelanggaran HAM 1998, otoriter, kasar, peniru, licik,
lemah, inkonsisten, inkompeten, penyebar fitnah, ambisius, dan tidak
bertanggungjawab. Sedangkan, citra Jokowi sebagai figur yang kuat, gemar
melakukan pencitraan diri, tulus, masa bodoh, merakyat, boneka partai, dan pintar.
Selanjutnya, penelitian yang dirujuk dilakukan oleh Puspita (2015). Dalam
penelitiannya, Puspita mengusut kepentingan terselubung yang diusung oleh SBY
selaku presiden Indonesia pada pidato terakhirnya. Berangkat dari hipotesis Fowler
linguistik dengan struktur sosial melalui analisis materi bahasa. Seterusnya, analisis
dilakukan untuk mengetahui representasi pemerintah dan kepentingan Presiden SBY
merepresentasikan pemerintah sebagaimana terdapat dalam pidatonya.
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Presiden SBY merepresentasikan
pemerintahannya sebagai pemerintah yang baik. Strategi Presiden SBY untuk
merepresentasikan pemerintah dengan baik adalah; (1) menunjukkan kemampuan
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (74,71 persen), (2)
menyamarkan kekurangan pemerintah (4,6 persen), dan (3) menyampaikan informasi
untuk menarik perhatian pendengar (20,69 persen). Representasi pemerintah yang
baik tersebut direalisasikan Presiden SBY melalui pilihan kata, kalimat, bahasa
asing, dan detail informasi yang disampaikan Presiden SBY melalui pidatonya.
Kepentingan presiden SBY merepresentasikan pemerintahannya dengan baik adalah
untuk meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat sebelum lengser dari
jabatannya.
Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian
kebahasaan dalam kaitannya dengan wacana kampanye presiden selalu berkembang
dan meluas. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai substansi kebahasaan seperti
pidato, kicauan di sosial media, teks koran, maupun simbol dan lambang partai.
Perbedaan mencolok dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni
perbandingan dan pergerakan wacananya. Sejauh ini, belum ditemukan adanya kajian
dan penelitian yang membahas perbandingan dan pergerakan wacana disebabkan
wacana dengan teori BREAK yang masih belum banyak digunakan dalam penelitian
kebahasaan di Indonesia khususnya analisis wacana.
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Analisis Wacana Kritis
Sebermulanya, penelitian ini bersifat analisis wacana kritis. Hal ini dijelaskan
oleh Fairclough (1989) dan Van Dijk (2003) menyatakan bahwa analisis wacana
kritis adalah salah satu jenis kajian analisis wacana yang memusatkan kajiannya
kepada penjelasan hubungan dialektis antara bahasa, praksis linguistik, teks/praksis
wacana, dan budaya/praksis sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Fairclough
(1995) mengatakan bahwa analisis wacana kritis berupaya menggali makna dalam
teks, bahasa dalam hubungannya dengan proses sosial melihat teks berfungsi secara
ideologi dan politik dalam suatu konteks, serta hubungan lebih luas dalam perubahan
sosial dan budaya dalam masyarakat.
Lebih lanjut, Fairlough memberikan gambaran bahwa analisis wacana kritis
memandang wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam hal ini, analisis wacana
kritis melihat bahasa sebagai faktor penting yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk
melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Fairlough kemudian menjelaskan
bahwa analisis wacana kritis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
(1) Wacana dipandang sebagai sebuah tindakan. Artinya, wacana merupakan
bentuk interaksi yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, mendebat, bereaksi
dan menyanggah.
(2) Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar
sejarah, baik latar situasi, peristiwa, maupun latar tempat. Hal ini sejalan dengan
mempertimbangkan konteks dari komunikasi dan dengan siapa, dalam situasi apa,
dan melalui medium apa.
(3) Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam
analisisnya. Dalam hal ini, setiap wacana yang muncul tidak dilihat sebagai sesuatu
yang empiris dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan.
(4) Konsep ideologi. Ideologi juga merupakan salah satu karakteristik dan
analisis wacana kritis. Hal ini dapat dipahami karena teks baik yang tertulis maupun
lisan merupakan bentuk praktik atau perwujudan dari ideologi tertentu.
Pada dasarnya, pendekatan analisis wacana kritis ini cukup siginifikan
digunakan untuk menganalisis wacana karena dapat menyingkap makna sosial,
kultural, ideologikal maupun historikal di balik sebuah teks. Dibanding dengan
pendekatan model analisis wacana lainnya, analisis wacana kritis sudah
menggunakan metode lintas-disiplin yang tidak hanya terfokus mengkaji aspek-aspek
struktural dari sebuah teks baik dari segi gramatikal maupun leksikal.
2.2.2 Teori BREAK (Pergerakan Wacana)
Teori BREAK adalah singkatan dari B untuk Basis, R untuk Relasi, E untuk
Ekuilibrium, A untuk Aktualisasi dan K untuk Keberlanjutan Wacana. Teori ini
adalah produk pengembangan dari kerangka berfikir (frame) E-135 karya Sawirman
(2005). Teori BREAK menawarkan beberapa hal-hal baru (novelties), kerangka dan
fitur-fitur solusi konseptual yang dapat menggabungkan kajian-kajian kebahasaan
dengan disiplin ilmu lain. Sawirman pertama kali dalam buku E-135 Reader
menerapkan teori BREAK kepada wacana teror pada kajian sapaan Osama Bin
batas (Sawirman 2014: viii). E-135 merupakan singkatan dari Eksemplar 1, 3 dan 5.
Angka 1 pada E-135 menyimbolkan landasan ontologis/filosofis (hermeneutika),
angka 3 menyimbolkan revisi pendekatan wacana terkini (kritis, dekonstruksionis,
cultural studies), serta angka 5 menyimbolkan tahapan analisis (elaborasi,
representasi, signifikasi, eksplorasi, dan transfigurasi) sekaligus landasan objek
material dan formal yang masing-masingnya diberi penjelasan ontologis,
epistemologis, dan aksiologis (Sawirman 2005). Ada pun penjabaran poin-poin utama
mengenai teori BREAK satu per satu adalah sebagai berikut:
1. Basis Wacana
Basis wacana merupakan titik awal sebelum membaca pergerakan wacana.
Ada tiga fitur utama yang harus diperhatikan dalam menentukan basis wacana yakni:
(i) Posisi Wacana.
Posisi menentukan apakah wacana tersebut masuk kategori primer atau
sekunder. Wacana primer adalah wacana yang menjadi sentral atau basis
perbandingan bagi wacana lainnya. Sedangkan wacana sekunder adalah wacana yang
dibandingkan dengan wacana primer untuk mengungkap proses pergerakan
wacananya.
Contoh kasus:
(ii)Konfigurasi wacana
Konfigurasi wacana bertujuan untuk merumuskan struktur internal wacana dari
segi wujud, esensi dan spirit. Wujud merupakan bentuk konstruksi yang berisikan
fitur-fitur linguistik yang terkait dengan aktifikas, aksi dan perilaku manusia. Esensi
dipahami sebagai kandungan pesan, makna atau gagasan sebuah wacana. Spirit
adalah motif, tujuan, orientasi ataupun motivasi dari sebuah wacana.
Contoh kasus:
a. Wujud
Klausa Lovewins terdiri atas dua kata; ‘love’ dan ‘wins’. Secara harfiah diartikan ‘cinta/kasih sayang’ dan ‘menang’. Kata love diposisikan sebagai subjek aktif yang melakukan verba aktifitas wins. Klausa intransitif ini meniadakan unsur objek di dalam struktur bangunan kalimatnya. Ini berarti, subjek love (cinta) melakukan wins (menang) tanpa menaklukkan lawan apapun (objek).
Dalam wacana sekunder, ada wujud simbol pelangi sebagai simbol untuk menyambut pengesahan pernikahan sejenis. Ditilik dari fitur semantisnya pelangi dan cinta (sesama jenis) memiliki persamaan gugus konfigurasi [+harmoni, +sejajar, +gembira].
b. Esensi
Seperti yang telah diuraikan dalam analisis wujud, lovewins merupakan klausa intransitif. Klausa ini menihilkan keberadaan objek dalam jejaring strukturnya. Subjek Love tidak mempunyai relasi objek apapun yang disebabkan oleh aktifitas wins. Verba aktifitas wins merupakan [+aktifitas, +mengalahkan, +unggul dari]. Namun, ketiadaan objek menyiratkan bahwa subjek Love tidak berkompetisi dengan apapun. Pesan yang ingin disampaikan oleh wacana ini adalah pelaku/doer cinta bukanlah permasalahan siapa unggul dan gagal, menang ataupun kalah. Cinta adalah kemenangan itu sendiri dan dapat mengalahkan (objek target) apapun.
Seperti yang telah diuraikan di atas, ada pun wacana sekunder menampilkan pelangi sebagai simbol penyambutan keputusan pelegalan pernikahan sejenis. Pelangi jika bertolak pada referennya yaitu cinta sejenis, maka titik persinggungannya adalah [+harmoni, +sejajar dan +gembira]. Harmoni menyuratkan persatuan yang alamiah dan natural antara dua insan karena cinta. Sejajar mewakili peran dan posisi seksual mereka berdua dalam sudut pandang cinta. Gembira mengungkapkan perayaan atas kemenangan perjuangan mereka atas nama cinta.
Spirit dari kedua kelompok wacana tersebut adalah kegembiraan. Pada wacana primer, unsur kemenangan (win) dalam klausa Lovewins memiliki kaitan erat dengan kegembiraan. Setiap kemenangan selalu diikuti oleh kegembiraan.
Begitu pun dengan wacana sekunder. Simbol pelangi juga mempunyai fitur kegembiraan dalam kaidah semantisnya. Pelangi muncul sesudah terjadinya hujan. Hujan identik dengan bencana (banjir, longsor, topan, badai, air bah). kehadiran pelangi merupakan simbol universal terhadap kegembiraan setelah bencana atau kabar buruk.
(iii) Tipe Umum Pergerakan Wacana
Hal ini menentukan sifat pergerakan wacana ditentukan dari konfigurasinya.
Di dalam teori BREAK, ada dua tipe umum yakni konvergen dan divergen.
Konvergen berarti kedua wacana yang dibandingkan saling melengkapi,
mendukung dan seide baik dari segi esensi maupun spirit. Divergen dipahami
sebagai pergerakan wacana yang bertolak belakang yang antara wacana
primer dan sekunder.
1. Relasi Wacana
Fitur ini membahas keterkaitan wacana dengan entitas, realitas atau wacana
lainnya. Relasi ini terbagi dari:
a. Relasi tekstual.
Relasi ini mengomparasikan teks dengan teks lain baik dari sisi wujud, esensi dan spirit.
Contoh kasus:
Teks #lovewins mempunyai ragam varian yang mengusung esensi dan spirit yang sama. Dalam survei Topsy, ada beberapa tagar lain yang berkembang yaitu #marriageequality #loveislove #pride.
Teks #marriageequality merujuk kepada posisi pernikahan gay/lesbian di mata hukum. Dengan diakuinya undang-undang pernikahan sejenis ini, maka tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasangan yang menikah layaknya pernikahan kaum heteroseksual.
Teks #loveislove mempunyai rantai kaitan pada kata love (cinta). Muatan/isi pesan yang ingin disampaikan adalah cinta pasangan sejenis adalah juga merupakan cinta layaknya manusia lainnya. Paradigma selama ini diamini, mengungkapkan tuduhan bahwa cinta sejenis bukanlah cinta yang wajar atau hanya berlandaskan nafsu belaka (atau juga dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan oleh WHO sampai 1973). Teks #loveislove kemudian menjadi justifikasi atas kemurnian cinta pasangan sejenis.
Teks #pride muncul sebagai respons terhadap diskriminasi yang dialami oleh pasangan sejenis. Leksikon pride atau bangga menunjukkan kepercayaan diri mereka untuk mengekspresikan orientasi seksual mereka tanpa harus mengalami diskriminasi dan intimidasi.
Secara bawah sadar, teks #lovewins menularkan semangat kesejajaran, bebas prasangka dan humanitas dibaliknya.
b. Relasi kontekstual.
Relasi ini merupakan pengaduan antar-konteks antar wacana dalam relasi tekstual.
Contoh kasus:
Kehadiran jargon lovewins dalam tagar di platform twitter bukan semata-mata komoditas/hal baru. Hal ini merupakan tak lebih dari
repackaging/pembungkusan ulang dari peristiwa-peristiwa sebelumnya.
Media sosial berfungsi sebagai sumber informasi layaknya koran, radio atau televisi pada generasi sebelumnya. Amerika Serikat telah lama menghadirkan jargon-jargon sebagai medium utama penggerak wacana.
pembenihan wacana pertama kali dimulai oleh Barrack Obama pada tahun 2009.
Obama mengajukan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat yang ke-49 dari ras negroid (kulit hitam). Belum genap seratus tahun Amerika Serikat terlepas dari budaya perbudakan kulit hitam, Obama melakukan langkah besar untuk maju sebagai pemimpin Amerika Serikat. Melalui media sosial, Obama merangkul setiap golongan dengan jargon “Yes, We Can.” Baik di setiap arena kampanye dan promosinya, Obama selalu menyematkan jargon tersebut.
Jika menilik ke belakang, pada tahun 1960-an, ketika perjuangan ras kulit hitam (negro) berusaha mencapai pengakuan dan hak-hak sipilnya di mata hukum juga diilhami oleh sebuah jargon. Jargon “I have a dream” ini dicetuskan Martin Luther King, Jr melalui pidatonya dengan judul yang sama. Dilhat dari esensi dan spiritnya, tagar lovewins mempunyai kemiripan dengan jargon “Yes, We Can” dari Obama serta“I Have a Dream” dari King. Mereka bergerak dari minoritas yang mencari dukungan dengan cara-cara persuasif dan berlandaskan semangat optimisme.
c. Relasi faktual.
Relasi ini mengaitkan isi pesan wacana dengan realitas di lapangan. Contoh kasus:
Untuk azas kebenaran, tidak semua golongan di Amerika Serikat bersimpati terhadap pelegalan pernikahan sejenis ini. Keputusan yang diambil pun harus melalui pemungutan yang alot disebabkan oleh perbedaan pandangan dari anggota Supreme’s Court.
Jika diturunkan ke masyarakat luas, yang dimana demografi AS sendiri terdiri dari berbagai macam ragam ras, ideologi, agama dan latar belakang pendidikan, wacana ini semakin menemui tantangan yang berat. Agama Islam dan Kristiani Ortodoks tidak membolehkan penganutnya untuk hal ini. Begitupun golongan-golongan ekstrimis lainnya seperti yang menunjukkan ketaksetujuannya karena berbenturan kepentingan (budaya, reproduksi, dan lainnya).
d. Relasi logika
Relasi ini merupakan pengujian isi pesan wacana dengan logika penalaran. Contoh kasus:
Wacana dukungan terhadap pernikahan sejenis ini dapat diukur basis logikanya dari pandangan ilmu hukum dan sosial.
warga negara, pelaku pernikahan sejenis juga mempunyai hak yang sama untuk diakui legalitasnya. Ini diusahakan agar mereka dapat menjalankan kesehariannya dengan lancar layaknya penganut orientasi seksual yang biasa (hetero). Pada azas ini, wacana ini memakai logika hukum yang jelas sebab-musababnya.
e. Relasi Ideologis
Relasi ini menguak kaitan isi wacana dengan ideologi yang disajikan. Contoh kasus:
Seperti yang telah diuraikan pada analisis Basis, #lovewins menawarkan ide bahwa cinta adalah kemenangan itu sendiri dan di atas segalanya. Secara tak sadar, wacana ini sejalan dengan anjuran/suggestion agama mayoritas di Amerika Serikat yakni Kristen. Agama Kristiani merupakan agama yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Simbol Yesus dengan matahari dibelakang kepalanya menyiratkan pancaran kasih sayang yang selalu menyinari pengikutnya. Begitupun simbol Bunda Maria, yang menyiratkan hubungan Tuhan dan umatnya layaknya antara seorang ibu yang menyayangi anaknya sendiri. Simbol salib yang merupakan simbol kecintaan Yesus kepada umatnya yang membuat dirinya rela menanggung dosa pengikutnya. Di sini bisa dilihat, tingkat kepopularan teks ‘#lovewins’ tidak semata-mata berdiri sendiri namun mempunyai relasi ideologi keagamaan dengan mayoritas penduduk Amerika Serikat.
2. Equilibrium Wacana
Tahap ini membahas aneka wacana tandingan yang memungkinkan terjadinya
perimbangan wacana. Pada proses ini, terdapat tiga fitur:
1. Legitimasi wacana
Legitimasi wacana adalah proses pembenaran wacana terhadap peristiwa, aksi, perilaku dan proses-proses realita lainnya berdasarkan faktor-faktor tertentu yang dijadikan standar nilai. Standar nilai bisa berupa standar ilmiah, logika, konvensi, sistem, kultur, adat istiadat, otoritas dan sejenisnya.
Contoh kasus:
Teks #lovewins pertama kali ditulis oleh akun @potus atau otoritas kekuasaan tertinggi di Amerika Serikat. Secara jelas, ini mendapat legitimasi dari negara sebagai sebuah nilai kebenaran. Selanjutnya, platform Twitter juga memberi legitimasi pada setiap tututan teks #lovewins dengan menampilkan fitur gambar pelangi.
2. Rentang Keseimbangan Wacana
Fitur ini mengukur keseimbangan wacana-wacana yang dibandingkan.
Contoh kasus:
Kicauan yang berisikan teks #lovewins menjadi sangat popular karena dipromosikan langsung oleh otoritas tertinggi yakni Presiden. Selain itu, sumber lahirnya wacana adalah salah satu kiblat budaya dunia. Pada wacana sekunder, juga memiliki wadah yang sangat strategis yakni Facebook. Belum lagi beberapa tokoh populer, merek-merek ternama serta figur publik lainnya juga ikut menyemarakkan wacana ini. Di sini terlihat tidak adanya wacana penyeimbang yang menyebabkan rentang wacana ini pada kondisi ekuilibrium rendah (lowequilibrium).
3. Wacana Penyeimbang
Fitur ini menelusuri wacana lain untuk ditarik ke dalam analisis sebagai
penyeimbang dari wacana dominan.
Contoh kasus:
Disebabkan rentang wacana berada pada ekuilibrium rendah, maka diperlukan adanya wacana tanding agar terjaganya kadar objektivitas dan bargaining
position dari wacana yang telah ada.
Jika dilihat dari keseluruhan proses narasi (penciptaan, pendistribusian, pengonsumsian dan interaksi wacananya), maka wacana penyeimbang yang mungkin hadir dari interaksi wacananya. Untuk membatasi penciptaan, pendistribusian dan pengonsumsian hampir tidak mungkin karena setting dan
participant-nya yang spesifik yakni, Amerika Serikat.
Wacana tanding yang mungkin ditawarkan adalah pesimisme dari aktualisasi wacananya. Pernikahan sejenis adalah barang baru. Layaknya sesuatu yang minoritas (unusual) kemudian umum (common), mungkin akan terjadi beberapa masalah yang belum diantisipasi solusinya yakni bagaimana penyelenggaraan pernikahan, hak anak angkat, pemberian nama keluarga, siapa yang bertindak sebagai suami atau istri, penyakit kelamin yang akan muncul, ketergabungan dalam masyarakat dan komunitas dsb.
3. Aktualisasi Wacana
Tahap ini merupakan proses pembacaan sejak dari perilaku wacana hingga
pembahasan efek wacana pada tataran aktual.
1. Perilaku wacana
Contoh kasus:
Perilaku wacana menyiratkan perilaku manusia. Ini disebabkan karena wacana diciptakan, didistribusikan dan dikonsumsi oleh manusia sendiri. Pada analisis ini, wacana primer atau sekunder berperilaku persuasif.
Persuasif di sini dapat dilihat dari instrumen yang digunakan. Pada wacana primer, instrumen yang digunakan adalah tagar. Tagar seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah konvensi dalam kesamaan topik pembicaraan. Pengguna/user yang menggunakan tagar lovewins secara otomatis tergabung dalam komunitas yang mendukung aksi tersebut. Jadi, tagar di sini berfungsi sebagai password/ kata kunci dalam ketergabungan dalam sebuah pergerakan. Dikarenakan kemudahan penggunaannya, banyak orang terhasut dan ikut berpartisipasi dalam wacana primer ini.
Begitupun halnya dengan wacana sekunder, simbol pelangi yang disematkan ke akun pengguna berfungsi layaknya tagar pada Twitter. Setiap orang boleh, bebas dan berhak menggunakannya tanpa terkecuali. Prinsip kebebasan dan penerimaan inilah menjadi kunci pergerakan dari kedua wacana tersebut.
2. Efek wacana
Fitur ini ini menelaah dampak jangka pendek dan potensi dampak dari wacana tersebut.
Contoh kasus:
Efek positif dari wacana ini berlaku terhadap golongan (minoritas) pelaku LGBT. Amerika Serikat sebagai patron budaya dunia (Hollywood, fashion, budaya pop, dan lain-lain), secara tidak langsung akan membuat pergeseran paradigma terhadap pelaku LGBT. Walaupun LGBT telah dihapuskan dari kategori penyakit/gangguan jiwa, namun stereotip dan kesan negatif masih marak didapati oleh penganutnya. Dengan pelegalan dan pengakuan hak-hak pelaku LGBT di mata hukum Amerika Serikat, tentu ini merupakan angin segar dan langkah besar bagi kaum LGBT.
Efek negatif juga hadir menyambut kedua wacana ini. Adanya tagar tandingan menyiratkan kehadiran oposisi terhadap wacana ini. Di negara-negara yang mayoritas islam (Asia Tenggara, Asia Tengah, Afrika Utara dan Timur Tengah) muncul sebagai daya perlawanan. Di Indonesia muncul beberapa wacana tandingan yang menyudutkan wacana ini seperti pelarangan masuk kampus (oleh Menristekdikti), pengobatan LGBT sebagai penyakit luar biasa (Kemenkes), dan protes dari ormas-ormas yang berkepentingan.
4. Keberlanjutan Wacana
Tahap ini menelaah memberi pandangan/tebakan beralasan (smart guess)
bagaimana wacana tersebut akan beradaptasi dan bertahan di masa depan. Ada
1. Adaptasi wacana
Adaptasi wacana merupakan kemampuan atau prediksi ilmiah suatu wacana
untuk berkembang dan bertahan eksis dalam pergerakan dan perubahan
realitas masa depan.
2. Solusi Wacana
Solusi wacana menyuguhkan jejaring strategis dalam upaya untuk mengisi
titik kosong (blindspot) dari wacana yang dianalisis.
3. Tipe perubahan Wacana
Fitur ini dapat menyediakan perubahan wacana ke depan dengan melihat
pola-pola terkait dengan konfigurasi wacananya.
2.2.3 Sistem Transitivitas Halliday
Untuk analisis konfigurasi linguistik (basis, esensi dan spirit) dari teks,
digunakan pendekatan Sistemik Fungsional Linguistik (lihat Halliday 1985; 1991)
yakni fitur sistem transitivitas. Sistem transitivitas mempunyai potensi untuk
mengungkap berbagai pengalaman-pengalaman sosial manusia yang terwujud dalam
bentuk gambaran pengalaman linguistik atau dalam istilah Halliday disebut proses
(process). Lebih jauh, sistem transitivitas bertujuan untuk menangkap makna
ideasional dari sebuah teks.
Menurut Halliday (1994:107), di dalam satu unit pengalaman yang sempurna
yang diwujudkan dalam bentuk klausa yang terdiri atas minimal 3 fitur yakni proses,
partisipan, dan sirkumstan. (1) proses, menurut cirinya direalisasikan oleh satu kata
kerja atau frasa kata kerja (2) partisipan-partisipan di dalam proses, menurut cirinya
yang berkaitan dengan proses, khususnya direalisasikan oleh frase ajektif atau frase
preposisi. Karena inti pengalaman adalah proses, maka dalam tataran klausa, proses
menentukan jumlah dan kategori partisipan. Selain itu, proses juga menentukan
sirkumstan secara tak langsung dengan tingkat probabilitas.
Selanjutnya Halliday (1994) menetapkan enam jenis proses dalam sistem
transitivitas model sistemik fungsional yakni material, mental, verbal, perilaku,
relasional dan eksistensial. Setiap jenis proses mempunyai jenis partisipan yang
berbeda karena sifat alamiah kejadian yang berbeda pula.
1. Material
Suatu proses yang berhubungan erat dengan aktifitas fisik dan materi. Proses ini
terdiri atas dua macam yakni melakukan sesuatu (doing) dan kejadian (happening).
Proses materi doing memiliki konstituen aktor-proses-goal. Proses materi doing dapat
berbentuk kreatif seperti membuat, mengembangkan, merancang maupun bersifat
dispositif seperti mengambil, memukul, mengirim. Sementara itu, konstituen proses
materi kejadian (happening) terdiri atas aktor dan proses. Aktor adalah partisipan
yang melakukan proses. Goal merupakan partisipan yang dikenai atau dipengaruhi
proses. Berikut adalah contoh proses material:
Proses materi melakukan sesuatu (doing)
Polisi Membuat Peraturan untuk pemotor
Aktor Proses: doing Goal Resipien/klien
Proses materi kejadian (happening)
Sepasang kekasih itu berkejaran
2. Verbal
Proses verbal adalah proses berkata murni. Konstituen dalam proses ini terdiri
atas penutur (sayer), hal yang dikatakan (verbiage), dan penerima tuturan (receiver).
Contoh proses verbal sebagai berikut:
Ayah menanyakan nilai rapor kepada adik
Sayer Proses Verbiage Receiver
3. Mental
Proses mental adalah proses berfikir, mengindera dan merasa. Proses ini
kemudian dikelompokkan lagi menjadi kognitif, perseptif dan afektif. Proses kognitif
berkenaan dengan penggunaan otak dalam berproses, misalnya; berfikir, mengerti,
melamun. Proses perseptif berhubungan dengan penggunaan indera dalam berproses
misalnya; melihat, mendengar, merasa. Proses afektif melibatkan penggunaan
parasaan dalam proses, misalnya; mencintai, membenci, suka, marah, dan sebagainya.
Konstituen dalam proses mental ini ada dua yakni senser (pengalam) dan
fenomena. Ada pun contoh dari proses mental adalah:
Nina
Proses perilaku verbal melibatkan verbal dalam aspek tindakannya seperti;
menyarankan, mengklaim, mendiskusikan, dan lainnya. Konstituen dari proses
partisipan yang melakukan proses verbal. Verbiage dan Receiver sama dengan
Proses perilaku mental merupakan gabungan dari proses mental dan material.
Proses ini melibatkan unsur fisik dan mental di dalam kejadiannya seperti
menyelidiki, mengamati, meneliti, dsb. Konstituen dari proses ini terdiri atas behaver
dan fenomena adalah sesuatu yang dikenai proses. Contoh perilaku mental sebagai
berikut:
Densus 88 telah meneliti lokasi pengemboman
Behaver Proses; perilaku mental Fenomena
5. Relasional
Proses relasional adalah proses yang menghubungkan antara partisipan dengan
partisipan atau unit lain. Hubungan tersebut kemudian memberi nilai kepada
partisipan yang pertama. Proses ini mempunyai dua jenis, yaitu proses relasional
atributif dan identifikasi. Pada proses relasional atributif, partisipan yang diberi nilai
dinamakan carrier. Pada proses relasional identifikasi, partisipan yang diberi nilai
adalah token dan nilai sesuatu tersebut disebut value.
Proses eksistensial yang menunjukkan keberadaan atau kejadian sesuatu. Proses
ini di dalam Bahasa Indonesia diwujudkan melalui kata ada, terdapat, muncul, dsb.
Partisipan dalam proses ini disebut eksisten. Berikut contoh proses eksistensial:
Terdapat ribuan buruh di jalan raya
Proses; eksistensial Eksisten Sirkumstan
2.2.4 Komponen-Komponen Tutur
Untuk analisis fitur relasi pada fitur R (relasi) dalam teori BREAK, maka
dibutuhkan teori-teori pendukung seperti ragam kontekstual. Di sini, dipilih teori
S.P.E.A.K.I.N.G dari Dell Hymes sebagai acuan utama analisis. Kerangka
S.P.E.A.K.I.N.G dipahami sebagai sebuah kerangka berfikir kontekstual yang
lengkap, padu dan mampu menjembatani analisis fitur relasi untuk teori BREAK.
Menurut Hymes (1972:54-62), konteks ialah situasi tutur yang terdiri dari enam
belas komponen tutur, meliputi message form ‘wujud pesan’, message content ‘isi pesan’, setting ‘latar’, scene ‘suasana’, speaker atau sender ‘penutur’, addressor
‘mitra tutur’, hearer (receiver, audience) ‘pendengar’, adresse ‘penerima’, purpose
-outcome ‘maksud-hasil’, purposes-goals ‘maksud-tujuan’, key ‘bunyi, pembawaan,
dan semangat’, channels ‘saluran’, forms of speech ‘bentuk tuturan’, norms of
interaction ‘norma interaksi’, norms of interpretation ‘norma interpretasi’, dan
genres‘kategori’.
Berdasarkan hal tersebut, Hymes mengelompokkan komponen-komponen
tersebut menjadi akronim dalam bahasa Inggris yaitu SPEAKING. S.P.E.A.K.I.N.G
‘urutan tindak’, key ‘kunci’, instrumentalities ‘piranti’, norms ‘norma’, dan genre
‘kategori’. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:
a) Situasi (Situation)
Situasi menurut Hymes (1972:55-56) terdiri atas setting ‘latar’ dan scene ‘suasana’.
Latar mengacu pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tutur, yang biasanya
mengacu pada keadaan fisik. Sedangkan suasana mengacu pada latar psikologis atau
batasan budaya tentang suatu kejadian sebagai suatu jenis suasana tertentu. Dalam
kehidupan sehari-hari, partisipan dapat mengubah suasana, misalnya, dari formal
menjadi informal atau dari serius menjadi santai.
b) Partisipan (Participant)
Partisipan (participant) terdiri atas speaker atau sender ‘penutur’, addressor ‘mitra tutur’, hearer/receiver/audience ‘pendengar’ dan addressee ‘penerima’. Dalam
penelitian ini, komponen ini mencakup penulis atau pembuat iklan dan pembaca atau
calon konsumen, karena tuturan disampaikan melalui majalah (media tulis).
Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan mitra tutur antara lain yaitu usia, latar
belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban.
c) Tujuan (End)
Tujuan meliputi purpose-outcome‘maksud-hasil’ dan purpose-goal‘maksud-tujuan’.
Outcome adalah hasil yang ingin dicapai dalam suatu peristiwa tutur, sedangkan
goals adalah tujuan (dalam angan) yang ingin dicapai dalam suatu peristiwa tutur.
Partisipan sangat menentukan hasil dan tujuan dari peristiwa tutur. Hal ini
dikarenakan partisipanlah yang dapat menentukan rencana dan keinginan, serta
d) Urutan Tindak (Act Sequence)
Urutan tindak menurut Hymes (1972:54-55) terdiri atas message form‘bentuk pesan’,
dan message content ‘isi pesan’. Bentuk pesan meliputi cara pemberitahuan suatu
topik. Sedangkan isi pesan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibicarakan, juga
perubahan topik pembicaraan. Dalam menyampaikan isi pesan, terdapat
pertimbangan pemilihan kata dan penggunaan bahasa sesuai dengan topik yang
sedang dibicarakan (isi pesan).
e) Kunci (Key)
Kunci menurut Hymes (1972:57) mengacu pada cara, nada atau semangat yang
muncul ketika suatu peristiwa tutur berlangsung. Tindak tutur dapat berbeda karena
key ‘kunci’, misalnya antara serius dan santai, hormat dan tak hormat, atau sederhana
dengan angkuh/sombong. Key ‘kunci’ dapat ditandai oleh isyarat (kedipan mata),
gerak tangan, gerak tubuh, gaya berpakaian, dan sebagainya.
f) Piranti (Instrumentalities)
Piranti menurut Hymes (1972:55-56) terdiri atas dua aspek yaitu channel ‘saluran’
dan forms of speech ‘bentuk tuturan’. Channel ‘saluran’ mengacu pada media
penyampaian tuturan. Form of speech ‘bentuk tuturan’ mengarah pada bahasa dan
dialek yang digunakan.
g) Norma (Norm)
Norma menurut Hymes (1972:60-61) mengacu pada norms of interaction ‘norma interaksi’ dan norms of interpretation ‘norma interpretasi’. Norms of interaction
merujuk pada semua kaidah yang mengatur tuturan, yaitu tingkah laku khas dan
Sedangkan norms of interpretation merujuk pada sistem kepercayaan dalam suatu
masyarakat.
h) Kategori (Genre)
Kategori mengacu pada kategori-kategori seperti puisi, mitos, dongeng, peribahasa,
do’a, orasi, perdagangan, surat edaran, editorial, dan sebagainya. Dengan demikian,