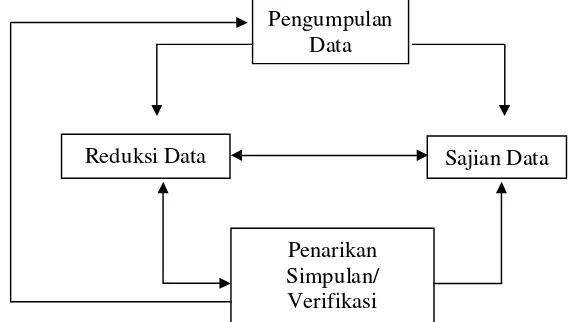commit to user
GOVERNANCE PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
(Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sukoharjo)
oleh :
TAUFIQ FAJAR NUGROHO D0105139
Skripsi
Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2.1.2 Definisi Pedagang Kaki Lima ... 20
2.1.3 Partisipasi Padagang Kaki Lima ... 26
2.1.4 Hukum, Konsistensi, dan Diskresi ... 37
2.1.5 Unsur-unsur yang Bisa Dianalisis dalam Governance... 40
2.2 Kerangka Pikir ... 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 45
3.1 Jenis Penelitian ... 45
3.2 Lokasi Penelitian ... 46
3.3 Sumber data ... 46
3.4 Teknik Pengambilan Sampel ... 47
3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 49
commit to user
ix
3.7 Teknik Analisis Data ... 52
BAB IV DESKRIPSI LOKASI ... 55
4.1 Paguyuban PKL Alun-Alun Sukoharjo (PPKLS)... 55
4.2 Struktur Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terkait Dengan PKL ... 57
4.3.1 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan …………...…………... 57
4.3.2 Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ... 59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 62
5.1 Hubungan antara Pemerintah dengan Kelompok PKL... 62
5.1.1 Penerapan Perda tentang PKL ... 63
5.1.2 Diskresi Kebijakan ………... 67
5.1.3 Penarikan Retribusi PKL ………. 74
5.1.4 Partisipasi PKL dalam Pengambilan Keputusan………. 77
5.1.5 Kepedulian Pemerintah Terhadap PKL ……….. 83
5.2 Hubungan antar Anggota dalam Paguyuban... 86
5.3 Hubungan antara Paguyuban PKL dengan Stakeholders Non-Government ... 92
5.3.1 Kepedulian Sektor Swasta ………... 92
commit to user ABSTRAK
TAUFIQ FAJAR NUGROHO, D0105139, GOVERNANCE PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO (KASUS PAGUYUPAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN SUKOHARJO), JURUSAN ILMU ADMINISTRASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2011.
Dalam upaya pemecahan masalah PKL, dimungkinkan governance yang dilakukan PKL mampu menjadi alternatif pemecahan masalah dikarenakan pemerintah sendiri tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, maka diperlukan penelitian yang menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan berlokasi di Alun-alun Sukoharjo. Sumber data yang diolah adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam (in-dept interview),observasi langsung, menggali dan menganalisa dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian termasuk dokumen pemerintah, LSM, data statistik. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi data dan untuk memperkuat validitasnya menggunakan intersubjektive trianggulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.
Dalam penelitian ini, governance Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup tiga bentuk interaksi yaitu: hubungan antara Pemerintah daerah dengan PKL, hubungan antara PKL dalam paguyuban, dan hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government. Penelitian ini menunjukkan bahwa didalam hubungan antara pemerintah daerah dengan PKL sudah terjalin komunikasi yang baik, masih adanya diskresi dalam penerapan aturan yang mengakomodasi kepentingan PKL, kurangnya transparansi dalam penarikan retribusi yang dilakukan oleh pemegang otoritas, dan partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan yang hanyalah sebagai window dressing. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hubungan antara PKL didalam paguyuban terdapat kerja sama diantara mereka, musyawarah rutin dalam penyelesaian konflik internal paguyuban, dan kegiatan sosial dalam pengadaan dana sosial bagi anggota yang terkena musibah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government yaitu adanya kepedulian sektor swasta menjadi sponsor pada event-event tertentu yang memberikan keuntungan finansial bagi PKL, kerja sama dengan masyarakat sekitar berupa kegiatan sosial seperti kerja bakti dan membangun tempat ibadah serta memanfaatkan tenaga keamanan informal (atau kadang ada yang menyebut preman / gali) untuk tujuan positif yakni kenyamanan pelayanan customer.
commit to user
xii ABSTRACT
TAUFIQ FAJAR NUGROHO, D0105139, GOVERNANCE OF STREET VENDORS IN SUKOHARJO DISTRICT (CASE STUDY OF STREET VENDORS ASSOCIATION IN SUKOHARJO SQUARE), DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE, SEBELAS MARET UNIVERSITY, SURAKARTA, 2011.
As an effort to solve problems associated with street vendors, probably governance carried by street vendors can be an alternative solution, because the government is not capable of addressing the issue.
To obtain the results of comprehensive research, it would require research that analyzes a problem from different angles. Therefore, this research used qualitative research approach and conducted in Sukoharjo square. The source of data used in this research was the primary data and secondary data. Purposive and snowball sampling were used in this research as sampling technique. The method used in this research was by in-depth interviews, direct observation, as well as explore and analyze documents which can be used as reference in the research, including documents from government, social community association, and statistical data. The data validity techniques used in this research was data triangulation techniques and this research used inter-subjective triangulation to strengthen the data validity. Meanwhile, the technique of analyzing data used in this research was an interactive model of data analysis techniques.
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Era reformasi yang diawali dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan banyaknya pengangguran. Di samping mereka yang sulit mencari pekerjaan, sampai kepada buruh atau karyawan yang terpaksa berhenti kerja karena mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan-perusahan banyak yang mengurangi tenaga kerjanya, karena produksi berkurang dan aktivitas perusahaan menurun.¹
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
berjualan untuk mendapatkan penghasilan. Dapat dikatakan sektor informal ini justru dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa.
Tetapi kadang-kadang keberadaan sektor informal ini juga diperlukan oleh sebagian masyarakat. Dengan alasan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan yang ditawarkan oleh sektor formal pada barang yang sama Fakta menunjukkan bahwa PKL juga memberikan peranan dalam menyerap lapangan pekerjaan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah karena PKL memberikan kontribusi finansial melalui retribusi yang dibayarkan pada pemerintah.
Dengan demikian ada dua sisi yang saling bertentangan, PKL dapat mendatangkan kontribusi positif maupun negatif. untuk mensikapi keberadaan sektor informal ini. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, karena pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakatnya.
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
Tidak hanya masalah PKL yang harus diselesaikan pemerintah Sekarang ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah yang begitu rumit. Persoalan-persoalan tak kunjung terselesaikan. Kemiskinan, penganguran, kesehatan maupun pendidikan menjadi fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Berbagai kebijakan telah dijalankan, begitu besar dana telah dikeluarkan, namun hasilnya negara masih dihadapkan permasalahan tak kunjung teratasi.
Namun dengan begitu kompleksnya masalah yang dihadapi, pemerintah tidak dapat mengatasinya sendiri. Bahkan para pemimpin yang dianggap begitu kuat (powerful) pun didunia yang mengadopsi teori dan praktek birokrasi rasional Weber yang sudah lazim di Negara Barat, yang dianggapnya mampu mencipakan kehidupan yang efisienpun, gagal untuk meredam persoalan dunia yang unpredictable (tidak dapat diprediksi) dan semakin sulit untuk diatasi. Teori tersebut bukanlah alat yang tepat dan bahkan tidak mampu mengatsasi masalah kompleks karena ia hanya tepat untuk kondisi lingkungan yang sangat stabil dan predictable (dapat diprediksi). Dunia sekarang ini yang semakin unpredictable dan tidak menentu (uncertain), kompleks, dinamik dan berubah dengan cepat, dan bahkan telah terjadi fragmentasi komunitas dunia dan institusi-institusi governance, maka jelas tidak bisa diatasi hanya dengan aplikasi birokrasi
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
(responsive) terhadap uncertainty (ketidakpastian) dan kompleksitas lingkungan dunia yang terjadi sekarang ini. Akibatnya kegagalan ini sudah bisa diduga, betapa tidak ada satupun institusi yang bersedia mengambil tanggung jawab atas carut marutnya kehidupan sekarang ini (Sudarmo,2008 : 101-102).
Dalam permasalahan PKL Pemerintah (state) sendiri seolah-olah kuwalahan dalam menghadapi masalah tersebut, sehingga terkesan mengabaikan ataupun kurang memperhatikannya, walaupun sebetulnya PKL juga berperan dalam perekonomian di perkotaan. Masalah penanganan PKL. sebenarnya bukan saja menjadi urusan Pemerintah, akan tetapi merupakan urusan semua komponen yang ada, seperti akademisi, pengusaha, LSM, organisasi sosial (LSM), parpol dan PKL itu sendiri. Keterlibatan semua komponen sebagaimana disebutkan di atas disebabkan masalah PKL merupakan permasalahan yang menyangkut tentang kehidupan masyarakat secara umum. Mereka yang terlibat dalam kegiatan PKL umumnya memiliki modal kecil dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga kehadiran PKL merupakan tanggung jawab semua pihak yang perlu ditangani dengan bijaksana.
tempat-commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
tempat usaha di sekitar pusat perbelanjaan (mall), jadi bukan dimonopoli oleh pihak pengusaha yang bersangkutan. LSM dan Organisasi sosial perlu memberikan penyuluhan dan pendidikan kewirausahaan serta kalau perlu mengusahakan bantuan pada PKL dalam berwiraswasta sehingga kesehatan masyarakat terutama para PKL yang dibimbing dan dibina.
Urusan PKL pada dasarnya merupakan persoalan internal masing-masing daerah dan bukan merupakan urusan pemerintah pusat; hanya ada 5 bidang urusan publik yang menjadi otoritas nasional yaitu; urusan hubungan luar negeri, pertahanan, kebijakan keuangan, agama, dan peradilan, selebihnya termasuk urusan PKL adalah persoalan otonomi daerah (Pratikno 2005 : 61). Terkait dengan penelitian ini maka governance PKL merupakan otoritas daerah beserta masyarakatnya.
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
gedung DPRD ke area alun-alun kota Kabupaten Sukoharjo. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini mempunyai nama PPKLS (Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sukoharjo. Kelompok ini memiliki anggota sekitar 68 anggota. Dalam kesehariannya, mereka menjalankan aktivitasnya pada jam 16.00 sampai dengan jam 11 malam. Namun ada sebagian kecil dari anggota kelompok tersebut yang masih berjualan sampai dini hari. Paguyuban ini cenderung tertib dengan aturan yang ada, membentuk suatu kekuatan serta norma-norma yang disepakati bersama sehingga lebih legitimate (kuat karena sah menurut undang-undang) dan memiliki wadah
serta kekuatan dalam menyampaikan suatu masukan kepada pemerintah maupun menolak terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan mereka. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi PKL maupun upaya dalam pengembangan usaha PKL, mereka tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya kolaborasi diantara stake holder. Hal ini dilakukan melalui jaringan atau network antar stakeholders. Yaitu dengan pemerintah maupun dengan masyarkat sekitar.
Dalam pemikiran inilah diperlukan adanya penelitian tentang Governance Pedagang Kaki Lima. Karena penelitian ini ingin menelusuri
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana governance
pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dirinci dalam sub-sub perumusan masalah sebagai berikut:
1) Hubungan antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah 2) Hubungan antar anggota dalam Paguyuban
3) Hubungan paguyuban PKL dengan stakeholders non-government.
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian tentang governance Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui sejauh mana hubungan antara PKL, pemerintah dan stakeholders non-government dalam pemecahan masalah-masalah
publik.
2. Mengetahui sikap yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap PKL khususnya di Alun-alun kota Kabupaten Sukoharjo.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:
commit to user
¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com
2. Memperkaya khasanah informasi akademik, khususnya yang berupa hasil permasalahan yang terjadi, demi mewujudkan alternatif pemecahan masalah yang timbul karena keberadaan PKL
3. Pada akhirnya penelitian ini tidak semata-mata diorientasikan pada kepentingan akademik, namun juga diorientasikan kepada kepentingan praktis bagi peningkatan hubungan antara PKL, pemerintah dan stakeholders terkait.
4. Diharapkan bisa memberikan peluang bagi penelitian yang lebih lanjut.
5. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
commit to user
10
BAB II KAJIAN TEORI
2.1. Pendahuluan
Pada suatu kesempatan, sering kita mendengar kata ”penataan”, ”pembinaan”
sebagaimana yang diucapkan atau dinyatakan oleh aparat pemerintah ketika mereka berurusan
dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun seiring dengan pernyataan-pernyataan tersebut
kita juga melihat realita bahwa penggusuran terhadap PKL dilakukan. Kita juga melihat di
sejumlah lokasi pemerintah mengharuskan PKL menggunakan tenda seragam/uniform agar
kelihatan bersih atau tertata rapi. Fenomena-fenomena dimana PKL diwajibkan mengikuti
peraturan atau instruksi pemerintah setempat, PKL menurut atau menentang, ada partisipasi
dalam pembuatan keputusan bersama atau hanya sekedar top-down approach dalam
memformulasikan alternatif pemecahan masalah terkait dengan keberadaan PKL, ada dialog
atau konflik yang mungkin terus berkepanjangan atau hanya beberapa saat saja, ada penarikan
retribusi atau tidak, ada penyelewengan keuangan hasil pengumpulan retribusi atau bersih dari
tindak penyelewengan, semua fenomena-fenomena ini pada dasarnya merupakan symptom
(tanda-tanda) bahwa di lokasi tersebut terdapat governance PKL. Tentu saja proses dan
tanda-tanda adanya governance PKL di suatu tempat berbeda dengan proses governance PKL
ditempat (daerah) lain.
Untuk memahami lebih rinci, bab ini mereview konsep governance dan sejumlah
dalam konsep-konsep tersebut adalah konsistensi implementasi aturan hukum termasuk
akuntabilitas, diskresi pelaksanaan keputusan hukum, isu konflik antara kelompok kuat dan
kelompok lemah maupun antara penduduk asli dan pendatang, dan isu keadilan. Keseluruhan
kajian teori yang dibahas dalam bab ini sengaja dikaitkan dengan isu pedagang kaki lima
(PKL).
2.1.1. Definisi Governance
Dalam pengertian yang paling umum Davis and Keating (dalam Sudarmo 2011: 72)
mendefiniskan governance sebagai the process by which institutions, both state and non-state
interact to manage a nation’s affairs” (suatu proses interaksi institusi-institusi mencakup
isntitusi-institusi negera dan institusi-institusi non-negara untuk mengelola persoalan bangsa).
Di antara banyaknya difinisi governance yang ada, yang paling tepat menurut sudut pandang
The United Nation Development Programme (UNDP) (dalam Abdellatif, 2003 : 4) :
Governance is “the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences.”
Stoker merinci konsep governance ke dalam lima proposisi. Pertama, governance
mengacu pada serangkaian institusi dan aktor yang berasal dari dalam pemerintah maupun di
luar pemerintah. Kedua, governance mengidentifikasikan kekaburan batas-batas dan tanggung
jawab untuk menangani isu-isu ekonomi dan sosial. Ketiga, governance mengidentifikasikan
ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam
commit to user
para aktor yang sifatnya self-governing (mengelola dirinya sendiri) secara otonom. Kelima,
governance mengakui kapasitas untuk mencapai sesuatu dengan tidak menggantungkan pada
kekuatan pemerintah untuk megkomando atau mengunakan otoritasnya; governance
memandang pemerintah mampu menggunakan alat-alat dan teknik-teknik baru untuk
mengendalikan atau membina. (Stoker, 1998 : 19)
Apa yang diungkapkan stoker, walaupun terdapat kategorisasi tentang makna
governance, adalah konsep governance dalam arti yang sangat luas dan seoalah-olah
merupakan tipe ideal governance karena dalam realita lapangan tidaklah selalu dan selamanya
dan tidak sepenuhnya konsepsi governance memenuhi ciri-ciri seperti yang diuraikannya.
Mungkin yang paling tepat adalah bahwa konsep governance yang dipaparkan adalah
kecenderungan kearah tipe-ideal tersebut (Sudarmo 2011 : 73). Dalam banyak hal, tidak
menutup kemungkinan proses governace sering ditunjukan dengan munculnya peran secara
dominan oleh pemerintah dan elit lain seperti elit bangsawan, ketua paguyuban dan bisnis
formal sedangkan stakeholder lemah cenderung kurang memiliki power untuk berkiprah dalam
pengambilan keputusan karena sikap dan tindakannya cenderung dikontrol oleh elit kuat
tersebut dan kadang menjadi korban akibat dominasi elit tersebut.
Dalam pengertian sempit, ‘governance’ biasanya mengacu pada “the capacity of the
government to make policy and put into effect” ( kapasitas pemerintah untuk membuat
kebijakan dan mengimplementasikannya) (Pierre and Peters, dalam Sudarmo 2011 : 73).
Pengertian ini merupakan pandangan tradisional yang melihat pemerintah sebagai stakeholder
utama yang dipandang paling memiliki otoritas untuk mebuat kebijakan/keputusan tanpa
seperti ini sampai sekarang masih terus berlangsung dan bahkan tetap hidup dalam kehidupan
bernegara yang kurang mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Tetapi di sebagian masayarakat
tertentu, proses formulasi kebjakan tidak lagi hanya di mainkan dan didominasi oleh Negara
atau pemerintah yang berkuasa saja (Denhardt and Denhardt dalam Sudarmo 20101 : 73); dan
bahkan ada kecenderungan diterimanya sebuah pemikiran bahwa governance mencakup
“participants from outside government recognized as stakeholders who have rights to be
involved should be engaged in deciding what should be done and possibly carrying it out.”
(partisipan dari luar pemerintah yang dikenal sebagai stakeholder, yaitu pihak-pihak yang
memiliki hak untuk harus dilibatkan dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan
termasuk kemungkinan untuk melaksanakan keputusan tersebut.) (Colebatch dalam Sudarmo
2011 : 73). Partisipasi bisa didefinisikan sebagai “broad forms of engagement by citizens in
policy formulation and decision making in key arenas which affect their lives.” (berbagai
bentuk keterlibatan warganegara dalam formulasi kebijakan dan pembuatan keputusan pada
wilayah-wilayah penting yang memperngaruhi hidup mereka) (Gaventa and Valderrama,
dalam sudarmo 2011 : 74). Ini berarti bahwa tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas dari
kelompok yang terkena kebijakan bisa saja melakukan negosiasi, dialog atau diskusi untuk
menemukan titik temu yang bisa disepakati bersama; namun demikian tidak menutup
kemungkinan partisipasi yang mereka ungkapkan bisa dalam bentuk yang lebih keras atau
kasar seperti protes-protes dengan kata-kata atau pernyataan sikap akibat ketidakpuasan atau
bahkan bentuk kekerasan fisik lainnya termasuk adu fisik dan atau pengrusakan sebagai bentuk
commit to user
kepentingannya. Namun dalam bentuk yang sangat parah, partisipasi tidak jarang diwujudkan
dengan perlawanan secara terbuka kepada pihak penguasa.
Definisi dari Davis walaupun terlalu luas tetapi memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi
para analis atau peneliti ketika akan menguraikan atau menanalisis konsepesi governance
seiring dengan kasus atau fenomena yang tengah ditangani pada situasi dan lokasi tertentu.
Boleh jadi sebuah konsep atau teori yang diadopsi dari hasil generaliasasi tidak sesuai ketika
diterapkan pada kasus tertentu walaupun masih dalam ranah konspensi governance karena
analisis tentang governance kadang sifatnya kasusistik dan spesifik serta unik. Dengan
demikian dalam kasus yang berbeda meskipun masih dalam domain governance, cakupan
analisis serta hal-hal apa saja yang yang terkait yang akan dianalisis tentu berbeda-beda. Oleh
karena itu, konsepsi governace dalam tulisan ini, disamping memanfaatkan sejumlah literatur
yang ada termasuk hasil-hasil penelitian di luar negeri dan berbagai pengalaman praktek
governance tingkat nasional sebagai dasar kajian dalam tulisan ini, juga tidak lepas dari
pengalaman-pengalaman penelitian penulis selama ini terkait dengan governance PKL di Solo
dan daerah lain di Solo Raya serta pengalaman pengabdian kepada masyarakat di sekitar Solo .
Dengan mengacu pada pengertian governance yang mencakup state dan non state, maka
konsepsi state dalam realitanya bisa mencakup pemerintah, dewan perwakilan rayat, polisi,
militer, kelompok kaum bangsawan yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan orang
banyak dan atau kelompok kepentingan lainnya yang berafiliasi ke pemerintah dan memiliki
otoritas untuk mengatur kelompok masyarakat lainnya; sedangkan non-state bisa mencakup
(1) kelompok bisnis (biasanya bisnis formal yang bisa mencakup pengusaha-pengusaha
kepentingan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung kebijakan pemerintah,
kelompok-kelompok kepentingan yang ingin memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah
(atau kekuatan yang berafiliasi ke pemerintah yang diberi otoritas oleh pemerintah atau pihak
yang berwenang), kelompok masyarakat yang terkena dampak kebijakan (Sudarmo 2011 : 75).
Namun demikian, stakeholder mana saja yang terlibat dalam struktur governance, tergantung
isu yang menjadi fokus kajian. Berbeda isu sangat mungkin berbeda stakeholder yang terlibat
atau harus dilibatkan; demikian pula bagaimana proses governance itu berlangsung tergantung
pada seberapa besar kekuatan partisipasi masing-masing stakeholder dalam proses pembuatan
keputusan karena sangat dimungkinkan stakeholder kuat dan dominan akan menjadi kekuatan
besar dalam pengambilan keputusan sedangkan stakeholder yang lemah hanya akan mengikuti
apa keputusan dari stakeholder dominan.
Betapapun partisipasi sering dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi di
sejumlah mayarakat tertentu, implementasi kebijakan kadang atau bahkan sering berada di
bawah personal rule untuk mencapai tujuan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
penguasa.. Pengertian “personal rule” sering digunakan secara bergantian dengan konsep
“neopatrimonialism.” (Acemoglu dalam Sudarmo 2011 : 75)
According to Jackson and Rosberg:
commit to user
Sistem tersebut disusun bukan melalui institusi tetapi oleh para politisi itu sendiri) (Jackson and Rosberg dalam Sudarmo 2011 : 75).
Personal rules dekat dengan praktek korupsi yang dilakukan secara berjamaah,
terselubung melalui undang-undang formal yang dimanipulasi untuk kepentingan dirinya dan
kelompoknya, sistematis melalui jaringan yang disusun rapi yang memungkinkan
dilibatkannya orang-orang kunci yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam pengambilan
keputusan di lingkungan birokrasi pemerintah. Jaringan yang dibangun sering sedemikian luas
dan mengakar sehingga sulit dan memerlukan waktu lama untuk diberantas. Bahkan dalam
jaringan tersebut, tidak jarang para penegak hukum dan keamaanan termasuk jaksa, hakim,
polisi, tentara, dan para pejabat pelayan publik serta penyelengara Negara termasuk menteri,
birokrat, wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif, ikut terlibat didalamnya sehingga pihak
pengusut kewalahan dan tidak jarang mengalami kendala yang sangat signifikan. Terlebih jika
jaringan tersebut menyangkut kepentingan presiden.
Indonesia masih merepresentasikan masyarakat politik yang merepresentasikan ciri-ciri
patrimonial yang memenuhi definisi sistem personal rule. (Webber dalam Sudarmo 2011 : 76).
Crouch memperlihatkan bahwa selama masa masa “Demokrasi Terpimpin” di era Sukarno dan
“Orde Baru” di era Suharto banyak ciri-ciri sistem politik pasca era-era tersebut justru kembali
pada politik patrimonial sebagaimana pada masa kekaisaran jawa pra kolonial. (Crouch dalam
Sudarmo 2011 : 76)
Menurut Crouch, terdapat sejumlah alasan mengapa neopatrimonialism masih tetap
bercokol: “(a) kekuasaan penguasa tergantung pada kapasitas diri penguasa tersebut untuk
tertentu; (b) para penguasa mengusahakan kemenangannya melalui aliansi secara sukarela
dengan cara memuaskan aspirasi-aspirasi para pendukungnya yang memiliki kepentingan
material melalui barter/pertukaran dimana para pendukungnya menerima suap dan
kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dinikmati sedangkan penguasa menerima penghormatan
dan loyalitas dari para pendukungnya, terutama dilakukan ketika penguasa tersebut sudah tidak
memiliki lagi kapasitas yang memadai untuk memaksakan aturan yang ingin diterapkan; (c)
pemerintah mampu mengatur sesuai dengan kepentingan-kepentingan para elit tanpa terlalu
banyak memperhitungkan kepentingan publik karena publik dipandang terbelakang secara
sosial dan secara politik pasif, dan tetap dalam pengawasan kekuatan regim militer.” (Crouch
dalam Sudarmo 2011 : 76)
Apa yang dikemukakan oleh Crouch masih relevan dengan kondisi di Indonesia, bukan
hanya pada era orde lama maupun orde baru, tetapi juga pada era reformasi yang notabene
mengagung-agungkan praktek demokrasi dan meniadakan praktek neopatriomonialisme,
meskipun sistem pemilihan langsung kepala daerah telah dimulai. Pada era reformasi justru
pasangan calon bupati/walikota dan wakilnya tidak jarang terlibat praktek aliansi dengan para
pendukungnya yang memberikan suaranya secara sukarela dan loyalis dengan cara
memberikan materi atau uang melalui sebuah tim yang dibayarnya untuk memfasilitasi
kesuksesan pasangan calon tersebut. Bahkan ketika mereka berhasil menuju kesuksesan, tidak
jarang mereka menggunakan kebijakan melalui kekuatan pemaksa yang didasari oleh kekuatan
hukum yang dibuatnya tanpa partisipasi kelompok yang menjadi sasaran dari penegakan
commit to user
aktivitas ekonomi informal, misalnya, tidak jarang dikenai aturan formal tertentu demi menjaga
situasi kota terlihat bersih dan teratur. Dengan demikian, betapapun mereka itu dibutuhkan
untuk memenangkan pasangan calonan bupati/walikota dengan janji atau imbalan tertentu pada
masa kampanye pemilihan, maka ketika pasangan tersebut berkuasa, mereka akan segera
melakukan tindakan tegas ketika para PKL yang dulunya pernah mendukung pencalonannya
karena dipandang bertentangan dengan kebijakan pasangan bupati/walikota dan wakilnya saat
ini yang memenangkan pemilihan tersebut. Bahkan, penguasa ini tidak segan-segan
mengerahkan dukungan pasukan satuan polisi pamong praja setempat untuk mengamankan
kebijakan yang diimplementasikannya dengan menggusur PKL tersebut (Sudarmo 2011 : 77).
Crouch menandaskan bahwa walaupun Indonesia mengalami perubahan sosial, ekonomi
dan politik yang begitu luas terutama setelah Negara ini memperoleh kemerdekaannnya,
Indonesia masih memperlihatkan patrimonial governance. Ia lebih jauh menyatakan bahwa
ciri-ciri patrimonial masih tetap bercokol, namun demikian ciri-ciri sekarang yang terlihat
sangat berbeda dari aslinya yang pernah muncul pada waktu lalu. Ini untuk menggarisbawahi
bahwa walaupun Indonesia telah mengalami era reformasi yang mencerminkan pergeseran
sistem politik dari otoriter ke demokrasi, tidak ada jaminan bahwa patrimonialisme dengan
sendirinya dibersihkan dan bahkan ciri-ciri patrimolialisme masih terus berlangsung meskipun
dengan bentuk yang lain dan variatif namun tetap saja memenuhi ciri-ciri patrimonialisme.
Patrimonialisme di era reformasi bisa terjadi di setiap wilayah administrasi di negeri ini, terlebih
di era otonomi daerah. Patrimonial governance bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda
namun masih memenuhi karakteristik dari patrimonilaisme itu sendiri, dan dimungkinkan
Menurut Bratton dan van der Walle, “the right to rule in a neopatrimonial regime is
ascribed to a person rather than to an office, despite the official existence of a written
constitution.” (hak untuk memerintah rejim patrimonial lebih mendasarkan pada pribadi
orangnya ketimbang aturan yang ada di kantornya, meskipun terdapat terdapat konstitusi
tertulis yang harus menjadi rujukannya) (Bratton and Walle dalam Sudarmo 2011 : 78). Untuk
mengamankan loyalitas patrimonial, pihak penguasa (yang memiliki otoritas atau pembuat
kebijakan, memberikan “the distribution of opportunities for personal profits.” (distribusi
kesempatan bagi keuntungan-keuntungan pribadi) (Crouch dalam Sudarmo 2011 : 78).
Keuntungan ini bisa berupa materi, financial maupun posisi-posisi tertentu yang bisa
memberikan kemanfaatan bagi pribadi yang menerimanya dari pihak yang memiliki otoritas
atau pembuat kebijakan atau bahkan oknum tertentu yang seolah-olah memiliki otoritas.
Keberhasilan penguasa/pihak yang memiliki otoritas dalam mengimplementasikan
kebijakannya, sebagian tergantung pada kemampuan menggunakan startegi memecah belah.
(Acemoglu dalam Sudarmo 2011 : 78). Strategi memecah belah ini merupakan metode yang
digunakan oleh pembuat kebijakan atau penguasa untuk memepertahankan kekuasaannya
melawan tantangan-tantangan, (Acemoglu dalam Sudarmo 2011 : 78) yang bisa dilakukan
dengan memberikan insentif tertentu secara selektif dan hukuman dan mengeksploitasi
kerapuhan kerjasama sosial dan ketika mereka menghadapi ancaman maka para penguasa atau
pembuat kebijakan atau yang memiliki otoritas tersebut mengentinsifkan tindakan kolektif
terhadap masalah dan menghancurkan koalisi yang menentang dirinya dengan memberikan
commit to user
Sudarmo 2011 : 78). Strategi seperti ini sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia yang
dilakukan oleh pihak penguasa. Dalam konteks PKL, maka strategi pecah belah bisa saja
terjadi atau dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan atau yang memiliki otoritas misalnya
dengan mengakomodasi kepentingan PKL yang memiliki hubungan dekat dengannya dan
sebaliknya tidak mengakomodasi kepentingan mereka yang bukan warga setempat atau kurang
memliki kedekatan hubungan secara personal kepada pihak penguasa atau pembuat kebijakan.
2.1.2. Definisi Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima merupakan salah satu tipe sektor informal. Sektor informal
mengacu pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang berlangsung diluar norma-norma formal
urusan ekonomi yang diakui oleh Negara dan bisnis. Sektor informal mencakup bisnis kecil
yang menyebabkan individu atau keluarga mempekerjakan dirinya atau memberikan
kesempatan kerja bagi mereka. Sektor informal mencakup “the production and exchange of
legal goods and services” (produksi dan pertukaran barang-barang dan pelayanan yang sah
secara hukum) yang juga ditandai oleh “the lack of appropriate business permits, violation of
zoning codes, failure to report tax liability, non-compliance with labour regulations governing
contracts and work conditions, and/or the lack of legal guarantees in relations with suppliers
and clients.” (tidak adanya ijin bisnis yang secara persis menjelaskan dengan tepat, tidak
mengikuti zona yang diperbolehkan sehingga dianggap merusak tatanan areal yang
diperbolehkan, tidak memiliki laporan pertanggungjawaban pembayaran pajak, tidak
adanya jaminan hukum antara pensuplai dan kliennya atau pelanggannya) (Cross dalam
Sudarmo 2011 : 78). Justru karena cirinya yang yang begitu luas, maka secara konseptual,
metodoligis dan teoritis, sulit mendefiniskan secara persis sifat, cakupan, dan signifikansinya.
Kondisi ini mengakibatkan munculnya kritik terhadap konsep sektor informal karena tidak
adanya kejelasan definisi ini. Namun begitu, sektor informal bisa diidentifikasi ciri-cirinya dan
bentuk-bentuknya yang banyak terjadi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan
tersebar di berbagai daerah di negeri ini. Beberapa bentuk sektor informal yang biasa ditemui
sehari-hari misalnya perdagangan kaki lima (PKL), pijat, industri rumah tangga, dan
perdagangan asongan, dan masih banyak lagi ragamnya.
Seperti halnya sektor informal, definisi pedagang kaki lima juga tidak memiliki definisi
tunggal yang bisa diterima oleh semua pihak mengingat sektor ini memiliki ragam yang
heterogen, dan sejumlah referensi juga mendefinisikan konsep ini dengan menyamakan seperti
halnya definisi sektor informal padahal lingkup sektor iniformal jauh lebih luas dari pada
lingkup pedagang kaki lima (Nurhanafiansyah, dalam Sudarmo 2011 : 80). Walaupun kadang
terdapat overlapping antara definisi sektor informal dan definisi pedagang kaki lima, batasan
pedagang kaki lima memerlukan definisi yang lebih sepesifik. Edi Suharto mendefiniskan
pedagang kaki lima sebagai berikut:
commit to user
retribusi harian kepada pemerintah setempat untuk kepentingan kebersihan dan keamanan; (6) Bisnis mereka biasanya melibatkan anggota keluarga dalam hal kepemilikan dan sistem manajemen; (7) Perusahaan mereka kecil dan pada umumnya pemilik sekaligus merangkap sebagai pekerjanya atau mempekerjakan kurang dari lima orang buruh atau anggota keluarganya; (8). Kepegawaiannya dalam hal perolehan kemanfaatan tidak dilindungi oleh pemerintah misalnya seperti pelayanan sosial dan pensiun; maupun oleh serikat buruh misalnya dalam hal asuransi atau gaji tetap; (9). Tempat mangkal atau lapak mereka pada umumnya ditandai dengan infrastruktur dan teknologi yang sederhana dan modal ekonomi dan sumberdaya yang terbatas (Suharto dalam Sudarmo 2011 : 80-81).
Walaupun definisi ini nampak komprehensif namun definisi ini masih belum
mencakup kemungkinan adanya pengusaha informal dengan capital yang besar namun
menjalankan akitivitas ekonominya layaknya pedagang kaki lima, sehingga ketentuan bahwa
pelaku ekonomi informal harus memiliki modal kecil adalah kurang tepat karena pengalaman
lapangan saya selaku peneliti yang banyak berkecimpung menyoroti penataan PKL
memperlihatkan bahwa sebagian dari PKL justru memiliki modal dengan skala menengah dan
besar. Pada umumnya PKL juga tidak membedakan apakah mereka yang berdagang memiliki
modal besar atau kecil tetapi sepanjang mereka berjualan di tempat-tempat publik secara
informal mereka kategorikan sebagai pedagang kaki lima. Ada sejumlah pihak mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan modal kecil adalah kurang dari Rp 10 juta rupiah, sedangkan
skala menengah antara Rp 10-25 juta rupiah, dan mereka yang bermodal lebih dari Rp 25 juta
dipandang sebagai PKL besar. Namun dilapangan, PKL juga mengakui ada sejumlah rekannya
dengan modal lebih dari seratus juta rupiah namun mereka oleh rekannya dipandang sebagai
PKL juga (Sudarmo 2011 : 81). Informasi ini mengarisbawahi bahwa PKL adalah orang yang
menjalankan aktivitas bisnis yang menawarkan barang atau pelayanan ekonomi secara
informal di ruang-ruang publik yang menggunakan peralatan, infrastrukur ataupun teknologi
menjalankan bisnisnya PKL bisa menggunakan tikar tanpa atap atau dengan atap sederhana,
tenda bongkar pasang, kios semi permanent seperti gerobak dorong, atau bahkan kios
permanent.
Keberadaan PKL sering dikritik oleh para perencana Kota atau daerah dan otoritas
pemerintah yang menyalahkan sektor informal ini sebagai anomaly. PKL dituduh sebagai
sumber ketidakteraturan, dan hambatan bagi pembangunan ekonomi modern (Nwaka dalam
Sudarmo 2011 : 82). Bahkan kekumuhan, resiko kesehatan, ketidakamanan dan eksploitasi
sering dituduhkan kepada PKL sebagai sumber penyebabnya. Juga dituduh bahwa PKL
sering dituduh sebagai sumber masalah sosial baru seperti kemacetan arus lalu lintas,
pemukiman liar, kekumuhan lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan,
kebersihan dan kerapihan. Perdagangan informal PKL juga dituduh sebagi aktivitas ekonomi
yang tidak mampu memberikan pendapatan yang memadai bagi pemerintah untuk memenuhi
semua biaya yang dikeluarkan pemerintah sehingga mengurangi kemampuan pemerintah
untuk menyediakan pelayanan publik yang memuaskan (Franks, dalam Sudarmo 2011 : 82).
Lebih parah lagi PKL dituduh tidak menghargai hukum formal, melanggar aturan, tidak
memenuhi standar kualitas, aturan sosial dan kesehatan, serta tidak membayar pajak sesuai
ketentuan sehinga mereka melanggar aturan main yang adil dalam berkompetisi (Sudarmo
2011 : 82).
Namun di kalangan PKL sendiri mereka merasa bahwa sektor informal yang mereka
tekuni memberikan kontribusi yang tidak kecil secara financial dan bahkan signifikan secara
commit to user
sektor formal lainnya tidak mampu menyerap tenaga kerja. Kedua, PKL mengklaim bahwa
mereka telah memberikan kesempatan kerja bagi orang lain yang kehidupannya jauh tidak
beruntung dibanding dirinya. Pada umumnya mereka mengklaim bahwa sebagian mereka
yang sudah cukup berkembang usahanya mempekerjakan orang-orang lain selain pemiliknya
(suami-istri) sejumlah antara 2 sampai 3 orang. Ketiga mereka menyatakan bahwa PKL telah
memberikan kontribusi secara financial bagi pemerintah setempat karena mereka membayar
retribusi harian, disamping uang kebersihan dan keamanan lingkungan yang masing-masing
daerah besarannya berbeda-beda, namun paling tidak mereka memberikan kontribusi kepada
pemerintah setempat tidak kurang dari Rp 30.000 per bulan dengan asumsi mereka menggelar
dagangannya setiap hari dan pegawai pemungut menyambanginya secara rutin. Keempat,
mereka mengkalim bahwa mereka secara ekonomi telah memberikan pelayanan kepada publik
semua lapisan dengan menyediakan berbagai barang atau pelayanan dengan harga yang amat
terjangkau bukan hanya kaum ekonomi atas tetapi juga kaum ekonomi bawah yang secara
financial, dan bahkan PKL secara tidak langsung telah memberikan subsidi kepada pelanggan
dengan ekonomi kuat melalui penawaran harga yang murah yang disediakan PKL. Kelima,
PKL juga secara tidak langsung telah ikut menjaga keamanan lingkunagn sosial secara umum
karena keberadaannya bisa ikut membantu mengawasi lokasi-lokasi tertentu yang dipandang
rawan dari tindakan kriminalitas. Klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan tersebut tidak perlu
disangkal lagi karena fakta lapangan di berbagai tempat telah membuktikannya.
Penilaian yang saling berlawanan satu sama lain terhadap PKL terutama konflik antara
sisi positif dan sisi negatif dari PKL ini telah menimbulkan dilema bagi para perencana dan
sektor informal ini. Pertama, jika PKL ini berhasil karena sifat informalitasnya dan arena
hukum ditegakkan atau dipaksakan secara lunak, lalu muncul keraguan apakah masuk akal
untuk memformalisasikan dan mengintegrasikan sektor informal ini kedalam ekonomi formal
dengan hukum dan aturan , kode dan standar tertentu yang dapat mengangu aktivitas dan
pertumbuhan PKL tersebut (Nwaka dalam Sudarmo 2011 : 83). Namun, jika sektor ini
dikontrol secara ketat melalui hukum formal maka timbul keraguan apakah kesinambungan
hidup kelompok yang termarjinalkan dan rentan terhadap kehancuran ini bisa diselamatkan.
Lebih dari itu, walaupun sektor informal ini termasuk PKL telah berkembang jauh lebih pesat
dari pada sektor industri formal di banyak Negara-negara kurang maju termasuk berbagai
daerah di Indonesia telah memunculkan pertanyaan penting yakni apakah penerapan
norma-norma pengaturan formal secara ketat terhadap sektor informal ini tidak akan beresiko
mengurangi kesempatan hidup bagi PKL (Cross dalam Sudarmo 2011 : 83).
Memang debat antara pro dan kontra terhadap keberadaan dan aktivitas bisnis PKL
tidak berkesudahan. Sebagian menganggap bahwa PKL memiliki sejumlah kontribusi positif
karena bisa mengatasi masalah pembangunan seperti penyediaan lapangan kerja dan
pendapatan; namun senbagian lain memandang dari sisi negatif yang bisa ditimbulkan dari
aktivitas PKL seperti ganguan lalu lintas, kebersihan kota, ketertiban dan kerapihan. Karena
dua pandangan yang berkonflik inilah maka kompromi yang sangat mungkin untuk dilakukan
agar aspek positif tidak terbuang dan aspek negatif bisa diminimalisir seoptimal mungkin,
maka perlunya melibatkan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan terutama terkait
commit to user
dalam governance PKL, partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang
penting untuk dilakukan atau dikembangkan bersama stakeholder lainnya yang kemungkinan
terkena dampak oleh aktivitas PKL atau justru bisa mengakibatkan dampak tertentu bagi
kehidupan PKL.
2.1.3. Partisipasi Pedagang Kaki Lima
Partisipasi merupakan elemen penting dalam governance. Hal ini karena
dimungkinkan warganegara atau masyarakat termasuk di dalamnya PKL bisa dilibatkan dalam
formulasi maupun implementasi kebijakan. Partisipasi bisa diartikan sebagai pengambilan
bagian atau keterlibatan dan bisa memiliki banyak makna yang berbeda. Publikasi oleh
Nasikun berjudul “Partisipasi Penduduk Miskin Dalam Pembangunan Pedesaan: Suatu
Tinjiauan Kritis” yang didasarkan pada karya Ralph M Kramer berjudul “Participation of the
Poor: Comparative Community Case Studies in the War on Poverty” mendefinisikan
partisipasi ke dalam tiga kategori (dalam Sudarmo 2011 : 84). Kategori pertama, adalah bahwa
“partisipasi memerlukan keterlibatan warga Negara miskin dalam proses pembuatan keputusan
yang diwakili oleh wakil-wakil mereka dalm koalisi bersama institusi-institusi pemerintah dan
organisasi-organisasi non pemerintah, serta pemimpin-pemimpin lain dari kelompok-kelompok
kepentingan”. Kategori kedua, adalah bahwa “partisipasi berarti warga negera miskin
ditempatkan sebagai pelanggan utama dari program pembangunan dan oleh karena itu
kepentingan mereka dan pendapat-pendapatnya harus didengar dan dipertimbangkan oleh para
pembuat kebijakan.” Kategori ketiga adalah apa yang disebut sebagai ‘radical participation’,
yang secara politik mereka ini “powerless” dan oleh karenanya mereka memerlukan stimulasi
dan dukungan.” Menurut Nasikun justru keadaan mereka yang “powerless” inilah yang
merupakan faktor penyebab mereka tetap miskin; dan hanya dengan memobilisasi mereka dan
memobilisasi organisasinya mereka sebagai kelompok penekan, mereka akan dapat
berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan yang kelak akan berpengaruh bagi kehidupan
mereka. Dalam pengertian ini, bisa dimaknai bahwa partisipasi kaum miskin karena
ketidakberdayaannya bisa digerakkan melalui mobilisasi oleh kekuatan tertentu misalnya oleh
lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional ataupun internasional atau kelompok-kelompok
tertentu yang peduli terhadap kaum lemah dan miskin atau oleh kekutan tertentu yang anti
kemapanan/ status quo penguasa. Ini berarti, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa
mobilisasi bukanlah partisipasi, namun dalam konteks dimana masyarakat yang dimobilisasi
adalah masyarakat miskin yang secara politik powerless, bisa dikategorikan dalam pengertian
partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipatif merupakan elemen penting dalam praktek
governance karena dengan cara ini kaum lemah diberdayakan secara politik dalam
pengambilan keputusan bersama stakeholder lainya termasuk pemerintah dan non-pemerintah
lainnya, terutama keputusan-keputusan yang kemungkinan berdampak besar bagi
kehidupannya. Betapapun begitu, dalam prakteknya partisipasi sering digunakan sebagai
“window dressing”, yakni sekedar sebagai hiasan untuk memperindah suasana bagi para
pembuat kebijakan atau kelompok yang kuat yang sudah memiliki sejumlah agenda-agenda
yang akan digulirkan untuk diterima semua pihak termasuk kaum lemah. Dengan partisipasi
commit to user
bentuk partisipasi nyata yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau hanyalah untuk mencari
popularitas pihak penguasa agar dinilai berhasil dalam berdemokrasi, namun sesunguhnya
semua itu hanyalah semu dan rekayasa yang sama sekali tidak pernah mengakomodasi
kepentingan-kepentingan kaum lemah yang harus dipertimbangkan dan menuntut
keberpihakan dan kepedulian kaum yang kuat.
Nagel mendefinisikan partisipasi secara lebih umum sebagai “actions through which
ordinary members of a political system influence or attempt to influence outcomes.”
(tindakan-tindakan yang dilakukan para anggota sebuah system politik mempengaruhi atau berusaha
mempengaruhi hasil dari suatu tindakan” ‘Actions’ mengandung pengertian gerakan, tenaga
dan usaha atau aktivitas yang ditujukan untuk menncapai suatu hasil. ‘Ordinary members’ dari
sebuah sistem politik merupakan orang-orang non-elite yaitu siapa saja kecuali mereka yang
menjalankan aktivitas sebagai kepala dalam pekerjaannya. ‘Influence’ mengandung pengertian
bahwa para partisipan mencapai apa yang mereka tuntut untuk didapatnya karena mereka
mendambakan untuk memperolehnya. Sebuah ‘political system’ didefinisikan secara luas
sebagai struktur kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang terorganisir; dan “outcome” secara
umum merupakan berbagai peristiwa yang dipengaruhi oleh para partisipan (Nagel dalam
Sudarmo 2011 : 86). Menurut Nagel, partisipasi mencakup keterlibatan psikology dan
keterlibatan dalam melakukan tindakan. Ia juga mencatat bahwa walaupun mungkin terdapat
keterlibatan dalam sebuah aktivitas, tidak berarti bahwa aktivitas tersebut disebut partisipasi
ketika aktivitas tersebut tidak berdasarkan preferensi dari orang yang melakukan aktivitas
disebut partisipasi ketika ektivitas tersebut dimobilisasi dari pihak luar, bukan dari dirinya
sendiri.
Definisi yang digunakan Nagel tidak secara khusus diarahkan pada keberadaan
orang-orang yang “powerless” sebagaimana dididiskusikan dalam karya Nasikun, yang menyatakan
bahwa mereka pada dasarnya memerlukan membutuhkan dukungan dari pihak lain atau
orang-orang lain sehingga mereka akan bertindak dengan cara tertentu. Dalaam definisi Nasikun,
mobilisasi dan pemberian dukungan dari pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat atau
kekuatan lainnya kepada kelompok yang orang-orang “powerless” ini yang ditujukan untuk
membuat agar mereka sadar akan kepentingannya dan mendorong mereka untuk berperan serta
atau terlibat dan memberikan suara berdasarkan kepentingannya dalam proses pembuatan
keputusan, bisa disebut sebagai partisipasi (Nasikun dalam Sudarmo 2011 : 86).
Karena partisipasi menyangkut segala bentuk keterlibatan apapun bentuknya,
sebagaimana didiskusikan sebelumnya, maka apa yang akan didefiniskan sebagai partisipasi
PKL dalam tulisan ini bisa dalam bentuk tindakan dialog, musyawarah untuk mufakat,
mengemukakan pernyataan sikap, protes, demonstrasi, gerakan-gerakan, dan bentuk-bentuk
tindakan lainya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik yakni keputusan yang
didominasi oleh pihak pemerintah dan atau elit/stakeholder yang powerful lainnya yang
mempengaruhi kehidupan para PKL (Sudarmo 2011 : 86).
Partisipasi warganegara dalam proses kebijakan dalam governance kemungkinan besar
bisa menghadapi sejumlah hambatan: (1) kontrol hubungan kekuasaan oleh negara, (2)
commit to user
Valderrama dalam Sudarmo 2009 : 113). Disamping lima hal tersebut, hambatan lain berupa
(1) kooptasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lokal yang
tidak netral dan merupakan kepanjangan tangan elit penguasa, menjadikan partisipasi tidak
berjalan sebagaimana seharusnya, sehingga dialog yang dilakukan adalah sebatas rekayasa dan
penentuan keputusan terakhir tetap ada pada pihak yang dominan; dan (2) tekanan yang
dilakukan oleh anggota dominan yang berafiliasi kepada kepentingan pemerintah karena
mereka telah diberikan sesuatu berupa materi maupun jasa lainnya sebagai bentuk imbalan atas
dukungan atau loyalitas kepada penguasa tersebut.
Gaventa menjelaskan bahwa walaupun partisipasi merupakan kekuasaan dan
pelaksanaan kekuasaan dan oleh berbagai aktor sosial pada ruang-ruang yang diciptakan untuk
interaksi anatara warganegara dan otoritas lokal, para aktor, agenda dan prosedur, biasanya
tetap ada di tangan institusi pemerintah dan bisa menjadi hambatan bagi keterlibatan
warganegara untuk ikut berpartisipasi secara efektif . Penelitian Sudarmo memperlihatkan
betapa partisipasi PKL dalam musyawarah rencana pembangunan kota di Solo tidak mampu
mensukseskan agenda mereka untuk diakomodasi oleh pemerintah karena pemerintah sendiri
telah memiliki agenda tersendiri sedangkan agenda PKL tidak sejalan atau tidak termasuk yang
diagendakan pemerintah setempat.
Studi oleh Schonwalder (dalam Sudarmo 2011 : 87), yang meneliti tingkat
desentralisasi terhadap penyediaan ruang bagi partisipasi demokratik di Amerika Latin
menyatakan bahwa perhatian yang pada persoalan kekuasaan malah tidak memadai. Ia
memperlihatkan bahwa elit lokal, pemerintah lokal dan para aktor lain yang beroperasi di
lokal cenderung sering melakukan gerakan-gerakan popular yang sudah menjadi agenda
mereka.”
Studi di Tanzania oleh Mukandela (dalam Sudarmo 2011 : 87-88) menemukan bahwa
keputusan-keputusan terhadap siapa yang harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan
pada lembaga-lembaga tingkat lokal yang paling bawah yang telah disetujui permintaannya
sebelum diteruskan ke pemerintah tingkat atas, menghalangi efektivitas dalam pencapaian
tingkat partispasi masyarakat secara luas dalam pembuatan keputusan. Ia menggarisbawahi
bahwa walaupun norma-norma/aturan-aturan menegaskan bahwa mayoritas jabatan-jabatan
adalah bagi para perwakilan komunitas, namun dalam tataran praktis, keputusan-keputusan
siapa yang diundang oleh para pejabat pemerintah tingkat atas di beberapa pemerintah daerah
adalah orang-orang yang berpengaruh ketika keputusan penting dibuat.”
Kontrol oleh pemerintah terhadap keputusan-keputusan tentang sifat dan saluran
struktur partisipasi di tingkat lokal juga menghalangi badan-badan pembuatan keputusan dalam
urusan-urusan publik di tingkat lokal. Studi oleh Muzitwa dan kawan-kawan di Zimbabwe
memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan tertentu dari struktur tradisional pembuatan
keputusan diambil alih dan ditentukan oleh komite-komite pembangunan desa dan
pembangunan wilayah, konflik antara para pemimpin tradisional dan para pemimpin yang
terpilih secara demokratis muncul (Gaventa and Valderrama dalam Sudarmo 2011 : 88).
Dari studi yang dilakukan Robin di Bolivia, Gaventa dan Valderrama menyimpulkan
bahwa pemerintah kabupaten/kota dengan tradisi perserikatan (berorganisasi) yang kuat,
commit to user
berorganisasi mereka pada umumnya memiliki kapasitas partisipasi politik yanag rendah.
Mereka juga menyimpulkan dari studi Herzer dan Pirez di Argentina, Peru dan negara Amerika
Latin lainnya, bahwa “keberadaan organisasi-organisasi yang dikenal dikalangan publik
dengan semangat tertentu di tingkat lokal dan jabatan-jabatan politik di pemerintahan
daerah/kota oleh partai-partai atau individu-individu yang menguntungkan partispasi publik
nampaknya menjadi kondisi penting bagi warganegara untuk bisa mempengaruhi
keputusan-keputusan di tingkat lokal (Gaventa and Valderrama dalam Sudarmo 2011 : 88).”
Partisipasi warga negara juga dipengaruhi oleh ketrampilan berpartisipasi dari
pemegang otoritas lokal dalam proses perencanaan. Studi yang dilakukan oleh Mukandala di
Tanzania, sebagai contoh, menemukan pentingnya para pejabat yang terdidik dalam
menjelaskan kebutuhan orang-orang (masyarakat) lokal. Ia menyimpulakan bahwa ketika para
anggota legislatif yang populis kurang berpendidikan mereka kesulitan untuk mendorong
melalui isu-isu tertentu dari akar rumput dan memiliki kesulitan menghadapi
presentasi-presentasi teknis yang dilakukan oleh staf-staf departemen teknis. Studi lain yang dilakukan
oleh Manor dan Crook juga menemukan pentingnya keahlian/keterampilan dan pengalaman
perencanaan dari para pemegang ototritas di daerah sebagai faktor penting bagi terselengaranya
partisipasi. Mereka berpendapat bahwa ketika keahlian dan pengalaman perencanaan yang
esensial itu tidak dimiliki maka keadaan seperti itu menjadi hambatan bagi partisipasi yang
berarti bagi kelompok-kelompok yang tak diuntungkan (Gaventa and Valderrama dalam
Sudarmo 2011 : 88-89). Ini untuk menggarisbawahi bahwa kaum marginal termasuk PKL
kemungkinan tidak akan bisa berpartisipasi ketika para perencana daerah sendiri tidak memiliki
Hambatan lain bagi terselengaranya partisipasi warganegara adalah kemauan politik.
Gaventa dan Valderrama menggarisbawahi pentingnya kemauan politik maupun kesempatan
bagi orang-orang lokal untuk berpartispasi. Keduanya berpendapat bahwa hambatan untuk
memperkuat partisipasi mencakup tidak adanya otoritas pemerintah pusat yang kuat dan
memberikan jaminan dalam menyediakan dan membuka secara paksa kesempatan bagi
terselengaranya partisipasi di tingkat lokal dan tidak adanya kemauan politik oleh para pejabat
pemerintah lokal (daerah) untuk menyusun perundangan yang diciptakan untuk tujuan tersebut
(terselengaranya partisipasi) (Gaventa and Valderrama dalam Sudarmo 2011 : 89).”
Pemerintah Pusat di Indonesia secara formal telah memberikan kesempatan kepada pemerintah
daerah bagi terselengaranya partisipasi seperti pemilihan kepala daerah langsung sejak 2004,
namun belum ada jaminan bahwa setiap kebijakan yang kelak akan mempengaruhi kehidupan
kaum atau kelompok tertentu mereka yang akan terkena kebijakan tersebut diberi kesempatan
untuk berpartisipasi secara aktif atau diakomodasi kepentingannya.
Hambatan bagi partispasi bisa juga terjadi karena faktor struktur sosial yang sangat
hirarkhis (Gaffar dalam Sudarmo 2011 : 89). Sampai saat ini budaya Jawa ,masih
meperlihatkan hirarki sosial. Orang-orang masih dikategorikan sebagai wong gedhe
(orang-orang dengan derajat status tinggi, termasuk didalamnya antara lain (orang-orang-(orang-orang kaya, pejabat,
keluarga pejabat, pengusaha, pemilik perusahaan, pedagang formal, keluarga kraton) dan wong
cilik (orang-orang biasa maupun orang-orang yang memiliki derajat status sosial rendah,
termasuk masyarakat kebanyakan, petani, buruh, PKL miskin). Dikotomisasi ini berakibat pada
commit to user
secara sosial, ekonomi dan secara politik tertinggal. Akibatnya, wong cilik ini (rakyat
kebanyakan) dipandang dan diperlakukan sebagai pihak yang perlu dibantu. Sebagai imbalan
atas kebaikan para pejabat atau pemerintah, masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan
para pejabat tersebut. Keadaan ini kemudian menjadi hambatan lebih jauh bagi terselengaranya
partisipasi oleh masyarakat/wong cilik (Gaffar dalam Sudarmo 2011 : 90).
Disamping itu, partisipasi warganegara langsung dalam pembuatan keputusan di
tingkat lokal bisa juga dipengaruhi oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau
institusi-institusi yang memeperkuat keberadaan mereka dan seberapa besar sumber keuangan dari
pemerintah daerah disediakan untuk mendukung partisipasi tersebut (Gaffar dalam Sudarmo
2011 : 90). Faktor-faktor lain, termasuk tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi, tingkat
ketidaksetaraan dan hirarki sosial yang kuat, semuanya ikut berkontribusi dalam menghambat
terselenggaranya partisipasi (Gaffar dalam Sudarmo 2011 : 90).
Kegagalan organisasi-organisasi lokal seperti paguyuban, ikatan, asosiasi dan
kelompok yang dibangun untuk meningkatkan partisipasi dalam formulasi kebijakan mungkin
bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Montgomery mengklasifikasikan
bentuk-bentuk partisipasi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah kelompok yang digambarkan
sebagai ‘apathy’, yaitu kondisi dimana organisasi gagal karena tidak adanya daya
tanggap/perhatian dari para anggotanya; kelompok kegagalan kedua adalah diidentifikasikan
sebagai ‘internal colonization’, yang terjadi ketika kelompok-kelompok kecil yang ada di
tingkat lokal (daerah) terlalu melakukan kontrol berlebihan terhadap organisasi yang tengah
menjalankan fungsinya dan dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan mereka pribadi; Ketiga
ketika aktor di luar organisasi (biasanya pemerintah) menemukan organisasi lokal yang
berjalan bagus dan berusaha memanfaatkanya untuk tujuan-tujuan yang tidak sejalan dengan
prioritas-prioritas lokal (Montgomery dalam Sudarmo 2011 : 90).
Hambatan partisipasi kaum marginal seperti PKL di Solo Raya atau di Jawa (dan
mungkin di wilayah Indonesia lainnya) dalam proses kebijakan atau perencanaan
pembangunan lokal masing-masing daerah bisa diakibatkan oleh salah satu atau lebih
bentuk-bentuk hambatan sebagaimana didiskusikan diatas seperti hambatan yang berasal dari internal
kelompok atau individu-individu tersebut seperti status sosial ekonomi dan status sosial dalam
hirarki budaya Jawa, tetapi juga hambatan eksternal seperti hirarki birokrasi pemerintah
setempat, kemauan politik dari pemerintah dan para anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah, dan kurangnya dukungan dari para individu, kelompok atau institusi lokal seperti para
ketua paguyuban tingkat lokasi maupun tingkat kabupaten/kota dan lembaga swadaya lokal
(Sudarmo 2011 : 91).
Walaupun partisipasi bisa dilakukan melalui negosiasi dan juga protes (Munro-Clark
dalam Sudarmo 2011 : 91) tidak berarti bahwa semua tuntutan, kepentingan dan pemikiran
kaum marginal tersebut bisa diakomodasi oleh pihak pemegang otoritas karena partisipasi bisa
berubah menjadi kooptasi politik (Cooke and Kothari dalam Sudarmo 2011 : 91) mengingat
pihak otoritas tidak jarang memanfaatkan struktur otoritas yang mereka miliki untuk meraih
tujuan-tujuan pribadi (Munro-Clark dalam Sudarmo 2011 : 91). dan dengan demikian itu sama
saja berjalannya sentralisasi secara terus berkelanjutan atas nama desentraliasi (Cooke dalam
commit to user
down tetap terus diabadikan. Dengan kata lain, walaupun seluruh pemerintah daerah di
Indonesia sejak kira-kira tahun 2000 dan setelahnya telah mengimplementasikan pemerintahan
daerah yang terdesentralisir dan telah mempraktekan sistem pemilihan umum kepala
daerah/walikota secara sangat demokratis sejak sekitar tahun 2005 melalui pemilihan langsung,
dan mungkin melibatkan juga paguyuban PKL atau kaum marginal lainnya dalam proses
pembuatan keputusan, ada kemungkinan bahwa ketua mereka atau beberapa anggota mereka
terkooptasi oleh elit atau pemerintah untuk mempengaruhi rekan-rekan sejawatnya. Mungkin
saja pembuatan keputusan masih terus didominasi oleh pemerintah dan bahkan kemungkinan
masih dilakukan melalui pendekatan top-down, yang terpusat di tangan pemerintah yang
mencerminkan atau agenda kepentingan pemerintah yang kemungkinan besar berbeda dengan
kepentingan, permintaan, keinginan dan pikiran kaum marginal (PKL). Lebih dari itu,
peraturan-peraturan dan porses partisipasi termasuk berbagai pengetahuan, hubungan kekuatan
untuk bernegosiasi, aktivitas politik dan sebagainya bisa menyembunyikan dan melaksanakan
tindakan kekejaman dan ketidak adilan dalam berbagai bentuk. (Cooke dalam Sudarmo 2011 :
91-92) Ini untuk menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah/kota/pemegang otoritas untuk
mencapai semua tujuan-tujuannya dan merealisasikan agenda-agenda politiknya dan
kebijakannya bisa saja melakukan tindakan opresif, pembersihan/penggarukan secara keras dan
pilih kasih, mengadudomba antara mereka yang menjadi sasaran kebijakannya, atau tindakan
kejam lainnya melalui implementasi kebijakan.
2.1.4. Hukum, Konsistensi dan Diskresi
Hampir setiap tindakan penataan mengunakan ketentuan-ketentuan hukum, baik itu
berupa peraturan daerah, keputusan bupati, surat edaran atau instruksi bupati/walikota yang
sifatnya mengikat. Sebagian pemerintrah daerah/kota secara eksplisit menggunakan peraturan
daerah untuk mengatur atau menata serta membina PKL di daerahnya, sedangkan sebagian
lainnya mengunakan peraturan daerah yang cakupannya luas misalnya peraturan daerah
tentang ketertiban dan kebersihan , namun didalamnya ada bagian atau pasal-pasal yang
mengatur PKL.
Keberadaan hukum formal yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban pemerintah dan PKL maupun mekanisme penegakan hukum dan
mekanisme pemecahan masalah akibat ketidaksetujuan terhadap peraturan tersebut dengan
cara yang tidak memihak dan adil merupakan hal penting bagi governance karena keadaan
seperti itu merupakah persyaratan bagi akuntabilitas dalam implementasi sebuah kebijakan atau
aturan. Untuk mencapai akuntabilitas, implementasi peraturan tersebut harus predictable
dalam arti bahwa peraturan atau ketentuan tersebut dilakukan secara konsisten dan adil dalam
pelaksanannya.³ Dengan kata lain, kewajiban para PKL dan hak-hak yang harus mereka
terima harus seimbang.
Menurut Scott, hukum formal sampai dengan tingkat yang sangat besar adalah
parasitic terhadap proses informal karena rancangan atau perencanaan secara skematik bagi
tatanan sosial bisa mengabaikan hal-hal penting sebuah kondisi riil sehinga semata-mata
commit to user
Dengan demikian, peraturan formal yang ditujukan untuk menjamin bahwa PKL taat
pada peraturan hukum harus dibarengi dengan kesadaran oleh pemerintah bahwa peraturan
hukum tidak selalu cocok atau sesuai untuk situasi yang berkembang saat ini. Juga terdapat
kemungkinan bahwa pendekatan otoriter yang bersifat top-down hanya akan menyulut
resistensi di tingkat akar rumput dan pendekatan seperti itu meminta kepada mereka tentang
apa yang harus dilakukan ketimbang mendorong mereka untuk melakukan apa yang bisa
dikerjakan oleh mereka sendiri (Edgar dalam Sudarmo 2011 : 93). Lebih dari itu aturan formal
bukanlah alat yang selalu efektif untuk memecahkan masalah. Sebagaimana dikatakan Edgar
bahwa “solusi-solusi yang efektif tidak pernah datang dari program-program yang terpisah dari
komunitas disekelilingnya. Mereka datang dari usaha-usaha yang berkaitan, terintegrasi, dan
terkoordinasi dari seluruh institusi masyarakat yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan
dukungan (Edgar dalam Sudarmo 2011 : 93).
Peraturan daerah, peraturan bupati atau instruksi bupati yang bisa dikemas dalam
sebuah surat edaran merupakan salah satu tipe kebijakan publik yang disebut ‘protective
regulatory’; kebijakan seperti ini ditujukan untuk melindungi publik dengan membangun
sebuah kondisi dimana aktivitas privat bisa dilakukan; kondisi yang diyakini mengalami
kerusakan atau ganguan tidak diperkenankan atau dilarang; aktivitas-aktivitas yang
bermanfaat diperlukan; kebijakan seperti ini memerlukan kondisi dimana sektor masyarakat
sesuai dengan aturan hukum umum. Ia dibentuk dalam sebuah proses yang sangat politis
melalui pembuatan kebijakan yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan dan
usaha-usaha melakukan lobi dan stekholder-stakeholder lainnya tergantung sistem politik di negara