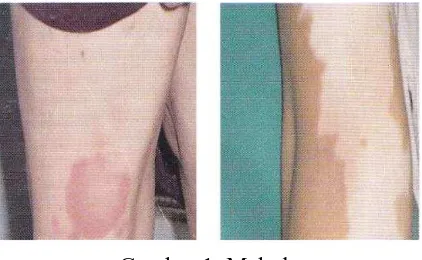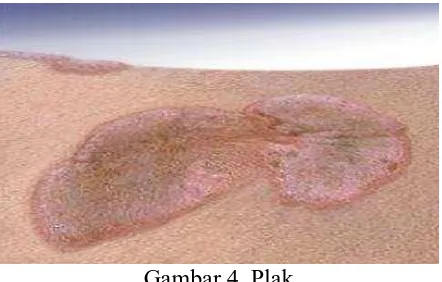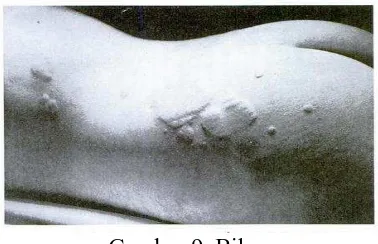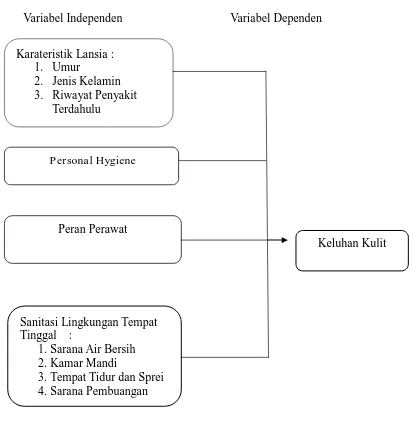BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Personal Hygiene
2.1.1. Defenisi Personal Hygiene
Menurut Wartonah (2010), personal hygiene berasal dari bahasa yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan
perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan
seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.
Menurut Tarwoto (2010) personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan
psikis. Pemenuhan personal hygiene diperlukan untuk kenyamanan individu,
keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan personal hygiene ini diperlukan baik pada orang sehat maupu pada orang sakit.
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene
Menurut Tarwoto (2004), sikap seseorang melakukan personal hygiene dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain :
a. Citra tubuh
Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan
fisiknya. Personal hygiene yang baik akan mempengaruhi terhadap peningkatan citra tubuh individu. Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi
kebersihan diri misalnya karena adanya perubahan fisik sehingga individu tidak
b. Praktik sosial
Kebiasaan keluarga, jumlah orang di rumah, dan ketersediaan air panas
atau air mengalir hanya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi
perawatan personal hygiene. Praktik personal hygiene pada lansia dapat berubah dikarenakan situasi kehidupan, misalnya jika mereka tinggal dipanti jompo
mereka tidak dapat mempunyai privasi dalam lingkungannya yang baru. Privasi
tersebut akan mereka dapatkan dalam rumah mereka sendiri, karena mereka tidak
mempunyai kemampuan fisik untuk melakukan personal hygiene sendiri.
c. Status sosioekonomi
Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampo dan alat mandi yang semuanya memerlukan uang untuk
menyediakannya.
d. Pengetahuan
Pengetahuan personal hygiene sangat penting karena pengetahuan yang
baik dapat meningkatkan kesehatan. Kendati demikian, pengetahuan itu sendiri
tidaklah cukup. Seseorang harus termotivasi untuk memelihara perawatan diri.
Seringkali pembelajaran tentang penyakit atau kondisi yang mendorong individu
untuk meningkatkan personal hygiene.
e. Budaya
Kepercayaan kebudayaan dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Disebagian masyarakat jika individu sakit tertentu maka tidak
merupakan sebuah atribut psikologis yang membentuk sebuah kontinum dari
sangat maskulin sampai sangat feminin. Seorang lakilaki mungkin memiliki
karakteristik-karakteristik feminin tertentu sama seperti halnya perempuan
memiliki sifat-sifat maskulin. Cara berpikir gender semacam ini jauh lebih
canggih dibandingkan dengan pembagian dua arah yang memandang semua
laki-laki maskulin dan semua perempuan feminin, namun kelemahannya bahwa
cara berpikir ini mengasumsikan bahwa semua orang yang tinggi maskulinitasnya
pastilah juga rendah feminitasnya. Seseorang yang memiliki dua sifat maskulin
dan feminin semacam ini disebut “bersifat androgini”. Model gender semacam ini
menghasilkan ruang psikologis yang lebih kompleks yang orang dapat memetakan
identitas gender orang lain.
f. Kebiasaan seseorang
Setiap individu mempunyai pilihan kapan untuk mandi, bercukur dan
melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan orang yang menggunakan produk
tertentu dalam perawatan diri seperti penggunaan shampo, dan lain-lain.
g. Kondisi fisik
Pada keadaan sakit, tentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan
perlu bantuan untuk melakukannya.
2.1.3. Dampak yang Sering Timbul pada Masalah Personal Hygiene Dampak yang akan timbul jika kurangnya personal hygiene adalah :
a. Dampak fisik
Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak
terjadi adalah munculnya kutu pada rambut, gangguan integritas kulit, gangguan
membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telingan, dan ganguan fisik pada
kuku.
b. Dampak psikososial
Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai, kebutuhan harga diri,
aktualisasi diri dan gangguan interaksi sosial. (Tarwoto, 2004)
2.1.4. Tanda dan Gejala
Menurut Departemen Kesehatan RI (2000), tanda dan gejala individu dengan
kurang perawatan diri adalah:
1. Fisik
a) Badan bau dan pakaian kotor
b) Rambut dan kulit kotor
c) Kuku panjang dan kotor
d) Gigi kotor disertai mulut bau
e) Penampilan tidak rapi
2. Psikologis
a) Malas dan tidak ada inisiatif
b) Menarik diri atau isolasi diri
c) Merasa tak berdaya , rendah diri dan merasa hina
3. Sosial
a) Interaksi kurang
c) Tidak mampu berperilaku sesuai norma
d) Cara makan tidak teratur, buang air besar dan buang air kecil di
sembarang tempat, gosok gigi dan mandi tidak mampu mandiri.
2.1.5. Pemeliharaan dalam Personal Hygiene
Pemeliharaan personal hygiene berarti tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Seseorang
dikatakan memiliki personal hygiene baik apabila, orang tersebut dapat menjaga kebersihan tubuhnya yang meliputi kebersihan kulit, gigi dan mulut, rambut, mata,
hidung, dan telinga, kaki dan kuku, genitalia, serta kebersihan dan kerapihan
pakaiannya. Menurut Potter dan Perry (2006) macam-macam personal hygiene adalah:
a. Perawatan kulit
Kulit merupakan organ aktif yang berfungsi pelindung, sekresi, ekskresi,
pengatur temperatur, dan sensasi. Kulit memilki tiga lapisan utama yaitu
epidermis, dermis dan subkutan. Epidermis (lapisan luar) disusun beberapa
lapisan tipis dari sel yang mengalami tahapan berbeda dari maturasi, melindungi
jaringan yang berada di bawahnya terhadap kehilangan cairan dan cedera mekanis
maupun kimia serta mencegah masuknya mikroorganisme yang memproduksi
penyakit. Dermis, merupakan lapisan kulit yang lebih tebal yang terdiri dari ikatan
kolagen dan serabut elastik untuk mendukung epidermis. Serabut saraf, pembuluh
darah, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan folikel rambut bagian yang melalui
lapisan dermal. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, minyak, cairan odor,
tetap lemas dan liat. Lapisan Subkutan terdiri dari pembuluh darah, saraf, limfe,
dan jaringan penyambung halus yang terisi dengan sel-sel lemak. Jaringan lemak
berfungsi sebagai insulator panas bagi tubuh. Kulit berfungsi sebagai pertukaran
oksigen, nutrisi, dan cairan dengan pembuluh darah yang berada dibawahnya,
mensintesa sel baru, dan mengeliminasi sel mati, sel yang tidak berfungsi.
Sirkulasi yang adekuat penting untuk memelihara kehidupan sel. Kulit sering kali
merefleksikan perubahan pada kondisi fisik dengan perubahan pada warna,
ketebalan, tekstur, turgor, temperatur. Selama kulit masih utuh dan sehat, fungsi
fisiologisnya masih optimal.
b. Mandi
Mandi adalah bagian perawatan hygiene total. Mandi dapat dikategorikan sebagai pembersihan atau terapeutik. Mandi di tempat tidur yang lengkap
diperlukan bagi individu dengan ketergantungan total dan memerlukan personal hygiene total. Keluasan mandi individu dan metode yang digunakan untuk mandi berdasarkan pada kemampuan fisik individu dan kebutuhan tingkat hygiene yang diperlukan. Individu yang bergantung dalam kebutuhan hygienenya sebagian atau
individu yang terbaring di tempat tidur dengan kecukupan diri yang tidak mampu
mencapai semua bagian badan memperoleh mandi sebagian di tempat tidur. Pada
lansia, mandi biasanya dilakukan dua kali sehari atau lebih sesuai selera dengan
air dingin atau air hangat. Diusahakan agar satu kali mandi tidak dibawah
pancuran atau konsensional, tetapi merendam diri di bak mandi yang akan
memberi kenikmatan, relaksasi dan menambah tenaga serta kebugaran tubuh.
(perineum). Gosokan dimulai dari sisi alat kelamin kea rah dubur. Bagi wanita,
puting payudara jangan lupa dibersihkan dan kemudian dikeringkan. Setelah
selesai mandi keringkan badan, termasuk rongga telinga, lipatan-lipatan kulit dan
celah-celah jari kaki untuk menghindarkan timbulnya infeksi jamur, juga pada
semua lipatanlipatan kulit lainnya (Setiabudhi, 2002).
c. Perawatan Mulut
Hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, gusi,
dan bibir. Menggosok membersihkan gigi dari partikel-partikel makanan, plak,
dan bakteri, memasase gusi, dan mengurangi ketidaknyamanan yang dihasilkan
dari bau dan rasa yang tidak nyaman. Beberapa penyakit yang muncul akibat
perawatan gigi dan mulut yang buruk adalah karies, radang gusi, dan sariawan.
Hygiene mulut yang baik memberikan rasa sehat dan selanjutnya menstimulasi nafsu makan.
Golongan lansia sering mengalami tanggalnya gigi geligi. Salah satu sebab
adalah karena proses penuaan dan penyebab lain yang lebih sering adalah kurang
baiknya perawatan gigi dan mulut. Osteoporosis dan periodontitis pada lansia menyebabkan akar gigi agak longgar dan dicelah-celah ini sering tersangkut sisa
makanan. Inilah penyebab terjadinya peradangan. (Setiabudhi, 2002)
Bagi lansia yang masih mempunyai gigi agak lengkap dapat menyikta
giginya dua kali sehari, pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur, dan pada
lansia yang ompong dianjurkan untuk berkumur-kumur setalah makan serta
melepas dan menggosok gigi di air mengalir dengan menggunakan pasta gigi
2008)
d. Perawatan mata, hidung dan telinga
Secara normal tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk
membersihkan mata, hidung, dan telinga selama individu mandi. Secara normal
tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata karena secara
terus-menerus dibersihkan oleh air mata, kelopak mata dan bulu mata mencegah
masuknya partikel asing kedalam mata. Normalnya, telinga tidak terlalu
memerlukan pembersihan. Namun, telinga yang serumen terlalu banyak
telinganya perlu dibersihlkan baik mandiri atau dibantu oleh keluarga. Hygiene telinga mempunyai implikasi untuk ketajaman pendengaran. Bila benda asing
berkumpul pada kanal telinga luar, maka akan mengganggu konduksi suara.
Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, memantau temperatur dan
kelembapan udara yang dihirup, serta mencegah masuknya partikel asing ke
dalam sistem pernapasan.
e. Perawatan rambut
Penampilan dan kesejahteraan seseorang seringkali tergantung dari cara
penampilan dan perasaan mengenai rambutnya. Penyakit atau ketidakmampuan
mencegah seseorang untuk memelihara perawatan rambut sehari-hari. Menyikat,
menyisir dan bershampo adalah cara-cara dasar higienis perawatan rambut,
distribusi pola rambut dapat menjadi indikator status kesehatan umum, perubahan
hormonal, stress emosional maupun fisik, penuaan, infeksi dan penyakit tertentu
atau obat obatan dapat mempengaruhi karakteristik rambut. Rambut merupakan
melalui rambut perubahan status kesehatan diri dapat diidentifikasi. Kerontokan
rambut sering terjadi pada lansia. Jumlah rambut ratarata adalah lebih 100.000
helai, 80% bersifat aktif tumbuh dan sisanya 20% berada dalam stadium tidak
aktif. Rambut membutuhkan perawatan yang baik dan teratur, terutama pada
wanita. Agar tidak mengalami banyak kerontokan, antara lain karena kurangnya
sanitasi atau adanya infeksi jamur yang lazim disebut ketombe. Rata-rata 50- 100
helai rambut dapat rontok dalam masa sehari. Oleh itu rambut sebaik-baiknya
perlu dicuci dengan shampo yang mengandung anti ketombe yang cocok. Cuci
rambut sebaiknya dilakukan tiap 2 atau 3 hari dan minimal sekali seminggu
(Setiabudhi, 2002).
Dan pada lansia yang sama sekali yang tidak dapat mencuci rambutnya
karena sakit atau kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan dapat mecuci rambut
di tempat tidur ( Ekasari dkk ,2008)
f. Perawatan kaki dan kuku
Kaki dan kuku seringkali memerlukan perhatian khusus untuk mencegah
infeksi, bau, dan cedera pada jaringan. Tetapi seringkali orang tidak sadar akan
masalah kaki dan kuku sampai terjadi nyeri atau ketidaknyamanan. Menjaga
kebersihan kuku penting dalam mempertahankan personal hygiene karena
berbagai kuman dapat masuk kedalam tubuh melalui kuku. Oleh sebab itu, kuku
seharusnya tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Perawatan dapat digabungkan
selama mandi atau pada waktu yang terpisah.
Pada lansia, proses penuaan memberi perubahan pada kuku yaitu
menjadi bergaris dan mudah pecah karena agak keropos. Warnanya bisa berubah
menjadi kuning atau opaque. Kuku bisa menjadi lembek terutama kuku kaki akan
menjadi lebih tebal dan kaku serta sering ujung kuku kiri dan kanan menusuk
masuk ke jaringan disekitarnya (ungus incarnates). Pengguntingan dilakukan setelah kuku direndam dalam air hangat selama 5-10 menit karena pemanasan
membuat kuku menjadi lembek dan mudah digunting (Setiabudhi, 2002).
g. Perawatan genetalia
Perawatan genitalia merupakan bagian dari mandi lengkap. Seseorang yang
paling butuh perawatan genitalia yang teliti adalah yang beresiko terbesar
memperoleh infeksi. Seseorang yang tidak mampu melakukan perawatan diri
dapat dibantu keluarga untuk melakukan personal hygiene. (Azizah,2011)
2.1.6. Hal-hal yang Mencakup Personal Hygiene
Kegiatan-kegiatan yang mencakup personal hygiene adalah:
a. Mandi
Mandi merupakan bagian yang penting dalam menjaga kebersihan diri.
Mandi dapat menghilangkan bau, menghilangkan kotoran, merangsang peredaran
darah, memberikan kesegaran pada tubuh. Sebaiknya mandi dua kali sehari,
alasan utama ialah agar tubuh sehat dan segar bugar. Mandi membuat tubuh kita
segar dengan membersihkan seluruh tubuh kita (Stassi, 2005).
Menurut Irianto (2007), urutan mandi yang benar adalah seluruh tubuh
dicuci dengan sabun mandi. Oleh buih sabun, semua kotoran dan kuman yang
melekat mengotori kulit lepas dari permukaan kulit, kemudian tubuh disiram
Keluarkan daki dari wajah, kaki, dan lipatan- lipatan. Gosok terus dengan tangan,
kemudian seluruh tubuh disiram sampai bersih sampai kaki.
b. Perawatan mulut dan gigi
Mulut yang bersih sangat penting secara fisikal dan mental seseorang.
Perawatan pada mulut juga disebut oral hygiene. Melalui perawatan pada rongga mulut, sisa-sisa makanan yang terdapat di mulut dapat dibersihkan. Selain itu,
sirkulasi pada gusi juga dapat distimulasi dan dapat mencegah halitosis (Stassi,
2005). Maka penting untuk menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan
sangat dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menggosok gigi setiap kali selepas
kita makan (Sharma, 2007). Kesehatan gigi dan rongga mulut bukan sekedar
menyangkut kesehatan di rongga mulut saja. Kesehatan mencerminkan kesehatan
seluruh tubuh. Orang yang giginya tidak sehat, pasti kesehatan dirinya berkurang.
Sebaliknya apabila gigi sehat dan terawat baik, seluruh dirinya sehat dan segar
bugar. Menggosok gigi sebaiknya dilakukan setiap selesai makan. Sikat gigi
jangan ditekan keras-keras pada gigi kemudian digosokkan cepat-cepat. Tujuan
menggosok gigi ialah membersihkan gigi dan seluruh rongga mulut. Dibersihkan
dari sisa-sisa makanan, agar tidak ada sesuatu yang membusuk dan menjadi
sarang bakteri (Irianto, 2007).
c. Cuci tangan
Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak berhubungan dengan apa
saja. Kita menggunakan tangan untuk menjamah makanan setiap hari. Selain itu,
sehabis memegang sesuatu yang kotor atau mengandung kuman penyakit, selalu
dapat menyebabkan pemindahan sesuatu yang dapat berupa penyebab
terganggunya kesehatan karena tangan merupakan perantara penularan kuman
(Irianto, 2007). Berdasarkan penelitan WHO dalam National Campaign for
Handwashing with Soap (2007) telah menunjukkan mencuci tangan pakai sabun
dengan benar pada lima waktu penting yaitu sebelum makan, sesudah buang
air besar, sebelum memegang bayi, sesudah menceboki anak, dan sebelum
menyiapkan makanan dapat mengurangi angka kejadian diare sampai 40%. Cuci
tangan pakai sabun dengan benar juga dapat mencegah penyakit menular lainnya
seperti tifus dan flu burung.
Langkah yang tepat cuci tangan pakai sabun adalah seperti berikut
(National Campaign for Handwashing with Soap, 2007):
1. Basuh tangan dengan air mengalir dan gosokkan kedua permukaan tangan
dengan sabun secara merata, dan jangan lupakan sela-sela jari.
2. Bilas kedua tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.
3. Keringkan tangan dengan menggunakan kain lap yang bersih dan kering.
d. Membersihkan Pakaian
Pakaian yang kotor akan menghalangi seseorang untuk terlihat sehat dan
segar walaupun seluruh tubuh sudah bersih. Pakaian banyak menyerap keringat,
lemak dan kotoran yang dikeluarkan badan. Dalam sehari saja, pakaian
berkeringat dan berlemak ini akan berbau busuk dan menganggu. Untuk itu perlu
mengganti pakaian dengan yang besih setiap hari. Saat tidur hendaknya kita
mengenakan pakaian yang khusus untuk tidur dan bukannya pakaian yang sudah
2 kali harus dibersihkan. (Irianto, 2007).
2.1.7 Tujuan Personal Hygiene
a. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang.
b. Memelihara kebersihan diri seseorang
c. Memperbaiki personal hygiene yang kurang
d. Pencegahan penyakit
e. Meningkatkan percaya diri seseorang
f. Menciptakan keindahan (Tarwoto, 2004)
2.2. Karateristik Lansia 2.2.1. Umur
Menurut KBBI umur adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau
diadakan. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan
suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Umur manusia
dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.
Batasan usia bagi lansia menurut WHO meliputi usia pertengahan
(middle age) antara 45-59 tahun, usia lanjut (elderly) antara 60-74 tahun, dan
usia lanjut tua (old) antara 75-90 tahun, serta usia sangat tua (very old) di atas
90 tahun (Azizah, 2011) .
Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonugroho, lanjut usia dikelompokkan
menjdia usia dewaasa muda (eldelry adulhood), 18 atau 19-25 tahun, usia dewasa
2.2.2. Jenis Kelamin
Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah lansia perempuan
lebih besar daripada laki-laki, yaitu 10,77 juta lansia perempuan dibandingkan
9,47 juta lansia laki-laki.(BPS,2014)
Akibat dari usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki, maka
jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia lebih didominasi perempuan. Perlu
diketahui sebagai akibat dari perbedaan yang sifatnya kodrati maupun sebagai
akibat dari perbedaan gender, perempuan lanjut usia di Indonesia memiliki ciri
yang berbeda dengan laki-laki lanjut usia. Karena kebiasaannya mengurus rumah
tangga membuat perempuan lanjut usia dianggap lebih siap menghadapi masa
tuanya. Selain itu, karena kebiasaan mengurus diri sendiri, hidup menjadi janda
pun bukan hal yang berat bagi perempuan lanjut usia. Perempuan lanjut usia lebih
siap menjalani kehidupan seorang diri. Perempuan lanjut usia juga memiliki
kemampuan berkomunitas lebih baik dan tetap aktif bermasyarakat (arisan,
pengajian, dan sebagainya). Perempuan lanjut usia juga cenderung tinggal dalam
keluarga untuk melampiaskan kebiasaannya mengurus rumah tangga. Sementara
itu, struktur sosial menjadikan perempuan harus bekerja di ranah domestik,
menyebabkan perempuan tidak mempunyai akses yang sama dengan laki-laki
untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang. (Krisna,2011)
2.2.3. Riwayat Penyakit Terdahulu
Riwayat alamiah penyakit (natural history of disease) adalah deskripsi
sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit,
seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi
preventif maupun terapetik. Riwayat penyakit terdahulu pada lansia mungkin
mempengaruhi penyakit lansia di masa sekarang. Penilaian medis pada lansia
meliputi penilaian riwayat penyakit dahulu maupun riwayat penyakit sekarang dan
mengevaluasi status gizi lansia.
Penilaian terhadap riwayat penyakit lansia yang terdahulu
diharapkan dapat mempermudah untuk mengetahui faktor risiko yang dapat
menyebabkan penurunan kondisi medis lansia dimasa sekarang. Secara garis besar
terdapat empat faktor risiko yang dapat menurunkan kondisi medis lansia
dimasa tuanya dan harus menjadi fokus penilaian kondisi medis,
yaitu usia dari lansia, gangguan fungsi kognitif, gangguan fungsi dasar dan
gangguan mobilitas. Keempat faktor risiko tersebut dapat
menimbulkan sindrom geriatri, diantaranya ulkus, inkontinensia,
peningkatan terjadinya jatuh pada lansia, penurunan fungsi dan
penurunan kesadaran (delirium).
2.3. Peran Perawat
Keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional dalam memberikan
asuhan keperawatan kepada pasien secara berkesinambungan mulai dari pasien
membutuhkan pelayanan sampai pasien mampu melakukan kegiatan sehari-hari
secara produktif untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ketidakmampuan pasien,
kurangnya pengetahuan, kondisi penyakit, serta motivasi diri selama menjalani
sehari-hari pasien. Salah satu peran perawat adalah sebagai pemberi asuhan
keperawatan atau care provider. Peran perawat sebagai care provider harus
dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh, tidak hanya berfokus pada
tindakan promotif tetapi juga pada tindakan preventif seperti pelaksanaan
personal. (Kusnanto, 2004)
Tingkat pencapaian kesempurnaan pemberian asuhan keperawatan sangat
tergantung dari kemauan, kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang baik
dari perawat. Selain itu juga harus ditunjang dengan tersedianya fasilitas secara
memadai, kondisi kuantitas yang sesuai penempatan yang tepat serta persiapan
sumber daya manusia (perawat) yang baik. Pelaksanaan personal hygiene pasien harus selalu diperhatikan oleh perawat karena pemeliharaan personal hygiene dapat meningkatkan rasa nyaman bagi pasien. Kondisi pasien yang sakit atau
memiliki keterbatasan dalam pergerakan memerlukan orang lain atau perawat
dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. (Kusnanto, 2004)
Menurut Maryam (2008) tujuan dari perawat lansia adalah
1. Mempertahankan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pada lanjut
usia pada taraf yang setinggi-tingginya sehingga terhindar dari penyakit atau
gangguan.
2. Memenuhi kebutuhan lanjut usia sehari-hari
3. Mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari
4. Memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitasa fisik dan mental
5. Merangsang petugas kesehatan untuk dapat mengenal dan menegakkan
6. Mencari upaya semaksimal mungkin apabila lanjut usia yang menderita suatu
penyakit atau gangguan masih dapat mempertahankan kebebasan yang
maksimal tanpa perlu suatu pertolongan (memelihara kemandirian secara
maksimal)
2.4. Sanitasi Lingkungan
Menurut Notoadmojo (2007), sanitasi lingkungan adalah status
kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran,
penyediaan air bersih, dan sebagainya. Banyak sekali permasalahan lingkungan
yang harus dicapai dan sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan
lingkungan. Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap kondisi
elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem. Bila lingkungan tidak
sehat maka sakitlah elemennya, tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat
pulalah ekosistem tersebut. Perilaku yang kurang baik dari manusia telah
mengakibatkan perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah masalah sanitasi.
2.4.1 Hygiene dan Sanitasi
Menurut Entjang (2000), hygiene dan sanitasi adalah pengawasan lingkungan fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan
manusia, dimana lingkungan yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak
sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan. Usaha dalam hygiene dan
sanitasi lingkungan di Indonesia terutama meliputi:
a. Menyediakan air rumah tangga yang baik, cukup kualitas maupun
kuantitasnya
c. Mendirikan rumah-rumah sehat, menambah jumlah rumah agar
rumah-rumah tersebut menjadi pusat kesenangan rumah tangga yang
sehat
d. Pembasmian binatang-binatang penyebar penyakit seperti : lalat dan
nyamuk
Istilah hygiene dan sanitasi mempunyai tujuan yang sama pada dasarnya, yakni mengusahakan cara hidup yang sehat agar terhindar dari berbagai penyakit,
namun dalam penerapannya memiliki arti yang sedikit berbeda. Usaha sanitasi
lebih menitik beratkan pada faktor lingkungan hidup manusia, sedangkan hygiene
lebih menitik beratkan pada usaha-usaha kebersihan perorangan (Kusnoputranto,
2000).
2.4.2 Sanitasi Rumah
Kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman adalah kondisi fisik,
kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan sehingga
memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.
Persyaratan kesehatan perumahan dan permukiman adalah ketentuan teknis
kesehatan yang wajib di penuhi dalam rangka melindungi penghuni dan
masyarakat yang bermukim di perumahan atau masyarakat sekitar dari bahaya
atau gangguan kesehatan (Soedjadi, 2005).
Adapun kriteria rumah sehat yang tercantum
dalam Residential Environment dari WHO (1974), antara lain:
1. Harus dapat melindungi dari hujan, panas, dingin, dan
2. Mempunyai tempat-tempat untuk tidur, masak, mandi, mencuci,
kakus, dan kamar mandi,
3. Dapat melindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran,
4. Bebas dari bahan bangunan berbahaya,
5. Terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi
penghuninya dari gempa, keruntuhan, dan penyakit menular,
6. Memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi.
Sementara itu, kriteria rumah sehat menurut Winslow, antara lain:
1. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis
2. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis
3. Dapat menghindarkan dari terjadinya kecelakaan.
4. Dapat menghindarkan terjdinya penularan penyakit.
Persyaratan kesehatan suatu rumah tinggal sesuai dengan
Permenkes No.829/Menkes/SK/VII/1999 adalah sebagai berikut:
1. Bahan bangunan
a. Tidak terbuat dari bahan-bahan yang dapat melepaskan
zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain:
1) Debu total tidak lebih dari 150 μg/m3
2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m3/jam
3) Timah hitam (Pb) tidak melebihi 300 mg/kg.
b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya
mikroorganisme patogen.
persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:
a. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan
b. Dinding
1) Di ruang tidur dan ruang keluarga dilengkapi dengan saran
ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara.
2) Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air
dan mudah dibersihkan.
3) Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan
4) Bumbungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter
atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir
5) Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi
sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur,
ruang dapur, kamar mandi dan ruang bermain anak.
6) Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap.
3. Pencahayaan alam dan atau buatan langsung maupun tidak
langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal
intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan mata.
4. Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut:
a) Suhu udara berkisar antara 18-30 C
b) Kelembaban udara berkisar antara 40-70%
c) Konsentrasi gas SO2 tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam
d) Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam
5. Ventilasi luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang
permanen minimal 10% dari luas lantai.
6. Binatang penular penyakit tidak ada tikus, nyamuk ataupun
lalat yang bersarang di dalam rumah
7. Penyediaan air
a) Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas 60 liter/hari/orang
b) Kualitas air minum harus memenuhi persyaratan kesehatan air
bersih dan atau air minum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Tersedia sarana penyimpanan makanan yang aman.
9. Limbah
a) Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari
sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari
permukaan tanah.
b) Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan
bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.
10. Kepadatan hunian ruang tidur luas minimal 8 m dan tidak
dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang dalam satu ruang tidur, kecuali
anak di bawah usia 5 tahun (Depkes RI, 1999).
2.4.3 Sarana Air Bersih
Air merupkakan suatu sarana untuk menigkatkan derajat kesehatan
masyarakat karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam
Menurut Mubarak dan Chayatin (2009), penyediaan air bersih harus memenuhi
persyaratan yaitu :
a. Syarat fisik : persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah tidak
berbau, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa dan suhu air sebaiknya
sejuk atau tidak panas.
b. Syarat bakteriologis : air minum harus bebas dari segala bakteri, terutama
bakteri patogen. Untuk mengetahuinya dengan memeriksa melalui sampel air,
jika dari hasil pemeriksaan 100 cc air terdapat <4 bakteri E.coli maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan.
c. Syarat kimia : air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam
jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia
didalam air, akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia.
Menurut Chandra (2006), Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air
dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya.
Mekanisme penularan penyakit terbagi menjadi empat:
1. Waterborne mechanism
Di dalam mekanisme ini, kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan
penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem
pencernaan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain
kolera, tifoid, hepatitis viral, disentri basiler, dan poliomyelitis. 2. Waterwashed mechanism
Mekanisme penularan berkaitan dengan kebersihan umum dan perorangan.
a. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak.
b. Infeksi melalui kulit dan mata.
c. Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis.
3. Water-based mechanism
Penyakit ini ditularkan dengan mekanisme yang memiliki agent penyebab
yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai
intermediate host yang hidup di dalam air. Contohnya: skistomiasis dan penyakit
akibat dracunculucmedinensis.
4. Water-related insect vector mechanism
Agent penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di
dalam air. Contoh penyakit dengan mekanisme penularan seperti ini adalah
filariasis, dengue, malaria, dan yellow fever.
Menurut Chandra (2006), Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi
menjadi air angkasa (hujan), air permukaan, dan air tanah.
1. Air Angkasa
Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Walau pada
saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tesebut cenderung
mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung
di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas,
misalnya, karbon dioksida, nitrogen, dan ammonia.
2. Air Permukaan
Air permukaan yang meliputi badan-badan air seperti sungai, danau, telaga,
jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami
pencemaran baik oleh tanah, sampah maupun lainnya.
3. Air Tanah
Air tanah (ground water) berasal dari air hujan jatuh ke permukaan bumi yang
kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami
proses filtrasi secara alamiah. Proses-proses yang telah dialami air hujan tersebut,
di dalam perjalanannya ke bawah tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik
dan lebih murni dibandingakan air permukaan.
2.4.4. Kamar Mandi
Kamar mandi adalah Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat
mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kadang-kadang kamar mandi juga
dilengkapi dengan wastafel (tempat cuci tangan) dan juga kakus / closet (tempat
buang air) . Kamar mandi dapat dilengkapi dengan atap, bak air dan pintu. Jalan
masuk ke kamar mandi yang tidak dilengkapi dengan pintu harus dibuat
sedemikian rupa sehingga orang yang sedang mandi tidak terlihat langsung dari
luar. (SNI 03-2399-2002)
Syarat kamar mandi berdasarkan SNI 03-2399-2002 tentang MCK Umum
adalah sebagai berikut
1. Lantai, luas lantai minimal 1,2 m2 (1,0 m x 1,2 m ) dan dibuat tidak licin
dengan kemiringan kearah lubang tempat pembuangan kurang lebih 1%
2. Mempunyai dinding sebagai pemisah antara ruang yang satu dengan yang
lainnya.
tinggi minimal 1,6 m
4. Bak mandi sebagai penampung air untuk mandi harus menggunakan gayung.
5. Ventilasi dan penerangan untuk menjamin terselenggaranya pembaharuan
udara bersih dan penerangan yang cukup dalam kamar mandi, maka harus ada
ventilasi dan harus rnempunyai lubang cahaya yang langsung berhubungan
dengan udara sebagai penerangan alamiah
6. Air bekas mandi dapat dibuang ke sistem saluran atau tangki septik yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Jenis kamar mandi di bagi menjadi 2 yaitu
1. Kamar mandi basah
Kamar mandi basah biasanya mempunyai sebuah wadah penampungan seperti bak,
tempayan atau ember. Dari wadah penampungan air tersebut orang mencidukkan
air dengan gayung yang kemudian disiramkan ke tubuhnya. Kamar mandi seperti
ini paling umum digunakan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena
aliran air tidak selalu terjamin, atau di tempat itu tidak terdapat aliran air, sehingga
dibutuhkan sebuah wadah penampungan dengan air yang siap digunakan setiap
saat.
2. Kamar mandi kering
Kamar mandi kering biasanya menyediakan sebuah tempat khusus untuk orang
yang mandi. Cara mandinya pun berbeda, biasanya menggunakan pancuran
(shower) atau dengan duduk atau setengah berbaring berendam di sebuah bak
mandi yang di sebut bathtub. Bak besar ini kadang-kadang juga ditambah dengan
dilakukan untuk lebih menghemat penggunaan air. Kamar mandi kering paling
banyak ditemukan di negara-negara barat, karena aliran airnya lebih terjamin.
Syarat kamar mandi untuk lansia untuk lansia adalah
1) Pasang pegangan pada dinding kamar mandi, terutama pada sisi pancuran,
toilet, serta bak mandi untuk berendam. Pegangan bisa memudahkan lansia
untuk masuk dan keluar dari bak mandi, dan mengurangi risiko tergelincir.
2) Tempat duduk di bawah pancuran membuat lansia yang tidak kuat berdiri
lama dapat mandi sambil duduk. Pastikan kaki tempat duduk tidak mudah
bergeser di atas lantai licin.
3) Tempatkan alas kaki karet antiselip pada lantai kamar mandi.
2.4.5 Kebersihan Tempat Tidur dan Seprei
Tempat tidur atau ranjang adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan
sebagai tempat tidur atau beristirahat. Sepanjang sejarah, ranjang telah
berkembang dari jenis yang sederhana, seperti kasur yang diisi jerami sampai
perlengkapan mewah yang didekorasi dengan kain-kain.
Para lansia sering mengalami kesulitan untuk berjalan, oleh karena itu
jangan menggunakan terlalu banyak furniture didalam kamar tidur lansia. Pintu
kamar tidut pun dibuat agak lebih luas, untuk mempermudah mereka untuk keluar
masuk kamar dengan menggunakan tongkat atau kursi roda. Jangan juga
meletakkan lemari yang terlalu tinggi karena dapat menyulitkan lansia untuk
mengambil sesuatu dari lemari tersebut, sebaiknya buatlah lemari – lemari yang
pendek tidak melebihi tinggi dari para lansia. Sebaiknya gunakan tempat tidur
makin melengkung akibat tempat tidur terlalu empuk.
Sediakan pegangan di kamar lansia. Pegangan ini akan memudahkan
lansia saat berdiri ataupun berjalan. Material apapun dapat digunakan yang
terpenting keamanan dan kenyaman menggenggam terjaga. Tinggi pegangan
sebaiknya disesuaikan dengan tinggi lansia, biasanya sekitar 70-80cm.
Tempat tidur lansia harus selalu di bersihkan dan di rapikan. Selimut, sprei,
dan sarung bantal juga harus diusahakan supaya selalu dalam keadaan bersih.
Sedangkan kasur dan bantal harus sering dijemur minimal 1 minggu sekali, dan
seprei juga di jemur minimal 1 minggu sekali. (Azizah, 2011)
2.4.6 Sarana Pembuangan Sampah
Sampah adalah benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan dan di buang
atau sesuatu yang tidak di gunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu
yang di buang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan
sendirinya. (Mubarak dan Chayatin, 2009)
Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan
pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan, (sementara, pengumpulan,
pemindahan/pengangkutan, pemprosesan, dan pembuangan sampah) dengan suatu
cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat seperti
teknik (engineering), perlindungan alam (conversation), keindahan dan
pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya, serta mempertimbangkan sikap
masyarakat. Pengelolaan sampah pada saat ini merupakan masalah yang kompleks,
karena makin banyaknya sampah yang dihasilkan, beraneka ragam komposisinya,
masalah lain yang berkaitan (Mubarak dan Chayatin, 2009).
Menurut Chandra (2006), sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:
a. Sampah yang berasal dari pemukiman penduduk
Sampah di suatu pemukiman biasanya di hasilkan oleh satu atau beberapa
keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di kota
atau desa. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa-sisa makanan yang sudah
dimasak ataupun belum atau sampah basah (garbage) sampah kering (rubbish),
abu, atau sampah sisa tumbuhan
b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum
Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat
hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa
sisa-sisa makanan, sampah kering, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus dan
terkadang sampah berbahaya.
c. Sampah yang berasal dari perkantoran atau sarana layanan masyarakat milik
pemerintah
Sampah dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen,
perusahaan, daan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon,
klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering, dan mudah dibakar
(rabbish).
d. Sampah yang berasal dari industry berat dan ringan
Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari
pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi,
tekstil, kaleng, dan sebagainya.
e. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan
Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa
sayur-mayur, batang padi, batang jagung, pupuk, maupun pembasmi serangga.
Menurut Mubarak dan Chayati (2009), jenis sampah padat adalah:
a) Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya.
1) Organik, misal; sisa makanan, daun, sayur, dan buah.
2) Anorganik, misal; logam, pecah belah, abu, dan lain-lain.
b) Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar.
1) mudah terbakar, misal; kertas, plastik, daun kering, kayu.
2) Tidak mudah terbakar, misal; kaleng, besi, gelas, dan lain-lain.
c) Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk.
1) mudah membusuk, misal; sisa makanan, potongan daging, dan sebagainya.
2) Sulit membusuk, misal; plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.
d) Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah.
1) Garbage, terdiri atas zat-zat mudah membusuk dan dapat terurai.\ 2) Rubbish, terbagi menjadi dua:
a) Rubbish mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misal; kertas, kayu, karet, daun kering, dan sebagainya.
b) Rubbish tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik, misal; kaca, kaleng, dan sebagainya.
3) Ashes, semua sisa pembakaran dari industri.
manusia.
5) Dead animal, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
6) House hold refuse, atau sampah campuran (misal; garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.
7) Abandoned vehicle, berasal dari bangkai kendaraan.
8) Demolision waste, berasal dan hasil sisa-sisa pembangunan gedung.
Contructions waste, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung, seperti, tanah, batu, dan kayu.
9) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.
10)Santage solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.
11)Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus
seperti kaleng dan zat radioaktif.
Ada beberapa cara pengelolaan sampah menurut Mubarak dan Chayati (2009),
yaitu:
1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah
Penyimpanan sementara atau pengumpulan sampah yang perlu diperhatikan
adalah konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor, memiliki tutup, mudah di
buka tanpa menotori tangan serta mudah diangkut. Pengumpulan sampah di
lakukan dengan dua metode, yaitu: (a) sistem duet (tempat sampah kering dan
basah); (b) sistem trio ) tempat sampah basah, kering, dan tidak mudah terbakar)
menghasilkan sampah tersebut. Kemudian dari masing-masing tempat
pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke penampungan sementara (TPS)
sampah, dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA).
2. Pemusnahan dan pengolahan sampah
a) Metode yang memuaskan
a. Landfill (ditanam), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang ditanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah.
b. Incenaration (dibakar), yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran khusus.
c. Composting (dijadikan pupuk), yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk, khususnya untuk sampah organik.
b) Metode yang tidak memuaskan
a. Open dumping, yaitu pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka dan dapat menjadi sumber penularan penyakit.
b. Dumping in water, yaitu pembuangan sampah ke dalam air. Hal ini dapat merusak ekosistem air dan dapat menimbulkan penyakit yang di
tularkan melalui air;
c. Burning on premises/individual inceneration, yaitu pembakaran sampah dilakukan di rumah-rumah tangga.
2.5.Kulit
2.5.1 Defenisi Kulit
Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan mempunyai
luar.fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti
pembentukan lapisan tanduk secara terus – menerus (keratinisasi dan pelepasan
sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, serta pembentukan
pigmen untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari. Selain itu
kulit juga berfungsi sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan
dan infeksi dari luar (Azhara, 2011).
Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh, luasnya sekitar
2 m². Kulit merupakan bagian luar yang lentur dan lembut.
Kulit merupakan benteng pertahanan pertama dari berbagai
ancaman yang datang dari luar seperti kuman, virus dan bakteri.
2.5.2 Anatomi Kulit
Kulit merupakan pembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari
pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas
ukurannya, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya 1,50-1,75 m2. Rata-rata tebal
kulit 1-2 mm. Paling tebal 6(mm) terdapat di telapak tangan dan kaki dan paling
tipis (0,5 mm) terdapat di penis (Harahap, 2000).
Menurut Harahap (2000), Kulit terbagi atas tiga lapisan pokok, yaitu:
1. Epidermis
Epidermis terbagi atas empat lapisan yaitu, lapisan basal atau stratum
germinativum, lapisan malpighi atau stratum spinosum, lapisan ganular atau
stratum granulosum dan lapisan tanduk atau stratum korneum.
2. Dermis
kelenjar, folikel rambut, otot, jaringan lemak dan saraf bersama organ akhir
kulit.
3. Jaringan Subkutan (Subkutis atau Hipodermis)
Jaringan subkutan merupakan lapisan yang langsung di bawah dermis.
(Harahap, 2000)
2.5.3 Fungsi Kulit
Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk menyesuaikan tubuh dengan
lingkungan. Fungsi kulit adalah sebagai:
a. Pelindung
Jaringan tanduk sel-sel epidermis paling luar membatasi masuknya
benda-benda dari luar dan keluarnya cairan berlebihan dari tubuh. Melanin yang
member warna pada kulit melindungi kulit dari akibat buruk sinar ultra violet.
b. Pengatur suhu
Di waktu suhu dingin, peredaran darah dikulit berkurang guna
mempertahankan suhu badan. Pada waktu suhu panas, peredaran darah di kulit
meningkat dan terjadi penguapan keringat dari kelenar keringat, sehingga suhu
tubuh dapat dijaga tidak terlalu panas.
c. Penyerap
Kulit dapat menyerap bahan-bahan tertentu seperti gas dan zat yang larut
dalam lemak, tetapi air dan elektrolit sukar masuk melalui kulit. Zat-zat yang larut
dalam lemak lebih mudah masuk ke dalam kulit dan masuk peredaran darah,
karena dapat bercampur dengan lemak yang menutupi permukaan kulit.
Masuknya zat-zat tersebut melalui folikel rambut dan hanya sedikit sekali yang
melalui muara kelenjar keringat.
Indera perasa terjadi di kulit karena rangsangan saraf sensoris dalam kulit.
Fungsi indera peras yang poko yaitu merasakan nyeri, perabaa, panas, dan dingin.
e. Fungsi pergetahan
Kulit diliputi oleh dua jenis pergetahan, yaitu sebum dan keringat. Getah
sebum dihasilkan oleh kelenjar sebaseus dan keringat dihasilkan oleh kelenjar
keringat. Sebum adalah sejenis zat lemak yang membuat kulit menjadi lentur
(Harahap, 2000).
2.5.4. Keluhan Kulit
Salah satu bagian tubuh yang cukup sensitif terhadap berbagai macam
penyakit adalah kulit. Lingkungan yang sehat dan bersih akan membawa efek
yang baik bagi kulit. Demikian pula sebaliknya, lingkungan yang kotor akan
menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit antara lain penyakit kulit
(Harahap, 2000)
Pada penyakit kulit terdapat berbagai keluhan pada kulit, yaitu:
1. Gatal-gatal
Gatal adalah perasaan yang timbul secara spontan ingin menggaruk. Namun
tindakan penggarukan itu sendiridapat mengakibatkan sesuatu yang lebih parah
lagi yakni munculnya kemerahan pada kulit dan goresan. (Harahap,2000)
Gatal-gatal mudah sekali terjadi apabila didukung oleh:
- Kulit berkeringat, gatal-gatal mudah sekali terjadi apabila kulit berekeringat.
Gatal-gatal juga dapat timbul karena kulit terkena benda plastik terlalu lama
atau terkena kain sintesis.
- Pakaian, pakaian yang kotor akan disenangi oleh bakteri yang sudah
- Alergi, beberapa kasus gatal-gatal disebabkan oleh alergi. Walaupun bukan
merupakan faktor dominan, namun hal ini tidak dapat dibiarkan. Alergi
dapat terjadi karena terhirup debu, bulu hewan dan pakaian. Upaya yang
penting dalam pencegahan adalah pola hidup yang baik.
2. Kulit Kemerahan
Kemerahan atau rubor, biasanya merupakan hal pertama yang terlihat didaerah
yang mengalami perdangan.
3. Panas
Panas atau kalor, berjalan sejajar dengan kemerahan reaksi perdangan akut.
4. Bentol-bentol
Salah satu efek dari kelainan kulit pada tingkatan menengah keatas, biasanya
disertai gatal-gatal dan berisi cairan atau nanah.
5. Bercak-bercak putih atau kecokelatan
Adanya bercak-bercak pada kulit yang berwarna putih (hipopigmentasi) atau
berwarna cokelat (hiperpigmentasi).
6. Ruam pada kulit
Ruam adalah kondisi kulit yang ditandai dengan iritasi, bengkak atau
gembung kulit yang diketahui dengan adanya warna merah, rasa gatal, bersisik,
kulit yang mengeras atau benjolan melepuh pada kulit. Beberapa penyebab ruam
adalah akibat alergi, efek samping obat-obatan dan berbagai macam penyakit.
Berikut desksripsi mengenai gambaran struktur lesi kulit pada keluhan
1. Makula
Perubahan warna kulit berbentuk bulatan dengan permukaan rata (bercak
merah). Biasanya berbentuk bulat, oval, atau menyebar di sekitarnya. Makula
merupakan lesi yang dihasilkan dari perubahan dalam lapisan atau komponen kulit
seperti hiperpigmentasi dan kelainan vaskular. Makula dalam berbagai kondisi,
seperti panu, dapat ditemukan dengan skala yang sangat kecil.
Gambar 1. Makula 2. Papula
Papula adalah tonjolan kulit yang padat dengan tidak ada cairan di dalamnya.
Papula memiliki ukuran diameter kurang dari 1 cm. Biasanya berada di lubang
saluran keringat atau folikel rambut.
Gambar 2. Papula
3. Nodul
atau elips dengan ukuran yang berbeda (diameter lebih dari 1 cm), bisa berada di
epidermis atau ke dalam dermis atau jaringan subkutan.
Gambar 3. Nodul
4. Plak
Plak adalah suatu daerah yang menonjol pada permukaan kulit, berbentuk
lempengan dan bulat. Plak sering terbentuk oleh pertemuan papula, seperti pada
psoriasis. Ukuran plak biasanya berdiameter lebih kecil dari 2 cm pada plak kecil
dan lebih besar dari 2 cm pada plak besar.
Gambar 4. Plak
5. Vesikel
Vesikel adalah benjolan yang berisi cairan yang dapat dilihat dan dindingnya
Gambar 5. Vesikel
6. Bula
Bula adalah pengumpulan cairan yang dapat dilihat, berbentuk bulat atau tidak
beraturan. Bula adalah vesikel yang ukuran diameternya lebih dari 0,5 cm.
Gambar 6. Bula
7. Pustula
Pustula adalah timbunan pada kulit yang berisi nanah, berwarna keputihan atau
kekuningan atau bisa kemerahan jika mengandung darah dengan nanah. Bentuk
pustula mirip dengan vesikel. Pustula bisa terjadi atau berkembang dari papula dan
Gambar 7. Pustula
8. Ulkus
Ulkus adalah sebuah lesi yang terjadi karena kerusakan pada epidermis dan
dermis. Ulkus dapat terjadi sebagai akibat dari infark jaringan tubuh, muncul pada
tumor atau benjolan yang disebabkan oleh berbagai agen infeksi seperti bakteri,
parasit dan bakteri.
Gambar 8. Ulkus
9. Bilur (Weal)
Bilur atau weal adalah daerah menonjol yang merupakan hasil dari edema pada
lapisan atas dermis. Bilur berdiameter 3-4 mm, terasa gatal dan berwarna merah
Gambar 9. Bilur
2.5.5. Jenis-jenis Penyakit Kulit
a. Penyakit kulit karena infeksi bakteri adalah skrofuloderma, tuberkolosis kutis verukosa, kusta (lepra), patek. Gangguan kulit karena infeksi bakteri pada kulit yang paling sering adalah pioderma (Harahap, 2000).
Gambar 10. Pioderma
Gambar 11. Scabies
c. Penyakit kulit karena jamur adalah Pitariasis Versikolor (panu), tinea nigra palmaris, tinea kapitis, tinea barbae, tinea korporis, tinea imbrikata, tinea pedis, tinea manus, tinea kruris, kandidiasis, sporotrikosis, aktinomikosis, kromomikosis, fikomikosis, misetoma.
Gangguan kulit karena infeksi jamur pada kulit yang paling sering adalah
Pitariasis Versikolor (panu). Penyebab Pitariasis Versikolor (panu) adalah Malazessia furfur ini akan terlihat sebagai spora yang bundar dengan dinding yang tebal atau dua lapis dinding, ditemukan dalam kelompok bersama pseudohifa
yang biasanya pendek seperti gambaran spaghetti dan meatballs. Pitariasis Versikolor (panu) terjadi bila terdapat perubahan keseimbangan hubungan antara hospes dengan ragi sebagai flora normal kulit. Keadaan yang mempengaruhi
keseimbangan antara hospes dengan ragi tersebut diduga adalah faktor lingkungan
atau faktor suseptibilitas individual. Faktor lingkungan di antaranya adalah lingkungan mikro pada kulit misalnya kelembaban kulit. Sedangkan faktor
individual antara lain adanya kecenderungan genetik, atau adanya penyakit yang
mendasari misalnya sindrom chusing atau malnutrisi (Harahap, 2000).
Lesi Pitariasis Versikolor dijumpai di bagian atas dada dan meluas ke lengan atas, leher dan perut atau tungkai atas/bawah. Lesi khususnya dijumpai
pada bagian yang tertutup atau mendapat tekanan pakaian, misalnya pada bagian
yang tertutup pakaian dalam. Keluhan Pitariasis Versikolor yang di alami penderita adalah adanya bercak/ muncul berwarna putih (hipopigmentasi) atau
kecoklatan (hiperpigmentasi) dengan rasa gatal ringan yang munculnya saat
berkeringat. Pada kulit hitam atau coklat umumnya berwarna putih sedang pada
kulit putih atau terang cenderung berwarna coklat atau kemerahan (Soebono,
Menurut Harahap (2000), Gangguan kulit karena infeksi bakteri pada kulit
yang paling sering adalah dermatofitosis (kurap). Dermatofitosis (kurap) yang terdiri atas tinea kapitis menyerang kulit kepala, tinea korporis pada permukaan kulit, tinea kruris pada lipatan kulit, tinea pedis pada sela jari kaki (athlete's foot), tinea manus pada kulit telapak tangan, tinea imbrikata berupa sisik pada kulit di daerah tertentu, dan Tinea ungium (pada kuku).
Umumnya berbentuk sisik kemerahan pada kulit atau sisik putih. Pada
kuku, terjadi peradangan di sekitar kuku, dan bisa menyebabkan bentuk kuku tak
rata permukaannya, berwarna kusam, atau membiru. Keluhan yang dialami
penderita tinea kapitis, tinea korporis, tinea imbrikata, tinea pedis dan tinea kruris adalah rasa gatal (Harahap, 2000).
d. Penyakit kulit alergi adalah dermatitis kontak toksik, dermatitis kontak alergik,
dermatitis okupasional, dermatitis atopic, dermatitis stasis, dermatitis numularis, dermatitis solaris, pompliks, eritema nodosum dan lain-lain (Harahap, 2000).
Gambar 13. Keluhan Kulit karena Alergi
Pada umumnya keluhan gangguan pada kulit adalah rasa gatal-gatal (saat pagi,
siang, malam, ataupun sepanjang hari), muncul bintik-bintik merah/
bentolbentol/ bula-bula yang berisi cairan bening ataupun nanah pada kulit
permukaan tubuh timbul ruam-ruam.
Menurut Harahap (2000), pada infeksi jamur superficial yang terinfeksi adalah
kulit (epidermis), selaput lendir mulut dan genitalia, kuku, dan rambut. Seseorang
mendapat penyakit ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
a. Predisposisi
b. Pekerjaan
c. Perubahan pH kulit atau metabolisme kulit
d. Daya tahan tubuh seseorang yang menurun
e. Menderita penyakit kronik atau tumor ganas
f. Kebersihan perorangan yang kurang baik
g. Gangguan hormonal
Sumber penularan bisa dari tanah (geophilic), hewan (zoophilic), atau manusia (antrophilic).
2.6. Lanjut Usia (Lansia) 2.6.1 Defenis Lansia
Di Indonesia, istilah untuk kelompok lansia belum baku, orang memiliki
sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah usia lanjut ada pula
lanjut usia. Atau jompo dengan padanan kata dalam bahasa Inggris biasa di sebut
Kategori usia pada lanjut usia terbagi dua yaitu : (1) usia kronologis, yaitu:
di hitung dengan tahun kalender. Misalnya usia pensuin pada umur 56 tahun yang
dianggap mulai memasuki usia lanjut. (2) usia biologis, yaitu: usia sebenarnya di
mana biasanya di terapkan kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia
biologis. (Noorkasiani, 2009)
Lanjut Usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara
tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi,anak-anak, dewasa dan
akhirnya menjadi tua. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa
tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Di masa ini seseorang
mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Azizah, 2011).
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2, yang di maksud dengan lanjut usia adalah
seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas.
Sementara WHO menyatakan bahwa lanjut usia meliputi
usia pertengahan yaitu kelompok 45-59 tahun. Selain itu lansia
adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologi
dan fisik serta kejiwaan dan sosial. Menua (menjadi tua) adalah
suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan
untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya
sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan
memperbaiki kerusakan yang di derita (Nugroho, 2008).
Menurut Nugroho (2000), perubahan yang terjadi pada lansia adalah :
a. Perubahan atau kemunduran biologis
1) Kulit menjadi tipis, kering, keriput dan tidak elastis lagi. Fungsi kulit
sebagai pengaturan suhu tubuh lingkungan dan mencegah kuman-kuman
penyakit masuk.
2) Rambut mulai rontok, berwarna putih, kering dan tidak mengkilat.
3) Gigi mulai habis.
4) Penglihatan dan pendengaran berkurang.
5) Mudah lelah, gerakan mulai lamban dan kurang lincah.
6) Jumlah sel otot berkurang mengalami atrofi sementara jumlah jaringan ikat
bertambah, volume otot secara keseluruhan menyusut, fungsinya menurun
dan kekuatannya berkurang.
7) Pada proses menua kadar kapur atau kalsium tulang menurun akibatnya
tulang menjadi keropos dan mudah patah.
8) Seks merupakan produksi hormon testosteron pada pria dan hormon
progresteron dan estrogen pada wanita menurun dengan bertambahnya
umur.
b. Perubahan atau kemunduran kemampuan kognitif
1) Mudah lupa karena ingatan tidak berfungsi dengan baik.
2) Ingatan hal-hal dimasa muda lebih baik dari pada yang terjadi pada masa
tuanya yang pertama dilupakan adalah nama-nama.
3) Orientasi umum dan persepsi terhadap waktu dan ruang atau tempat juga
mundur, erat hubungannya dengan daya ingatan yang sudah mundur dan
4) Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman skor yang dicapai dalam
test test intelegensi menjadi lebih rendah sehingga lansai tidak mudah
untuk menerima hal-hal yang baru.
c. Perubahan sistem pernapasan
Perubahan sistem pernapasan yang berhubungan dengan usia
yang mempengaruhi kapasitas dan fungsi paru. Peningkatan volume residu paru
dan penurunan kapasitas vital paru dan penurunan luas
permukaan alveoli. Penurunan efisiensi batuk, berkurangnya aktifitas
silia dan peningkatan ruang rugi pernapasan membuat lanjut usia lebih
rentan terhadap infeksi pernapasan.
d. Perubahan kulit
Bertambahnya usia mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit, dimana
epidermis dan dermis menjadi lebih tipis, jumlah serat elastik
berkurang dan kolagen menjadi lebih kaku. Lemak subkutan
terutama di ekstremitas berkurang. Hilangnya kapiler di kulit
mengakibatkan penurunan suplai darah, kulit menjadi hilang
kekenyalannya, keriput dan menggelambir. Pigmentasi rambut menurun
dan rambut menjadi beruban, distribusi pigmen kulit tidak rata dan
tidak beraturan terutama pada bagian yang selalu terpajan sinar
matahari. Kulit menjadi lebih kering dan rentan terhadap
iritasi karena penurunan aktivitas kelenjar sebasea dan
kelenjar keringat sehingga menyebabkan kulit lebih rentan
pajanan sinar matahari yang ekstrim menurun (Nugroho, 2000).
e. Perubahan kardiovaskular
Perubahan struktur jantung dan sistem vaskuler mengakibatkan
penurunan kemampuan untuk berfungsi secara efisien. Katup jantung menjadi
lebih tebal dan kaku, jantung serta arteri kehilangan elastisitasnya. Timbunan
kalsium dan lemak berkumpul di dalam dinding arteri, vena menjadi sangat
berkelok-kelok (Nugroho, 2000).
2.7. Panti Jompo
Panti jompo merupakan suatu institusi hunian bersama dari
para lansia yang secara fisik/kesehatan masih mandiri, akan tetapi (terutama)
mempunyai keterbatasan di bidang sosial-ekonomi. Kebutuhan harian dari para
penghuni biasanya disediakan oleh pengurus panti.
Panti jompo yang dikelola oleh pemerintah memiliki sasaran
pelayanan pada usia lanjut berusia 60 tahun keatas yang tidak
memiliki keluarga, terlantar, tidak mempunyai keluarga yang dapat membantu
kehidupannya sehari-hari, karena kemauannya sendiri atau terpaksa. (Fatimah,
2.8 Kerangka Konsep
Variabel Independen Variabel Dependen
Gambar 14. Kerangka Konsep Karateristik Lansia :
1. Umur
2. Jenis Kelamin 3. Riwayat Penyakit
Terdahulu
Sanitasi Lingkungan Tempat Tinggal :
1.Sarana Air Bersih 2.Kamar Mandi
3.Tempat Tidur dan Sprei 4.Sarana Pembuangan
Sampah
Keluhan Kulit Personal Hygiene