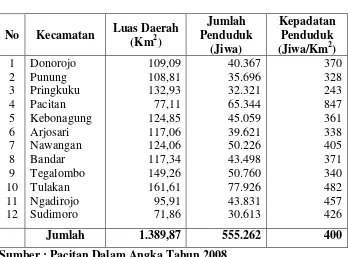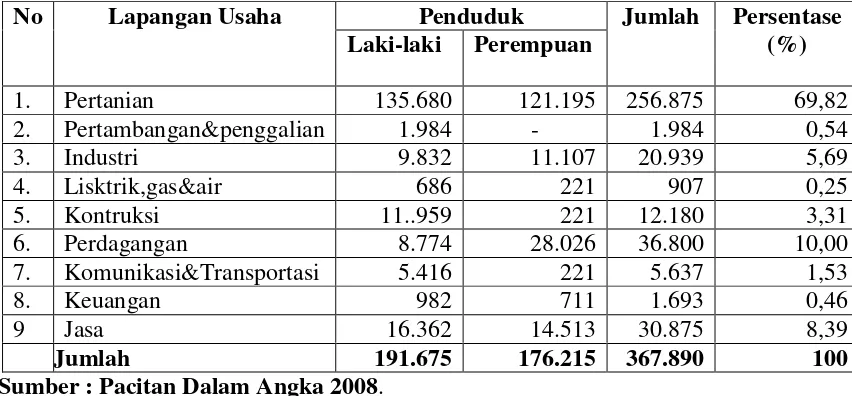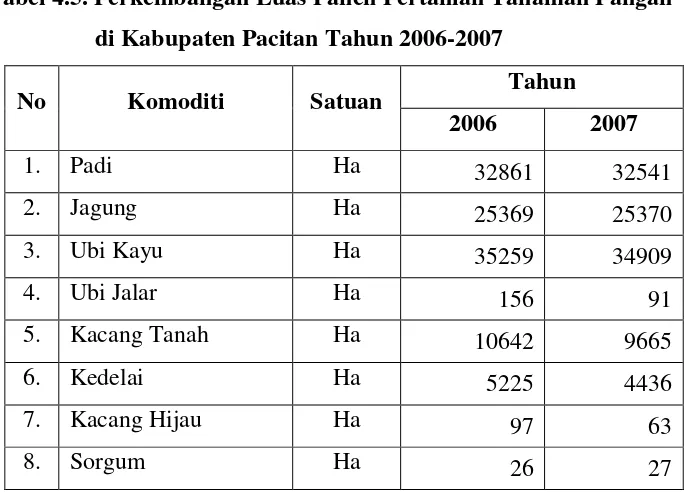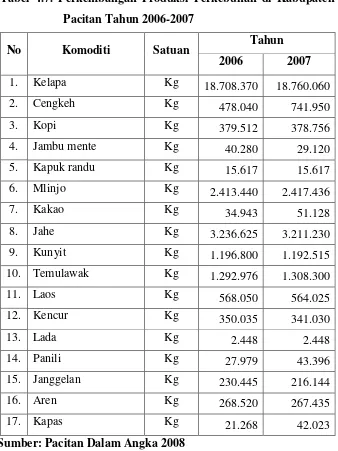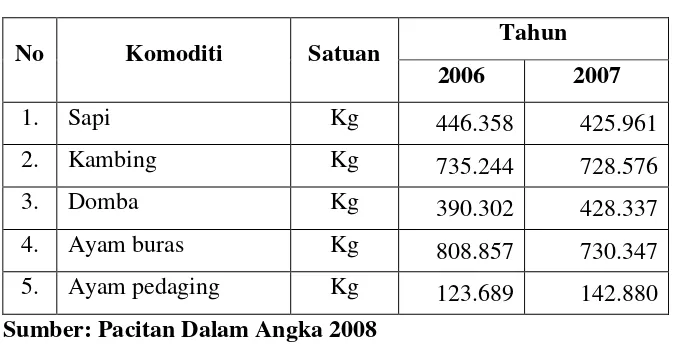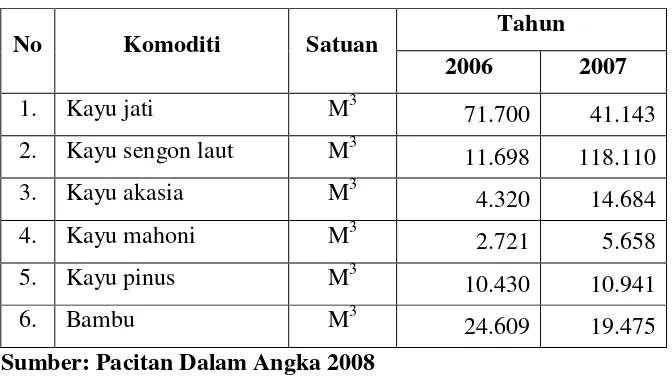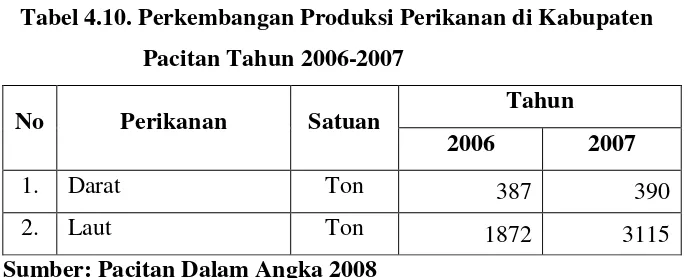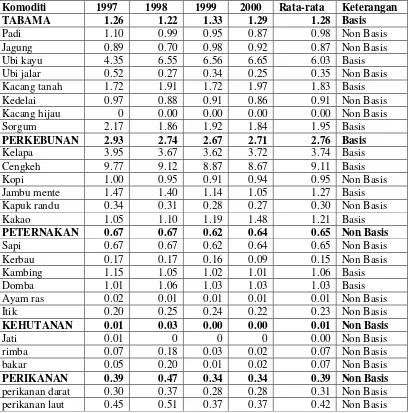Analisis komoditi unggulan
sektor pertanian Kabupaten Pacitan
sebelum dan selama otonomi daerah
Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Ekonomi Pembangunan
Rovina Darmasanti
F1105024
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup
berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan
institusi-institusi nasional, mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,
penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.
Pembangunan mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau
penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman
kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial,
untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang baik, secara
material dan spiritual. (Todaro, 2000:20).
Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia merupakan hakekat pembangunan. Pembangunan
mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan,
dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa
keadilan, rasa sehat; ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat
sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. (Emil
Salim, 1986: 3).
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya
yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah
tersebut (Lincolyn Arsyad,1999: 108).
Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu
produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan
nelayan, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha,
menunjang pembangunan industri serta memperluas pasar baik pasar dalam
negeri maupun luar negeri. Tujuan pembangunan pertanian layak ditempatkan
sebagai prioritas utama agar tercapainya swasembada pangan. Pembangunan
pertanian mengupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada, yaitu
memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.
Pertanian tidak lagi dianggap sebagai usaha tradisional yang berskala kecil,
dan apabila dikelola dengan baik produk yang dihasilkan akan mempunyai
kualitas yang mampu bersaing, sehingga sangat menguntungkan bagi
perekonomian Indonesia.
Sektor pertanian diharapkan mampu memberikan sumbangan yang
berarti dalam peningkatan pendapatan nasional. Sektor ini berperan sebagai
sumber penghasil bahan pangan, sumber bahan baku bagi industri, mata
pencaharian sebagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor
komoditinya bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan
nasional. Penduduk Indonesia yang sebagian besar penghasilannya bergantung
pada bidang pertanian, namun tingkat produksinya tidak dapat memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Penyebabnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam
Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting karena dilihat
dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk pada tahun 2005
yang berjumah 219,3 juta dan diprediksikan akan bertambah sebesar 1,25
persen (Nainggolan, 2006: 78) (dalam Yunastiti Purwaningsih).
Program peningkatan bahan pangan dapat diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan pangan di dalam negeri dari produksi pangan nasional. Unsur-
unsur dari ketahanan pangan antara lain tersedianya pangan dan aksesabilitas
masyarakat terhadap bahan pangan. Jumlah penduduk yang cukup tinggi
selalu menggantungkan penyediaan bahan pangan dari pasar nasional
sehingga tidak ada pilihan lain untuk berusaha membangun sistem ketahanan
pangan yang kokoh pada keragaman sumber bahan pangan lokal. Ketersediaan
dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan
sedangkan aksesabilitas adalah kemampuan bagi setiap individu untuk
memenuhi kebutuhan pangan karena didukung pemasaran yang efektif dan
efisien.
Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan yaitu menjamin
ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan,
kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk
meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang dalam memenuhi
kebutuhan dasar penduduknya selalu mengabaikan keswadayaan, akan
bergantung pada negara lain dan menjadi negara yang tidak berdaulat (Arifin,
2004) (dalam Yunastiti Purwaningsih).
Pertambahan penduduk mendorong perlunya pengadaan pangan yang
produksi pertanian dicapai dengan peningkatan produktivitas disebabkan
karena terbatasnya tanah dan waktu. (Emil salim, 1986:32). Sempitnya lahan
pertanian dan dibangunnya industri-industri maupun bangunan fisik yang
ditandai dengan tidak suburnya lahan akan mengganggu proses kegiatan
pertanian dalam menghasilkan produksi. Pengalihan fungsi lahan dari fungsi
pertanian ke fungsi bangunan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan
pertanian yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya produksi produk
pertanian, terutama pangan. Tenaga kerja di sektor ini juga cenderung
berkurang, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Faktor penyebab
lain yaitu adanya perubahan iklim global yang mengakibatkan bencana alam,
sehingga banyak areal panen menjadi puso, dan produksi menghadapi resiko
berupa ketidakpastian iklim. (Yunastiti Purwaningsih, 2008: 6).
Sektor pertanian mempunyai peranan penting baik di tingkat nasional
maupun regional, namun peranan tersebut menurun sejalan dengan
peningkatan pendapatan perkapita yang mencerminkan proses transformasi
struktural. Penurunan ini disebabkan oleh interaksi dari berbagai proses yang
bekerja antara lain disisi permintaan, penawaran, dan pergeseran kegiatan.
Penurunan sektor pertanian tidak berarti menyebabkan sektor ini kurang
berarti. (Ikhsan dan Arman, 1993) (dalam Ropingi dan Agustono, 2006: 117).
Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara
masih sangat besar. Sebagian besar penduduk Indonesia masih
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Turunnya sektor pertanian
dalam menyumbangkan output nasional dan penyediaan lapangan pekerjaan
perkembangan yang dinamis. Sektor pertanian merupakan penopang bagi
sektor-sektor perekonomian lainnya sehingga pembangunan ekonomi tidak
dapat berpaling dari sektor ini. (Nuning Setyowati dan Mei Tri Sundari, 2005:
57)
Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perspektif
ekonomi makro. Pertama, sektor pertanian merupakan sumber pertumbuhan
output nasional. Studi Herliana (2004) menunjukkan sektor pertanian
memberikan kontribusi 19,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari
keseluruhan sektor perekonomian Indonesia, walaupun secara kuantitas lebih
kecil jika dibanding dengan kontribusi sektor jasa (43,5%) dan manufaktur
(23%) namun sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar
yakni 47%. Kedua, sektor pertanian memiliki karakteristik yang spesifik
khususnya dalam hal ketahanan terhadap guncangan struktural dari
perekonomian makro (Simatupang dan Dermoredjo, 2003) (dalam Andi
Irawan, 2005: 250).
Sektor perekonomian yang mempengaruhi pembangunan daerah di
Kabupaten Pacitan adalah sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman
bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor
kehutanan, dan sub sektor perikanan. Penentuan komoditi unggulan daerah
merupakan salah satu faktor dari pengembangan ekonomi. Pada kenyataannya
hampir di semua daerah mempunyai komoditas unggulan. Pengembangan
komoditas unggulan di semua daerah tidak seluruhnya berjalan sukses karena
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk
menganalisis mengenai komoditi unggulan sektor pertanian di Kabupaten
Pacitan sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi
daerah. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul : ”ANALISIS
KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
PACITAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH ”.
B. Perumusan Masalah
1. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi unggulan ekonomi di
Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?
2. Komoditi pertanian apa saja yang potensial untuk dikembangkan di
Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui komoditi pertanian yang menjadi unggulan ekonomi di
Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?
2. Untuk mengetahuikomoditi pertanian yang potensial untuk dikembangkan
di Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan didalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan
tentang komoditi unggulan yang dimiliki di Kabupaten Pacitan sebelum
dan selama Otonomi Daerah dan untuk melengkapi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
3. Bagi dunia pendidikan, sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Produksi
1. Pengertian Produksi
Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut
input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output.
Proses perubahan bentuk faktor produksi disebut dengan proses produksi.
Produksi pertanian dapat diartikan sebagai usaha untuk memelihara dan
mengembangkan suatu komoditi untuk kebutuhan manusia. Pada proses
produksi untuk menambah guna dan manfaat dilakukan proses penanaman
dari bibit dan dipelihara untuk memperoleh manfaat atau hasil dari suatu
komoditi pertanian.
Proses produksi pertanian menumbuhkan macam-macam faktor
produksi seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan manajemen pertanian
yang berfungsi mengkoordinasikan faktor-faktor yang ada sehingga
benar-benar mengeluarkan hasil produksi (output). Sumbangan tanah adalah
berupa unsur-unsur tanah yang asli dan sifat-sifat tanah yang tak dapat
dirusakan dengan mana hasil pertanian yang dapat diperoleh. Tetapi untuk
memungkinkan diperolehnya produksi diperlukan tangan manusia yaitu
tenaga kerja petani (labor). Faktor produksi modal adalah sumber-sumber
ekonomi diluar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Modal dilihat
dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan nilai sumber-sumber ekonomi
Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab
menghasilkan barang atau jasa harus menentukan kombinasi berbagai
input yang akan dipakai untuk outputnya.
2. FaktorProduksi
Faktor produksi merupakan input yang digunakan dalam proses
produksi, dibidang pertanian output yang dihasilkan dalam bentuk hasil
produksi fisik membutuhkan sumberdaya yang digunakan sebagai faktor
produksi berupa tanah, tenaga kerja, bibit, pupuk serta teknologi sebagai
penunjang dalam usaha tani dengan tujuan menghasilkan output yang
maksimal.
a. Tanah merupakan faktor produksi yang paling penting. Hal ini terbukti
dari besarnya balas jasa yang terima oleh tanah dibandingkan faktor -
faktor produksi lain. Tingkat produktifitas tanah dipengaruhi oleh
tingkat kesuburan tanah, sarana dan prasarana yang ada sebagai
penunjang dalam meningkatkan produksi pertanian. Ada kemungkinan
pemilik faktor produksi tanah menyakapkan tanahnya pada petani
penggarap dengan sistem bagi hasil. David Ricardo dalam Mubyarto
mengungkapkan teorinya tentang sewa tanah deferensial, dimana
ditunjukan bahwa tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan perbedaan
kesuburan tanah, makin subur tanah makin tinggi harganya.
(Mubyarto, 1994: 90).
b. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam usaha
tani. Tenaga kerja adalah manusia yang dengan aktifitasnya
hidup, dalam hal ini adalah syarat hidup yang baik bagi usaha tani.
Tenaga kerja dalam usaha tani tidak hanya mengembangkan tenaga
(labor) saja tetapi juga mengatur organisasi produksi secara
keseluruhan.(Mubyarto,1994:124).
c. Bibit merupakan salah satu faktor produksi sangat menentukan
keberhasilan usaha tani. Pemilihan bibit yang baik dan lahan terhadap
hama sangat menunjang untuk menghasilkan output yang maksimal.
d. Pupuk merupakan faktor produksi yang mendukung keberhasilan
usaha tani. Pupuk dibedakan menjadi dua yaitu:
1) Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari kotoran ternak
atau sisa-sisa mahluk hidup yang karena alam dengan bantuan
mikro organisme mengalami pembusukan.
2) Pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang dihasilkan oleh
manusia melalui proses pabrikasi, dengan meramu
bahan-bahan-bahan kimia yang mengandung kadar hava tinggi.
3. Fungsi Produksi
Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah output
maksimum yang diproduksi dan input yang diperlukan guna menghasilkan
output tersebut dengan tingkat pengetahuan teknik tertentu. (Paul A
Samuelson dan William D Nourdhaus, 1996: 128). Fungsi Produksi
menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari
pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu.
persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat
( dan kombinasi ) penggunaan input-input. (Boediono, 2000: 64).
Q = f (X1, X2, X3,...Xn)
Dimana
Q = tingkat produksi (output)
X1, X2, X3,...Xn = input
Berdasarkan faktor produksi yang digunakan dalam jangka pendek
faktor tenaga kerja dianggap sebagai faktor tetap dan berlaku tambahan
yang semakin berkurang (Law Diminishing Return), produk marginal
setiap unit input akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang
bersangkutan , dengan asumsi semua input lainnya konstan (Paul A
Samuelson dan Willian D Noudous,1996:130). Dalam jangka pendek
perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap
tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya modal seperti mesin
dan peralatan, bangunan perusahaan, sedangkan faktor produksi yang
dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja.
Hukum hasil lebih yang semakin berkurang (The Law of
Diminishing Marginal Return) menyatakan bahwa apabila faktor produksi
yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah
sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak
pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi
tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai negatif. Sifat
pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi
kemudian menurun. (Sadono Sukirno, 2005: 196). Berlakunya hukum ini
disebabkan oleh kelangkaan faktor produksi (makin memburuknya
kualitas input), dan kejenuhan (laju keausan yang meningkat) dari faktor
produksi.
Produksi jangka panjang menggunakan seluruh faktor produksi
yang bersifat variabel. Output diartikan dengan mengubah faktor produksi
atau input dalam tingkat kombinasi yang seoptimal mungkin. Perubahan
input ini memiliki proporsi yang sama atau berbeda. Dalam jangka
panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan sehingga
perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi di pasar.
Suatu isoquant menunjukkan kombinasi yang berbeda dari input
tenaga kerja (L) dan barang modal (K), yang memungkinkan perusahaan
menghasilkan jumlah output tertentu. Isoquant yang lebih tinggi
menunjukkan jumlah output yang lebih besar sedangkan isoquant yang
lebih rendah menunjukkan jumlah output yang lebih kecil. (Dominick
Salvatore, 1995: 150). Isoquant mempunyai karakteristik yaitu di daerah
asal relevan, isoquant mempunyai kemiringan negatif, isoquant cembung
terhadap titik asal dan isoquant tidak pernah saling berpotongan. Kurva
biaya sama menunjukkan semua kombinasi berbeda dari tenaga kerja dan
barang-barang modal yang dapat dibeli perusahan dengan pengeluaran
total dan harga-harga faktor produksi tertentu. Kemiringan kurva biaya
sama ditentukan oleh harga tenaga kerja dan harga barang-barang modal.
4. Teori Biaya Produksi
Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh
perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan
mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang
diproduksi oleh perusahaan tersebut. (Sadono Sukirno, 2005: 205).
Kegiatan produksi dalam mengubah input menjadi output, suatu
perusahaan tidak hanya menentukan input saja yang diperlukan, tetapi
harus mempertimbangkan harga dari input-input tersebut yang merupakan
biaya produksi dari output. Biaya produksi sangat penting peranannya bagi
perusahaan dalam menentukan jumlah output. (Sugiarto, 2002: 248).
Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat
dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi.
Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa
pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan
bahan mentah yang dibutuhkan. Biaya tersembunyi adalah taksiran
pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan
itu sendiri. Pengeluaran biaya tersembunyi antara lain adalah pembayaran
untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang
digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki.
(Sadono Sukirno, 2005: 208).
Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan
jangka waktunya yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi
jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu dimana
input tetap selain dari input variabel. Beberapa konsep yang berhubungan
dengan biaya produksi jangka pendek adalah sebagai berikut:
1. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost = TFC)
Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor
produksi (input) yang tidak dapat diubah jumlahnya walaupun jumlah
outputnya yang dihasilkan berubah.
2. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost = TVC)
Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor
produksi yang dapat diubah jumlahnya.
3. Biaya Total (Total Cost = TC)
Keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam
menghasilkan output. Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap
total dan biaya variabel total.
4. Biaya Marginal (Marginal Cost = MC)
Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi
sebanyak satu unit.
MC = ∆TC / ∆q
5. Biaya Tetap Rata-rata (Average Fixed Cost =AFC)
Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan
output. AFC diperoleh dari membagi biaya tetap total dengan jumlah
output. Karena TFC konstan maka nilai AFC akan semakin kecil jika
output yang dihasilkan semakin bertambah.
6. Biaya Variabel Rata-rata (Average Variabel Cost = AVC)
Rata- rata biaya variabel yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan
output. AVC diperoleh dari membagi biaya variabel total dengan
jumlah output.
AVC = TVC / Q
7. Biaya Total Rata-rata (Average Cost = AC)
Besarnya biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan
output. AC diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah
output.
AC = TQ / C atau AC = AFC + AVC
Biaya produksi jangka panjang adalah jangka waktu dimana semua
faktor produksi dapat mengalami perubahan. Perusahaan dapat
menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Di
dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua jenis biaya yang
dikeluarkan merupakan biaya variabel.
5. Penerimaan Produsen
a. Penerimaan Total (TR)
Penerimaan total produsen dari hasil penjualan output dikalikan
dengan harganya. Secara matematika dinotasikan:
TR = Q . Pq
Dimana:
TR = Total Penerimaan
Q = Jumlah output
b. Penerimaan Rata-rata (AR)
Penerimaan dari unit output yang dijual. Secara matematika
dinotasikan (Boediono, 1996: 95):
AR = TR/ Q
c. Penerimaan Marginal (MR)
Kenaikan dari penerimaan total (TR) yang disebabkan oleh tambahan
penjualan per unit. Secara matematika dinotasikan (Boediono, 1996:
95):
MR = ∆TR / ∆Q
6. Keuntungan Maksimum
Permintaan individu akan suatu komoditi merupakan jumlah suatu
komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu.
Permintaan tersebut tergantung pada harga komoditi itu, pendapatan
nominal individu, harga komoditi lain, dan citarasa individu. Semuanya itu
harus dianggap konstan (asumsi citeris paribus). Penawaran komoditi oleh
produsen tunggal yaitu jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh
produsen tunggal selama periode waktu tertentu. Penawaran tersebut
tergantung pada harga komoditi itu dan biaya produksi untuk produsen
tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi harus
dipertahankan konstan (asumsi citeris paribus) antara lain teknologi, harga
input yang diperlukan untuk memproduksi komoditi itu, dan untuk
komoditi pertanian adalah kondisi iklim dan cuaca. Dalam teori ekonomi,
waktu yang sama dengan jumlah komoditi yang ditawarkan selama
periode yang sama.
Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output dimana
keuntungan yang diperoleh adalah maksimum. Keuntungan adalah
perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total
yang dikeluarkan. Posisi tersebut dinyatakan sebagai posisi ekuilibrium,
karena ada kecenderungan bagi produsen untuk mengubah output dan
harga output. Bila produsen mengurangi atau menambah volume
outputnya (penjualannya), maka keuntungan justru menurun. (Walter
Nicholson, 1991: 251).
Upaya peningkatan produksi tidak akan menguntungkan bila
penggunaan input produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh
dan modal yang dikeluarkan oleh petani. Petani yang rasional tidak hanya
berorientasi pada produksi yang tinggi, akan tetapi lebih menitikberatkan
pada semakin tingginya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh.
Nicholson (1991) menyatakan bahwa petani sebagai produsen yang
rasional akan memaksimumkan keuntungan atau akan menjalankan usaha
tani secara efisien. Keuntungan maksimum diperoleh apabila produksi per
satuan luas pengusahaan dapat optimal, artinya mencapai produksi yang
maksimal dengan menggunakan input produksi secara tepat dan
berimbang. Pemakaian input produksi juga berpengaruh terhadap
pendapatan petani sehingga petani perlu mengetahui dan mengambil sikap
B. Pengertian Pembangunan Ekonomi
Tiga nilai pokok dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu :
1. Ketahanan (Sustenance) merupakan kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, proteksi untuk
mempertahankan hidup.
2. Harga diri (Self Esteam) merupakan pembangunan yang seharusnya
memanusiakan orang. Pengertian dalam arti luas pembangunan suatu
daerah seharusnya meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang
berada di daerah atau wilayah tersebut.
3. Freedom from servitude merupakan kebebasan bagi setiap individu suatu
negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup
masyarakat. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara
dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.
Pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :
1. Suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus.
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang misalnya ekonomi, politik,
hukum, sosial dan budaya. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2
di bidang regulasi (baik formal maupun informal). (Lincolyn Arsyad,
1999:6).
Pembangunan sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial
yang menekankan pada pentingnya pertumbuhan dengan perubahan
khususnya perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. (Mudrajad Kuncoro, 2004:
63)
C. Pembangunan Ekonomi Daerah
1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana
pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakatnya mengelola
sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999:
108).
Tiga pengertian daerah berdasarkan aspek ekonomi yaitu (Lincolin
Arsyad, 1999: 107-108):
a. Daerah Homogen adalah daerah yang dianggap sebagai ruang dimana
kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang terdapat
sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat-sifat-sifat tersebut antara lain dari segi
pendapatan per kapita, sosial-budayanya, geografis, dan sebagainya.
b. Daerah Nodal adalah suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ruang
ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan
c. Daerah Perencanaan atau Daerah Administrasi adalah suatu daerah
yang ruang ekonomi berada di bawah satu administrasi tertentu seperti
satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah ini
berdasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada
penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan
pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi
sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal
(daerah).
Ada empat peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam
proses pembangunan ekonomi daerah yaitu (Lincolin Arsyad, 1999: 120)
a. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan
suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu
usaha sendiri (BUMD). Pemerintah daerah harus dapat mengelola
aset-aset dengan lebih baik sehingga secara ekonomis dapat
menguntungkan.
b. Koordinator
Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk
menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi
pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah bisa mengikutsertakan
lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat
dalam proses penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana,
c. Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui
perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di
daerahnya. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan dan
prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang
lebih baik.
d. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan
pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus. Hal ini dapat
mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut
dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya tetap
berada di daerah tersebut.
2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
Para ahli mengemukakan berbagai teori tentang pembangunan daerah
antara lain (Lincolin Arsyad, 1999: 115).
a. Teori Ekonomi Neo Klasik
Konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu
keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Sistem
perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah apabila modal
bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Modal akan mengalir dari
daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.
b. Teori Basis Ekonomi ( Economics Base Theory)
Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama
dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,
termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan
menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.
Teori basis ekonomi membagi kegiatan ekonomi ke dalam dua
sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan sektor basis
merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya berupa barang
dan jasa yang ditujukan untuk ekspor keluar, regional, nasional, dan
internasional. Kegiatan sektor non basis merupakan kegiatan
masyarakat yang hasilnya berupa barang dan jasa yang diperuntukkan
bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi
masyarakat tersebut. (Rachmat Hendayana, 2003: 3).
Penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia
usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional
merupakan strategi dari pembangunan daerah. Implementasi
kebijakannya mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap
perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan
didirikan di daerah tersebut.
Ketergantungan yang tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar
secara nasional maupun global merupakan kelemahan dari model ini.
Model ini juga berguna untuk menentukan keseimbangan antara
jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk
c. Teori Lokasi
Teori ini mengatakan bahwa lokasi mempengaruhi
pertumbuhan daerah khususnya bila dikaitkan dengan pengembangan
kawasan industri. Pemilihan lokasi yang tepat seperti
memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar lebih dipilih oleh
perusahaan karena dapat meminimumkan biaya. Model pengembangan
industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya
termurah antara bahan baku dengan pasar. Keterbatasan dari teori
lokasi ini adalah teknologi dan komunikasi modern yang telah
mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi
dan distribusi barang.
d. Teori Tempat Sentral
Teori tempat sentral menganggap bahwa ada hirarki tempat
dan disetiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih
kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku).
Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan
jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
Pembangunan ekonomi daerah di perkotaan maupun di
pedesaan dapat menerapkan teori ini, misal perlu pembedaan fungsi
antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah
bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai
e. Teori Kausasi Kumulatif
Teori kausasi kumulatif menunjukkan kondisi daerah sekitar
kota semakin buruk. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperoleh
kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang).
Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif
dibandingkan dengan daerah lainnya.
f. Model Daya Tarik
Teori daya tarik industri merupakan model pembangunan
ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori
ekonomi yang mendasari adalah bahwa suatu masyarakat dapat
memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian
subsidi dan insentif.
D. Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan
untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia dan
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-
sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. (Lincolin Arsyad, 1999: 127).
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat melihat secara
keseluruhan suatu daerah sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya
terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.
Tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah
yaitu (Lincolin Arsyad, 1999: 133).
1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan
(horizontal dan vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian
darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi
akhir dari interaksi tersebut.
2. Perencanaan yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk
daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara
nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misal
administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya berbeda
pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Derajat
pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.
Perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan penggunaan
sumberdaya - sumberdaya pembangunan dengan sebaik mungkin, dan
mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat
daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.
Proses perencanaan pembangunan daerah dapat dipengaruhi oleh dua
kondisi yaitu (Mudrajad Kuncoro, 2004: 47):
1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri
yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan
perekonomian
2. Perekonomian daerah dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh setiap
sektor yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pertumbuhan di beberapa
daerah, misal beberapa daerah mengalami pertumbuhan sedangkan di
Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang
integratif dan komprehensif, artinya bahwa penentuan dan pemilihan prioritas
didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah
harus melibatkan seluruh bidang sosial dan ekonomi serta mengacu pada
kebijakan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah harus berdasarkan pada kondisi
dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
Karakteristik pembangunan daerah terletak pada penekanan pembangunan
yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous
development) dengan menggunakan potensi sumber daya daerah yang ada.
(Gunawan Sumodiningrat, 1997) (dalam Lilis Siti Badriah, 2003:143).
E. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “autos”
yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Daerah otonom sebagai
kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang No 32 Tahun
2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Penjelasan dalam
Undang-Undang tersebut adalah pemberian kewenangan otonomi pada daerah
kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi
Tujuan Otonomi Daerah menurut Undang-undang no 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah adalah Otonomi Daerah diarahkan untuk memacu
pemerataan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan
pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata,
dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah
yang akan memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal.
Di era otonomi daerah dan globalisasi yang sedang terjadi, setiap
daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh daerah
bersangkutan. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang
dimiliki suatu daerah, sehingga akan lebih cepat dan tanggap dalam menyusun
strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sasaran
pembangunan akan terwujud apabila pemerintah daerah mengetahui potensi
daerah dan kawasan andalan serta merumuskan strategi kebijakan
pengembangan produk atau komoditi basis ekonominya. (Ropingi dan
Agustono, 2007: 61).
Pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkan sumber daya
manusia yang handal, mampu bersaing dengan tenaga dari luar daerah dan
mampu untuk mengolah potensi daerah. Sumber daya manusia yang tidak atau
belum berkualitas dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah tidak
berjalan sebagaimana mestinya seperti adanya konflik dan penyelewengan
yang diwarnai oleh menonjolnya kepentingan pribadi dan kelompok. Sumber
berkualitas karena nantinya akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan
otonomi daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah membawa pemerintah daerah
dituntut untuk lebih pro aktif dalam menggali potensi yang ada didaerahnya.
Namun ada kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk mengeksploitasi
sumber daya alam yang ada. Rusaknya sumber daya alam disebabkan karena
keinginan dari pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan daerah,
dimana sumber daya alam yang potensial dieksploitasi secara besar-besaran
tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau kerusakan lingkungan dan
prinsip pembangunan berkelanjutan.
Penyelengaraan pemerintah daerah di berbagai daerah yang
mementingkan kepentingannya sendiri akan menciptakan ego daerah yang
tinggi. Hal ini akan membawa dampak negatif dari otonomi daerah yaitu
setiap daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola pemerintah daerah
sesuai dengan kehendak dan aspirasi daerah sendiri yang cenderung keluar
dari konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Pelaksanaan otonomi daerah semakin memperluas kewenangan
daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerahnya.
Konsekuensi dari semakin meluasnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab,
suatu daerah harus merespon untuk segera menetapkan suatu pandangan baru
perencanaan pembangunan sebagai suatu konsep dasar untuk menjawab
Kebijakan otonomi daerah yang lebih luas membuat kewenangan
daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah
semakin meluas. Perhatian pemerintah daerah harus diperlukan untuk
menghasilkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar
kebijakan pembangunan ekonomi. Para perencana daerah diharapkan mampu
menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan lokal. (Abdul Aziz Ahmad, 2008: 61).
Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi
yaitu pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah. Konsep desentralisasi merupakan kebalikan dari
sistem sentralisasi di mana seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah
pusat. Ciri –ciri dari teori desentralisasi adalah pemerintah lokal harus diberi
otonomi dan kebebasan, dan harus dianggap sebagai wilayah terpisah yang
tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Karakteristik
lainnya adalah pemerintah lokal seharusnya memiliki batas-batas kewilayahan
yang ditetapkan secara hukum, agar tataran administrasi sebuah pemerintah
lokal mampu melaksanakan fungsi-fungsinya yang secara otomatis sinergis
dengan pemerintah lokal lainnya dan memperoleh status kelembagaan yang
F. Penelitian yang Relevan
1. Ropingi dan Agustono, Jurnal SEPA, Vol. 4 No. 1, September 2007.
“PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN BERBASIS
KOMODITI PERTANIAN DI KABUPATEN BOYOLALI
(PENDEKATAN SHIFF-SHARE ANALISIS)”.
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui komoditi
pertanian yang menjadi basis pada masing-masing kecamatan di
Kabupaten Boyolali, mengetahui komponen pertumbuhan komoditi
pertanian di masing-masing kecamatan dan mengetahui jenis komoditi
pertanian dan wilayah pengembangannya di tiap-tiap kecamatan wilayah
Kabupaten Boyolali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang bersifat time series tahun 2004-2005. Data yang dimaksud
adalah data nilai produksi komoditi pertanian dan harga komoditi
pertanian. Penentuan komoditi pertanian basis di tiap-tiap kecamatan
menggunakan analisis Location Quotien (LQ). Dari hasil analisis diketahui
bahwa komoditi pertanian basis yang paling banyak adalah komoditi padi,
kelapa, ayam buras, dan ikan lele. Berdasarkan hasil analisis shiff – share
dari berbagai komoditi pertanian basis diketahui bahwa pertumbuhan
selama tahun 2004-2005 sebesar 8,09%. Pertumbuhan komoditi pertanian
di setiap kecamatan berbeda-beda, ada yang pertumbuhan dibawah
pertumbuhan tingkat kabupaten ada yang dibawah tingkat kabupaten.
Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan beberapa faktor diantaranya
daya dukung sumberdaya, kondisi topografi, kondisi kesuburan lahan,
2. Catur Sugiyanto, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 22 No.4,
Oktober 2007.
”STRATEGI PENYUSUNAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH”
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan
metode penentuan komoditas unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah dengan perbankan. Data yang digunakan oleh pemerintah daerah
adalah komoditi unggulan masing-masing sektor sedangkan dari
perbankan adalah melakukan survei potensi dasar terhadap Usaha Kecil
Menengah (UKM) di daerah. Alat analisis yang digunakan adalah
Revealed Comparative Advantage (RCA). Dari hasil analisis tersebut
diketahui bahwa tidak semua produk unggulan termasuk dalam kelompok
industri primadona yang menggabungkan keunggulan relatif dalam hal:
jumlah usaha, nilai tambah, dan jumlah tenaga kerja dapat mendeteksi
kriteria jenis usaha atau sektor yang primadona maupun sektor yang dapat
menopang menyelesaikan masalah ekonomi daerah (kesempatan kerja dan
pendapatan).
3. Mei Tri Sundari dan Nuning Setyowati, Jurnal SEPA, Vol. 2 No. 2,
Februari 2005.
” ANALISIS BASIS EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PENDEKATAN
ANALISIS LOCATION QUOTIENT”.
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sektor
perekonomian yang menjadi basis di Kabupaten Karanganyar. Data yang
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan
tahun 1993 Kabupaten Karanganyar dan Propinsi Jawa Tengah tahun
1999-2003. Alat analisis yang digunakan adalah LQ. Dari hasil analisis
diketahui bahwa selama tahun 1999-2003 sektor pertanian yang menjadi
basis di Kabupaten Karanganyar adalah sektor industri pengolahan, sektor
listrik, gas dan air minum, dan sektor jasa-jasa. Secara umum sektor
pertanian belum mampu menjadi sektor basis, namun ada subsektor yang
menjadi basis yaitu sektor perkebunan dan peternakan.
4. Rachmat Hendayana, Jurnal Informatika Pertanian, Vol 12, Desember
2003.
”APLIKASI METODE LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM
PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN NASIONAL”.
Tujuan penelitian tersebut adalah membahas penerapan metode LQ
dalam mengidentifikasi komoditas pertanian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series tahun
1997-2001. Data yang dimaksud meliputi data areal panen tanaman pangan,
holtikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan dan populasi ternak.
Dari hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai salah satu teknik
untuk mengidentifikasi penyebaran komoditas pertanian. Dalam hal ini
komoditas yang memiliki nilai LQ > 1 dianggap memiliki keunggulan
komparatif karena basis. Komoditas pertanian yang tergolong basis dan
memiliki sebaran wilayah paling luas menjadi salah satu indikator
5. Lilis Siti Badriah, Jurnal JEBA, Vol. 5 No. 2, September 2003.
“IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI
PROPINSI JAWA TENGAH”.
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sektor-sektor
ekonomi yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Jawa
Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang meliputi data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas
dasar harga konstan tahun 1993 Propinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang
digunakan adalah Location Qoutient (LQ), Model Ratio Pertumbuhan
(MRP), dan Overlay. Dari hasil analisis diketahui bahwa sektor – sektor
ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah secara
keseluruhan terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan
sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang potensial terdiri dari
sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air minum,
sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang unggul tetapi cenderung menurun
adalah sektor jasa-jasa.
6. Ropingi dan Dyah Listiarini, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No.2,
Desember 2003.
” PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN PATI
BERDASAR ANALISIS LQ DAN SHIFF SHARE”.
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sektor-sektor
yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Pati, posisi
peternakan, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pati. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time
series tahun 1998-2001 yang meliputi data Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1993. Alat analis yang
digunakan adalah Location Qoutient (LQ), Shiff share, dan Gabungan LQ
dan Shiff Share. Dari hasil analisis LQ diketahui bahwa yang menjadi
sektor basis adalah sektor Pertanian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan
sektor Keuangan. Berdasarkan dari gabungan analisis LQ dan Shiff Share
diketahui bahwa sektor-sektor unggulan dibagi menjadi enam klasifikasi
yaitu prioritas pertama adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Prioritas
ketiga adalah sektor Industri dan Jasa, Prioritas keempat adalah sektor
Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Perdagangan, dan sektor
Pengangkutan dan Komunikasi dan prioritas alternatif meliputi sektor
G. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan melihat komoditi
unggulan sektor pertanian di Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi
Daerah yaitu pada periode 1997-2007. Sektor pertanian yang terdiri dari sub
sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan,
sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan Komoditi Jawa Timur
Sektor Pertanian
(subsektor Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan
Kehutanan
Komoditi Unggulan Sektor Pertanian
Kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan
Tujuan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten
Pacitan
Keunggulan suatu daerah yang difokuskan pada komoditi unggulan
sektor pertanian dapat diketahui dengan membandingkan satu daerah dengan
daerah yang lebih tinggi kedudukannya, misal propinsi. Penentuan komoditi
unggulan daerah merupakan salah satu faktor kunci pengembangan ekonomi
daerah. Penetapan komoditi unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
biasanya berdasarkan potensi daerah. Potensi suatu daerah dapat berupa
sumber daya alam, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam
proses pembangunan ekonomi daerah. Sehingga dapat memudahkan
pemerintah daerah untuk merumuskan strategi kebijakan agar mampu
melaksanakan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian deskriptif analisis
yang menganalisa komoditi unggulan sektor pertanian. Adapun wilayah yang
diambil sebagai daerah penelitian adalah Kabupaten Pacitan. Kurun waktu
yang digunakan adalah tahun 1997 dan 2007. Kurun waktu tersebut dibagi
menjadi kurun 1997-2000 dimana tahun tersebut merupakan periode sebelum
diterapkan Otonomi Daerah sedangkan kurun 2001-2007 merupakan periode
selama diterapkan Otonomi Daerah.
B. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai
data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil
data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait
dan yang diperlukan. Dalam hal ini buku-buku statistik yang diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan yang merupakan sumber yang
relevan dengan penelitian ini.
C. Definisi Operasional
Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Sektor adalah kegiatan atau lapangan usaha yang berhubungan dengan
bidang tertentu atau mencakup beberapa unit produksi yang terdapat dalam
2. Sub sektor adalah unit produksi yang terdapat dalam suatu sektor
perekonomian sehingga mempunyai lingkup usaha yang lebih sempit
daripada sektor. Sub sektor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sub
sektor dari sektor pertanian.
3. Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang mempunyai proses produksi
khas yaitu proses produksi yang berdasarkan pada proses pertumbuhan
dan perkembangan tanaman dan hewan. Sektor pertanian terdiri dari 5 sub
sektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan,
dan kehutanan.
4. Komoditi unggulan adalah komoditas yang diunggulkan suatu daerah yang
tumbuh dan berkembang dengan baik karena sesuai dengan agroklimat
setempat ( kondisi tanah dan iklim ).
D. Teknik Analisis Data
1. Analisis LQ (Location Quontient)
Analisis Location Quontient digunakan untuk menentukan
subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah.
Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.
(Mudrajad Kuncoro, 2004: 183)
Model analisis ini digunakan untuk melihat keunggulan sektora
dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan wilayah studi
dengan wilayah referensi. Analisis Location Quontient dilakukan dengan
masing-masing wilayah kabupaten atau kota dengan propinsi. (Lincolyn Arsyad,
1999).
Penggunaaan pendekatan LQ dimanfaatkan untuk menentukan
sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan
potensinya. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas
unggulan antara lain adalah penerapannya sederhana, mudah dan tidak
memerlukan program pengolahan data yang rumit. Kelemahannya adalah
data yang digunakan harus akurat. Hasil olahan LQ tidak akan banyak
manfaat jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu data yang
digunakan perlu diklarifikasi dahulu dengan beberapa sumber data lainnya,
sehingga mendapatkan konsistensi data yang akurat. (Rachmat Hendayana,
2003: 4)
Dari hasil perhitungan analisis Location Quontient dapat
dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
a. Jika LQ > 1, maka komoditi yang bersangkutan di tingkat
kota/kabupaten lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan
kota/kabupaten memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan
sebagai komoditi basis.
b. Jika LQ = 1, maka komoditi yang bersangkutan baik di tingkat
kota/kabupaten maupun di tingkat propinsi memiliki tingkat
spesialisasi atau dominasi yang sama.
c. Jika LQ < 1, maka komoditi yang bersangkutan di tingkat
kota/kabupaten kurang berspesialisasi atau kurang dominan
dibandingkan di tingkat propinsi. Komoditi ini dalam perekonomian di
tingkat kota/kabupaten tidak memiliki keunggulan komparatif dan
dikategorikan sebagai komoditi non basis.
2. Analisis Shiff Share
Analisis Shiff Share merupakan teknik yang berguna dalam
menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan
perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan
kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dengan
membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Analisis ini memberikan
data tentang kinerja perekonomian dalam 3 (tiga) bidang yang saling
berhubungan yaitu (Lincolin Arsyad, 1999: 139).
a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis
perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan
perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan
acuan
b. Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan
lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan
untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada
industri – industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian
yang dijadikan acuan.
c. Pergeseran diferensial membantu dalam menentukan seberapa jauh
daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang
dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu
industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya
saingnya daripada industri yang sama pada perekonomian yang
dijadikan acuan.
Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai
perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai
tambah, pendapatan atau output selama waktu tertentu dalam hal ini akan
mempengaruhi pertumbuhan propinsi (N), bauran industri atau industri
mix (M) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan propinsi
disebut pengaruh pangsa pasar (share), pengaruh bauran industri disebut
proporsional shift atau bauran komposisi, sedangkan pengaruh keunggulan
kompetitif disebut regional share atau deferensial shift. Itulah sebabnya
disebut teknik shift share (Prasetyo Soepono dalam Faizal Reza
Salahuddin, 2005:39-44).
Persamaan shift-share untuk sektor i di daerah j adalah :
Persamaan tersebut mengandung pengertian bahwa pertumbuhan PDRB
(Dij) merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh propinsi (Nij), pengaruh
bauran industri (Mij), dan pengaruh keunggulan kompetitif (Cij).
Bila analisis tersebut diterapkan pada nilai (E), maka persamaannya :
Dij = E*ij - Eij
Nij = Eij . rn
Mij = Eij . (rin – rn)
Cij = Eij . (rij - rin)
Dimana :
rij = laju pertumbuhan sektor i di daerah j.
rin = laju pertumbuhan sektor i di propinsi.
rn = laju pertumbuhan PDRB propinsi.
Laju pertumbuhan PDRB propinsi maupun laju pertumbuhan sektor i
di daerah j diperoleh dari :
rij = (E*ij – Eij) / Eij
rin = (E*ij – Ein) /Ein
rn = (E*n – En) / En
Dimana :
Eij = Nilai tambah sektor i di daerah j pada awal tahun analisis.
E*ij = Nilai tambah sektor i di daerah j pada akhir tahun analisis.
Ein = Nilai tambah sektor i di propinsi pada awal tahun analisis.
E*in =Nilai tambah sektor i di propinsi pada akhir tahun analisis.
En = Nilai tambah PDRB propinsi pada awal tahun analisis.
Untuk suatu daerah, pertumbuhan propinsi, bauran industri dan
keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai
keseluruhan daerah, sehingga persamaan Shift-Share untuk sektor i di
daerah j:
Dij = Eij . rn + Eij (rin – rn) + Eij (rij – rin)
3. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Dalam model ini ada dua macam rasio yang digunakan untuk
membandingkan pertumbuhan sektor dalam suatu wilayah studi maupun
wilayah referensi, yaitu :
a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR)
Membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
dengan laju pertumbuhan total sektor wilayah referensi, dengan rumus
(Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah, 2003:148-149):
RPR=
ΔEiR = Perubahan pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal dan
akhir tahun penelitian.
EiR(t) = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun
penelitian.
ΔER = Perubahan pendapatan wilayah referensi pada awal dan akhir
tahun penelitian.
Jika RPr > 1, maka RPr dikatakan (+), berarti laju pertumbuhan sektor
i di wilayah referensi lebih tinggi dari laju pertumbuhan seluruh sektor
di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya.
b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)
Membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi dengan
laju pertumbuhan sektor sejenis di wilayah referensi, dengan rumus
(Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah, 2003:148-149):
RPs =
ΔEij = Perubahan pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal dan
akhir tahun penelitian.
Eij(t)= Pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal tahun
penelitian.
ΔEiR = Perubahan pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal dan
akhir tahun penelitian.
EiR(t) = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun
penelitian.
Jika RPs > 1, maka RPs dikatakan (+), berarti bahwa laju pertumbuhan
sektor i di wilayah studi lebih besar dari laju pertumbuhan sektor
Dari hasil analisis MRP dengan melihat nilai RPR dan RPs akan
diklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dalam empat klasfikasi, yaitu :
1) Nilai RPR (+) dan RPS (+) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat
wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) dan tingkat wilayah studi
(Kabupaten Pacitan) memiliki pertumbuhan yang menonjol.
2) Nilai RPR (+) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat
wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) memiliki pertumbuhan yang
menonjol, tetapi tingkat wilayah studi (Kabupaten Pacitan) kurang
menonjol
3) Nilai RPR (-) dan nilai RPS (+) berarti sektor tersebut pada tingkat
wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) memiliki pertumbuhan yang
kurang menonjol tetapi di tingkat wilayah studi (Kabupaten Pacitan)
memiliki pertumbuhan yang menonjol.
4) Nilai RPR (-) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat
wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) maupun di tingkat wilayah
studi (Kabupaten Pacitan) memiliki pertumbuhan yang rendah.
4. Analisis Overlay
Menurut Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah (2003: 149)
mengatakan bahwa model analisis Overlay ini digunakan untuk melihat
deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs = rasio
a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut
merupakan sektor unggulan karena mempunyai tingkat pertumbuhan
dan tingkat kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat proiritas
dalam pembangunan.
b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut
merupakan sektor yang potensial karena walaupun kontribusinya
rendah tetapi pertumbuhannya tinggi. Sektor ini sedang mengalami
perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk kontribusinya
dalam pembentukan PDRB.
c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut
merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun
karena walaupun kontribusinya tinggi tetapi pertumbuhannya rendah.
Sektor ini menunjukkan sedang mengalami penurunan, sehingga perlu
dipacu pertumbuhannya.
d. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut
merupakan sektor yang rendah baik dari segi pertumbuhan dan
kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A Gambaran Umum Daerah Penelitian
1. Keadaan Geografis
Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 kabupaten yang ada
di wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak di antara 7,550 – 8,170 Lintang
Selatan dan 110,550 – 111,250 Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di
Pantai Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah
dan daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pintu gerbang bagian barat
dari Jawa Timur. Keadaan alamnya sebagian besar berupa bukit dan
gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang
membujur sepanjang Pulau Jawa.
Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah
sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten
Wonogiri (Jawa Tengah).
b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
c. Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
d. Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur).
Secara administratif wilayah Kabupaten Pacitan terbagi dalam 12
kecamatan yaitu Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan
Pringkulu, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan
Tegalombo, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan
Sudimoro. Dilengkapi dengan 166 wilayah desa dan 5 kelurahan.
Kecamatan Sudimoro yang memiliki luas wilayah 71,856 Km2, merupakan
kecamatan yang tersempit di Kabupaten Pacitan, sedangkan kecamatan
yang paling luas adalah Kecamatan Tulakan dengan luas wilayah 161,615
Km2.
Bentuk wilayah adalah bentuk pemukiman wilayah dalam kaitannya
dengan lereng dan perbedaan ketinggian. Jadi aspek yang penting dalam
topografi adalah bentuk relief wilayah yang dicerminkan oleh ketinggian
tempat dan kemiringan lereng.
Secara topografi areal tanah yang ada di Kabupaten Pacitan
digolongkan menjadi 5 (lima) daerah ketinggian di atas permukaan air
laut, yaitu:
a. Ketinggian 0 - 25 m, meliputi wilayah seluas 2,62 %.
b. Ketinggian 25 - 100 m, meliputi wilayah seluas 2,67 %.
c. Ketinggian 100 - 500 m, meliputi wilayah seluas 52,68%.
d. Ketinggian 500 - 1000 m, meliputi wilayah seluas 36,43 %.
e. Ketinggian 1000 m, meliputi wilayah seluas 5,59 %.
Lingkungan fisik topografi wilayah Kabupaten Pacitan dibedakan
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu wilayah selatan pada umumnya berupa batu
kapur, sedangkan dibagian utara berupa tanah. Adapun kandungan
tanahnya terdiri dari Assosiasilitosal, Mediteran Merah Litosal, Campuran
kelabu, endapan tanah liat yang mengandung potensi bahan galian mineral
yang ternyata didalamnya banyak mengandung potensi bahan tambang.
Iklim Kabupaten Pacitan berada disekitar garis khatulistiwa, maka
seperti daerah lain di Indonesia, wilayah ini mempunyai dua musim setiap
tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan
maksimum suhu maksimum rata-rata 330 C, sedangkan suhu minimum
rata-rata mencapai 220 C.
Keadaan hari hujan pada tahun 2007 di Kabupaten Pacitan
meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2006. Hari-hari hujan yang
paling banyak yaitu jatuh pada bulan Februari dan Desember sebanyak
252 hari dan 349 hari, sedangkan rata-rata curah hujan bulan Desember
581mm3. Pada musim kemarau bulan yang paling kering jatuh pada bulan
Agustus karena pada bulan tersebut hanya terdapat lima hari hujan.
2. Distribusi Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan oleh manusia dengan
berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhannya. Kabupaten Pacitan
memiliki luas 138.987,2 Ha, berdasarkan atas distribusi penggunaan tanah
terdiri dari lahan sawah seluas 13.014,26 Ha (9,36 persen) dan lahan
kering seluas 125.971,90 Ha (90,64 persen). Menurut jenis pengairannya
sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan
tadah hujan sebesar 6707 Ha (4,83 persen), lainnya berpengairan irigasi
teknis, irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana. Menurut jenis
penggunaannya sebagian besar lahan kering digunakan untuk tanaman