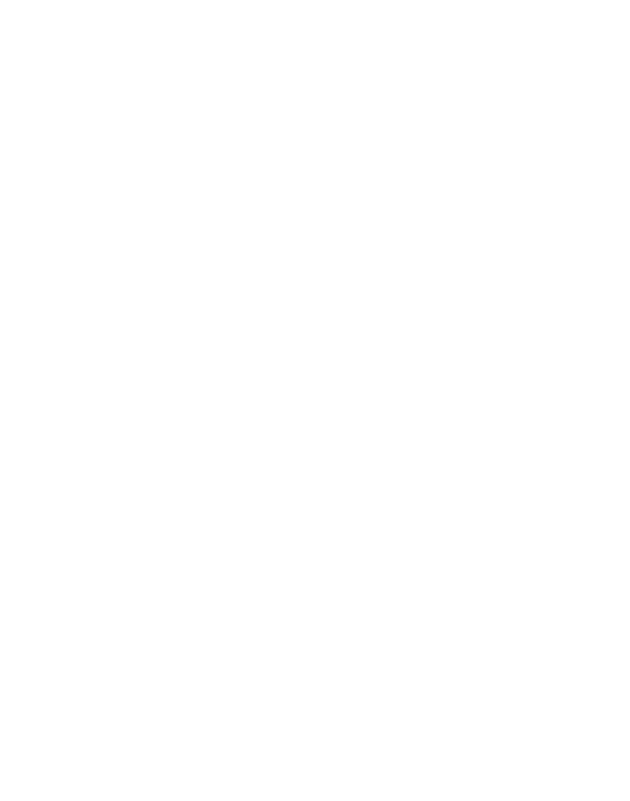AWAL PERADABAN DAN KERAJAAN LUWU
(Sebuah Tinjauan Linguistik Diakronik)
Oleh: Ashari Thamrin
Gambar 1. Peta Kerajaan Luwu Periode 6 Raja (Generasi) Pertama atau Periode Galigo
ABSTRAK
Dari sumber sejarah, tinjauan kebahasaan, dan Epos Lagaligo, diketahui bahwa Peradaban Luwu muncul dari Salu Pongko yakni di wilayah Wotu antara 3.000 hingga 2.000 tahun silam. Diduga, Wotu dahulu kala pernah didiami suku tertua yang bernama To Pongko, namun nama suku ini tidak lagi berhasil diidentifikasi oleh peneliti sejarah, maupun sumber sejarah (penutur). Dari To Pongko lahir 2 (dua) anak suku, yakni To Liu’ (Lowland) dan To Riu’ (Highland) antara 2.500 hingga 2.000 tahun silam. Ke-2 nama anak suku ini juga tak dapat diidentifikasi oleh peneliti sejarah maupun sumber sejarah, tetapi masih dapat diidentifikasi melalui Epos Lagaligo dengan term (istilah) yang berbeda.
Simpelnya, To Pongko (Wotu) melahirkan 2 (dua) anak suku utama. Suku pertama adalah suku To LIU’ (di kenal dalam Epos Lagaligo dengan nama Buriq Liu’) yang akhirnya lebih populer disebut dengan To Luwu. Suku ini berdiaspora dari Wotu ke Muara Salu’ Pongko (sekarang Salo’ Bongko’) dan akhirnya membentuk sebuah peradaban Lowland (dataran rendah) di Pesisir Pantai Malangke, setelah merangkak perlahan melalui Pantai Lemo di Burau. Suku kedua adalah suku To RIU’ (dalam Epos Lagaligo dikenal dengan nama WAWENRIU’ -singkatan dari Wawa INIA Rahampu’u), yang berdiaspora dari Wotu dan akhirnya berkumpul dan membentuk sebuah peradaban Highland (dataran tinggi) di sekitar Danau Matano, setelah merangkak perlahan melalui beberapa sungai, seperti sungai Manurung dan sungai Larona (keduanya di Luwu Timur sekarang).
Perkawinan Batara Guru (La Toge’ Langi’) dengan We Nyili’ Timo dianggap sebagai lambang reunifikasi (penyatuan kembali) 2 (dua) keluarga besar dari suku To RIU (WAWENRIU) dengan suku To LIU (LUWU) yang berasal dari satu nenek moyang To PONGKO (Wotu), yang lama terpisah dan tercerai berai akibat diaspora (penyebaran penduduk/keturunan). Kelahiran BATARA LATTU dari Perkawinan ini dapat dianggap sebagai simbol lahirnya kembali (reinkarnasi) nenek moyang mereka ‘To PONGKO’, sebagai manusia awal yang pernah mendiami Tana Luwu di Wotu. Karena itulah, Reunifikasi keluarga ini dikukuhkan dengan dijadikannya Wotu sebagai Ware’ (Kotaraja) Kerajaan Luwu yang pertama.
PENDAHULUAN
Kerajaan Luwu adalah Kerajaan Tertua di Sulawesi yang amat luas wilayah kekuasaannya. Peta di bawah judul tulisan ini yang dikutip dari tulisan ALBERT SCHRAUWERS dalam buku Houses, Hierarchy, Headhunting and Exchange: Rethinking Political Relations in the Southeast Asian Realm of Luwu' menggambarkan hal tersebut. Penuturan beberapa orang masyarakat Gorontalo di ujung utara bekas kerajaan ini yang mengakui bahwa nenek moyang mereka berasal dari Bugis (Luwu), hanya contoh kecil hegemony kerajaan ini di masa lalu. Dari beberapa Lontara yang kemudian dijadikan catatan sejarah, juga diketahui bahwa Silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat bersumber dari Kerajaan Luwu. Hal tersebut diungkap Andi Zainal Abidin dalam Buku ‘The Emergency of Early Kingdoms in South Sulawesi, 1983: halaman 212, sebagai berikut:
“.... No one in South Sulawesi denies the importance of Luwu’. According to a popular belief and genealogies of the kings and nobility in South Sulawesi, Luwu’ was founded before the formation of Bugis, Makassar and Mandar kingdoms. Several Lontara’ readers estimated that Luwu’ was founded in the thirteenth century, while two Assistant Commissioners of Bone ... estimated, without giving any evidence, that Luwu’ was founded about the twelfth century. According to Couvreur, the Governor of Celeves (1929), Luwu’ was the most powerful kingdom in Sulawesi from the tenth to the fourteenth century. This opinion is supported by the highest respect that the nobility in Luwu’ traditionally enjoyed. Even petty principalities like Selayar, Siang, Lamatti’ and Bulo-Bulo claimed that their first kings had come from Luwu’ ....”
Titik awal peradaban dapat diketahui dari buku Republik Indonesia Propinsi Sulawesi bertarikh tahun 1951. Dalam buku tersebut tertulis bahwa asal-usul orang Toradja sama saja dengan orang' Bugis yang mendiami daerah sekitar Afdeeling Luwu. Kedua suku ini berasal dari Pulau Pongko sekitar 2000 hingga 3000 tahun silam.
Disebutkan pula bahwa melihat tjatatan tahun kedatangan orang Toradja itu di daerah tempat kediaman mereka sekarang, dan memperbandingkan tjatatan tahun turunnja Tomanurung Tamborolangie, jang kira2 1 a 2000 tahun jang lalu, maka agaknja tidak ada suatu alasan positief jang menjangkal, bahwa asal turunan orang Toradja itu sama sadja dengan turunan orang Bugis jang kini mendiami daerah2 sebelah Utara Luwu. Apalagi menurut tjerita tersebut, bahwa Pongko itu terletak disebelah Selatan dari daerah jang didiami oleh mereka sekarang. Djadinja termasuk dalam daerah jang penduduknja terdiri dari orang2 Bugis Luwu. --- Meski keterangan di atas lebih ditujukan kepada asal-usul orang Toraja, namun dengan adanya kata Bugis dan Afdeling Luwu maka sumber ini tetap relevan untuk dijadikan salah satu rujukan utama. Masalah yang timbul dari keterangan tersebut adalah kata majemuk ‘PULAU PONGKO’. Hasil penelusuran Peta Sulawesi Selatan tidak diketahui adanya Pulau Pongko di sebelah selatan, kecuali Pongkor di Bali atau juga Pongkor di Sunda. Adapun kata “PONGKO” di Pulau Sulawesi ini tersebar dari Selatan hingga ke Utara, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Kata PONGKO digunakan untuk menamai gunung, sungai, dan toponim geografis lainnya, namun tak satupun yang menggunakannya untuk nama Pulau di sebelah Selatan. Pulau Pongko adanya di sebelah Utara yakni kabupaten Tojo Una-una.
Pulau terdekat yang ada di Sebelah Selatan Afdeeling Luwu adalah Pulau Liwukang, sedangkan pulau terjauh adalah Pulau Selayar. Timbul dugaan bahwa Pulau Liwukang (sekarang; Libukang) dahulu kala bernama Pulau Pongko. Keterangan yang diperoleh dari masyarakat menyebutkan bahwa Pulau tersebut sebelumnya memang sekian lama menjadi hunian manusia, sebelum generasi terakhir dari Pulau tersebut migrasi ke Penggoli (Palopo). Di Pulau yang mungil ini terdapat kuburan-kuburan tua To Libukang (orang Libukang). Dugaan yang sama berlaku untuk Pulau Selayar. Boleh jadi nama Pulau ini sebelumnya bernama Pongko, kemudian dalam Epos Lagaligo dikenal dengan nama Silaja. Bahasa orang Selayar pun mirip dengan bahasa Wotu, suku yang dianggap paling tua di Luwu, atas dasar bahasa yang digunakannya yang tidak digunakan di tempat lain. Laporan hasil eskavasi arkeologi pun menempatkan Selayar diurutan lebih tua –secara radio karbon- dibanding hasil eskavasi arkeologi di Wotu pada khususnya, dan Luwu pada umumnya.
Keyakinan paling kuat atas masalah ersebut adalah telah terjadi kesalahan ketik ataupun kesalahan tutur dari sumber sejarah. Yang dimaksud dengan Pulau Pongko dalam keterangan itu adalah SALU’ PONGKO yang secara geografis berada di Malangke. Salu’ Pongko artinya Muara Sungai, jenis tutur bahasa yang menggunakan hukum DM. Jika diubah dalam Hukum MD menjadi PONGKO SALU, atau PENGKASALU (Bhs. TAE). Keyakinan ini sejalan dengan kutipan dari Blog Anak Bugis Dijemput Di sini, yang menuliskan bahwa: “... ada satu bahasa yang dipergunakan oleh penduduk satu kampung saja, namanya "bahasa Wotu", untuk kampung Wotu sendiri...”.
Dalam linguistik diakronik, untuk menentukan suku tertua di suatu wilayah, atau suku mana yang menjadi sumber asal dari suku-suku lain di sekitarnya, dapat diketahui dari seberapa banyak suatu bahasa dari sebuah suku dipengaruhi oleh kosa kata bahasa-bahasa lain di sekitarnya. Semakin sedikit pengaruh, -atau bahkan nol- maka semakin tua bahasa suku tersebut. Wotu begitu dekat dengan Salu Pongko dan sekerabat dengan Suku To Luwu, salah satu suku tertua di Luwu yang pernah mendiami daerah Pabbiringeng, Malangke. Tidak keliru jika kita meyakini bahwa di Wotu zaman dahulu, hidup sebuah komunitas awal yang
bernama ‘To Pongko’, yang kemudian melahirkan suku To Luwu dan dan To Riu, dan suku-suku tua lainnya di sekitar wilayah tersebut yang tidak dapat lagi dideteksi oleh peneliti sejarah, ataupun penutur sejarah.
Kesulitan identifikasi ini terkait anak-anak To Luwu yang menyempal ke jazirah Selatan Teluk Bone hingga membentuk identitas diri sebagai To Ugi (suku Bugis), kemudian kembali ke kampung leluhur mereka di Luwu sejak abad ke 15. Akibat arus balik ini, beberapa tempat bersejarah yang seharusnya dipertahankan nama aslinya, kini berganti nama menyesuaikan lidah anak suku tersebut. Sebagai contoh, SALU PONGKO (Muara Sungai) yang dijelaskan di atas sebagai sumber asal peradaban, kini telah berubah nama menjadi SALO’ BONGKO (Sungai Udang).
PERIODESASI KERAJAAN
Kutipan dari Abidin pada bagian Pendahuluan di atas menempatkan tarikh Kerajaan Luwu berada pada abad ke 10 hingga ke-14 Masehi. Sementara keterangan-keterangan dalam Epos I Lagaligo yang berceritera tentang Senrijawa (Sriwijaya), Sunra (Sunda), Bakke (Bangka), Gima (Bima), Kerajaan-kerajaan Bate Salapang di Makassar dan beberapa kerajaan Nusantara yang sezaman dengan itu menempatkan tarikh kerajaan ini berada pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi.
Keterangan ini dikuatkan dengan Laporan Arkeologi David Bullbeck yang dikutip dari Van der Hoop 1941:319, bahwa: “... A waste piece of cast glass found 60 cm beneath the soil near Palopo (van der Hoop 1941:319) offers some evidence of advanced pyrotechnology in Luwu by 1000 years ago. Maksudnya, sekitar 1000 tahun lalu Palopo pernah menjadi sentra industri ‘pyrotechnology’ atau pencetakan gelas dan kaca.
Keterangan di atas diperkuat pula dengan silsilah raja Gowa-Makassar versi Inggris yang menenempatkan Sawerigading sebagai raja ke- 3 yang bertahta pada abad 1000 Masehi. Dua Raja yang mendahului Sawerigading adalah Batara Guru dan Batara Lattu, merupakan Raja yang sama yang memimpin Kerajaan Luwu. Berikut Silsilah Raja Gowa menurut Forum Award Clasical Studies, Britannica Internet Guide Award:
First Dynasty : # Batara Guru I # Batara Lettu # Saweri Gading………..fl. c. 1000 ? # Letta Pareppa # Simpuru Siyang # Anekaji # Punyangkuli # La Malolo Second Dynasty :
# Ratu Sapu Marantaiya……….fl. c. 1100 ? # Karaeng Katangka I
# Ka-Karaeng-an Bate Salapang : 1. Karaeng Garassi 2. Karaeng Katengang 3. Karaeng Parigi 4. Karaeng Siang………..fl. c. 1200 ? 5. Karaeng Sidangraye 6. Karaeng Lebangan 7. Karaeng Panaikang 8. Karaeng Madulo 9. Karaeng Jampaga
Sumber: http://my.raex.com/~obsidian/seasiaisl.html Silsilah di atas memang masih diperdebatkan. Penyusun silsilah ini pun tidak menjamin keabsahan tulisannya, sehingga beberapa diantaranya diberi tanda tanya. Apalagi dalam Lontara Gowa dan Tallo telah tertulis silsilah raja Gowa Kuno dengan 4 (empat) orang Raja sebelum Bate Salapang, yakni: (1) Batara Guru; (2) Sariqbattanna tunabunoa Tolali; (3) Ratu Sa(m)pu Mara(n)taiya; (4) Karaeng Katangka. Menurut tafsiran J. Noorduyn dan kemudian diteruskan oleh AZ. Abidin, Raja kedua dari Gowa Kuno ini adalah Saudara dari Batara Guru. Kemudian dalam Epos Lagaligo, saat Sawerigading memasuki istana baru di Ware’ beberapa nama kerajaan yang berada di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan (sekarang) turut diundang, seperti Mattoanging, Sawammeqga (Saumata), Kalling, dan Makka ri Ajang (Makassar sekarang).
Periode Sawerigading yang ditempatkan pada abad ke -10 Masehi ini terbantahkan oleh tutur masyarakat tentang pertemuan Sawerigading dengan Nabi Muhammad. Namun ada kesimpulan penting yang dipetik dari keterangan di atas, yakni Luwu dan Makassar pada masa Batara Guru dan Batara Lattu serta beberapa Raja sesudahnya (di luar Sawerigading) adalah 2 (dua) wilayah kerajaan dengan 1 (satu) pemerintahan. Hal tersebut dikuatkan dalam Lontara Makassar sebagai berikut:
“Lanri niana kananna angkana : Tanajawakko kuta’nang tonji pangngassenna maggauka ri
Bone Na iya pakkuta’nannu kanamako inai uru manurung ri Luwu napunna najawa’ kanamako inai uru makkasara ri Luwu, inai butta Luwu, inai Limanna buttaya ri Luwu, inai pocci’na buttaya ri Luwu, inai bangkenna buttaya ri Luwu, punna tana assenga najawa’ sikammaya tayyai antu asana manurunga ri Luwu naungi antu ri empoanna. Napunna lebba'mo pa'kuta'nannu ri Karaengan ri Luwu kuta'nang tongi seng Karaenga ri Gowa siagadang Ma'gauka ri Bone, napunna tanajawakka sikamma anjo pa'kuta'nanga naungi antu ri empoanna ngaseng sikamma-kammaya.
Gambar 2. Aksara kuno Lalembate atau Lalebbata atau Laklakbatak digunakan di Malangke abad ke-10
Transliterasi I Lagaligo asli dari Van Sirk melukiskan ‘Teologi Batara Guru’ yang begitu mirip –tapi tak sama- dengan ‘Teologi Islam’ yang diajarkan oleh Muhammad. Begitu pun tutur masyarakat yang mengaitkan pertemuan Nabi Muhammad dengan Sawerigading, sehingga meninggalkan bekas keyakinan di Cerekang, Bawakaraeng dan To Lotang, atau juga keyakinan yang dianut oleh Bissu Puang Matoa Saidi tentang “Nur Muhammad”, menempatkan tarikh kerajaan ini sebelum dan sesudah kelahiran Muhammad SAW, yakni sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi.
Keterangan dari Van Sirk tentang aksara Pallawa yang digunakan dalam Epos Lagaligo (yang asli, berkode BC -Bugis Christomatie) menguatkan tutur masyarakat bahwa Kerajaan ini bertarikh antara abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Sebab dalam Genealogy Script (Silsilah Aksara International) dituliskan bahwa Aksara Pallawa yang berasal dari India ini digunakan antara tahun 400 Masehi hingga munculnya aksara Kawi pada tahun 775 Masehi.
Gambar 3. Aksara Pallawa (Kamboja) yang digunakan pada Lagaligo
Sementara itu, keterangan dari David Bullbeck bahwa aksara yang digunakan adalah ‘Indic Script’ atau ‘Brahmi’ (aksara India), justru menempatkan kerajaan ini pada abad 600 tahun sebelum Masehi hingga munculnya aksara Pallawa tahun 400 Masehi, jauh lebih tua dari perkiraan semua orang selama ini. Berikut kutipan silsilah aksara Asia Tenggara yang berasal dari India, beserta periode kemunculan dan pemakaiannya:
2.1.1.1. Brahmi abugida - c. 600 BC (India, Sri Lanka) 2.1.1.1.3. Pallava abugida - c. 400 (S. India)
2.1.1.1.3.3. Old Kawi abugida- c. 775 (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.1. Javanese abugida - c. 900 (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.2. Balinese abugida - c. 1000 (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.3. Old Sundanese abugida - c. 1300 (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.3.1. Formal Sundanese abugida - 1997 (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.4. Batak abugida - c. 1300 (Indonesia)
2.1.1.1.3.3.5. Baybayin abugida - c. 1300 (Philippines) 2.1.1.1.3.3.6. Buhid abugida- c. 1300 (Philippines) 2.1.1.1.3.3.7. Hanunó'o abugida - c. 1300 (Philippines) 2.1.1.1.3.3.8. Tagbanwa abugida - c. 1300 (Philippines) 2.1.1.1.3.3.9. Lontara abugida - c. 1600 (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.10. Rejang abugida - ? (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.11. Lampung abugida - ? (Indonesia) 2.1.1.1.3.3.12. Kerinci abugida - ? (Indonesia)
Laporan Arkeologi OXYS dan beberapa laporan-laporan arkeologi lain yang mendahuluinya menyatakan bahwa di Seko dan Matano telah dilakukan aktivitas tambang Metalurgy berupa Besi dan Nickel sejak 2000 tahun silam, semakin menambah kebingungan kita menetukan periodesasi awal Kerajaan Luwu ini. Andai saja hal ini hanya sebagai asumsi atau dugaan, maka kita dapat mengabaikannya dalam rangka penentuan Periodesasi Peradaban Kerajaan Luwu masa lampau. Tapi ternyata tidak, laporan arkeologi untuk pernyataan ini memang telah ada sebelumnya. Bahkan laporan arkeologi yang menyatakan bahwa peradaban di
wilayah ini lebih tua dari zaman exploitasi besi 2000 tahun silam, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Temuan tertua dari tabel di atas berupa 10 unit ‘charcoal’ atau arang untuk kremasi atau pembakaran mayat di dapat di daerah Sabbang bertarikh abad 410 SM hingga 430 Masehi . Sementara temuan termuda berupa 3 buah tulang dan gigi ditemukan di Salabu bertarikh 1430 Masehi hingga 1640 Masehi.
Nah, mengikut pada beberapa keterangan sejarah, Epos Lagaligo, dan laporan arkeologi di atas dan dengan berbagai pertimbangan, dapat disimpulkan tentang periodesasi Peradaban dan Kerajaan Luwu, dibagi sebagai sebagai berikut:
1. Peradaban dimulai antara 3000 hingga 2600 Masehi.
2. Kerajaan Wawenriu’ (Matano), Kerajaan Luwu Kuno (Malangke) dan Kerajaan Tompotikka (Palopo) telah ada sebelum 400 Masehi. Ke-3 kerajaan ini akan dibahas dibagian akhir tulisan ini.
3. Kerajaan Luwu Periode Galigo dengan Batara Guru sebagai Datu pertama diikuti empat generasi sesudahnya dimulai sekira 400 Masehi hingga 1100 Masehi. Ibukota Pertamanya di Ussu’, disekitar sungai Manurung kemudian dipindah ke Wotu ketika Batara Lattu naik Tahta.
4. Kerajaan Luwu Periode Lontara dengan Simpurusiang sebagai Datu pertama dimulai sejak 1100 Masehi hingga tahun 1945 saat Datu terakhir Andi Djemma menyatakan bergabung ke NKRI. (Belum dibahas dalam tulisan ini, dan akan dibahas kemudian) SUKU DAN BAHASA
Pelras dalam The Bugis, Catatan Kaki No. 9 di halaman 124 mengatakan: "Sebenarnya, pada mulanya, kerajaan Luwu’ bukan kerajaan Bugis, melainkan kerajaan multi-etnis, yang lama kelamaan, sebagai akibat proses perkawinan antar bangsawan tinggi se-Sulawesi Selatan, akhirnya dipimpin oleh sebuah elite yang mengaku Bugis. Dalam sure’ Galigo, tampak jelas bahwa penduduk Tanah Bugis tidak mengerti pembicaraan orang Luwu’, dan dalam Sejarah
Wajo’, sekurang-kurangnya sampai abad ke-15, orang Luwu’ dan orang Bugis masih dibedakan.”
--- Dari Wikipedia bahasa Indonesia dituliskan bahwa Bahasa Luwu adalah suatu bahasa yang digunakan di Tana Luwu, salah satu suku bahasa dari lebih sepuluh suku bangsa yang mendiami Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Bahasa Luwu ini digunakan oleh sebagian besar penduduk dari Tana Luwu, dari empat kabupaten dan kota, masing-masing kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan kota Palopo. Bahasa Luwu, termasuk serumpun dengan bahasa Toraja. Bahasa Luwu ini digunakan selaku bahasa percapakan penduduk setempat, mulai dari Selatan perbatasan dengan Buriko Kabupatan Wajo sampai dengan daerah Kabupaten Luwu Timur Malili.
--- Dari Blog Anak Bugis Dijemput Di sini, diketahui bahwa Malaysia familiar dengan nama 5 anak Raja Bugis dari Luwu, Daeng Parani, Daeng Manambung, Daeng Marewa, Daeng Celak dan Daeng Kamase. Kelimanya putra Daeng Kamboja. Dan karena Luwu adalah satu kerajaan Besar yang kuat yang sangat tua di jantung pulau Sulawesi/Selebesi (penamaan dari Sele' atau keris dari besi) dan silsilah Raja Raja Bugis Makassar berasal dari Luwu'. Penduduk Asli kerajaan Luwu, terbagi dalam beberapa suku suku kecil yaitu: (1) Bugis, (2) Toraja, (3) Torongkong, (4) Bela, (5) Baree, (6) Mekongga, (7) Bajo (Bajau).
Tiap suku suku itu, mempunyai bahasa sendiri sendiri, misalnya: Bahasa Bugis, Bahasa Toraja, Bahasa To Rongkong, Bahasa Bela, Bahasa Baree, dan Bahasa Mekongga. Malah ada satu bahasa yang dipergunakan oleh penduduk satu kampung saja, namanya "bahasa Wotu", untuk kampung Wotu sendiri. Bahasa yang banyak dipakai adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Toraja, karena kedua bahasa ini dianggap bahasa penghubung dalam masyarakat Luwu. Dan kitab I La Galigo Luwu' juga ditulis dalam bahasa Bugis Kuno. Suku Rongkong umumnya terdapat didaerah Masamba, terutama dikecamatan Rampi, dan sedikit di kecamatan Wara (Palopo) di kampung Lebang. Suku Toraja (yang sudah memisahkan diri dari Luwu) terdapat di bahagian Makale dan Rante Pao, dan di Kewedanaan Palopo di Pantilang dan Rante Balla. Suku Bela dan Baree, terdapat di Kewedanaan Malili, terutama di Kecamatan Wotu dan Nuha. Suku Mekongga, terdapat di seluruh daerah Kolaka, DAN SUKU BUGIS, TERDAPAT DI SEMUA DAERAH LUWU, terutama di daerah-daerah pantai. Suku Bajo, tempatnya hanya dilautan dan sangat kurang jumlahnya.
--- Keterangan dari Dian Cahyadi1 yang tidak Ia sebutkan sumbernya mengatakan:
Tana Lu'u (Luwu) asalnya didiami oleh suku To A'a (To A' atau To Awa atau To La'lang) disekitar wilayah Masamba hingga Wotu. Anak suku dari To Rampi O atau Rampi skg, persilangan dari suku To Mpere O' (sdh hilang) sempalan dari suku To Alan dari wilayah Wera atau Wai Ra' (sekitar danau To Wuti) kemudian lebih dikenal sebagai To Wuti (Woite). Rampi sempalan dari suku BoliO di wilayah danau Poso. Di daerah selatannya (Baebunta = Baabanta) hingga Larompong (Ara) didiami oleh suku To Alang (To Ala')(?) anak suku dari To Raya Tae' (To Ta') dan puluhan perkampungan dengan sebutan kaum tiap kampung. Dalam Genealogy (silsilah) Bahasa Austronesia terungkap bahwa Bahasa TAE dan Bahasa BARE’E berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya, dari hasil akulturasi penutur bahasa TAE dan Bahasa BARE’E, maka lahirlah bahasa MAKASSAR. Bahasa Makassar melahirkan bahasa WOLIO, dan bahasa Wolio melahirkan Bahasa BUGIS dan Bahasa MANDAR. ---
DIAKRONIK
Melihat dari tutur bahasa yang digunakan di bekas-bekas peradaban Kerajaan Luwu masa lalu sesuai peta di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) kelompok besar jenis bahasa yang pernah digunakan. Kelompok pertama yaitu jenis bahasa yang banyak menggunakan vokal ‘O’. Penutur bahasa-bahasa ini bermukim di Gorontalo hingga ke sekitar Danau Poso, Sulawesi Tengah. Bahasa ini lebih cenderung dimasukkan sebagai rumpun bahasa CEBUANO, serumpun dengan bahasa-bahasa yang di pakai di Sulawesi Utara dan di beberapa tempat di Sulawesi Tengah. Rumpun bahasa ini diturunkan dari bahasa MARANAO (MINDANAO), Filipina Selatan.
Hegemony bahasa bervokal ‘O’ mendapat saingan ketat dari bahasa tetangganya yang justru banyak menggunakan vokal ‘E’. Penutur bahasa ini mendiami wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa titik di Sulawesi Tengah. Sedangkan titik temu antara kedua hegemony ini adalah terlihat pada penutur bahasa yang agak seimbang menggunakan vokal ‘O’ dan vokal ‘E’, yang pengaruhnya dimulai di sekitar Danau Poso, Pamona, Matano hingga ke Wotu (Luwu Timur). Hegemony bahasa campur ini memanjang hingga ke bekas kerajaan WOLIO di Sulawesi Tenggara.
Dalam Genealogy bahasa-bahasa Austronesia, bahasa campur ini disebut sebagai bahasa BARE’E, yang dianggap sebagai Saudara kembar bahasa TAE’. Kosakata bahasa BARE’E di sekitar Danau Matano yang berbanding 65% bahasa Melayu dan 35% bahasa Cebuano, menyebabkan bahasa ini lebih cenderung dikategorikan sebagai turunan bahasa Melayu ketimbang bahasa Cebuano.
Selain perbandingan kosakata tersebut, hal yang paling penting yang tak dapat diingkari oleh penutur bahasa BARE’E di sekitar Danau Matano adalah mereka anak suku pertama yang menyempal dari suku induk To Pongko (Wotu), bersamaan dengan penyempalan suku To Luwu dari induk yang sama. Sebelum membentuk peradaban di sekitar Danau Matano serta bahasa identitas mereka (BARE’E), penyempalan penutur vokal campur ini, awalnya merangkak dari Wotu ke arah utara dan timur kemudian menyusur 4 (empat) muara lembah sungai di Luwu Timur, yakni muara Sungai Cerekang, muara sungai Manurung, muara sungai Ussu, dan muara Sungai Larona. Penyusuran ini bergerak perlahan dan memakan waktu antar 500 tahun hingga 1 (satu) millenium (1000 tahun), hingga keturunan masing-masing mencapai hulu (Puncak) ke-4 (empat) sungai tersebut.
Singkatnya, setelah mencapai 4 hulu sungai ini, diaspora anak-anak To Pongko dari hulu ke arah Timur justru berlangsung lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena di daerah hulu, mereka tidak terhambat oleh derasnya aliran sungai yang disebut di atas, banyaknya rawa, rimbunnya hutan dan semak belukar liar di dataran tengah. Percepatan diaspora ini menyebabkan mereka kembali bertemu di sekitar Danau Matano dan membentuk sebuah Peradaban Highland (Dataran Tinggi). Pergerakan ini tidak terhenti sampai di situ, mereka terus melakukan penetrasi ke berbagai arah, termasuk ke arah utara hingga mereka bertemu dengan penutur vokal ‘O’ di sekitar Danau Poso, Pamona, dan beberapa titik yang saat ini masuk dalam wilayah Sulawesi Tengah. Pada saat itulah Bahasa BARE’E mulai terbentuk.
Sementara itu pergerakan mereka dari atas hulu ke arah Barat menyebabkan mereka bertemu dengan anak-anak To Pongko lainnya yang sebelumnya telah membentuk peradaban Lowland (dataran rendah) di muara Salu’ Pongko (Salo’Bongko’). Reuni di dataran tinggi tersebut, selain memberi andil untuk terciptanya beberapa anak suku lain, seperti To Rongkong, To Seko, To Limbong, To Riaja (Toraja) dan sebagainya, reuni ini juga memberi andil yang signifikan untuk terbentuknya bahasa TAE’, sebagai turunan dari bahasa To Luwu di Malangke yang bersumber dari bahasa To Pongko di Wotu. Bahasa TAE ini akhirnya digunakan sebagai bahasa tutur (lingua Franca) dari anak-anak suku Highland yang telah disebutkan di atas.
--- Penyempalan penutur vokal campur yang diuraikan di atas bersamaan dengan penyempalan penutur vokal ‘E’ dari To Pongko (Wotu) yang awalnya merangkak dari Wotu. Sebelum membentuk sebuah peradaban, penyempalan penutur vokal campur ini, awalnya merangkak dari Wotu ke arah Barat, menyusur berbagai muara sungai seperti; muara sungai Lambarese, muara sungai Rongkong (Salu Pongko/Salo Bongko) di Malangke, muara sungai Batu Sitanduk, muara Sungai Battang, muara Sungai Boting dan Tompotikka (di Palopo), muara Sungai Kamanre, muara Sungai Bajo, muara sungai Larompong, dan muara Sungai Siwa. Bahkan ada juga yang berdiaspora melalui laut hingga ke Pammana (Siwa dan Pammana sekarang masuk wilayah Kab. Wajo).
Ada 2 (dua) titik peradaban yang terbentuk dari hasil diaspora menyusuri berbagai muara sungai ini, yakni To Liu (Luwu) di Malangke dan To Ompo (Tompo –Tikka-) di Palopo (berdasarkan analisa berbagai sumber, To Ompo di Soppeng itu awalnya berasal dari Palopo). Setelah penyusuran melalui muara sungai, mereka lalu bergerak ke arah utara melalui muara sungai ke hulu sungai. Dalam kurun waktu 500 tahun hingga 1 (satu) millenum (1000 tahun), mereka pun berhasil menempatkan keturunan mereka hingga di beberapa hulu sungai tersebut, dan membentuk beberapa anak suku, seperti yang dikutip di bagian suku dan bahasa di atas.
Dari segi kebahasaan, dapat dikatakan bahwa diaspora penutur vokal ‘E’ ini agak lambat dalam membentuk bahasa baru. Mereka tidak bertemu dengan pesaing dari bahasa lain, kecuali di antara sesama mereka, sehingga dalam kurun waktu millenia pertama sejak menyempal dari induknya, hanya lahir sebuah bahasa baru yakni bahasa TAE, itupun tidak jauh beda dengan bahasa To Luwu (induk bahasa Tae) di Malangke. Atau, dapat dikatakan tak ada bahasa baru dari diaspora ini, kecuali dialek baru.
Satu keterangan penting terkait hal ini diperoleh dari salah seorang masyarakat Luwu Utara bahwa dahulu kala daerah Wotu hingga Malangke dihuni suatu komunitas tertua bernama Suku To Luwu. Ditambahkan pula bahwa bahasa leluhur suku ini adalah bahasa TAE dengan sedikit nuansa bahasa Bugis. Meski generasi To Luwu saat ini lebih cenderung dikatakan sebagai penutur bahasa BUGIS (dialek Luwu), namun jejak-jejak dari bahasa leluhur mereka banyak diabadikan dalam beberapa Lontara’ Sulawesi Selatan, termasuk dalam EPOS I LAGALIGO (yang asli). Karena itu, mereka lebih suka menyebut bahasa leluhur mereka itu dengan istilah bahasa Lontara’.
Kelahiran bahasa baru dari diaspora ini, baru terjadi antara abad ke-4 hingga abad ke-10 Masehi. Itu pun setelah adanya interaksi antar penutur vokal ‘E’ dengan kembarannya penutur vocal campuran melalui perkawinan. Ironisnya, tempat yang menjadi lahan pembentukan bahasa baru tersebut, justru berada dalam rentang jarak 400 hingga 500 km dari tempat asalnya. Bahasa baru yang terbentuk itu adalah bahasa MAKASSAR, yang lahir dari percampuran bahasa TAE (Luwu) dan bahasa BARE’E (Matano).
SEJARAH PENEMUAN BESI
Fenomena kebahasaan (Linguistik) di bekas Kerajaan Luwu ini, menguatkan keyakinan bahwa pada masa lalu, sesungguhnya ada 2 (dua) peradaban besar yang saling bertanding sekaligus bersanding memperebutkan pengaruh yang bermuara pada Kebesaran Kerajaan Luwu. Kedua peradaban ini mewakili Peradaban LEMBAH DANAU MATANO (kabupaten Luwu Timur sekarang), dan Peradaban LEMBAH SALU PONGKO (sekarang masuk wilayah Kabupaten Luwu Utara). Peradaban Lembah Danau Matano memainkan hegemony di wilayah Geografis penutur vokal ‘O’ dan penutur vokal campur (BARE’E). Sementara Peradaban Lembah Salu Pongko menguasai wilayah-wilayah Geografis penutur vokal ‘E’. Selain berebut pengaruh, kedua peradaban ini bersaing memproduksi Metalurgy dari perut bumi masing-masing untuk pasokan bahan-bahan pembuatan senjata, alat perang dan
kebutuhan-kebutuhan lainnya, baik untuk dipakai sendiri atau pun pesanan dari komunitas lain. Dua sungai besar yakni sungai LARONA dan sungai RONGKONG- menjadi arus lalulintas untuk mengangkut hasil produksi metalurgy mereka ke tempat tujuan pemesanan. Sungai Larona yang mengalirkan air Danau Matano melalui Kota Malili, dan berujung di Teluk Bone, dijadikan sebagai sarana angkut produk tambang oleh penutur vokal ‘campur’, dari sekitar gunung Pongko (Matano) ke tempat tujuan. Sementara sungai Rongkong yang mengalirkan air dari Seko dan Limbong melalui Sabbang/Baebunta dan berakhir di Muara Salo’Pongko, dijadikan sarana angkut produk tambang oleh penutur vokal ‘E’ dari Seko ke tujuan pemesanan. Penggalian Arkeologi besar-besaran tahun 1938 yang dilaporkan oleh Willems dan kawan-kawan dan juga OXYS tahun 2004 pada 2 (dua) peradaban itu menguatkan hal tersebut.
Persaingan yang ketat di antara keduanya, tak urung menyulut api permusuhan dan ancaman peperangan. Untungnya, peranan besar MACOA BAWALIPU di WOTU yang berada di antara kedua belah pihak dapat meredam percikan api permusuhan tersebut. Solusi kawin mawin yang ditawarkan MACOA, dapat diterima dengan senang hati oleh kedua belah pihak. Solusi damai atas ancaman perang ini justru dilukiskan dengan sangat indah oleh Lagaligo Putra Sawerigading dalam EPOS LAGALIGO, sebagai pengisian ALE’ KAWA (Dunia Tengah) oleh Batara Guru dari Highland (BOTING LANGI’/Danau Matano) dan We Nyili’timo dari Lowland (BURIQ LIU’/Pesisir Pantai Malangke).
Perkawinan Batara Guru (La Toge’ Langi’) dengan We Nyili’ Timo dianggap sebagai lambang reunifikasi (penyatuan kembali) 2 (dua) keluarga besar dari suku To RIU (WAWENRIU) dengan suku To LIU (LUWU) yang berasal dari satu nenek moyang (To PONGKO), yang lama terpisah dan tercerai berai akibat diaspora (penyebaran penduduk/keturunan).
Selain sebagai lambang reunifikasi, perkawinan ini pun dapat dianggap strategi yang sengaja dilakukan sebagai bentuk gebrakan diaspora (penyebaran penduduk), untuk mematahkan kebiasaan lama berdiaspora melalui hilir (laut/pantai) dan hulu (gunung) yang telah dilakukan berabad-abad sebelumnya. Pilihan diaspora melalui pesisir pantai atau juga gunung dan mengabaikan diaspora di dataran tengah, dianggap nyaman oleh anak-anak To Pongko yang tidak ingin direpotkan oleh hutan dan semak belukar liar yang memenuhi dataran tengah wilayah Luwu pada masa lampau.
Pilihan diaspora lama dengan menyusuri daerah aliran sungai (DAS) dari hilir ke hulu lebih disukai karena dengan begitu mereka tidak direpotkan dengan persediaan bahan makanan berupa ikan dan udang yang melimpah di sepanjang DAS. Apalagi, tak jauh dari tepi DAS jutaan pohon sagu pun telah siap menanti untuk ditebang dan diambil isinya. Cukup dengan menebang sepohon, mereka sudah dapat hidup sebulan. Mereka tak perlu memikirkan kapan datangnya musim tanam dan kapan waktunya musim panen. Yang ada hanyalah masa panen dan terus memanen.
Satu-satunya hal yang membebani pikiran mereka adalah bagaimana mendapatkan alat tebang yang efektif untuk ‘massambe tabaro’ (menebang pohon sagu) untuk makanan, dan menebang pohon kayu untuk perumahan. Alat tebang berupa batu runcing dianggap sulit dan lamban, dan begitu banyak menguras waktu dan tenaga. Beban pikiran ini justru membawa berkah tersendiri bagi nenek moyang orang Luwu. Pencarian alat tebang yang baik, membawa mereka pada penemuan besi.
Dan ketika mereka mengetahui bahwa ternyata perut bumi mereka dipenuhi oleh biji-biji besi, dan sangat mubazzir jika hanya digunakan untuk keperluan penebangan pohon sagu dan pohon kayu, mereka pun mulai mengeksploitasi besi-besi tersebut untuk ditukar dan diperdagangkan kepada komunitas lain. Eksploitasi besar-besaran tingkat lokal mulai terjadi ketika telah terbentuk 2 peradaban di Danau Matano dan Malangke, yang berujung pada
persaingan yang ketat di antara keduanya dan sering menyulut api permusuhan dan ancaman peperangan antar sesama keturunan To Pongko, sesuai diceriterakan di atas.
TERBENTUKNYA KERAJAAN LUWU
Kembali ke reuni keluarga. Telah disebutkan bahwa perkawinan Batara Guru (La Toge’ Langi’) dengan We Nyili’ Timo dianggap sebagai lambang reunifikasi (penyatuan kembali) 2 (dua) keluarga besar dari suku To RIU (WAWENRIU) dengan suku To LIU (LUWU) yang berasal dari satu nenek moyang (To PONGKO), yang lama terpisah dan tercerai berai akibat diaspora (penyebaran penduduk/keturunan).
Selain sebagai reuni, perkawinan itu juga dianggap sebagai peredam percikan api permusuhan di antara kedua peradaban. Dan perkawinan itu pun telah menjadi sebuah gebrakan yang mematahkan kebiasaan lama berdiaspora, yang melebar di bagian hilir dan hulu, serta membiarkan bagian tengah menjadi kosong. Pengisian dataran tengah yang kosong ini dilukiskan dengan indah dalam Epos Lagaligo sebagai pengisian ‘Aleq Kawa’ atau dunia tengah.
Beberapa tujuan tersirat di atas juga dilandasi oleh sebuah fikosofi yang bijak akan masa depan keturunan mereka. Orangtua dari kedua belah pihak tentu telah berpikir bahwa keturunan mereka tidak dapat terus menerus mengandalkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia, yang lama kelamaan akan terkuras habis manakala tidak dilakukan peremajaan. Karena itulah, ketika kita membuka episode pertama Epos Lagaligo: Saat Diturunkannya Batara Guru”, terlihat benar bagaimana Raja Pertama Kerajaan Luwu ini di training habis-habisan. Ia tidak diberi makan dan minum selama tiga hari-tiga malam, hingga benar-benar merasakan penderitaan.
Tak ada tujuan lain dari pada training tersebut kecuali memberi proyeksi kepada Batara Guru bahwa penderitaan seperti itulah yang akan dihadapi oleh keturunan Batara Guru, kelak manakala tidak ada upaya untuk mulai belajar bercocok tanam. Dan tempat paling sesuai untuk bercocok tanam adalah dataran tengah. Efektifitas dari filosofi ini terlihat hingga zaman orde baru lalu, di mana Luwu selalau menjadi penghasil beras nomor satu di Sulsel. Kelahiran BATARA LATTU dari Perkawinan ini dapat dianggap sebagai simbol lahirnya kembali (reinkarnasi) nenek moyang mereka ‘To PONGKO’, sebagai manusia awal yang pernah mendiami Tana Luwu di Wotu. Karena itulah, reunifikasi keluarga ini dikukuhkan dengan dijadikannya Wotu sebagai Ware’ (Kotaraja) Kerajaan Luwu yang pertama, dengan La Toge’ Langi’ sebagai Datu’ Pertama. Selanjutnya, kerajaan ini diserahkan kepada Batara Lattu ketika Ia telah dewasa dan dianggap cakap memimpin sebuah Kerajaan.
Kelahiran putra mahkota ini dianggap sebagai titik awal menyatunya 2 (dua) peradaban yang diwakili oleh 3 (tiga) kerajaan tua di Luwu yakni Wawenriu’, Luwu’, dan Tampotikka.
WELCOME TO WAWENRIU’
Dari uraian di atas dapat ditebak bahwa nama Kerajaan Luwu diambil dari kata ‘To Luwu’ (orang Luwu), salah satu suku tertua yang mendiami Malangke, sempalan dari To Pongko (Wotu). Tak ada keterangan yang dapat dijadikan rujukan kenapa dan kapan nama ini disepakati untuk mewakili kedua peradaban tersebut. Kuat dugaan, keterampilan orang To Luwu dalam membuat publikasi dalam bentuk karya tulis berupa Lontara dan juga Epos Lagaligo menjadi alasan utama kata Luwu dijadikan pemersatu keduanya.
Bahasa yang digunakan dalam Epos Lagaligo maupun Lontara berasal dari penutur vokal ‘E’, dan bukan menggunakan bahasa dari penutur vokal ‘O’, dan bukan juga menggunakan bahasa titik temu antara keduanya, Bahasa BARE’E. Kendati demikian, bukan berarti tak ada Lontara atau Lagaligo yang ditulis dalam bahasa Bare’e, karena kenyataannya Orang Selayar mengenal juga Lagaligo dan bahasa orang Selayar begitu mirip dengan bahasa Wotu.
Jika nama Kerajaan Luwu diambil dari Komunitas suku To Luwu, lalu apakah nama yang digunakan untuk menyebut Peradaban Danau Matano ketika itu? Mungkin inilah jawaban dari teka-teki menghilangnya Kerajaan WeWanriu’ selama ini. Agaknya telah terjadi salah eja atau salah tulis dalam Epos Lagaligo, untuk nama Kerajaan Wawenriu’. Inilah yang menyebabkan banyak sejarawan mengalami kesulitan mengidentifikasi toponim kerajaan ini. Kesalahan eja atau penulisan terletak pada pertukaran vokal. Sebetulnya bukan Wewanriu, tetapi Wawenriu’.
Wawenriu’ adalah singkatan dari Wawa INIA Rahampu’u. Pembuktian akan hal ini dapat dilakukan dengan melafalkan kemajemukan kata Wawa Inia Rahampu’u secara berulang-ulang. Secepat apapun kita melafalkan kemajemukan kata tersebut secara berulang-ulang, maka secepat itu pula kita mendapatkan kata Wawenriu’.
Arkeologis Bugis Makassar Iwan Sumantri, dalam bukunya yang berjudul “KEDATUAN LUWU menegaskan, bahwa Wawa Inia Rahampu’u adalah Luwu, dan Luwu adalah Wawa Inia Rahampu’u. Penegasan Iwan Sumantri ini menguatkan bahwa Wawenriu itu adalah Wewanriu yang sering disebut-sebut dalam Epos Lagaligo.
Kerajaan ini pula yang maksud dalam Epos I Lagaligo sebagai BOTING LANGI’, kerajaan yang merupakan tempat asal BATARA GURU (La Toge’ Langi’), Raja pertama Kedatuan Luwu. Jika ditelusuri melalui kajian linguistik, BOTI(ng) sama dengan WOTI(ng). WOTI artinya Wadah atau Waduk atau DANAU, sedangkan LANGI’ berarti tempat yang tinggi. Dengan demikian, BOTI(ng) LANGI’ artinya DANAU yang berada di KETINGGIAN. Kita dapat membuktikan bahwa satu-satunya danau yang berada di ketinggian di Sulawesi Selatan hanya dijumpai ketika kita berjalan dari WASUPONDA ke SOROAKO. Itulah DANAU MATANO, dan di sekitar danau inilah –pada masa lampau- berdiri Kerajaan Wawa Inia Rahampu’u, atau WAWENRIU’.
Dari segi asal usul kata, WAWENRIU adalah derivasi (turunan) kata WaeNRIU yang artinya air minum atau air tawar. Jelas, ini asli ucapan lidah dari penutur vokal ‘E’, seperti yang diuraikan di atas. Jika kata ini ditransformasi ke lidah penutur vokal ‘O’, maka ada beberapa variasi yang akan ditemui, seperti: WAWONRIO, WOWONRIO, WAWONDIO, WOWONDIO, dan sebagainya. 2 (dua) bunyi terakhir yakni WAWONDIO dan WOWONDIO, dekat dengan nama sebuah Kecamatan di Luwu Timur, yaitu WAWONDULA, atau biasa juga orang tuturkan dengan nama WOWONDULA. Kata Wawondula atau Wowondula ini dapat dianggap sebagai bentuk bias dari bahasa BARE’E, sebagai akibat dari persaingan hegemony dua penutur bahasa, yakni kelompok penutur vokal ‘E’ dari Selatan dan kelompok penutur vokal ‘O’ dari Utara.
Jadi jelas bahwa Wawenriu’ itu adalah Kerajaan Highland, atau kerajaan air tawar. Karena itu tempatnya bukan di muara sungai atau ditepi pantai. Beberapa argumen di atas cukup jelas bagi kita bahwa argumen-argumen itu hanya merujuk kepada Wawa Inia Rahampu’u, sebagai satu-satunya kerajaan yang disebut sebagai WEWANRIU’ dalam Epos I Lagaligo. Persoalan kesulitan identifikasi selama ini bersumber pada kesalahan eja ataupun salah tulis.
TAMPOTIKKA
Satu lagi kerajaan yang menjadi perdebatan panjang dari Epos Lagaligo adalah toponim (letak) kerajaan Tompotikka. Sejarawan dan budayawan Internasional, nasional, dan lokal Bugis Makassar lebih sepakat kalau Tompotikka itu berada di Luwuk Banggai. Tapi tak ada salahnya kalau orang Bone memiliki sejumlah argumen yang menyatakan bahwa Tompotikka itu di Bone. Dan sah-sah saja kalau orang Makassar pun punya argumen yang kuat bahwa Tompotikka itu di Makassar. Orang Luwu pun memiliki argumen yang kuat bahwa Tompotikka itu letaknya di Palopo.
Term (istilah) Tompotikka adalah asli bahasa Luwu dan bukan bahasa Luwuk Banggai. Tompotikka adalah kata majemuk, yang jika diurai menghasilkan 2 kosa kata yakni Tompo dan Tikka. Tompo artinya muncul, namun dapat juga diurai menjadi To dan Ompo yang berarti orang yang muncul. Adapun Tikka memiliki variasi makna, antara lain; air pasang, musim kering dan siang hari. Makna ‘Tikka’ ini lazim dimengerti di Luwu hingga saat ini, untuk menunjukkan air pasang, musim kering atau juga terkait teriknya matahari di siang hari, dan bukan dimaknai terbitnya matahari di pagi hari. Dengan demikian, makna Tompotikka dapat berarti munculnya air pasang, muncul di siang hari, atau pun muncul di musim kemarau. Bisa juga berarti orang yang muncul saat air pasang atau orang yang muncul saat terang, atau pun muncul di musim kemarau.
Jika diurai lebih dalam dari sudut bahasa, maka kata Tompo itu akan menunjukkan beberapa nama tempat (Toponim) di Luwu. TOMPO adalah derivasi (turunan kata) dari TAMPO. Sementara TAMPO adalah derivasi dari kata TAMPU.
TOMPO = TOMPE di Malangke TAMPO = TAPPO(ng) di Palopo TAMPU = TAMPU(mia) di Malili
TEMPE = BASSE(i) SANG TEMPE (BASTEM) alias Bassi sang Tompo’(?)
Adakah hubungan makna ini dengan kejadian masa lampau di Luwu? Hingga saat ini hampir setiap hari masih dijumpai orang berduyun-duyun ke Pelabuhan Tanjung Ringgit di Palopo. Kemunculan orang-orang tersebut berada sekitar jam 9 hingga jam 11 Pagi untuk melakukan penyeberangan ke Malangke Bone-bone, Wotu dan Malili, hingga ke Sulawesi Tenggara, atau juga ke arah selatan seperti Belopa Suli Larompong hingga ke Wajo dan Bone. Saat jam 9 hingga jam 11 itulah yang disebut dengan Tikka (terang) karena saat itu pula biasanya terjadi Tikka (air pasang). Mereka menunggu air pasang saat terang untuk melakukan penyeberangan. Sebaliknya, orang-orang dari luar Palopo yang ingin masuk ke Palopo, biasanya harus menunggu air pasang agar dapat tiba tepat di anjungan kapal atau perahu di pesisir tanjung ringgit ataupun masuk ke pusat Palopo melalui Sungai Tompotikka atau
Sungai Boting. Biasa juga air pasang lebih dulu datang mendahului terang. Namun orang-orang lebih suka berdiam dalam kapal/perahu hingga terang itu datang.
1000 tahun silam, air pasang Tanjung Ringgit Palopo yang terlihat dari gambar ini naik menohok (Ma’tumpa’/Ma’tuppa’/Latuppa’) hingga ke kaki bukit yang terlihat lebih jauh di belakang, Akibatnya, benda-benda di kaki bukit menjadi MAWA’ atau MAWANG yang artinya terapung.
Seperti itulah makna Tompotikka yang lazim di mengerti di Luwu. Pemandangan tersebut memang tidak seramai dulu. Transportasi melalui jalan-jalan darat yang telah menembus sekat-sekat isolasi antar daerah kini lebih disukai masyarakat menggantikan jalur penyeberangan melalui laut. Meski demikian, kebiasaan menunggu air pasang menjelang siang tersebut hingga kini masih tetap berlaku bagi beberapa warga atau pelaut, termasuk para nelayan yang ingin melaut atau membawa pulang hasil tangkapan ke rumah atau ke tempat pelelangan ikan di Palopo.
TO OMPO
Tentang To Ompo yang telah disinggung di atas, Telah disebutkan bahwa berdasarkan analisa berbagai sumber, To Ompo di Soppeng itu awalnya berasal dari Palopo. Lalu ada apa sehingga mereka pindah ke Soppeng? Nama ini dianggap sebagai nama suku yang pertama yang mendiami Palopo. Nama suku ini senasib dengan To Liu’ (Luwu) dan To Riu’ (Wawenriu’) yang tak dapat diidentifikasi oleh peneliti sejarah maupun penutur sejarah, namun masih dapat dikenali melalui Epos Lagaligo, dengan term yang agak berbeda. Dari nama suku inilah lahir nama TOMPOTIKKA. Selain makna yang telah diurai di atas, Tompotikka dapat pula berarti Orang yang hidup di tempat air pasang.
Dari penuturan Jabbar Hamseng, SH, MH, seorang warga Palopo asal Larompong diketahui bahwa Palopo pernah dilanda banjir bandang yang sangat besar. Banjir bandang ini terjadi akibat bertemunya air pasang dan air bah (banjir). Meski tidak menyebut kapan terjadinya banjir bandang tersebut, namun dari hasil eskavasi (galian) arkeologi diketahui bahwa daerah ini bukan hanya sekali dilanda banjir bandang, tapi telah berkali-kali. 2 (dua) diantara banjir bandang tersebut teridentifikasi melalui laporan arkeologi yang disampaikan oleh David
Bullbeck, bahwa sekitar 1000 tahun yang lalu, Palopo pernah menjadi sentra industri ‘pyrotechnology’ atau pencetakan gelas/kaca. Berikut kutipan dari pernyataan David Bullbeck: “...A waste piece of cast glass found 60 cm beneath the soil near Palopo (van der Hoop 1941:319) offers some evidence of advanced pyrotechnology in Luwu by 1000 years ago....”
Dikatakan pula dalam laporan tersebut bahwa Palopo, meski belum menjadi ibukota Luwu hingga abad ke-17 (Caldwell 1993), ditemukan area yang menggemparkan, di mana dieskavasi 2 lembar jubah Che-chiang, yang berasal dari abad ke 13 dan abad ke-14, sesuai yang diidentifikasi oleh Orsoy de Flines.
Berikut kutipannya: “...Palopo, eventhogh it did not become Luwuk’s capital until the 17th century (Caldwell 1993), contains a “tumultous area” where two 13th-14th century Che-chiang celadons were excavated, as identified by Orsoy de Flines....”. Laporan arkeologi di atas dapat kita temukan dalam Ancient Chinese and Southeast Asian Bronze Age Cultures, oleh David Bullbeck, 1998.
Keterangan hasil galian arkeologi di atas cukup memberi petunjuk bahwa setidaknya telah dua kali daerah ini dilanda banjir bandang, yakni 1000 tahun lalu dan 700 tahun lalu. Begitu besarnya banjir sehingga membenamkan wilayah ini. Diduga, banyak korban jiwa akibat banjir tersebut, sementara yang selamat mencari tempat hunian baru. Yang hanyut ke Teluk Bone dan selamat dari banjir ini menjadi orang Liwukang (Libukang). Korban Bandang di bagian Barat Daya menjadi orang Warompo, singkatan dari Wara Ompo (Larompong sekarang). Yang hijrah dan mencari tempat tinggi menjadi orang Taulette (sekarang Tanete, di Wajo). Dan yang hijrah dari Tompotikka (Palopo sekarang) ke Daerah Soppeng Timur melalui laut, tetap menggunakan identitas To Ompo dari Tompotikka agar mudah dikenali oleh kerabat dan keluarga yang menjadi asal usul mereka. OMPO’ adalah bahasa Luwu, sama maknanya dengan OMBO (bahasa TAE’) atau OPPO’ (Bahasa Bugis Luwu). Kata yang terakhir ini (oppo’) kini lebih cenderung digunakan untuk memaknai pemenang PILKADA. Hingga tahun 1970-an air pasang di Palopo masih dijumpai naik hingga ke tempat yang sekarang menjadi Kantor Walikota Palopo. Air pasang di Kota Palopo saat ini masih dapat dilihat hampir setiap hari pada 2 (dua) sungai yang membelah Kota Palopo, yakni Sungai Tompotikka dan Sungai Boting. Air pasang yang besar yang melalui sungai Boting masih biasa dijumpai naik hingga ke Luminda, bahkan ke Boting. Sementara air pasang yang melalui Sungai Tompotikka masih biasa dijumpai naik hingga ke daerah Sempowae, bahkan Mawa.
Seperti itulah gambaran air pasang di Palopo saat ini dan 30 tahun silam, sehingga dapat diduga bahwa 1000 tahun lalu air pasang yang melalui sungai Tompotikka itu mencapai Latuppa’, sementara yang melalui sungai Boting mencapai Lebang. Jika dianalisis secara bahasa, LA TUPPA’ itu adalah asli tuturan lidah orang Bugis. Jika kata tersebut ditransformasi ke lidah penutur bahasa TAE maka menjadi LA TUMPA’. Tumpa’ artinya menjolok/menohok dari bawah ke atas. Sementara “LA” di depan kata Tumpa’(Tuppa’) adalah penanda defenitif, sama dengan “The” dalam bahasa Inggris atau juga “Al” (alif lam ma’rifah) dalam bahasa Arab. Dari analisis ini, kita ketahui bahwa La Tumpa’ (La Tuppa’) itu bermakna sesuatu yang menjolok/menohok dari bawah ke atas ATAU sipenjolok/ sipenohok dari bawah.
Gambaran air pasang yang ketinggiannya mencapai daerah Latuppa ataupun Lebang sekitar 1000 (seribu) tahun yang lalu ini menyebabkan benda-benda di daerah sebelumnya menjadi MAWA’ atau MAWA(NG) yang artinya terapung. Makanya, tidak heran jika dataran yang diapit di antara kedua belah sungai ini di namakan MAWA’. Selain hubungan makna tersebut, warga Palopo saat ini masih banyak yang memegang kepercayaan lama (To Dolo) terkait air pasang. Orang-orangtua yang mengaku modern sekalipun hanya menganjurkan
prosesi pindah rumah ketika air pasang, dan tidak akan menganjurkan prosesi pindah rumah ketika air surut.
Nah, itulah sekelumit gambaran tentang Tompotikka yang dimaksud dalam Epos Lagaligo. Sungai Tompotikka dan bekas Benteng Tompotikka jadi saksi abadi bahwa Palopo adalah Tompotikka yang dimaksud dalam Epos Lagaligo. Pengabadian itu tetap terpelihara dengan dibentuknya sebuah kelurahan bernama Tompotikka di daerah yang lebih dikenal di Palopo dengan nama Tappo(ng). Dan Tappo(ng) ini adalah bentuk derivasi dari kata Tampo.
Peta di atas menunjukkan letak sungai dan Benteng Tompotikka di Palopo Dikutip dari : Economy, Military and Ideology in Pre-Islamic Luwu,
South Sulawesi, Indonesia oleh David Bullbeck
Istri Batara Lattuq atau Ibunda dari Sawerigading dan Tenriabeng dalam Epos Lagaligo berasal dari Tompotikka. Dalam silsilah yang dikeluarkan Friedericy, yang dapat dilihat dalam buku Ritumpanna Welenrengnge halaman 95, Ibunda Sawerigading dan Tenriabeng itu bernama WE OPU SENGNGENG. ‘OPU’ adalah sapaan yang hanya berlaku bagi bangsawan Luwu yang telah berkeluarga dan punya keturunan, dan tidak berlaku untuk bangsawan lain di luar wilayah Luwu.
Itulah beberapa bukti sejarah (bukan Mitos) bahwa Tompotikka itu adalah Palopo. Tiga Toponim dalam Epos Lagaligo yakni WAWENRIU’, LUWU dan TOMPOTIKKA adalah satu rangkaian yang tak dapat dipisah antara satu dengan yang lain. Tiga kerajaan inilah yang tergabung menjadi satu dalam ikatan perkawinan yang diusulkan oleh Macoa Bawalipu WOTU, sehingga berujung pada kebesaran Kerajaan Luwu.
Setting utama cerita Epos Lagaligo adalah berkisah tentang Luwu, diperankan oleh Raja-raja Luwu, dan ditulis dalam bahasa Luwu. Ketiga toponim tersebut di atas berada di Luwu, karena itu sangat keliru jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mengaburkan salah satu dari ketiga Toponim tersebut dengan maksud ingin mengklaim EPOS LAGALIGO sebagai milik mereka. Bagaimana pun, EPOS LAGALIGO adalah milik orang Luwu.
Palopo pada awal abad peradaban adalah Tompotikka. Penamaan menjadi Palopo ini setelah acara penancapan tiang Masjid Jami’ Tua ke dalam lubang pondasi pada tahun 1604. Saat itupula ibukota kerajaan Luwu berpindah dari Malangke ke Palopo. Seiring perjalanan waktu, dengan melihat tingginya peradaban Palopo pada masa lampau dan dibandingkan dengan tingkat prestasi pembangunan yang dicapai oleh warga Kota Palopo saat ini, patut kita bertanya: ADA APA DENGAN PALOPO?
PALOPO artinya “Benamkan”. Lawan kata dari itu adalah PA-OMPO yang artinya “Munculkan”. Usai prosesi pembenaman tiang Masjid Jami’ tahun 1604 silam, serta penamaan Kotaraja terakhir Kerajaan Luwu ini dengan nama PALOPO yang berarti ‘BENAMKAN’ maka berangsur-angsur terbenam pulalah Palopo sebagai Kotaraja Luwu pada khususnya, dan peradaban Luwu pada umumnya, dari dominasi hiruk pikuk Kejayaan masa lampau. Apakah hal ini terkait dengan penamaan sebuah tempat/daerah? W Allahu a’lam bisshawaab! Rasullullah SAW pernah berwasiat agar memberi nama yang baik kepada anak atau cucu yang baru lahir, karena NAMA ADALAH HARAPAN. Orang yang beriman
kepada Allah dan Rasulnya, akan menunaikan wasiat ini. Namun orang yang mengingkari amanah ini lebih nyaman dengan slogan dari Shakespear: APALAH ARTI SEBUAH NAMA?
PENUTUP
Tulisan yang membahas tentang Awal Peradaban dan Kerajaan Luwu ini berpedoman pada Catatan Sejarah, Epos Lagaligo, Laporan Arkeologi dan Tinjauan Kebahasaan (Linguistik). Tulisan ini mungkin berbeda dengan tulisan yang telah ada sebelumnya (jika ada), dan hal tersebut dapat dipahami sebagai perbedaan dari sudut pandang semata.
Karena itu, tulisan ini dapat dikatakan masih bersifat HIPOTESIS. Pengakuan, pembenaran serta koreksi dari berbagai komponen Masyarakat Luwu dapat mengukuhkannya sebagai sumber literatur sejarah.
---