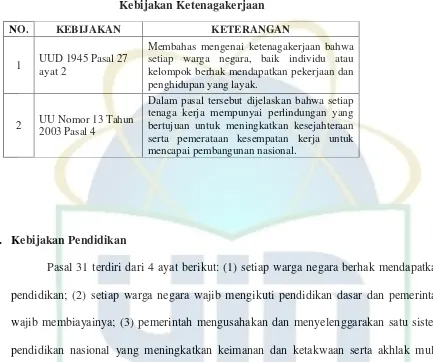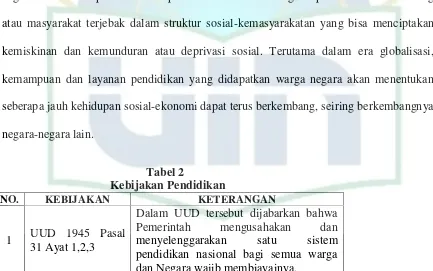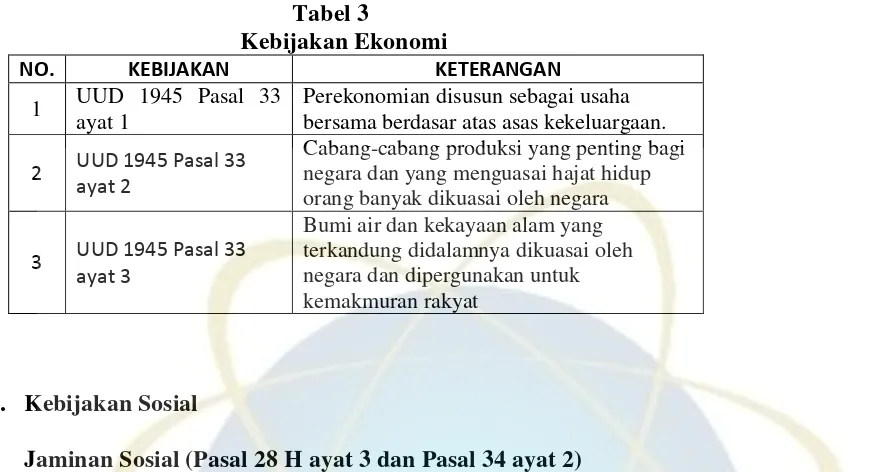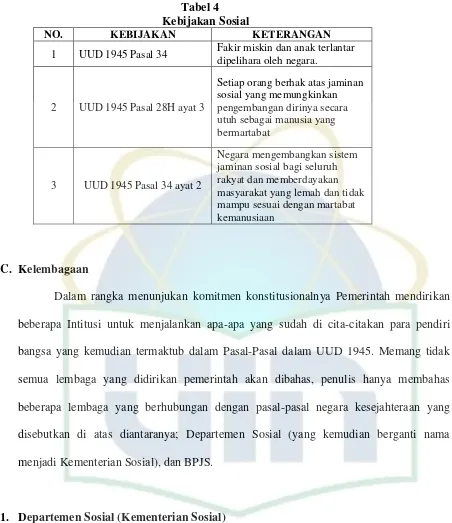DALAM PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Mamur Rizki
1110054100038
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Mamur Rizki 1110054100038
Dibawah Bimbingan :
Muhtadi, M.Si 19750601 2014111 001
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
i ABSTRAK
Mamur Rizki
Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.
Negara kesejahteraan merupakan model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Pilihan model seperti itu juga telah diinisiasi oleh para pendiri bangsa dan tertuang jelas dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep dan praktik negara kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library
reasearch) dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analisis, Deskriptif berarti memaparkan dan menggambarkan secara objektif isi seluruh UUD 1945 dan Pancasila yang berkaitan dengan materi muatan negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan sosial. Sementara analitis berarti upaya memahami posisi, pemikiran, dan upaya menularkan gagasan baru tentang konsep negara kesejahteraan disertai kritik dan kesimpulan.
Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa Indonesia menganut negara kesjehateraan. Hal tersebut tertuang jelas dalam undang-undang dasar dan bertumpu
pada sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dimana
dalam proses perumusan Pancasila para pendiri bangsa menghendaki bentuk Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Kemudian prinsip dalam UUD 1945
mengakomodir ketiga konsep rezim negara kesejahteraan. Konsep residual welfare
state tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Konsep universal welfare state tertuang dalam
pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 ayat 2, 3, 4. Konsep social
insurance welfare state tercermin pada pasal 28C ayat 2. Sementara pada praktiknya
Indonesia lebih dekat dengan Konsep Residual Welfare State, hal itu terlihat dari
program-program yang dikeluarkan lebih bersifat kuratif dan residu.
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:
1. Bapak Dr. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Suparto, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
2. Ibu Lisma Dyawati Fuaida, M.Si selaku Ketua Program Studi
Kesejahteraan Sosial, Ibu Nunung Khoiriyah, MA selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial. Terima kasih atas nasehat dan bimbingannya.
3. Bapak Muhtadi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu
iii
4. Seluruh dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
5. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bukhori Muslim dan Siti
Khodijah yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. HMJ Kesejahteraan Sosial, DEMA Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi dan keluarga besar mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah menjadi tempat belajar dan berproses yang “asik” bagi
peneliti.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menemukan,
merumuskan dan menyelesaikan skripsi ini.
Dengan demikian skripsi ini penulis susun dengan sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua yang membacanya, terutama dalam memajukan keilmuan Kesejahteraan Sosial. Amin.
Ciputat, Januari 2017
iv
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iv DAFTAR TABEL……….. . vi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10
D. Metodologi Penelitian ... 11
E. Tinjauan Pustaka………. 13
F. Sistematika Penulisan……….. 14
BAB II LANDASAN TEORI A. Negara Kesejahtaraan ... 15
1. Pengertian Negara Kesejahteraan ... 15
2. Filosofi Negara Kesejahteraan……… 21
3. Sejarah dan Dinamika Negara Kesejahteraan ... 26
BAB III ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UUD 1945 A. Latar Belakang Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila .. 37
v
1. Kebijakan Ketenagakerjaan ... 51
2. Kebijakan Pendidikan ... 53
3. Kebijakan Ekonomi ... 55
4. Kebijakan Sosial ... 59
C. Kelembagaan ... 62
1. Departemen Sosial (Kementerian Sosial) ... 62
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ... 64
BAB IV PRAKTIK NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA A. Praktik Negara Kesejahteraan Di Indonesia ... 66
B. Analisis Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945 ... 74
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 86
B. Saran ... 87
vi
1. Tabel 1 Kebijakan ketenagakerjaan……….. 53
2. Tabel 2 Kebijakan Pendidikan……. ... 54
3. Tabel 3 Kebijakan Ekonomi... 59
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertanyaan awal ketika berbicara tentang negara kesejahteraan
Adalah bagaimana mendefinisikan konsep negara kesejahteraan itu
sendiri, karena negara kesejahteraan bukanlah sebuah konsep dengan
pendekatan baku. negara kesejahteraan sering ditengarai dari
atribut-atribut kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan
negara kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan
pekerjaan, pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan
kebijakan sosial sering diidentikkan.1
Sebagai kajian makro dalam ilmu kesejahteraan sosial, negara
kesejahteraan jarang sekali mendapat perhatian. Hal tersebut terjadi karena
pertama-tama wacana pendekatan negara kesejahteraan lebih sering
bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya saja, seperti yang sering
kita dengar bahwa negara kesejahteraan adalah pendekatan yang boros,
tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan
ketergantungan penerima manfaat (beneficiaries). Akibatnya, tidak sedikit
yang beranggapan sistem ini telah menemui ajalnya, alias sudah tidak
dipraktekkan lagi di negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang
1
Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan
disertai argumen dan riset yang memadai, banyak orang menjadi kurang
berminat membicarakan, dan apalagi memperhitungkan pendekatan ini.2
Di sisi lain kajian mikro maupun mezzo lebih populer di Indonesia.
Seperti kita tahu bidang ini mengedepankan pelayanan pada lingkup
individu yang sudah kadung menyandang masalah kesejahteraan sosial,
yang tidak lain sifat dari lingkup ini adalah kuratif (mengobati). Sementara
ada yang salah di bagian hulu sehingga terkesan individu-individu yang
mempunyai masalah kesejahteraan sosial tak pernah habis dan bertambah
terus jumlahnya. Seperti yang disampaikan Edi Suharto dalam makalahnya “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos” bahwa peningkatan
kesejahteraan, termasuk pemberdayaan masyarakat, tidaklah vakum dari
situasi sosial yang mengitarinya. Seringkali, kemiskinan yang dialami
masyarakat di suatu wilayah bukanlah disebabkan oleh ketiadaan modal
finansial dan faktor-faktor produksi lainnya. Melainkan, oleh lemahnya
modal sosial, tidak adanya perlindungan sosial, dan tidak beroperasinya
sistem keadilan sosial.3
Sementara itu program dalam lingkup mikro tersebut juga kerap
menimbulkan stigma. Di Inggris, sebagai ilustrasi, The Poor Law
dirancang untuk orang miskin. Karena tidak efektif dan menimbulkan
stigma pada penerimanya sistem ini ganti oleh Welfare State. Program dan
pelayanan yang hanya diberikan kepada orang miskin tidak akan dapat
2 Edi Suharto, “
Negara Kesejahteraan dan Reniventing Depsos,” artikel diakses pada 6
September 2008 dari
http://209.85.175.104/search?q=cache:gBlPSii64oJ:www.depsos.go.id/modules.php%3Fnam %3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D24+sejarah+lahir+negara+kesejahteraan&hl=id&c =clnk&cd=5&gl=id
mencegah kemiskinan. Karena orang harus miskin terlebih dahulu agar
dapat menerima program dan pelayanan ini.4
Saat ini upaya untuk mentransformasikan gagasan konsep negara
kesejahteraan begitu urgen. Faktor utama yang mendorong mengapa
konsep negara kesejahteraan begitu urgen dan secepat mungkin harus
direalisasikan karena didasarkan pada fakta bahwa di negara-negara
berkembang saat ini tingkat kemiskinan kian hari kian memperihatinkan.
Peran negara yang semakin berkurang di sektor publik seiring dengan
berjalannya proses demokratisasi, segala sesuatu yang bukan menjadi
urusan negara akan diserahkan kepada masyarakat. Sebagai salah satu
contoh misalnya ialah privatisasi beberapa perguruan tinggi negeri, rumah
sakit dan perusahaan-perusahan milik negara.
Tim Peneliti PSIK dalam bukunya ”Negara Kesejahteraan dan
Globalisasi”, mengutip dari buku Adam Smith, yang berjudul “An Inquiry
into the Nature and the Causes of the Wealth of Nation”, menjelaskan
bahwa ada dua tugas utama yang menjadi tanggung jawab negara.
Pertama, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sebuah rasa aman
bagi setiap warga negaranya dari ancaman dalam bentuk apa pun. Kedua,
kewajiban negara harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan
ekonomi bagi semua warga negara. Faktor keamanan biasanya menjadi
pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan sosial.5 Jadi keamanan dan
kesejahteraan merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan,
4 Suharto, “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos,” h. 16. 5
Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman (Jakarta: PSIK Universitas
situasi sosial dan politik yang tidak stabil akan menyulitkan terciptanya
kesejahteraan sosial, dan situasi keamanan sulit untuk terwujud bila suatu
negara warganya tidak memiliki jaminan kesejahteraan sosial.
Mimpi akan terciptanya sebuah negara yang “Budiman”, yakni
sebuah negara yang kuat namun mencurahkan segala upaya untuk
memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dan negara yang berdaya
dan peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar sosial-politik-ekonomi
warga negaranya. Namun setelah tiga dasawarsa lebih, Negara lebih sering
diidentikkan dengan wajah bengisnya, angan-angan tentang sebentuk
negara yang kuat dan budiman bisa menjadi bahan “cemooh”. Tidak dapat
dipungkiri lagi ruang publik didominasi oleh wacana “emoh negara” atau
“state denial”. Negara seolah-olah berasosiasi dengan segala keburukan.
Dibidang ekonomi, negara berkonotasi dengan kolusi, inefisiensi dan
nepotisme; di ranah birokrasi, bergandeng makna korupsi; sedangkan di
dalam ranah politik, negara disandingkan dengan aneka bentuk
pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sebuah reputasi buruk yang seolah
memberikan legitimasi bagi pelucutan kapasitas dan peran Negara.6
Pengalaman empiris negara-negara Eropa dengan demikian
merupakan sumber telaah yang menarik dan penting. Perjalanan negara
kesejahteraan Eropa yang dimulai dari era Otto Van Bismarck pada tahun
1883 hingga awal abad ke-21 ini telah menggambarkan pengalaman
empiris yang kaya tentang bagaimana negara menjalankan peran
kesejahteraan dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan eksternal dan
internal yang terus berubah. Eksperimen yang dilakukan negara-negara
Eropa Barat dan Utara melalui format negara kesejahteraan tersebut
menunjukkan bahwa negara mampu memikul peran yang aktif dalam
pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja yang luas, sistem
kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh warga, serta jaminan sosial
yang universal. Hal ini membuktikan bahwa negara kesejahteraan (walfare
state) merupakan bentuk paling riil dari angan-angan tentang “negara budiman”.7
Indonesia, merupakan negara yang unik. Yang berbeda dengan
negara lain. Dalam hal ideologi, Indonesia tidak menganut paham sosialis,
liberalis, nasionalis, ataupun agamis. Melainkan ideologi yang dibentuk
melalui budaya bangsa Indonesia sendiri. Adalah Pancasila, yang menjadi
dasar bagi negara Indonesia. Sedangkan penjelas bagi Pancasila termaktub
dalam Undang-undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan
umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.8
Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan
emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan
partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima
(keadilan) dari pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat
7
Triwibowo dan Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, h. 4. 8
dipisahkan. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, hasil rumusan
orisinil Panitia 9, kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung (“serta”), “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam
permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”9
Soekarno menyebut keterkaitan kedua sila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip “sosio-demokrasi”.
Istilah terakhir ini dia pinjam dari seorang teoritikus Marxis Austria, Fritz Adler, yang mendefinisikan “sosio demokrasi” sebagai “Politiek
ekonomische democratie” (demokrasi politik-ekonomi). Ungkapan Adler
yang sering dikutip Bung Karno adalah bahwa, “demokrasi yang kita kejar
janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi.”10
Dalam suatu pamflet berjudul „Menuju Indonesia Merdeka’ Bung
Hatta menulis, “Di atas sendi [cita-cita tolong menolong] dapat didirikan
tonggak demokrasi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil
yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang,
melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi
pedoman perusahaan dan penghasilan”. Selanjutnya dia menegaskan
bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dan saling terkait. “Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja
demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi.” Senada dengan itu,
Soekarno kerap mengatakan bahwa “Untuk membangun satu negara yang
9
Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas,dan Aktualitas Pancasila
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.491. 10
demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa
ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak
mungkin kita mendirikan negara, tak mungkin kita tetap hidup”.11
Para pendiri Republik Indonesia secara sadar menganut pendirian
bahwa revolusi kebangkitan bangsa Indonesia, sebagai bekas bangsa
terjajah dan sebagai bangsa yang telah hidup dalam alam feodalisme
ratusan tahun lamanya, haruslah berwajah dua: revolusi politik (nasional)
dan revolusi sosial. Revolusi politik (nasional) adalah untuk
mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu
Negara Republik Indonesia. Revolusi sosial adalah untuk mengoreksi
struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur.12
Cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari
revolusi Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan
demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan
pengintegrasian pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial
yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan. Keadilan
ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik
dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka
penguatan daulat rakyat (keadilan sosial). Sebagai katalis untuk
menghadirkan pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial
yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan itu, para pendiri
8 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 492.
bangsa menghendaki penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai
“Negara Kesejahteraan” (dalam istilah Yamin) atau “Negara Pengurus”
(dalam istilah Hatta).13
Sebagai gagasan atau cita-cita kebangsaan “Kesejahteraan Sosial”
pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945,
sebagai sila ke 4 Pancasila. Tapi istilah itu hilang dari rumusan Pancasila dan diganti dengan istilah “Keadilan Sosial”, sebuah istilah yang
dikemukakan oleh Bung Hatta. Tapi istilah keadilan sosial itu, oleh Bung
Hatta dijelaskan sebagai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat
diinterpretasikan bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang mendasari
kesejahteraan sosial. Dalam pengertian itu istilah kesejahteraan sosial sinonim dengan istilah “adil dan makmur” atau kemakmuran yang
berkeadilan yang dijelaskan juga sebagai kemakmuran yang merata di
antara semua warga atau istilah “samarasa-samarata” dalam istilah
pejuang sosialis Mas Marco.14
Istilah kejahteraan muncul kembali dalam Piagam Jakarta dan Mukaddimah UUD 1945, dalam istilah “kesejahteraan umum” sebagai
salah satu tujuan kemerdekaan. Sementara itu istilah kesejahteraan sosial
sendiri menjadi judul bab XIV UUD 1945, yang berisikan pasal 33 dan
34.15
Landasan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
dengan jelas menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara
13
Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 492-493.
14
M. Dawam Rahardjo, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Era Globalisasi, h. 1. 15
kesejahteraan. Tetapi sistem negara kesejahteraan Indonesia berbeda
dengan ketiga model sistem negara kesejahteraan diutarakan di atas.
Sistem negara kesejahteraan dari negara-negara kapitalis barat, baik model
universal, asuransi sosial, maupun selektif residual, semuanya berbasis
kapitalisme liberal, sebagai lampiran dari sistem kaptalisme, untuk
memelihara kelangsungan hidup kaptalisme, bukan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan yang adil. Sistem negara
kesejahteraan Indonesia berdasarkan demokrasi politik dan demokrasi
ekonomi.16
Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin memahami
dan mengkaji serta ikut berpartisipasi memberikan sedikit sumbangsih
literasi tentang “Konsepsi Negara Kesejahteraan Menurut Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar penelitian ini tidak jauh melebar perlu kiranya penulis
membatasi masalah, yaitu memfokuskan penelitian pada persoalan
bagaimana konsep negara kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945
serta bagaimana praktik negara kesejahteraan di indonesia.
Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan beberapa hal
pokok yang akan menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, antara
lain:
16
1. Bagaimana konsep Negara Kesejahteraan menurut Pancasila dan
UUD 1945 ?
2. Bagaimana praktik negara kesejahteraan di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui konsep negara
kesejahteraan menurut Pancasila dan UUD 1945.
2. Manfaat Penelitian
a) Manfaat Akademis
1) Melacak jejak akar konsep Negara Kesejahteraan
dalam sejarah politik Indonesia pada masa-masa
awal kemerdekaan.
2) Sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi
studi-studi selajutnya, dan akan menambah jumlah
studi mengenai Negara Kesejahteraan.
3) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
strata satu (S1) di Program Studi Kesejahteraan
Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
b) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai
referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang Negara
Kesejahteraan dan atau kebijakan sosial di Indonesia.
D. Metodelogi Penelitian 1. Pendekatan
Dalam menggarap skripsi ini, jenis data yang digunakan adalah
kualitatif dimana pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber
tertulis seperti buku, artikel, jurnal, serta majalah yang berkaitan dengan
Pancasila dan UUD 1945 serta hubungannya dengan konsep negara
kesejahteraan dan kesejahteraan sosial.
2. Teknik Pengumpulan Data
Secara kategoris, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini
menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu dengan
memanfaatkan sumber informasi yang berada di perpustakaan baik berupa
buku, jurnal dan lain sebagainya. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ’Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud
dengan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,
catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan. 17
17
Peneliti juga menambahkan metode wawancara dalam skripsi ini
kepada narasumber yaitu Yudi Latif (penulis buku Negara Paripurna dan
Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila). Alasan penulis
memilih Yudi Latif sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah karena
beliau fokus mengkaji Pancasila, itu terlihat dari karya-karyanya seperti “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila”
yang merupakan karya monumental yang oleh banyak kalangan intelektual
dianggap sebagai buku klasik yang menjadi rujukan di era mendatang, satu lagi adalah buku yudi latif yang berjudul “Mata Air Keteladanan:
Pancasila dalam Perbuatan”.
3. Teknik Analisis Data
Data tersebut kemudian diklasifikasi sesuai dengan judul yang akan
dibahas oleh penulis. Secara metodologis, penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis. Deskriptif berarti memaparkan dan menggambarkan secara
objektif isi seluruh UUD 1945 dan Pancasila dalam kaitannya dengan
materi muatan negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan sejarah dan sosial. Sementara analitis berarti upaya memahami
posisi, pemikiran, dan upaya menularkan gagasan baru tentang konsep
Negara Kesejahteraan disertai kritik dan kesimpulan.
4. Keabsahan Data
Pada teknik keabsahan data, penulis melakukan diskusi secara
analitis dimana hasil penelitian sementara diekspos. Kemudian, dilakukan
perbaikan secara terus menerus dan memfokuskan pada isu yang sedang
diteliti.
5. Pedoman Penulisan Skripsi
Untuk tujuan mempermudah, teknik penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini merujuk pada buku “Pedoman Karya Ilmiah” yang
diterbitkan oleh CeQda UIN Jakarta 2008.
E. Tinjauan Pustaka
Seperti yang telah disinggung di atas, topik tentang negara
kesejahteraan seolah tak ada habisnya untuk dikaji dan diteliti. Oleh
karena itu, penelitian tentang negara kesejahteraan juga telah banyak
dilakukan, akan tetapi hanya sedikit yang mengungkapkan dan meneliti
konsep negara kesejahteraan menurut Pancasila dan UUD 1945.
Dari beberapa skripsi yang penulis temukan ada juga yang
membahas negara kesejahteraan, tetapi tidak mengkhusukan diri pada
Pancasila dan UUD 1945 tentang konsep negara kesejahteraan. Seperti
skripsi Abdul Aziz Azamzami, dari Fakultas Ushuludin dan Filsafat,
Jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2008, yang berjudul Negara
Kesejahteraan Dalam Kepemimpinan Umar Bin Khattab. Skripsi ini,
sesuai dengan judulnya lebih mengulas konsep kepemimpinan syaidinna
Umar tentang negara kesejahteraan. Dalam bentuk karya tulis lain ada juga
yang membahas tentang negara kesejahteraan dalam konteks Indonesia
salah satunnya adalah Antonius Galih Prasetyo yang bertajuk “Ekonomi
karya tersebut berbebentuk prosiding yang diterbitkan oleh Institute of
International Studies Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, tahun 2013.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian skripsi ini, terdiri dari beberapa bab dengan
penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,
pedoman penulisan skripsi, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
BAB II : PENGERTIAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Menguraikan mengenai pengertian dan beberapa contoh model
Negara Kesejahteraan di dunia.
BAB III : ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCSILA dan UUD 1945
Menguraikan tentang latar belakang dan bentuk negara
kesejahteran dalam pancasila dan UUD 1945.
BAB IV: PRAKTIK NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA
Menguraikan tentang praktik negara kesejahteraan di Indonesia.
BAB V : PENUTUP
15 BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
A. Negara Kesejahteraan (Welfare State)
1. Pengertian Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Kesejahteraan rakyat merupakan wacana yang menarik untuk
selalu dijadikan bahan perdebatan oleh politisi dan akademisi, karena
kesejahteraan merupakan hal paling mendasar yang harus diciptakan oleh
negara. Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara
dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk
menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan mulia untuk mensejahterakan
rakyat, kemudian direalisasikan oleh negara lewat kebijakan-kebijakan
pelayanan sosial (social service). Dengan demikian dalam negara
kesejahteraan menuntut adanya peranan yang dominan dalam
pengelolaan sektor publik.
Seperti yang dituliskan pada bab sebelumnya pengertian tentang
sebuah negara kesejahteraan sangatlah beragam dan itu artinya
pengertian negara kesejahteraan tidak bersifat statis dan baku.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteran
adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan
mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan
hidup warga dengan memberantas pengangguran.1 Sedangkan Edi
Suharto dalam bukunya berjudul Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan
1
Publik mendefinisikan negara kesejahteraan (welfare state) sebagai
model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan
kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara
dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif
kepada warganya. Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah
untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga
bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan
kewajiban negara.2 Negara kesejahteraan sebenarnya tidak hanya
menciptakan pelayanan-pelayanan sosial untuk orang miskin saja, akan
tetapi pelayanan sosial ditunjukan untuk semua penduduk seperti; orang
tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin. Hal ini
dimaksudkan agar pelayanan sosial yang diselanggarakan oleh negara
bisa tersebar secara merata dan adil.
Karya Richard Titmuss, Essays on the Welfare State (1958) telah
mendapat tempat istimewa dalam studi-studi tentang negara
kesejahteraan, Buku Titmuss ini dapat dikatakan sebagai magnum-opus
yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai
berikut: "a welfare state is a state in which organized power is
deliberately used through politics and administration in an effort to
modify the play of market forces to achieve social prosperity and
economic well-being of thepeople".3
2
Edi Suharto, Kebijakan Sosial:Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: ALFABET, 2007), h. 57.
3 Richard Titmuss, “Essays on the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed.,
Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial.
Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk
memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan
hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial
jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga
mereka dapat menghadapi masa-masa krisis, seperti sakit, usia lanjut,
menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak
pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status
dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan
sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak
balita), sanitasi, dan air bersih.4
Negara kesejahteraan sering ditengarai dari atribut-atribut
kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan negara
kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan,
pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan kebijakan
sosial sering diidentikkan.5 Namun hal tersebut dinilai kurang tepat
karena kebijakan sosial dan negara kesejahteraan tidak mempunyai
hubungan dua arah. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan
negara kesejahteraan, tapi sebaliknya negara kesejahteraan selalu
membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.6
Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara
kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (i) social
4 Titmuss, “Essays on the Welfare State” h. 12. 5
Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES,2006), h. 8.
6
citizenship; (ii) full democracy; (iii) modern industrial relation systems;
serta (iv) rights to education and the expansion of modern mass
education systems.7 Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara
kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial
sebagai “penganugerahkan hak-hak sosial” (the granting of social rights)
kepada warganya yang diberikan berdasarkan basis kewargaan
(citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.8
Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari
ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan
yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya
sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan
sosial yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak
sosial dan social citizenship ini digunakan oleh negara untuk menata
ulang relasi kelas dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan
kelas yang terjadi. Seperti yang di ungkapan oleh Esping-Andersen: “…negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme untuk
melakukan intervensi terhadap, atau mengoreksi struktur
ketidaksetaraan yang ada. Namun, merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan merupakan suatu kekuatan
yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial…”.9
Jelaslah bahwa negara kesejahteraan adalah lebih dari kumpulan
kebijakan sosial. Keberadaannya tidak bisa dengan sederhana diukur
melalui besaran pengeluaran sosial oleh negara karena negara
7
Esping-Andersen “Three World of Welfare Capitalism” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 9.
8 Esping-Andersen “Three World of Welfare Capitalism” h. 9.
kesejahteraan adalah upaya negara untuk menggunakan kebijakan sosial
sebagai alat untuk meredefinisikan relasinya terhadap warga. Seperti
halnya yang diungkapkan Marshall:
“…istilah tersebut (negara kesejahteraan) merujuk pada suatu komitmen politik yang baru, penulisan ulang kontrak sosial antara negara dan warganya.. yang melibatkan pengakuan atas hak sosial seluruh warga dan merefleksikan suatu tekad untuk menjembatani
kesenjangan kelas sosial yang ada…”.10
Dalam negara kesejahteraan, adanya sistem kesejahteraan sebagai
hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terakait, yaitu
pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh (full employment).
Di satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsentif bagi warga
untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga Negara harus
menerapakan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif untuk mendorong
partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya
basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai
melalui sistem perpajakan yang kuat yang hanya dimungkinkan dalam
pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah didalamnya.
Segitiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak
sosial-kebijakan aktif tenaga kerja merupakan karakteristik kunci dari
suatu negara kesejahteraan.11
Negara kesejahteraan sendiri bukanlah satu entitas berwajah
tunggal. Luas cakupan dan ragam kebijakan sosial yang diterapkan oleh
negara bervariasi dari satu negara kesejahteraan dengan negara
10 Esping-Andersen, “Social Foundation for Postindustrial Economies” h. 10-11.
kesejahteraan lainnya. Titmuss telah mengidentifikasi adanya dua
tipologi negara kesejahteraan, yaitu residual welfare state dan
institusional welfare state. Residual welfare state mengasumsikan
tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan jika dan hanya
jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada
kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marginal serta
mereka yang patut mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara.
Sedangkan institutional welfare state bersifat universal, mencakup
semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijkan sosial
yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat.12
Penggolongan Titmuss membawa kita pada pemahaman tentang
pengaruh rezim kesejahteraan terhadap kemampuan negara
kesejahteraan untuk memproduksi dan mendistribusi kesejahteraan
melalui kebijkan sosial. Rezim kesejahteraan mengacu pada pola
interaksi dan saling keterkaitan dalam produksi dan alokasi
kesejahteraan antara negara, sistem pasar, dan keluarga/rumah tangga.
Ketiga lembaga tersebut merupakan penyedia kesejahteraan dan tempat
individu mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko sosial.
Masing-masing lembaga menerapkan pola pengelolaan resiko yang berbeda.
Sebagai contoh, dalam keluarga, pola alokasi kesejahteraan bersandar
pada resiprositas (reciprocity), sedangkan pada pasar basisnya adalah
pertukaran tunai (cash nexus), dan dalam negara basisnya adalah
redistribusi otoritatif (authoritative redistribution) melalui kebijakan
12
sosial. Bagaimana risiko dikelola dan siapa aktor utama pengelola
risiko/penyedia kesejahteraan akan menentukan bentuk rezim
kesejahteraan.13
2. Filosofi Negara Kesejahteraan
Negara kesejahteraan adalah bagian dari rezim kesejahteraan.
Rezim mengacu pada seperangkat norma, prinsip, aturan dan prosedur
pengambilan keputusan, baik implisit maupun eksplisit, yang
menyatukan ekspektasi para aktor dalam wilayah tertentu dalam
kehidupan sosial.14 Sebagai temuan kelembagaan (institutional invention)
dalam suatu bentuk rezim, negara kesejahteraan juga terikat dan
didasarkan pada kerangka etik spesifik. Barr (1998) menyatakan bahwa
kerangka etik negara kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai
Katolik dan pengaruh doktrin karitatif sosial (social charity) gereja. Hal
senada juga diungkapkan oleh Huber dan Stephens (2001) maupun
Manow (2004) yang menengarai pengaruh doktrin sosial katolik dalam
desain dan proses pengembangan negara kesejahteraan di negara-negara
Eropa. Manow menyimpulkan bahwa perbedaan rezim kesejahteraan di
negara-negara Eropa juga dipengaruhi oleh “ragam” basis religius, yang
didalamnya negara-negara dengan basis Protestan reformis lebih memilih
rezim kesejahteraan liberal; negara dengan basis Protestan Lutheran
cenderung kearah rezim sosial demokrat; sedangkan negara dengan basis
13
Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, h. 13-14.
Gereja Katolik Roma lebih condong ke rezim kesejahteraan
konservatif.15
Kelley (1994) menyatakan bahwa etika Katolik yang “alergi”
terhadap orientasi-diri (selfishness) dan ketamakan (avarice),
menyebakan munculnya paham keadilan sosial yang menjadi legitimasi
intervensi negara terhadap mekanisme pasar.16 Kelley membagi paham
keadilan sosial menjadi dua aliran, yaitu Welafrism dan egalitarianism.
Welafrism memandang bahwa individu mempunyai hak untuk
mendapatkan kebutuhan dasar tertentu dalam hidup, sehingga menjadi
kewajiban masyarakat untuk memastikan setiap individu mempunyai
akses pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sistem kapitalis laissez-faire
tidak mampu menjamin tercapainya hal tersebut, sehingga dibutuhkan
intervensi negara untuk memodifikasi pasar agar bisa memenuhi
tanggung jawab distribusinya. Egalitarianism, disisi lain, menyatakan
bahwa kemakmuran yang diproduksi oleh masyarakat harus
didistribusikan dengan adil. Sistem kapitalis berbasis pasar cenderung
membenarkan bahkan mendorong terjadinya kesenjangan, baik
pendapatan maupun kemakmuran di antara individu-individu. Inilah yang
menyebabkan dibutuhkannya negara untuk memastikan terjadinya
distribusi kemakmuran yang lebih merata.
Paham ini sangat dekat dengan pandangan liberal dalam teori
sosial. Seperti yang diungkapkan George dan Wilding dalam Barr (1998),
15
Philip Manow, “The Good, the Bad,and the Ugly: Esping-Andersen’s Regime Typology and the Religious Roots of the Western Welfare State,” dalam Triwibowo dan Bahagijo,
Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 19. 16
kaum liberal memandang bahwa: (i) kapitalisme merupakan sistem yang
paling efisien dibandingkan dengan sistem lain yang ada; (ii) meskipun
efisien, kapitalisme mempunyai efek negatif berupa kemiskinan dan
ketimpangan; (iii) negara mampu mengatasi efek negatif tersebut.
Berbeda dengan kaum natural –right libertarian (seperti Nozick), yang
memandang intervensi negara salah secara moral, dan kaum empirical
libertarian (seperti layaknya Hayek dan Friedman), yang memandang
bahwa campur tangan negara akan menurunkan kesejahteraan agregat,
kaum liberal meyakini pentingnya fungsi redistribusi kesejahteraan dari
negara untuk menjamin terjadinya keadilan sosial dan pemerataan dalam
sistem kapitalis.17 Merujuk pada Beveridge:
“(adalah suatu hal yang penting) untuk menggunakan kuasa negara, sepanjang diperlukan dengan tanpa
batasan apapun, untuk menghindari merajalelanya lima „iblis’
utama didalam tatanan masyarakat, yaitu ketamakan, penyakit
menular, ketidakpedulian, kekejaman (squalor), serta kesia-siaan
(idleness)”18
Seperti halnya Beveridge, Keynes memandang bahwa kapitalisme
tidak mengatur dirinya sendiri.19 Berbeda dengan yang dijanjikan hukum
pasar say, permintaan tidak selalu bisa mengimbangi tingkat produksi.
Keynes menunjukkan bahwa kapitalisme, sebagai suatu sistem ekonomi,
tidak selalu akan dengan sendirinya mengoordinasi permintaan dan
penawaran dengan harmonis melalui mekanisme pasar bagi keseluruhan
17
Nicholas Barr, “The Economics of the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo,
Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 20-21. 18 Barr, “The Economics of the Welfare State”
h. 22. 19
perekonomian, khususnya ketika terjadi defisit permintaan agregat.20
Kaum kolektivis setengah hati, seperti Keynes, Galbraith, dan Beveridge,
sependapat dengan pandangan liberal dan percaya tentang dibutuhkannya
peran negara dalam perokonomian. Mereka berpendapat bahwa negara
dibutuhkan untuk memikul tanggung jawab pengelolaan perekonomian
guna memelihara suatu agregat permintaan yang akan menjamin
kesempatan kerja penuh.21 Mereka juga percaya bahwa tanpa tindakan
pemerintah, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu mengahapuskan
kemiskinan.22
Hanya saja, seperti disampaikan Tawney, negara kesejahteraan
bukanlah wujud dari sosialisme.23 Dalam format negara kesejahteraan
memang terdapat persinggungan antara pemikiran liberal dan kolektivis sosial demokrat, khususnya dalam area “social justice” dan “mutual
responsibility and the duty of the strong aid to the weak”.24 Namun,
persinggungan tersebut tidak bisa menghapuskan perbedaan dasar
diantara pandangan kolektivis dan liberal. Kaum kolektivis menilai
negara kesejahteraan sebagai bentuk peralihan dari kapitalisme
laissez-faire menuju sosialisme, sehingga dalam kaca mata mereka, negara kesejahteraan tidak pernah lebih dari suatu “tahapan antara” (a staging
post in the transition).25 Kaum kolektivis Marxian bahkan menilai
20
George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h. 82. 21
George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h.90. 22
George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h.93. 23
George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h.108.
24 Nicholas Barr, “The Economics of the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo,
Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 22. 25
negara kesejahteraan bukan didorong oleh motif keadilan sosial,
melainkan lebih sebagai tipu daya kaum kapitalis untuk melindungi
kepentingan kapitalisme itu sendiri. Negara kesejahteraan kemudian
hanya berfungsi membantu memenuhi kebutuhan industri kapitalis untuk
tenaga kerja terdidik yang sehat, dan itu adalah uang tebusan yang
dibayar oleh elite penguasa yang mengandung kerusuhan sosial.26
Pandangan a la Marx ini akurat pada tahap awal pengembangan negara
kesejahteraan, khususnya di Eropa kontinental yang konservatif, tapi
menjadi tidak akurat dengan makin berkembangnya pengakuan hak
sosial warga yang makin universal, khususnya di Skandinavia.
Rawls, Keynes, Beveridge, maupun Galbraith, sebaliknya,
bukanlah kolektivis. Mereka memandang kapitalisme sebagai sistem
yang paripurna dan negara kesejahteraan adalah upaya untuk
menyelamatkan kapitalisme agar bisa lebih diterima secara moral dengan
menggunakan campur tangan negara.27 Apa yang ingin mereka capai
adalah menyelamatkan kapitalisme dan unsur-unsur pentingnya, sambil
mengurangi atau menghapus hal-hal yang sekarang tidak dapat diterima.
Keynes melihat kesalahan-kesalahan kapitalisme lebih sebagai kesalahan
teknis daripada kesalahan mendasar. Kapitalisme, merujuk pada Keynes,
jika dikelola secara bijak mungkin dapat menjadi alat yang efisien untuk
mencapai tujuan ekonomi dibandingkan dengan sistem lain manapun
yang dibayangkan. Melalui tindakan yang tepat ia percaya bahwa suatu
26
Triwibowo dan Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, h. 23. 27
jalan tengah dapat ditemukan antara anarki laissez-faire dan kelaliman
totaliterisme.28 Negara kesejahteraan, dengan demikian, merupakan jalan
tengah tersebut.
3. Sejarah dan Dinamika Negara Kesejahteraan
Gagasan Negara kesejahteraan lahir di Eropa sebagai respon
kemiskinan akibat proses industrialisasi pada abad 19. Munculnya
teknologi baru dalam industri dimana mesin-mesin mengambil peran
lebih dan menggantikan tenaga manusia mengakibatkan pengangguran
dan menurunkan upah buruh. Dengan demikian, maka sumber
kemiskinan ada dua, upah buruh rendah dan pengangguran.
Di Jerman cikal bakal Welfare State adalah program kesejahteran
yang diciptakan oleh Kanselir Jerman, Otto Van Bismark (1815-1878).
Latar belakang ontologisnya adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh
proses industrialisasi yang menimbulkan kemerosotan kesejahteraan
dikalangan kaum buruh. Karena kekhawatiran terhadap gerakan sosialis
yang merebak kuat di Jerman ketika itu, maka Bismark berusaha
membendungnya dengan program kesejahteraan dalam bidang yang
sempit, yaitu jaminan sosial dalam bentuk skema asuransi oleh negara.
Tapi UU itu disertai dengan UU Anti-Sosialis pada tahun 1878, yang
pada intinya adalah pemberangusan kebebasan pers.29 Dalam kasus ini
program kesejahteran sosial yang di gagas oleh Bismark adalah sebagai
peredam dari gerakan sosialisme yang masiv di negara-negara eropa
28
George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h. 84. 29
dalam konteks ini adalah Jerman. Setelah Jerman pada tahun 1884
menerapkan sistem asuransi nasional wajib pertama untuk
penanggulangan penyakit. Segera setelah itu Denmark dan
Negara-negara Skandinavia lain ikut menyusul.
Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963) adalah
merupakan tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara
kesejahteraan. Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance
and Allied Services (asuransi sosial dan kumpulan pelayanan sosial),
yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge, menyebut
kekurangan (want), kemelaratan (squalor), Kebodohan (ignorance),
Penyakit (disease) dan Kemalasan (idleness) sebagai „the five giant evil’
(lima setan-setan raksasa) yang harus diperangi. Dalam laporan itu,
Beveridge, memiliki gagasan-gagasan mengenai perlindungan hak-hak
warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu dengan
menciptakan sebuah sistem asuransi sosial yang komperhensif. Menurut
Beveridge, hanya sistem itu yang mampu memberikan kesejahteraan dan
mampu melindungi hak-hak warga negara dari mulai lahir hingga
meninggal (from cradle to grave). Pengaruh laporan Beveridge tidak
hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di
Eropa dan bahkan hingga ke Amerika Serikat dan kemudian menjadi
dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara
tersebut.30
Kesejahteraan sosial dengan sistem asuransi yang digagas oleh
Beveridge, memiliki banyak kekurangan. Karena dengan menggunakan
dasar prinsip dan skema asuransi, banyak resiko-resiko yang dihadapi
oleh warga negara, terutama ketika mereka tidak mampu membayar
kontribusi (premi). Kemudian asuransi sosial juga tidak mampu
merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti; orang cacat,
orang tua tunggal, serta orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan.
Manfaat asuransi sosial terkadang tidak mampu memenuhi kesejahteraan
warga negara, karena jumlahnya yang terlalu kecil sehingga hanya
mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal.
Marshall, memiliki pemikiran yang berbeda mengenai
kesejahteraan sosial terutama dalam konteks kapitalisme. Menurutnya
kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial menjadi
tanggungjawab semua warga negara. Warga negara memiliki kewajiban
kolektif untuk memperjuangkan kesejahteraan orang lain lewat sebuah
lembaga yang disebut negara. Ketidakadilan yang disebabkan karena
ketidak sempurnaan pasar menyebabkan kesejahteraan sosial tidak
tumbuh secara merata dalam kehidupan warga negara. Menjadikan
negara sebagai lembaga yang mampu menciptakan pelayanan sosial dan
kesejahteraan sosial merupakan sebuah solusi untuk menutupi dan
mengurangi ketidak sempurnaan pasar dan juga untuk mengurangi
dampak-dampak negatif dari sistem kapitalisme.31
Pematangan konsep negara kesejahteraan terjadi pada periode
akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pada periode-periode tersebut di
negara-negara Eropa khususnya, kebijakan-kebijakan sosial tumbuh
dengan pesat dan negara banyak mengeluarkan kas negaranya untuk
menciptakan pelayanan sosial. Negara-negara Eropa banyak mengadopsi
berbagai program jaminan sosial baru, seperti; program pensiun, program
jaminan orang cacat, dan santunan bagi pengangguran.32
Program-program kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh negara terus
mengalami peningkatan sesuai dengan kemajuan industrialisasi dan laju
pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Sistem negara kesejahteraan mencoba menjadi penyeimbang
antara peran negara dan pasar, antara oligarki dan redistribusi ekonomi,
antara pertumbuhan dan pemerataan. Seperti Amerika Serikat, Inggris,
Kanada, Uni Eropa dan negara Skandinavia, menganut negara
kesejahteraan atau welfare state sebagai langkah untuk membangun
kesejahteraan sosial warganya. Seperti telah dijelaskan diatas, pada
hakikatnya kesejahteraan sosial merupakan hak asasi warga negara yang
wajib dipenuhi oleh negara. Maka, hak asasi merupakan sebuah titik
sentral pertimbangan negara dalam pengambilan kebijakan-kebijakan
sosial. hak-hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara,
yaitu; hak untuk mendapatkan keamanan sosial, hak mendapatkan
pekerjaan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak
mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan
32
jaminan-jaminan sosial lainnya. Bila hak warga negara tidak dipenuhi
oleh negara maka negara telah melakukan pelanggaran kemanusiaan dan
tidak menjalankan fungsinya.33
Upaya untuk menyingkirkan peranan negara atau intervensi
negara terhadap kebijakan-kebijakan publik telah dimulai sejak lahirnya
pemikiran aliran Kanan Baru, aliran ini sering disebut ekonomi
Thatcherisme atau Reaganisme.
Neoliberalisme pertama kali dipraktekkan oleh Perdana Menteri
Margareth Thatcher di Inggris, yaitu dengan menghapus kewajiban
negara memikul tanggung jawab terhadap rakyat yang tidak produktif,
meminggirkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan full employment
(kesempatan kerja penuh), memangkas secara radikal subsidi-subsidi
sosial, dan sebagai gantinya, pemerintahan Thatcher lebih mementingkan
pelayanan terhadap swasta, melakukan pemotongan pajak, menjalankan
program privatisasi/swastanisasi dan liberalisasi, menghilangkan
pengawasan terhadap penyiaran, telekomunikasi, transportasi, dan
perikanan, kemudian membabat habis seluruh serikat buruh dan
menyalahkannya sebagai penyebab rendahnya kinerja industri Inggris.34
Pelucutan peran negara terus berlanjut lewat pengaruh globalisasi
pada abad ke-21. Istilah globalisasi menempati berbagai agenda
intelektual dan politik. Kata itu sekarang muncul dimana-mana, pidato
politik tidak lengkap, atau manual bisnis tidak dapat diterima jika tidak
33
Negara dan Kesejahteraan, artikel diakses pada 6 September 2015 dari http://www.inilah.com/berita/2008/07/24/40004/negara-dan-kesejahteraan/.
34
menyebut kata globalisasi. Globalisasi dengan segala kebaikan dan
keburukannya telah mendorong perdebatan intens, dan menjadi pusat dari
sebagian besar diskusi politik dan perdebatan ekonomi.35
Istilah globalisasi berakar pada konsep yang lebih umum bahwa
akumulasi modal, perdagangan dan investasi tidak lagi dibatasi pada
negara-bangsa. Dalam pengertiannya yang lebih umum, globalisasi
mengacu pada aliran-aliran barang, investasi, produksi dan teknologi
lintas bangsa. Globalisasi telah menciptakan sebuah tatanan dunia baru
dengan lembaga-lembaga dan konfigurasi-konfigurasi kekuasaannya
yang menggantikan struktur-struktur sebelumnya yang diasosiasikan
dengan negara-bangsa.36
Perkembangan ekonomi global memiliki implikasi terhadap
negara kesejahteraan (welfare state). Batas dan kekuatan negara yang
semakin memudar, organisasi-organisasi independen, badan-badan
supra-nasional dan perusahaan perusahaan multisupra-nasional. Sebuah konsekuensi
logis dari kecenderungan global dan telah memunculkan kritik terhadap
sistem negara kesejahteraan yang dipandang tidak tepat lagi untuk
diterapkan sebagai pendekatan dalam pembangunan suatu negara.
Bahkan berkembangnya anggapan yang menyatakan bahwa negara
kesejahteraan telah mati (welfare state has gone away and died).37
35
Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, dengan judul asli buku; “The Third Way: The Renewal of Social Democracy” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),
Cet. Ke-4, h. 32. 36
James Petras dan Henry Veltmeyer, Imperialisme Abad 21, dengan judul asli buku; “Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 Century” (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2002), h.37.
37 Edi Suharto, “
Peta dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara”, artikel diakses
pada tenggal 12 September 2016 dari
Edi Suharto, dalam makalahnya yang berjudul “Islam dan Negara
Kesejahteraan” mengutip dari bukunya Ramesh Misrah, yang berjudul
“Globalization and welfare state” , dijelaskan bahwa globalisasi telah
membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan
sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank)
dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF)
menjual kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara
berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil
pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan
terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.38
Adanya anggapan yang mengatakan bahwa negara kesejahteraan
telah berakhir (mati), karena tidak mampu menghadapi ancaman
globalisasi dan berkuasanya sistem kapitalisme adalah sebuah anggapan
yang tidak benar. Sistem Negara Kesejahteraan masih tetap berdiri kokoh
dengan segala skema-skema kesejahteraan sosial yang dipraktekkan di
negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, bahkan di negara-negara yang
menganut paham liberal yang kuat seperti Amerika, Inggris dan
Australia. Dalam hal ini, negara kesejahteraan sedang mengalami
reformulasi dan penyesuaian sejalan dengan tuntutan perubahan tatanan
global. Jadi, sangat salah bila menganggap sistem negara kesejahteraan
telah menemui akhir dari sejarahnya.
38 Edi Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan”, artikel diakses pada tanggal 25 September 2016 dari
Salah satu bukti yang mampu mematahkan mitos the end of
welfare state, adalah masih beroperasi 3 (tiga) model negara
kesejahteraan yang dipraktekkan oleh negara-negara di dunia, yaitu:39
1. Model Residual (Residual Welfare State)
Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang
meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia
Baru. Model negara kesejahteraan residual dicirikan dengan basis
rezim kesejahteraan liberal dan pemberian jaminan sosial kepada
warga negara secara terbatas dan selektif, serta adanya kesempatan
besar bagi swastanisasi pelayanan publik. Umumnya pelayanan
sosial yang diberikan berjangka pendek dan relatif kecil.
2. Model Universal (Universalist Welfare State)
Model universal sering juga disebut sebagai The
Scandinavia Welfare State. Model ini diadopsi oleh negara-negara
seperti; Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Belanda.
Model negara kesejahteraan ini dicirikan dengan basis rezim
kesejahteraan sosial demokrat dan jaminan sosial yang diberikan
kepada warga negara bersifat komprehensif.
3. Model Korporasi (Social Insurance Welfare State)
Model korporasi ini diadopsi oleh negara-negara seperti;
Jerman, Austria, Belgia, Prancis, Italia, dan Spanyol. Model negara
kesejahteraan ini dicirikan dengan basis rezim kesejahteraan
konservatif dan jaminan sosial yang diberikan kepada warga negara
39
Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan
dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi
terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pilar,
yaitu; pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Dalam hal ini,
pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan
terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan
kontribusi melalui skema asuransi sosial. Ide model negara
kesejahteraan ini pertama kali dikembangkan oleh Otto Van
Bismarck dari Jerman, dan model negara kesejahteraan ini sering
disebut sebagai model Bismarck.
Globalisasi yang menjadi anak kandung dari sistem kapitalisme
memiliki peran yang besar dalam upaya pelucutan segi tiga “suci”
(pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja penuh-jaminan sosial) sistem
negara kesejahteraan. Seiring perubahan tatanan global dan perekonomian
dunia, peristiwa itu telah memaksa sistem negara kesejahteraan yang
dipraktekkan di beberapa negara-negara direstrukturisasi. Restrukturisasi
itu sebenarnya lebih kepada upaya untuk melucuti skema-skema
kesejahteraan yang ada dalam sistem negara kesejahteraan.40
Negara memang bukan satu-satunya lembaga yang dapat
menyelenggarakan pelayanan sosial kepada warga negaranya. Namun,
negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada
warga negaranya sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan sosial,
dan mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat dari
pada masyarakat, dunia usaha atau lembaga-lembaga kemanusiaan
40
internasional. Negara sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik
yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, memiliki kewajiban untuk
memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak dasar warga negara,
ekonomi dan budaya.
Edi Suharto, dalam makalahnya yang berjudul “Negara
Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, mengutip dari buku Bessant, Rob
Watts Judith, Tony Dalton dan Paul Smith yang berjudul, “Talking Policy:
How Social Policy in Made”, menjelaskan bahwa akar atau ide dasar
konsep negara kesejahteraan telah ada sejak abad ke-18, yaitu ketika
Jeremy Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest
happiness (welfare) of the greatest number of their citizens (kebahagiaan
terbesar atau kesejahteraan dari sebanyak-banyaknya warga negara
mereka). Ia mencoba menjelaskan konsep kebahagiaan dan kesejahteraan
dengan menggunakan istilah kegunaan (Utilitarian). Menurutnya segala
sesuatu yang mampu menciptakan atau menghadirkan kebahagiaan yang
lebih adalah sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya sesuatu yang tidak
menghadirkan kebahagiaan atau kesejahteraan adalah sesuatu yang buruk.
Dalam hal ini ia ingin menjelaskan bahwa negara harus mampu
menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan sebanyak mungkin untuk
rakyat. Negara pun harus mampu melakukan upaya reformasi hukum yang
tidak mengarah kepada kesejahteraan, peran konstitusi dan penelitian
gagasan-gagasannya itu ia digelari sebagai “Bapak Negara Kesejahteraan” (father
of welfare state).41
37 BAB III
NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UUD 1945
A. Latar Belakang Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila
Dalam penetapan tujuan-tujuan hidup berbangsa dan bernegara, sebuah
bangsa merumuskan konsep-konsep tersendiri yang diidentifikasi oleh pemimpin
dan rakyatnya sebagai kristalisasi dari hasrat dan ikhtiar untuk membumikan
apa-apa yang dianggap sebagai ideal. Dasar dan ideologi negara seringkali menjadi
payung dan sumber referensi utama untuk pencarian tujuan-tujuan bersama
tersebut. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai sumber mata air
konseptual tersebut sehingga darinyalah kemudian para pendiri bangsa
merumuskan model-model tata pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam segala bidang. Termasuk dalam konteks negara kesejahteraan di Indonesia,
Pancasila merupakan sumber telaah penting. Sehingga membaca dan mempelajari
teks serta konteks dalam proses perumusan Pancasila adalah jalan untuk
menemukan pengetahuan tentang bagaimana negara ini dirancang.
Sejarah konseptualisasi pancasila sudah melewati beberapa fase yang panjang, fase “pembuahan” ,fase “perumusan” dan fase “pengesahan”. Fase
“pembuahan” dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk
mencari sintesis antar ideologi dan gerakan. Fase “perumusan” dimulai pada masa
persidangan pertama BPUPK dengan pidato Soekarno (1 juni) yang kemudian
memunculkan istilah pancasila, dan di godok melalui pertemuan Chuo Sangi in