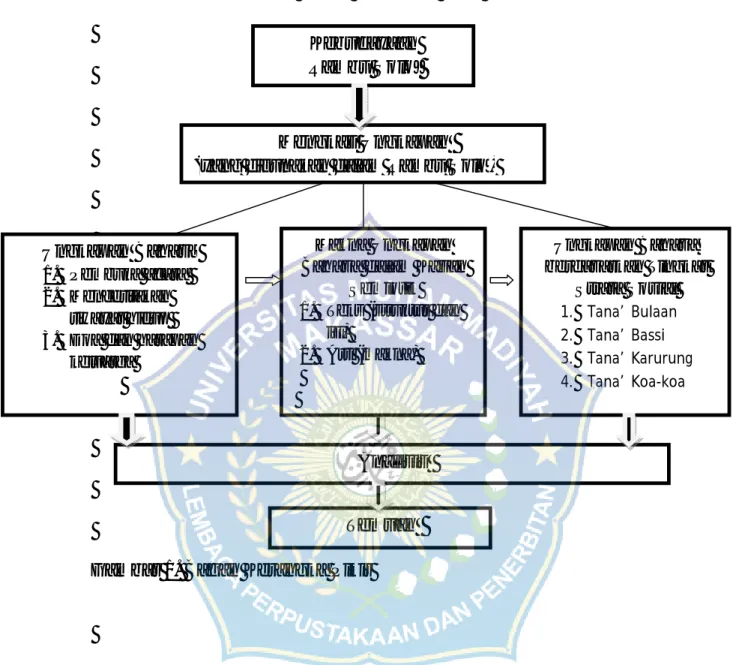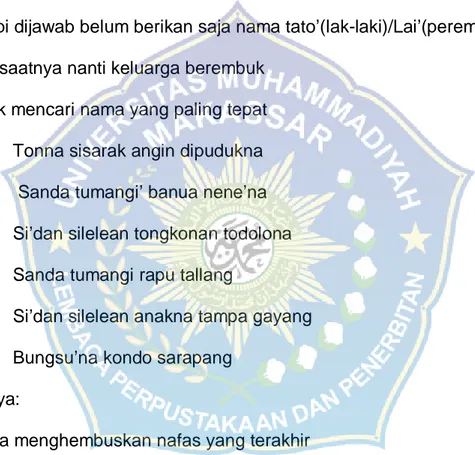RITUAL “RAMBU SOLO” NORTH TORAJA
TESIS
Oleh
MAKDALENA
Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.910.2013
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
TESIS
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister
PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA
DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH
MAKDALENA
Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.910.2013
Kepada
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
Yang Disusun dan Diajukan oleh
MAKDALENA
Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.910.2013
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 01 Juni 2015Menyetujui Komisi Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Munirah, M.Pd. Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana Ketua Prodi Magister Pend Bahasa dan Sastra Indonesia
Prof. Dr. H.M. Ide Said D M, M.Pd. Dr. Abdul Rahman Rahim , M.Hum.
Solo’ Masyarakat Balusu Toraja Utara
Nama : Makdalena
Nim : 04.08.910.2013
Program studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia
Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 01 Juni 2015 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, 01 Juni 2015
TIM Penguji :
1. Dr. Munirah, M.Pd. ...
(Pembimbing I)
2. Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. ... (Pembimbing II)
3. Prof. Dr. H. M. Ide Said D M, M.Pd. ... (Penguji I)
4. Dr. Abdul Masyhar, M.Si. ... (Penguji II)
NIM : 04.08.910.2013
Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 30 Mei 2015 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis, Panitia Penguji :
1. Dr. Munirah, M.Pd. ( )
(Pembimbing I)
2. Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. ( )
(Pembimbing II)
3. Prof. Dr. H.M. Ide Said D M, M.Pd. ( ) (Penguji I)
4. Dr. Abdul Masyhar, M.Si. ( )
(Penguji II)
Makassar, Mei 2015
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Makassar
Tetapi, Tuhan Yang Maha Kuasa menetukan segalanya
Kupersembahkan karya ini untuk ibu dan ayahku
yang telah memberiku kasih sayang yang tulus dan ikhlas
kepada keluarga kecil serta saudara-saudaraku yang telah tulus dan iklas mendoakan dan memberiku semangat untuk meraih cita-cita.
Nim : 04.08.910.2013
Program studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan
pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian
hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis
ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan
tersebut.
Makassar, ... Mei 2015
Yang menyatakan,
HALAMAN JUDUL ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
MOTO ... iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ... v
ABSTRAK ... vi
ABSTRACT ... v
KATA PENGANTAR ... vii
DAFTAR ISI ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN ... xii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Penelitian ... 1
B. Rumusan Masalah ... 6
C. Tujuan Penelitian... 7
D. Manfaat Penelitian... 8
E. Batasan Istilah ... 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 10
A. Tinjauan Hasil Penelitian ... 10
B. Tinjauan Teori dan Konsep ... 12
C. Kerangka Pikir ... 64
BAB III METODE PENELITIAN ... 66
A. Jenis Penelitian ... 66
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 68
C. Unit Analisis dan Penentuan Informan ... 68
D. Teknik Pengumpulan Data ... 69
E. Teknik Analisis Data ... 70
B. Paparan Dimensi Penelitian ... 79
C. Pembahasan ... 137
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 143
A. Simpulan ... 143 B. Saran ... 144 DAFTAR PUSTAKA ... 145 RIWAYAT HIDUP ... 146 LAMPIRAN ... 148 1. KORPUS DATA ... 148 2. IZIN PENELITIAN ... 149 3. BIODATA INFORMAN ... 4. DOKUMENTASI ...
Tujuan penelitian mengetahui Ungkapan Bahasa dalam Ritual Budaya Rambu Solo’. Makna kajian semiotik menggungkap makna yang terdapat dalam ungkapan bahasa ritual budaya Rambu Solo’. Perbedaan ungkapan bahasa berdasarkan strata sosial masyarakat dalam ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja Utara
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dari pengamatan yang berwujud pernyataan atau kata-kata dari informan yang mendeteksikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dalam ritual Rambu Solo’. Selain itu, mengambil konsep dasar dari studi etnografis karena etnografi terkait dengan konsep budaya (cultural concept). Subjek penelitian atau informan, yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, To’minaa/Pemangku adat, dan Protokol upacara Rambu Solo’. Terkait kriteria penilaian pada ungkapan bahasa dalam Rambu Solo’ berdasarkan tingkat strata sosialnya adalah diksi yang ada dalam ungkapan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, teknik observasi, dan teknik wawancara, sedangkan teknik analisis data melalui beberapa tahap, yaitu mengorganisasikan data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data, mencari alternatif penjelasan bagi data, dan menulis hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan bahasa yang terdapat dalam ritual Rambu Solo’ sesuai dengan strata sosialnya merupakan bentuk komunikasi dalam lingkungan masyarakat juga menjadi identitas atau ciri dari lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, terkait nilai-nilai yang terkandung dapat dipahami dari pesan-pesan yang disampaikan secara tersirat dalam ungkapan bahasa tersebut seperti nilai tentang harga diri pada ungkapan dalam bahasa Indonesia yaitu Berkumpullah semua keluarga. Bersatu
saudara-saudara. Membangun tongkonan. Mendirikan rumah adat. Menancapkan tiang besar. Tempat melaksanakan ritus. Pagelaran pesta besar. Kajian makna yang bernilai tentang harga diri dilihat pada ungkapan
membangun tongkonan, mendirikan rumah adat dan bentuk tersirat. Perbedaan dari ungkapan berdasarkan tingkat strata sosial dari hasil penelitian di atas sangat jelas, dapat dilihat pada ungkapan tentang “penghormatan kepada yang hadir” antara strata satu dan yang lainnya berbeda pengucapan tetapi makna yang ada di dalammya sama yaitu memberi rasa hormat kepada tamu yang hadir.
2. Surat Keterangan Pembimbing ... 149
3. Surat Izin Penelitian dari Dekan ... 149
4. Dokumentasi ... 150
Tana’ Bassi : Kasta bangsawan menengah
Tana’ Karurung : Rakyat merdeka atau kebanyakan
Tana’ Koa-Koa : Kasta hamba sahaya
Tominaa : Subjek atau pelaku yang berperan dalam
mengucapkan ungkapan bahasa pada budaya
berjudul “Ungkapan Bahasa dalam Ritual Budaya Rambu Solo’
Masyarakat Balusu Toraja Utara” dapat penulis selesaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari
berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga
kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
Dr. Munirah, M. Pd. pembimbing I dan Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum.
pembimbing II dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu,
tenaga, dan pikiran memberikan bimbigan, motivasi, arahan, dan
saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan tesis.
Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada
Dr. Irwan Akib, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia. Prof. Dr. H. M. Ide Said D M, M.Pd. Direktur Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
mengizinkan penulis dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk
melaksanakan penelitian dan menyiapkan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan selama menempuh pendidikan Program S-2. Penulis tidak
mengikuti pendidikan serta membimbing selama proses perkuliahan
hingga selesai. Seluruh Sivitas Akademika yang selama ini memberikan
arahan dan bimbingan kepada penulis.
Ucapan terima kasih kepada informan di wilayah Kecamatan
Balusu Toraja Utara atas segala bantuannya berupa data dan informasi
terkait penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih yang sama juga diberikan
kepada : Daud Bunga Patiung, S.Pd., Kepala SMP Negeri 2 Balusu Toraja
Utara, rekan-rekan guru, dan tata usaha atas dukungan, fasilitas, serta
motivasi yang telah diberikan selama mengikuti program S-2 di Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Ucapan terima kasih yang sama kepada kedua orang tua,
saudara-saudara, dan keponakan yang telah memberikan dukungan, baik dalam
bentuk moril maupun materil. Selanjutnya, kepada suamiku Yulianus
Tandi, anak-anakku tersayang Mikolanda Karamang Tandi, Marvel
Yunarei Tandi, dan Maikel Pasoloran Tandi atas pengertian, motivasi,
kesabaran, dan doa selama penulis melanjutkan pendidikan.
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
membantu penyelesaian tesis ini. Semoga segala budi baik yang
diberikan kepada penulis mendapat limpahan rahmat dan berkah yang
kepada kita semua dan semoga tesis ini memiliki manfaat bagi
pengembangan pendidikan di tanah air. Amin.
Makassar, Juni 2015
Bone, 2 Juni 1972. Anak kedua dari lima
bersaudara, buah pasangan Matius R.P dan
Martina Pirade. Penulis adalah istri dari Yulianus
Tandi dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu
Mikolanda Karamang Tandi, Marvel Yunarei Tandi, dan Maikel Pasoloran
Tandi. Penulis mulai memasuki pendidikan dasar di kampung
halamannya, yaitu SDN 45 Palawa dan tamat pada tahun 1985. Kemudian
penulis masuk SMP Pelangi dan tamat pada tahun 1988. Pada Tahun
yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri
Rantepangli dan tamat 1991. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan
Diploma III pada tahun 1991 di IKIP Ujung Pandang Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, selesai tahun 1994. Perjuangan keras
penulis dalam menuntut ilmu dilanjutkannya dengan mendaftar pada
Universitas Negeri Makassar tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di akhir
perjuangannya, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas
yang berada di Kota Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah
Makassar pada Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, saat ini sedang penyelesaian studi dan akan menamatkan
pendidikan pada tahun 2015. Penulis diangkat Pegawai Negeri Sipil dan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia kaya dengan keanekaragaman suku, budaya, agama
maupun ras. Hal inilah yang membuat Indonesia terkenal dengan
kemajemukannya. Namun, kemajemukan ini tidak menjadikan Indonesia
menjadi bangsa yang terpecah belah. Keberagaman yang ada justru
menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia yang diharapkan tetap
menjunjung tinggi semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Budaya menjadi lambang suatu daerah, ciri
tradisi yang dapat membangun sebuah peradaban yang kokoh. Budaya
merupakan bagian yang universal yang mempunyai peranan penting
dalam masyarakat. Melalui budaya dapat dilihat tinggi rendahnya suatu
bangsa. Peranan budaya tidak dapat terlepas dari bahasa sebagai
medianya dalam komunikasi sehari-hari oleh dalam masyarakat budaya
sebagai wujud dari pemahaman dan pemberian respons terhadap hal
yang dikerjakan orang lain. Dengan kebudayaan, kita dapat mengenal
kehidupan manusia, cara-cara kelompok manusia menyusun
pengetahuan, menampilkan perasaan, dan cara mereka bertindak.
Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh Taylor (2012) bahwa kebudayaan adalah
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan
kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia
sebagai anggota masyarakat (Setiadi, 2007:27). Tanpa masyarakat akan
sukar bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa
kebudayaan tidak mungkin manusia, baik secara individual maupun
masyarakat dapat mempertahankan kehidupannya sehingga kebudayaan
merupakan kebudayaan manusia. Masyarakat adalah wadah, dan budaya
adalah isi. Terdapat hubungan mutlak antara manusia dengan
kebudayaan, yakni manusia menciptakan budaya kemudian budaya
memberikan arah dalam hidup dan tingkah laku manusia sehingga
manusia pada hakikatnya disebut makhluk budaya.
Kebudayaan juga mencakup aturan, prinsip, dan ketentuan
kepercayaan yang tersususun rapi yang secara turun-temurun diwariskan
kepada generasi ke generasi yang harus tetap dipertahankan dan
dilestarikan. Setiap suku yang ada di Indonesia, masih banyak yang tetap
mempertahankan keaslian kebudayaannya, ini merupakan daya tarik
utama bagi negara lain sehingga menjadikan Indonesia sebagai sebuah
negara pariwisata.
Manusia dengan kemampuan akal budinya telah mengembangkan
berbagai macam sistem tindakan demi keperluan hidupnya sehingga ia
menjadi makhluk yang paling berkuasa di muka bumi ini. Namun, berbagai
macam sistem tindakan harus dibiasakan olehnya dengan belajar sejak ia
Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil
karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik
diri manusia dengan belajar. Salah satu kebudayaan yang patut untuk
dikaji lebih dalam adalah kebudayaan di Tana Toraja.
Suku Toraja adalah salah satu dari ratusan suku di Indonesia yang
kaya akan budaya yang penuh dengan keunikan tingkah manusia yang
merupakan warisan dari leluhur. Keunikan dan keaslian inilah yang
membuat Toraja terkenal sampai ke luar negeri dan menjadi salah satu
budaya warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO (United Nation
Education Scientific and Cultural Organization) tentang penetapan
Warisan Dunia. UNESCO dalam konferensi World Heritage Cultural
mengambil keputusan bahwa dalam upaya pelestarian peninggalan
kepurbakalan budaya dan alam Tana Toraja yang unik dan langka, maka
daerah ini dimasukkan dalam daftar kawasan wisata budaya dunia
(Sitonda, 2007:28). Orang Toraja dalam kehidupannya sangat terikat oleh
sistem adat yang berlaku, sehingga hal ini berimbas pada keberadaan
upacara-upacara adat. Upacara keagamaan itu terdiri atas tiga dasar
upacara adat yang disebut Aluk Titanan Tallu, yakni :
1. Aluk Rampe Matallo atau Upacara Rambu Tuka’, merupakan upacara
yang berhubungan dengan syukuran dan kesukaan.
2. Aluk Rampe Matampu atau Upacara Rambu Solo’ atau upacara yang
3. Aluk Mangola Tangnga’, merupakan upacara yang berhubungan
dengan harapan. Dalam perkembangannya upacara ini sudah jarang
dilaksanakan seiring dengan perkembangan agama yang masuk ke Tana
Toraja.
Ketiga upacara di atas mengikat hidup dan kehidupan orang Toraja
yang dalam perkembangannya masih susah ditinggalkan karena
upacara-upacara ini adalah tempat pembinaan kekayaan dan kesenian Toraja
yang ada hingga sekarang. Kepercayaan adat suku Toraja dikenal dengan
nama Aluk Todolo yang artinya agama para leluhur. Jadi, ketiga dasar
upacara adat dalam kehidupan orang Toraja tersebut di atas adalah
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dari ajaran Aluk Todolo
(Tangdilintin, 1981:9).
Salah satu upacara adat yang masih sering dilakukan di Toraja
adalah upacara Rambu Solo’ yang merupakan acara yang berhubungan
dengan kematian. Prosesi upacara Rambu Solo’ terdapat banyak tahapan
ritual unik dan sangat menarik, baik yang dilakukan secara simbolik
maupun dengan unsur-unsur visual dan audiovisual seperti arsitektur,
kesenian, dan bahasa. Semuanya itu bagi masyarakat Toraja merupakan
tahapan ritual-ritual yang memiliki makna sangat mendalam. Rambu Solo’
merupakan upacara pemakaman orang yang sudah meninggal.
Bagaimanapun miskinnya harus dipestakan, sekalipun yang dikurbankan
Rambu Solo’ dilakukan atas dasar kepercayaan, strata sosial, ekonomi,
dan tata aturan yang telah ditentukan.
Pada kepentingan dan situasi tertentu seperti upacara ritual
kematian Rambu Solo’, bahasa Toraja yang sering digunakan oleh tokoh
adat dan agama berbeda dengan situasi pergaulan sehari-hari karena
sangat berkaitan dengan nilai, etika, dan moral dalam kehidupan
masyarakat yang lazim disebut ungkapan. Ungkapan hanya digunakan
oleh anggota masyarakat yang dituakan dalam upacara-upacara
tradisional, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
lainnya.
Upacara Rambu Solo’ sebagai suatu bentuk penghormatan terakhir
yang mengandung pesan-pesan dan menggambarkan suasana atau
konteks kesedihan, serta dipenuhi berbagai kajian bahasa yang sangat
identik dengan beragam makna di dalamnya. Bentuk upacara ini berbeda
antara satu dan yang lainnya, yakni pada lamanya upacara dan status
sosial pada masa hidupnya, hal tersebut juga tampak pada keragaman
bahasa yang digunakan dalam prosesi upacara. Mengenai susunan kasta
yang ada di Toraja, ada empat yaitu :
1. Tana’ Bulaan yaitu kasta bangsawan tinggi
2. Tana’ Bassi yaitu kasta bangsawan menengah
3. Tana’ Karurung yaitu rakyat merdeka atau kebanyakan
Suku Toraja memiliki bahasa sendiri yang digunakan sebagai alat
komunikasi di rumah atau di lingkungan sekitar. Bahasa Toraja terdiri atas
dua jenis yaitu bahasa Toraja biasa yang digunakan dalam pergaulan
sehari-hari dan bahasa Tominaa yang sering digunakan dalam upacara
adat Toraja. Bahasa Tominaa berbeda dengan bahasa Toraja yang biasa
digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai bahasa alat
komunikasi.
Kondisi wilayah yang telah mengalami pemekaran dalam beberapa
kecamatan, namuan aspek otentisitas tidak mengalami perubahan. Selain
bentuk arsitektur bangunan yang masih dijaga keasliannya, tradisi ritual
keagamaan yang penuh dengan makna juga masih terjaga. Ungkapan
dalam Rambu Solo’ disampaikan melalui lantunan yang berbeda antara
daerah satu dengan daerah lain, akan tetapi menurut masyarakat sekitar
makna yang disampaikan dalam ungkapan tersebut sama. Hal tersebut
terlihat jelas pada upacara Rambu Solo’ yang diadakan bulan Agustus
2014 dan upacara Rambu Solo’ pada bulan Februari 2015 di daerah yang
berbeda pula. Perbedaan yang tampak selain pada dekorasi upacara adat
juga pada ungkapan-ungkapan yang digunakan. Fenomena inilah yang
menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang adanya bentuk
perbedaan ungkapan tersebut, karena berdasarkan informasi singkat dari
masyarakat sekitar perbedaan itu disebabkan oleh tingkat strata sosialnya.
Perbedaan ungkapan bahasa dalam budaya Toraja khususnya
lingkungan masyarakat tersebut. Hal lain yang menjadi alasan peneliti
untuk mengkaji ungkapan dalam Rambu Solo’ yaitu bagaimana makna
bahasa dalam ungkapan tersebut, tentunya dengan melihat ungkapan
yang dalam bahasa Toraja ke dalam bahasa Indonesia agar makna dari
tiap ungkapan lebih mudah dipahami.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah, sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah ungkapan bahasa yang terdapat dalam ritual budaya
RambuSolo’ masyarakat Balusu Toraja Utara ?
2. Bagaimanakah kajian semiotik mengungkap makna yang terdapat
dalam ungkapan bahasa ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat
Balusu Toraja Utara ?
3. Bagaimanakah perbedaan ungkapan bahasa berdasarkan strata
sosial dalam ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja
Utara ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan peneitian ini untuk mendeskripsikan :
1. Ungkapan bahasa yang terdapat dalam ritual budaya Rambu Solo’
masyarakat Balusu Toraja Utara
2. Makna kajian semiotik mengungkap makna yang terdapat dalam
ungkapan bahasa ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu
3. Perbedaan ungkapan bahasa berdasarkan strata sosial masyarakat
dalam ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja Utara
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat
teoretis dan praktis
1. Manfaat Teoretis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan
informasi ilmiah dalam perkembangan studi kebudayaan tradisi lisan.
b. Hasil penelitian dapat menambah khazanah pengetahuan tentang
makna-makna yang terkandung pada ritual budaya tersebut.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan bahasa Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan mengenai makna-makna
yang terkandung pada upacara Rambu Solo’.
b. Bagi masyarakat, memberikan sumbangan teoretis untuk peningkatan
kesadaran akan pentingnya menjaga sebuah tradisi yang telah
diwariskan nenek moyang dan memahami apa makna yang akan
disampaikan dalam upacara tersebut
c. Bagi peneliti lanjut, merupakan bahan referensi atau acuan untuk
melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul
E. Batasan Istilah
Agar tidak menyimpang jauh dari topik permasalahan dan untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti
serta menghindari salah pengertian atau salah tafsir terhadap
penelitian ini, maka batasan istilah atau definisi penelitian yang
dibahas, yaitu:
1. Ungkapan bahasa dalam ritual budaya Rambu Solo’ adalah
rangkaian kata yang mengandung makna filosofis dan diucapkan
atau dilantunkan dalam ritual Rambu Solo’.
2. Makna ungkapan adalah arti yang terkandung dalam ungkapan dan
dapat berupa makna leksikal.
3. Budaya Rambu Solo’ adalah merupakan upacara adat untuk
menghormati sekaligus mengantar orang tercinta yang telah
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Hasil Penelitian
Penelitian tentang kajian bahasa yang terdapat dalam ritual budaya
Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja Utara bertujuan untuk mengetahui
kajian ungkapan bahasa terhadap ritual budaya tersebut, baik gerakan
atau tuturan yang mengandung pesan dari tiap prosesi adat yang ada
dalam ritual Rambu Solo’ berdasarkan tingkat strata sosial
masyarakatnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya.
Berikut adalah jurnal penelitian yang sama maupun yang berbeda dengan
kajian penelitian ini.
Jurnal penelitian yang sama, yaitu peneltian yang dilakukan oleh
beberapa peneliti, di antaranya : Ungkapan Tradisional dan Makna
Bahasa Biak Numfor dan Tehit Daerah Irian Jaya (Depdikbud, 1990), Analisis Ungkapan dalam Upacara Adat Perkawinan Bugis Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Hasniah, 1998), Makna Ungkapan Mantra pada Upacara Mappalili di Kecamatan Sigeri Mandalle Kabupaten Pangkep (Rosdiana, 2000), dan peneltian lain yang sama objek kajiannya,
yaitu peneltian yang dilakukan oleh Langan (2013), yang mengkaji tentang
Makna PesanTari Ma’randing dalam Upacara Adat Rambu Solo’ di Tana Toraja. Penelitian ini memfokuskan pada pesan-pesan atau makna dalam
pesan Tari Ma’randing dalam Upacara Adat Rambu Solo’ adalah tarian
yang bersifat tarian perang atau tarian prajurit yang berfungsi untuk
memuji keberanian orang yang telah meninggal ketika masih hidup.
Jurnal penelitian yang berbeda, yaitu pada penelitian Problem
Psikologis dan Strategi Coping Pelaku Upacara Kematian Rambu Solo’ di
Toraja (studi fenomenologi pada tana’ bulaan) yang dilakukan oleh
Alumnus Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Hasil temuan penelitian ini adalah: a) faktor-faktor yang mendorong
pelaksanaan upacara Rambu Solo’, merupakan upaya individu untuk
memenuhi kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya, yaitu kebutuhan
untuk survive, love and belonging, power, dan freedom. b) Keputusan
terlibat membuat para pelaku menghadapi dampak langsung dan dampak
tidak langsung dari beban keuangan Rambu Solo’. c) Dalam menghadapi
beban keuangan Rambu Solo’ sebagai stresor, Strategi coping yang
dilakukan para pelaku, utamanya pelaku upacara Rambu Solo’ besar,
cenderung mengalami penurunan secara bertahap dari coping berfokus
pada masalah kemudian beralih pada coping berfokus pada emosi dan
dari coping adaptif beralih pada coping maladaptif. (d) dampak psikologis
yang ditemukan: stres, ketakutan (kecemasan), depresi ringan. (e)
dinamika psikologis pelaku upacara Rambu Solo’ sangat kompleks,
sebagai pilihan dari proses internal, beban keuangan Rambu Solo’ dinilai
subjek sebagai konsekuensi dan untuk itu mereka berupaya mencari
derivasi kebutuhan dasar dalam dirinya. Letak perbedaan penelitian ini,
yaitu sasaran objek penelitiannya karena peneltian ini lebih pada
pelaku-pelaku ritualnya, bukan pada makna dalam ritual Rambu Solo’.
B. Tinjauan Teori dan Konsep
Pengolahan data dalam penelitian ini tentunya memerlukan beberapa
teori yang mendukung dan dianggap relevan, dari bentuk dukungan yang
diharapkan dapat membantu temuan di lapangan sehingga dapat
memperkuat teori dan keakuratan data.
1. Ungkapan
a. Pengertian Ungkapan
Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah
menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya.
Idiom atau disebut juga dengan ungkapan adalah gabungan kata yang
membentuk arti baru karena tidak berhubungan dengan kata pembentuk
dasarnya.
Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan
seseorang dalam situasi tertentu untuk mengiaskan suatu hal. Ungkapan
terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata ini jika tidak
ada konteks yang menyertainya memiliki dua kemungkinan makna, yaitu
makna sebenarnya (denotasi) dan makna tidak sebenarnya (makna kias
atau konotasi). Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gabungan kata
menyertainya, untuk lebih jelasnya kita ambil sebuah contoh “Membanting
tulang”.
Chaer (1994) berpendapat bahwa idiom adalah satuan ujaran yang
maknanya tidak dapat “diramalkan’ dari makna unsur-unsurnya, baik
secara leksikal maupun secara gramatikal. Umpamanya, secara
gramatikal bentuk menjual rumah bermakna ‘yang menjual menerima
uang dan yang membeli menerima rumahnya’; tetapi, dalam bahasa
Indonesia bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna seperti itu, tetapi
bermakna ‘tertawa keras-keras’. Jadi, makna seperti yang dimiliki bentuk
menjual gigi ialah yang disebut makna idiomatikal. Contoh lain dari idiom
adalah bentuk membanting tulang yang bermakna ‘bekerja keras’, meja
hijau dengan makna ‘pengadilan, dan sudah beratap seng dengan makna
‘sudah tua’.
Menurut Saryono, (1997:68) makna idiomatis adalah makna
konstruksi yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan
atau dijabarkan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Contohnya: tanah
air ‘negeri tempat lahir’, besar kepala ‘sombong’, dan mengambing hitamkan ‘menuduh bersalah’. Oka dan Suparno (1994) menyatakan
bahwa makna kias adalah makna yang sudah menyimpang dalam bentuk
ada pengiasan hal atau benda yang dimaksudkan penutur dengan hal
atau benda yang sebenarnya.
Jadi, secara umum ungkapan berarti gabungan kata yang memberi
sebenarnya. Ungkapan dapat juga diartikan makna leksikal yang dibangun
dari beberapa kata, yang tidak dapat dijelaskan lagi lewat makna
kata-kata pembentuknya.
Ada dua macam bentuk idiom atau ungkapan, yaitu yang disebut
idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua
unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang
dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Bentuk-bentuk seperti
membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau termasuk contoh idiom
penuh. Sedangkan yang dimaksud dengan idiom sebagian adalah idiom
yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri.
Misalnya, buku putih yang bermakna ‘buku yang memuat keterangan
resmi mengenai suatu kasus’; daftar hitam yang bermakna ‘daftar yang
memuat nama-nama orang yang diduga atau dicurigai berbuat kejahatan’;
dan koran kuning dengan makna ‘koran yang biasa memuat berita
sensasi’. Pada contoh tersebut, kata buku, daftar, dan koran masih
memiliki makna leksikalnya. Ungkapan juga bersifat seperti bahasa pada
umumnya. Ungkapan selalu berkembang mengikuti bahasa itu sendiri,
seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga menurut zaman
ungkapan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ungkapan lama dan ungkapan
baru. Contoh-contoh ungkapan lama masih dapat kita jumpai pada zaman
sekarang ini, seperti: matanya bagai bintang timur : bersinar atau tajam,
rambutnya bagai mayang mengurai : ikal atau keriting, berminyak air :
Undang-Undang Pers, berebut senja : siang berganti malam, ranum dunia :
penyebab kesulitan.
Komunikasi secara lisan ataupun tidak lisan, masyarakat sering
menyelipkan sebuah ungkapan atau idiom dalam suatu komunikasi. Ini
bertujuan untuk memperjelas suatu makna atau maksud tertentu.
Dalam ranah sastra, baik puisi ataupun prosa. Sering dibubuhi oleh
ungkapan-ungkapan. Seumpama sayur yang dibubuhi banyak ramuan
atau bumbu untuk menjadikannya nikmat. Dalam sastra ramuan itu sejenis
dengan ungkapan. Sehingga karya itu menjadi hidup, sehingga pembaca
dapat merasakan apa yang diungkapkan oleh penulis atau penyair dalam
memandang bahasa.
Bahasa, bagi seorang penyair adalah miliknya yang paling
berharga. Dengan bahasa, ia mengutuk atau mencaci maki dunia, tetapi
juga dengan bahasa ia menyanyikan perasaannya atau mengembara
dalam angan-angannya. Bahasa tidak pernah kering dalam jiwanya,
setiap sentuhan, setiap situasi, setiap merasa dan mengagumi, dicobanya
hendak ditemukan dalam bahasa.Itulah pentingnya bahasa bagi seorang
penyair. Bahasa adalah nyawanya sendiri, jadi tidak seorang pun yang
dapat memisahkan bahasa dengan penyair, karena sama halnya dengan
mengambil nyawanya. Dalam penggunaan bahasa yang digodok oleh
seorang penyair tersebut, dia sangat membutuhkan makna-makna yang
Pemerkosaan bahasa, yaitu pemilihan kata-kata (diksi) serta
penggunaan cara-cara pengungkapan, dengan menggunakan
makna-makna dalam semantik khususnya ungkapan. Sebagaimana yang
dikatakan Ricoeur (2013:24), sehingga menciptakan “kegelapan semantik”
atau ‘ketidakpastian makna yang terkandung dalam ungkapan’. Hal ini
akan mengajak masyarakat khususnya kaum adam untuk memuji berita
yang sangat rendahan itu. Hal tersebut di atas membuat ungkapan itu
hanya sebuah bahasa biasa, yang kadang merusak bahasa dan
masyarakat atau bahasa sastranya mati, lesu, dan rusak. Ini menghambat
perkembangan sebuah bahasa, khususnya bahasa Indonesia, karena
tanpa makna-makna yang digarap oleh semantik, suatu bahasa akan sulit
untuk bergerak. Ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat Indonesia,
mengenai pemakaian bahasa Indonesia, bukti nyatanya, pada zaman
sekarang ini bahasa Indonesia telah didahului oleh bahasa Inggris di
negerinya sendiri, ini sangat bersifat fatal kepada garapan Sosiolinguistik
pula, mengenai penutur bahasa Indonesia dalam masyarakat.
Suatu hal yang harus dibedah lagi, khususnya kepada mereka yang
mempunyai otoritas dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia, seperti
penulis, media masa, elektronik dan sebagainya, seharusnya memberikan
suatu catatan kecil mengenai makna yang terkandung di dalam suatu
Berikut adalah contoh ungkapan :
(a) banting tulang : kerja keras
(b) gulung tikar : bangkrut (c) angkat kaki : pergi
(d) naik pitam : marah
(e) tinggi hati : sombong
Contoh kalimat dengan:
1. Mereka sudah banyak makan garam dalam hal itu. (banyak
pengalaman)
2. Hati-hati terhadapnya, ia terkenal si panjang tangan. (suka mencuri)
3. Jeng Sri memang tinggi hati. (sombong)
4. Karena ucapan orang itu, Waluyo naik darah. (marah)
5. Itulah akibatnya kalau menjadi anak yang berkepala batu. (tidak mau
menurut)
6. Hati-hati terhadap orang yang besar mulut itu. (suka membual)
7. Merah telinganya ketika ia dituduh sebagai koruptor. (marah)
8. Karena gelap mata, dia mengamuk di kantor. (hilang kesabaran)
b. Jenis-jenis Ungkapan
1) Berdasarkan makna unsur pembentuknya, ungkapan dapat
dikelompokkan menjadi dua macam.
a) Ungkapan penuh (idiom penuh) berupa kata ataupun frasa yang
Contoh: Kita tidak boleh menjual gigi ketika mengunjungi korban lumpur
panas.
menjual gigi = tertawa keras-keras
b) Ungkapan sebagian (idiom sebagian) berupa kata atau frasa yang
maknanya masih tergambar dalam makna unsur pembentuknya.
Contoh: Kampung Kedungbendo seperti desa mati karena gelap gulita
dan sunyi.
gelap gulita = gelap sekali
2) Berdasarkan kata yang membentuknya, ungkapan dapat dibagi
menjadi tujuh macam.
1. Ungkapan dengan bagian tubuh
Contoh: Masyarakat Porong bahu-membahu membersihkan lumpur di
jalan dan desa.
bahu-membahu = bergotong-royong
2. Ungkapan dengan indra
Contoh: Meskipun jauh di mata, tetapi aku dapat merasakan penderitaan
penduduk Kedungbendo.
jauh di mata = terpisah jauh
3. Ungkapan dengan warna
Contoh: Bantuan bagi korban lumpur panas dibuatkan perjanjian hitam di
atas putih agar dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terjadi
penyelewengan.
4. Ungkapan dengan nama benda-benda alam
Contoh: Banyak korban lumpur panas yang tidak masuk buku untuk
mendapatkan dana dan bantuan.
tidak masuk buku = tidak masuk dalam hitungan
5. Ungkapan dengan bagian-bagian tumbuhan
Contoh: Wilayah desa Kedungbendo dibatasi dengan batang air.
batang air = sungai
6. Ungkapan dengan nama binatang
Contoh: Coba hindari adu domba jika menyelesaikan kasus ini!
adu domba = menjadikan pertengkaran
7. Ungkapan dengan kata-kata yang menunjuk bilangan.
Contoh: Dampak luapan lumpur membuat masyarakat mendua hati.
mendua hati = bimbang, ragu
2. Pengertian Bahasa
Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu
makna atau pengertian, sehingga seringkali membingungkan. Bahasa
sebagai objek linguistik merupakan langue dan parole. Langue merupakan
objek yang abstrak karena langue itu berwujud suatu sistem. Bahasa
tertentu secara keseluruhan, sedangkan langue merupakan objek yang
paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal.Yang
dikaji linguistik secara langsung adalah parole, karena parole itulah yang
berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian
langue dan dari kajian terhadap langue ini akan diperoleh kaidah-kaidah language kaidah bahasa secara universal.
Sehubungan dengan hal tersebut, Chaer (1994: 3) mengemukakan
pendapatnya bahwa bahasa sebagai objek linguistik, parole adalah objek
konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para
bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Pendapat tersebut
menunjukkan bahwa bahasa dapat diartikan sebagai parole. Parole
berwujud nyata yang diucapkan oleh pemakai bahasa sehingga diamati
dan diobservasi, ini merupakan objek yang abstrak yang berwujud sistem
suatu bahasa tertentu secara keseluruhan.
Pendidikan formal di sekolah menengah, kalau ditanyakan apakah
bahasa itu? biasanya jawabannya yang muncul adalah bahasa sebagai
alat komunikasi. Kondisi seperti ini seringkali dijumpai dalam lingkungan,
pendidikan formal. Jawaban tersebut hanya menyatakan fungsi dari
bahasa yaitu bahasa sebagai alat. Jadi, fungsi bahasa itu yang dijelaskan,
bukan sosok bahasa itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut,
Kridalaksana (dalam Chaer, 1994 : 32) mengemukakan bahwa bahasa
adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para
anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan
mengindetifikan diri.
Selanjutnya, masalah lain yang berkenan dengan pengertian
bahasa adalah bilamana sebuah tuturan disebut bahasa yang berbeda
suatu bahasa. Secara linguistik dua buah tuturan dianggap sebagai dua
buah bahasa yang berbeda, kalau anggota-anggota dari dua masyarakat
tuturan itu tidak saling mengerti. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
tentang bahasa perlu diperhatikan oleh pemakainya.
Keraf (1991 : 15) menjelaskan bahasa sebagai berikut :
“…..Bahasa itu meliputi dua bidang yaitu : bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tadi; bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengar kita, serta arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu untuk selanjutnya arus bunyi kita namakan arus ujaran”.
Dari kutipan tersebut, Keraf menjelaskan bahasa sebagai bunyi
yang dihasilkan alat-alat artikulasi manusia. Bunyi tersebut merupakan
getaran yang merangsang alat pendengar dan arti yang terkandung dalam
bunyi tersebut.
Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa setiap bunyi yang dihasilkan
oleh alat-alat ucap belum bisa dikatakan bahasa bila belum terkandung
makna di dalamnya. Apakah setiap arus ujaran mengandung makna atau
tidak haruslah dititik dari konvensi masyarakat tertentu. Selain itu, Keraf
(1991 : 16) memberikan batasan bahasa yaitu “ alat komunikasi antara
anggota masyarakat, berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh
alat ucap manusia”.
Menurut Chaer (1998 : 1) bahasa adalah “ suatu sistem lambang
bunyi yang arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja
menjelaskan bahwa sebagai sebuah sistem bahasa itu terbentuk oleh
suatu aturan, kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi,
kata bentuk kata, maupun kalimat. Bila aturan, kaidah, pola ini dilanggar,
maka komunikasi dapat terganggu.
Bahasa adalah lambang-lambang yang berupa bunyi bersifat
arbitrer, artinya dalam bahasa tidak ada ketentuan data hubungan antara
suatu lambang bunyi dengan benda atau konsep yang dilambangkannya.
Misalnya kata kuda, yaitu sejenis binatang berkaki empat yang biasa
dipakai untuk menarik beban, meskipun lambang-lambang bahasa itu
bersifat arbitrer, bila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan lambang
itu, pasti akan terganggu jika aturan terhadap lambang bahasa tidak
dipatuhi (Chaer, 1998 :2). Selanjutnya Chaer dan Agustina ( 2004 : 36)
menjelaskan, bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan
menjadi unit satuan-satuan, yaitu fonem, morfem, kata, dan kalimat.
Hubungan antara lambang-lambang bahasa dengan maknanya bukan
ditentukan oleh adanya persetujuan antara lambang bahasa itu bersifat
terbuka. Artinya, lambang-lambang bahasa dibuat sesuai dengan
keperluan manusia untuk menguasai aturan-aturan tersebut, diperlukan
suatu ketekunan dalam mempelajari kaidah-kaidah tersebut.
Pei (dalam Pringgawidagda, 2003: 5) mengemukakan bahwa
bahasa adalah suatu sistem komunikasi bunyi, yang diucapkan melalui
organ-organ ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat,
konvensional secara arbitrer. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan
bahwa bahasa merupakan sebuah sistem simbol vokal yang arbitrer dan
digunakan untuk komunikasi manusia.
Santoso (1990: 1) menjelaskan bahwa bahasa adalah alat
komunikasi berupa rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap
manusia secara sadar yang diatur oleh suatu sistem, selain itu juga
dijelaskan bahwa sebagai komunikasi, bahasa mampu untuk menampung
perasaan dan pikiran pemakainya, serta mampu menimbulkan adanya
saling pengertian antara penutur dan lawan tutur atau antara pembaca
dan penulis. Semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dalam
penampilannya sebagai bahasa diatur oleh suatu sistem tertentu yang
berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Seseorang dapat
berkomunikasi dengan baik dalam suatu bahasa, apabila orang tersebut
dapat menguasai sistem bahasa itu. Bahasa sebagai alat komunikasi
umum sangat ditentukan oleh kesempurnaan sistem atau aturan bahasa
dari masyarakat pemakainya.
Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bahasa
adalah alat komunikasi kehidupan manusia berupa lambang bunyi suara
yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu terbentuk oleh aturan,
kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk
kata, maupun kalimat secara konvensional. Sehubungan dengan hal
tersebut, bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa tentu tidak akan keluar
bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia, juga
ditentukan oleh kesempurnaan sistem bahasa dari masyarakat
pemakainya.
a. Ilmu Bahasa (Linguistik)
Ilmu bahasa yang dipelajari saat ini bermula dari penelitian tentang
bahasa sejak zaman Yunani (abad 6 SM). Secara garis besar studi
tentang bahasa dapat dibedakan antara (1) tata bahasa tradisional dan (2)
linguistik modern. Selanjutnya linguistik dapat dibagi menjadi beberapa
cabang yaitu, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.
b. Hakikat Bahasa
Hakikat bahasa merupakan ciri-ciri bahasa itu sendiri.Chaer (2004:63)
menjelaskan bahwa bahasa pada dasarnya memiliki ciri-ciri. Sifat dan ciri
yang dimaksud antara lain:
a. Bahasa itu adalah suatu sistem
b. Bahasa itu berwujud lambang
c. Bahasa itu berupa bunyi
d. Bahasa itu berupa arbitrer
e. Bahasa itu bermakna
f. Bahasa itu berisfat konvensional
g. Bahasa itu bersifat unik
h. Bahasa itu bersifat universal
i. Bahasa itu bersifat dinamis
k. Bahasa itu berfungsi sebagai alat
Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
bahwa fungsi bahasa dalam kehidupan manusia sangat penting, oleh
karena itu, hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat turut
dipengaruhi oleh bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa sebagai
media komunikasi juga mengikat hubungan antara yang satu dengan
individu yang lainnya dalam komunikasi. Hal ini disebabkan oleh bahasa
yang secara fungsional merupakan salah satu alat yang digunakan untuk
menyampaikan pikiran dan perasaan manusia. Kondisi tersebut dapat
berjalan dengan lancar apabila bahasa yang dipergunakannya dapat
saling dimengerti, baik oleh penutur atau penulis maupun lawan tutur atau
pembaca.
Dari seluruh uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
bahasa lambang bunyi yang mempunyai arti dengan fungsi sebagai alat
komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi
merupakan lambang yang mempunyai arti maupun bunyi yang berfungsi
sebagai alat yang digunakan manusia sebagai pemakai bahasa, dalam
mengadakan hubungan antara sesamanya. Hal tersebut menunjukkan
bahwa bahasa berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan manusia,
interaksi dan segala macam aktivitas yang bersifat sosial akan menjadi
a. Bahasa merupakan milik manusia
Manusia sebagai penutur dan pengguna bahasa dalam kehidupan
bermasyarakat, maka dianggap wajar jika dikatakan bahwa bahasa
merupakan milik manusia yang digunakan sebagai alat komunikasi.
Hanya manusia yang dianggap dapat menggunakan bahasa.
Dikatakan demikian karena bahasa merupakan simbol vokal. Bahasa
lisan merupakan bahasa primer manusia. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa hanya manusia yang memiliki potensi berbicara.
b. Bahasa adalah berpikir dan bertindak
Bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dianggap sebagai
bentuk atau manifestasi berpikir dan bertindak. Oleh karena itu,
proses berpikir bahasa tampak dalam kompetensi kebahasaan.
Kompetensi ini bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat. Gejala bahasa
atau penampilan berbahasa yang dapat dilihat disebut tindak tutur.
Ada pula yang menyebut dengan istilah performansi bahasa.
c. Bunyi merupakan bagian bahasa
Bunyi bahasa dipelajari dalam linguistik, terutama di dalam fonologi
(ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa). Media bahasa yang
paling mudah untuk dimengerti oleh manusia normal adalah yang
menggunakan bunyi atau simbol-simbol, bukan dengan isyarat atau
gerakan anggotan badan. Oleh karena itu, wajar apabila definisi
bahasa adalah simbol vokal. Simbol vokal ini berkaitan dengan
bahasa lisan.Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan
bahasa tulis bersifat sekunder. Media lain seperti bahasa isyarat
hanya sebagai pertolongan yang bersifat kasuistis.
d. Bahasa memiliki tingkatan
Bahasa disusun atas simbol-simbol vokal. Simbol-simbol vokal itu
dirangkaikan secara hierarkis:
1) Fonem 2) Silabe 3) Morfem 4) Kata 5) Frase 6) Klausa 7) Kalimat 8) Wacana
Fonem merupakan lambang bunyi yang membedakan arti. Gabungan
fonem menjadi silabe.Rangkaian silabe menjadi kata, rangkaian kata
menjadi frasa atau klausa, unit bahasa yang lebih besar dari pada
klausa adalah kalimat. Gabungan antarkalimat yang membentuk
makna secara utuh disebut wacana.
e. Bahasa selalu melekat pada gestur
Bahasa adalah aktivitas manusia yang dapat didengar dan dapat
dilihat. Gestur biasa juga disebut paralanguage atau kinestik. Body
(berbahasa) dengan gerak mimik, kerdip mata, kerut dahi, gerak
kepala, gerak tangan, dan lain-lain. Keberhasilan berbicara dengan
tatap muka dipengaruhi oleh pendengaran dan gerak-gerik yang
tampak dari pembicara.
f. Bahasa adalah unsur arbitrer dan nonarbitrer
Penentuan bentuk kebahasaan bersifat arbitrer, artinya
sewenang-wenang. Menentukan nama satuan (satuan linguistik) dan makna
suatu benda tidak ada aturan secara konvensional. Semua bersifat
sewenang-wenang (arbitrer) atau sekehendak pencipta bahasa itu.
Tidak ada aturan dan alasan yang mapan, umum, dan masuk akal.
Seseorang mencipta bahasa atau kata. Tidak ada hubungan logis
antara nama dan makna, mengapa itu bernama sawah, hutan, pohon,
makan, minum, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu benda yang
sama dapat diacu oleh beberapa bentuk kebahasaan, misalnya untuk
mengacu pada benda yang bernama ayam digunakan untuk
kebahasaan (kata). Penentuan bentuk kebahasaan itu bergantung
pada kemauan masyarakat pemakainya.
g. Bahasa adalah vertikal dan horizontal
Bahasa dapat dilihat secara vertikal dan horizontal.Vertikal mengacu
pada sifat bahasa yang paradigmatik, sedangkan horizontal mengacu
pada sintagmatik. Pada deret paradigmatik (vertikal) diisi dengan
(horizontal) yang terdiri atas struktur, yaitu struktur
subjek-predikat-objek (S,P,O).
h. Bahasa adalah didengar dan diucapkan
Secara primer, bahasa itu diucapkan oleh pembicara dan disebut
primer karena bahasa yang pertama kali digunakan manusia adalah
bahasa lisan. Bahasa lisan bersifat momental artinya bergantung pada
momen, situasi, atau konteks. Bahasa lisan itu begitu didengar begitu
hilang, sulit untuk diulang secara persis atau sama seperti semula.
karena sifatnya momental, bahasa lisan perlu diawetkan agar orang
lain dapat pula menikmati. Kemudian, manusia berkreasi untuk
melukiskan bahasa dalam bentuk lambang bahasa. Sejak itu lahirlah
budaya tulis yang bersifat sekunder karena merupakan turunan
bahasa lisan.
i. Bahasa adalah kesamaan struktur
Struktur kebahasaan yang bersifat konvensional. Artinya dalam
kearbitrerannya struktur itu masih harus menaati aturan-aturan atau
kaidah-kaidah kebahasaan yang dipakai masyarakat. Seluruh
masyarakat pemakai bahasa yang sama tentu akan memiliki
kaidah-kaidah kebahasaan yang sama pula, tidak boleh semaunya sendiri.
Kemampuan bahasa menurut Chomsky merupakan sesuatu yang di
bawah sejak lahir yang diturunkan oleh orang tuanya. Sejak lahir alat
manusia untuk menguasai bahasa yang disebut language acquisition
j. Bahasa adalah berubah
Bahasa bersifat dinamis. Oleh karena itu, bahasa senantiasa berubah
mengikuti masyarakat pemakainya. Bahasa yang sama pada suatu
periode tertentu akan berbeda dengan periode sebelumnya dan
sesudahnya. Wajar apabila bahasa Jawa memiliki bahasa Jawa Kuno,
tengahan, dan baru. Akibat yang besar yaitu perubahan arti yang
terkandung dalam kata itu.Ini dengan jelas menunjukkan bahwa
kesatuan-kesatuan kecil yang terjadi dari bunyi-bunyi itu mempunyai
peranan dalam membedakan arti.
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa bahasa
memiliki beberapa karakteristik yaitu sistematis dan generatif, seperangkat
simbol vokal yang arbitrer, diucapkan dan didengarkan, simbol-simbol itu
memiliki makna yang konvensional, digunakan untuk berkomunikasi,
mereflesikan masyarakat penutur dan budayanya, milik manusia,
diperoleh oleh semua manusia dengan cara yang sama, dinamis, bersifat
hierarkis, vertikal dan horizontal, dipakai berpikir dan bertindak.
c. Fungsi bahasa
a) Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal-balik
antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat.
b) Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap,
gagasan,emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembaca.
c) Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan
seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat,
kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya.
d) Fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap
dan pendapat orang lain.
Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi :
a) Fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk memperoleh
sesuatu
b) Fungsi regulatoris, yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan
perilaku orang lain
c) Fungsi intraksional, yaitu bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan
orang lain
d) Fungsi personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi
secara individu
e) Fungsi heuristik, yakni bahasa dapat digunakan untuk belajar dan
menemukan sesuatu
f) Fungsi imajinatif, yakni bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan
dunia imajinasi
g) Fungsi representasional, bahasa difungsikan untuk menyampaikan
informasi
Fungsi bahasa Indonesia :
a) Bahasa resmi kenegaraan
c) Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah
d) Alat pengembangan kebudayaan
Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku :
a) Fungsi pemersatu, artinya bahasa Indonesia mempersatukan suku
bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda
b) Fungsi pemberi kekhasan, artinya bahasa baku memperbedakan
bahasa itu dengan bahasa yang lain
c) Fungsi penambah kewibawaan, penggunaan bahasa baku akan
menambah kewibawaan atau prestise.
d) Fungsi sebagai kerangka acuan, mengandung maksud bahwa bahasa
baku merupakan kerangka acuan pemakaian bahasa
d. Ragam Bahasa
Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam
masyarakat menggunakan bahasa, dan dalam masyarakat tersebut
terdapat bermacam–macam bahasa yang disebut ragam bahasa.
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, yang
dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan pola kebudayaan sendiri-sendiri,
pasti melahirkan berbagai ragam bahasa yang bermacam-macam dan ini
disebut Ragam Bahasa Indonesia.
Keragaman bahasa yang ada dalam masyarakat menjadi warna
tersendiri meskipun melahirkan perbedaan kompetensi berbahasa individu
komunikatif adalah kemampuan bertutur atau menggunakan bahasa
sesuai dengan fungsi, situasi, serta norma-norma berbahasa dalam
masyarakat yang sebenarnya. Kompetensi komunikatif berhubungan
dengan kemampuan sosial dan kebudayaan pemakai bahasa yang dapat
membantu untuk menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk
linguistik. Kemampuan komunikatif juga biasa disebut dengan repertoir
bahasa. Repertoir bahasa yang dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok
pemakai bahasa atau masyarakat disebut masyarakat tutur.
Menurut Fishman dan Labov (2014 ; 21), masyarakat tutur berbeda
dengan masyarakat bahasa, tipe masyarakat tutur itu sendiri lambat laun
mengalami pergeseran dari faktor keturunan ke faktor pendidikan. Ada 4
pengklasifisikan tipe masyarakat tutur yakni; berdasarkan pada perolehan
dan kepandaian berbahasa antara lain masyarakat ekabahasa
(monolingual), masyarakat dwibahasa (bilingual), dan masyarakat tutur
multibahasa (multilingual). Berdasarkan strata sosial, masyarakat tutur
terbagi atas lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah.
Penyebab adanya lapisan sosial ialah sesuatu yang dihargai. Berdasarkan
ciri perkembangan ada empat tipe masyarakat tutur yakni masyarakat
primitif, desa tradisional, kota praindustri dan modern. Sedangkan
berdasar kegiatan tutur komunikasi terbagi atas situasi tutur, peristiwa
tutur, dan tindak tutur.
Kajian tentang ragam bahasa juga bisa ditinjau berdasarkan
masyarakat tutur sebagai suatu kelompok orang atau masyarakat yang
memiliki verbal repertoir yang relatif sama serta mereka mempunyai
penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang
digunakan di dalam masyarakat itu. Maka dapat dikatakan, bahwa
kelompok orang itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur.
Satu hal lagi yang perlu dicatat, untuk dapat disebut satu masyarakat tutur
adalah adanya perasaan di antara penuturnya, bahwa mereka merasa
menggunakan tutur yang sama;
Ragam bahasa menurut sudut pandang penutur :
a) Ragam daerah ( logat / dialek)
b) Ragam pendidikan :
(1) Bahasa baku
(2) Bahasa tidak baku
c) Ragam bahasa menurut sikap penutur, gaya atau langgam yang
digunakan penutur terhadap orang yang diajak bicara.
d) Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya :
1. ragam dari sudut pandangan bidang atau pokok persoalan
2. ragam menurut sarananya :
(1) Lisan : dengan intonasi yaitu tekanan, nada, tempo suara, dan
perhentian.
3. ragam yang mengalami gangguan pencampuran
e) Ragam bahasa menurut bidang wacana :
(1) Ragam ilmiah : bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah,
ceramah, tulisan-tulisan ilmiah
(2) Ragam populer : bahasa yang digunakan dalam pergaulan
sehari-hari dan dalam tulisan populer
f) Ragam bahasa baku dan tidak baku
Ciri–ciri ragam bahasa baku :
(1) Kemantapan dinamis, memiliki kaidah dan aturan yang relatif
tetap dan luwes.
(2) Kecendekiaan, sanggup mengungkap proses pemikiran yang
rumit di berbagai ilmu dan teknologi
(3) Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma
Proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunikasi.
Dalam proses pembakuan atau standardisasi variasi bahasa, bahasa itu
disebut bahasa baku atau standar. Pembakuan tidak bermaksud untuk
mematikan variasi-variasi bahasa tidak baku.
g) Ragam Bahasa Tulis dan Bahasa Lisan
Ada dua perbedaan yang mencolok mata yang dapat diamati antara
ragam bahas tulis dengan ragam bahasa lisan, yaitu :
(1) Dari segi suasana peristiwa
Jika menggunakan bahasa tulisan tentu saja orang yang diajak
digunakan perlu lebih jelas. Fungsi gramatikal, seperti subjek, predikat,
objek, dan hubungan antara setiap fungsi itu harus nyata dan erat.
Sedangkan dalam bahasa lisan, karena pembicara berhadapan langsung
dengan pendengar, unsur (subjek-predikat-objek) kadangkala dapat
diabaikan.
(b) Dari segi intonasi
Perbedaan bahasa lisan dan tulisan adalah berkaitan dengan
intonasi (panjang-pendek suara/tempo, tinggi-rendah suara/nada,
keras-lembut suara/tekanan) yang sulit dilambangkan dalam ejaan dan tanda
baca, serta tata tulis yang dimiliki. Goeller (1980) mengemukakan bahwa
ada tiga karakteristik bahasa tulisan yaitu acuracy, brevety, claryty (ABC).
Acuracy (akurat) adalah segala informasi atau gagasan yang
dituliskan dapat memberi keyakinan bagi pembaca bahwa hal tersebut
masuk akal atau logis. Brevety (ringkas) yang berarti gagasan tertulis yang
disampaikan bersifat singkat karena tidak menggunakan kata yang
mubazir dan berulang, seluruh kata yang digunakan dalam kalimat ada
fungsinya. Claryty (jelas) adalah tulisan itu mudah dipahami, alur
pikirannya mudah diikuti oleh pembaca, tidak menimbulkan salah tafsir
bagi pembaca.
e. Bahasa dan Kajian Semiotik
Bahasa sebagai sistem tanda memiliki konsep yang sejalan dengan semiotika. Ferdinand de Saussure lebih sering menggunakan istilah tanda ketimbang simbol atau lambang. Tanda (signe) atau tanda linguistik (signe
linguistique) adalah istilah yang sering disebut Saussure. Dalam Linguistik Umum karya Chaer (1994), ia menjelaskan pelbagai tanda yang menjadi objek kajian semiotik yaitu,
(1). Tanda, sesuatu yang dapat mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Contoh, asap menandakan adanya api.
(2). Lambang, sesuatu yang dapat menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Contoh, bendera kuning melambangkan adanya orang yang meninggal.
(3). Sinyal atau isyarat, tanda yang sengaja dibuat oleh pemberi sinyal agar penerima sinyal melakukan sesuatu. Contoh, letusan pistol dalam lomba lari.
(4). Gerak isyarat atau gestur, tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan. Contoh, anggukan kepala yang menandakan persetujuan akan suatu perkara.
(5). Gejala atau sympton, tanda yang tidak disengaja, yang dihasilkan
tanpa maksud, tetapi alamiah untuk menunjukkan atau
mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Contoh, demam selama beberapa hari, kemudian dokter berkata “ini gejala tipus”. (Chaer, 1994:40-41).
(6). Ikon, tanda yang paling mudah dipahami karena kemiripannya dengan sesuatu yang diwakili. Contoh, denah jalan, maket, dan patung dada.
(7). Indeks, tanda yang menunjukan adanya sesuatu yang lain. Contoh, suara air yang menunjukkan adanya sungai atau air terjun.
(8). Kode, ciri kode sebagai tanda adalah adanya sistem, baik berupa simbol, sinyal, maupun gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, benda, dan tindakan yang disepakati untuk maksud tertentu (Chaer, 1994:40-42).
Semiotik adalah ‘ilmu yang’ mengkaji tanda dalam kehidupan
manusia karena manusia memiliki kemampuan untuk memberikan makna
kepada berbagai gejala sosial budaya dan alamiah, maka semiotik dapat
disimpulkan bahwa tanda adalah bagian dari kebudayaan manusia. Ini
berarti mempelajari semiotika sama dengan mempelajari tentang berbagai
tanda. Cara kita berpakaian, apa yang kita makan, dan cara kita
bersosialisasi sebetulnya juga mengomunikasikan hal-hal mengenai diri
kita, dan dengan begitu, dapat kita pelajari sebagai tanda.
Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal dari
kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Istilah semeion tampaknya
diturunkan dari kedokteran hipokratik atau asklepiadik dengan
perhatiannya pada simtomatologi dan diagnostik inferensial. Tanda pada
masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal
lain. Secara terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan
dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas
objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ahli sastra
Teew (1984:6) mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindak
komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi model sastra yang
mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk
pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam
masyarakat mana pun. Namun, banyak pula masalah jika ada seseorang
bertanya apa yang dimaksud dengan tanda. Van Zoest memberikan lima
ciri dari tanda.
Pertama, tanda harus dapat diamati agar dapat berfungsi sebagai
tanda. Sebagai contoh van Zoest menggambarkan bahwa di pantai ada
orang-orang duduk dalam kubangan pasir, di sekitar kubangan dibuat
semacam dinding pengaman (lekuk) dari pasir dan pada dinding itu
diletakkan kerang-kerang yang sedemikian rupa sehingga membentuk
kata ‘Duisburg’ maka kita mengambil kesimpulan bahwa di sana duduk
orang-orang Jerman dari Duisburg. Bisa sampai pada kesimpulan itu,
karena kita tahu bahwa kata tersebut menandakan sebuah kota di
Republik Bond, menganggap dan menginterpretasikannya sebagai tanda.
Kedua, tanda harus ‘bisa ditangkap’ merupakan syarat mutlak. Kata
Duisburg dapat ditangkap, tidak penting apakah tanda itu diwujudkan
dengan pasir, kerang atau ditulis di bendera kecil atau dengar dari orang