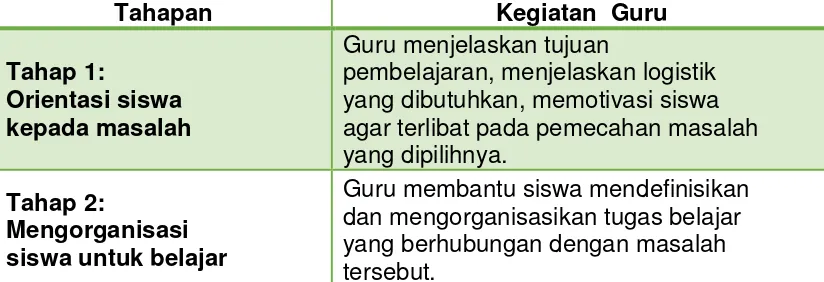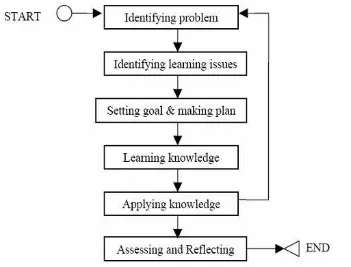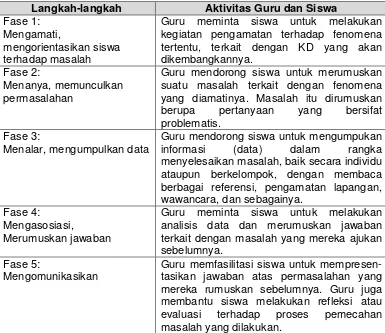i
IMPLEMENTASI
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
(PROBLEM BASED LEARNING)
PADA MATA PELAJARAN RUMPUN MIPA
(SAINS)
Makalah Tugas Kelompok
Mata Kuliah Kajian Pengembangan Bidang MIPA/IPS?Bahasa Dosen Pengampu: Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Subagyo, M.Pd.
Oleh:
Kelompok I
AGUS SAEFUDIN
/ 0102514057
AHMAD KUSFANDI / 0102514064
SUYATNO
/ 0102514068
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
KONSENTRASI KEPENGAWASAN SEKOLAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
OKTOBER
ii
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan banyak kenikmatan, utamanya nikmat iman,
sehat, sempat dan diberi kekuatan tetap setia mengabdi pada bidang
pendidikan untuk berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pula makalah dengan judul
“Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) pada Mata Pelajaran Rumpun MIPA (Sains)” dapat
diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi Tugas
Kelompok Mata Kuliah Kajian Pengembangan Bidang MIPA/IPS/Bahasa
dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Subagyo, M.Pd.
Banyak bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam
penyusunan makalah ini, untuk itu disampaikan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Subagyo, M.Pd. yang telah memberikan
bimbingan dan banyak ilmu tentang Kajian Pengembangan Bidang
MIPA/IPS/Bahasa kepada kami;
2. Teman-teman mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan (Kepengawasan
Sekolah) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang
merupakan mitra diskusi dan berbagi pengalaman yang luar biasa.
Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan
pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagaimana kata pepatah
tak ada gading yang tak retak, makalah ini pun masih terdapat
kekurangan. Saran dan masukan demi perbaikan sangat dinantikan. Kami
berharap semoga makalah ini membawa manfaat bagi kita semua dalam
mengabdi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin.
Semarang, 12 Oktober 2015
iii A. Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning) ... 1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah ... 2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah ... 3. Teori Belajar yang Melandasar Pembelajaran Berbasis
Masalah ... B. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah .. 1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 2. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah ... C. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning) ... D. Contoh Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah
(Problem Based Learning) ... E. Desaian Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
iv
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
(PROBLEM BASED LEARNING) PADA MATA PELAJARAN RUMPUN MIPA (SAINS)
Oleh:
Agus Saefudin / 0102514057 Ahmad Kusfandi / 0102514064 Suyatno / 0102514068
Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Konsentrasi Kepengawasan Sekolah Universitas Negeri Semarang
Tujuan penulisan makalah ini adalah adalah diperolehnya pemahaman dan gambaran yang jelas tentang implementasi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains), meliputi: konsep, keunggulan dan kelemahan, sintaks, contoh implementasi dan desain pembelajaran berbasis masalah (problem based learning).
Pembelajaran Berbasis Masalah (problem Based Learning) merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk belajar aktif memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah bagi siswa, diantaranya: didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah, membangun pengetahuannya sendiri, berfokus pada masalah, aktivitas ilmiah, terbiasa menggunakan sumber pengetahuan bervariasi, memiliki kemampuan komunikasi ilmiah, dan peer teaching untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara mandiri. Sedangkan kekurangan pembelajaran berbasis masalah, diantaranya: lebih cocok untuk pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah, kesulitan dalam pembagian tugas dalam kelas dengan keragaman siswa tinggi, kurang cocok untuk siswa sekolah dasar, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan kemampuan guru untuk mendorong kerja siswa, dan sumber belajar kadang tidak tersedia dengan lengkap.
Langkah-langkah pembelajaran (sintaks) model pembelajaran berbasis masalah pada kurikulum 2013 terdiri dari lima fase, yaitu: mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
v
ABSTRACT
IMPLEMENTATION PROBLEMBASED LEARNING ON THE SUBJECTS OF CLUMPS OF SCIENCE
by:
Agus Saefudin / 0102514057 Ahmad Kusfandi / 0102514064 Suyatno / 0102514068
Post Graduate Program Studies Education Management Concentration Supervisory School Semarang State University
The purpose of writing this paper is to obtain an understanding and a clear picture of the implementation of problem-based learning on the subjects of clumps of Science, include: concept, advantages and disadvantages, syntax, examples of implementation and design of problem-based learning.
Problem Based Learning is an instructional model that involves students to learn actively solve a problem through the stages of the scientific method. Excess problem-based learning for students, such as: are encouraged to have the ability to solve problems, build his own knowledge, focusing on the problem, the scientific activity, accustomed to using varied sources of knowledge, the ability of scientific communication, and peer teaching to overcome the learning difficulties students independently. While the lack of problem-based learning, such as: more suitable for learning related to solving problems, difficulty in the division of tasks in a class with a diversity of students is high, less suitable for primary school students, requires substantial time, require the ability of teachers to encourage the students' work, and learning resources sometimes unavailable to complete.
Learning steps (syntax) model of problem-based learning in the curriculum in 2013 consists of five phases, namely: to observe, to question, reason, associate and communicate.
- 1 -
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran mata pelajaran rumpun MIPA (sains) berupaya
meningkatkan minat siswa untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan berpikir tentang alam seisinya yang
penuh dengan rahasia yang tiada habisnya. Berdasarkan
Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan, bahwa: (1) pada
dimensi sikap diharapkan siswa memiliki kualifikasi kemampuan
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak
mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia;
(2) pada dimensi pengetahuan siswa memiliki kualifikasi kemampuan
memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian; dan (3) pada
dimensi keterampilan siswa memiliki kualifikasi kemampuan memiliki
kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah
abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di
sekolah secara mandiri.
Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan
adalah lemahnya kemampuan siswa dalam menggunakan
kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan masalah. Siswa
cenderung dijejali dengan berbagai informasi yang menuntut hapalan
saja. Banyak sekali pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa
tetapi sulit untuk dihubungkan dengan situasi yang mereka hadapi.
- 2 -
tidak relevan dengan apa yang mereka hadapi. Ketika siswa mengikuti
sebuah pendidikan tiada lain untuk menyiapkan mereka menjadi
manusia yang tidak hanya cerdas tetapi mampu menyelesaikan
persoalan yang akan mereka hadapi di kemudian hari.
Sudah sering mendengar keluhan siswa betapa beratnya
mereka mengikuti beban dari sekolah. Mereka dituntut untuk
mengetahui segala hal yang dituntut oleh kurikulum. Walaupun
kapasitas intelektualnya dapat menjangkau beban tersebut, siswa
seperti telepas dari dunianya. Padahal yang mereka hadapi harus
dapat diselesaikan dengan kemampuan sendiri. Oleh karena itu,
pendidikan harus membekali mereka dengan
kemampuan-kemampuan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan
yang mereka hadapi. Kemampuan tersebut adalah kemampuan
memecahkan masalah. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui
pembelajaran dimana masalah dihadirkan di kelas dan siswa diminta
untuk menyelesaikannya dengan segala pengetahuan dan
keterampilan yang mereka miliki. Pembelajaran bukan lagi sebagai
“transfer of knowledge”, tetapi mengembangkan potensi siswa secara sadar melalui kemampuan yang lebih dinamis dan aplikatif.
Di lapangan banyak ditemukan kenyataan yang menunjukkan
bahwa dalam pembelajaran MIPA (sains) siswa cenderung kurang aktif
dan kreatif dalam belajar dikarenakan guru masih banyak
menggunakan teknik menghafal yaitu siswa mencatat penjelasan guru
dan atau buku serta kurang melibatkan sumber belajar yang nyata.
Selain itu strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran masih
bersifat konvensional, teacher centered yang cenderung otoriter dan
tidak merangsang aktivitas belajar siswa secara optimal.
Bentuk proses pembelajaran MIPA (sains) seperti yang banyak
ditemukan dilapangan ini menjadi salah satu hambatan tercapainya
tujuan pembelajaran MIPA sebagaimana telah digariskan dalam
Standar Kompetensi Lulusan. Hal ini berarti bahwa berhasilnya atau
- 3 -
proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Melalui proses
pembelajaran akan dicapai tujuan pembelajaran dalam bentuk
terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri anak, mengembangkan
potensi peserta didik secara aktif.
Aderson (1993) menyatakan bahwa kebanyakan pembelajaran
manusia melibatkan proses pemecahan masalah. Proses pemecahan
masalah cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran MIPA (sains)
karena dapat meningkatan kemampuan berpikir siswa secara logis,
kritis, kreatif dan inovatif. Pemecahan masalah yang dimaksud bukan
sekedar menerapkan aturan-aturan yang sudah dipelajari guna
menjawab sebuah permasalahan tetapi harus melalui tahap
mengidentifikasi, mendefinisikan, mengeksplorasi, mengantisipasi dan
mengambil pelajaran. Menurut Lie (2009: 75) walaupun kemajuan
teknologi sudah pesat tetapi banyak tenaga pengajar yang belum
sepenuhnya jelas tentang bagaimana sebaiknya meningkatkan
kemahiran siswa dalam memecahkan suatu masalah. Pemecahan
masalah yang dibangun cenderung bersifat otomatis, pengetahuan
yang dibangun untuk memecahkan masalah tersebut masih bersifat
umum. Dalam pembelajaran MIPA, hal ini seringkali menyebabkan
siswa yang sudah bersusah payah menemukan bukti-bukti yang
signifikan untuk masalahnya tetapi ternyata hipotesa yang mereka
ajukan tidak relevan.
Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)
merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok untuk
diterapkan dalam pembelajaran MIPA. Sesuai dengan namanya,
pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang
berdasar pada masalah-masalah yang dihadapi siswa terkait dengan
Kompetensi Dasar (KD) yang sedang dipelajari siswa. Masalah yang
dimaksud bersifat nyata atau sesuatu yang menjadi pertanyaan pelik
bagi siswa. Hal ini berbeda dengan model pembelajaran penemuan
yang masalahnya cenderung direkayasa karena tujuannya bukan
- 4 -
yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tuntutan KD dalam
kurikulum.
Model pembelajaran berbasis masalah akan berlangsung
dengan baik apabila para siswa sudah memiliki kemampuan berpikir
kritis terhadap suatu fenomena. Siswa memiliki keleluasaan untuk
berpendapat, tanpa terbebani oleh berbagai tekanan. Juga diliputi oleh
suasana yang penuh dengan toleransi akan kemungkinan munculnya
beragam tanggapan yang saling bertentangan. Untuk menuju tahap
seperti itu, para siswa terlebih dahulu perlu memiliki pengetahuan
mendalam ataupun referensi yang banyak sehingga mereka bisa
membedakan benar salahnya suatu konsep, peristiwa, keadaan, dan
yang lainnya. Apabila menganggap adanya sesuatu yang salah, berarti
siswa itu sudah menemukan suatu masalah dan hal ini perlu
ditindaklanjuti dengan merumuskan pemecahannya (Kosasih, 2014).
Dengan memperhatikan uraian di atas kami memandang bahwa
menarik untuk mengkaji implementasi pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning) pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains),
dimulai dengan pengertian dan ciri-ciri yang khas, serta menganalisis
keunggulan dan kelemahan, dilanjutkan dengan langkah-langkah
implementasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis masalah di kelas.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep pembelajaran berbasis masalah (problem
based learning) ?
2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis
masalah (problem based learning) ?
3. Bagaiamana langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis
masalah pada mata pelajaran rumpun MIPA (problem based
learning) ?
4. Bagaimana contoh implementasi pembelajaran berbasis masalah
- 5 -
5. Bagaimana desain pembelajaran yang mengimplemen-tasikan
model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran
rumpun MIPA (problem based learning) ?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang
hendak dicapai dalam pembahasan makalah ini adalah diperolehnya
pemahaman dan gambaran yang jelas tentang implementasi
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) pada mata
pelajaran rumpun MIPA (sains), meliputi:
1. Konsep pembelajaran berbasis masalah (problem based learning);
2. Keunggulan dan kelamahan pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning);
3. Langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning);
4. Contoh implementasi pembelajaran berbasis masalah (problem
based learning);
5. Desain pembelajaran yang mengimplementasikan model
pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran rumpun MIPA
(problem based learning).
D. Manfaat
1. Manfaat Teoritis
Memberikan penjelasan dan deskripsi teoritis tentang tentang
implementasi pembelajaran berbasis masalah (problem based
learning) pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains), meliputi:
pengertian, ciri-ciri, keunggulan dan kelemahan, langkah-langkah
implementasi dan contoh desain pembelajaran dengan model
- 6 -
2. Manfaat Praktis
a. Bagi sekolah diperoleh gambaran tentang efektivitas
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)
sebagai salah satu model alternatif dalam pembelajaran yang
dapat diterapkan pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains) di
samping model-model pembelaran lainnya. Dengan
bervariasinya model pembelajaran yang diimplementasikan oleh
sekolah maka diharapkan dinamika pembelajaran siswa lebih
terasa dan dapat tumbuh budaya belajar di sekolah. Sekolah
diharapkan dapat memperkaya model-model pembelajaran
dengan pendekatan pembelajaran berpusat siswa (student
centered learning) dan pendekatan sains (science approach)
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan yang
unggul.
b. Bagi guru diperoleh pemahaman yang mendalam tentang
keunggulan implementasi pembelajaran berbasis masalah ada
mata pelajaran rumpun MIPA (sains) sehingga guru dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.
c. Bagi siswa calon pengawas diperoleh gambaran nyata tentang
implementasi pembelajaran berbasis masalah pada mata
pelajaran rumpun MIPA (sains), baik secara teoritis maupun
fakta empiris di lapangan sebagai contoh sehingga mempunyai
pemahaman yang benar tentang model-model pembelajaran
siswa aktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan
- 7 -
BAB II
PEMBAHASAN
A. Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)
Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem Based
Learning (PBL) didasarkan pada hasil penelitian Barrow and Tamblyn
(1980, Barret, 2005) dan pertama kali diimplementasikan pada sekolah
kedokteran di McMaster University Kanada pada tahun 60-an. PBM
sebagai sebuah pendekatan pembelajaran diterapkan dengan alasan
bahwa PBM sangat efektif untuk sekolah kedokteran dimana siswa
dihadapkan pada permasalahan kemudian dituntut untuk
memecahkannya. PBM lebih tepat dilaksanakan dibandingkan dengan
pendekatan pembelajaran tradisional. Hal ini dapat dimengerti bahwa
para dokter yang nanti bertugas pada kenyataannya selalu dihadapkan
pada masalah pasiennya sehingga harus mampu menyelesaikannya.
Walaupun pertama dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah
kedokteran tetapi pada perkembangan selanjutnya diterapkan dalan
pembelajaran secara umum.
Barrow (1980, Barret, 2005) mendefinisikan PBM sebagai “The
learning that results from the process of working towards the
understanding of a resolution of a problem. The problem is
encountered first in the learning process.” Sementara Cunningham et.al.(2000, Chasman er.al., 2003) mendefiniskan PBM sebagai
“…Problem-based learning (PBL) has been defined as a teaching
strategy that “simultaneously develops problem-solving strategies, disciplinary knowledge, and skills by placing students in the active role
as problem-solvers confronted with a structured problem which mirrors
- 8 -
1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah
Pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak
zaman John Dewey. Menurut Dewey (dalam Trianto, 2009:91)
belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan
respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan
lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta
didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak
berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah
yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari
pemecahannya dengan baik.
Pembelajaran Berbasis Masalah yang berasal dari bahasa
Inggris Problem Based Learning adalah suatu pendekatan
pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah,
tetapi untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan
pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Pendekatan
pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning/PBL)
adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan
lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang
penting dan relevan (bersangkut-paut) bagi peserta didik, dan
memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar
yang lebih realistik (nyata).
Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta
didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat
kepada peserta didik, yang mengembangkan kemampuan
pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang
diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan
karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini.
Pembelajaran Berbasis Masalah dapat pula dimulai dengan
melakukan kerja kelompok antarpeserta didik. peserta
didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, kemudian
- 9 -
Pembelajaran Berbasis Masalah menyarankan
kepada peserta didik untuk mencari atau menentukan
sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran berbasis
masalah memberikan tantangan kepada peserta didik untuk belajar
sendiri. Dalam hal ini, peserta didik lebih diajak untuk membentuk
suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan guru
sementara pada pembelajaran tradisional, peserta didik lebih
diperlakukan sebagai penerima pengetahuan yang diberikan
secara terstruktur oleh seorang guru.
Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based learning),
selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model
pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif
kepada peserta didik. PBL adalah suatu model pembelajaran vang,
melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui
tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat
mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah
tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan
masalah. Untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal,
pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah perlu
dirancang dengan baik mulai dari penyiapan masalah yang yang
sesuai dengan kurikulum yang akan dikembangkan di kelas,
memunculkan masalah dari peserta didik, peralatan yang mungkin
diperlukan, dan penilaian yang digunakan. Pengajar yang
menerapkan pendekatan ini harus mengembangkan diri melalui
pengalaman mengelola di kelasnya, melalui pendidikan pelatihan
atau pendidikan formal yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang
efektif untuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi. Pembelajaran
ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah
jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri
tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk
- 10 -
2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah
Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow, Min Liu (2005)
menjelaskan karakteristik dari PBM, yaitu :
a. Learning is student-centered
Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada
siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga
oleh teori konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat
mengembangkan pengetahuannya sendiri.
b. Authentic problems form the organizing focus for learning
Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang
otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami
masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan
profesionalnya nanti.
c. New information is acquired through self-directed learning
Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum
mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya,
sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui
sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya.
d. Learning occurs in small groups
Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha
membangun pengetahuan secara kolaborative, maka PBM
dilaksakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat
menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan
yang jelas.
e. Teachers act as facilitators.
Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai
fasilitator. Namun, walaupun begitu guru harus selalu memantau
perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar
- 11 -
3. Teori Belajar yang Melandasi Pembelajaran Berbasis Masalah
Ada beberapa teori belajar yang melandasi Model Pembelajaran
Berbasis Masalah (Problem Based Learning) sebagai berikut :
(Rusman, 2010)
a. Teori Belajar Konstruktivisme
Dari segi pedagogis, Model Pembelajaran Berbasis Masalah
(Problem Based Learning) didasarkan pada teori
konstruktivisme dengan ciri :
1) Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario
permasalahan dan lingkungan belajar.
2) Pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah
menciptakan disonansi kognitif yang menstimulasi belajar.
3) Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negoisasi
sosial dan evaluasi terhadap keberadaan sebuah sudut
pandang.
b. Teori Belajar dari Piaget
Piaget menegaskan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu
bawaan dan secara terus menerus berusaha ingin memahami
dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini, menurut Piaget dapat
memotivasi mereka untuk secara aktif membangun tampilan
dalam otak mereka mengenai lingkungan yang mereka hayati.
Pada saat mereka tumbuh semakin dewasa dan memperoleh
lebih banyak kemampuan bahasa dan memori, tampilan mental
mereka tentang dunia menjadi lebih luas dan lebih abstrak.
Sementara itu, pada semua tahap perkembangan, anak perlu
memahami lingkungan mereka dan memotivasinya untuk
menyelidiki dan membangun teori-teori yang menjelaskan
lingkungan itu.
c. Teori Belajar Bermakna dari David Ausubel
Suparno dalam Rusman (2010) mengatakan bahwa Ausubel
membedakan antara belajar bermakna (meaningfull learning)
- 12 -
merupakan proses belajar dimana informasi baru dihubungkan
dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang
sedang belajar. Belajar menghafal, diperlukan bila seseorang
memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama
sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya.
Kaitannya dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah
(Problem Based Learning) dalam hal mengaitkan informasi baru
dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa.
d. Teori Belajar Vigotsky
Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu
berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang serta
ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang
dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman, individu
berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan
awal yang telah dimilikinya kemudian kemudian membangun
pengertian baru. Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2010)
Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman lain
memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya
perkembangan intelektual siswa. Kaitannya dengan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif
yang telah dimiliki oleh siswa melalui kegiatan belajar dalam
interkasi sosial dengan teman lain.
e. Teori Belajar dari Albert Bandura
Model Pembelajaran Berbasis Masalah juga berlandaskan
pada social leraning theory Albert Bandura, yang fokus pada
pembelajaran dalam konteks sosial (social context). Teori ini
menyatakan bahwa seorang belajar dari orang lain, termasuk
konsep dari belajar observasional, imination dan modeling.
Prinsip umum dari social learning theory selengkapnya
- 13 -
General principles of social learning theory follows:
1) People can learn by observing the behavior is of others and
the autcomes of those behaviors.
2) Learning can occur without a change in behavior.
Behaciorists say that learning has to be represented by a
permanent change in behavior, in contrast social learning
theorists say that because people can learn thourg
observation alone, their learning may not necessarily be
shown in their performance. Learning may or may not result
in a behavior change.
3) Cognition plays a role in learning. Over the last 30 years
social learning theory has become increasingly cognitive in
its interpretation of human learning. Awareness and
expectation of future reinforcements or punishments can
have a major effect on the behaviors that people exhibit.
4) Social learning theory can be considered a bridge or a
transition between behaviorist learning theories and
cognitive learning theories.
f. Teori Belajar Jerome S. Bruner
Metode penemuan merupakan metode dimana siswa
menemukan kembali, bukan menemukan yang sama sekali
benar-benar baru. Belajar penemuan sesuai dengan pencarian
pengetahuan secara aktif oleh manusia, dengan sendirinya
memberikan hasil yang lebih baik, berusaha sendiri mencari
pemecahan masalah serta didukung oleh pengetahuan yang
menyertainya, serta menghasilkan pengetahuan yang
benar-benar bermakna (Dahar dalam Rusman, 2010).
Bruner juga menggunakan konsep scaffolding dan interaksi
sosial di kelas maupun di luar kelas. Scaffolding adalah suatu
proses untuk membantu siswa menuntaskan masalah tertentu
melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan guru,
- 14 -
Kaitan intelektual antara pembelajaran penemuan dan
belajar berbasis masalah sangat jelas. Pada kedua model ini,
guru menekankan keterlibatan siswa secara aktif, orientasi
induktif lebih ditekankan dari pada deduktif, dan siswa
menentukan atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.
Pada belajar berbasis masalah atau penemuan, guru
mengajukan pertanyaan atau masalah kepada siswa dan
memperbolehkan siswa untuk menemukan ide dan teori mereka
sendiri.
B. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah
Dalam pelaksanaannya, PBM tentunya memiliki kelebihan dan
kelemahannya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari PBM.
1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah
a. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan
masalah dalam situasi nyata
b. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya
sendiri melalui aktivitas belajar
c. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang
tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa.
Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau
menyimpan informasi
d. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok
e. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan
baik dari perpustakaan, internet, wawancara dan observasi
f. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri
g. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah
dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka
h. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui
- 15 -
2. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah
a. PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada
bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBM lebih
cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu
yang kaitannya dengan pemecahan masalah.
b. Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang
tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas.
c. PBM kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena
masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. PBM sangat
cocok untuk siswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah
menengah.
d. PBM biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga
dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang
diharapkan walapun PBM berfokus pada masalah bukan konten
materi.
e. Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja
siswa dalam kelompok secara efektif, artinya guru harus memilki
kemampuan memotivasi siswa dengan baik.
f. Adakalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan
lengkap.
C. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)
Menurut Fibrayir (2012), berbgai pengembang pembelajaran
berbasis masalah telah menunjukkkan ciri-ciri pengajaran berbasis
masalah sebagai berikut.
1. Pengajuan masalah atau pertanyaan
Pengajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan
prinsip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu, pembelajaran
berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar
pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting
dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka dihadapkan
- 16 -
sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi
untuk situasi itu. Menurut Arends (dalam Abbas, 2000:13),
pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memenuhi kriteria
sebagai berikut.
a. Autentik. Yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan
dunia nyata siswa dari pada berakar pada prinsip-prinsip disiplin
ilmu tertentu.
b. Jelas. Yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam arti tidak
menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya
menyulitkan penyelesaian siswa.
c. Mudah dipahami. Yaitu masalah yang diberikan hendaknya
mudah dipahami siswa. Selain itu masalah disusun dan dibuat
sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.
d. Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yaitu masalah
yang disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas, artinya
masalah tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan
diajarkan sesuai dengan waktu, ruang dan sumber yang tersedia.
Selain itu, masalah yang telah disusun tersebut harus didasarkan
pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
e. Bermanfaat. Yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan
haruslah bermanfaat, baik siswa sebagai pemecah masalah
maupun guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang
bermanfaat adalah masalah yang dapat meningkatkan
kemampuan berfikir memecahkan masalah siswa, serta
membangkitkan motivasi belajar siswa.
2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin
Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada
mata pelajaran tertentu (IPA, Matematika, Ilmu-ilmu Sosial),
masalah yang akan diselidiki telah yang dipilih benar-benar nyata
agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak
- 17 -
3. Penyelidikan autentik
Pengajaran berbasis masalah siswa melakukan penyelidikan
autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata.
Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah,
mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan
dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika
diperlukan), membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan.
Metode penyelidikan yang digunakan bergantung pada masalah
yang sedang dipelajari.
4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya
Pengajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan
produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan
peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian
masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat berupa transkip
debat, laporan, model fisik, video atau program komputer.
Pengajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa bekerja sama
satu sama lain (paling sering secara berpasangan atau dalam
kelompok kecil). Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara
berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan
memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk
mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berfikir.
Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
Tahapan Kegiatan Guru
Tahap 1:
Orientasi siswa kepada masalah
Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya.
Tahap 2:
Mengorganisasi siswa untuk belajar
- 18 -
Tahapan Kegiatan Guru Tahap 3: dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video dan model serta membantu mereka berbagi tugas
a. Langkah-Langkah PBM
Pelaksanaan PBM memiliki ciri tersendiri berkaitan dengan
langkah pembelajarannya. Barret (2005) menjelaskan
langkah-langkah pelaksanaan PBM sebagai berikut :
1) Siswa diberi permasalahan oleh guru (atau permasalahan
diungkap dari pengalaman siswa)
2) Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan
melakukan hal-hal berikut.
Mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan
Mendefinisikan masalah Melakukan tukar pikiran
berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki Menetapkan
hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah
Menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk
menyelesaikan masalah
3) Siswa melakukan kajian secara independen berkaitan
dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat
melakukannya dengan cara mencari sumber di
perpustakaan, database, internet, sumber personal atau
- 19 -
4) Siswa kembali kepada kelompok PBM semula untuk
melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat,
dan bekerjasaman dalam menyelesaikan masalah.
5) Siswa menyajikan solusi yang mereka temukan
6) Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan
dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini meliputi
sejauhmana pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa
serta bagaiman peran masing-masing siswa dalam
kelompok.
7) Sementara itu Yongwu Miao et.al. membut model Protokol
PBM yang disajikan dalam ilustrasi berikut.
Gambar 1. Model Protokol PBL
Pada dasarnya, langkah-langkah menurut Barret (2005) dan
Miao et.al. (2000) ini memiliki kesamaan. Peran guru sebagai
fasilitator sangat penting karena berpengaruh kepada proses
belajar siswa. Walaupun siswa lebih banyak belajar sendiri
- 20 -
guru sebagai tutor adalah memantau aktivitas siswa,
memfasilitasi proses belajar dan menstimulasi siswa dengan
pertanyaan. Guru harus mengetahui dengan baik tahapan kerja
siswa baika aktivitas fisik ataupun tahapan berpikir siswa.
Barret (2005) menyebutkan beberapa hal yang harus dikuasai
atau dilakukan oleh tutor agar kegiatan PBM dalap berjalan
dengan baik, yaitu :
1) Harus berpenampilan meyakinkan dan antusias
2) Tidak memberikan penjelasan saat siswa bekerja
3) Diam saat siswa bekerja
4) Menyarankan siswa untuk berbicara dengan siswa lain
bukan dengan dirinya
5) Meyakinkan siswa untuk menyepakati terlebih dahulu
tentang pemahaman terhadap permasalahan secara
kelompok sebelum siswa bekerja individual
6) Memberikan saran pada siswa tentang sumber informasi
yang dapat diakses berkaitan dengan permasalahan
7) Selalu mengingat hasil pembelajaran yang ingin dicapai
8) Mengkondisikan lingkungan atau suasana belajar yang baik
untuk kegiatan kelompok Menjadi diri sendiri atau tampil
sesuai dengan gaya sendiri sehingga tidak menampilkan
sikap di luar kebiasaan dirinya.
b. Penilaian Pada PBM
Penilaian dalam PBM tentunya tidak hanya kepada hasilnya
saja tetapi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh
siswa. National Research Council (NRC) (dalam Waters and
McCracken, -) memberikan tiga prinsip berkaitan penilaian
dalam PBM, yaitu yang berkaitan dengan konten, proses
pembelajaran, dan kesamaan. Lebih jelasnaya sebagai berikut.
Konten : penilaian harus merefleksikan apa yang sangat penting
- 21 -
Proses pembelajaran : penilaian harus sesuai dan diarahkan
pada proses pembelajaran
Kesamaan : penilaian harus menggambarkan kesamaan
kesempatan siswa untuk belajar.
Oleh karena itu, menurut Waters and McCracken penilaian yang
dilakukan harus dapat :
1) Menyajikan situasi secara otentik
2) Menyajikan data secara berulang-ulang
3) Memberikan peluang pada siswa untuk dapat mengevaluasi
dan merefleksi pemahaman dan kemampuannya sendiri
4) Menyajikan laporan perkembangan kegiatan siswa.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam
PBM tidak hanya kepada hasil aakhir tetapi juga yang tidak
kalah pentingnya adalah penilaian proses. Penilaian ini bisa
didasarkan pada jenis penilaian otentik (autentic assessment)
dimana penilaian difokuskan terhap proses belajar. Oleh karena
itu, peran guru dalam proses PBM tidak pasif tetapi harus aktif
dalam memantau kegiatan siswa serta mengontrol agar proses
pembelajaran berjalan dengan baik. Sementar itu, untuk
mengetahui sejauhmana hasil belajar yang telah diperoleh
siswa, guru pun perlu untuk mengadakan tes secara individual.
Jadi penialaian dilakukan secara kelompok juga individual.
D. Contoh Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)
Ada beberapa cara menerapkan PBL dalam pembelajaran.
Secara umum penerapan model ini mulai dengan adanya masalah
yang diharus dipecahkan atau dicari pemecahannya oleh siswa/siswa.
Masalah tersebut dapat berasal dari siswa/siswa atau mungkin juga
diberikan oleh pengajar. Siswa/siswa akan memusatkan pembelajaran
di sekitar masalah tersebut, dengan arti lain, siswa belajar teori dan
- 22 -
perhatiannya. Pemecahan masalah dalam PBL harus sesuai dengan
langkah-langkah metode ilmiah. Dengan demikian siswa/siswa belajar
memecahkan masalah secara sistematis dan terencana. Oleh sebab
itu, penggunaan PBL dapat memberikan pengalaman belajar
melakukan kerja ilmiah yang sangat baik kepada siswa/siswa.
Langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran
PBL paling sedikit ada delapan tahapan (Pannen, 2001), yaitu:
1. mengidentifikasi masalah,
2. mengumpulkan data,
3. menganalisis data,
4. memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan
analisisnya,
5. memilih cara untuk memecahkan masalah,
6. merencanakan penerapan pemecahan masalah,
7. melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan
8. melakukan tindakan (action) untuk memecahkan masalah.
Empat tahap yang pertama mutlak diperlukan untuk berbagai
kategori tingkat berfikir, sedangkan empat tahap berikutnya harus
dicapai bila pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai keterampilan
berfikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Dalam proses
pemecahan masalah sehari-hari, seluruh tahapan terjadi dan bergulir
dengan sendirinya, demikian pula keterampilan seseorang harus
mencapai seluruh tahapan tersebut. Langkah mengidentifikasi
masalah merupakan tahapan yang sangat penting dalam PBL.
Pemilihan masalah yang tepat agar dapat memberikan
pengalaman belajar yang mencirikan kerja ilmiah seringkali menjadi
‖masalah‖ bagi guru dan siswa. Artinya, pemilihan masalah yang
kurang luas, kurang relevan dengan konteks materi pembelajaran,
atau suatu masalah yang sangat menyeimpang dengan tingkat berpikir
siswa dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran.
Oleh sebab itu, sangat penting adanya pendampingan oleh guru pada
- 23 -
tetapi dapat memfokuskan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan
agar siswa/siswa melakukan refleksi lebih dalam terhadap masalah
yang dipilih. Dalam hal ini guru/dosen harus berperan sebagai
fasilitator agar pembelajaran tetap pada bingkai yang direncanakan.
Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam PBL
adalah pertanyaan berbasis why bukan sekedar how. Oleh karena itu,
setiap tahap dalam pemecahan masalah, keterampilan siswa dalam
tahap tersebut hendaknya tidak semata-mata keterampilan how, tetapi
kemampuan menjelaskan permasalahan dan bagaimana
permasalahan dapat terjadi. Tahapan dalam proses pemecahan
masalah digunakan sebagai kerangka atau panduan dalam proses
belajar melalui PBL. Namun yang harus dicapai pada akhir
pembelajaran adalah kemampuannya untuk memahami permasalahan
dan alasan timbulnya permasalahan tersebut serta kedudukan
permasalahan tersebut dalam tatanan sistem yang sangat luas.
Fase-fase implementasi PBL dengan merujuk pada
tahap-tahapan praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu:
Fase 1: Mengorientasikan siswa pada masalah, yaitu: menjelaskan
tujuan pembelajaran, logistik yang diperlukan, memotivasi siswa
terlibat aktif pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Fase 2:
Mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu: membantu siswa
membatasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah yang dihadapi. Fase 3: Membimbing penyelidikan
individu maupun kelompok, yaitu: mendorong siswa mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk
penjelasan dan pemecahan. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan
hasil karya, yaitu: membantu siswa merencanakan dan menyi-apkan
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu
mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Fase 5: Menganalisis
dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu: membantu
siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses
- 24 -
1. Fase 1: Mengorientasikan siswa pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran
dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan
PBL, tahapan ini sangat penting dimana guru/dosen harus
menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh
siswa/siswa dan juga oleh dosen. Disamping proses yang akan
berlangsung, sangat penting juga dijelaskan bagaimana guru/dosen
akan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting
untuk memberikan motivasi agar siswa dapat engage dalam
pembelajaran yang akan dilakukan. Sutrisno (2006) menekankan
empat hal penting pada proses ini, yaitu: (1) Tujuan utama
pengajaran ini tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi
baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki
masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri, (2)
Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai
jawaban mutlak ―benar―, sebuah masalah yang rumit atau
kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali
bertentangan, (3) Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran
ini), siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari
informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap
membantu, namun siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri
atau dengan temannya, dan (4) Selama tahap analisis dan
penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka dan penuh kebebasan. Tidak ada ide yang akan
ditertawakan oleh guru atau teman sekelas. Semua siswa diberi
peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan
menyampaikan ide-ide mereka.
2. Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar
Disamping mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah,
pembelajaran PBL juga mendorong siswa/siswa belajar
berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan
- 25 -
dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk
kelompok-kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan
memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat
digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok harus heterogen,
pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif,
adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru/dosen sangat penting
memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk
menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah
membentuk kelompok belajar selanjutnya guru dan siswa
menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas
penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap
ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam
sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini
dapat menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan
tersebut.
3. Fase 3: Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi
permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda,
namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik,
yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan
penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan
eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap
ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan
melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka
betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya
adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk
menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Pada fase ini
seharusnya lebih dari sekedar membaca tentang masalah-masalah
dalam buku-buku. Guru membantu siswa untuk mengumpulkan
- 26 -
seharusnya mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berifikir
tentang massalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk
sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan
permasalahan tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya
mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis,
penjelesan, dan pemecahan. Selama pengajaran pada fase ini,
guru mendorong siswa untuk menyampikan semua ide-idenya dan
menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus mengajukan
pertanyaan yang membuat siswa berfikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta tentang kualitas
informasi yang dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut
kiranya cukup memadai untuk membangkitkan semangat
penyelidikan bagi siswa. ― Apa yang Anda butuhkan agar Anda
yakin bahwa pemecahan dengan cara Anda adalah yang terbaik?
atau ― Apa yang dapat Anda lakukan untuk menguji kelayakan pemecahanmu ? atau ―Apakah ada solusi lain yang dapat Anda
usulkan ?. Oleh karena itu, selama fase ini, guru harus
menyediakan bantuan yang dibutuhkan tanpa mengganggu
aktivitas siswa dalam kegaitan penyelidikan.
4. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan artifak (hasil karya) dan
mempamerkannya Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan
artifak (hasil karya) dan pameran. Artifak lebih dari sekedar laporan
tertulis, namun bisa suatu videotape (menunjukkan situasi masalah
dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik
dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan
sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat
dipengaruhi tingkat berfikir siswa. Langkah selanjutnya adalah
mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai
organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini
melibatkan siswa-siswa lainnya, guru-guru, orangtua, dan lainnya
- 27 -
5. Fase 5: Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan
untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses
mereka sendiri dan kete-rampilan penyelidikan dan intelektual yang
mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan
selama proses kegiatan belajarnya. Kapan mereka pertama kali
memperoleh pemahaman yang jelas tentang situasi masalah?
Kapan mereka yakin dalam pemecahan tertentu? Mengapa mereka
dapat menerima penjelasan lebih siap dibanding yang lain?
Mengapa mereka menolak beberapa penjelasan? Mengapa mereka
mengadopsi pemecahan akhir dari mereka? Apakah mereka
berubah pikiran tentang situasi masalah ketika penyelidikan
berlangsung? Apa penyebab perubahan itu? Apakah mereka akan
melakukan secara berbeda di waktu yang akan datang? Tentunya
masih banyak lagi pertanyaan yang dapat diajukan untuk
memberikan umpan balik dan menginvestigasi kelemahan dan
kekuatan PBL untuk pengajaran. PBL telah banyak diterapkan
dalam pengajaran sains. Gallagher, dkk. (1995) menyatakan bahwa
PBL dapat dan perlu termasuk untuk eksperimentasi sebagai suatu
alat untuk memecahkan masalah. Mereka menggunakan suatu
kerangka kerja yang menekankan bagaimana para siswa
merencanakan suatu eksperimen untuk menjawab sederet
pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Gallagher
berbasis pada ―what do I know ?, ―what do I need to know ?, ― what do I need to learn ?, dan ― how do I measure or describe the
result ?. Selama fase merancang eksperimen berbasis masalah,
para siswa mengembangkan suatu protokol yang mendaftar setiap
tahap dalam eksperimen itu. Dalam protokol ini, tampak ada
kecenderungan yang khas seperti standar perencanaan
laboratorium, menjadi suatu tuntunan metakognitif bagi para siswa
- 28 -
Penerapan dengan model ini cukup berhasil serta mendukung
bahwa PBL dapat mempelopori penggunaan perencanaan
laboratorium melalui metode nontradisional. Model problem based
learning telah digunakan oleh para ahli dalam pembelajaran kimia
dan turunannya, antara lain pengajaran Biokimia oleh Dods (1996),
pembelajaran kimia sintesis bahan alam kompleks oleh Cannon
dan Krow (1998), Yu Ying (2003) dalam pengajaran elektrokimia,
dan Liu Yu (2004) dalam pengajaran kimia analitik. Liu Yu (2004,
Dosen Jurusan Kimia Univ. Tianjin China) menggunakan PBL
dalam pengajaran Kimia Analitik. Menurut Liu Yu, PBL adalah suatu
pembelajaran yang didorong atau ditandai oleh adanya masalah,
bukan oleh konsep yang abstrak. Idealnya, masalah tersebut dapat
ditemukan atau diperoleh dalam kehidupan nyata, dan tidak cepat
terselesaikan tetapi dapat diselesaikan dengan mudah. Dalam
merancang kegiatan perkuliahan ini Liu Yu memerlukan waktu 40
jam kuliah dan 32 jam kerja laboratorium. Tujuan perkuliahan
adalah: (1) Meningkatkan pengertian lebih mendalam tentang
prinsip kimia analitik yang meliputi: sampling, preparasi sampel,
separasi, teknik klasik, teknik instrumentasi: spektroskopi,
kromatografi, elektrokimia, dan jaminan mutu, (2) Meningkatkan
keterampilan teknis kimia analitik dan keterampilan lain pada
umumnya, dan (3) Membantu siswa mengembangkan suatu
pengertian dan pemahaman yang lebih (mendalam) dan apresiasi
terhadap sains.
Prosedur pengembangan PBL yang dilakukan Liu Yu sebagai
berikut:
1. Problem/Masalah: orientasi permasalahan seperti diuraikan pada
bagian berikut.
2. Perkuliahan: mahaiswa dibekali prinsip-prinsip dasar metode
analitik, dan pengantar menggunakan internet dan perpustakaan
- 29 -
sudah familier dengan internet yang kedua ini tidak terlalu
bermanfaat, dan mereka boleh menghindarinya.
3. Melacak literatur: berlangsung di luar kelas, siswa menggunakan
perpustakaan dan internet untuk memperoleh sumber informasi
dalam rangka pemecahan masalah.
4. Seminar: siswa menyampaikan informasi/gagasan/ide yang telah
ditemukan, mendisikusikan masalah dan tukar gagasan.
5. Tutorial: apabila siswa mempunyai berbagai pertanyaan, mereka
dapat menanyakan kepada dosen selama sesi tutorial ini. Tutor
bertindak untuk mengobesrvasi, membimbing, dan mendukung.
Setelah siswa menemukan suatu pemecahan, selanjutnya mereka
dapat mempersiapkan untuk eksperimen.
6. Demonstrasi: sebelum siswa melaksanakan eksperimen, dosen
dapat mendemonstrasikan (dihadapan siswa) bagaimana
mengoperasikan instrumen yang akan digunakan, dan
mengenalkan aspek mana yang mendapat perhatian lebih.
7. Eksperimen: siswa memperoleh data dari eksperimen,
menginterpretasikan hasil, dan menulis laporan. Kegiatan
laboratorium menekankan keterampilan teknik dan problem solving.
Kosasih (2014: 91) menyatakan bahwa secara umum model
pembelajaran berbasis masalah dalam implementasi kurikulum 2013
tetap berkerangka pendekatan saintifik, yakni: diawali dengan
langkah-langkah pengamatan terhadap teks ataupun fenomena tertentu dan
diakhiri dengan mengomunikasikan. Langkah-langkah tersebut
kemudian diisi dengan strategi yang berlaku dalam pembelajaran
berbasis masalah. Pada bagian awal pembelajaran, sebelum
memasuki inti kegiatan pembelajaran berbasis masalah, siswa terlebih
dahulu mengobservasi suatu fenomena yang ada lingkungannya,
yang relevan pula dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan.
Kemudian, siswa mengajukan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan
- 30 -
adalah menstimulus siswa untuk bisa berpikir kritis terhadap fenomena
yang diamatinya. Hasil berpikir kritis siswa akan terlihat dari kemauan
mereka untuk mengajukan pertanyaan. Kemudia,
pertanyaan-pertanyaan ini dijadikan bahan pemecahan masalah dalam
langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah sebagaimana ditunjukkan
tabel 2.
Tabel 2. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah
Langkah-langkah Aktivitas Guru dan Siswa
Fase 1: Mengamati,
mengorientasikan siswa terhadap masalah
Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap fenomena tertentu, terkait dengan KD yang akan dikembangkannya.
Fase 2:
Menanya, memunculkan permasalahan
Guru mendorong siswa untuk merumuskan suatu masalah terkait dengan fenomena yang diamatinya. Masalah itu dirumuskan
berupa pertanyaan yang bersifat
problematis. Fase 3:
Menalar, mengumpulkan data
Guru mendorong siswa untuk mengumpukan
informasi (data) dalam rangka
menyelesaikan masalah, baik secara individu ataupun berkelompok, dengan membaca berbagai referensi, pengamatan lapangan, wawancara, dan sebagainya.
Fase 4: Mengasosiasi,
Merumuskan jawaban
Guru meminta siswa untuk melakukan analisis data dan merumuskan jawaban terkait dengan masalah yang mereka ajukan sebelumnya.
Fase 5:
Mengomunikasikan
Guru memfasilitasi siswa untuk mempresen-tasikan jawaban atas permasalahan yang mereka rumuskan sebelumnya. Guru juga membantu siswa melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap proses pemecahan
- 31 -
E. Design Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)
Kompetensi Inti : Menerapkan rangkaian elektronika dasar
Kompetensi Dasar : Mengkasifikasi penguat daya
Tujuan Pembelajaran : 1. Menjelaskan konsep dasar klasifikasi penguat
daya (penguat akhir).
2. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas A untuk penguat daya.
3. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas B untuk penguat daya push pull.
4. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas AB untuk penguat daya push pull.
5. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas C untuk penguat daya push pull.
6. Menjelaskan prinsip dasar metoda pencarian kesalahan akibat bergesernya titik kerja transistor untuk penguat daya push pull.
Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning)
Alokasi waktu : 8 JP x 45 menit (360 menit)
No. KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI
WAKTU
1. Kegiatan Awal/
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam,
memimpin do’a memulai
pembelajaran, dilanjutkan
menanya-kan keadaan siswa dan mempresensi siswa;
2. Guru mengatur kondisi kelas yang
kondusif dan mempersiapkan
materi pembelajaran;
3. Guru menyampaikan standar
kompetensi dan kompetensi
dasar, silabus serta tujuan yang
akan dicapai dari kegiatan
pembelajaran;
4. Guru menyampaikan cakupan
materi KD 2 tentang menjelaskan rangkaian amplifier daya kecil
yang akan dipelajari sesuai
dengan silabus;
5. Guru bertanya sebagai apersepsi kepada siswa untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang penguat daya.
6. Guru mempersilahkan siswa
membentuk kelompok diskusi
masing-masing kelompok terdiri
- 32 -
No. KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI
WAKTU dari 4 siswa secara heterogen.
2. Kegiatan Inti
Dengan menggunakan LCD guru
menayangkan video contoh-contoh rangkaian penguat daya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengamati dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.
Berdasarkan tayangan video guru
mempersilahkan siswa untuk diskusi kelompok merumuskan masalah terkait dengan fenomena yang diamatinya yang banyak ditemui di lingkungan sekitar
Siswa masing-masing kelompok
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait video contoh penguat daya yang telah ditayangkan.
Pertanyaan-pertanyaan dari siswa
masing-masing kelompok diinventarisir dan dirumuskan berupa pertanyaan yang bersifat problematis melalui mekanisme diskusi kelas.
Rumusan masalah problematis
yang diajukan siswa menjadi dasar yang akan dinalar dan dicarikan data untuk diselesaikan
Berbekal informasi dari sumber
belajaran teks siswa melakukan uji coba macam-macam rangkaian penguat daya kelas A, kelas AB, dan kelas C untuk mengumpulkan
- 33 -
No. KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI
WAKTU data hasil uji coba dan dasar teori dari referensi teks untuk
menyelesaikan masalah problematik berkaitan dengan rangkaian penguat daya.
Hasil praktikum dan analisis hasil
diskusi dituliskan dalam laporan teoritis dan hasil praktikum. Siswa lain memperhatikan.
membuat rangkuman dan
kesimpulan hasil pembelajaran; 2. Guru memberikan tugas individual
berupa pekerjaan rumah (PR) untuk memperkaya pemahaman peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari;
3. Guru menyampaikan rencana
pembelajaran minggu depan
sehingga siswa dapat
mempersiapkan diri.
4. Guru mengakhiri kegiatan
pembelajaran dengan do’a
bersama.
- 34 -
BAB III PENUTUP
A. Simpulan
1. Pembelajaran Berbasis Masalah (problem Based Learning)
merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta
didik untuk belajar aktif memecahkan suatu masalah melalui
tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari
pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan
sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.
2. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah bagi siswa, diantaranya:
didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah, membangun
pengetahuannya sendiri, berfokus pada masalah, aktivitas ilmiah,
terbiasa menggunakan sumber pengetahuan bervariasi, memiliki
kemampuan komunikasi ilmiah, dan peer teaching untuk mengatasi
kesulitan belajar siswa secara mandiri. Sedangkan kekurangan
pembelajaran berbasis masalah, diantaranya: lebih cocok untuk
pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah,
kesulitan dalam pembagian tugas dalam kelas dengan keragaman
siswa tinggi, kurang cocok untuk siswa sekolah dasar,
membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan kemampuan
guru untuk mendorong kerja siswa, dan sumber belajar kadang
tidak tersedia dengan lengkap.
3. Langkah-langkah pembelajaran (sintaks) model pembelajaran
berbasis masalah pada kurikulum 2013 terdiri dari lima fase, yaitu:
mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan
mengomunikasikan.
4. Desain pembelajaran mata pelajaran rumpun MIPA (sains) dengan
menerapkan model pembelajaran berbasis masalah mengikuti
secara urut lima fase, yaitu: (a) Fase 1: mengamati, yaitu