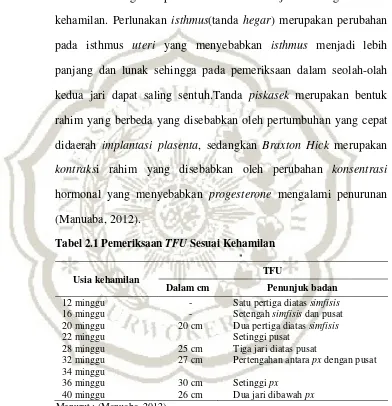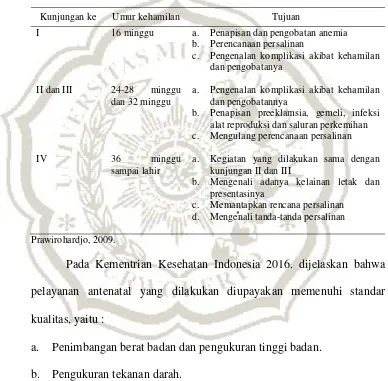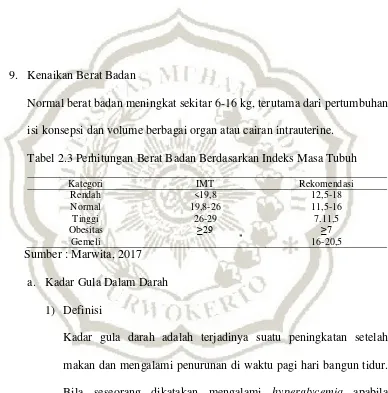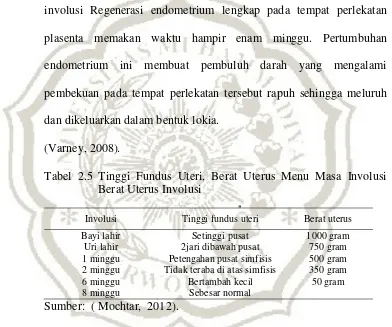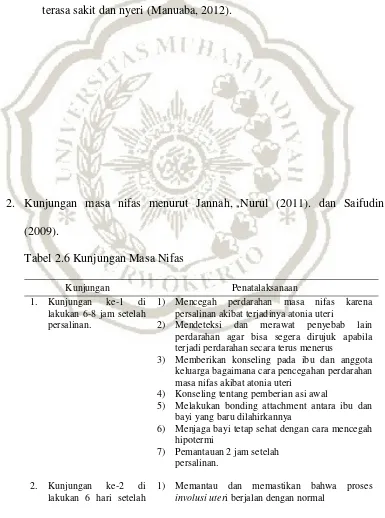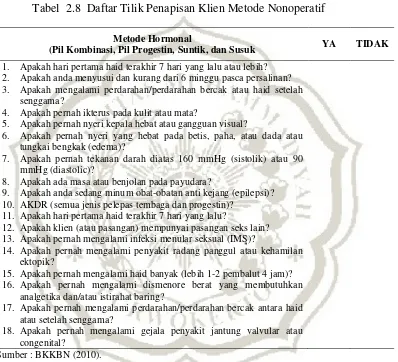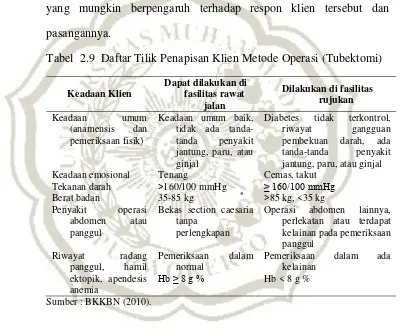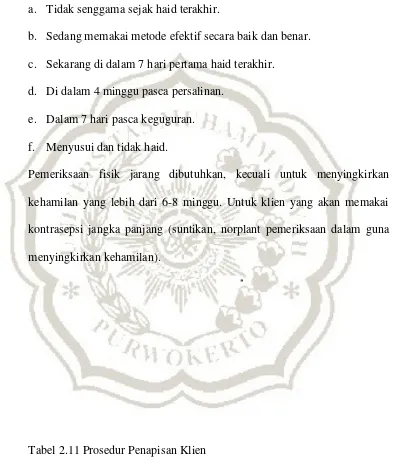BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KEHAMILAN
1. Pengertian kehamilan
Menurut Federasi Obstetri Ginekologi internasional dalam (Prawirohardjo, 2010). Kehamilan adalah suatu proses penyatuan dari
spermatozoa dan ovum yang selanjutnya akan terjadi nidasi. Menurut Mochtar, (2012). Kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40
minggu (10 bulan) dihitung dari saat hari pertama haid terakhir sampai
lahirnya bayi. Dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu proses
penyatuan sel telur dan sperma yang berlangsung 40 minggu dihitung
dari saat hari pertama haid terakhir sampai persalinan.
Kehamilan merupakan waktu transisi, yaitu suatu masa antara
kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam
kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir
(Varney, 2014).
2. Penyebab terjadinya kehamilan
Menurut Manuaba (2012). Peristiwa terjadinya kehamilan di antaranya
yaitu:
a. Ovulasi
perubahan menjadi folikel de Graaf yang menuju ke permukaan
ovum disertai pembentukan cairan folikel. Selama pertumbuhan menjadi folikel de graaf, ovarium mengeluarkan hormon estrogen
yang dapat mempengaruhi gerak dari tuba yang makin mendekati
ovarium, gerak sel rambut lumen tuba makin tinggi, sehingga
peristaltic tuba makin aktif, yang mengalir menuju uterus. Dengan pengaruh LH yang semakin besar dan fluktusi yang mendadak, terjadi proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. Ovum yang dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae, dan ovum yang ditamngkap terus berjalan mengikuti tuba menuju uterus dalam bentuk pematangan yang siap untuk dibuahi
b. Konsepsi
Merupakan pertemuan antara inti ovum dengan inti spermatozoa
yang nantinya akan membentuk zigot. c. Nidasi atau implantasi
Setelah terbentuknya zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya serta berjalan
terus menuju uterus, hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum, maka terjadilah proses penanaman blastula
d. Pembentukan plasenta
Terjadinya nidasi mendorong sel blastula mengadakan
diferensisi, sel yang dekat dengan ruangan eksoselom membentuk kantong kuning telur sedangkan sel lain membentuk ruangan
amnion, sedangkan plat embrio terbentuk diantara dua ruangan
amnion dan kantong kuning telur tersebut. Ruangan amnion dengan cepat mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat diantara
amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi talipusat.Vili korealis menghancurkan desidua sampai pembuluh darah vena mulai pada hari ke 10 sampai 11 setelah konsepsi sedangkan arteri pada hari ke 14 sampai 15. Bagian desidua yang tidak dihancurkan akan membentuk plasenta 15- 20 kotiledon maternal, pada janin plasenta
akan dibagi menjadi sekitar 200 kotiledon fetus dan setiap kotiledon fetus terus bercabang dan mengambang ditengah aliran darah yang nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi dan pertumbuhan (Manuaba, 2012).
3. Perubahan fisiologi selama kehamilan
Menurut Manuaba (2012). Dengan terjadinya kehamilan, maka
seluruh sistem genetalia wanita mengalami perubahan sedangkan
a. Uterus
Uterus yang semula beratnya 30 gram akan mengalami
hipertrofi dan hyperplasia, sehingga otot rahim menjadi lebih besar lunak dan mengikuti pembesaran rahim menjadi 1000 gram akhir
kehamilan. Perlunakan isthmus(tanda hegar) merupakan perubahan pada isthmus uteri yang menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang dan lunak sehingga pada pemeriksaan dalam seolah-olah
kedua jari dapat saling sentuh.Tanda piskasek merupakan bentuk rahim yang berbeda yang disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat
didaerah implantasi plasenta, sedangkan Braxton Hick merupakan
kontraksi rahim yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi
hormonal yang menyebabkan progesterone mengalami penurunan (Manuaba, 2012).
Tabel 2.1 Pemeriksaan TFU Sesuai Kehamilan
Usia kehamilan TFU
Dalam cm Penunjuk badan 12 minggu - Satu pertiga diatas simfisis 16 minggu - Setengah simfisis dan pusat 20 minggu 20 cm Dua pertiga diatas simfisis
22 minggu Setinggi pusat
28 minggu 25 cm Tiga jari diatas pusat
32 minggu 27 cm Pertengahan antara px dengan pusat 34 minggu
36 minggu 30 cm Setinggi px
40 minggu 26 cm Dua jari dibawah px Menurut : (Manuaba, 2012).
b. Vagina
c. Ovarium (indung telur)
Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung
korpus luteum gravidarumakan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur kehamilan 16 minggu (Manuaba, 2012).
d. Payudara
Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai
persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Hormone yang mempengaruhi dalam laktasi yaitu hormone estrogen, progesterone, somatomammotropin (Manuaba, 2012).
e. Sirkulasi darah ibu
Peredarahan darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim.
1) Terjadinya hubungan langsung antara arteri dan vena pada
sirkulasiretro-plasenter
2) Pengaruh hormone estrogen dan progesterone makin meningkat (Manuaba, 2012).
4. Perubahan psikologis dalam kehamilan
a. Trimester I
Sering disebut masa penentuan bahwa dia hamil.Pada kehamilan
trimester pertama segera setelah konsepsi, kadarhormon progesteron
dan estrogen dalam tubuh akan meningkat. Ini menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah dan
membesarnya payudara. Ibu merasa tidak sehat dan seringkali
membenci kehamilannya. Banyak ibu yang merasakan kekecewaan,
penolakan, kecemasan dan kesedihan. Seringkali, pada awalmasa
kehamilan ibu berharap untuk tidak hamil.
b. Trimester II
Trimester kedua biasanya ibu sudah merasa sehat dan sering
disebut dengan periode pancaran kesehatan. Tubuh ibu telah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Ibu telah menerima kehamilannya
dan mulai dapat menggunakan energi serta pikirannya secara lebih
konstruktif. Pada trimester ini pula ibu mampu merasakan gerakan janinnya. Banyak ibu yang merasa terlepas dari kecemasan dan rasa
tidak nyaman, seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan
merasakan naiknya libido. c. Trimester III
Trimester ketiga seringkalidisebut periode penantian untuk kelahiran bagi bayi dan kebahagiaan dalam menanti seperti apa rupa
sabar menunggu kelahiran bayinya. Kadang ibu merasa khawatir bila
bayinya lahir sewaktu-waktu. Ibu sering merasa khawatir
kalau-kalau bayinya lahir tidak normal. Kebanyakan ibu juga akan
bersikap melindungi bayinya dan cenderung menghindari orang atau
benda apa saja yang dianggapnya membahayakan bayi.
Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada
trimester ketiga dan banyak ibu merasakan aneh atau jelek. Di
samping itu ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari
bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima semasa
hamil.
5. Tanda gejala kehamilan
a. Menurut Manuaba (2013). tanda mungkin hamil adalah:
1) Amenore
2) Mual dipagi hari
3) Mengidam
4) Sering buang air kecil
5) Pingsan
6) Mammae menjadi tegang dan membesar 7) Anoreksia
8) Konstipasi dan Obstipasi
9) Pigmentasi kulit 10) Epulis
12) Pembesaran perut
13) Tanda Hegar
14) Tanda Goodel
15) Tanda Chadwicks
16) Kontraksi braxton hicks
17) Teraba ballotement
18) Pemeriksaan tes biologis kehamilan b. Tanda pasti hamil
Menurut Mochtar (2012). tanda pasti hamil adalah
1) Gerakan janin
Gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasakan atau diraba,
juga bagian-bagian janin.
2) Denyut jantung janin
DJJ dapat di dengar dengan stetoskop-monoaural Laennec,
dicatat dan di dengar dengan alat dopler, di catat dengan
foto-elektrokardiogram. Dilihat pada USG.
3) Bagian-bagian janin
Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen.
6. Pemeriksaan Antenatal Care
ANC adalah upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetric
untuk optimilisasi luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian
kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan (Prawirohardjo, 2014).
a. Tujuan umum adalah menyampaikan seoptimal mungkin fisik dan
mental ibu dan anak selama dalam masa kehamilan, persalinan,
dengan demikian didapatkan ibu dan anak yang sehat.
b. Tujuan khusus
1) Mengenali dan menangani penylit-penyulit yang mungkin
dijumpai dalam kehamilan, persalinan, dan nifas.
2) Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin
diderita sedini mungkin
3) Menuurunkan angka mobiditas dan mortalitas ibu dan anak dan
4) Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan
keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi.
Bila kehamilan termasuk risiko tinggi perhatian dan jadwal
kunjungan harus lebih ketat. dan bila kehamilan normal jadwal asuhan
cukup 4 kali. Dalam bahasa program kesehatan ibu dan anak, kunjungan
antenatal di beri kode K yang merupakan singkatan dari kunjungan.
Pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah K1, K2, K3, K4. Hal ini
berarti, minimal dilakukan sekali saat kunjungan antenatal hingg usia
kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan
28-36 minggu dan sebanyak dua kali kunjungan antenatal pada usia
Tabel 2.2 Kunjungan Antenatal Care
Kunjungan ke Umur kehamilan Tujuan
I 16 minggu a. Penapisan dan pengobatan anemia b. Perencanaan persalinan
c. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatanya
II dan III 24-28 minggu dan 32 minggu
a. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya
b. Penapisan preeklamsia, gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan c. Mengulang perencanaan persalinan
IV 36 minggu
sampai lahir
a. Kegiatan yang dilakukan sama dengan kunjungan II dan III
b. Mengenali adanya kelainan letak dan presentasinya
c. Memantapkan rencana persalinan d. Mengenali tanda-tanda persalinan Prawirohardjo, 2009.
Pada Kementrian Kesehatan Indonesia 2016. dijelaskan bahwa
pelayanan antenatal yang dilakukan diupayakan memenuhi standar
kualitas, yaitu :
a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
b. Pengukuran tekanan darah.
c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus
f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan
konseling, termasuk keluarga berencana).
i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin
darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan
darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
j. Tatalaksana kasus. (Kementrian Kesehatan Indonesia 2016).
7. Komplikasi
Komplikasi Kehamilan (Mochtar, 2012).
a. Hiperemesis Gravidarum
Adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil
sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya
menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi.
Tanda dan tingkat
1) Tingkat I ringan yait mual muntah terus menurus menyebabkan
lemah, tidak mau makan, berat badan turun, dan rasa nyeri
epigastrium, nadi cepat, tekanan darah turun, turgor kulit
kurang, lidah kering dan mata cekung.
2) Tingkat II sedang yaitu mual dan muntah yang hebat
menyebabkan keadaan umum penderita lemah sama seperti
konstipasi. Daat pula terjadi asetonuria, dan dari nafas keluar
bau aseton
3) Tingkat III berat yaitu keadaan umum jelek, keadaan umum
samnolen sampai koma.
b. Toksemia gravidarum
Digunakan untuk kumpulan gejala-gejala dalam kehamilan yang
merupakan trias HPE (hipertensi, proeinuria, dan edema)
Klasifikasi :
1) Pre eklamsi
a) Ringan jika disertai tekanan darah 140/90 mmHg diikuti
protein urin +1
b) Berat jika tekanan darah 160/110 mmHg dan diikuti protein
urin lebih dari +2
2) Hipertensi esensial
a) Tanpa ada komplikasi
b) Superimposed pre-eklampsia
3) Eklamsi kelanjutan dari preeklamsi berat yang mengakibatkan
pasien kejang
c. Abortus (keguguran) adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum
janin dapat hidup diluar kandungan. Umur kehamilan kurang dari 28
minggu.
1) Abortus immines yaitu keguguran belum terjadi sehingga masih
2) Abortus insipiens adalah proses keguguran yang sedang
berlangsung
3) Abortus inkompletus (keguguran bersisa)
4) Abortus kompletus (keguguran lengkap)
5) Missed abortion (janin yang telah mati didalamnya)
d. Kelainan letak kehamilan (kehamilan ektopik)
Kehamilan dengan hasil konsepsi berimplantasi diluar endometrium
rahim.
e. Ketuban pecah dini
Adalah pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan
pada primi kurang dari 3 cm dan multi kurang dari 5cm.
f. Perdarahan antepartum
Adalah perdarahan yang terjadi setelah kehamilan 28 minggu
g. Kehamilan dengan Anemia, Hamil lewat bulan, dan resiko dengan
usia ibu pada kehamilan
1) Anemia pada kehamilan
Anmia pada kehamlan aalah anemia karena kekurangan
zat besi, dan merupakan jenis anemia yang pengobatannya
relatif mudah, bahkan murah. Menurut WHO, kejadian anemia
kehamilan berkisar antara 20 dan 89% dengan menentukan Hb
11g%(g/dl) sebagai dasarnya. Pemeriksaan dan pengawasan Hb
dapat dilakukan dengan menggunakan alat Sahli. Hasil pemeriksaan Hb dengan Sahli dapat digolongkan sebagai
Hb 11g% Tidak anemia
Hb 9-10g% Anemia ringan
Hb 7-8g% Anemia sedang
Hb<7g% Anemia berat
2) Kehamilan lewat bulan
Beragam istilah digunakan untuk menggambarkan
kehamilan yang berlangsung melebihi 42 minggu, antara lain
kehamilan memanjang, kehamilan lewat bulan, kehamilan
postterem. Definisi standar untuk kehamilan lewat bulan adalah
294 hari setelah haid terakhir, atau 280 hari setelah ovulasi.
Kriteria untuk mendiagnosis kehamilan lewat bulan
dipenuhi apabila tidak terjadi dalam 2 minggu setelah tanggal
persalinan yang ditetapkan, beberapa ahli menyatakan bahwa
kehamilan dapat dia anggap memanjang pada usia 41 minggu
karena angka morbiditas dan mortalitas neonatus meningkat
setelah usia kehamilan 40 minggu hingga 41 minggu (Varney,
2007).
h. Ketuban Pecah Dini (KPD)
Ketuban pecah dini atau spontaneous/early/premature rupture of
the membrane (PROM) adalah pecahnya ketuban sebelum in partu;
multipara kurang dari 5 cm.
Bila periode laten terlalu panjang dan ketuban sudah pecah,
maka dapat terjadi infeksi yang dapat meningkatkan angka kematian
ibu dan anak. Untunglah karena adanya antibiotika spectrum luas
maka hal ini dapat ditekan.
Sampai saat ini masih banyak pertentangan mengenai
penatalaksanaan PROM yang bervariasi dari “doing nothing” sampai
pada tindakan yang berlebih-lebihan.
Menurut EASTMAN insidens PROM ini kira-kira 12% dari
semua kehamilan.
1) Etiologi
Penyebab dari PROM tidak atau masih belum jelas, maka
preventif tidak dapat di lakukan, kecuali dalam usaha menekan
infeksi.
2) Patogenesis
TAYLOR dkk. (Mochtar, 2012). Telah menyelidiki hal
ini, ternyata ada hubunganya dengan hal-hal berikut :
a) Adanya hipermotilitas rahim yang sudah lama terjadi
sebelum ketuban pecah. Penyakit-penyakit seperti
pielonefritis, sistitis, sefisitis, dan vaginitis terdapat
bersama-sama dengan hipermotilitas rahim ini.
c) Infeksi (Amnionitis atau korioamnionitis ).
d) Faktor-faktor lain yang merupakan predisposisi ialah
multipara, malposisi, disproporsi, cervix incompeten dan lain-lain.
e) Ketuban pecah dini artivisial (Amniotomi) di mana ketuban
di pecahkan terlalu dini.
Kadang-kadang agak sulit atau meragukan kita apakah
ketuban benar sudah pecah atau belum, apalagi bila pembukaan
kanalis servikalis belum ada atau kecil.
Cara menentukanya adalah dengan :
a) Memeriksa adanya cairan yang berisi meconium, vernik
kaseosa, rambut lanugo, atau bila telah infeksi berbau.
b) Inspekulo : lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban
c) keluar dari kanalis servisis dan apakah ada bagian yang
sudah pecah (Mochtar, 2012).
Gunakan kertas lakmus (litmus) :
a) Bila menjadi biru (basa) = air ketuban.
b) Bila menjadi merah = air kemih (urin).
c) Pemeriksaan pH forniks posterior pada PROM pH adalah
basa (air ketuban).
d) Pemeriksaan histo patologi air (ketuban).
Jarak antara pecahnya ketuban dan permulaan dari persalinan di
sebut periode laten = LP= lag period. Makin muda umur kehamilan makin memanjang LP-nya. Sedangkan lamanya persalinan lebih
pendek dari biasa, yaitu pada primi 10 jam dan multi 6 jam (
Mochtar, 2012).
Pengaruh PROM
1) Terhadap janin
Walaupun ibu belum menunjukan gejala-gejala infeksi
tetapi janin mungkin sudah terkena infeksi, karena infeksi intra
uterin lebih dahulu terjadi (Amnionitis, Vaskulitis) sebelum
gejala pada ibu di rasakan. Jadi akan meninggikan mortalitas
dan morbiditas perinatal.
2) Terhadap ibu
Karena jalan telah terbuka, maka dapat terjadi infeksi
intrapartal, apalagi bila terlalu sering di periksa dalam. Selain itu
juga dapat di jumpai infeksi puerpuralis (nifas), peritonitis, dan septikemia, serta dry-labor.
Ibu akan merasa kelelahan karena terbaring di tempat
tidur, partus akan menjadi lama maka suhu badan naik, nadi
cepat dan nampaklah gejala-gejala infeksi.
Hal-hal di atas akan meninggikan angka kematian dan
3) Prognosis
Ditentukan oleh cara penatalaksanaan dan
komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul serta umur dari kehamilan.
4) Pimpinan persalinan
Ada bermacam-macam pendapat mengenai
penatalaksanaan dan pimpinan persalinan dalam menghadapi
PROM. Beberapa institute menganjurkan penatalaksanaan untuk
PROM kira-kira sebagai berikut:
a) Bila anak belum viable ( kurang dari 36 minggu), penderita
di anjurkan untuk beristirahat di tempat tidur dan berikan
obat-obat antibiotika profilaksis, spasmolitika, dan
roboransia dengan tujuan untuk mengundur waktu sampai
anak viable (Mochtar, 2012).
b) Bila anak sudah viable (lebih dari 36 minggu), lakukan
induksi partus 6-12 jam setelah lagphase dan berikan antibiotika profilaksis. Pada kasus-kasus tertentu di mana
induksi partus dengan PGE2 dan atau drips sintosinon gagal, maka lakukanlah tindakan operatif (Mochtar, 2012).
Jadi pada PROM penyelesaian persalinan bisa :
(1) Partus spontan
(2) Ekstraksi vakum
(3) Ekstraksi vorcep
(4) Embriotomi bila anak sudah meninggal
(5) Seksio sesaria bila ada indikasi obstetric
1) Pada anak : IUFD dan IPFD, Asfiksia, dan Prematuritas.
2) Pada ibu : Partus lama dan infeksi, atonia uteri, perdarahan
postpartum, atau infeksi nifas (Mochtar, 2012).
8. Diabetes Mellitus Gestasional
a. Pengertian
Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) didefinisikan sebagai gangguan
toleransi glukosa berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat
hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapat insulin
atau tidak. Pada kehamilan trimester pertama kadar glukosa akan turun
antara 55-65% dan hal ini merupakan respon terhadap transportasi
glukosa dari ibu ke janin. Sebagian besar DMG asimtomatis sehingga
diagnosis ditentukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan rutin. Di
Indonesia insiden DMG sekitar 1,9-3,6% dan sekitar 40-60% wanita
yang pernah mengalami DMG pada pengamatan lanjut pasca
persalinan akan mengidap diabetes mellitus atau gangguan toleransi
glukosa (Manuaba, 2007).
b. Patofisiologi
Pada DMG, selain perubahan-perubahan fisiologi tersebut akan terjadi
suatu keadaan di mana jumlah/fungsi insulin menjadi tidak optimal.
Terjadi perubahan kinetika insulin dan resistensi terhadap efek insulin.
Akibatnya, komposisi sumber energi dalam plasma ibu bertambah
(kadar gula darah tinggi, kadar insulin tetap tinggi).
Melalui difusi terfasilitasi dalam membran plasenta, dimana sirkulasi
janin juga ikut terjadi komposisi sumber energi abnormal.
(menyebabkan kemungkinan terjadi berbagai komplikasi). Selain itu
metabolik (hipoglikemia, hipomagnesemia, hipokalsemia,
hiperbilirubinemia, dan sebagainya). Pemeriksaan penyaring dapat
dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah sewaktu dan 2 jam post
prandial. Bila hasilnya belum dapat memastikan diagnosis DM, dapat
diikuti dengan test toleransi glukosa oral. DM ditegakkan apabila
kadar glukosa darah sewaktu melebihi 200 mg%. Jika didapatkan nilai
di bawah 100 mg% berarti bukan DM dan bila nilainya diantara
100-200 mg% belum pasti DM (Wordpres, 100-2008).
c. Klasifikasi
1) Klasifikasi Diabetes Mellitus secara Umum
a) Tipe I: Diabetes Mellitus tergantung insulin (Insulin
Dependen Diabetes Mellitus : IDDM).
b) Tipe II: Diabetes Mellitus tidak tergantung insulin (Non
Insulin Dependen Diabetes Mellitus: NIDDM).
c) Diabetes Mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau
sindrom lainnya.
d) Diabetes mellitus Gestasional (DMG).
2) Klasifikasi dibuat berdasarkan umur, waktu penyakit timbul,
lamanya sakit, berat penyakit dan komplikasi :
a) Kelas A : diabetes laten (subklinis atau diabetes hamil). Uji
toleransi gula tidak normal. Pengobatan tidak memerlukan
insulin, cukup dengan diet saja. Prognosis ibu dan janin baik,
b) Kelas B : diabetes dewasa diketahui setelah usia 19 tahun,
pembuluh darah.
c) Kelas C : timbul pada umur 10-19 tahun, berlangsung selama
10-19 tahun, tanpa kelainan pembuluh darah.
d) Kelas D : diderita sejak umur 10 tahun, lama 20 tahun,
disertai kelainan pembuluh darah serta arterioskleriosis pada
retina, tungkai dan renitis.
e) Kelas E : telah terjadi klasifikasi pembuluh darah
f) Kelas F : diabetes dengan nefropasia termasuk adanya
gromeluronefritis dan pielonefritis. Diabetes anak remaja
(juvenilis) merupakan diabetes yang diderita sejak
anak-anak/remaja. Karena sedikit atau tidak ada insulin endogen,
cenderung timbul keto asidosis (Nugraheny, 2010).
d. Etiologi
1) Diabetes tipe I
Menurut Brunner dan Suddart ada beberapa faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya dabetes tipe I :
a) Faktor genetik
Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe I itu sendiri;
tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik
ke arah terjadinya diabetes tipe I.
b) Faktor imunologi
Pada diabetes tipe I terdapat adanya respon otoimun abnormal
cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya
seolah-olah sebagai jaringan asing.
c) Faktor lingkungan
Penyelidikan sedang dilakukan terhadap kemungkinan
faktor-faktor eksternal yang dapat memicu destruksi sel beta.
2) Diabetes tipe II
Menurut Brunner dan Suddarth, mekanisme yang tepat yang
menyebabkan belum diketahui. Namun, ada beberapa resiko yang
berhubungan dengan terjadinya DM type II, antara lain:
a) Faktor genetik.
b) Usia.
c) Obesitas.
d) Riwayat keluarga.
e) Kelompok etnik.
e. Diagnosis
Diagnosis diabetes mellitus pada ibu hamil agak sukar karena terdapat
beberapa faktor yang meningkatkan dan menurunkan konsentrasi
glukosa pada ibu hamil. Bila pada trimester pertama terdapat penyulit
emesis gravidarum, mungkin saja terjadi penurunan konsentrasi gula
darah. Hal ini disebabkan oleh nutrisi ibu hamil kurang akibat tidak
dapat makan dan minum dengan baik. Setelah masa emesis gravidarum
dipastikan karena terdapat faktor hormonal yang meningkatkan dan
menurunkan glukosa pada saat bersamaan akibat dipergunakan untuk
tumbuh kembang janin.
f. Dugaan ibu hamil dengan diabetes mellitus :
1) Riwayat keluarga
2) Sering mengalami abortus tanpa sebab yang jelas
3) Persalinan sulit dengan janin besar (makrosomia)
4) Kematian janin intra uteri
5) Intrautery growth retardasion
6) Prematuritas
7) Terdapat kelainan kongenital janin (Manuaba, 2007).
g. Pengaruh Diabetes pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi :
1) Kehamilan
a) Hiperemesis gravidarum dapat mengubah metabolismus
hidrat-arang
b) Pemakaian glikogen bertambah karena myometrium dan
jaringan-jaringan lain bertambah
c) Janin yang bertumbuh memerlukan makin lama makin banyak
bahan makanan, termasuk hidrat-arang
d) Adanya pankreas dan adrenal janin yang sudah berfungsi in
utero
e) Meningkatnya metabolisme basal dengan pertukaran zat yang
cadangan
f) Sebagian insulin ibu dimusnahkan oleh enzim insulinase
dalam plasenta
g) Khasiat insulin dalam kehamilan dikurangi oleh plasenta
laktogen, dan mungkin juga oleh estrogen dan progesterone.
2) Persalinan
Kegiatan otot Rahim dan usaha meneran mengakibatkan
pemakaian glukosa lebih banyak, sehingga dapat terjadi
hipoglikemia, apalagi jikalau wanita muntah-muntah.
3) Pengaruh Nifas
Laktasi menyebabkan keluarnya zat-zat makanan, termasuk
hidrat-arang dari tubuh ibu.
h. Komplikasi yang timbul akibat diabetes pada kehamilan, persalinan,
nifas :
1) Kehamilan
a) Abortus dan partus prematurus
b) Pre-eklampsia
c) Hidramnion
d) Kelainan letak janin
e) Insufisiensi plasenta
2) Persalinan
b) Distosia bahu karena bayi besar
c) Kelahiran mati
d) Lebih sering pengakhiran partus dengan tindakan, termasuk
seksio cesaria
e) Lebih mudah terjadi infeksi
f) Angka kematian maternal lebih tinggi
3) Nifas
Diabetes lebih sering mengakibatkan infeksi nifas dan sepsis, dan
menghambat penyembuhan luka jalan lahir, baik rupture perinei
maupun luka episiotomy (Saifuddin, 2005).
i. Penanganan
1) Pengobatan medik dan bekerjasama dengan ahli penyakit dalam
a) Diabetes diet
Penderita diabetes dengan berat badan rata-rata cukup diberi
diet yang mengandung 1200-1800 kalori sehat selama
berlangsungnya kehamilan. Pemeriksaan darah dan urin
berkala dilakukan untuk mengubah dietnya apabila perlu.
Dalam triwulan I diet dan pengobatan tidak banyak berbeda
denagan keadaan di luar kehamilan. White menganjurkan
30-40 kalori per Kg berat badan. Garam perlu dibatasi untuk
mengurangi kecenderungan akan retensi air dan edema. Diet
yang dianjurkan ialah karbohidrat 40 %, protein 2 g/Kg berat
Dalam triwulan II metabolisme hidrat-arang dalam tubuh itu
berubah, ibu memerlukan lebih banyak bahan makanan,
terutama kalori dan protein. Penderita yang di luar kehamilan
dan dalam kehamilan triwulan I tidak memerlukan insulin,
mungkin sekali perlu diobati dengan insulin dalam triwulan II
dan III. Karena itu, gula darah harus diperiksa ulang. Diet dan
dosis insulin setiap kali harus disesuaikan dengan keperluan
yang berubah-ubah itu, lebih-lebih dalam triwulan III. Juga
dalam masa nifas dan laktasi pemeriksaan perlu diulang dan
diet disesuaikan.
b) Pengobatan Insulin
Pada penderita diabetes dalam kehamilan daya tahan terhadap
insulin meningkat dengan makin tuanya kehamilan, yang
dibebaskan oleh kegiatan antiinsulin plasenta.
Penderita yang sebelum kehamilan sudah memerlukan insulin
diberi insulin dalam dosis yang sama dengan dosis di luar
kehamilan sampai terdapat tanda-tanda bahwa dosis perlu
ditambah atau dikurangi. Perubahan-perubahan dalam
kehamilan disatu pihak memudahkan terjadinya hiperglikemik.
Karena itu, dosis insulin perlu diubah menurut keperluan.
Perubahan-perubahan dosis itu harus dilakukan dengan
hati-hati, dengan berpedoman pada 140 mg/dl pemeriksaan gula
Terutama dalam triwulan I mudah terjadi hipoglikemia apabila
dosis insulin tidak dikurangi karena wanita kurang makan
akibat emesis dan hyperemesis gravidarum. Sebaliknya, dosis
insulin perlu ditambah dalam triwulan II apabila wanita sudah
mulai suka makan, lebih-lebih dalam triwulan III.
Selama berlangsungnya persalinan dan dalam hari-hari
berikutnya cadangan hidrat-arang berkurang dan keperluan
akan insulin berkurang pula. Akibatnya ialah bahwa penderita
mudah mengalami hipoglikemia apabila diet tidak disesuaikan
dan/atau dosis insulin tidak dikurangi. Pemberian insulin yang
kurang hati-hati dapat merupakan bahaya besar karena reaksi
hipoglikemik dapat disalahtafsirkan sebagai koma diabetikum.
Dosis insulin perlu dikurangi selama wanita dalam persalinan
dan nifas dini. Dianjurkan pula supaya dalam masa persalinan
diberi infus glukosa dan insulin. Pada hiperglikemia berat dan
keto-asidosis diberi insulin secara infus intravena dengan
kecepatan 2-4 satuan per jam untuk mengatasi komplikasi yang
berbahaya ini (Saifuddin, 2005).
2) Penanganan Obstetrik
a) Penanganan berdasarkan pertimbangan beratnya penyakit, lama
penderita, umur, paritas, riwayat persalinan terdahulu dan ada
tidaknya komplikasi.
c) Bila agak berat memerlukan insulin, induksi persalinan lebih
dini 36-38 minggu
d) Diabetes agak berat riwayat IUFD lakukan SC pada 37 minggu
e) Diabetes berat dengan komplikasi (preeklamsi, hidramnion,
dll), riwayat persalinan yang lalu buruk, induksi persalinan/SC
lebih dini
f) Dalam pengawasan persalinan monitor janin dengan baik (DJJ,
EKG, USG)
g) Untuk kehamilan yg mengancam ibu dan janin sarankan
tubektomi
(Nugraheny, 2010).
3) Penanganan Neonatus
Penanggulangan neonatus, baik yang prematur maupun yang
matur, dari seorang penderita diabetes sangat penting dan
kadang-kadang menentukan bagi prognosis anak. Walaupun bayi besar dan
tampaknya sehat pada permulaan, namun ia tidak bebas dari
bahaya yang setiap saat berikutnya dapat mengancam jiwanya.
Sebaiknya bayi segera dipindah ke unit perawatan intensif
(intensive care) neonatal jikalau ada. Setiap neonatus harus
dianggap dan diperlakukan sebagai bayi prematur tanpa
memandang umur kehamilannya dan berat badannya, karena
hipoglikemia pada bayi sering dijumpai dan dapat bertahan lama,
kehamilan belum mencapai 38 minggu. Pengobatan hipoglikemia
secara aktif sangat penting untuk mencegah kemungkinan kelainan
neurologik akibat hipoglikemia berat yang berlangsung lama
(Saifuddin, 2005).
9. Kenaikan Berat Badan
Normal berat badan meningkat sekitar 6-16 kg, terutama dari pertumbuhan
isi konsepsi dan volume berbagai organ atau cairan intrauterine.
Tabel 2.3 Perhitungan Berat Badan Berdasarkan Indeks Masa Tubuh
Kategori IMT Rekomendasi
Rendah
a. Kadar Gula Dalam Darah
1) Definisi
Kadar gula darah adalah terjadinya suatu peningkatan setelah
makan dan mengalami penurunan di waktu pagi hari bangun tidur.
Bila seseorang dikatakan mengalami hyperglycemia apabila keadaan kadar gula dalam darah jauh diatas nilai normal,
sedangkan hypoglycemia suatu keadaan kondisi dimana seseorang mengalami penurunan nilai gula dalam darah dibawah normal
(Rudi, 2013). Kadar gula darah merupakan peningkatan glukosa
glukosa serum diatur secara ketat di dalam tubuh. Glukosa
dialirkan melalui darah merupakan sumber utama energi untuk
sel-sel tubuh.
2) Macam-macam Pemeriksaan Gula Darah
Menurut Depkes (2008). ada macam-macam pemeriksaan gula
darah, yaitu :
a) Gula darah sewaktu
Suatu pemeriksaan gula darah yang dilakukan setiap waktu
tanpa tidak harus memperhatikan makanan terakhir yang
dimakan.
b) Gula darah puasa dan 2 jam setelah makan
Suatu pemeriksaan gula darah yang dilakukan pasien sesudah
berpuasa selama 8 – 10 jam, sedangkan pemeriksaan gula darah
2 jam sesudah makan yaitu pemeriksaan yang dilakukan 2 jam
dihitung sesudah pasien menyelesaikan makan.
3) Nilai Normal Kadar Gula Darah
Nilai untuk kadar gula darah dalam darah bisa dihitung dengan
beberapa cara dan kriteria yang berbeda. Berikut ini tabel untuk
penggolongan kadar glukosa dalam darah sebagai patokan
penyaring (lihat tabel 2.1)
Tabel 2.4 Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring dan diagnosa DM (mg/dl)
Bukan DM
Belum
Kadar
Sedangkan menurut Rudi (2013). Hasil pemeriksaan kadar gula
darah dikatakan normal bila :
a) Gula darah sewaktu : < 110 mg/dL
1. Pengertian Persalinan
Menurut Manuaba (2010). persalinan adalah proses pengeluaran
hasil konsepsi yang telah cukup bulan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Persalianan
Persalinan adalah rangkaian yang berakhir dengan pengeluaran
hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi
persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks,
dan di akhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2008).
2. Tanda –tanda persalinan
a. Tanda-tanda permulaan persalinan yaitu:
Menurut Mochtar (2012). Tanda tanda permulaan persalinan
yaitu:
1) Lightening atau settling atau dropping yaitu kepala turun memasukipintu atas panggul
2) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun.
3) Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karna kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin.
4) Perasaan nyeri diperut dan di pinggang oleh adanya
kontraksi-kontraksi lemah uterus, kadang-kadang disebut “false labor pains”.
5) Serviks menjadi lembek, mulai mendatar,sekresinya betambah dankadang bercampur darah (bloody show)
b. Tanda-tanda inpartu
1) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan
teratur.
2) Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karna
robekan-robekan kecil pada serviks.
4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada pembukaan (Mochtar, 2012).
3. Mekanisme persalinan
Menuurut Holmes, D & Baker (2011). terdapat tiga faktor penting
dalam persalinan yaitu:Kekuatan-kekuatan yang ada pada ibu seperti
kekuatan his dan kekuatan mengejan, keadaan jalan lahir, dan faktor
janin. Sedangkan mekanisme persalinan dimulai dari masuknya kepala
melintasi pintu atas panggul dalam keadaan sinklintismus, ialah apabila
bagian terluas dari bagian presentasi janin berhasil masuk ke pintu atas
panggul, jika kepala janin masih dapat dipalpasi lebih dari dua perlimaan
diabdomen maka belum terjadinya engagement.selama kala satu
persalinan, kontraksi dan reaksi otot uterus memberikan tekanan pada
janin untuk turun, proses ini dipercepat dengan pecahnya ketuban dan
upaya ibu untuk mengejan sehingga menyebabkan kepala mengadakan
fleksi di dalam rongga panggul.
Kepala yang sedang turun menemui diafragma pelvis yang berjalan
dari belakang atas kebawah depan. Akibat kombinasi elastisitas
diafragma pelvis dan tekanan intra uterin disebabkan oleh his yang
berulang-ulang, maka kepala mengadakan rotasi yang disebut putaran
paksi dalamdengan suboksiput sebagai hipomoklion, kepala mengadakan
gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada setiap his vulva lebih
lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his
bersama dengan kekuatan mengejan, berturut-turut tampak bregma, dahi,
muka, dan akhirnya dagu terlahir. Setelah kepala lahir maka kepala
melakukan rotasi yang disebut putaran paksi luar untuk
menyesuaikankedudukan kepala dan punggung bayi (Prawirohardjo,
2010).
4. Tahapan persalinan
Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu:
a. Kala I (kala pembukaan)
Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah (bloody show) karena serviks mulai membuka
(dilatasi) dan mendatar (effacement). Kala 1 di bagi atas 2 fase, yaitu:
1) Fase laten: pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm. Lamanya 7-8 jam.
2) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase:
a) Periode askselerasi: berlangsung jam, pembukaan menjadi 4 cm.
b) Periode dilatasi maksimal (steady): selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
pembukaan menjadi 10 cm (Mochtar, 2012).
Rencana asuhan persalinan pada kala I satu: menurut (Sondakh ,
2013). ada beberapa rencana tindakan dalam asuhan kala 1 dapat
dilihat pada penjelasan di bawah ini.
1) Mempersiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran bayi
2) Persiapan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang
diperlukan
3) Persiapan rujukan
4) Memberikan asuhan sayang ibu
5) Pengurangan rasa sakit
Menurut Varney, pendekatan untuk mengurangi rasa sakit
dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a) Menghadirkan seseorang yang dapat memberikan dukungan
selama persalinan (suami, orang tua)
b) Pengaturan posisi, duduk atau setengah duduk, merangkak,
berjongkok, berdiri, atau berbaring miring ke kiri
c) Relaksasi pernafasan
d) Istirahat dan privasi
e) Penjelasan mengenai proses atau kemajuan persalinan atau
prosedur yang akan di lakukan
f) Asuhan diri
g) Sentuhan
(2) Mengatur posisi
(3) Pemberian cairan dan nutrisi
(4) Kebutuhan psikologis
(5) Kamar mandi
(6) Mengkosongkan kandung kemih
h) Pencegahan infeksi
i) Persiapan persalinan
b. Kala II (kala pengeluaran janin)
Kepala janin telah turun dan masuk ruang panggul sehingga
terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang melalui
lengkung refleks menimbulkan rasa mengedan. Karena tekanan pada
rektum, membuat ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka, vulva membuka dan perinium meregang.
Dengan his dan mengedan yang terpimpin, akan lahir kepala, diikuti
oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi berlangsung selama 1
½- 2 jam, pada multi ½ - 1 jam (Mochtar, 2012).
Menurut (Varney, 2007). penjadwalan pengecekan tanda-tanda
vital berikut menunjukan frekuensi normal yang dapat diterima
untuk seorang wanita normal selama fase aktif kala satu persalinan
tanpa memerhatihan lingkungan :
1) Tekanan darah; setiap jam
a) Setiap 2 jam ( atau setiap 4 jam) jika temperature normal
dan ketuban keruh.
b) Setiap jam ( atau setiap 2 jam ) setelah ketuban pecah)
c. Kala III (Kala pengeluaran Uri)
Kala III berlangsung mulai dari bayi lahir sampai plasenta
lahir lengkap. Biasanya, plasenta akan lahir dalam 15-30 menit
(Mochtar, 2012).
Rencana asuhan persalinan kala III
1) Perubahan fisiologis pada kala III
2) Perubahan bentuk dan tinggi fundus
Menurut (Sondakh, 2013). setelah bayi lahir dan sebelum
miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh,
dan tinggi fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah
uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah. Uterus
berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat, dan fundus berada
di atas pusat (sering kali mengarah ke sisi kanan)
3) Tali pusat memanjang
4) Semburan darah mendadak dan singkat
Manajemen aktif kala III
Tujuan manajemen kala III adalah untuk menghasilkan
waktu. Mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan kala III
persalinan jika di bandingkan dengan penatalaksanaan fisiologis
(Sondakh, 2013).
Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:
1) Memberikan suntikan oksitosin dalam satu menit pertama
setelah bayi lahir.
2) Melakukan penegangan tali pusat terkendali
3) Masase fundus uteri
d. Kala IV
Kala IV yaitu kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan
plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap
bahaya perdarahan postpartum (Mochtar, 2012). Asuhan persalinan pada kala IV
1) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi
pendarahan pervaginam
2) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,
balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin
selama 10 menit
3) Menempatkan klem tali pusat DTT atau mengikat tali pusat
dengan simpul mati bagian pusat yang berseragaman dengan
simpul mati sekeliling tali pusat 1 cm dari pusat
4) Mengikat satu lagi simpul mati bagian pusat yang berseragaman
5) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin
0,5% untuk dekomentasi selama 10 menit. Cuci dan bilas
peralatan setelah di dekontaminasi
6) Membuang bahan – bahan yang terkontaminasi ke tempat
sampah yang sesuai
7) Membersihkan badan ibu dengan menggunakan air DTT.
Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu
memakai pakaian yang bersih dan kering
8) Memastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI
dan anjurkan keluarga untuk memberi makan dan minum yang
di inginkan ibu
9) Mendokumentasikan tempat bersalin dengan larutan klorin
0.5%
10) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian
keringkan dengan handuk yang kering dan bersih
11) Membiarkan bayi berada di atas perut ibu untuk melakukan
kontak kulit ibu dan bayi di dada ibu kurang lebih 30 menit
12) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan
pervaginam
a) 2-3 kali dalam 15 menit pertam pasca persalinan
b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan
d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik. Laksanakan
perawatan yang sesuai untuk melaksanakan atonia uteri
e) Jika di temukan laserasi yang memerlukan penjahitan,
lakukan penjahitan dengan anesthesi local dan
menggunakan tehnik yang sesuai.
13) Menganjurkan ibu / keluarga cara untuk melakukan massase
uterus dan menilai kontraksi
14) Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah
15) Memantau nadi, kandung kemih, suhu, pernafasan, dan tekanan
darah dan TFU
16) Memastikan kembali kondisi bayi bahwa bayi bernafas dengan
baik serta suhu tubuh normal
17) Melakukan penimbangan/ pengukuran bayi. Dari tetes mata
antibiotic profilaksis dan vitamin K1 dengan dosis 1 mg secara
intramuscular di paha kiri anterolateral setelah kurang lebih 30
menit kontak kulit ibu dan bayi
18) Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam
pemberian vitamin K1
Meletakan bayi di dalam janngkauan ibu agar sewaktu-waktu
bisa disusukan
19) Melengkapi lembaran partograf, periksa tanda vital dan asuhan
kala IV
a. Perasaan takut ketika hendak melahirkan
b. Perasaan cemas menjelang proses melahirkan
c. Rasa sakit, tegang dan takut yang membuat jalur lahir menjadi
mengeras dan menyempit
d. Depresi merupakan penyakit psikologis yang berbahaya, agar ibu
melahirkan tidak mengalami depresi ia harus ditemani anggota
keluarga karena ibu membutuhkan semangat dan motivasi dari
suami dan keluarganya
e. Perasaan sedih jika persalinannya tidak sesuai dengan apa yang telah
diharapkan sebelumnya dan apakah bayinya normal atau tidak
f. Marasakan ragu atas kemampuannya dalam merawat bayinya
6. Komplikasi / penyulit selama persalinan
a. Persalinan Prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu yang membutuhkan pemantauan
yang ketat terhadap kemungkinan komplikasi lain yang timbul.
b. Ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah tanpa memadang usia kehamilan dan sebelum ada tanda tanda persalinan setelah
ketuban pecah 6 jam.
c. Amnionitis dan karioamnionitis merupakan infeksi dari selaput ketubanmaupun ketuban yang pecah lebih dari 24 jam tanpa adanya
tanda tanda persalinan.
7. Kelainan yang disebabkan oleh persalinan menurut Manuaba
(2012). antara lain : Kaput suksedaneum, Sefal hematoma dan Molase
tulang kepala janin.
8. APN dalam melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman
sesuai standar APN maka dirumuskan 60 langkah APN sebagai berikut:
a. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua. ¾ Ibu mempunyai
keinginan untuk meneran. ¾ Ibu merasa tekanan yang semakin
meningkat pada rektum dan/atau vaginanya. ¾ Perineum menonjol. ¾
Vulva-vagina dan sfingter anal membuka.
b. Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap
digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan
tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set.
c. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih.
d. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci
kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan
mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang
bersih.
e. Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua
pemeriksaan dalam.
f. Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai
sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan meletakkan
kembali di partus set/wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa
g. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari
depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah
dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum atau
anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan
seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang
kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar.
Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi (meletakkan kedua
sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi).
h. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam
untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila
selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap,
lakukan amniotomi.
i. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan
yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin
0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta
merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci
kedua tangan (seperti di atas).
j. Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir
untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal ( 100 – 180 kali /
menit). Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal..
Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua
k. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.
Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya.
Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran.
Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin
sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan
temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana
mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu
mulai meneran.
l. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu utuk
meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk
dan pastikan ia merasa nyaman). Melakukan pimpinan meneran saat
Ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran :
1) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinganan
untuk meneran.
2) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran.
3) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya
(tidak meminta ibu berbaring terlentang).
4) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.
5) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat
pada ibu. Menganjurkan asupan cairan per oral.
m. Menilai DJJ setiap lima menit.
n. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera
60/menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak
mempunyai keinginan untuk meneran Menganjurkan ibu untuk
berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang aman. Jika ibu
belum ingin meneran dalam 60 menit, menganjurkan ibu untuk mulai
meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di
antara kontraksi.
o. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera
setalah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera.
p. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm,
meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi.
q. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah bokong ibu.
r. Membuka partus set.
s. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.
t. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi
perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan
yang lain di kelapa bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak
menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar
perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau
bernapas cepat saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan
ketuban, segera hisap mulut dan hidung setelah kepala lahir
menggunakan penghisap lendir DeLee disinfeksi tingkat tinggi atau
steril atau bola karet penghisap yang baru dan bersih.
atau kasa yang bersih.
v. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika
hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran
bayi:
a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat
bagian atas kepala bayi.
b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di dua
tempat dan memotongnya.
23) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara
spontan Lahir bahu.
24) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua
tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk
meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke
arah bawah dan kearah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah
arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan
ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior.
25) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala
bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan,
membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut.
Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati
perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh
bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior (bagian atas)
untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya
26) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di
atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya
saat panggung dari kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi
dengan hati-hati membantu kelahiran kaki.
27) Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut
ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya
(bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang
memungkinkan).
28) Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi
kecuali bagian pusat.
29) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat
bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu
dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah ibu).
30) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari
gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut.
31) Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain
atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala,
membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan
bernapas, mengambil tindakan yang sesuai.
32) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk
memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu
menghendakinya.
33) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi
34) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik.
35) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan
oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar, setelah
mengaspirasinya terlebih dahulu penegangan tali pusat terkendali.
36) Memindahkan klem pada tali pusat. Meletakkan satu tangan diatas
kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan
menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan
menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem dengan tangan
yang lain.
37) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan
penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan
tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan
cara menekan uterus ke arah atas dan belakang (dorso kranial)
dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio
uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, menghentikan
penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai.
Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota
keluarga untuk melakukan ransangan puting susu.
38) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil
menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas,
mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan
arah pada uterus. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem
hingga berjarak sekitar 5 – 10 cm dari vulva.
selama 15 menit :
a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM.
b) Menilai kandung kemih dan mengkateterisasi kandung kemih
dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu.
c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya.
e) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak
kelahiran bayi.
40) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran
plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta
dengan dua tangan dan dengan hatihati memutar plasenta hingga
selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput
ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung
tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan
serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau
klem atau forseps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk
melepaskan bagian selapuk yang tertinggal.
41) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase
uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase
dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi
(fundus menjadi keras).
42) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun
lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau
tempat khusus. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan
masase selam 15 detik mengambil tindakan yang sesuai.
43) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera
menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif.
44) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik.
Mengevaluasi perdarahan persalinan vagina.
45) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam
larutan klorin 0,5 %, membilas kedua tangan yang masih bersarung
tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan
mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering.
46) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau
mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati
sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat.
47) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang berseberangan
dengan simpul mati yang pertama.
48) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin
0,5 %.
49) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya.
Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering.
50) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.
51) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan
pervaginam:
b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan.
c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan.
d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melaksanakan
perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. Jika
ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan
penjahitan dengan anestesia lokal dan menggunakan teknik yang
sesuai.
e) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase
uterus dan memeriksa kontraksi uterus.
f) Mengevaluasi kehilangan darah.
52) Memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih setiap
15 menit selama satu jam pertama pasca persalinan dan setiap 30
menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur
tubuh ibu sekali setiap jam selama dua jam pertama pasca persalinan.
Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal.
Kebersihan dan keamanan
53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk
dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah
dekontaminasi
54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat
sampah yang sesuai.
55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat
tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu
56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI.
Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan
makanan yang diinginkan dan mendekontaminasi daerah yang
digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan
membilas dengan air bersih.
57) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,
membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam larutan
klorin 0,5% selama 10 menit dan mencuci kedua tangan dengan
sabuun dan air mengalir.
58) Melengkapi partograf (buku asuhan persalinan normal, 2014).
9. Komplikasi dalam persalinan
a. Komplikasi pada kala satu dan dua dalam persalinan menurut Varney
(2008). adalah sebagai berikut:
1) Riwayat sekso sesaria sebelumnya
2) Persalinan atau kelahiran prematur
Persalinan prematur adalah persalinan yang dimulai pada awal
usia kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu ke 37.
Penatalaksanaan pada persalinan prematur didasarkan pada
pertama kali dengan mengidentifikasi wanita yang beresiko
mengalami Ini
Menurut Varney (2008). mengatakan amnionitis adalah inflamtasi
kantong dan cairan amnion. Korioamnionitis adalah inflamta si
korion selain infeksi cairan amnion dan kantong amnion
4) Prolaps tali pusat
Tindakan berikut dilakukan jika terjadi prolaps tali pusat menurut
Varney (2008).
a) Menempatkan seluruh tangan anda kedalam vagina wanita dan
pegang bagian presentasi janin kertas sehingga tidak
menyentuh tali pusat dipintu atas panggul.
b) Tidak boleh mencoba mengubah letak tali pusat pada kondisi
apapun
c) Segera panggil bantuan dan panggil dokter atau segera rujuk ke
fasilitas yang memadai.
b. Komplikasi pada Kala tiga persalinan
1) Plasenta tertinggal
Plasenta tertinggal adalah plasenta yang belum terlepas dan
mengakibatkan tidak terlihat. Manajemen untuk kasus ini adalah
dengan manual plasenta (Varney, 2008).
2) Perdarahan kala tiga
Komplikasi yang terjadi pada kala III persalinan dapat beresiko
menyebabkan perdarahan post partum, perdarahan post partum
3) Retensio plasenta
Adalah plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi
lahir. Manajemen untuk kasus ini adalah dengan plasenta dan
segera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memadai ( Varney,
2008).
4) Inversio Uterus
Adalah keadaan uterus benar-benar membaik dari bagian dalam
keluar sehingga bagian dalam fundus menonjil keluar melalui
orifisum servik, turun dan masuk kedalam introitus vagina, dan
menonjol keluar melewati vulva (Varney, 2008).
c. Komplikasi pada kala empat persalinan
1) Perdarahan post partum
Definisi perdarahan adalah kehilangan darah secara abnormal.
Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran pervaginam tanpa
komplikasi adalah lebih dari 500 ml (Varney, 2008).
2) Faktor predisposisi
a) Distensi berlebihan pada uterus
b) Induksi oksitosin atau augmentasi
c) Persalinan cepat atau presipitatus
d) Kala satu atau kala dua yang memanjang
C. MASA NIFAS
1. Pengertian Masa Nifas
a. Menurut Prawirohardjo (2010). masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan
kembali seperti keadaan sebelum hamil.Masa nifas ini berlangsung
selama 4 sampai 6 minggu (Williams, 2014). Sedangkan menurut
Manuaba (2013). masa nifas adalah masa pemulihan organ genetalia interna menjadi normal secara anatomi dan fungsional yang berlangsung sekitar 6 minggu.Jadi kesimpulannya masa nifas adalah
masa pemulihan setelah persalinan yang berlangsung antara 4 sampai
dengan 6 minggu sampai alat alat kandungan kembali seperti saat
sebelum hamil.
b. Menurut Sulistyawati (2009). nifas dibagi dalam 3 periode:
1) Puerperium dini merupakan suatu masa pemulihan dimana ibu sudahdiperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan dalam agama
Islam dianggap bersih setelah 40 hari
2) Puerperium intermedial merupakan masa pemulihan secara menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu
3) Remote Puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk pemulihan dan sehat sempurna, terutama apabila selama hamil atau
waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat
sempurna dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bulanan
2. Perubahan Fisiologis Nifas
a. Uterus Involusi uterus meliputi reorganisasi dan endometrium dan
eksfoliasi tempat perlekatan plasenta yang ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan pada lokasi uterus juga ditandai
dengan warna dan jumlah lokia. Menyusui akan mempercepat proses
involusi Regenerasi endometrium lengkap pada tempat perlekatan
plasenta memakan waktu hampir enam minggu. Pertumbuhan
endometrium ini membuat pembuluh darah yang mengalami
pembekuan pada tempat perlekatan tersebut rapuh sehingga meluruh
dan dikeluarkan dalam bentuk lokia.
(Varney, 2008).
Tabel 2.5 Tinggi Fundus Uteri, Berat Uterus Menu Masa Involusi Berat Uterus Involusi
Involusi Tinggi fundus uteri Berat uterus
Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram
Uri lahir 2jari dibawah pusat 750 gram 1 minggu Petengahan pusat simfisis 500 gram 2 minggu Tidak teraba di atas simfisis 350 gram
6 minggu Bertambah kecil 50 gram
8 minggu Sebesar normal
Sumber: ( Mochtar, 2012).
b. Lokia adalah istilah untuk sekret dari uterus yang keluar melalui
vagina selama puerperium. Karena perubahan warnanya, ada lokia
rubra (mengandung darah dan jaringan desidua), serosa (warnanya
lebih pucat dari rubra), alba (merah muda, kuning atau putih)
(Varney, 2008).
Menurut (Sulistyawati, 2009). menjelaskan Lokhea adalah ekskresi
jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus. Lokhea mempunyai
reaksi basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih
cepat daripada kondisi yang normal. Lokhea amis anyir dengan
volume yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lokhea yang berbau
tidak sedap menandakan adanya infeksi. ea mempunyai perubahan
warna dan volume karena adanya proses involusi.
Lokhea dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan warna dan waktu
keluarnya
1) Lokhea rubra/merah
Ini keluar pada hari pertama sampai hari ke-4 masa post partum.
Cairan yang keluar merah karena terisi darah segar, jaringan
sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan
mekonium (Sulistyawati, 2009).
2) Lokhea sanguinolenta
Lokhea ini berwarna merah kecokelatan dan berlendir, serta
berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 post partum
(Sulistyawati, 2009).
3) Lokhea serosa
Lokhea iberwarna kuning kecokelatan karena mengandung serum,
leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7
sampai hari ke-14 (Sulistyawati, 2009).
Lendir mengandung leukosit, sel desidua, sel epite selaput dapat
serviks, serabut jaringan yang mas alba ini berlangsung selama 2-6
minggu post partum (Sulistyawati, 2009).
c. Vagina dan Perineum, segera setelah pelahiran, vagina tetap terbuka
lebar, mungkin mengalami beberapa derajat edema dan memar, dan
celah pada introitus. Setelah satu hingga dua hari pascapartum, tonus
otot vagina kembali, celah tidak lagi lebar edema dan dinding vagina
lunak (Sulistyawati, 2009).
d. Payudara laktasi dimulai pada semua wanita dengan perubahan
hormon saat melahirkan. Dapat mengalami kongesti payudara selama
beberapa hari pertama pascapartum karena tubuhnya mempersiapkan
untuk memberikan nutrisi kepada bayi. Wanita yang menyusui
berespons terhadap menstimulus bayi yang disusui akan terus
melepaskan hormon dan stimulasi alveoli yang memproduksi Susu
(Sulistyawati, 2009).
e. Tanda-tanda vital
1) Tekanan darah mengalami peningkatan sementara tekanan darah
sistolik dan diastolik, kembali secara spontan ke tekanan darah
sebelum hamil selama beberapa hari (Sulistyawati, 2009).
2) Suhu matemal kembali normal dari suhu yang sedikit meningkat
selama periode intrapartum dan stabil dalam 24 jam pertama
pascapartum (Sulistyawati, 2009).
3) Nadi meningkat selama persalinan akhir, kembali normal setelah