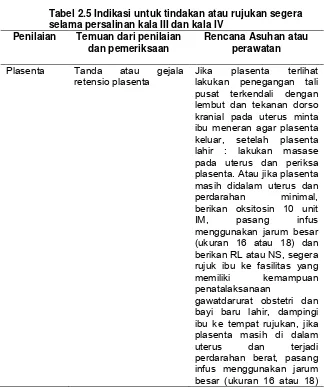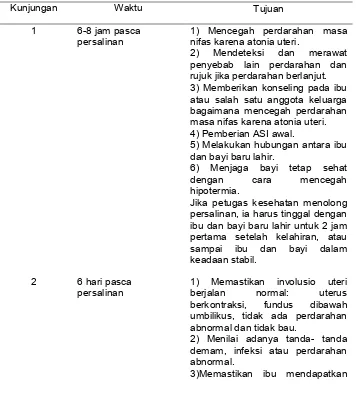BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KONSEP DASAR TEORI
1. Kehamilan
a. Definisi
Kehamilan adalah suatu masa yang dimulai dari konsepsi
sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40
minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid terakhir (Prawirohardjo,
2006).
Kehamilan adalah fertilisasi sel spermatozoa dan ovum yang
akan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat
fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung
dalam waktu 40 minggu (Prawirohardjo, 2010; h. 213).
Kehamilan didefinisikan sebagai persatuan antara sebuah telur
dan sebuah sperma, yang menandai awal suatu peristiwa yang
terpisah. Kejadian-kejadian itu ialah pembentukan gamet (telur dan
sperma), ovulasi (pelepasan telur), penggabungan gamet dan
berlangsung baik, maka proses perkembangan embrio dan janin
dapat dimulai (Bopak, 2005,p.74).
b. Tanda atau gejala
Beberapa perubahan fisiologis yang timbul selama masa hamil
dikenal sebagai tanda kehamilan. Ada tiga kategori, persumsi, yaitu
perubahan yang dirasakan wanita (misalnya amenorea, keletihan,
diobservasi oleh pemeriksa (misalnya tanda Hegar, ballotment, tes
kehamilan, dan pasti (misalnya ultrasonografi, bunyi denyut jantung
janin) (Bobak, 2005; h. 106)
(1) Tanda Dugaan Hamil
1) Amenorea (tidak dapat haid) gejala ini sangat penting karena
umumnya wanita hamil tidaak dapat haid lagi. Penting
diketahui tanggal pertama haid terakhir supaya ditentukan
tuanya kehamilan dan bila persalinan diperkirakan akan
terjadi. Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid
terakhir (HT) supaya dapat ditaksir umur
2) Kehamilan dan taksiran tanggal persalinan (HTP) yang
dihitung dengan menggunakan rumus Naegele : TTP = (hari
HT+7) dan (bulan HT-3) dan (tahun HT+1) (Mochtar R, 2012 ;
h. 35)
3) Nausea (enek) dan emesis (muntah) terjadi karena umumnya
pada bulan-bulan perta,a kehamilan, disertai kadang-kadang
oleh emesis. Sering terjadi pada pagi hari tetapi tidak selalu.
Keadaan ini lazim disebut morning sickness. Dalam
batas-batas tertentu keadaan ini masih fisiologik. Bila terlampau
sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan
disebut hiperemesis gravidarum (Prawirohardjo, 2007 ; h.125)
4) Mengidam (ingin makanan khusus) ibu hamil sering meminta
5) Pingsan, sering dijumpai bila berada pada tempat-tempat
ramai. Dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat ramai
pada bulan-bulan pertama kehamilan. Hilang sesudah
kehamilan 16 minggu.
6) Mammae menjadi tegang dan membesar, keadaan ini
disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang
merangsang duktuli dan alveoli dimammae, glandula
montgomery tampak lebih jelas (Prawirohardjo, 2007 ; h.125)
7) Anoreksia (tidak ada nafsu makan) pada bulan-bulan pertama
tetapi setelah itu nafsu makan timbul lagi. Hendaknya dijaga
jangan sampai salah pengertia makan untuk “dua orang”,
sehingga kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tuanya
kehamilan.
8) Sering kencing, terjadi karena kandung kencing pada
bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai
membesar. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini hilang
oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga
panggul. Pada akhir triwulan gejala bisa timbul kembali karena
janin mulai masuk keruang panggul dan menekan kembali
kandung kencing.
9) Konstipasi/obstipasi, terjadi karena tonus otot menurun yang
disebabkan oleh pengaruh hormon steroid.
10) Pigmentasi kulit, terjadi pada kehamilan 12 minggu keatas.
Pada pipi, hidung dan dahi kadang-kadang tampak deposit
gravidarum. Areola mammae juga menjadi lebih hitam karena
didapatkan deposit pigmen yang berlebih. Daerah leher
menjadi lebih hitam. Demikian pula linea alba digaris tengah
abdomen menjadi lebih hitam (linea grisea). Pigmentasi ini
terjadi karena pengaruh dari hormon kortiko-steroid plasenta
yang merangsang melanofor dan kulit.
11) Epulis adalah suatu hipertrofi papilla ginggivae. Sering terjadi
pada triwulan pertama.
12) Varises, sering dijumpai pada trimester terakhir. Didapat pada
daerah genitalia eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis. Pada
multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada
kehamilan yang terdahulu, timbul kembali pada triwulan
pertama. Kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejala
pertama kehamilan muda.
(2)Tanda Kemungkinan hamil
1) Tanda Hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthmus
uteri dari arah yang berlawanan.
2) Tanda Chadwick adalah perubahan warna menjadi kebiruan
keunguan pada v Tanda Piscaseck merupakan pembesaran
uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum berimplantasi
pada daerah dekat dengan kornu tersebut dapat dikenali
melalui pemeriksaan bimanual pelvikpada usia kehamila
kedelapan hingga sepuluh minggu (Saifuddin, 2008;
3) Tanda Braxton-Hicks, bila uterus dirangsang mudah
berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa hamil.
Pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak da
kehamilan misalnya pada mioma uteri, tanda Braxton-Hicks
tidak ditemukan.
4) Teraba ballotment, ketukan yang mendadak pada uterus
menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang
dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa.
5) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif
Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi tanda human
chorionic gonadothropin (hCG). Horon diekskresi di peredaran
darah ibu (pada plasma darah) diekskresi pada urine ibu
(Walyani, 2015 ; h. 73)
6) Vulva dan mukosa vagina termasuk juga poriso dan serviks.
(3) Tanda Pasti Kehamilan
Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh
ibunya pada kehamilan 18 minggu, sedangkan padaa multigravida
pada 16 minggu, oleh karena sudah berpengalaman dari
kehamilan terdahulu. Gerakan janin kadang-kadang pada
kehamilan 20 minggu dapat diraba secara objektif oleh pemeriksa,
balotment dalam uterus dapat diraba pada kehamilan lebih tua.
Bila dilakukan pemeriksaan dengan rontgen kerangka fetus mulai
dapat dilihat. Dengan alat fetal electro cadiograph denyut jantung
janin dapat dicatat pada kehamilan 12 minggu. Dengan memakai
Keuntungan cara yang terakhir ini adalah bahwa janin tidak
terpengaruh seperti oleh sinar rontgen. Dengan stetoscop laennec
bunyi jantung janin baru dapat didengar pada kehamilan 18-20
minggu. Pula didengar bising dari uterus yang sinkron dengan
nadi ibu karena pembuluh - pembuluh darah uterus membesar.
Dalam triwulan terakhir gerakan janin lebih gesit. Bunyi
jantung janin dapat pula didengar lebih jelas. Bagian-bagian besar
janin, ialah kepala dan bokong, dan bagian-bagian kecil ialah kaki
dan lengan, dapat diraba dengan jelas, pada primigravida kepala
janin mulai turun pada kehamilan kira-kira 36 minggu, sedangkan
multigravida pada kira-kira 38 minggu, kadang-kadang baru
permulaan partus. Dari keseluruhan yang diuraikan diatas, maka
diagnosis pasti kehamilan dapat ditegakkan dengan :
1) Dapat diraba dan kemudian dikenal bagian-bagian janin
2) Dapata dicatat dan didengar bunyi jantung janin dengan
beberapa cara
3) Dapat dirasakan gerakan janin dan balotmet
4) Pada pemeriksaan sinar rontgen tampak kerangka janin
5) Dengan ultrasonografi (scanning) dapat diketahui ukuran
kantong janin, panjangnya janiin (crown-rump) dan diameter
bipaietalis hingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan, dan
selanjutnya dapat dipakai bila ada kecurigaan dalam
kehamilan mola, blighted ovum, kematian janin iontra uterin,
anensefali, kehamilan ganda, hidramnion, plasena previa dan
kehamilan 16-18 minggu yang diperkirakan aman meman
menjadi pegangan untuk pasien dan dokternya untuk
pengawasan lebih yakin dan mantap.
(4) Fetoskopi (Prawirohardjo, 2009 h.129-130).
a) Perubahan pada sistem reproduksi
(1) Uterus
2.1 Tabel pembesaran uterus
Involusi Tinggi Fundus Uterus Berat Uterus Bayi Lahir Setinggi pusat 1000 gram Uri Lahir 2 jari dibawah pusat 750 gram 1 minggu Pertengahan pusat-
simpisis
500 gram
2 minggu Tak teraba diatas simpisis
350 gram
6 minggu Bertambah kecil 50 gram 8 minggu Sebesar normal
Sumber: Sulistyawati (2009)
(2) Ovarium
Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh
plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen.
Selama kehamilan ovarium tenang/ beristirahat.
(3) Payudara
Akibat pengaruh estrogen terjadi hiperplasia sistem duktus
dan jaringan intertesial payudara.
(a). Pada kehamilan trimester 1
Setelah terjadinya peningkatan hormon estrogen dan
progesteron dalam tubuh, maka akan muncul berbagai
macam ketidaknyamanan secara fisiologis pada ibu
misalnya mual, muntah, dan pembesaran pada payudara.
Hal ini akan membuat perubahan psikologis seperti ibu
membenci kehamilanya, merasakan kekecewaan,
penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Pada trimester ini
mencari tahu secara aktif apakah benar-benar hamil dengan
memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan bila terjadi
perubahan pada dirinya maka akan selalu diperhatikan (Hani
dkk,2011 : 68 )
(b). Pada trimester II
Trimester kedua sering dikenal sebagai periode
kesehatan yang baik, yakni ketika wanita merasa nyaman
dan bebas dari segala ketidaknyamanan fisik dan ukuran
perut wanita belum menjadi masalah besar. Lubrikasi vagina
semakin banyak pada masa ini, kecemasan, kekhawatiran,
dan masalah-masalah yang sebelumnya menimbulkan
ambivalensi pada wanita tersebut mereda. Menjadi
seorang yang memcari kasih sayang dari pasanganya, dan
semua faktor ini turut mempengaruhi peningkatan libido dan
(c). Pada Trimester III
Trimester tiga biasanya disebut periode menunggu
dan waspada sebab pada saat itu ibu sudah tidak sabar
menunggu kehadiran bayinya keluar kedunia.gerakan bayi
dan membesarnya perut membuat ibu merasa khawatir
bayinya akan lahir sewaktu-waktu atau bahkan lahir tidak
normal. Kebanyakan ibu juga akan berusaha melindungi dan
menghindari bayinya dari orang atau benda apa saja yang
dapat membahayakan bayinya (Hani dkk, 2011 : 69).
c. Kebutuhan gizi pada ibu hamil
Menurut (Kusmiyati dkk,2009:85) standar minimal untuk
ukuran lengan atas pada wamita dewasa atau usia reproduksi adalah
23,5 cm, jika ukuran LILA kurang dari 23,5 cm maka interpretasinya
adalah kurang energi kronis (KEK) atau pemenuhan kebutuhan gizi
yang kurang. Status gizi ibu yang kurang baik sebelum dan selama
kehamilan merupakan penyebab utama dari berbagai persoalan
kesehatan yang serius pada ibu dan bayi. Yang berakibat terjadinya
anemia, abortus, inersia uteri, perdarahan pasca persalinan, bayi
lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur serta kematian
neonatal dan perinatal. Kebutuhan makanan pada ibu hamil mutlak
harus dipenuhi dengan meningkatkan asupan energinya sebesar 285
kkal perhari, tujuanya untuk memasak dalam memenuhi kebutuhan
janin. Kurang energi kronis (KEK) itu sendiri disebabkan kurangnya
kebutuhan akan protein, sedangkan kebutuhan protein pada ibu
menambahkan asupan protein menjadi 12% perhari atau 75
100gram, sumber protein yang baik yaitu daging tak berlemak, ikan,
telur, dan susu (Sulistyawati, 2011:107-108).
d. Tanda bahaya dalam kehamilan
a. Perdarahan per vaginam
Perdarahan vagina dalam kehamilan adalah normal, pada
awal kehamilan mungkin ibu akan mengalami perdarahan yang
sedikit atau spotting disekitar waktu haidnya terlambat.
Perdarahan ini dinamakan perdarahan implamantasi dan normal.
Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak normal adalah yang
berwarna merah, perdarahan yang banyak, atau perdarahn yang
sangat menyakitkan, perdarahan ini dapat berarti abortus,
kehamilan mola, atau kehamilan ektopik (Hani dkk, 2011: 108)
1) Abortus imminens
Jenis abortus permulaan merupakan suatu ancaman, ditandai
dengan perdarahan pervaginam, ostium uteri masih tertutup
dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Diagnosis
abortus imminens biasanya diawali dengan keluhan
perdarahan pervaginam pada umur kehamilan kurang dari 20
minggu. Penderita mengeluh mules sedikit ataupun tidak ada
keluhan sam sekali kecuali perdarahan pervaginam
(prawirohardjo, 2010: 467)
2) Abortus insipens
Abortus yang sedang mengancam, ditandai dengan
membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kovum
uteri dan dalam proses pengeluaran. Penderita akan
merasa mules karena adanya kontraksi yang sering dan
kuat, perdarahannya terus bertambah sesuai pembukaan
serviks uterus dan umur kehamilan (prawihardjo, 2010:
469)
3) Abortus inkomplet
Didiagnosa apabila sebagian dari hasil konsepsi telah lahir
atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal.
Perdarahan biasanya terus berlangsung, banyak dan
membahayakan ibu. Servik terbuka karena maih ada
benda didalam rahim yang dianggap sebagai benda asing
(walyani,2015: 147)
4) Abortus komplet
Hasil konsepsi lahir dengan lengkap pada keadaan ini
curetase tidak perlu dilakukan. Perdarahan segera
berkurang setelah isi rahim dikeluarkan dan
selambat-lambatnya dalam 10 hari perdarahan akan berhenti sama
sekali, karena dalam masa ini luka rahim telah sembuh
dan epitelisasi telah selesai. Serviks dengan segera
menutup kembali (walyani, 2015: 148)
5) Kehamilan ektopik terganggu
Kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan implantasi
terjadi diluar uterus. Tuba fallopi merupakan tempat yang
dari 90%) tanda dan gejalanya bermacam-macam
tergantung dengan pecah atau tidaknya kehamilan
tersebut (Hani dkk, 2011: 112)
6) Mola hodatisoda
Merupakan penyimpangan pertumbuhan dan
perkembangan kehamilan yang tidak disertai janin dan
seluruh vili korealis mengalami perubahan hidrovik.
Terdapat beberapa kejadian, sebagai janin dapat tumbuh
dan berkembang bahkan sampai aterm, keadaan tersebut
dinamakan mola hidatisoda parsialis (Manuaba, 2010: 326)
b. Hipertensi gravidarum
Hipertensi dalam kehamilan termasuk hipertensi kronik
meningkatnya tekanan darah sebelum kehamilan 20 minggu.
Nyeri kepala, kejang, dan hilangnya kesadaran sering
berhubungan dengan hiperteni daam kehamiilan. Keadaan ini
yang mengakibatkan kejang adalah epilepsi, malaria, trauma
kepala, meningiti, dan ensefallis (Hani dkk, 2011: 112)
c. Sakit kepala yang hebat
Sakit kepala yang sangat fatal adalah sakit kepala hebat,
yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Bahkan
dapat menimbulkan penglihatan kabur atau berbayang. Sakit
kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari
d. Bengkak pada muka dan tangan
Hampir sebagian ibu hamil akan mengalami bengkak
yang normal pada kaki biasanya muncul sore hari dan hilang
setelah beristirahat atau meletakan kaki lebih tinggi. Bengkak
dapat menjadi serius jika muncul pada permukaan muka dan
tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan diikuti keluhan
fisik yang lain. Hal ini bisa merupakan pertanda anemia, gagal
jantung, atau preeklamsia ( Hani dkk, 2010: 121)
e. Bayi kurang bergerak seperti biasa
Ibu mulai merasakan gerakan bayinya pada bulan ke-5
atau ke-6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya
lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi
harus bergerak sedikitnya 3 kali dalam waktu 3 jam. Gerakan
bayi akan mudah teraa jika ibu berbaring atau beristirahat dan
jika ibu makan dan minum dengan baik (Rukiyah, 2009: 127).
e. Pelayanan antenatal (Antenatal Care)
Pelayanan antenatal merupakan cara penting untuk
menfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya
dengan cara membina hubungan saling percaya dengan ibu,
mendeteksi komplikasi, mempersiapkan persalinan, memberikan
pendidikan. Asuhan antenatal penting untuk menjamin agar proses
alamiah tetap berjalan normal selama kehamilan (Dewi, Tri sunarsih,
2011).
(a). Standar pelayanan antenatal
Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan kunjungan antenatal
i). Satu kali pada triwulan pertama (sebelum 14 minggu).
ii). Satu kali pada triwulan kedua ( antara 14-28 minggu).
iii). Dua kali pada triwulan ketiga (antara 29-36 dan sesudah
minggu ke-36).
f. Jadwal Kunjungan Ibu Hamil
Frekuensi pelayanan antenatal oleh WHO ditetapkan 4 kali
kunjungan ibu hamil dalam pelayanan antenatal selama kehamilan
dengan ketentuan sebagai berikut:
(a). 1 kali kunjungan pertama (K-1) selama trimester pertama (<14
minggu).
(b). 1 kali kunjungan kedua (K-2) selama trimester kedua (antara
minggu ke 14- 28).
(c). 2 kali kunjungan ketiga (K-3 dan K-4) selama trimester ketiga
(antara minggu ke 28-36 dan sesudah minggu ke-36) (Mufdlilah,
2009).
Perencanaan jadwal pemeriksaan (usia kehamilan dari hari
pertama haid terakhir) yang ideal adalah sebagai berikut:
(a). Sampai 28 minggu : 4 minggu sekali.
(b). 28- 36 minggu : 2 minggu sekali.
(c). Diatas 36 minggu : 1 minggu sekali kecuali jika ditemukan kelainan
atau faktor risiko yang memerlukan penatalaksanaan medik lain,
Tabel 2.2 Jadwal kunjungan antenatal Kunjungan Waktu Info Penting
Trimester I Sebelum minggu ke 14
Membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil.
Mendeteksi masalah dan menanganinnya. Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonaturum, anemia kekurangan zat besi, penggunaan praktik trdisional yang merugikan.
Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi.
Mendorong prilaku yang sehat (gizi, latihan dan kebersihan, istirahat, dan sebagainnya).
Trimester II Sebelum minggu ke 28
Sama seperti di atas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklamsia (tanya ibu tentang gejala-gejala preeklamsia, pantau tekanan darah, evaluasi edema, periksa untuk mengetahui proteinuria).
Trimester III Antara minggu 28-36
Sama seperti di atas, ditamah palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda.
Trimester III Setelah 36 minggu
Sama seperti di atas, ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal, atau kondisi lain yang memerlukan kondisi kelahiran di rumah sakit
(Sumber: Saifuddin, 2012;h. N-2)
1) Standar Pelayanan ANC
Menurut Saifudin (2009; h. 89-90) dimana dalam setiap
pertemuan harus memberikan asuhan standar minimal yang sering
disebut dengan 7T yaitu:
a) Timbang berat badan
b) Ukur tekanan darah
c) Ukur tinggi fundus uteri
d) Pemberian imunisasi TT lengkap
e) Pemberian tablet zat besi, minimal 90 tablet selama kehamilan
dimana tiap tablet besi mengandung fe so4 320 mg (zat besi
60mg) dan asam folat 0,5 mg
g) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan.
2. PERSALINAN
1. Definisi
Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput
ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika
prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37
minggu) tanpa disertai adanya penyulit (JNPK-KR, 2008).
Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik, dari
janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin
dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir (Sarwono,2001).
Persalinan normal disebut juga partus spontan adalah proses
lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri,
tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang
umumnya berlangsung kurang dari 24 jam (Rustam Mochtar,1998).
Persalinan normaladalah proses pengeluaran janin yang terjadi
pada kehamilan cukup bulan (37 minggu – 42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18 jam, tanpa
komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2001).
2. Faktor Predisposisi
Faktor yang mempengaruhi persalinan adalah :
a. Power
Power atau tenaga yang mendorong anak adalah :
serviks terdiri dari his pembukaan, his pengeluaran dan his
pelepasan plasenta, his pendahuluan tidak berpengaruh
terhadap serviks. Tenaga mengejan ( kontraksi otot – otot dinding perut, kepala didasar panggul merangsang mengejan,
paling efektif saat kontraksi/his)
b. Passanger
Akhir minggu ke 8 janin mulai nampak menyerupai manusia
dewasa, menjadi jelas pada akhir minggu ke 12 (Sukarni, 2013;
h.194)
c. Passage
Bagian – bagian tulang panggul (2 Os Coxae, Os Cossygis, Os Sacrum) (Sukarni, 2013; h.187)
Dibagi atas : bagian keras tulang – tulang panggul (rangka panggul), dan bagian lunak (otot – otot, jaringan – jaringan, dan ligamen – ligamen) (Mochtar, 2011; h.58)
d. Psikologis
Dalam persalinan terdapat kebutuhan emosional jika
kebutuhan tidak tepenuhi paling tidak sama seperti kebutuhan
jasmaninya. Prognosis keseluruhan wanita tersebut yang
berkenan dengan kehadiran anaknya terkena akibat yang
merugikan.
e. Penolong
Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk
maternal dan neonatal. Pengetahuan dan kompetensi yang
baik diharapkan tidak ada kesalahan atau malpraktik yang
terjadi(Mochtar R,2012;h.58).
3. Tanda-tanda Permulaan Persalinan
Sebelum terjadi persalinan sebenarnya beberapa minggu
sebelumnya wanita memasuki “bulannya” atau “minggunya” atau “harinya” yang disebut kala pendahuluan (prepatory stage of labor). Ini
memberikan tanda- tanda sebagai berikut :
a. Lightening atau setting atau dropping yaitu kepala turun memasuki
pintu atas panggul terutama pada primigravida, sedangkan pada
multipara tidak begitu ketara.
b. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun.
c. Perasaan sering- sering atau susah kencing (polakisuria) karena
kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin.
d. Perasaan nyeri di perut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-
kontraksi lemah dari uterus, kadang- kadang disebut “false labor pains”.
e. Serviks menjadi lembek, mulai mendatar, dan sekresinya
bertambah bisa bercampur darah (bloody show) (Mochtar, 2011).
a. Tanda- Tanda Inpartu
1) Kekuatan His makin sering terjadi dan teratur dengan jarak
kontraksi yang semakin pendek (frekuensi minimal 2 kali
dalam 10 menit)
2) Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks,
dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda (pengeluaran
3) Dapat disertai ketuban pecah.
4) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks
(perlunakkan serviks, pendataran serviks, terjadi pembukaan
serviks) (Manuaba, 2010).
4. Tahap-Tahap Persalinan
Menurut Kemenkes RI (2013) Persalinan dibagi menjadi 4 kala
yaitu:
1) Kala I dibagi menjadi 2 yaitu:
a) Fase Laten
Dimulai dari pembukaan serviks 1cm sampai 3 cm yang
terjadi dalam 8 jam.
b) Fase Aktif
Dimulai dari pembukaan 4 cm sampai 10 cm yang terjadi
sekitar 6 jam.
2) Kala II dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir,
3) Kala III yaitu segera setelah bayi lahir sampai pengeluaran plasenta
secara lengkap.
4) Kala IV adalah kala yang dimulai setelah plasenta lahir legkap
sampai 2 jam post partum.
5) Mekanisme Persalinan
Mekanisme persalinan terdiri dari engagement, penurunan,
fleksi, putar paksi dalam, ekstensi, putar paksi luar dan ekspulsi
1) Engagement
Merupakan masuknya kepala di pintu atas panggul (PAP)
dan terjadi peristiwa sinklitismus (sutura sagitalis berada
ditengah- tengah jalan lahir dan tepat diantara simfisis dan
promontorium). Pada primipara terjadi sebelum persalinan aktif
dimulai, karena otot- otot abdomen masih tegang, sehinnga
presentasi terdorong ke dalam panggul. Pada multipara yang
otot- otot abdomennya lebih kendur, kepala seringkali digerakkan
di atas permukaan panggulsampai persalinan dimulai.
2) Penurunan
Penurunan adalah gerakan bagian presentasi kepala
melewati panggul, terjadi peristiwa asinklintismus posterior
(sutura sagitalis mendekati simfisis dan os parietal belakang
lebih rendah dari pada os parietal depan). Terjadi akibat tiga
kekuatan yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung
kontraksi fundus pada janin dan kontraksi diafragma dan otot
abdomen ibu pada tahap kedua persalinan. Efek ketiga kekuatan
itu dimodifikasi oleh ukuran dan bentuk bidang panggul ibu dan
kapasitas kepala janin untuk molague.
3) Fleksi
Segera setelah kepala yang turun tertahan oleh serviks,
dinding panggul, atau dasar panggul, dalam keadaan normal
fleksi terjadi dan dagu didekatkan kearah dada janin. Dengan
fleksi, suboksipitobregmantika yang diameter lebih kecil (9,5 cm)
dapat masuk ke dalam pintu bawah panggul (PBP).
Putar paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina
isciadika, tetapi putaran ini belum selesai sampai bagian
presentasi mencapai panggul bagian bawah. Ketika oksiput
berputar ke arah anterior, wajah berputar ke posterior. Setiap
terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan oleh tulang panggul dan
otot- otot dasar panggul. Akhirnya, oksiput berada di garis tengah
di bawah lengkung pubis.
5) Ekstensi
Saat kepala janin mencapai perinium, kepala akan defleksi
ke arah anterior oleh promontorium. Mula- mula oksiput melewati
permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar akibat
ekstensi: pertama- tama oksiput, kemudian wajah, dan akhirnya
dagu.
6) Restitusi dan Putar Paksi Luar
Setelah kepala keluar, bayi berputar hingga mencapai
posisi yang sama dengan saat kepala memasuki PAP. Gerakan
ini dikenal dengan restitusi dan putaran 45 derajat membuat
kepala janin kembali sejajar dengan punggung dan bahunya.
Dengan demikian, kepala dapat terlihat berputar lebih lanjut.
Putaran paksi luar terjadi saat bahu engaged dan turun dengan
gerakan mirip dengan gerakkan kepala.
7) Ekspulsi
Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas
fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Ketika seluruh tubuh bayi
keluar, persalinan bayi selesai.
1. Proses Persalinan
A. Kala I
Yaitu waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi
pembukaan lengkap 10 cm. Inpartu ditandai dengan keluarnya
lendir darah (bloody show). Kala I (kala pembukaan) terdiri atas 2
fase, yaitu:
a) Fase laten: pembukaan serviks berlangsung lambat sampai
pembukaan 3 cm. Pada primigravida berlangsung 8-10 jam
dan multigravida berlangsung 6-8 jam (Manuaba, 2007).
b) Fase aktif: frekuensi dan lama kontraksi uterus meningkat
secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat atau memadai
jika terjadi tiga kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan
berlangsung selama 40 detik atau lebih) (Depkes, 2008).
Fase aktifdibagi menjadi 3 subfase:
(1) Fase akselerasi (pembukaan 3-4 cm) berlangsung
selama 2 jam.
(2) Fase dilatasi maksimal (pembukaan 4-9 cm) berlangsung
2 jam. Rata-rata kecepatan pembukaan pada primipara
atau nulipara adalah 1 cm perjam sedangkan pada
multipara adalah 2-3 cm perjam.
(3) Fase deselerasi (pembukaan 9-10) berlangsung kira-kira
selama 2 jam (Manuaba, 2007).
1) Beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu
2) Jika ibu tampak gelisah/kesakitan : biarkan ia berganti
posisi sesuai keinginan, tapi jika di tempat tidur sarankan
untuk miring kiri, biarkan ia berjalan atau beraktivitas
ringan sesuai kesanggupannya, anjurkan suami atau
keluarga memijat punggung atau membasuh muka ibu,
ajari teknik bernapas.
3) Jaga privasi ibu, gunakan tirai penutup dan tidak
menghadirkan orang tanpa seizin ibu.
4) Izinkan ibu untuk mandi atau membasuh kemaluannya
setelah buang air kecil/besar.
5) Jaga kondisi ruangan ruangan sejuk. Untuk mencegah
kehilangan panas pada bayi baru lahir, suhu ruangan
minimal 25 ºC dan semua pintu serta jendela harus
tertutup.
6) Beri minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi.
Sarankan ibu berkemih sesering mungkin.
7) Pasang infus intravena untuk pasien dengan : kehamilan
lebih dari 5, hemoglobin <9 gr/dl atau hematokrit <29 %,
riwayat gangguan perdarahan, sungsang, kehamilan
ganda, hipertensi, persalinan lama.
8) Isi dan letakkan partograf disamping tempat tidur atau
didekat pasien.
9) Lakukan pemeriksaan kardiotokografi jika memungkinkan.
Temuan – temuan anamnesis atau
pemeriksaan
Rencana untuk asuhan atau perawatan
Riwayat bedah sesar Segera rujuk ibu ke fasilitas yang mempunyai kemampuan untuk melakukakn bedah sesar.Dampingi ibu ke tempat rujukan dengan memberikan dukungan dan semangat.
Perdarahan
pervaginam selain lendir bercampur darah (show)
Jangan melakukan pemeriksaan dalam : baringkan ibu ke sisi kiri, pasang infus menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat, segera rujuk ke fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan bedah sesar, dampingi ibu ke tempat rujukan.
Kurang dari 37 minggu (persalinan kurang bulan)
Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat. Ketuban pecah disertai handuk/kain untuk mengeringkan dan menyelimuti bayi untuk mengantisipasi jika ibu melahirkan diperjalanan.
Ketuban pecah (lebih dari 24 jam atau ketubahn pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan <27 minggu.
Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri, dampingi ibu ke tempat rujukan dan berikan dukungan serta semangat. menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram fisiologis (NS) dengan tetesan 125 cc/jam, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Tekanan darah lebih dari 160/110 atau terdapat protein dalam urine (preeklampsia berat)
Temuan – temuan anamnesis atau
pemeriksaan
Rencana untuk asuhan atau perawatan
pada bokong kiri dan kanan), segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Tinggu fundus 40 cm kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat. DJJ <100 atau >180 menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram fisiologis (NS) dengan tetesan 125 cc/jam, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Primipara dalam fase aktif kala satu gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Presentasi ganda (majemuk) adanya bagian lain dari janin, misalnya lengan atau tangan, bersama gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Tali pusat menumbung (jika tali pusat masih berdenyut)
Gunakan sarung tangan Desinfeksi tingkat tinggi, letakkan satu tangan di vagina dan jauhkan kepala janin dari tali pusat yang menumbung, Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Temuan – temuan anamnesis atau
pemeriksaan
Rencana untuk asuhan atau perawatan
: Nadi cepat lemah (lebih dari 110x/menit), Tekanan darah menurun (sistolik kurang dari 90 mmHg), pucat, berkeringat atau dingin, napas cepat (>30 x/menit), cemas, bingung atau tidak sadar, produksi urine sedikit (kurang dari 30 ml/jam)
ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan kontraksi teratur (>2 dalam 10 menit)
Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Tanda dan gejala perubahan serviks, evaluasi DJJ jika tidak ada tanda – tanda kegawatan pada ibu dan janin, persilahkan ibu pulang dengan nasehat untuk makan dan minum, datang dan mendapatkan asuhan jika terjadi peningkatan frekuensi dan lama kontraksi. Tanda dan gejala kontraksi kurang dari 2 kali dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 40 detik.
Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
10) (Sumber JNPK-KR, 2008; h. 48-51) 11)
B. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)
Yaitu kala pengeluaran janin. Pada kala ini, his terakomodir,
tekanan pada otot-otot dasar panggul dan menimbulkan rasa
ingin mengedan. Kala II pada primigravida berlangsung 1,5-2 jam
dan pada multigravida 0,5-1 jam (Depkes, 2008).Penatalaksanaan
kala II berdasarkan Asuhan Persalinan Normal (APN) ada
padalangkah 1 sampai 26 (Kemenkes, 2013).
Asuhan pada kala II
1) Mengenali tanda gejala kala dua : ibu mempunyai keinginan
kuat untuk meneran, ibu merasa takanan yang semakin
meningkat pada rektum atau vaginanya.
2) Menyiapkan pertolongan persalinan, pastikan kelengkapan
peralatan, bahan dan obat esensial : klem, gunting, benang
tali pusat, penghisap lendir steril/DTT siap dalam wadahnya.
semua pakaian, handuk, selimut dan kain untuk bayi dalam
kondisi bersih dan hangat, timbangan pita ukur, stetoskop
bayi, dan termometer dalam kondisi baik dan bersih.
Paatahkan ampul oksitosin 10 IU dan tempatkan spuit steril
sekali pakai di dalam partus set/wadah DTT. Untuk resusitasi
(tempat datar, rata, bersih, kering dan hangat, 3 handuk, atau
kain bersih dan kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60
watt dengan jarak 60 cm di atas tubuh bayi. Persiapan bila
yerjadi kegawatdaruratan pada ibu cairan kristaloid, set infus.
3) Kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih,
sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker dan
4) Lepas semua perhiasan pada lengan dan tangan lalu cuci
kedua tangan dengan sabu
n dan air
bersih kemudiankeringkan dengan handuk atau tisu bersih.
5) Pakai sarung tangan steril/DTT untuk pemeriksaan dalam.
6) Ambil spuit dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan
oksitosin 10 IU dan letakkan kembali spuit tersebut di partus
set/wadah DTT atau steril tanpa mengontaminasi spuit.
7) Bersihkan vulva dan perineum, dari depan ke belakang
dengan kapas atau kassa yang dibasahi air DTT.
8) Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa
pembukaan serviks sudah lengkap. Lakukan amniotomi bila
selaput ketuban belum pecah, dengan syarat : kepala sudah
masuk ke dalam panggul dan tali pusat tidak teraba.
9) Dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan
yang masih memakai saring tangan kedalam larutan klorin
0,5% kemudian lepaskan sarung tangan dalam kedaan
terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10
menit. Cuci kedua tangan setelahnya.
10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) segera setelah kontraksi
berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal
(120 – 160) kali/menit). Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.
11) Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin
12) Minta bantuan keluarga untuk membantu proses bimbingan
meneran.
13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan
yang kuat untuk meneran.
14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil
posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan
untuk meneran dalam 40 menit.
15) Jika kepala bayi sudah membuka vulva diameter 5 – 6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain
bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan
kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu
lahirnya kepala.
16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong
ibu.
17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkaap alat
dan bahan.
18) Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.
19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 – 6 cm, dilindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain
bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan
kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu
lahirnya kepala, anjurkan ibu meneran sambil bernafas cepat
dan dangkal.
20) Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan yang sesuai jika
21) Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar
secara spontan.
22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara
biparietal anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi (dengan
lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu
depan muncul di bawah arkus pubis, gerakan arah atas dan
distal untuk mekahirkan bahu belakang.
23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan yang berada dibawah
di bawah ke arah perineum ibu untuk menyanhgga kepala,
lengan dan siku sebelah bawah (gunakan tangan yang
berada diatas untuk menelusurui dan memegang tangan dan
sikut sebelah atas.
24) Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran
tangan yang berada di atas ke pinggang, bokong, tungkai,
dan kaki bayi, pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk di
antara kaki dan pegang masing – masing mata kaki dengan ibu jari dan jari – jari lainnya).
25) Lakukan penilaian sekilas
26) Bila tidak ada Asfiksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir
normal. Keingkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu
(keringkan bayi mulai dari muka kepala dan bagian tubuh
lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks,
ganti handuk basah dengan handuk yang kering, pastikan
bayi dalam kondisi baik di atas dada atau perut ibu.
Penilaian Temuan dari penilaian darah rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg).
Baringkan ibu miring ke kiri, naikkan kedua kaki untuk meningkatkan aliran darah kejantung, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuanpenatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan.
Nadi, urine Tanda atau gejala dehidrasi : perubahan nadi (100 x/menit atau lebih), produksi urine partograf) jika kondisinya tidak membaik dalam waktu satu jam, pasang infus menggunakan jarum diameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan RL atau NS 125 ml/jam, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan nadi cepat (110 x/menit atau lebih), suhu lebih dari 38ºC, menggigil, air ketuban atau cairan vagina yang berbau
Baringkan ibu miring ke kiri, pasang infus menggunakan jarum diameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan RL preeklampsia ringan : tekanan darah diastolik 90-110 mmHg, proteinuria hingga 2+
Nilai ulang tekanan darah setiap 15 menit (saat diantara kontraksi atau meneran), baringkan ibu miring ke kiri dan cukup istirahat, bila gejala bertambah berat maka tatalaksana sebagai preeklampsia berat
Kejang Tanda atau gejala preeklampsia berat atau eklampsia : tekanan darah diastolik 110 mmHg atau lebih, tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih dengan kejang nyeri kepala, gangguan penglihatan,
Penilaian Temuan dari penilaian fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan
Anjurkan ibu mengubah posisi dan berjalan – jalan, anjurkan untuk minum, jika selaput ketuban masih utuh dan pembukaan diatas 6 cm maka pecahkan (gunakan setengah kocher DTT), stimulasi puting susu, anjurkan ibu untuk yang memiliki kemampuan penatalaksanaan nilai ulang DJJ setelah 5 menit : jika DJJ normal, minta ibu kembali meneran dan pantau DJJ setelah setiap kontraksi pastikan ibu tidak berbaring terlentang dan tidak menahan nafasnya saat meneran, jika DJJ abnormal, rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan.
Penurunan kepala bayi
Kepala bayi tidak turun Anjurkan meneran sambil jongkok atau berdiri, jika grafik penurunan kepala pada partograf melewati garis waspada sedangkan pembukaan serviks dan kontraksi cukup memuaskan maka segera rujuk pasien ke fasilitas rujukan, dampingi ibu ke tempat rujukan.
Lahirnya bahu
Tanda – tanda distosia bahu :
Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan
Rencana Asuhan atau perawatan
tindakan yang yang dilakukan) : perasat Mc Robert, Pronce Mc Robert (menungging), anterior dysimpact, perasat Cork-screw dari Wood, dan pantau DJJ setelah setiap kontraksi dan pastika ibu tidak terlentang dan tidak menahan nafasnya saat meneran, jika DJJ tidak normal tangani sebagai gawat janin (lihat diatas), setelah kepala bayi lahir, lakukan penillaian segera dan bila bayi tidak bernapas maka hisap lendir di mulut kemudian hidung bayi dengan penghisap lendir Dee Lee (DTT/steril\0 atau bola karet penghisap (baru dan bersih) lakukan tindakan lanjutan sesuai dengan hasil penilaian.
Tidak pucat Tanda – tanda tali pusat menumbung : tali pusat teraba atau terlihat saat periksa dalam
Tanda – tanda lilitan tali pusat : tali pusat melilit leher bayi
Nilai DJJ jika ada segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, baringkan miring kiri dengan pinggul agak naik, dengan memakai sarung tangan DTT/steril, satu tangan di dalam vagina untuk menahan kepala bayi agar tidak menekan tali pusat dan tangan lain di abdomen untuk menahan bayi pada posisinya (keluarga dapat membantu melakukannya), atau ganjal bokong ibu agar lebih tinggi dari kepalanya, dengan menggunakan sarung tangan ke dalam vagina untuk menahan kepala bayi agar tak menekan tali pusat, jika tidak ada DJJ beritahukan ibu dan keluarganya, lahirkan bayi dengan cara yang paling aman.
Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan
Rencana Asuhan atau perawatan
dengan klem di dua tempat kemudian potong diantaranya kemudian lahirkan bayi dengan segera.
Untuk kehamilan kembar tak terdeteksi
Kehamilan kembar tak terdeteksi
Nilai DJJ, jika bayi kedua dengan presentasi kepala segera turun, biarkan kelahiran berlangsung seperti pertama, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, baringkan ibu miring kiri, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan.
C. Kala III
Yaitu waktu untuk pelepasan dan pengeluaran uri. Setelah
bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat.
Beberapa menit kemudian berkontraksi lagi untuk melepas
plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6
sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau
dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai
pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Depkes,
2008).Penatalaksanaan kala III berdasarkan APN ada pada
langkah 27 sampai 41 (Kemenkes, 2013).
Asuhan pada kala III
27) Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi
lain dalam uterus (hamil tunggal)
28) Beritahukan kepada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan
29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan
oksitosin 10 IU di sepertiga paha atas bagian distal lateral
(lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin)
30) Dengan menggunakan klem, 2 menit setelah bayi lahir, jepit
tali pusat pada sekitas 3 cm dari pusat (umbilikus) bayi
(kecuali pada asfiksia neonatus, lakukan sesegera mungkin.
31) Potong dan ikat tali pusat, dengan satu tangan angkat tali
pusat diantara 2 klem tersebut (sambil lindungi perut bayi),
ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi
kemudian dilonggarkan yang telah dijepit kemudian lingkarkan
kembali benang ke sisi berlawanan dan laukuan ikatan kedua
menggunakan sampul kunci. Lepaskan klem dan masukkan
dalam larutan klorin 0,5 %.
32) Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit
bayi. Letakkan bayi dalam posisi tengkurap di dada ibu.
Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel dengan baik
didinding dada – perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara peyudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting
payudara ibu.
33) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering dan
pasang topi pada kepala bayi.
35) Lakukan satu tangan diatas kain yang ada di perut ibu, tepat
diepi atas simfisis dan tegangkan tali pusat ke arah dorso – kranial secara hati – hati.
36) Lakukan penegangan dan dorongan dorso kranial hingga
plasenta terlepas, lalu minta ibu meneran sambil menarik tali
pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas,
mengikuti poros jalan lahir dengan tetap melakukan tekanan
dorso – kranial.
37) Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelhairan
plasenta dengan menggunakan kedua tangan.
38) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan
masase uterus dengan meletakkan telapak tangan difundus
dan lakukan masase dengan gerakan melingkar secara
lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)
39) Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu
maupun ke janin dan pastikan bahwa selaputnya lengkap dan
utuh.
40) Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan
lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan
aktif.
41) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi
perdarahan pervaginam.
Yaitu dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam
postpartum pertama. Kala IV ini disebut sebagai kala pemantauan
untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan postpartum.
Beberapa hal mengalami perubahan dan perlu dipantau selama
kala IV antara lain TTV, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih
dan perdarahan (Depkes, 2008). Penatalaksanaan kala IV
berdasarkan APN ada pada langkah 42 sampai 58 (Kemenkes,
2013).
Asuhan pada kala IV
42) Mulai Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan memberi cukup
waktu untuk melakukan kontak kulit ibu – bayi (di dada ibu minimal 1 jam)
43) Setelah kontak kulit ibu – bayi dan IMD selesai : timbang dan ukur bayi, beri bayi salep mata antibiotik profilaksis (tetrasiklin
1 % atau antibiotika lain), suntikan vitamin K1 1 mg (0,5 ml
untuk sediaan 2 mg/mL) IM dipaha kiri anterolateral bayi,
pastikan suhu tubuh bayi normal 36,5 – 37,5 ºC, berikan gelang pengenal pada bayi yang berisi informasi nama, ayah,
ibu, waktu lahir, jenis kelamin, lakukan pemeriksaan untuk
melihat adanya cacat bawaan.
44) Satu jam setelah pemberian vit K1, berikan suntikan imunisasi
hepatitis B di paha kanan anterolateral bayi.
45) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan
pascasalin, setiap 15 menit pertama pascasalin, setiap 20 – 30 menit pada jam kedua pascasalin.
46) Lakukan asuhan yang sesuai untuk menatalaksana atonia
uteri jika uterus tidak berkontraksi dengan baik.
47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan
menilai kontraksi, mewaspadai tanda bahaya ibu, serta kapan
harus memanggil bantuan medis.
48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.
49) Periksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih ibu
setiap 15 menit selama 1 jam pertama pascasalin dan setiap
30 menit selama jam kedua pascasalin.
50) Periksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi
bernafas dengan baik (40 – 60 kali/menit) serta suhu tubuh normal (36,5 – 37,5ºC)
51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin
0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci peralatan setelah
didekontanminasi.
52) Buang bahan – bahan yang terkontamionasi ke tempat smpah yang sesuai.
53) Bersihkan badan ibu menggunakan air DTT, bersihkan sisa
cairan ketuban, lendir dan darah, bantu ibu memakai pakaian
yang bersih dan kering.
54) Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI,
anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan
55) Dekoontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.
56) Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5%,
balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin
0,5% selama 10 menit.
57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang
mengalir lkemudian keringkan dengan handuk kering dan
bersih.
58) Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang, -0periksa
tanda vital, dan asuhan kala IV) (Kemenkes RI, 2013; h. 36 – 49)
Tabel 2.5 Indikasi untuk tindakan atau rujukan segera selama persalinan kala III dan kala IV
Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan
Rencana Asuhan atau perawatan Plasenta Tanda atau gejala
retensio plasenta
Jika plasenta terlihat lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan lembut dan tekanan dorso kranial pada uterus minta ibu meneran agar plasenta keluar, setelah plasenta lahir : lakukan masase pada uterus dan periksa plasenta. Atau jika plasenta masih didalam uterus dan perdarahan minimal, berikan oksitosin 10 unit IM, pasang infus menggunakan jarum besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan RL atau NS, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan
Penilaian Temuan dari penilaian plasenta dan lakukan penanganan lanjutan, bila tidak memenuhi syarat plasenta manual di tempat atau tidak kompeten maka segera rujuk ibu ke fasilitas terdekat dengan kapabilitas
Tanda atau gejala avulsi (putus) : tali pusat putus atau plasenta tidak lahir
Palpasi uterus untuk menilai kontraksi, minta ibu meneran setiap kontraksi, setiap plasneta terlepas, lakukan periksa dalam hati
– hati, jika mungkinbcari tali pusat dan keluarkan plasenta dari vagina sambil melakukan tekanan dorso-kranial pada uterus, setelah plasenta lahir, lakukan masase uterus dan periksa plasenta, jika plasenta belum llahir dalam 30 menit tangani sebagai retensio plasenta.
Plasenta, perdarahan pervaginam
Tanda atau gejala bagian plasenta yang tertahan : bagian permukaan plasenta yang menempel pada ibu hilang, bagian selaput ketuban robek, perdarahan pasca persalinan, uterus berkontraksi
Lakukakn periksa dalam, keluarkan selaput ketuban dan bekuan darah yang mungkinmasih tertinggal, lakukan masase uterus, jika ada perdarahan hebat, ikuti langkah – langkah
Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan
Rencana Asuhan atau perawatan
ke fasilitas terdekat dengan kapabilitas
Tanda atau gejala syok : nadi cepat, lemah (110 kali/menit atau lebih), tekanan darah rednah (sistolik <90 mmHg), pucat, berkeringat atau dingin, kulit lembab, nafas cepat (>30 kali/menit), cemas, kesadaran menurun atau tidak sadar, produksi urine sedikit (kuranng dari 30 cc/jam)
Baringkan miring kiri, jika mungkin naikkan kedua
tungkai untuk
meningkatkan curah darah ke jantuung, pasang infus
dengan jarum
menggunakan jarum besar (ukuran 16 atau 18) dan segera rujuk ibu ke fasilitas terdekat dengan kapabilitas
sampai dengan 42 hari pascapersalinan (Kemenkes RI, 2013).
Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah
plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali
seperti keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung
selama kira- kira 6 minggu (Sulistyawati, 2009).
Masa nifas adalah masa setelah keluarnya placenta sampai
masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari (Ambarwati,
2010).
Periode post natal adalah waktu penyerahan dari selaput dan
plasenta (menandai akhir dari periode intrapartum) menjadi kembali
ke saluran reproduktif wanita pada masa sebelum hamil. Periode ini
disebut juga masa puerperium (Varney, 1997, hal.:549).
1) Adaptasi masa nifas
1) Uterus (Sulistyawati 2009)
Bayi lahir : Setinggi pusat
Setelah lahir : 2 Jari dibawah pusat
Satu minggu setelah lahir : Pertengahan pusat-simpisis
Dua minggu setelah lahir : Tidak teraba diatas simpisis
Enam minggu setelah lahir : Bertambah kecil
Delapan minggu setelah lahir : Tidak teraba
2) Serviks
Serviks mengalami involusi bersama-sama uterus.
Setelah persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki oleh
dua hingga tiga jari tangan, setelah 6 minggu nifas, serviks
menutup.Serviks tidak pernah kembali ke keadaan sebelum
hamil (nulipara) yang berupa lubang kecil seperti mata
jarum. Serviks hanya kembali pada keadaan tidak hamil
yang berupa lubang yang sudah sembuh, tertutup tapi
berbentuk celah (Bahiyatun, 2009).
Setelah melahirkan vagina tetap terbuka lebar,
mungkin mengalami beberapa derajat edema dan memar
serta celah pada introitus. Setelah satu atau dua hari
pertama pascapartum tonus otot vagina kembali, celah
vagina tidak lebar dan vagina tidak lagi edema. Sekarang
vagina menjadi berdinding lunak, lebih besar dari biasanya
dan umumnya longgar. Ukurannya menurun dan kembalinya
rugae vagina sekitar minggu ketiga pascapartum.
Ruang vagina selalu sedikit lebih besar dari pada
sebelum kelahiran pertama. Akan tetapi, latihan
pengencangan otot perineum akan mengembalikan
tonusnya dan memungkinkan wanita secara
perlahan
mengencangkan
vaginanya.
Pengencangan
ini
sempurna pada akhir puerperium dengan latihan setiap
hari (Varney, 2008).
4) Lokhea
Lokhea adalah eskresi cairan rahim selama masa
nifas yang dapat terbagi menjadi 3, yaitu:
(1) Lokhea Rubra yaitu cairan yang keluar pada hari ke 1
sampai hari ke 4 postpartum, berwarna merah karena
mengandung darah dan desidua.
(2) Lokhea Serosa yaitu cairan yang keluar pada hari ke 4
sampai hari ke 8 postpartum, berwarna merah muda,
kuning, lokhea serosa mengandung cairan serosa
(3) Lokhea Alba yaitu cairan yang keluar pada hari ke 8
sampai hari ke 12, warna lokhea alba adalah putih
kream dan terutama mengandung leukosit dan desidua
(Bahiyatun, 2009).
5) Hemokonsentrasi
Pada masa hamil didapat hubungan pendek sirkulasi
ibu dan plasenta. Setelah melahirkan, volume darah pada
ibu relative akan bertambah. Keadaan ini akan
menyebabkan perubahan pada jantung, sehingga
menimbulkan dekompensasi kordis pada penderita-
penderita vitium kordis. Keadaan ini dapat di atasi dengan
adanyahemokonsentrasi sehingga volume darah kembali
seperti sediakala. Umumnya hal ini akan terjadi pada hari ke
3 sampai hari ke 15 postpartum (Sulistyawati, 2009).
6) Rahim dan Involusi
Rahim biasanya akan mengecil dan membesar
dengan menambah atau mengurangi jumlah sel pada wanita
yang tidak hamil, berat rahim sekitar 30 gram, kurang lebih
sebesar telur ayam atau bebek (Bobak, 2005).
7) Laktasi
Setelah proses persalinan, tepatnya setelah plasenta
keluar akan timbul rangsangan untuk memicu laktasi.
Laktasi didukung oleh dua jenis hormon yang sangat penting
tersebut dirangsang oleh hisapan bayi pada putting susu
saat menyusui. Semakin sering menyusui akan
memperlancar pengeluaran kedua hormon tersebut.
Penanda biokimiawi mengindikasikan bahwa proses laktasi
pascapersalianan dimulai sekitar 30-40 jam setelah
melahirkan, tetapi biasanya para ibu baru merasakan
payudara penuh sekitar 50-73 jam (2-3 hari) setelah
melahirkan. Artinya, memang produksi ASI sebenarnya tidak
langsung setelah melahirkan (Saleha, 2009).
8) Sistem Urinarius
Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan
setelah wanita melahirkan. Diperlukan kira- kira 2 sampai 8
minggu supaya hipotonia pada kehamilan dan dilatasi uterus
serta pelvis ginjal kembali ke keadaan sebelum hamil. Pada
sebagian kecil wanita dilatasi traktus urinarius bisa menetap
selama 3 bulan (Bobak, 2005).
9) Perubahan Tanda-tanda Vital
(1) Suhu Badan
Selama 24 jam pertama, suhu mungkin meningkat
menjadi 38o C, sebagai akibat meningkatnya kerja otot,
dehidrasi dan perubahan hormonal. Jika terjadi
peningkatan suhu 38o C yang menetapkan 2 hari setelah
24 jam melahirkan,maka perlu dipikirkan adanya infeksi
infeksi saluran kemih, endometriosis (peradangan
endometrium), pembengkakan payudara, dan lain- lain.
(2) Denyut nadi
Dalam periode waktu 6-7 jam sesudah melahirkan,
sering ditemukan adanya bradikardia 50-70 kali permenit
(normalnya 80-100 kali permenit) dan dapat berlangsung
sampai 6-10 jam setelah melahirkan. Keadaan ini bisa
berhubungan dengan penurunan usaha jantung,
penurunan volume darah yang mengikuti pemisahan
plasenta dan kontraksi uterus dan peningkatan stroke
volume. Takhikardia kurang sering terjadi, bila terjadi
hubungan peningkatan kehilangan darah.
(3) Tekanan Darah
Selama beberapa jam setelah melahirkan, ibu
dapat mengalami hipotensi orthostik (penurunan 20
mmHg) yang ditandai dengan adanya pusing segera
setelah berdiri, yang dapat terjadi hingga 46 jam
pertama. Hasil pengukuran tekanan darah seharusnya
tetap stabil setelah melahirkan. Penurunan tekanan
darah bisa mengindikasikan penyesuaian fisiologis
terhadap penurunan tekanan intravena atau adanya
hipovolemia sekunder yang berkaitan dengan hemorhagi
uterus.
Pada umumnya respirasi lambat atau bahkan
normal. Hal ini terjadi karena ibu dalam keadaan
pemulihan/ dalam kondisi istirahat. Bila ada respirasi
cepat postpartum (>30x per menit) mungkin karena
ikutan tanda- tanda syok (Maryunani, 2009).
10) Adaptasi Psikologis
Menurut Bahiyatun (2009), adaptasi psikologis dapat
diklasifikasikan menjadi 3 antara lain:
(1) Fase Taking In
Fase ini merupakan periode ketergantungan yang
berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua
setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus asuhan ibu
terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman selama
proses persalinan sering berulang diceritakan, kelelahan
membuat ibu membutuhkan waktu yang cukup dalam
istirahat untuk mencegah gejala kurang tidur. Pada fase
ini ibu menjadi mudah tersinggung,oleh karena itu
kondisi ibu perlu dipahami dengan menjaga komunikasi
yang baik.
(2) Fase Taking Hold
Fase ini berlangsung selama 3-10 hari setelah
melahirkan. Pada masa taking hold ibu merasa khawatir
akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam
merawat bayi. Ibu akan berusaha keras untuk
menggendong dan menyusui. Ibu agak sensitif dan
merasa tidak mahir dalam melakukan hal tersebut,
sehingga cenderung menerima nasihat dari bidan karena
ia terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritikan
yang bersifat pribadi.
(3) Fase Letting Go
Fase ini merupakan fase menerima tanggung
jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari
setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri
dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk
merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini.
2. Kebutuhan dasar ibu nifas
a. Nutrisi dan cairan
Menurut ( salehah, 2009: 71) pada masa nifas masalah diet
perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang
baik dapat menpercepat penyembuhan ibu dan sangat
memengaruhi susunan air susu. Diet yang diberikan harus
bermutu, bergisi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak
mengandung cairan.
Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi
sebagai berikut.
1) Mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari
2) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein,
mineral, dan vitamin yang cukup.
4) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi,
setidaknya selama 40 hari pascapersalinan.
5) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan
vitamin A kepada bayinya melalui ASI.
3. Program dan Kebijakan Teknis Masa Nifas
Menurut Saifuddin (2006), paling sedikit 4 kali kunjungan masa
nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan untuk
mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang
terjadi.Kunjungan tersebut dapat terinci sebagai berikut:
Tabel 2.6 Program kebijakan teknis masa nifas
Kunjungan Waktu Tujuan
1 6-8 jam pasca persalinan
1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.
2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan rujuk jika perdarahan berlanjut. 3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 4) Pemberian ASI awal.
5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.
6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.
Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.
2 6 hari pasca persalinan
1) Memastikan involusio uteri berjalan normal: uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal dan tidak bau.
2) Menilai adanya tanda- tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal.
cukup makanan, cairan dan istirahat.
4) Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan tidak memperlihatkan adanya tanda- tanda penyulit.
5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari- hari. 3 2 minggu pasca
persalinan
Sama seperti diatas (6 hari setelah persalinan)
4 6 minggu pasca persalinan
1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit- penyulit yang ia atau bayi alami.
2) Memberikan konseling untuk KB secara dini.
Sumber : Saifuddin (2006)
Kunjungan postpartum mempunyai keuntungan bagi bidan agar
dapat merencanakan konseling kesehatan sedangkan keterbatasan
kunjungan terletak pada biaya, jumlah bidan dan keamanan saat
berkunjung ke rumah ibu. Efektivitas asuhan masa nifas dapat diukur
dari proses pemulihan fisiologis ibu, pengetahuan dasar tentang dasar
teknik menyusui yang dimiliki ibu, kemampuan ibu dalam melakukan
perawatan yang tepat untuk menjaga dirinya dan bayinya serta
kemampuan ibu untuk berinteraksi terhadap bayi dan keluarganya
(Aisyaroh, 2010).
Tabel 2.7 Tinggu fundus uteri dan berat uterus normal
Involusi TFU Berat Uterus
Bayi Lahir Setinggi pusat 1.000 gr
Plasenta lahir 2 jari bawah pusat 750 gr 1 minggu Pertengahan pusat simfisis 500 gr 2 minggu Tidak teraba diatas simfisis 300 gr