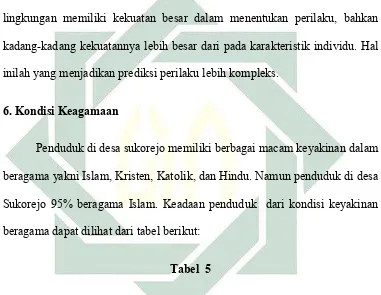INTERAKSI SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA
(Studi Kasus Jama’ah Shalawat Wahidiyah dan Jama’ah Nahdliyin
Di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo)
Skripsi
Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Disusun Oleh
:
Brenda Fadkhuli Jannahti
NIM. E02213004
PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN
ABSTRAK
Brenda Fadkhuli Jannahti E02213004, Interaksi Sosial Antarumat Beragama
(Studi Kasus Jama’ah Shalawat Wahidiyah dan Jama’ah Nahdliyin yang berada di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo).
Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui dua persoalan, yaitu pertama, untuk mendeskripsikan sejarah,
ajaran, dan aktivitas keagamaan jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin. Dimana masing-masing jama’aah ini memiliki sejarah , ajaran, dan aktivitas yang berbeda, akan tetapi dua jama’ah tersebut saling menghormati, meskipun
mempunyai pemahaman yang berbeda. Kedua, untuk menganalisis bentuk
interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah dengan jama’ah Nahdliyin (NU). Dimana bentuk interaksi sosial mempunyai makna sebagai kegiatan individu atau kelompok individu dalam rangka pertentangan, pemanfaatan, partisipasi, dan penyesuaian dengan individu atau kelompok individu lainnya (lingkungannya). Manfaat dari penelitian ini sebagai sumber informasi khususnya dalam bermasyarakat. dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan yang menggambarkan suatu kenyataan sosial dalam masyarakat. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. metode ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk melihat, mengamati dan menyelidiki fakta-fakta yang terjadi, setelah penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. sumber data dari penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang di jadikan informan yaitu jama’ah lembaga keagamaan tersebut dan tokoh masyarakat desa
Sukorejo. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Interaksi
Sosial Antarumat Beragama (Studi kasus Jama’ah Wahiddiyah dan Jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo, Kab. Sidoarjo) bahwa Interaksi sosial sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan cara berinteraksi dapat membuat kesejahteraan hidup bagi setiap individu, bahkan interaksi sosial yang baik dapat mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Dengan cara berinteraksi kepada lembaga keagamaan lain dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Oleh karena itu adanya interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.
DAFTAR ISI
SAMPUL LUAR...
SAMPUL DALAM...i
PERSETUJUAN PEMBIMBING...ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI ...iii
PERNYATAAN KEASLIAN...iv
MOTTO...v
ABSTRAK...vi
PERSEMBAHAN...vii
KATA PENGANTAR...viii
DAFTAR ISI...x
DAFTAR TABEL...xi
xi BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah...1
B. Rumusan Masalah...6
C. Tujuan Penelitian...6
D. Manfaat Penelitian...6
E. Tinjauan Pustaka...7
F. Metode Penelitian...9
G. Sistematika Pembahasan...14
BAB II: LANDASAN TEORI A. Agama 1. Pengertian Agama...16
2. . Fungsi Agama dalam Masyarakat...18
3. Peran Agama di Masyarakat...20
B. Interaksi Sosial 1. Pengertian Interaksi Sosial...21
2. Unsur Dasar Interaksi Sosial...23
3. Ciri-ciri Interaksi Sosial...25
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial...25
5. Faktor-faktor yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial...28
6. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial...30
C. Teori Agama Perspektif Emile Durkheim...35
A. Gambaran Wilayah Desa Sukorejo Sidoarjo
1. Letak Geografis...41
2. Kondisi Demografis...41
3. Kondisi Pendidikan...43
4. Kondisi Ekonomi...44
5. Kondisi Sosial...45
6. Kondisi Keagamaan...45
B. Profil Lembaga Keagamaan 1. Lembaga Jama’ah Shalawat Wahidiyah...47
2. Lembaga Jama’ah Nahdliyin...48
BAB IV: SEJARAH, AJARAN, DAN AKTIVITAS LEMBAGA KEAGAMAAN A. Sejarah dan Ajaran Jama’ah Shalawat Wahidiyah 1. Sejarah Jama’ah Shalawat Wahidiyah...49
2. Ajaran Jama’ah Shalawat Wahidiyah...52
3. Aktivitas Keagamaan Jama’ah Shalawat Wahidiyah...60
B. Sejarah dan Ajaran Jama’ah Nahdliyin 1. Sejarah Jama’ah Nahdliyin...61
xiii
3. Aktivitas Keagamaan Jama’ah Nahdliyin...69
BAB V: BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL JAMA’AH WAHIDIYAH DAN JAMA’AH NAHDLIYIN A. Bidang Keagamaan...74
B. Bidang Sosial...76
C. Bidang Ekonomi...76
D. Bidang Pendidikan...77
BAB VI: ANALISA DATA A. Jama’ah Shalawat Wahidiyah 1. Sejarah Jama’ah Shalawat Wahidiyah...79
2. Ajaran Jama’ah Shalawat Wahidiyah...81
3. Aktivitas Jama’ah Shalawat Wahidiyah...82
4. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial...83
B. Jama’ah Nahdliyin 1. Sejarah Jama’ah Nahdliyin...83
2. Ajaran Jama’ah Nahdliyin...84
3. Aktivitas Jama’ah Nahdliyin...85
BAB VII: PENUTUP
A. Kesimpulan...89
B. Saran...90
DAFTAR PUSTAKA...92
1 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Makna kata agama sering menimbulkan banyak kontroversi. Agama dapat
dipandang sebagai kepercayaan dan keyakinan yang diyakini kebenarannya sehingga
menjadi kepercayaan keagamaan atau kepercayaan religius. Mengadakan
upacara-upacara pada momen tertentu, dalam agama dinamakan Ibadah dan dalam antropologi
dinamakan ritual dan mempercayai sesuatu yang suci atau sakral sebagai ciri khas
kehidupan beragama. Adanya aturan terhadap kehidupan individu dan kehidupan
bermasyarakat, yang berhubungan dengan alam linkungannya atau adanya aturan
kehidupan yang dipercayai berasal dari Tuhan. Hal tersebut termasuk ciri kehidupan
beragama.
Upacara keagamaan dan kepercayaan itu dilakukan dan dihayati secara
khusuk, khidmat, cinta, dan intens sekali. Penghayatan ruhaniah terhadap berbagai
tingkatannya ini, dari sekedar khusyuk atau cinta mendalam dinamakan aspek mistik
atau keruhanian dalam kehidupan beragama dan ditemukan di setiap kehidupan
masyarakat dan individu. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama itu
aneh tapi nyata, dan merupakan gejala universal, ditemukan dimanapun dan
kapanpun dalam kehidupan individu dan masyarakat.1
2
Adapun hal-hal yang mendorong manusia untuk melaksanakan
aktivitas-aktivitas yang bersifat keagamaan diantarannya adalah karena adanya emosi dan
getaran jiwa yang sangat mendalam yang disebabkan rasa takut, terpesona pada
sesuatu yang gaib dan keramat, di samping juga adanya harapan-harapan yang
mengiringi perjalanan kehidupannya. Perasaan-perasaan itu terpancar dari daya
misterius yang merupakan prinsip kemenyatuan dengan alam semesta.
Adanya sikap toleransi beragama merupakan suatu elemen penting dalam
kehidupan beragama. Sehingga ketika adanya sikap toleransi dan kesadaran dalam
beragama akan terhindar dari konflik dan terciptalah sebuah perdamaian. Karena pada
dasarnya konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan yang dibawa individu dalam suatu
interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, adat istiadat,
keyakinan dan lain sebagainya. Akan tetapi adanya suatu konflik dalam sebuah
organisasi lembaga masyarakat atau komunitas masyarakat merupakan situasi yang
wajar, bahkan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar
anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik tersebut hanya akan
hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang ajaran agama memiliki pengaruh
yang sangat besar dalam menciptakan pola pemahaman dan citra keagamaan di
tengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya informasi inilah yang lebih banyak
dijadikan titik awal dari kesadaran dan pemahaman keagamaan masyarakat. Maka
3
memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam menghiasi wajah agama di masyarakat.2
Dalam Setiap keagamaan biasanya mempunyai lembaga-lembaga tersendiri.
keikutsertaan lembaga-lembaga keagamaan baik formal maupun non formal sangat
besar peranannya dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai religius yang sudah ada
di tengah-tengah masyarakat.
Lembaga-lembaga keagamaan tersebut adalah Jama’ah Wahidiyah, yang
merupakan salah satu bentuk organisasi keagamaan yang berkarakterkan sufistik.
Organisasi lembaga ini merupakan salah satu di antara tarekat yang ada di Indonesia.
Keberadaanya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mensosialisasikan
ajaran-ajaran agama Islam, yang mana ajaran tarekat dalam beberapa ritualnya dapat
memberikan pembinaan karakter (kepribadian) kepada setiap pengikut dan
anggotanya. Dengan arti lain tarekat itu merupakan bentuk pelaksanaan ibadah
dengan menjalankan syari’at Islam dan dikerjakan secara istiqamah atau tekun
melalui jalan tertentu yang sesuai syari’at Islam.
Merupakan suatu kenyataan di Indonesia, banyak lembaga atau organisasi
keagamaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.
Lembaga atau organisasi keagamaan tersebut mempunyai berbagai macam
aliran/ajaran dan metode serta penyebutan nama-nama yang berbeda, sebagai contoh
adalah lembaga keagamaan jama’ah Wahidiyah. Pusat atau perkumpulan lembaga
tarekat ini tumbuh berkembang pesat di Jawa Timur, di desa Kedunglo Kota Kediri.
4
Yang mana perkembangannya sampai ke Desa Sukorejo Kota Sidoarjo, dan
keberadaan jama’ah Wahidiyah ini turut mewarnai pola dan perilaku masyarakatnya,
terutatama dalam prilaku keagamaan dan budayanya.
Lembaga keagamaan lain yakni jama’ah Ahlussunnah wal Jama’ah atau NU
(Nahdlatul Ulama). Organisasi yang dipimpin oleh para kyai dan ulama yang basis
kekuatan masanya terkonsentrasi di pesantren-pesantren yang memiliki
momentum-momentum historis sepanjang gerakan-gerakannya.3 NU (Nahdlatul Ulama)
merupakan bentuk organisasi keagamaan yang berkarakterkan tasawuf (sufisme). NU
(Nahdlatul Ulama) dikenal telah mampu mengembangkan suatu organisasi yang
stabilitasnya sangat mengagumkan, walaupun sering menghadapi
tantangan-tantangan dari luar yang cukup berat. Modal utamanya adalah karena para kyai
memiliki memiliki suatu perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (highly
developed social sense) dan selalu menghormati tradisi.4
Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat terdapat tradisi-tradisi
keagamaan yang dimiliki oleh individu menjadi bersifat kumulatif dan kohesif, yang
menyatukan keanekaragaman interpretasi dan sistem-sistem keyakinan keagamaan.
Penyatuan keanekaragaman itu dapat terjadi karena, pada hakikatnya, dalam setiap
kehidupan berkelompok terdapat pola-pola interaksi tertentu yang melibatkan dua
orang atau lebih, dan dari pola-pola tersebut para anggotanya secara bersama
memiliki satu tujuan atau tujuan-tujuan utama yang diwujudkan sebagai
3 Faisal Ismail, NU Gusdurisme dan Politik Kiai, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 11
5
tindakan berpola. Itu dimungkinkan karena kegiatan-kegiatan berkelompok tersebut
terarah atau terpimpin berdasarkan atas norma-norma yang disepakati bersama, yang
terwujud dari kehidupan berkelompok.
Kelompok-kelompok tersebut terwujud karena adanya kesamaan tujuan-tujuan
yang ingin dicapai oleh para anggotanya, dan mereka merasa bahwa dalam kelompok
itulah tujuan-tujuan yang ingin dicapai akan terlaksana dengan lebih baik. Dalam
kelompok keagamaan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para anggotannya
didasari oleh keyakinan keagamaan mereka, suatu keyakinan yang berisikan
penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk untuk memahami gejala-gejala dan
pengalaman-pengalaman; penjelasan yang menghasilkan berbagai bentuk rasional
yang masuk akal dan menghasilkan penemuan-penemuan mengenai
kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia di mana
pun, tidak selamanya mulus; selalu dibayangi oleh kegagalan, frustasi, dan rasa
ketidakadilan. Agama menjadi fungsional dalam struktur kehidupan manusia dalam
usaha untuk mengatasi dan menetralkan bayangan-bayangan buruk tersebut.
Usaha-usaha menetralkan dan mengatasi hal-hal buruk dalam kehidupan manusia yang
dilakukan dalam kelompok dirasakan lebih efektif dan meyakinkan dibandingkan
dengan usaha-usaha secara pribadi.5
6
Berdasarkan uraian di atas penulis tergugah untuk mengadakan suatu penelitian
yang lebih jauh tentang Interaksi Sosial Antar Umat Beragama; Jama’ah Wahidiyah
dan Jama’ah Nahdliyin yang berada di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah, ajaran dan aktivitas keagamaan jama’ah Wahidiyah dan
jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah dan jama’ah
Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan sejarah, ajaran dan aktivitas keagamaan jama’ah
Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah
dengan jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo .
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Masyarakat
a. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi khususnya dalam bermasyarakat.
b. Bagi mahasiswa akan dapat membantu untuk mengetahui arti perbedaan dalam
praktik keagamaan.
c. Diharapkan menjadi respon positif sebagai kajian ilmiah terutama bagi mahasiswa
7
2. Bagi Peneliti
a. Bagi peneliti akan sangat bermanfaat sebagai bekal untuk memahami perbedaan
melakukan praktik keagamaan.
b. Penulis akan dapat memperluas cakrawala tentang ajaran yang ada pada jama’ah
Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin.
c. Dengan adanya kajian ini, diharapkan akan mampu memberikan manfaat yang
besar, baik bagi penulis maupun semua orang yang menaruh perhatian besar
terhadap agama, sebagai wujud cinta kepada Tuhan.
E. Tinjauan Pustaka
Mengetahui tinjauan terdahulu terhadap tarekat Wahidiyah ini sudah pernah
diteliti oleh Nurul Rochani, mahasiswa UIN Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin tahun
2014.6 Penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologi agama.
Pembahasannya meliputi organisasi Sholawat Wahidiyah kedudukan organisasi di
daerah tersebut, aktifitas organisasi Wahidiyah kepada masyarakat tersebut (bidang
agama, sosial, budaya, dan pendidikan).
Akan tetapi dalam hal ini penulis membahas dan menulis tentang interaksi
sosial antara jama’ah Wahidiyah dengan jama’ah Nahdliyin, serta kondisi sosial
masyarakat, teologi dan ajaran, model pengamalan keagamaan serta budaya tarekat
Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi.
8
Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data
sekunder, diantaranya:
1. Lailatun Naqiyah, Kumpulan Teks Kuliah Wahidiyah, (Kediri: DPW Wahidiyah, 1999) buku ini membahas tentang hal menjernihkan hati Sholawat, ajaran
Wahidiyah, hal adab, hal mujahadah, hal tangis dalam mujahadah dan penyiaran
Sholawat Wahidiyah.
2. DPP PSW, Pedoman Pokok-pokok Sholawat Sahidiyah, (Jombang: TA, 1997) buku ini membahas tentang ajaran Wahidiyah , pokok-pokok ajaran Shalawat
Wahidiyah, kebaikan/keuntungan, kerugian/kecemasan di dalam wilayah dan
lain-lain.
3. H. Qomari Mukhtar, Sejarah dan Awal Perjuangan Wahidiyah, (Kediri Kedunglo,
1997) buku ini membahas tentang mengenal akhlakul karimah mualif Wahidiyah,
sejarah ringkas lahirnya Wahidiyah, sekilas peristiwa yang terjadi di awal
perjuangan Wahidiyah, hikayah-hikayah yang penuh hikmah, mutiara hikmah
dawuh-dawuh mualif Sholawat Wahidiyah.
4. Faisal Ismail, NU Gusdurisme dan Politik Kiai, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
buku ini menceritakan sejarah Nahdlatul ulama serta organisasi yang ada di
Nahdlatul Ulama.
5. Ridwan, Paradigma Politik NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) buku ini melihat keterkaitan NU secara idiologis mengenai rancang bangun pemikiran NU.
9
orang NU sendiri, pendasarannya yang kukuh yang diambil dari kitab-kitab
kuning.
7. Soeleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1993) buku ini mempelajari tentang kemasyarakatan, baik mengenai aspek
struktural maupun prosesesualnya.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data
dan analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang diahadapi, sebagai
rencana pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diselidiki.7 Adapun metode
yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian Kualitatif. Menurut Bagdan
dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data diskriptif, berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati.8 Dan penelitian diskriptif merupakan penelitian non hipotesis,
sehingga dalam melangkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis tersebut.
Metode diskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
“Dilakukan pada latar alamiah atau pada kontek dari suatu keutuhan (unity) manusia (peneliti atau dengan bantuan orang lain), sebagai alat pengumpul data utama, menggunakan metode kualitatif, menggunakan metode analisa data secara induktif, lebih menghendaki arah bimbingan, penyusunan teori berasal dari data.
7 Arief Farhan, Pengatar Penelitian dalam Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 50.
10
Sedang data yang berupa kata-kata bergambar lebih banyak mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data desain yang bersifat sementara, juga menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dan dirundingkan, disepakati oleh manusia yang akan dijadikan objek atau sumber data”.9
Sedangkan ciri diskriptif menurut Jalaluddin Rahmat “Titik beratnya pada observasi dan suasana alamiah (Naturalistic setting) peneliti betindak sebagai pengamat, dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mengamatinya dalam buku observasinnya”.10
Agar data yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,
maka diperlukan metode tertentu dalam melakukan penelitian. Dengan adanya
metode maka diharapkan suatu penelitian lebih terarah dan mudah dikaji. Adapun
metode yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, karena
metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap
suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Agama. Dalam hal
ini meliputi:
a. Kondisi sosial masyarakat (baik ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan).
b. Pengaruh ajaran tarekat Wahidiyah dan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (NU)
dalam kehidupan masyarakat.
c. Tokoh Agama jama’ah Wahidiyah, sebagai koordinator Wahidiyah.
9 Ibid., 49.
11
d. Anggota (pengikut Wahidiyah) Jama’ah Wahiddiyah.
e. Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, sebagai koordinator Nahdliyin.
f. Anggota Jama’ah Nahdlatul Ulama.
g. Tokoh masyarakat dan masyarakat desa Sukorejo pada umumnya.
h. Bentuk interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah dengan jama’ah Nahdliyin.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data primer dan
sumber data sekunder.
a. Sumber Primer
Sumber data yang bersifat utama dan terpenting untuk mendapat informasi yang
diperlukan oleh peneliti lapangan di mana peneliti terjun langsung untuk mencari data
atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terutama informasi
dari tokoh jama’ah Wahidiyah dan tokoh jama’ah Nahdliyin.
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat menunjang dan melengkapi
sumber data primer yaitu menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku
kepustakaan dan informasi dari tokoh masyarakat desa sekitar.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik metode
12
menggunakan data literatur, yaitu bahan-bahan yang bersifat teoritis, bersumber dari
buku-buku atau majalah yang berkaitan dengan topik pembahasan.
Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode Observasi: yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang
dimiliki.11 Dalam penelitian ini hal yang perlu di observasi meliputi:
1) Bagaimana sejarah dan aktivitas keagamaan antara jama’ah Wahidiyah dan
jama’ah Nahdliyin di desa Sukorejo.
2) Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya bentuk interaksi sosial antar umat
beragama antara jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin di Desa
Sukorejo Kab. Sidoarjo.
3) Adapun cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah
dengan ikut berperan aktif dan membaur diri ke dalam pergaulan masyarakat
desa dan anggota lembaga keagamaan di wilayah penelitian.
Metode observasi juga memerlukan adanya data lapangan, yaitu sumber data yang
dapat diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa dokumen dan arsip-arsip penting
sebagai pelengkap dari data. Sumber-sumber ini berasal dari:
a) Jumlah penduduk yang mengikuti jama’ah Wahidiyah.
b) Jenis kegiatan keagamaan jama’ah Wahidiyah.
c) Sarana tempat peribadatan Wahidiyah.
13
d) Jumlah penduduk yang mengikuti jama’ah Nahdliyin.
e) Jenis kegiatan keagamaan jama’ah Nahdliyin.
f) Sarana tempat peribadatan jama’ah Nadhliyin.
b. Metode Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak
yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.12
Wawancara ini dibutuhkan dalam rangka mengkaji perihal:
1) Bagaimana pendapat masyarakat yang mengikuti ajaran Nahdliyin terhadap
jama’ah tarekat Wahidiyah, serta bagaimana pendapat masyarakat yang
mengikuti ajaran Wahidiyah terhadap jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo.
2) Bagaimana tanggapan anggota jama’ah Wahidiyah dalam menjalankan
ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.
3) Serta bagaimana syarat-syarat dan ketentuan menjadi anggota Jama’ah
Wahidiyah dan menjadi jama’ah Nahdliyin.
Metode Wawancara ini meliputi semua personil yang ada di tempat penelitian dan
yang menjadi responden terdiri dari:
a) Tokoh Agama Wahidiyah, sebagai koordinator jama’ah Wahidiyah.
b) Tokoh Agama Nadhliyin, sebagai koordinator jama’ah Nahdliyin.
c) Anggota (pengikut Wahidiyah) Jama’ah Wahidiyah.
d) Anggota Jama’ah Nahdliyin.
e) Tokoh masyarakat Desa Sukorejo pada umumnya.
14
3. Teknik Analisa Data
Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisa data, sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas. Salah satu dari pokok penelitian kualitatif adalah
analisisnya mudah dilakukan semenjak pengumpulan data dan untuk selanjutnya baru
dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan.
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya
adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan denga jalan abstraksi, kemudian
menyusun dalam satuan-satuan dan dikategorikan pada langkah selanjutnya. Juga
tidak mengabaikan prinsip berfikir induktif dan deduktif yang akan digunakan secara
proposional dalam proses analisa data.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan sistematika yang jelas maka pada proposal pengajuan judul
skripsi ini penulis menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika
pembahasan terdiriri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:
Bab I pendahuluan, data pada bab ini di uraikan tentang latar belakang
15
telaah kepustakaan, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan
daftar pustaka.
Bab IIBerisi tentang pengertian agama, pengertian tentang interaksi sosial dan
kajian teori yang digunakan untuk menguatkan penelitian. Dalam bab ini peneliti
menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan interaksi sosial antar umat beragama,
yakni antara jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin.
Bab III Berisi tentang gambaran umum desa sukorejo yang meliputi letak
geografis, kondisi demografis, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
Bab IV berisi tentang pembahasan pokok yang terdiri dari tiga sub pokok
bahasan a) sejarah berdirinya jama’ah Wahidiyah dan Nahdlatul Ulama di Desa
Sukorejo. b) pembahasan tentang ajaran anggota jama’ah Wahidiyah dan jama’ah
Nahdlatul Ulama terhadap ajaran-ajaran yang sudah di lakukan. c) aktivitas
keagamaan jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdlatul Ulama.
Bab V berisi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial jama’ah Shalawat
Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin, yang meliputi aspek bidang keagamaan,
pendidikan, ekonomi, sosial budaya.
Bab VI Merupakan penyajian dan analisa data yang terdiri dari:
a) sejarah jama’ah Wahidiyah dan Nahdlatul Ulama di Desa Sukorejo. b) ajaran
jama’ah Wahidiyah dan Nahdlatul Ulama. c) aktivitas jama’ah Wahidiyah dan
Nahdlatul Ulama. d) kondisi sosial masyarakat atau bentuk-bentuk interaksi sosial
16
Bab VII Merupakan pembahasan yang terakhir dalam skripsi ini yang berisikan
17 BAB II
LANDASAN TEORI
A. Agama
1. Pengertian Agama
Agama dipandang sebagai institusi yang mempunyai tugas (fungsi)
agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik dalam lingkup lokal, regional,
maupun nasional. Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan ialah daya
guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga eksistensi dan
fungsi agama (agama-agama), cita-cita masyarakat (akan keadilan, dan
kedamaian, dan akan kesejahteraan jasmani dan rohani) dapat terwujud.1
Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur
dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.
Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan
untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain.
Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna, dan
juga perasaan takut. Meskipun perhatian tertuju sepenuhnya kepada adanya
suatu dunia yang tidak dapat dilihat (akhirat), namun agama (juga)
melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.
Agama senantiasa dipakai untuk menanamkan keyakinan baru ke dalam hati.
18
Namun demikian agama juga berfungsi melepaskan belenggu-belenggu adat
atau kepercayaan manusia.2
Secara lebih khusus, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem
keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu
kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon
terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Sebagai
suatu sistem keyakinan, agama berbeda dari sistem-sistem keyakinan atau
isme-isme lainnya karena landasan keyakinan keagamaan adalah pada konsep
suci (sacred) yang dibedakan dari, atau dipertentangkan dengan yang duniawi
(profane), dan pada yang gaib atau supranatural (supernatural) yang menjadi
lawan dari hukum-hukum alamiah (natural).
Agama, sebagai sebuah sistem keyakinan, berisikan ajaran dan
petunjuk bagi para penganutnya agar diberi keselamatan dalam kehidupan
setelah mati. Karena itu juga keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai
berorientasi pada masa yang akan datang. Dengan cara mengikuti
kewajiban-kewajiban keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan agama
yang dianut dan diyakininya. Dan salah satu perbedaan yang ada dalam
agama, yang berbeda dari isme-isme lainnya, adalah penyerahan diri secara
total kepada Tuhannya. Penyerahan diri ini tidak terwujud dalam bentuk
ucapan melainkan dalam tindakan-tindakan keagamaan dan bahkan juga
dalam tindakan-tindakan duniawi sehari-hari. Tidak ada satu agama pun yang
19
tidak menuntut adanya penyerahan diri secara total dari para penganut atau
pemeluknya, termasuk juga agama-agama lokal yang di Indonesia
digolongkan sebagai religi atau kepercayaan.
Dapat dikatakan bahwa agama merupakan sistem keyakinan yang
dipunyai secara individual yang melibatkan emosi-emosi dan
pemikiran-pemikiran yang sifatnya pribadi, dan yang diwujudkan dalam
tindakan-tindakan keagamaan (upacara, ibadat, dan amal ibadah) yang sifatnya
individual ataupun kelompok dan sosial yang melibatkan sebagian atau
seluruh masyarakat. Bahkan dalam hal pahala, misalanya, pahala yang lebih
banyak adalah dalam kegiatan beribadat secara berjamaah dibandingkan
dengan kegiatan ibadat secara individual. Kegiatan-kegiatan keagamaan
dalam bentuk berjamaah, kongregasi atau upacara-upacara keagamaan dalam
kelompok amat penting dalam setiap agama.3
2. Fungsi Agama dalam Masyarakat
Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang unsur-unsurnya
saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan salah satu bagian
akan mempengaruhi bagian lain, yang akhirnya mempunyai dampak terhadap
kondisi sistem secara keseluruhan. Masyarakat dan kebudayaannya
merupakan dwitunggal yang sukar dibedakan, di dalamnya tersimpul
sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan dan nilai. Yang
3Roland Robertson, ed, Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis,
(Jakarta:
20
menentukan situasi dan kondisi perilaku anggota masyarakat. Dengam kata
lain, di dalam kebudayaan tersimpul suatu maknawi (symbolic system of
meanings).
Dilihat dari terminologi kebudayaan, agama merupakan cultural
universal, artinya agama terdapat di setiap daerah kebudayaan di mana saja
masyarakat dan kebudayaan itu bereksistensi. Salah satu prinsip teori
fungsional antara lain menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi
akan lenyap dengan sendirinya. Dengan kata lain setiap unsur kebudayaan
memiliki fungsi, konsekuensinya sesuatu pola atau lembaga sosial yang
berfungsi akan sirna. Karena sejak dahulu hingga sekarang, agama dengan
tangguh menyatakan eksistensinya, berarti agama mempunyai dan
memerankan sejumlah fungsi di dalam masyarakat.
Fungsi psikologis maupun sosial yang diperankan oleh agama sangat
mendasar. Agama berfungsi memenuhi sebahagian atau mungkin seluruh
kebutuhan manusia. Di dalam masyarakat terdapat norma-norma perilaku
masyarakat tradisional yang kadang-kadang sukar ditelusuri asal mulanya.
Tetapi tidak sedikit aturan tradisional itu mengandung nilai ajaran agama.
Misalnya secara tradisional hormat kepada orang tua adalah sangat dianjurkan
dan merupakan perilaku terpuji.
Ternyata aturan tersebut terdapat juga di dalam ajaran agama.
Sehingga agama berfungsi sebagai pendukung adat istiadat, dan memperkuat
21
melaksanakan tradisi, karena ia melakukan hal itu bukan hanya demi tradisi,
tetapi dirasakan secara manifes, sebagai pemenuhan titah Tuhan timbul dari
rasa sakral.4
3. Peran Agama di Masyarakat
Konsepsi tentang agama merupakan bagian tak terpisahkan dari
pandangan hidup dalam bermasyarakat dan sangat diwarnai oleh perasaan
yang khas terhadap apa yang dianggap sakral (suci).5 Signifikansi eksistensi
agama adalah membimbing sekaligus mengikat manusia demi terwujudnya
ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan mereka dalam kehidupan di dunia
serta kehidupan di hari kemudian, yaitu kehidupan ukhrawi. Setiap agama
membawa misi suci walaupun pada tataran implementasi oleh penganutnya
tidak selalu demikian yang terjadi. Ketidak sinkronan antara fakta normatif
dan historis ini disebabkan karena pandangannya yang berbeda terhadap dan
segala yang terlahir darinya berupa doktrin yang berhubungan dengan aturan
ritual maupun sosial.6
Agama memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk memahami
tujuan hidup. Untuk memenuhi tujuan agama, maka lembaga agama
memberikan konstribusi kepada kehidupan sosial sekular. Untuk memberi arti
kepada eksistensi pribadi, agama memberi gambaran tentang dunia tempat
manusia hidup. Misalnya di dalam testamen baru disebutkan bahwa alam raya
4Djamari, Agama Dalam Perspektif Sosiologi, (Bandung: Alfabeta, 1993),79-82
22
ada tiga tingkatan, yang di bawah adalah neraka, di tengah adalah dunia, di
atas adalah surga. Struktur realitas seperti itu membantu manusia untuk
belajar bagaimana seharusnya manusia berperilaku di dunia ini sehingga
terhindar dari neraka dan bisa masuk surga. Gambaran dunia secara religius
menentukan realitas sosial yang pengaruhnya bukan semata-mata persoalan
agama itu sendiri.7
B. Interaksi Sosial
1. Pengertian Interaksi Sosial
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidaklah lepas dari hubungan
satu dengan yang lain. Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya,
sehingga kepribadian individu, kecakapan-kecakapannya, ciri-ciri
kegiatannya baru menjadi kepribadian individu yang sebenar-benarnya
apabila keseluruhan sistem psycho-physik tersebut berhubungan dengan
lingkungannya.
Bentuk umum sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan
proses sosial), karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya
aktifitas-aktifitas sosial. Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan
bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Dalam konteks ini Wood Worth
menambahkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan meliputi
pengertian :
23
a. Individu dapat bertentangan dengan lingkungan
b. Individu dapat menggunakan lingkungan
c. Individu dapat berpartisipasi (ikut-serta) dengan lingkungan
d. Individu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan.8
Dari pengertian tersebut, maka interaksi sosial adalah kegiatan individu
atau kelompok individu dalam rangka pertentangan, pemanfaatan, partisipasi,
dan penyesuaian dengan individu atau kelompok individu lainnya
(lingkungannya).
Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat
menyesuaikan dengan yang lain, atau sebaliknya. Pengertian penyesuaian di
sini dalam arti yang luas, yaitu bahwa individu dapat meleburkan diri dengan
keadaan di sekitarnya, atau sebaliknya individu dapat mengubah lingkungan
sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh individu yang bersangkutan.9
Pengertian yang diberikan Worth tersebut, diperjelas oleh H. Bonner
dengan menitikberatkan fungsi manusia dalam interaksi sosia. Ia
menyebutkan bahwa:
8 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 53
24
“Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 2 individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memberbaiki
kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”.10
Soerjono Soekamto dalam bukunya mengatakan:
“Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok-kelompok
manusia”.11
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dijelaskan dalam penulisan
skripsi ini, bahwa interaksi sosial adalah kegiatan individu atau kelompok
individu dalam rangka pertentangan, pemanfaatan, partisipasi dan
penyesuaian dengan individu atau kelompok individu lainnya
(lingkungannya), dalam rangka memperbaiki kelakuan yang lain atau
sebaliknya, baik dilakukan secara pasif maupun aktif.
2. Unsur Dasar Interaksi Sosial
Di dalam interaksi sosial mengandung makna tentang kontak secara
timbal balik atau inter-stimulasi dan respon antara individu-individu dan
kelompok-kelompok. Karena itu, bagi Alvin dan Helen Gouldner suatu
interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat
yaitu:
25
individu atau kelompok. Kontak antara individu tidak saja terjadi pada jarak
yang dekat misalnya dengan berhadapan muka, juga tidak hanya pada jarak
sejauh kemampuan panca indera manusia, tetapi alat-alat kebudayaan
manusia memungkinkan individu-individu berkontak pada jarak yang amat
jauh, misalnya orang menelpon dan mendapat jawaban dari seorang individu
di ujung lain. Maka telah terjadi kontak diantara kedua itu.
b. Adanya Komunikasi
Sehubungan dengan komunikasi, Schlegel berpendapat bahwa manusia
adalah makhluk sosial yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri,
menafsirkan makna-makna obyek-obyek didalam kesadarannya dan
memutuskan bagaimana ia bertindak secara berarti sesuai dengan
penafsirannya itu. Sehubungan komunikasi sebagai kegiatan interaksi sosial
ini, Schlegel menyampaikan pandangan tentang bahwa:
“Tetapi keadannya tidak berbeda dengan tingkah laku kelompok yang melibatkan beberapa atau banyak orang, misalnya, tingkah laku kelompok sosial adalah seperti keluaga-keluarga, lembaga-lembaga sosial (seperti bank) atau organisasi (seperti partai)”.
“Tingkah laku kelompok yaitu tingkah laku bersama harus dibentuk melalui proses penafsiran juga, agar orang-orang (di dalam kelompok) dapat bertindak bersama dalam keadaan-keadaan yang dihadapi kelompok itu. Tetapi yang menafsirkan dan bertindak adalah orang-orang juga. Kelompok tidak pernah bertindak; kelompok terdiri dari orang-orang dan mereka bertindak bersama. Tingkah laku di dalam kelompok, tindakan banyak orang
bisa sama, karena makna-makna dari keadaan itu ditafsirkan sama”.12
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak dapat hubungan antara
kelompok atau perorangan dengan kelompok, oleh karena kelompok itu tidak
26
bisa bertindak dan karena kelompok itu adalah orang-orang juga, maka
hubungan yang terjadi adalah antara orang dengan orang, antara satu orang
dengan banyak orang, atau antara banyak orang dengan banyak orang.
3. Ciri-ciri Interaksi Sosial
Apabila dilacak dengan seksama deskripsi di atas, maka ucapan dari
Charles P. Lommis mengenai ciri-ciri penting dari interaksi sosial yaitu:
a. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih.
b. Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan
simbol-simbol.
c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan
datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
d. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan
yang diperkirakan oleh para pengamat.
Apabila interaksi sosial itu diulang menurut pola yang sama dan
bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial
(social relation).
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial
a. Toleransi
Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan
27
tersebut mendorong terjadinya komunikasi, maka faktor tersebut dapat
mempercepat terjadinya interaksi sosial.
b. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di Bidang Ekonomi
Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi bagi pelbagai
golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dapat
mempercepat proses interaksi sosial. Di dalam sistem ekonomi yang
demikian, dimana masing-masing individu mendapat kesempatan yang sama
untuk mencapai kedudukan tertentu atau dasar kemampuan dan jasa-jasanya.
Proses interaksi dipercepat oleh karena kenyataan yang demikian dapat
menetralisir perbedaan-perbedaan kesempatan yang diberikan sebagai
peluang oleh kebudayaan-kebudayaan yang berlainan tersebut.
c. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
Sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh
masyarakat yang lain dimana masing-masing mengakui
kelemahan-kelemahannya, kelebihan-kelebihannya akan mendekatkan
masyarakat-masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan-kebudayaan tersebut.
Apabila ada prasangka, maka hal demikian akan menjadi penghambat bagi
berlangsungnya proses interaksi sosial.
d. Sikap terbuka dari golongan berkuasa dalam masyarakat
Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat juga
28
dengan memberikan kesempatan yang sama bagi golongan minoritas untuk
memperoleh pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penggunaan tempat
rekreasi dan seterusnya.
e. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
Pengetahuan akan persamaan-persamaan unsur pada kebudayaan yang
berlainan, akan lebih mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang
satu dengan yang lainnya.
f. Perkawinan campuran (Amalgamation)
Perkawinan campuran agaknya merupakan faktor paling
menguntungkan bagi lancarnya proses interaksi sosial. Hal itu terjadi, apabila
seorang warga dari golongan tertentu menikah dengan golongan lain, apakah
itu terjadi dengan golongan minoritas atau mayoritas atau sebaliknya.
g. Adanya musuh bersama di luar
Adanya musuh bersama di luar cenderung memperkuat kesatuan
masyarakat atau golongan masyarakat yang mengalami ancaman musuh
tersebut. Dalam keadaan demikian, antara golongan minoritas dengan
golongan mayoritas akan mencari suatu kompromi agar dapat secara
bersama-sama menghadapi ancaman-ancaman luar yang membahayakan
29
5. Faktor-faktor yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial
Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, baik
secara tunggal maupun secara bergabung ialah:
a. Faktor Imitasi
Menurut G. Tarde faktor imitasi ini merupakan satu-satunya faktor yang
mendasari atau melandasi interaksi sosial. G. Tarde mengatakan bahwa,
masyarakat itu tiada lain dari pengelompokkan manusia dimana
individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain atau sebaliknya, bahkan
masyarakat itu baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai
mengimitasi kegiatan manusia lainnya.
Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses
interaksi sosial, salah satu segi positifnya yaitu bahwa imitasi dapat
mendorong seseorang untuk memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang
berlaku. Faktor imitasi mungkin pula mengakibatkan hal-hal yang negatif
dimana yang ditiru adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Imitasi
juga dapat melemahkan atau mematikan pengembangan daya kreasi
seseorang.
Jadi, faktor imitasi merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial
yang menerangkan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam
30
b. Faktor Sugesti
Yang dimaksud faktor sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang
dari diri sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada umumnya
diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan.
Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan
atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.
Proses ini hampir sama dengan faktor imitasi akan tetapi titik tolaknya
berbeda. Berlangsungnya faktor sugesti dapat terjadi karena pihak yang
menerima dilanda emosi, hal mana menghambat daya pikirnya secara
rasional. Kiranya mungkin pula bahwa faktor sugesti terjadi oleh sebab
memberikan pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari kelompok
yang bersangkutan.
c. Faktor Identifikasi
Identifikasi adalah suatu istilah yang dikemukakan oleh Freud. Menurut
Freud, identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan
orang lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karena
kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses
identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar),
maupun dengan sengaja olek karena seringkali seseorang memerlukan
31
d. Faktor Simpati
Faktor simpati merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain. Maka
simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan atas dasar perasaan
atau emosi. Dalam simpati orang merasa tertarik kepada orang lain yang
seakan-akan berlangsung dengan sendirinya, apa sebabnya merasa tertarik
sering tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Di samping individu
mempunyai kecenderungan tertarik pada orang lain, individu juga
mempunyai kecenderungan untuk menolak orang lain, ini yang sering disebut
antipati. Jadi kalau simpati itu bersifat positif, maka antipati bersifat negatif.13
Hal-hal tersebut diatas merupakan proses minimal yang terjadi dan
berlangsungnya interaksi sosial yang dalam kenyataannya sangat kompleks,
sehingga kadang-kadang sulit mengadakan pembedaan tugas antara proses
tersebut. Imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat, dan pengaruhnya kurang
mendalam bila dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang secara
relatif agak lebih cepat proses berlangsungnya.
6. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
Interaksi sosial terdiri dari kontak dan komunikasi, dan di dalam
proses komunikasi mungkin saja terjadi pelbagai penafsiran makna perilaku.
Mengetahui hal tersebut maka bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu adalah
terdiri dari :
32
a. Kerja Sama
b. Pertikaian
c. Persaingan
d. Akomodasi
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk
umum dari interaksi sosial, yaitu assosiatif dan dissosiatif. Suatu interaksi
sosial yang assosiatif merupakan proses yang menuju pada kerja sama.
Sedangkan bentuk interaksi dissosiatif dapat diartikan sebagai suatu
perjuangan melawan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai
tujuan tertentu. Proses interaksi dissosiatif mungkin berguna bagi masyarakat
yang bersangkutan terutama dalam hal-hal sebagai berikut:
1) Untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif.
2) Sebagai suatu jalan atau saluran di mana keinginan-keinginan,
kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat
perhatian, tersalur dengan sebaik-baiknya.
3) Sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial.
4) Sebagai alat untuk menyaring warga-warga masyarakat untuk mengadakan
33
Menelaah pernyataan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bentuk umum
dan bentuk khusus dari bentuk umum dari interaksi sosial adalah sebagai
berikut:
Bentuk umum Assosiatif, meliputi bentuk khusus diantaranya:
a) Kerja Sama
Timbulnya kerja sama, menurut Charles H. Cooley adalah apabila
orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang
sama, dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan
pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan
tersebut melalui kerja sama.
Pada masyarakat dimana bentuk kerja samamerupakan unsur dari
sistem nilai-nilai sosial yang seringkali dijumpai dalam keadaan-keadaan
dimana warga masyarakat-masyarakat ttersebut tidak mempunyai inisiatif
ataupun daya kreasi, oleh karena perorangan atau individu tersebut
mengandalkan bantuan dari rekan-rekannya. Kerjasama sebagai salah satu
bentuk interaksi sosial merupakan gejala universal yang ada pada masyarakat.
Walaupun secara tidak sadar kerja sama tersebut mungkin timbul terutama
didalam keadaan-keadaan dimana kelompok tersebut mengalami ancaman
34
b) Akomodasi
Soerjono Soekamto menyatakan, bahwa akomodasi itu menunjuk pada
dua arti atau makna. Pertama, akomodasi menunjuk pada suatu keadaan dan
kedua, akomodasi itu menunjuk pada suatu proses. Sebagai suatu proses,
akomodasi menunjuk pada usaha-usaha untuk mencapai penyelesaian
pertikaian; sedangkan sebagai suatu keadaan, akomodasi menunjuk pada
suatu kondisi selesainya pertikaian tersebut.
Bentuk unum Dissosiatif, meliputi bentuk khusus diantaranya:
(1) Pertikaian
Pertikaian dapat terjadi karena proses interaksi, di mana penafsiran
makna perilaku tidak sesuai dengan maksud dari fihak pertama, yaitu fihak
yang melakukan aksi, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana tidak
terdapat keserasian di antara kepentingan-kepentingan para fihak yang
melakukan interaksi. Oleh karena telah terjadi suatu situasi yang tidak serasi,
maka untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dilakukan dengan carav
mengenyahkan fihak yang telah menjadi penghalangnya itu. Pada
pertentangan atau pertikaian terdapat usaha untuk menjatuhkan fihak lawan
dengan cara kekerasan (violence).
Mungkin, pertentangan atau pertikaian ini timbul karena persaingan
atau kompetisi, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Horton dan Hunt,
menyatakan bahwa sekali pertikaian dimulai, maka proses ini sulit untuk
35
pada dasarnya diilhami oleh sifat bermusuhan tersebut, sehingga proses
pertikaian terus berlangsung dan menumbuhkan situasi yang tidak
menguntungkan.
(2) Persaingan
Persaingan adalah suatu perjuangan (struggle) dari fihak-fihak untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu ciri dari persaingan adalah perjuangan
menyingkirkan fihak lawan itu dilakukan secara damai atau secara
“fair-play”, artinya selalu menjunjung tinggi batas-batas yang diharuskan.
Persaingan dapat terjadi dalam segala bidang kehidupan, misalnya
bidang ekonomi dan perdagangan, kedudukan, kekuasaan, percintaan dan
sebagainya. Persaingan meliputi beberapa fihak yang melakukan persaingan,
fihak-fihak yang berkomprtisi (bersaing) disebut “saingan”.14
Keempat bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut merupakan suatu
kontinuitas dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja sama yang
kemudian menjadi pertikaian untuk akhirnya pada akomodasi. Akan tetapi
ada baiknya untuk menelaah proses-proses interaksi-interaksi tersebut
didalam kelangsungannya, sebagai contoh dapat ditelaah kemungkinan apa
yang akan terjadi apabila suatu kelompok baru (misalnya kaum pendatang
dari arab) datang untuk menetap disuatu daerah yang telah ada penduduknya
yang merupakan masyarat asli daerah tersebut (misalnya jawa)
36
C. Teori Agama Menurut Emile Durkheim
Dalam pembahasan judul “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama
(Studi kasus Jama’ah Wahidiyah dan Jama’ah Nahdliyin Di Desa Sukorejo,
Kab. Sidoarjo)”, Penulis menggunakan pendekatan kajian Sosiologi. Dengan
menggunakan teori tokoh Emile Durkheim yang merupakan figur yang
berpengaruh kuat terhadap pemikiran sosiologi.15
Persoalan yang dikemukakan oleh Durkheim yang diuraikan dalam
bukunya The Elementary Forms of The Religious Life adalah melihat “Sebab
yang selalu hadir yang menjadi tempat bergantungnya bentuk-bentuk
pemikiran dan praktek keagamaan yang paling esensial” dan untuk
melakukan hal itu Durkheim perlu mengkaji agama dalam “Bentuknya yang
paling primitif dan sederhana” dan mencoba membahas sifatnya dengan
mengkaji asal-usulnya.16 dalam hal ini Durkheim berusaha mencari definisi
yang lebih luas. “Agama itu lebih dari sekedar gagasan tentang Tuhan dan
roh” tulisnya dan “Konsekuensinya tidak dapat didefinisikan semata-mata
dalam kaitannya dengan kedua hal tersebut”. Maka Durkheim kemudian
mendefinisikan dari sudut pandang yang sakral. Bagi Durkheim agama pada
dasarnya merupakan sesuatu yang kolektif, dan bahkan Durkheim
membedakan agama dari magis dengan menyatakan bahwa magis merupakan
15 Brian Morris, Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer, (Yogyakarta: AK Group, 2003), 133.
37
upaya individual, sementara agama tidak bisa dipisahkan dari ide komunitas,
peribadatan atau moral.17
Dalam bukunya The Elementary Forms of The Religious Life
tersebut Durkheim juga mengemukakan teori tentang dasar-dasar agama yang
sama sekali berbeda dengan teori-teori yang pernah dikembangkan oleh para
ilmuwan sebelumnya.
Teori itu berpusat pada pengertian dasar berikut:
1. Bahwa untuk pertama kalinya, aktivitas religi yang ada pada manusia bukan
karena alam pikirannya terdapat bayangan-bayangan abstrak tentang jiwa
atau roh (suatu kekuatan yang menyebabkan hidup dan gerak di dalam alam)
tetapi, karena suatu getaran jiwa, atau emosi keagamaan yang timbul dalam
alam jiwa manusia dahulu, karena pengaruh suatu sentimen kemasyarakatan.
2. Bahwa sentimen kemasyarakatan dalam batin manusia berupa suatu
kompleksitas perasaan yang mengandung rasa terikat, bakti, cinta, dan
perasaan lainnya terhadap masyarakat di mana ia hidup.
3. Bahwa sentimen kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya emosi
keagamaan dan merupakan pangkal dari segala kelakuan keagamaan manusia
itu, tidak selalu berkobar-kobar dalam alam batinnya. Apabila tidak
dipelihara, maka sentimen kemasyarakatan itu menjadi lemah, sehingga perlu
dikobarkan sentimen kemasyarakatan dengan mengadakan satu kontraksi
masyarakat, artinya dengan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam
pertemuan-pertemuan.
38
4. Bahwa emosi keagamaan yang timbul karena rasa sentimen kemasyarakatan
membutuhkan suatu objek tujuan. Sifat yang menyebabkan sesuatu itu
menjadi objek dari emosi keagamaan bukan karena sifat luar biasanya,
anehnya melainkan tekanan anggapan umum masyarakat. Objek itu ada
karena terjadinya satu peristiwa secara kebetulan di dalam sejarah kehidupan
suatu masyarakat yang menarik perhatian di dalam masyarakat tersebut.
Objek yang menjadi tujuan emosi keagamaan juga objek yang bersifat sakral.
Maka objek lain yang tidak mendapat nilai keagamaan (tirual value)
dipandang sebagai objek yang tidak sakral (profane).
5. Objek sakral sebenarnya merupakan suatu lambang masyarakat. Pada
suku-suku bangsa asli Australia misalnya, objek sakral sering berupa binatang dan
tumbuh-tumbuhan. Objek sakral seperti itu disebut Totem. Totem adalah
mengkonkretkan prinsip suatu kelompok di dalam masyarakat berupa clan
(suku) atau lainnya.
Pendapat tersebut, yang pertama mengenai emosi keagamaan dan
sentimen kemasyarakatan. Menurut Durkheim, pengertian-pengertian dasar
yang merupakan inti atau esensi dari religi, sedangkan ketiga pengertian
lainnya yakni kontraksi masyarakat, kesadaran akan objek yang sakral
berlawanan dengan objek yang tidak sakral, dan totem sebagai lambang
masyarakat.
Objek sakral dan totem akan menjelaskan upacara, kepercayaan, dan
39
Perbedaan itu tampak dari upacara-upacara kepercayaan dan
metodologinya.18
Pendekatan Emile Durkheim senada dengan paralelisme metafora
(Metaphoric Paralelism) dari winter. Ia meyakini bahwa dunia sakral adalah
dunia yang paralel dengan “keduniaan” (mundane world). Pola-pola perilaku
yang akan menyebabkan kekacauan sosial dicegah dengan takut kepada
sanksi dari kekuasaan supernatural, yang dikatakan sebagai taboo. Menurut
Durkheim istilah tuhan adalah suatu metafor (ibarat) bagi masyarakat, karena
itu kata Durkheim, menyembah tuhan sebenarnya menyembah masyarakat
sendiri. Orang tidak menyadari proses proyeksi seperti ini, akhirnya taboo
dan kode moral menjadi mutlak dan mengikat tanpa dipersonalkan lagi.
Kaum fungsionalis tidak selalu sependapat dengan Durkheim, bahwa
percaya kepada tuhan adalah fatamorgana atau angan-angan saja, bagi
kebanyakan fungsionalis ada atau tidak adanya tuhan di luarkemampuan
empirik untuk membuktikkannya. Masalah kaum fungsionalis tidak
memperdulikan kepada benar atau palsunya suatu kepercayaan, tetapi yang
penting bagaimana kepercayaan dan ritual itu fungsinya atau pengaruhnya
dalam masyarakat.
Emile Durkheim dan Radcliffe Brown menganggap bahwa agama
mungkin melayani beberapa fungsi individual, tetapi fungsi agama terpenting
adalah struktural. Bahkan Emile Durkheim menekankan bahwa kontribusi
40
agama bukan menentukan identitas individu tetapi memperkuat identitas
kolektif. Agama membantu kelompok mengidentifikasi siapa mereka, agama
membantu mereka menentukan kelompok sebagai suatu komuniti moral
dengan nilai-nilai dan misi umum dalam kehidupan.19
Dalam definisi yang diberikan Durkheim tentang agama, dia mengatakan
bahwa agama adalah satu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang
utuh dan selalu dikaitkan dengan yang sakral, yaitu sesuatu yang terpisah dan
terlarang.20 Durkheim juga mengatakan bahwa kekuatan agama adalah
kekuatan manusia, kekuatan moral. Memang benar oleh karena sentimen
kolektif dapat mendorong kesadaran warga atau masyarakat dengan cara
mendekatkan diri mereka kepada objek di luar diri mereka yakni
kekuatan-kekuatan keagamaan, kekuatan-kekuatan agama bahkan dapat menjelma menjadi
semacam unsur fisik, dalam hal ini agama akan berpadu dengan kehidupan
material, kemudian dianggap mempunyai kemampuan yang menjelaskan apa
yang terjadi. Tetapi jika kekuatan-kekuatan agama hanya ditilik atau dilihat
dari sudut pandangan ini, hanya aspek yang paling superfisial yang dapat
dilihat. Dalam kenyataan, unsur-unsur esensial yang membentuk sentimen
kolektif ini diperoleh melalui pemahaman. Biasanya nampak bahwa
kekuatan-kekuatan agama itu hanya memiliki karakter manusia apabila
kekuatan-kekuatan itu dimengerti dari segi manusiannya, tetapi bahkan yang
19 Djamari, Agama Dalam Perspektif Sosiologi,.... 86-88
41
paling anonim dan paling impersonal sekalipun tak lain adalah
sentimen-sentimen yang diobjektivasi.21
Seluruh pandangan Durkheim berada dalam klaimnya yang mengatakan
bahwa “agama adalah sesuatu yang bersifat sosial”. Durkheim menegaskan,
walaupun sebagai orang individu memang memiliki pilihan-pilihan dalam
hidup ini, namun pilihan itu tetap berada dalam kerangka sosial. Dalam setiap
kebudayaan, agama adalah bagian yang paling berharga dari seluruh
kehidupan sosial. Dia (agama) melayani masyarakat dengan menyediakan
ide, ritual dan perasaan-perasaan yang akan menuntun seseorang dalam hidup
bermasyarakat.22
21 Roland Robertson, ed, Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis,...44-45
BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SUKOREJO
A. Gambaran Wilayah Desa Sukorejo
1. Letak Geografis
Sukorejo adalah nama sebuah dusun dan Buduran adalah kecamatan
di Sidoarjo. Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur
antara 112, 5’ dan 112, 9’ Bujur Timur dan antara 7,3’ dan 7,5’ Lintang
Selatan. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, batas sebelah utara
wilayah Sidoarjo adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah
selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan
sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Dataran Sidoarjo dengan
ketinggian antara 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha.
2. Kondisi Demografis
Berdasarkan data terakhir pada bulan juni 2017 jumlah penduduk di Desa
Sukorejo Kecamatan Buduran ini seluruhnya berjumlah 4.728 jiwa terdiri dari
1.338 Kepala Keluarga (KK). Dari keseluruhan jumlah penduduk, laki-laki
berjumlah 2.413 jiwa, sedangkan perempuan bejumlah 2.315 jiwa. Untuk
43
Tabel 1
Jumlah Penduduk dilihat dari jenis kelamin
NO Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-laki 2.413
2. Perempuan 2.315
Jumlah 4.728
Sumber data dokumen Desa Sukorejo bulan Juni 2017
Sedangkan jumlah penduduk secara rinci berdasarkan usia, dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2
Keadaan Peduduk berdasarkan usia
No. Usia Jumlah
1. 0-3 819
2. 4-6 136
3. 7-12 283
4. 13-15 152
5. 16-18 175
6. 19 keatas 3.163
Jumlah 4.728
44
3. Kondisi Pendidikan
Kondisi pendidikan di desa Sukorejo terbilang sudah maju atau bersifat
modern. Karena mendekati sekolahan-sekolahan yakni SDN Sukorejo, SMPN
Buduran dan SMKN Buduran, jadi pendidikan di desa sukorejo ini terbilang
cukup baik. Keadaan penduduk dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3
Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1. Taman Kanak-kanak 389
2. Sekolah Dasar 1.830
3. SMP/SLTP 680
4. SMA/SLTA 580
5. Sarjana (S1-S3) 151
6. Pondok Pesantren 95
7. Madrasah 133
8. Sekolah Luar Biasa 5
Sumber data dokumen Desa Sukorejo bulan Juni 2017
Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa
45
4. Kondisi Ekonomi
Sebagaimana data geografis yang dipaparkan sebelumnya, sebagian
besar mata pencaharian penduduk desa Sukorejo ini adalah pegawai swasta,
namun banyak juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), petani
dan lain-lain. Lahan yang berada di desa Sukorejo terbilang cukup luas yakni
telah di bangun berbagai macam pabrik, seperti pabrik kayu, pabrik
pengupasan udang, dan lain sebagainya. Keadaan penduduk dari kondisi
pekerjaan/ekonomi dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4
Keadaan Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Ekonomi
No. Mata Pencaharian Jumlah
1. Pegawai Negeri Sipil 180
2. Pegawai Swasta 2.765
3. ABRI 120
4. Tani 5
5. Pertukangan 80
6. Buruh Tani 20
7. Pensiunan 111
8. Pedagang 1.447
46
5. Kondisi Sosial
Penduduk desa Sukorejo memiliki berbagai karakteristik individu yang
meliputi berbagai variabel seperti nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap
saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan
faktor-faktor lingkungan yang menentukan faktor prilaku mereka. Faktor
lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan
kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu. Hal
inilah yang menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks.
6. Kondisi Keagamaan
Penduduk di desa sukorejo memiliki berbagai macam keyakinan dalam
beragama yakni Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Namun penduduk di desa
Sukorejo 95% beragama Islam. Keadaan penduduk dari kondisi keyakinan
beragama dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 5
Keadaan Penduduk berdasarkan Keyakinan Beragama
No. Agama Jumlah
1. Islam 4.573
2. Kristen 107
3. Katolik 7
4. Hindu 1