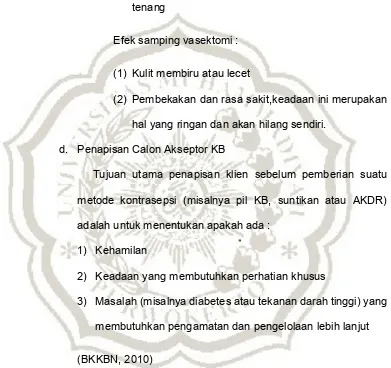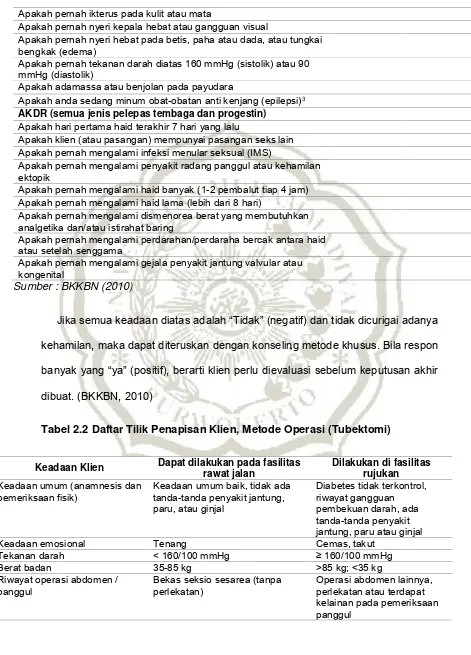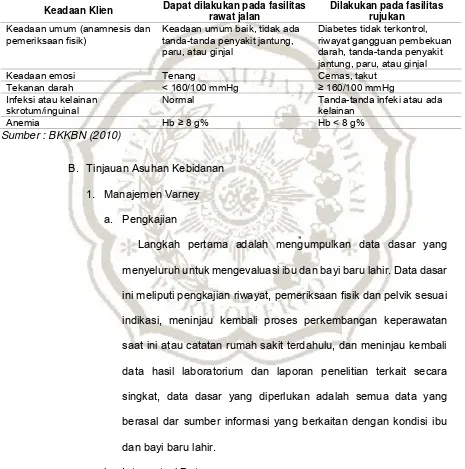BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Medis
1. Kehamilan
a. Pengertian
Periode antepatum adalah periode kehamilan yang dihitung
sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) hingga dimulainya
persalinan sejati, yang menandai awal periode antepartum.
Sebaliknya, periode prenatal adalah kurun waktu terhitung sejak
hari pertama haid terakhir hingga kelahiran bayi yang menandai
awal periode pascanatal. (Varney, 2007 h. 492)
b. Fisiologi Kehamilan
1) Fertilisasi
Pembuahan/fertilisasi adalah suatu peristiwa penyatuan
antara sel mani dengan sel telur di tuba fallopi, umumnya
terjadi di ampula tuba, pada hari ke sebelas sampai empat
belas dalam siklus menstruasi. (Siwi Walyani, 2015 h. 46)
2) Hasil Pembuahan
Dalam beberapa jam setelah pembuahan, mulai terjadi
pembelahan zigot selama tiga hari (mulai 2 sel, 4 sel, 8 sel,
dan 16 sel/blastomer). Setelah 3 hari sel-sel tersebut akan
(4hari). Saat morulla memasuki rongga rahim, cairan mulai
menembus zona pellusida masuk ke dalam ruang antar sel
yang ada di massa sel dalam. Berangsur-angsur ruang antar
sel menyatu dan akhirnya terbentuklah sebuah rongga atau
blastokel sehingga disebut blastokista (4,5-5 hari). Sel yang
ada dibagian dalam disebut embriblas dan sel diluar disebut
trofoblas. Zona pellusida akhirnya menghilang sehingga bisa
memasuki dinding rahim (endometrium) dan siap
berimplantasi (5,5-6 hari) dalam bentuk blastokista tingkat
lanjut. (Kuswanti, 2014 h. 62)
3) Implantasi
Implantasi atau nidasi adalah peristiwa tertanamnya atau
bersarangnya sel telur yang telah dibuahi ke dalam
endometrium. (Kuswanti, 2014 h. 63) Pada akhir minggu
pertama (hari ke 5 sampai hari ke 7) zigot mencapai cavum
uteri. Pada saat ini, uterus sedang berada dalam fase
sekresi lendir dibawah pengaruh progesteron dari korpus
luteum yang masih aktif, sehingga lapisan endometrium
dinding rahim menjadi kaya pembuluh darah dan banyak
muara kelenjar selaput lendir rahim yang terbuka dan aktif
(Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 55).
4) Pembentukan Plasenta, Tali pusat dan Cairan Amnion
Plasenta adalah alat yang sangat penting bagi janin
karena merupakan alat pertukaran zat antara ibu dan
bayi serta sebaliknya. Plasenta berbentuk bundar atau
agak bundar dengan diameter 15-20 cm dan tebal
kurang lebih 2,5 cm, beratnya rata-rata 500 gram.
Umumnya plasenta berbentuk lengkap pada kehamilan
lebih kurang 16 minggu dengan ruang amnion telah
mengisi seluruh kavum uteri. (Kuswanti, 2014 h. 70)
Fungsi plasenta menurut Kuswanti (2014), yaitu
sebagai nutrisasi (alat pemberi makan pada janin),
respirasi (alat penyalur zat asam dan pembuang CO2),
ekskresi (alat pengeluaran sampah metabolisme),
produksi (alat yang menghasilkan hormon-hormon,
imunisasi (alat penyalur bermacam-macam antibodi ke
janin), dan pertahanan (alat yang menyaring
obat-obatan dan kuman-kuman yang bisa melewati uri.
b) Tali Pusat
Merupakan penghubung antara plasenta dengan
janin. Terdapat 2 pembuluh darah arteri dan vena
umbilicalis yang terbungkus jelly wharton dengan
panjang 30-100 cm, insersi normal di tengah plasenta.
(Siwi Walyani, 2015 h. 52)
Amnion adalah selaput yang membatasi rongga
amnion yang berisi cairan jenih seperti air yang sebagian
dihasilkan oleh sel-sel amnion. Volume air ketuban pada
kehamilan cukup bulan 1000-1500 cc, warna putih keruh,
bau amis, berasa manis, reaksi agak alkali. Komposisi
terdiri atas 98% air, sisanya albumin, urea, asam urik,
kreatinin, sel-sel epitel, rambut lanugo, verniks caseosa
dan garam organik (Siwi Walyani, 2015; h. 52)
c. Tanda-tanda Kehamilan
1) Tanda Tidak Pasti Kehamilan
a) Amenorhoe
Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi
ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. Lamanya
amenorea dapat diinformasikan dengan memastikan hari
pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk
memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan.
(Siwi Walyani, 2015 h. 70). Untuk menghitung tafsiran
persalinan dapat menggunakan rumus Naegele sebagai
berikut, tanggal HPHT ditambahkan dengan 7 dan
bulannya dikurang 3 dan tahunnya ditambah 1 atau
tetap. (Yuli Aspiani, 2017 h. 42)
b) Mual dengan atau tanpa muntah
Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi
menimbulkan mual muntah yang terjadi terutama pada
pagi hari yang disebut morning sickness. Dalam batas
tertentu hal ini masih fisiologis, tetapi bila terlampau
sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang
disebut dengan hiperemesis gravidarum. (Siwi Walyani,
2015 h. 70)
c) Sering miksi
Biasanya terjadi pada trimester pertama yang
disebabkan oleh penekanan kandung kencing oleh
pembesaran uterus. Gejala ini akan berkurang sampai
hilang pada trimester kedua dan muncul kembali pada
akhir kehamilan yang disebabkan penekanan kandung
kemih oleh penurunan bagian terendah janin (kepala
atau bokong). (Yuli Aspiani, 2017 h. 43)
d) Konstipasi atau obstipasi
Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik
usus sehingga kesulitan BAB. (Siwi Walyani, 2015 h. 71).
Menurut Yuli Aspiani (2017), hal ini disebabkan karena
menurunnya tonus otot khusus oleh pengaruh hormone
steroid.
e) Payudara Tegang
Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri, yang
disebabkan pengaruh estrogen dan progesteron yang
montgomery terlihat lebih membesar. (Kuswanti, 2014 h.
101)
f) Pigmentasi Kulit
Terjadi penumpukan melanin pada kulit dibagian
tubuh tertentu terutama di bagian pipi dan dahi yang
disebut dengan cloasma gravidarum. Garis middle
abdomen juga mengalami perubahan warna menjadi
lebih gelap yang disebut dengan linea nigra. (Yuli
Aspiani, 2017 h. 43).
2) Tanda Kemungkinan Hamil
Beberapa tanda kemungkinan hamil menurut Siwi
Walyani (2015) :
a) Pembesaran Perut
Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada
bulan keempat kehamilan
b) Tanda Hegar
Adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthimus uteri.
c) Tanda Goodel
Adalah pelunakan serviks. Pada wanita tidak hamil
serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita
hamil melunak seperti bibir.
d) Tanda Chadwick
Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan
e) Tanda Piscaseck
Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris.
Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat
dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang
lebuh dahulu.
f) Teraba Ballotement
Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan
janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat
dirasakan oleh tangan pemeriksa.
g) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif
Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya
human chorionic gonadotropin (hCG) yang di produksi
oleh sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormon
ini dapat mulai di deteksi pada 26 hari setelah konsepsi
dan meningkat dengan cepat pada hari ke 30-60.
3) Tanda pasti hamil
Menurut Yuli Aspiani (2017), tanda pasti hamil
diantaranya :
a) Denyut Jantung Janin, dengan stetoskop pada usia
kehamilan 17-19 mnggu, dengan dopler pada usia
kehamilan 10 minggu, dengan elektrokardiografi dapat
mendeteksi sejak 48 hari setelah HPHT terakhir.
b) Persepsi Gerakan Janin, terdeteksi oleh pemeriksa
c) Deteksi Kehamilan Secara Ultrasonografi
Setelah 6 minggu, denyut jantung janin sudah
terdeteksi. Kantung gestasi mulai dapat dilihat sejak
usia kehamilan 4-5 minggu sejak menstruasi terakhir.
Dan pada minggu ke 8, usia gestasi dapat diperkirakan
secara cukup akurat.
d. Adaptasi Fisiologi Ibu Hamil
1) Sistem Reproduksi
Uterus berisi 5-10 liter, pada akhir kehamilan akan
500-1000 kali lebih besar daripada keadaan tidak hamil. Berat
kehamian aterm 1100 gram, tidak hamil 70 gram. Dinding
lebih tipis. Serviks akan menjadi lebih lunak, perubahan
warna kebiruan karena peningkatan vaskularisasi dan
edema pada seluruh serviks, hipertrofi dan hiperplasi
kelenjar serviks. (Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 68)
Vagina terdapat bercak keunguan (Chadwick Sign) pada
minggu ke 8 disebabkan oleh meningkatnya vaskularisasi
sebagai leucorrhea dan meningkatkan rangsangan seksual.
(Yuli Aspiani, 2017 h. 36)
Ovarium tidak akan mengalami ovulasi selama kehamilan
terjadi, maturasi folikel tidak tertunda dan payudara akan
terasa nyeri karena hipertrofi alveoli mammae serta
hiperpigmentasi areola. (Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 68)
Volume darah meningkat 30%-50%, tetapi tekanan darah
tidak berubah. Pembentukan sel-sel darah merah meningkat
tetapi terjadi hemodilusi, maka berkembang pseudoanemia
yaitu penekanan pada vena cava menyebabkan gejalan
sindrom supine hipotensi, statis vena, dan fibrin meningkat
membuat wanita lebih mudah mengalami trombosis. (Yuli
Aspiani, 2017 h. 37)
3) Sistem Pernafasan
a) Paru-paru dan pernafasan : letak diafragma berubah
karena pertumbuhan janin, tidal volume meningkat,
meningkatkan O2 dalam darah.
b) Membran mukosa : pembengkakan umum terjadi,
menyebabkan hidung tersumbat, sesak, dispnea dan
seterusnya.
(Yuli Aspiani, 2017 h. 37)
4) Sistem Gastrointestinal
Tonus dan gerakan traktus gastrointestinal berkurang
karena perpanjangan waktu pengosongan lambung dan
memperlambat perjalanan dalam intestinum, terjadi
hemoroid karen konstipasi dan peningkatan tekanan vena
sekunder terhadap pembesaran uterus. (Wagiyo dan
Putrono, 2016 h. 69)
Sering berkemih pada awal masa kehamilan disebabkan
karena penekanan uterus pada kandung kemih (Yuli Aspiani,
2017 h. 37).
6) Sistem Endokrin
a) Ovarium dan plasenta : corpus luteum membentuk
estrogen dan progesteron. Plasenta juga membentuk
HCG (Human Chorionic Gonadotropin), HPL (Human
Placental Laktogen) dan HCT (Hematocrit).
b) Kelenjar tiroid : membesar selama kehamilan, tetapi
jumlah tiroksin tetap konstan.
c) Kelenjar paratiroid : ukuran meningkat pada minggu ke
15-35, ketika kebutuhan janin meningkat.
d) Pankreas : pembentukan insulin meningkat selama
kehamilan, tetapi penyimpanan glikogen menjadi
terbatas.
e) Kelenjar hipoise : FSH (Follicle Stimulating Hormone),
ditekan oleh HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
yang dijadikan plasenta. Prolactin meningkat selama
kehamilan dan laktasi, oksitosin meningkat dan
menstimulasi kontraksi otot uterus.
f) Kelenjar adrenal : korlin meningkat tetapi epinefrin tetap
konstan.
(Yuli Aspiani, 2017 h. 36-37)
Penambahan berat badan yang diharapkan selama
kehamilan bervariasi antara ibu yang satu dengan lainnya.
Kenaikan BB selama hamil berdasarkan usia kehamilan :
10 mgg = 650 gram
20 mgg = 4000 gram
30 mgg = 8500 gram
40 mgg = 12500 gram
(Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 73)
e. Adaptasi Psikologis Ibu Hamil
1) Trimester I
Trimester pertama sering dianggap sebagai periode
penyesuaian yang dilakukan wanita adalah terhadap
kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Penerimaan
kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan
tugas psikologis yang paling penting pada trimester pertama
kehamilan. Sebagian besar wanita merasa sedih dan
ambivalen tentang kenyataan bahwa ia hamil. Kurang lebih
80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan,
kecemasan, depresi, dan kesedihan. (Siwi Walyani, 2015 h.
64)
2) Trimester II
Tubuh wanita telah terbiasa dengan perubahan tingkat
hormon yang tinggi, morning sickness telah hilang, ia telah
yang konstruktif. Saat kehamilan memasuki trimester II,
masalah baru muncul, yaitu gambaran penampilan tubuhnya
selama hamil. Sebagian besar bumil memiliki citra tubuh
yang negatif, yang akan semakin terasa seiring semakin
besarnya kehamilan. (Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 75)
3) Trimester III
Trimester III sering disebut periode penantuan dengan
penuh kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai
menyadari kehadiran bayi sebagai makhluk yang terpisah
sehingga ia menjadi tidak sabar menanti kehadiran sang
bayi. Ibu menjadi lebih protektif terhadap bayi, mulai
menghindari keramaian atau seseorang atau apapun yang
ia anggap berbahaya. Wanita mungkin merasa cemas
dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri, seperti :
apakah nanti bayinya akan lahir abnormal, terkait persalinan
dan pelahiran, apakah ia akan menyadari bahwa ia akan
bersalin, atau bayinya tidak mampu keluar karena perutnya
sudah luar biasa besar, atau apakah organ vitalnya akan
mengalami cidera akibat tendangan bayi. (Siwi Walyani,
2015 h. 67)
f. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil
1) Kebutuhan Fisik
a) Nutrisi
Di Indonesia, kebutuhan kalori untuk orang tidak
hamil adalah 2000 Kkal, sedang untuk ibu hamil dan
menyusui masing-masing adalah 2300 dan 2800
kkal. Kalori dipergunakan untuk produksi energi. Bla
kurang energi akan diambil dari pembakaran protein
yang mestinya dipakai untuk pertumbuhan.
(2) Protein
Protein sangat dibutuhkan untuk perkembangan
buah kehamilan yaitu untuk pertumbuhan janin,
uterus, dan plasenta. Bila wanita tidak hamil,
konsumsi protein yang ideal adalah 0,9
gram/kgBB/hari tetapi selama kehamilan dibutuhkan
tambahan protein hingga 30 gram/hari.
(3) Mineral
Pada prinsipnya semua mineral dapat terpenuhi
dengan makan makanan sehari-hari yaitu
buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Hanya besi yang
tidak bisa terpenuhi dengan makan sehari-hari.
Kebutuhan akan besi pada pertengahan kedua
kehamilan kira-kira 17mg/hari. Untuk memenuhi
kebutuhan ini dibutuhkan suplemen besi 30 mg/hari
dan pada kehamilan kembar atau wanita yang
anemia dibuthkan 60-100mg/hari. Kebutuhan
(4) Vitamin
Vitamin sebenarnya telah terpenuhi dengan
makan sayur dan buah-buahan, tetapi dapat pula
diberikan ekstra vitamin, pemberian asam folat
terbukti mencegah kecacatan pada janin.
(Kuswanti, 2014 h. 118-119)
b) Personal Hygiene
Personal hygiene pada ibu hamil adalah kebersihan
yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi
kemungkinan infeksi, karena badan yang kotor yag
banyak mengandung kuman-kuman. (Siwi walyani, 2015
h. 98)
c) Eliminasi
(1) BAK
Trimester I : frekuensi BAK meningkat karena
kandung kencing tertekan oleh pembesaran uterus.
Trimester II : frekuensi BAK normal kembali karena
uterus telah keluar dari rongga panggul
Trimester III : frekuensi BAK meningkat karena
penurunan kepala ke PAP.
(2) BAB
Defekasi menjadi tidak teratur karena :
(a) Pengaruh relaksasi otot polos oleh estrogen
(c) Pada kehamilan lanjut karena pengaruh
tekanan kepala yang telah masuk panggul.
d) Istirahat
Posisi tidur yang dianjurkan pada ibu hamil adalah
miring ke kiri, kaki kiri lurus, kaki kanan sedikit menekuk
dan diganjal dengan bantal, dan untuk mengurangi rasa
nyeri pada perut, ganja dengan bantal pada perut bawah
sebelah kiri. (Kuswanti, 2014 h. 123)
2) Kebutuhan Psikologis
a) Support Keluarga
Dukungan selama masa kehamilan sangat
dibutuhkan bagi seorang wanita yang sedang hamil,
terutama dari orang terdekat apalagi ibu yang baru
pertama kali hamil. Seorang wanita akan merasa tenang
dan nyaman dengan adanya dukungan dan perhatian
dari orang-orang terdekat.
b) Support Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan harus mampu mengenali tantang
keadaan yang ada disekitar ibu hamil atau pasca
bersalin.
g. Antenatal Care (Pemeriksaan Ibu Hamil)
Asuhan antenatal care adalah suatu program yang terencana
berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu
persiapan persalinan yang aman dan memuaskan. (Mufdillah,
2009 dalam Siwi Walyani, 2015).
Setiap wanita hamil menghadapi resiko komplikasi yang bisa
mengancam nyawanya. Oleh karena itu, setiap wanita hamil
memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode
antenatal :
1) Satu kali kunjungan selama trimester I (sebelum 14 minggu)
2) Satu kali kunjungan selama trimester II (antara mingu 14-28)
3) Dua kali kunjungan selama trimester III (antara minggu
28-40 minggu)
(Yuli Aspiani, 2017 h. 46)
Menurut Siwi Walyani (2015), pelayanan ANC minimal 5T,
meningkat menjadi 7T, dan sekarang menjadi 12T, sedangkan
untuk daerah gondok dan endemik malaria menjadi 14T, yakni
1) Timbang berat badan tinggi badan
Tinggi badan ibu dikategorikan adanya resiko apabila
hasil pengukuran < 145 cm. Berat badan ditimbang setiap ibu
datang atau berkunjung untuk mengetahui kenaikan BB dan
penurunan BB.Kenaikan BB ibu hamil normal rata – rataantara 6,5 kg sampai 16 kg.
2) Tekanan darah
Diukur setiap kali ibu datang atau berkunjung. Deteksi
normal kita pikirkan kearah anemia. Tekanan darah normal
berkisar sistole/diastole : 110/80 – 120/80 mmHg. 3) Pengukuran tinggi fundus uteri
Menggunakan pita sentimeter, letakkan titik nol pada tepi
atas sympisis dan rentangkan sampai fundus uteri (fundus
tidak boleh ditekan)
4) Pemberian tablet tambah darah (Tablet Fe)
Untuk memenuhi kebutuhan volume darah pada ibu hamil
dan nifas, karena masa kehamilan kebutuhan meningkat
seiring dengan pertumbuhan janin.
5) Pemberian imunisasi TT
Untuk melindungi dari tetanus neonatorum. Efek samping
TT yaitu nyeri, kemerah – kemerahan dan bengkak untuk 1 – 2 hari pada tempat penyuntikan.
6) Pemeriksaan Hb
Pemeriksaan Hb dilakukan pada kunjungan ibu hamil
yang pertama kali, lalu diperiksa lagi menjelang persalinan.
Pemeriksaan Hb adalah salah satu upaya untuk mendeteksi
anemia pada ibu hamil.
7) Pemeriksaan protein urine
Untuk mengetahui adanya protein dalam urine ibu hamil.
Protein urine ini untuk mendeteksi ibu hamil kearah
preeklamsi.
Pemeriksaan Veneral Desease Research Laboratoty
(VDRL) untuk mengetahui adanya treponema
pallidum/penyakit menular seksual, antara lain syphilish.
9) Pemeriksaan urine reduksi
Dilakukan pemeriksaan urine reduksi hanya kepada ibu
dengan ibu dengan indikasi penyakit gula/DM atau riwayat
penyakit gula pada keluarga ibu dan suami.
10) Perawatan payudara
Meliputi senam payudara, perawatan payudara, pijat
tekan payudara yang ditunjukkan kepada ibu hamil. Manfaat
perawatan payudara adalah :
a) Menjaga kebersihan payudara, terutama putting susu
b) Mengencangkan serta memperbaiki bentuk puting susu
(pada putting susu terbenam)
c) Merangsang kelenjar – kelenjar susu sehingga produksi ASI lancar
d) Mempersiapkan ibu dalam laktasi
Perawatan payudara dilakukan 2 kali sehari sebelum
mandi dan mulai pada kehamilan 6 bulan.
11) Senam ibu hamil
Bermanfaat membantu ibu dalam persalinan dan
mempercepat pemulihan setelah melahirkan serta
mencagah sembelit.
Pemberian obat malaria diberikan khusus untuk pada ibu
hamil didaerah endemik malaria atau kepada ibu dengan
gejala khas malaria yaitu panas tinggi disertai menggigil.
13) Pemberian kapsul minyak beryodium
Kekurangan yodium dipengaruhi oleh faktor – faktor lingkungan dimana tanah dan air tidak mengandung unsur
yodium. Akibat kekurangan yodium dapat mengakibatkan
gondok dan kretin yang ditandai dengan :
a) Gangguan fungsi mental
b) Gangguan fungsi pendengaran
c) Gangguan pertumbuhan
d) Gangguan kadar hormon yang rend
14) Temu Wicara
Adalah suatu bentuk wawancara (tatap muka) untuk
menolong orang lain memperoleh pengertian yang lebih baik
mengenai dirinya dalam usahanya untuk memahami dan
mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya.
Jadwal pemeriksaan ANC :
1) Pemeriksaan Pertama
Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah
diketahui terlambat haid.
2) Pemeriksaan Ulang
a) Setiap bulan sampai umur kehamilan 6 sampai 7 bulan
c) Setiap 1 minggu sejak umur kehamilan 8 bulan sampai
terjadi persalinan.
h. Kehamilan dengan Penyulit
1) Anemia pada Kehamilan
Menurut Varney (2007; h. 623), anemia didefinisikan
sebagai penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan
kadar haemoglobin didalam sirkulasi darah. Untuk wanita
tidak hamil disebut anemia apabila kadar Hb kurang dari
12,0 gram per 100 mililiter. Sedangkan untuk wanita hamil,
nilai normal Hb yaitu 10,0 gram per 100 mililiter. Tanda
gejala anemia antara lain letih, sering mengantuk, pusing,
lemah, nyeri kepala, dan kulit pucat.
Perubahan fisiologis alami yang terjadi selama kehamilan
akan memengaruhi jumlah sel darah normal pada
kehamilan. Terdapat peningkatan jumlah sel darah merah
didalam sirkulasi, namun jumlahnya tidak seimbang dengan
peningkatan volume plasma. Ketidakseimbangan ini akan
menyebabkan penurunan kadar haemoglobin. Peningkatan
kadar eritrosit juga merupakan salah satu penyebab
peningkatan kebutuhan akan zat besi selama kehamilan
sekaligus untuk janin (Varney, 2007; h. 623).
Pemberian konseling tentang pengaturan diet sangat
penting diberkan karena zat besi lebih mudah diserap dari
terkandung dalam sayuran hijau, daging merah, kuning telur,
hati, tiram, dan beberapa sereal (Varney, 2007; h. 624)
2) Letak Lintang
Adalah suatu keadaan dimana janin melintang didalam
uterus dengan kepala pada sisi yang satu, sedangkan
bokong pada sisi yang lain. (Sarwono, 2005 dalam Yuli
Aspiani 2017 h. 302)
Etiologi letak lintang menurut Mochtar (1998) dalam Yuli
Aspiani (2017) :
a) Fiksasi kepala tidak ada, karena panggul sempit,
hidrosefalus, anensepalus, plasenta previa, dan
tumor-tumor pelvis.
b) Gemelli (kehamilan ganda)
c) Kelainan uterus
d) Lumbal scoliosis
e) Janin sudah bergerak pada hidramnion, multi paritas,
anak kecil, atau sudah mati
f) Kandung kemih serta rektum penuh
Penatalaksaan letak lintang menurut Yuli Aspiani (2017),
yaitu :
a) Pada kehamilan
Pada primigravida umur kehamilan kurang dari 28
multigravida umur kehamilan kurang dari 30 minggu
posisi lutut dada, kalau gagal posisi lutut dada sampai
persalinan.
b) Pada Persalinan
Jika pembukaan lebih dari 4 cm pada primigravida
dengan janin hidup dilakukan sectio caesaria, jika janin
mati, tunggu pembukaan lengkap, kemudian dilakukan
embriotomi. Pada multigravida dengan janin hidup dan
riwayat obstetri baik dilakukan versi ekstraksi, jika
riwayat obstetri jelek lakukan SC. Jika janin mati lakukan
embriotomi.
Beberapa literatur menyebutkan salah satu
penanganan dari letak lintang yaitu versi luar atau ECV
(Eksternal Cephalic Version). Versi adalah memutar
janin menjadi presentasi kepala dengan manipulasi
eksternal. Versi luar adalah manipulasi sepenuhnya
dilakukan melalui dinding abdomen. Adapun komplikasi
dari tindakan versi luar diantaranya solusio plasenta,
ruptur uteri, emboli air ketuban, hemorrhagia
fetomaternal, persalinan preterm, fraktur femur janin,
lilitan tali pusat, ketuban pecah, gawat janin, hingga
IUFD.
2. Persalinan
a. Pengertian Persalinan
Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin
dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar
kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa
bantuan. (Manuaba, 1998 dalam Shofa Ilmiah, 2015)
b. Etiologi Persalinan
Beberapa teori timbulnya persalinan menurut Mochtar (1998)
dalam Yuli Aspiani (2017), yaitu :
1) Teori Penurunan Hormon
Satu sampai dua minggu sebelum partus mulai terjadi
penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron.
Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos rahim
dan akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah
sehingga timbul his bila kadar progesteron turun.
2) Teori Plasenta menjadi Tua
Akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan
progesteron yang menyebabkan kekejangan pembuluh
darah. Hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim.
3) Teori Distensi Rahim
Rahim yang menjadi besar dan merenggang
menyebabkan iskemia otot-otot rahim, sehingga
Dibelakang serviks terletak ganglion servikale (fleksus
franskenhouser). Bila ganglion ini digeser dan tekanan,
misalnya oleh kepala janin, akan timbul kontraksi uterus.
c. Tanda dan Gejala dimulainya Proses Persalinan
Menurut Wagiyo dan Putrono (2016), terdapat 2 macam
tanda dan gejala dimulainya persalinan, yaitu :
1) Tanda-tanda palsu
His dengan interval tidak teratur, frekuensi semakin lama
tidak mengalami peningkatan, rasa nyeri saat kontraksi
hanya bagian depan, tidak keluar lendir dan darah, tidak ada
perubahan serviks uteri, dan bagian presentasi janin tidak
mengalami penurunan.
2) Tanda-tanda pasti
His dengan interval teratur, frekuensi semakin lama
semakin meningkat baik durasi maupun intensitasnya, rasa
nyeri menjalar mulai dari bagian belakang ke bagian depan,
keluar lendir dn darah, serviks uteri mengalami perubahan
dari melunak, menipis, dan berdilatasi, dan bagian
presentasi janin mengalami penurunan.
d. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan
1) Power/Tenaga
Power utama pada persalinan adalah tenaga/kekuatan
yang dihasilkan oleh kontraksi dan retraksi otot-otot rahim.
terjadi sementara waktu disebut kontraksi. Kontraksi ini
terjadi diluar sadar sedangkan retraksi mengejan adalah
tenaga kedua (otot-otot perut dan diafragma) digunakan
dalam kala II persalinan. Tenaga dipakai untuk mendorong
bayi keluar dan merupakan kekuatan ekspulsi yang
dihasilkan oleh otot-otot volunter ibu. (Yuli Aspiani, 2017 h.
209)
Menurut Shofa Ilmiah (2015), kontraksi uterus atau his
yang normal mempunyai sifat simetris, fundus dominan,
relaksasi, involuntir atau terjadi diluar kehendak, intermitten
(terjadi secara berkala), terasa sakit, dan terkoordinasi.
2) Passage (Jalan Lahir)
Janin harus berjalan lewat rongga panggul atau serviks
dan vagina sebelum dilahirkan untuk dapat dilahirkan, janin
harus mengatasi pula tahanan atau resisten yang
ditimbulkan oleh struktur dasar panggul dan sekitarnya. (Yuli
Aspiani, 2017 h. 209)
Menurut Shofa Ilmiah (2015), passage terdiri dari :
a) Bagian keras tulang-tulang panggul (rangka panggul) :
(1) Os. Coxae (Os. Illium, Os. Ischium, dan Os. Pubis)
(2) Os. Sacrum = promontorium
(3) Os. Coccygis
b) Bagian lunak : otot-otot, jaringan dan ligamen-ligamen
(1) Pintu Atas Panggul (PAP) = disebut inlet dibatasi
oleh promontorium, linea inominata dan pinggir atas
symphisis.
(2) Ruang tengah panggul (RTP) kira-kira pada spina
ischiadica disebut middlet.
(3) Pintu Bawah Panggul (PBP) dibatasi simfisis dan
arkus pubis disebut outlet.
(4) Ruang panggul yang sebenarnya (pelvis cavity)
berada antara inlet dan outlet.
Adapun bidang-bidang hodge menurut Kuswanti (2014),
yaitu :
a) Hodge I yaitu bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu
atas panggul (PAP) dengan bagian atas symphisis dan
promontorium.
b) Hodge II yaitu sejajar dengan hodge I, terletak setinggi
bagian bawah symphysis.
c) Hodge III yaitu sejajar dengan hodge I dan II, terletak
setinggi spina ischiadica kanan dan kiri.
d) Hodge IV yaitu sejajar dengan hodge I, II, III, terletak
setinggi os coccygis.
3) Passanger
Passenger utama lewat jalan lahir adalah janin dan
itu disertai dengan plasenta selaput dan cairan ketuban atau
amnion. (Yuli Aspiani, 2017 h. 209)
4) Psikologis
Dalam persalinan terdapat kebutuhan emosional jika
kebutuhan tidak terpenuhi paling tidak sama seperti
kebutuhan jasmaninya. Prognosis keseluruhan wanita
tersebut yang berkenan dengan kehadiran anaknya terkena
akibat yang merugikan. (Yuli Aspiani, 2017 h. 209)
Menurut Shofa Ilmiah (2015), psikologis meliputi :
a) Kondisi psikologis ibu sendiri, emosi dan persiapan
intelektual
b) Pengalaman melahirkan bayi sebelumnya
c) Kebiasaan adat
d) Dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu
5) Penolong
Peran dari penolong persalinan dalam hal ini Bidan
adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang
mungkin terjadi pada ibu dan janin. Proses tergantung dari
kemampuan skill dan kesiapan penolong dalam menghadapi
proses persalinan. (Shofa Ilmiah, 2015 h. 30)
e. Tahapan Persalinan
1) Kala I
Pada kala I serviks membuka sampai terjadi pembukaan
dimulai bila timbul his dan wanita tersebut mengeluarkan
lendir yang bersemu darah (bloody show) yang berasal dari
lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan
mendatar. (Shofa Ilmiah, 2015 h. 4)
Menurut Yuli Aspiani (2017), kala I dibagi menjadi 2 fase,
yaitu :
a) Fase Laten
Dimulainya sejak awal kontraksi yang menyebabkan
penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap.
Pembukaan serviks kurang dari 4 cm dan biasanya
berlangsung dibawah 8 jam.
b) Fase Aktif
Dapat dibedaan menjadi 3 fase :
(1) Akselerasi : pembukaan dari 3 cm menjadi 4 cm yang
membutuhkan waktu 2 jam
(2) Dilatasi maksimal : pembukaan dari 4 cm menjadi 9
cm dalam waktu 2 jam
(3) Deselarasi : pembukaan menjadi lambat, dari 9
menjadi 10 cm dalam waktu 2 jam.
2) Kala II
Kala dua persalinan dimulai ketika pembukaan serviks
sudah lengkap (10cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi.
Kala dua dikenal juga sebagai kala pengeluaran. (Yuli
Menurut Yuli Aspiani (2017), tanda gejala kala II yaitu :
a) Ibu merasakan keinginan meneran bersamaan dengan
terjadinya kontraksi.
b) Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada
rektum dan atau vaginanya.
c) Perineum terlihat menonjol
d) Vulva-vagina dan sfingter ani terlihat membuka
e) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah.
3) Kala III
Setelah bayi lahir, uterus keras dengan fundus uteriagak
diatas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi
lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya (6 hingga 15
menit) setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan
sedikit tekanan pada bagian fundus uteri. Lepasnya plasenta
dan keluarnya dari dalam uterus biasanya disertai dengan
pengeluaran darah. (Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 202)
4) Kala IV
Setelah plasenta lahir, kontraksi rahim tetap kuat dengan
amplitude 60 sampai 80 mmHg, kekuatan kontraksi ini tidak
diikuti oleh interval pembuluh darah tertutup rapat dan terjadi
kesempatan membentuk thrombus. Melalui kontraksi yang
kuat dan pembentukan thrombus terjadi penghentian
pengeluaran darah post partum. Kekuatan his dapat
oksitosin oleh kelenjar hipofise posterior. Pada kala IV
dilakukan observasi kesadaran ibu, pemeriksaan TTV,
kontraksi uterus, perdarahan, tinggi fundus uteri, dan
kandung kemih. (Yuli Aspiani, 2017 h. 212)
f. Asuhan Persalinan Normal
Dalam buku Asuhan Persalinan Normal oleh Widia Shofa
Ilmiah (2015), langkah-langkah pertolongan persalinan normal,
adalah sebagai berikut :
1) Mendengar dan melihat tanda gejala kala II :
a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran (doran)
b) Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada
rektum dan vagina (teknus)
c) Perineum tampak menonjol (perjol)
d) Vulva dan sfingter ani membuka (vulka)
2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan
esensial untuk mneolong persalinan dan menatalaksana
komplikasi ibu daan BBL
(Untuk asfiksia sediakan tempat datar dan keras, 2 kain dan
1 handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt (dengan
jarak 60 cm dari tubuh bayi), menggelar kain diatas perut ibu
dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi, siapkan
oksitosin 10 unit dan spuit steril sekali pakai didalam partus
set).
4) Mencuci tangan dan keringkan dengan tissue/handuk
5) Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan
untuk PD
6) Masukkan oksitosin ke dalam spuit (gunkan tangan yang
memakai sarung tangan DTT/steril, pastikan tidak terjadi
kontaminasi pada spuit).
7) Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan
hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan
kapan DTT
8) Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan
lengkap (bila selaput kektuban belum pecah dan pembukaan
sudah lengkap, lakukan amniotomi)
9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan
tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam
larutan klorin 0,5% selama 10 menit
10) Periksa DJJ setelah kontraksi/saat relaksasi uterus untuk
memastikan bahwa DJJ dalam batas normal
(120-160x/menit)
11) Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan
janin baik dan bantu ibu dalam menemukanposisi yang
nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran (bila
bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang
diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman)
13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada
dorongan kuat untuk meneran
a) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan
efektif
b) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan
perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai
c) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai
plihannya, kecuali posisi terlentang dalam waktu lama,
anjurkan ibu istirahat diantara kontranksi.
d) Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat
untuk ibu, berikan asupan cairan peroral yang cukup.
14) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai, segera rujuk bayi
jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120
menit meneran (primigravida) atau 60 menit meneran
(multigravida).
15) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil
posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan
untuk meneran dalam 60 menit.
16) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) diperut
ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter
17) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong
ibu.
18) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan
alat dan bahan
19) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan
20) Setelah tampak kepala bayi denga diameter 5-6 cm
membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu
tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan
yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi
defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk
meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal.
21) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil
tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan
proses kelahiran bayi.
22) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara
spontan.
23) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang
secara biparietal. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah
bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus
pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk
melahirkan bahu belakang
24) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah
sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan
memegang lengan dan siku sebelah atas.
25) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas
berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki serta
pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari
lainnya.
26) Lakukan penilaian selintas
27) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa
kesulitan?
28) Apakah bayi bergerak aktif?
Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau megap-megap
lakukan langkah resusitasi
29) Keringkan tubuh bayi
30) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi
dalam uterus (hamil tunggal)
31) Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus
berkontraksi dengan baik
32) Dalam wakt 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10
unit IM 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi
sebelum menyuntikkan oksitosin)
33) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan
klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong tali pusat ke
arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal
34) Pemotongan dan pengikatan tali pusat
a) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit
(lindungi perut bayi) dan lakukan pengguntingan tali
pusat diantara 2 klem tersebut.
b) Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi
kembudian melingkarkan kembali benang tersebut dan
mengikatnya dengan simpul kunci dengan sisi lainnya.
c) Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah
disediakan
35) Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke bayi, letakkan bayi
tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi
menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada
diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari
putting payudara ibu.
36) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi
dikepala bayi
37) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari
vulva
38) Letakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, ditepi atas
simfisis, untuk mendeteksi. Tanan lain menegangkan tali
pusat.
39) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah
belakang-atas (dorso kranial) secara hati-hati (untuk
mencegah inversio uteri).
a) Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan
penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul
kontraksi berikutnyadan ulangi prosedur diatas.
b) Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami
atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting
susu.
c) Lakukan penegangan tali pusat dan dorongan dorso
kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran
sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar
lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti proses jalan
lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial)
d) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem
hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan
plasenta.
e) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan
tali pusat :
(1) Beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM
(2) Lakukan kateterisasi (aseptik) jika kandung kemih
penuh
(3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan
(5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi
lahir atau bila terjadi perdarahan segera lakukan
plasenta manual.
40) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta
dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga
selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan
plasenta pada wadah yang telah disediakan.
41) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan
masase uterus, letakkan talapak tangan di fundus dan
lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut
hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)
42) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan
pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan
plasenta ke dalam kantung plastik dan tempat khusus.
43) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.
Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif segera
lakukan penjahitan.
44) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak erjadi
perdarahan pervaginam
45) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu
paling sedikit 1 jam
(a) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi
(b) Menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15
menit.
(c) Setelah satu jam, lakukan penimbangan atau
pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis
dan vitamin K, 1 mg IM di paha kiri anterolateral.
(d) Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berian suntikan
imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.
46) Lanjutkan pemantauan pemantauan kontraksi dan
mencegah perdarahan pervaginam.
a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan
b) Setiap 15 menit pertama pada 1 jam pertama pasca
persalinan
c) Setiap 20-30 menit pasca persalinan
d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan
asuhan yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia
uteri.
47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan
menilai kontraksi
48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah
49) Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15
menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30
menit selama jam kedua pasca persalinan.
50) Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi
51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan
klorin 0,5% untuk dekontaminasi.
52) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat yang
sesuai
53) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa
cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai
pakaian yang bersih dan kering.
54) Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu memberi
ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan
makanan yang diinginkan.
55) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%
56) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,
balik bagian dalam ke luar dan redam dalam larutan klorin
0,5% selama 10 menit.
57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.
58) Lengkapi partograf, periksa tanda-tanda vital dan asuhan
kala IV.
g. Partograf (Wagiyo dan Putrono, 2016; h. 270)
Partograf adalah alat pencatatan persalinan untuk menilai
keadaan ibu, janin dan seluruh proses persalinan. Partograf
digunakan untuk mendeteksi jika ada penyimpangan dari
persalinan, sehingga untuk menjadi partus abnormal dan
memerlukan tindakan bantuan lain untuk menyelesaikan
berbagai grafik dan kode yang menggambarkan berbagai
parameter untuk menilai kemajuan persalinan. Gambaran
partograf dinyatakan dengan garis tiap parameter (vertikal)
terhadap garis perjalanan waktu (horizontal).
Daerah sebelah kiri garis waspada merupakan garis
observasi. Daerah diantara garis waspada dan garis bertindak
merupakan daerah perlu pertimbangan untuk merujuk atau
mengambil tindakan sedangkan daerah disebelah kanan garis
tindakan adalah daerah harus segera bertindak.
h. Persalinan dengan Penyulit
1) CPD (Chephalopelvic Disproportion)
Abnormalitas panggul dimana sering terjadi ketika kepala
fetus terlalu besar untuk melalui rongga pelvis. Ini dapat
terjadi bila kepala terlalu besar. Panggul kecil dapat
disebabkan oleh karena penyakit rakhitis yang terjadi pada
masa anak-anak, menyebabkan kelainan bentuk pada pelvis
(Yuli Aspiani, 2017; h. 261). Bentuk panggul wanita yang
paling ideal untuk persalinan adalah bentuk gynekoid.
Kelainan bentuk atau ukuran panggul dapat diketahui dari
anamnesa dan pemeriksaan yang baik. Anamnesis perlu
ditanyakan riwayat penyakit dahulu, ada/tidaknya penyakit
rachitis, patah tulang panggul, coxitis dan sebagainya. Pada
2500 gram akan sulit dilahirkan (Wagiyo dan Putrono, 2016;
h. 352)
2) Partus Lama
Partus lama adalah suatu persalinan yang berlangsung
lebih dari 24 jam dimana kala 1 berlangsung lebih dari 20
jam dan kala 2 lebih dari 2 jam. (Depkes RI, 2005 dalam
Yulia Aspiani, 201 h. 241)
Menurut Yuli Aspiani (2017), partus lama jika tidak segera
diakhiri akan menimbulkan :
a) Kelelahan pada ibu karena mengejan terus-menerus
sedangkan intake kalori biasanya berkurang.
b) Dehidrasi dan gangguan keseimbangan asam
basa/elektrolit karena intake cairan yang kurang.
c) Gawat janin sampai kematian karena asfiksia dalam
jalan lahir.
d) Infeksi rahim, timbul karena ketuban pecah lama
sehingga terjadi infeksi rahim yang dipermudah karena
adanya manipulasi penolong yang kurang steril.
e) Perlukaan jalan lahir, timbulkan persalinan yang
traumatik.
Menurut Wiknjosastro (1999) dalam Yuli Aspiani (2017),
penatalaksanaan pada klien dengan partus lama :
(1) Pantau keadaan umum ibu dan janin (termasuk TTV
dan tingkat dehidrasinya)
(2) Perbaiki keadaan umum. Tetap memperhatikan
asupan gizi ibu terutama asupan cairan
(3) Atur posisi ibu (sesuai degan penanganan persalinan
normal)
(4) Periksa benda keton dalam urin dan berikan cairan
baik oral maupun pararental dan upayakan buang air
kecil (pasang kateter kalau perlu)
(5) Berikan analgesik : tramadol atau petidin 25 mg IM
(maximum 1 mg/kgBB) atau morin jika pasien
merasakan nyeri
(6) Kaji kembali partograf, tentukan apakah pasien
berada dalam persalinan.
(7) Pemantauan his dan mengontrol DJJ setiap setelah
his
(8) Beri oksigen bila terjadi tanda-tanda gawat janin
(9) Pemberian antibiotika : penisilin prokain : 1 juta IU IM
atau streptomisin : 1 gr IM
(10) Infus cairan (larutan garam fisiologis/Nacl, larutan
glukosa 5-10% pada jam pertama)
b) Penatalaksanaan Khusus
(a) Jika fase laten lebih dari 8 jam dan tidak ada
tanda-tanda kemajuan, lakukan penilaian ulang
terhadap serviks.
(b) Jika tidak ada perubahan pada pendataran atau
pembukaan serviks dan tidak ada gawat janin,
mungkin pasien belum inpartu.
(c) Jika ada kemajuan dalam pendataran atau
pembukaan serviks lakukan amniotomi dan
induksi persalinan dengan oksitosin atau
prostaglandin
(d) Lakukan penilaian ulang setiap 4 jam
(e) Jika pasien tidak mask fase aktif setelah
dilakukan pemberian oksitosin selama 8 jam,
lakukan SC
(f) Jika didapatkan tanda-tanda infeksi (demam,
cairan berbau) :
(i) Lakukan akselerasi persalinan dengan
oksitosin
(ii) Berikan antibiotika kombinasi sampai
persalinan : ampisilin 2 g IV setiap 6 jam,
ditambah gentaisin 5 mg/kgBB IV setiap 24
jam.
(iii) Jika terjadi persalinan pervaginam stop
(g) Jika dilakukan SC, lanjutkan pemberian
antibiotika ditambah metronidazole 500 mg IV
setiap 8 jam sampai ibu bebas demam selama 48
jam.
(2) Fase aktif memanjang
(a) Jika tidak ada tanda-tanda Cepalo Pelvic
Disproportion atau obstruksi dan ketuban masih
utuh, pecahkan ketuban
(b) Nilai his
Jika his adekuat pertimbangkan disproporsi,
obstruksi, malposisi/mal presentasi. Lakukan
penanganan umum untuk memperbaiki his dan
mempercepat kemajuan persalinan
3) Induksi Persalinan
Menurut Williams (2013; h. 522), induksi adalah stimulasi
kontraksi sebelum awitan persalinan spontan, dengan atau
tanpa ruptur membran. Indikasi dilakukannya induksi
diantaranya ruptur membran disertai korioamnionitis,
preeklamsia berat, hipertensi gestasional, status janin
meresahkan, kehamilan lebih bulan, dan berbagai kondisi
medis ibu seperti hipertensi kronis dan diabetes.
Kontraindikasi dilakukannya induksi diantaranya
panggul sempit, plasentasi abnormal, dan kondisi seperti
infeksi herpes genital aktif atau kanker serviks.
Macam-macam farmakologis induksi :
a) Prostaglandin E2
Pemberian prostaglandin E2 lokal (dinoprostone)
sering digunakan untuk mematangkan serviks. Bentuk
gel nya, prepidil, tersedia dalam suntikan 2,5 mL untuk
pemberian intraserviks berisi 0,5 mg dinoprostone.
Dengan ibu dalam posisi telentang, ujung suntikan yang
belum diisi diletakkan dalam serviks, dan gel dimasukkan
tepat dibawah os serviks interna. Setelah pemberian, ibu
tetap berbaring selama setidaknya 30 menit. Dosis dapat
diulang setiap 6 jam, dengan maksimum tiga dosis yang
direkomendasikan dalam 24 jam (Wiliams, 2013; h. 524).
b) Prostaglandin E1
Misoprostol atau cytotec adalah prostaglandin E1
sintetik, diakui sebagai tablet 100 atau 200 µg untuk
pencegahan ulkus peptikum. Pemberian misoprostol
dapat melalui pervagina atau per oral. Dosis misoprostol
intravaginal 50µg telah dikaitkan dengan peningkatan
signifikan terjadi takisistol uterus, pasase mekonium, dan
aspirasi mekonium dibandingkan dengan gel
prostaglandin E2. Tablet prostaglandin E1 juga efektif
yang serupa dengan pemberian intravagina untuk
mematangkan serviks. Dosis pemberian oral yaitu 100µg
sama efektifnya dengan dosis intravagina 25µg (Wiliams,
2013; h. 525)
c) Oksitosin
Tujuan induksi atau augmentasi adalah untuk
menghasilkan aktivitas uterus yang cukup untuk
menghasilkan perubahan serviks dan penurunan janin,
sembari menghindari berkembangnya status janin yang
meresahkan. Dosis untuk pemberian oksitosin yaitu satu
ampul 1 mL yang mengandung 10 unit dilarutkan
kedalam 1000mL larutan kristaloid dan diberikan melalui
pompa infus. Terdapat banyak sumber mengenai jumlah
regimen (tetesan infus) induksi oksitosin. Namun,
menurut data dari Parkland Hospital, Satin dkk (1992)
diantara 1112 perempuan yang menjalani induksi
dengan tetesan infus 6 tetes/menit menghasilkan
rata-rata waktu masuk persalinan lebih singkat, lebih sedikit
induksi yang gagal, dan tidak ada kasus sepsis
neonatus. Sedangkan interval untuk meningkatkan dosis
oksitosin bervariasi dari 15 sampai 40 menit dengan
tambahan 2mU/menit (Williams, 2013; h. 528)
Adalah perdarahan dalam keadaan dimana plasenta
telah lahir lengkap dan kontraksi rahim baik, dapat dipastikan
bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan jalan
lahir.
Terdapat 4 derajat robekan yang bisa terjadi saat
pelahiran menurut Yuli Aspiani (2017), diantaranya :
a) Tingkat I : robekan hanya pada selaput lendir vagina dan
jaringan ikat
b) Tingkat II : robekan mengenai mukosa vagina, jaringan
ikat, dan otot di bawahnya tetapi tidak mengenai sfingter
ani
c) Tingkat III : robekan mengenai transeksi lengkap dan
otot sfingter ani
d) Tingkat IV : robekan sampai mukosa rectum
3. Bayi Baru Lahir (BBL)
a. Definisi
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur
kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2500
gram sampai 4000 gram. (Departemen Kesehatan, 2005 dalam
Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 411)
Bayi Baru Lahir adalah bayi yang lahir dan umur kelahiran 37
minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram (Shofa
Ilmiah, 2015 h. 244)
Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus,
adalah :
1) Penyesuaian sistem pernapasan
Penyesuaian yang paling kritis dan segera terjadi yang
dialami bayi baru lahir adalah sistem pernapasan. Udara
harus diganti oleh cairan yang mengisi saluran pernapasan
sampai alveoli. (Shofa Ilmiah, 2015 h. 244)
2) Penyesuaian sistem kardiovaskuler
Sistem sirkulasi jantung mulai berdenyut pada minggu
ketiga kehamilan. Selama kehidupan janin, jantung
mendistribusikan oksigen dan zat nutrisi yang disuplai
melalui plasenta. (Shofa Ilmiah, 2015 h. 244)
Setelah bayi lahir, sistem kardiovaskular mengalami
perubahan yang mencolok, dimana voramen ovale, duktus
arterious, dan duktus venosus menutup. Arteri umbilikalis,
vena umbilikalis, dan arteri hepatika ligamen. Nafas pertama
yang dilakukan bayi baru lahir membuat paru-paru
berkembang dan menurunkan resistensi vaskular pulmoner,
sehingga darah paru mengalir. (Wagiyo dan Putrono, 2016
h. 412)
3) Penyesuaian Suhu Tubuh
Segera setelah bayi lahir, bayi akan berada ditempat
yang suhu lingkungannya lebih rendah dari lingkungan
36,5˚C sampai 37˚C. Bila bayi dibiarkan dalam suhu kamar (25˚C) maka bayi akan kehilangan panas melalui evaporasi
(penguapan), konveksi dan radiasi sebanyak 200
kalori/kg/BB/menit, sedangkan bentuk panas yang dapat di
produksi hanya per sepuluh dari jumlah kehilangan panas
diatas, dalam waktu yang bersamaan. (Bonak dan Jensen,
2004 : 376 dalam Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 415)
4) Penyesuaian Gastro intestinal
Sebelum lahir, janin cukup menghisap dan menelan air
ketuban. Refleks gumoh dan batuk yang matang sudah
terbentuk dengan baik pada saat lahir. (Shofa Ilmiah, 2015
h. 245)
Pada saat bayi lahir, didalam saluran cernanya tidak
terdapat bakteri. Setelah lahir, orifisum oral dan orifisum anal
memungkinkan bakteri dan udara sehingga bising usus
dapat kita dengakan satu jam setelah lahir. Kapasitas
lambung bayi bervariasi dari 30-90 ml sangat tergantung
pada ukuran bayi. (Wagiyo dan Putrono, 2016 g. 416)
5) Penyesuaian Sistem Kekebalan Tubuh
Pada masa awal kehidupan janin, sel-sel yang menyuplai
imunitas sudah mulai berkembang. Namun sel-sel ini tidak
aktif selama beberapa bulan. Bayi baru lahir dilindungi oleh
sangat rentan terhadap mikroorganisme, oleh karena itu bayi
rentan terkena infeksi. (Shofa Ilmiah, 2015 h. 245)
6) Sistem Hematopoiesis
Volume darah bayi baru lahir bervariasi dari 80-110
mg/kg. Nilai rata-rata hemoglobin dan sel darah merah lebih
tinggi dari nilai normal orang dewasa. Hemoglobin bayi baru
lahir berkisar antara 14,5-22,5 gr/dl, hematokrit bervariasi
dari 44% sampai 72% dan SDM berkisar antara 5-7,5
juta/mm3. Leukosit janin dengan nilai hitung sel berkisar
antara 18.000/mm3. (Bobak dan Jensen, 2004 : 365 dalam
Wagiyo dan Putrono, 2016 h. 414)
7) Traktus Urinarius
Pada bulan ke-4 kehidupan janin, ginjal terbentuk
didalam rahim, urine sudah terbentuk dan diekskresikan ke
dalamcairan amnion. Pada kehamilan cukup bulan, ginjal
menempati sebagian besar dinding abdomen posterior,
fungsi ginjal sudah sama dengan fungsi ginjal pada orang
dewasa sehingga pada saat lahir didalam kandung kemih
bayi terisi sedikit urine sehingga kemungkinan bayi baru lahir
tidak akan iksi sampai dalam waktu 12 jam sampai 24 jam.
(Bobak dan Jensen, 2004 dalam Wagiyo dan Putrono, 2016
h. 417)
Saat lahir ovarium bayi wanita berisi beribu-ribu sel
germinal primitif yang akan berkurang sekitar 90% sejak bayi
baru lahir sampai dewasa. Genetalia eksterna biasanya
edematosa disertai hiperpigmentasi. Pada bayi prematur,
klitoris menonjol, dan labia mayora kecil dan terbuka.
Testis turun kedalam skrotum pada 90% bayi baru lahir
laki-laki. Prepisium yang ketat sering kali dijumpai pada bayi
baru lahir. Muara uretra dapat tertutup prepusium dan tidak
dapat ditarik kebelakang selama 3-4 tahun.
c. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir
Adalah asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir selama
satu jam pertama setelah kelahiran. (Shofa Ilmiah, 2015 h. 245)
Asuhan segera bayi baru lahir menurut Shofa Ilmiah (2015),
yaitu :
1) Mempertahankan suhu tubuh bayi
Pada waktu baru lahir, bayi belum mampu mengatur suhu
tetap suhu badannya dan membutuhkan pengaturan dari
luar untuk membuatnya tetap hangat.
2) Membersihkan jalan nafas
Bayi normal akan menangis spontan segera setelah lahir.
Apabila tidak langsung menangis, penolong segera
melakukan resusitasi
Sebelum memotong tali pusat, dipastikan bahwa tali
pusat telah di klem dengan baik untuk mencegah terjadinya
perdarahan. Alat pengikat tali pusat atau klem dan gunting
steril harus selalu siap tersedia di ambulans, di kamar
bersalin, ruang penerima bayi, dan ruang perawatan bayi.
Tali pusat dipotong 3 cm dari dinding perut bayi. Luka tali at
dibalut kasa steril. Pembalut tersebut diganti setiap hari atau
setiap tali basah atau kotor.
4) Memberi Vitamin K
Kejadian perdarahan karena defisiensi vitamin K pada
bayi baru lahir dilaporkan cukup tinggi, berkisar antara
0,25-0,5%. Untuk mencegah terjadinya perdarahan tersebut,
diberi vitamin K parental dengan dosis 0,5-1 mg secara IM
5) Memberi obat tetes atau salep mata
Didaerah di mana prevalensi gonorhoe tinggi, setiap bayi
baru lahir perlu diberi alep mata sesudah lima jam bayi lahir.
Pemberian obat mata chloramphenicol 0,5% dianjurkan
untuk pencegahan penyakit mata karena klamidia (penyakit
menular seksual)
6) Pemantauan Bayi Lahir
Tujuan pemantauan bayi baru lahir adalah untuk
mengetahui aktivitas bayi normal atau tidak dan identifikasi
perhatian keluarga dan penolong persalinan serta tindak
lanjut petugas kesehatan.
d. Pemeriksaan Fisik pada Bayi Baru Lahir
Adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa
tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil
pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. (Wagiyo dan
Putrono, 2016 h. 427)
Tujuan dari pemeriksaan fisik menurut Wagiyodan Putrono
(2016), adalah :
1) Menentukan status kesehatan
2) Mengidentifikasi masalah
3) Mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan
4) Untuk mengenal dan menemukan kelainan yang perlu
mendapat tindakan segera
5) Untuk menentukan data objektif dari riwayat keperawatan
klien.
Prosedur pelaksanaan pemeriksaan fisik menurut Wagiyo
dan Putrono (2016), adalah :
1) Tanda-tanda vital
Suhu axila 36,5 C-37 C, suhu stabil setelah 8-10 jam
kelahiran, frekuensi jantung 120-140 denyut/menit,
pernafasa bayi baru lahir rata-rata 30-60 kali/menit dengan
Berat badan lahir 2500-4000 gram, panjang badan dari
kepala sampai tumit 45-55 cm, lingkar kepala diukur pada
bagian yang terbesar yaitu oksipito-frontalis 33-35 cm,
lingkar dada mengukur pada garis buah dada, sekitar 30-33
cm, lingkar abdomen mengukur di bawah umbilikalis, ukuran
sama dengan lingkaran dada.
3) Dilanjutkan pemeriksaan secara head to toe dari kepala,
wajah,mata,hidung, mulut, telinga, leher, dada, paru,
jantung, abdomen, ekstermitas atas,ekstermitas bawah,
spinal, genetalia, anus dan rektum, kulit.
4) Refleks
a) Refleks mencari puting (rooting)
b) Refleks menghisap (sucking)
c) Refleks menggenggam
d) Refleks moro
e) Refleks leher asimetrik tonik
f) Refleks melangkah
e. Kunjungan Neonatus
Dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak pelaksanaan
kesehatan bayi baru lahir oleh bidan dilaksanakan minimal 3
kali, yaitu :
Menurut jurnal penelitian Diah (2012), kunjungan neonatus
bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap
pelayanan kesehatan dasar, mengetahui bila terdapat kelainan
pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan.
Berdasarkan PMK no. 53 tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Neonatal Esensial, dalam setiap kunjungan
neonatus, hal yang harus dilakukan petugas kesehatan :
1) Menanyakan kepada ibu masalah yang dihadapi oleh
bayinya
2) Apabila menemukan bayi sakit, harus mampu
mengklasifikasikan penyakit bayi untuk :
a) Kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri
b) Diare
c) Ikterus
d) Kemungkinan berat badan rendah
3) Menangani masalah pemberian ASI
4) Menentukan status imunisasi
5) Menentukan masalah atau keluhan lain
6) Menentukan tindakan dan memberikan pengobatan bila
diperlukan
7) Bila perlu, merujuk bayi muda dan memberi tindakan pra
rujukan
4. Nifas
a. Pengertian
Masa nifas atau puerperium adalah dimulai sejak 1 jam
setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari)
setelah itu. (Hadijono, 2008 dalam Yuli Aspiani, 2017 h. 459)
Puerperium/nifas adalah masa sesudah persalinan simulai
setelah kelahiran plasenta san berakhirnya ketika alat-alat
kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas
berlangsung selama kurang lebih 6 minggu. (Pelayanan
Kesehatan Maternal dan Neonatal, 2002 dalam Yuli Aspiani,
2017 h. 459)
b. Tahap Masa Nifas
Masa nifas ibagi menjai 3 tahap menurut Yuli Aspiani, yaitu :
1) Puerperium Dini
Merupakan masa kepulihan, yang dalam hal ini ibu
telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam
agama Islam, dianggap bersih dan boleh bekerja setelah
40 hari.
2) Puerperium Intermedial
Puerperium intermedial merupakan masa kepulihan
menyeluruh alat-alat genetalia, yang lamanya sekitar
6-8 minggu.
Merupakan masa yang diperlukan untuk pulih dan
sehat sempurna, terutama bila selaa hamil atau waktu
persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat
sempurna apat berlangsung selama berminggu-minggu,
bulanan, bahkan tahunan.
c. Perubahan Masa Nifas (Yuli Aspiani, 2017)
1) Perubahan Fisik
a) Tanda-tanda Vital
Suhu tubuh alam 24 jam pertama >38˚C. Jika 1-2 hari pada hari ke 10 >38˚C hati-hati terhadap adanya infeksi puerperalis, infeksi saluran kemih, endometris, mastitis,
dan infeksi lain.
b) Involusio
Adalah perubahan yang merupakan proses
kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir
setelah bayi dilahirkan hingga mencapai keadaan eperti
sebelum hamil. Menurut Varney (2007; h. 959), tinggi
fundus uteri segera saat pascapartum 2 jari dibawah
pusat, saat hari pelahiran dan hari pertama 1 jari
dibawah pusat, hari kedua 1-2 jari dibawah pusat, hari
ketiga 2 jari dibawah pusat, hari keempat 3 jari dibawah
pusat, hari kelima 2 jari diatas simpisis pubis, hari
setinggi simpisis pubis, dan mulai tidak teraba setelah
hari ke 10.
c) Dinding Perut dan Peritonium
Setelah persalinan dinding perut longgar karena
diregang begitu lama, biasanya akan pulih dalam 6
minggu. Ligamen fascia dan diafragma pelvis yang
meregang pada waktu partus setelah bayi lahir
berangsur angsur mengecil dan pulih kembali.
d) Sistem Kardiovaskuler
(1) Tekanan darah stabil
(2) Bradikardi (50-70x/menit) normal jika tidak ada
keluhan
(3) Takhicardi akibat pesalinan lama dan perdarahan
hebat
(4) Diaforesis dan menggigil yang disebabkan instability
vasomotor. Keadaan ini normal jika tidak disertai
demam.
(5) Komponen darah trombosit lebih aktif
e) Sistem Urinaria
Aktivitas ginjal bertambah pada masa nifas karena
reduksi dari volume darah dan ekskresi produk sampah
dari autolysis. Puncak dari aktivitas ini terjadi pada hari
pertama post partum.