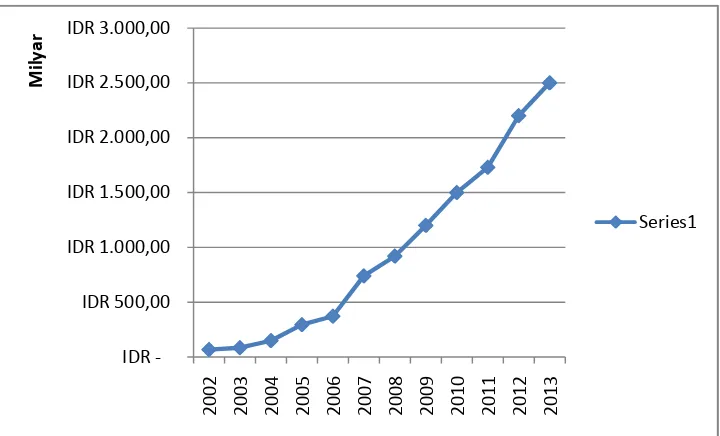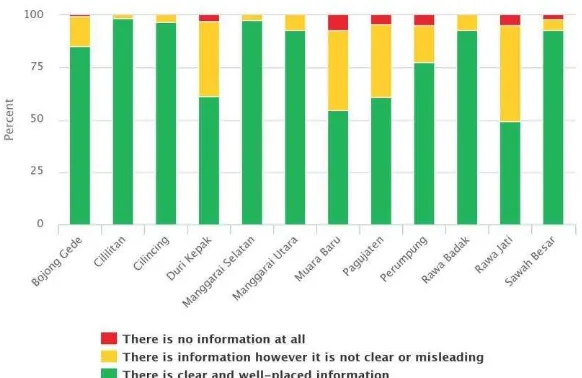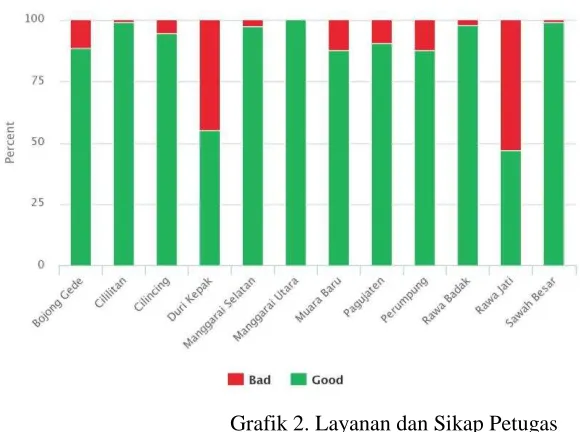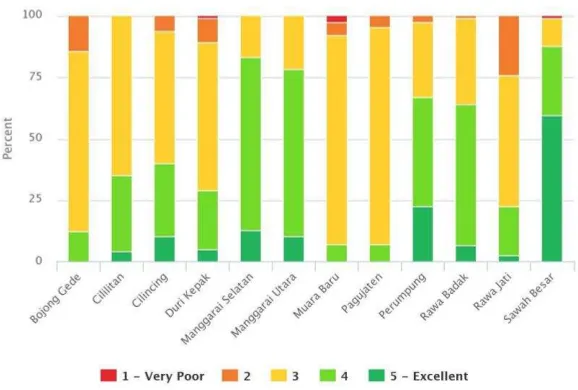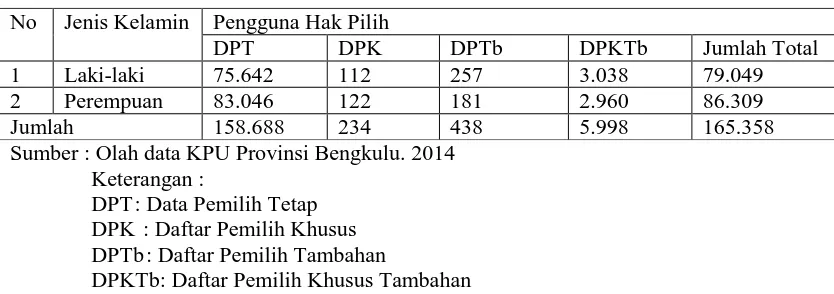268 KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM MANAJEMEN APARATUR
SIPIL NEGARA
(Suatu Kajian terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)
Didik G. Suharto
Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta Abstrak
Institusi pemerintahan atau birokrasi merupakan lembaga strategis dalam melayani dan membangun masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada institusi birokrasi. Dalam konteks tersebut, eksistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor birokrasi tidak terbantahkan lagi urgensinya. ASN berperan penting untuk mewujudkan kinerja unggul birokrasi, termasuk dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik responsif gender. Pembangunan dan pelayanan publik yang responsif gender tersebut memerlukan aparatur sipil negara yang berperspektif gender pula. Artikel ini pada prinsipnya menganalisis regulasi manajemen aparatur sipil negara dengan mengidentifikasi terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamati dari sudut pandang kesetaraan dan keadilan gender. Secara substansial dapat diidentifikasi beberapa temuan sebagai berikut: terdapat prinsip sistem merit yang melandasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penegasan sistem merit dalam asas kebijakan dan manajemen ASN, perhatian terhadap keterbukaan dan obyektivitas, adanya hak pegawai ASN yang nondiskriminatif, dan tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan sanksi (punishment). Pada prinsipnya, tidak ada hambatan yuridis bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam birokrasi. UU Nomor 5 tahun 2014 cenderung netral gender. Tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014. Demikian pula tidak ada perlakuan khusus (termasuk melalui affirmative action) terhadap salah satu jenis kelamin. Meskipun dari sisi regulasi kaum perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk terlibat dan menduduki posisi/jabatan dalam birokrasi, namun realitasnya perempuan seringkali termarginalkan terutama ketika bersaing memperebutkan jabatan struktural (eselon) tingkat atas. Selain dimensi regulasi (kebijakan), persoalan keterlibatan perempuan dalam birokrasi juga potensial dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, psikologis, dan struktural.
Kata kunci: gender, kesetaraan dan keadilan, aparatur sipil negara
Pendahuluan
Persoalan gender sampai dengan sekarang masih menjadi tema menarik untuk dikaji. Meskipun secara umum derajat pembangunan gender mengalami peningkatan, tetapi realitas kesetaraan dan keadilan gender di beberapa sektor masih memperlihatkan kesenjangan, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam pemerintahan/pembangunan.
The 4th World Conference on Women di Beijing tahun 1995 mengidentifikasi beberapa isu kritis gender yang merupakan bentuk keprihatinan dan perlu segera mendapat penanganan, yakni antara lain terbatasnya keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan terbatasnya lembaga-lembaga serta mekanisme yang dapat memperjuangkan kaum perempuan baik dalam sektor pemerintah maupun non pemerintah (Nurhaeni, 2009:59).
269 Indonesia meningkat dari 67,2 pada tahun 2010 menjadi 69,6 di tahun 2013, dan GEM meningkat dari 68.2 pada tahun 2010 menjadi 70.5 tahun 2013 (Menneg PP, 2015).
GDI mengungkapkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (diukur dari harapan hidup saat lahir), pengetahuan, tingkat pendidikan (diukur dari kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah), dan suatu standar hidup yang layak (diukur dari pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan / purchasing power parity). GEM mengukur ketimpangan gender dalam hal apakah perempuan dapat mengambil peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. GEM memfokuskan pada partisipasi, mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan (Nurhaeni, 2009:35).
Di sektor pemerintahan (birokrasi), isu-isu terkait gender tidak luput dari perhatian publik. Bagaimanapun juga, birokrasi atau institusi pemerintahan adalah aktor penting dalam kehidupan masyarakatnya. Apalagi di negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi menjadi stakeholder utama dalam pembangunan bangsa. Segenap kepentingan dan kebutuhan warga seringkali sangat tergantung kepada keberadaan birokrasi.
Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer seperti dikutip Nugroho (2008:110) mengatakan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala besar. Di dalam masyarakat modern hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawab banyak urusan yang terus menerus dan ajeg.
Menghubungkan gender dengan birokrasi, Puskapol UI (2012) memberikan penjelasan sebagai berikut:
―Sebuah birokrasi yang representatif lebih mungkin untuk mewadahi berbagai macam permasalahan sosial. Keterwakilan gender, khususnya perempuan, diperlukan untuk mengawasi regulasi nasional yang terkait dengan isu-isu perempuan dan ketaatan penyelenggara pemerintahan dalam implementasinya. Perempuan perlu hadir di jantung pemerintahan sehingga hal ini dapat menghapus diskriminasi dan mempromosikan kedudukan perempuan dan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan keterlibatan perempuan.‖
Pendapat Noor (2014), Sukesi (dalam Tarjana dkk., 2011), dan Suparno (2005) pada intinya senada. Pembangunan tanpa didukung oleh segenap unsur dan lapisan masyarakat akan mengakibatkan tersendatnya atau bahkan gagalnya upaya untuk mencapai masyarakat yang adil, sejahtera dan demokratis seperti yang dicita-citakan bersama (Noor, 2014). Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik formal dan arena pengambil keputusan adalah langkanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam segala level yang berpihak pada perempuan sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak dapat diartikulasikan (Suparno, 2005:4).
Sukesi (dalam Tarjana dkk., 2011:281) yang mengkaji masalah perempuan dan kemiskinan menarik kesimpulan bahwa sebagai akibat perempuan jarang dilibatkan dalam musyawarah di tingkat desa atau kelurahan maka perempuan miskin tidak dapat memperoleh informasi, merasa tidak pantas hadir dalam pertemuan di tingkat desa/kelurahan, dan tidak dapat menyuarakan kebutuhan mereka.
Nilai strategis kesetaraan dan keadilan gender seperti disampaikan sejumlah pihak tersebut didukung ―arus global‖ sebagaimana pernyataan berikut:
270 achieving the other MDGs. Women play a critical role in national economic growth and development. Their contributions have a lasting impact on households and communities as they most directly influence family nutrition, health and the education of children, and therefore affect not only the present but also the future. Giving women equal rights and opportunities is a way to enhance their contributions and bring us close to the goal of eliminating poverty, hunger and disease, and to stimulate development that is truly sustainable‖ (United Nations, 2007:12).
Bagaimana dengan keterwakilan (fisik) perempuan dalam birokrasi? Dari sisi kuantitas keseluruhan, jumlah dan persentase aparat birokrasi (Pegawai Negeri Sipil/PNS) perempuan sebenarnya cukup signifikan. Perbandingan jumlah PNS menurut jenis kelamin pada tahun 2013 tidak menunjukkan kesenjangan yang berarti. Mengacu data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari 4.362.805 PNS, sebanyak 2.102.197 atau 48,18% diantaranya berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebesar 2.260.608 (51,82%) laki-laki.
Kesenjangan tampak jelas saat mencermati komposisi pejabat struktural di institusi birokrasi. Hasil penelitian Puskapol UI (2012) menunjukkan proporsi laki-laki dan perempuan di jabatan struktural di 34 kementerian cenderung timpang. Hanya 22,38% jabatan struktural yang diisi oleh perempuan. Proporsinya menjadi lebih timpang jika dilihat berdasarkan jenjang jabatan struktural yang diduduki. Proporsi terbesar perempuan pejabat struktural berada pada jenjang bawah, yaitu di eselon III dan IV. Sedangkan pada jenjang atas rata-rata hanya ada 1 perempuan dari 10 pejabat eselon I. Padahal, pejabat struktural pada jenjang tertinggi ini banyak terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis di pemerintahan.
Kecenderungan yang sama juga terjadi di daerah. Kajian mengenai pemetaan isu gender di bidang politik di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil ―setali tiga uang‖. Perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki. Dari segi golongan, semakin tinggi golongan maka persentase perempuan semakin mengecil bahkan di beberapa unit kerja tidak ada perempuan yang mencapai golongan IV. Perempuan mayoritas hanya mencapai golongan III (Lidya, 2011:149).
Realitas di atas mengesankan adanya fenomena ―bias vertikal‖ dalam komposisi jabatan struktural, dimana semakin tinggi tingkat eselon semakin mengecil jumlah persentase perempuan. Bukan hanya ―bias vertikal‖, karakteristik penyebaran aparat birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga ―bias horisontal‖. Bias horisontal partisipasi perempuan dan laki-laki terlihat dari mengelompoknya (dominansi) perempuan/laki-laki di SKPD-SKPD tertentu (misal bidang kesehatan untuk perempuan dan bidang pekerjaan umum untuk laki-laki) atau di jabatan-jabatan fungsional.
Pola manajemen birokrasi yang berlaku mempengaruhi postur dan karakter birokrasi. Salah satu hal yang mendasari aspek manajerial itu ialah persoalan regulasi (peraturan perundang-undangan). Dalam perspektif tersebut, eksistensi UU Nomor 5 tahun 2014 mempunyai potensi pengaruh besar terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam manajemen aparat birokrasi.
Tinjauan Pustaka
271 Nurhaeni (2009:19) yang mendefinisikan gender sebagai perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Lebih lanjut dijelaskan Nurhaeni, berbeda dengan seks sebagai sesuatu yang ―given‖, maka gender lebih berhubungan dengan perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya maupun psikologis (2009:25).
Seks lebih berkonsentrasi pada biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya (Fauzi dalam Tarjana dkk., 2011:71). Batasan konsep kesetaraan dan keadilan gender menurut Fauzi yakni jika perbedaan kedua jenis kelamin tersebut berada pada hubungan yang linier dan seimbang. Sebaliknya bila lebih memihak kepada salah satu jenis kelamin (dalam hal ini lebih sering membela laki-laki daripada perempuan) maka disebut bias gender.
Hal itu lebih dipertegas oleh Nurhaeni (2009:26) bahwa ketika masyarakat memperlakukan perempuan dan laki-laki secara diskriminatif negatif bukan karena kompetensinya, tetapi semata-mata karena jenis kelaminnya, maka bisa dikatakan telah terjadi ketidak-keadilan gender. Pembedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki tidaklah menjadi masalah selama hal tersebut dilakukan karena merespon perbedaan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan antar laki-laki dan perempuan.
Persoalan kesetaraan gender pada dasarnya adalah persoalan distribusi kekuasaan, yaitu apakah ada sharing of power yang adil antara laki-laki dan perempuan ataukah yang terjadi adalah situasi sebaliknya, yaitu adanya hegemoni kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya (Darwin, 2005:55).
Ringkasnya, UNESCO (sebagaimana dikutip Nurhaeni, 2008:25) mendefinisikan kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut:
Kesetaraan gender (gender equality) merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggungjawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya.
Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, sub-ordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja telah terjadi di berbagai tingkatan di masyarakat (Nugroho, 2008:26).
Darwin (2005:59) memaparkan terdapat tiga model strategi untuk mengatasi ketimpangan gender, yaitu strategi perempuan dalam pembangunan (Women in Development / WID), strategi gender dan pembangunan (Gender and Development / GAD), dan strategi pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming / GM).
Pembahasan
272 Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.
Adanya amanat untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pada gilirannya memberikan dampak terhadap produk-produk regulasi yang tidak bias gender. Selama ini, bisa dikatakan tidak ada hambatan yuridis formal bagi keterlibatan perempuan di ranah publik. Undang-undang Dasar 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak mendiskriminasi salah satu jenis kelamin untuk berpartisipasi di wilayah publik.
Nugroho (2008:213) yang meneliti tentang kualitas kesetaraan gender di dalam administrasi publik Indonesia menyimpulkan bahwa dalam variabel kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah berada dalam tataran netral gender.
Dalam kajian ini, kesetaraan dan keadilan gender cukup relevan mengikuti batasan dari Nugroho (2008:60). Dinyatakan bahwa, kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.
Untuk memudahkan analisis isi (content analysis) terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, maka identifikasi dilakukan terhadap pasal-pasal (ketentuan) yang bersentuhan dengan persoalan gender. Berdasar penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa ketentuan yang memiliki perspektif gender.
Pertama, adanya prinsip sistem merit (merit system)yang melandasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, yang dimaksud sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa manajemen PNS tersebut meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan, kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan (Pasal 93). Dengan demikian, pengelolaan ASN sejak dari awal hingga akhir atau semua aspek manajemen kepegawaian dilakukan berdasar prinsip-prinsip profesional, dan tidak diperkenankan terjadi diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin.
273 keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Mencermati asas-asas tersebut mengandung arti bahwa kebijakan dan manajemen ASN tidak membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap salah satu jenis kelamin. Secara eksplisit juga dinyatakan adanya asas nondiskriminatif dan asas keadilan dan kesetaraan.―Asas nondiskriminatif‖ berarti dalam penyelenggaraan manajemen ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Sedangkan ―asas keadilan dan kesetaraan‖ maksudnya pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
Ketiga, perhatian terhadap keterbukaan dan obyektivitas. Keterbukaan dan obyektivitas dalam manajemen ASN secara langsung atau tidak langsung akan mendorong kompetisi yang fair. Pada hakekatnya, manajemen PNS dan manajemen PPPK -yang keduanya merupakan bagian dari aparatur sipil negara- pengaturannya relatif sama. Misalnya dalam rekrutmen aparatur sipil negara, prinsip yang berlaku pada manajemen PNS dan PPPK tidak berbeda. Ketentuan yang berlaku ialah bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Rekrutmen calon ASN melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
Prinsip obyektivitas terlihat pula dalam hal pengembangan karier PNS. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas (Pasal 69 ayat (1) dan (2)). Sama halnya dengan pengaturan mengenai promosi PNS. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Kebijakan nondiskriminatif itu lebih dipertegas dalam Pasal 72 ayat (2), bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Sejalan dengan obyektivitas dalam manajemen ASN, maka penilaian kinerja PNS dan PPPK diarahkan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier dan menjamin objektivitas prestasi kerja PPPK yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja PNS dan PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kompetisi ―bebas‖ yang mengedepankan prestasi dan tidak membeda-bedakan soal jenis kelamin di satu sisi menjadi angin segar bagi perempuan karena ada kesempatan tapi di sisi lain kompetisi semacam itu akan sangat ―kejam‖ menggusur perempuan jika tidak mampu bersaing dengan laki-laki.
274 kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Intinya, aspek/dimensi jenis kelamin tidak menjadi variabel yang mempengaruhi hak pegawai ASN. Pengecualian-pengecualian khusus terhadap hak salah satu jenis kelamin biasanya berkaitan dengan persoalan kodrati, contoh cuti melahirkan.
Kelima, tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan sanksi (punishment). Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melihat aspek/dimensi jenis kelamin sebagai ―alasan‖ untuk menghindar dari kewajiban atau sanksi. Pasal 86 dan Pasal 104 memberikan arah yang tegas bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS dan PPPK wajib mematuhi disiplin PNS. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Artinya, semua pegawai – laki-laki dan perempuan- terikat pada ketentuan yang sama. Tidak ada keistimewaan (privilege) bagi jenis kelamin tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda.
Mengamati dari substansi-substansi di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada prinsipnya, tidak ada hambatan yuridis formal bagi keterlibatan perempuan di birokrasi. Klausul pasal-pasal dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memperlihatkan adanya diskriminasi atau bias gender. Undang-undang tersebut bisa dikategorikan cenderung netral gender. Tidak ada keberpihakan atau kecondongan terhadap salah satu jenis kelamin. Mengacu pandangan UNESCO, UU Nomor 5 tahun 2014 dapat dikatakan memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Undang-undang ini juga memberikan keadilan gender, dalam arti memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Namun demikian, keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang setara (baca: sama) antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen aparatur sipil negara.
Kesimpulan
Kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung netral gender tidak secara linier akan meningkatkan peran/eksistensi perempuan dalam birokrasi. Ketentuan hitam di atas putih dalam regulasi hanya satu bagian variabel di tengah beragam variabel pengaruh lain. Dengan perspektif yang hampir sama, pelajaran bisa dipetik dari implementasi gender dalam politik. Peraturan atau kebijakan di bidang politik juga nondiskriminasi. Regulasi tidak bias gender dan telah mengakomodir potensi laki-laki maupun perempuan. Bahkan, dalam sistem politik kebijakan yang berlaku sudah responsif gender, yakni melalui kebijakan affirmative action yang ditujukan untuk mendorong jumlah anggota legislatif perempuan yang lebih representatif. Kebijakan affirmative action yang dimaksud berkaitan dengan ketentuan pengajuan calon anggota (Caleg) yang harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan ketentuan mengenai zipper system (dalam daftar caleg yang diajukan, setiap tiga calon harus memuat satu calon perempuan). Namun pada realitasnya, kebijakan tersebut belum signifikan mendongkrak partisipasi perempuan dalam legislatif. Sebagai gambaran, pada Pemilu 2009 terdapat 103 legislator perempuan dari 560 kursi DPR. Sementara pada Pemilu 2014 legislator perempuan turun menjadi 97. Padahal, jumlah Caleg perempuan naik dari 33,6% pada Pemilu 2009 menjadi 37% di Pemilu 2014.
Sejumlah penelitian maupun kajian telah mengidentifikasi persoalan partisipasi perempuan dalam politik. Sebagai misal UNDP (2010:21) yang memetakan isu/hambatan partisipasi perempuan dalam bidang politik sebagai berikut:
275 kurangnya minat perempuan terhadap politik kurangnya sumber daya finansial, kurang percaya diri, kurang mobilitas, tanggung jawab keluarga, kurangnya perempuan yang aktif sebagai kader partai politik, kurangnya dukungan dari partai politik, dan persepsi yang menganggap politik itu kotor).
b. Hambatan yang bersifat mendasar (budaya maskulin dan dominasi laki-laki, agenda partai politik yang berorientasi terhadap laki-laki, kurangnya demokrasi di internal partai politik, komersialisasi politik, sistem kepemiluan, nepotisme dan elitisme di dalam partai politik, kekerasan politis, dan korupsi dalam politik).
c. Hambatan struktural (dikotomi diskursif ranah publik-privat, patriarki publik dan privat, perilaku sosial yang patriarkis terhadap laki-laki dan perempuan, dan fundamentalisme keagamaan).
Senada hal tersebut, United Nations (2007:13) menyatakan:
―The type of electoral system in place in a country, the role and discipline of political parties, women‘s social and economic status, socio-cultural traditions and beliefs about women‘s place in the family and society, and women‘s double burden of work and family responsibilities can all have an impact on the number-and effectiveness-of women‘s participation in the electoral process.‖
Mengadopsi faktor-faktor pengaruh keterlibatan perempuan dalam politik di atas, persoalan kesetaraan dan keadilan gender dalam birokrasi secara garis besar juga potensial dipengaruhi oleh faktor kebijakan, sosiokultural, psikologis, dan struktural. Faktor kebijakan mempengaruhi kuat lemahnya landasan hukum keikutsertaan perempuan dalam birokrasi. Faktor sosiokultural terutama masih kuatnya budaya patriarki dan stigma/stereotipe negatif lain. Faktor psikologis menyangkut seberapa besar tingkat kepercayaan perempuan terhadap dirinya sendiri. Dan faktor struktural, terutama berkenaan dengan kapasitas dan kompetensi pihak penentu kebijakan (Baperjakat atau panitia rekrutmen pegawai) yang berperspektif adil gender.
Sebagai penutup, tampaknya penting untuk direnungkan kembali bahwa kuantitas perempuan yang aktif di lembaga birokrasi tidak memberikan makna dalam mendorong pemenuhan kepentingan perempuan bila para aparat birokrasi tersebut tidak responsif gender untuk memperjuangkan kebijakan yang berperspektif gender (Lidya, 2011:154). Dalam hal ini, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang responsif gender merupakan tujuan strategis daripada sekedar memenuhi kuantitas perempuan dalam birokrasi.
Daftar Pustaka:
Darwin, Muhadjir M., 2005, Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Grha Guru dan Media Wacana
Fauzi, Moh., ―Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Islam‖, dalam Tarjana, Sri Samiati dkk., 2011, Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan menuju Pengarusutamaan Gender, Surakarta: CakraBooks dan P3G UNS
Lidya, Eva, ―Pemetaan Isu Gender di Bidang Politik di Provinsi Sumatera Selatan‖, dalam Tarjana, Sri Samiati dkk., 2011, Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan menuju Pengarusutamaan Gender, Surakarta: CakraBooks dan P3G UNS
276 Noor, Ida Ruwaida, 2014, ―Perempuan dan Pembangunan di Indonesia:Kebijakan Keterwakilan Perempuan,‖ disampaikan pada: Dialog Kebijakan dan Pelatihan Advokasi”, INFID, Yogyakarta, 12 Februari 2014.
Nugroho, Riant, 2008, Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009, Kebijakan Publik Pro Gender, Surakarta: UNS Press Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2008, Reformasi Kebijakan Pendidikan; Menuju Kesetaraan
dan Keadilan Gender, Surakarta: UNS Press
Puskapol UI, 2012, ―Ketimpangan Keterwakilan Perempuan dalam Birokrasi‖,
www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/factsheet-ketimpangan-keterwakilan-perempuan-dalam-birokrasi.pdf
Suparno, Indriyati, Ismunandar, Kelik, dan Rochimah, Trihastuti Nur, 2005, Masih dalam Posisi Pinggiran; Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta, Surakarta: SPEK-HAM, UCN, dan Pustaka Pelajar
Sukesi, Keppi, ―Perempuan dan Kemiskinan: Profil dan Upaya Pengentasan‖, dalam Tarjana, Sri Samiati dkk., 2011, Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan menuju Pengarusutamaan Gender, Surakarta: CakraBooks dan P3G UNS
UNDP, 2010, ―Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan‖, Makalah Kebijakan, Jakarta: UNDP Indonesia
277 DISKRIMINASI GENDER SEBAGAI REFLEKSI KEKUASAAN
(Sebuah Studi Kasus Komunikasi Antar Budaya dalam Film Anna And The King)
Dyah Retno Pratiwi; Rahmat Wisudawanto
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Surakarta dyah.retno85@gmail.com; wisudawanto@gmail.com
Abstrak
Perkembangan teknologi yang pesat berperan serta dalam perkembangan komunikasi antar budaya. Hadirnya teknologi yang semakin canggih mengakibatkan komunikasi antar budaya tidak lagi mengalami hambatan jarak dan waktu. Namun demikian, terjadinya komunikasi antar budaya menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang nilai, norma atau aturan yang dipunyai dan diyakini oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. Disamping itu, perbedaan cara pandang yang dipunyai oleh setiap budaya juga memberikan andil terhadap masalah komunikasi antar budaya itu sendiri. Makalah ini berusaha untuk menganalisis bagaimana diskriminasi gender sebagai refleksi kekuasaan sebagai salah satu hambatan komunikasi antar budaya yang terjadi antara tokoh Anna yang berasal dari Inggris dan masyarakat Thailand dengan menggunakan film Anna and The King sebagai objeknya. Makalah ini akan menggunakan adegan-adegan dalam film tersebut sebagai data dan akan dianalisis dengan menggunakan content analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa deskriminasi gender sebagai refleksi kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat Thailand ditunjukan melalui bentuk verbal dan non verbal. Deskriminasi gender sebagai bentuk pencerminan kekuasaan dalam bentuk verbal dapat diamati tidak hanya melalui sikap dan tindakan akan tetapi juga cara pandang terhadap masalah kekuasaan. Adapun, bentuk non verbal yang muncul dapat diamati melalui bahasa yang digunakan untuk menunjukkan kekuasaan yang ada dalam masyarakat Thailand. Kata kunci: gender, kekuasaan, film, komunikasi antar budaya
Pendahuluan
Bahasa sebagai alat komunikasi yang utama memberikan kontribusi yang signifikan dalam kegiatan berinteraksi pada masyarakat. Dengan semakin berkembangnya masyarakat maka bahasa juga mengalami perkembangan. Dengan kata lain, perkembangan bahasa sangat terkait dengan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga mengakibatkan perkembangan komunikasi menjadi semakin luas. Dengan hadirnya teknologi maka memungkinkan orang untuk melakukan komunikasi tanpa terhalang atau terhambat jarak dan waktu.
Dalam era teknologi saat ini, keinginan seseorang untuk memanfaatkan media sebagai alat komunikasi semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari pola penggunaan media sebagai alat berkomunikasi oleh masyarakat. Penggunaan media sebagai alat komunikasi dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada media cetak saja tetapi juga penggunaan media elektronik. Salah satu contoh pemanfaatan media elektronik sebagai media komunikasi ini dapat diamati melalui penggunaan jejaring media sosial di masyarakat. Dengan hadirnya jejaring media sosial dalam masyarakat, proses komunikasi sudah tidak terhambat oleh jarak dan waktu lagi.
278 sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini berarti bahwa dengan perkembangan teknologi, komunikasi antara orang yang berbeda latar belakang budaya akan mudah terjadi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya teknologi perbengaruh pada perkembangan komunikasi antar budaya.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan komunikasi antar budaya bukan tanpa masalah. Masalah yang timbul dalam komunikasi antar budaya sangatlah beragam. Masalah yang timbul dalam komunikasi antar budaya diantaranya adalah masalah kesopanan dalam berkomunikasi. Hal ini terjadi karena dalam komunikasi antar budaya, orang-orang yang melakukan komunikasi terkendala dengan latar belakang budaya yang dia miliki. Bahkan, dengan perbedaan latar belakang budaya yang mana turut mempengaruhi keyakinan akan nilai yang dianut seseorang akan menjadi kendala yang berarti dalam komunikasi antar budaya. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pertukaran pesan atau komunikasi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ting-Toomey (2005) menyatakan dalam proses komunikasi antarbudaya, para partisipan komunikasi juga berada dalam situasi tertentu pula yang juga mempengaruhi bagaimana mereka melakukan penyandian dan penyandian balik pesan.
Tututan terjadinya komunikasi budaya dewasa ini salah satunya disebabkan karena adanya globalisasi. Dalam pandangan globalisasi maka diperlukan pemahaman akan nilai atau budaya yang lain sehingga komunikasi antar budaya dapat berlangsung dengan harmonis. Hal ini disebabkan karena dalam keterampilan berkomunikasi seseorang dituntut tidak hanya mempunyai pandangan mono kultural tetapi juga pandangan multi kultural. Oleh karena itu, pandangan ini sesuai dengan salah satu tujuan komunikasi antar budaya yang di sarankan oleh Litvin dalam Mulayana (2001) bahwa keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang mono kultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural. Dengan demikian, apabila seseorang sudah mempunyai pandangan multi kultural maka dia akan dengan mudah melakukan interaksi dengan penganut budaya yang lain dimana nilai yang dianut oleh orang tersebut berbeda dengan nilai yang dia diyakini.
Dalam komunikasi antar budaya, pertukaran pesan dapat berlangsung dengan baik apabila seseorang dapat saling memahami nilai yang dianut oleh masing-masing budaya yang mereka miliki. Oleh sebab itu, kesalahan dalam memahami nilai dapat berakibat pada ketidak keharmonisan dalam berkomunikasi. Nilai yang terkandung dalam budaya sangat beragam bentuknya. Hal ini salah satunya dapat dilihat diskriminasi gender dan kekuasaan. Setiap budaya tentunya akan menanggapi berbeda terkait dengan nilai gender dan kekuasaan dalam budaya mereka. Isu tentang kesetaraan gender yang sudah merupakan hal yang tidak dipermasalahkan dalam dunia barat ternyata masih menjadi bahan pembicaraan hangat di dunia timur. Bahkan, masih banyak negara-negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan yang sensitif akan masalah tersebut. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena nilai yang berlaku di dunia barat berbeda dengan dunia timur. Masalah perbedaan gender tersebut juga akan mempengaruhi bentuk kekuasaan dalam interaksi masyarakat. Dalam nilai yang dianut oleh budaya timur kekakuasaan akan banyak disimbolkan oleh gender tertentu sehingga profesi atau pekerjaan tertentu akan nampak terbedakan bagi gender-gender tertentu. Fakta ini salah satunya dapat dilihat dari pola kepemimpinan masyarakat timur yang mayoritas dipegang oleh gender tertentu.
279 kedudukan penting dalam penyampaian budaya. Melalui film kita dapat belajar dengan mudah budaya orang lain dengan biaya yang murah dan waktu yang tidak mengikat. Disamping itu, film Anna and The King ini juga merupakan film yang mengisahkan adanya interaksi budaya antara masayrakat barat yang diwakili oleh Anna dan masyarakat timur yang direpresentasikan melalui masyarakat Thailand dan raja mereka yaitu King Moungkut. Kajian pustaka
Komunikasi antar budaya
Terkait dengan komunikasi antar budaya sebagai bagian dari analisis pada makalah ini maka definisi dan hambatan komunikasi antar budaya dalam makah ini akan dipaparkan lebih lanjut. Terdapat berbagai macam definisi komunikasi antar budaya yang disampaikan oleh para ahli. Namun demikian, kesemua definisi komunikasi antar budaya tersebut mengacu pada satu hal yaitu terjadinya komunikasi antara satu orang dengan yang lainya dimana latar belakang budaya orang yang melakukan komunikasi tersebut berbeda satu dengan yang lainnya.
Definisi komunikasi antar budaya yang pertama dipaparkan dalam makalah ini adalah definisi komunikasi antar budaya yang diungkapkan oleh Devito (2011: 535). Dalam definisinya Devito menyatakan bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi diantara orang-orang dari kultur yang berbeda, yakni antara orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai dan cara berperilaku kultural yang berbeda. Devinisi Devito tersebut diatas menjelaskan bahwa perbedaan kepercayaan, nilai dan cara berperilaku yang berbeda merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Selanjutnya, Stewart dalam Mulyana (2001) mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai komunkasi yang terjadi dibawah suatu kondisi kebudayaan yang berbeda bahasa, norma, adat dan kebiasaan. Dari definisi-definisi diatas maka dapat dilihat keterkaitan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dimana latar belakang sistem kepercayaan, norma dan nilainya berbeda. Karena adanya perbedaan nilai, norma dan sistem kepercayaan yang melatarbelakangi komunikasi antar budaya maka dalam komunikasi antar budaya akan timbul berbagai macam hambatan-hambatan komunikasi antar budaya.
Hambatan komunikasi antar budaya
Novinger (2001) menyatakan bahwa dalam komunikasi antarbudaya, reaksi negatif dan evaluatif individu terhadap sebuah budaya dapat menciptakan hambatan komunikasi. Dalam hal ini reaksi individu yang bersifat evaluatif menyebabkan hadirnya hambatan komnikasi. Pada kasus ini yang menjadi fokus adalah reaksi individu yang merupakan hambatan yang muncul ketika komunikasi antar budaya tersebut terjadi. Dengan demikian, ketika seseorang menilai negatif sebuah budaya maka dia akan mengalami hambatan dalam komunikasinya. Selanjutnya, Tracy Novinger juga menambahkan bahwa hambatan komunikasi antar budaya dapat dibagi dalam tiga jenis, yakni hambatan persepsi, hambatan verbal dan hambatan nonverbal.
Hambatan presepsi komunikasi antar budaya
280 dipengaruhi dari interaksi sosial, dan lain sebagainya, sehingga hal ini bisa diperoleh atau bisa hilang.
Selain wajah (face) hambatan presepsi dalam komunikasi antar budaya juga disebabkan oleh adanya perbedaan sikap. Terkait dengan sikap sebagai salah satu hambatan presepsi, Novinger (2001: 42) menyatakan bahwa sikap merupakan ranah psikologis yang secara jelas memengaruhi perilaku dan menyimpangkan persepsi. Oleh karena itu, perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan penyimpangan presepsi yang ada pada diri seseorang adalah pengaruh dari sikap yang dimiliki orang tersebut. Lebih lanjut, Ting-Toomey (2005) mengklasifikasikan sikap dalam dua aspek yaitu kognitif dan afektif. Aspek kognitif merujuk pada keinginan untuk menahan pendapat yang bersifat etnosentris dan kesiapan untuk mempelajari mengenai isu perbedaan lintas budaya dengan pandangan terbuka. Adapun aspek afektif merujuk pada komitmen emosional untuk terlibat dalam partisipasi perspektif kultural, dan pengembangan rasa empati dalam memahami perbedaan kelompok kultural.
Faktor hambatan presepsi yang terakhir dalam komunikasi lintas budaya di pengaruhi oleh adanya perbedaan nilai. Salah satu nilai yang ada dalam masyarakat dapat diamati melalui agama atau sistem kepercayaan yang dianut atau berlaku dalam masyarakat. Nilai agama yang ada dalam masyarakat muncul dalam bentuk pola dan pandangan hidup. Bahkan, Ferraro dalam Samovar, Porter & McDaniel (2010) menambahkan bahwa pengaruh agama dapat dilihat dari jalinan semua budaya, karena hal ini bersifat dasar. Dengan demikian, Nilai agama ini juga berpengaruh pada cara pandang (worldview) yang meliputi bagaimana orientasi budaya terhadap Tuhan, alam, kehidupan, kematian dan alam semesta, arti kehidupan dan keberadaan.
Kekuasaan
Kekuasaan dapat dimaknai dalam berbagai perspektif. Perspektif yang muncul terhadap difinisi kekuasaan banyak yang mengacu pada kontrol atas orang lain. Dengan kata lain, kontrol orang lain terhadap diri kita adalah sebagai sebuah simbol kekuasaan. Namun demikian, perspektif akan kekuasaan sebagai sebuah kontrol terhadap orang lain tidak sepenuhnya benar. Dalam beberapa definisi kekuasaan yang dikemukakan oleh para ahli tidak sepenuhnya setuju akan definisi kekuasaan sebagai kontrol terhadap orang lain. Salah satunya adalah Foucault dalam Mudhoffir (2013) yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara tetapi kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Dengan kata lain, kekuasaan bukan mengacu pada istilah siapa yang mendominasi dan siapa yang terdominasi akan tetapi kekuasaan harus dipahami sebagai bentuk dukungan yang berhubungan dengan berbagai macam hal yang tetap ada di dalam wilayah aturan sebuah kelompok. Hal ini sejalan dengan kutipan yang diungkapkan oleh Foucault dalam (ibid, 79): ―...power must be under stood in the fir st insta nce a s the multiplicity of force relations imma nent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization”.
Lebih lanjut, Foucault dalam (ibid, 80) menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:
281 2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada
yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binar y opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.
Metode Penelitian
Makalah ini berusaha mendeskripsikan deskriminasi gender sebagai refleksi kekuasaan dengan menggunakan film Anna and The King sebagai objeknya. Makalah ini menggunakan teknik content analysis dalam memperoleh datanya. Dalam pengumpulan datanya, semua adegan dalam film akan diamati kemudian akan diambil adegan-adegan film yang relevan dengan analisis yang akan dilakukan. Data yang akan digunakan sebagai bahan analisis adalah adegan-adegan dalam film tersebut yang menunjukkan tindakan atau perkataan diskriminasi gender yang terkait dengan kekuasaan. Adapun adegan-adegan yang tidak mengandung nilai-nilai atau unsur-unsur diskriminasi gender yang terkait dengan kekuasaan akan direduksi. Oleh karena itu, data yang disajikan benar-benar data yang berupa adegan dalam film yang terkait dengan deskriminasi gender sebagai refleksi kekuasaan.
Pembahasan
Hasil analisis dari adegan-adegan yang terdapat dalam film tersebut menunjukkan bahwa terdapat adegan yang berupa verbal dan non verbal yang menunjukkan diskriminasi gender yang terkait dengan kekuasaan. Data-data dari adegan tersebut selanjutnya akan disajikan dan dibahas sebagai berikut.
282 Dalam adegan diatas dapat dilihat bahwa Louis yang merupakan anak laki-laki Anna meminta maaf kepada ibunya terkait dengan kesalahan yang dia lakukan tetapi pangeran Chulalangkorn tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Louis. Dalam budaya masyarakat barat adalah hal yang wajar manakala seseorang melakukan kesalahan maka ia akan meminta maaf. Permintaan maaf yang masyarakat barat lakukan sama sekali tidak terpengaruh oleh perbedaan gender yang ada. Hal ini tentunya sesuai dangan sistem nilai yang mereka anut dan yakini. Ucapan permintaan maaf yang dikemukakan oleh Louis merupakan bagian dari presepsi mereka dalam menghargai orang lain. Dalam meminta maaf, masyarakat Inggris bisa melakukan permintaan maaf kepada orang yang lebih muda atau lebih tua. Bahkan, dalam masyarakat Inggris juga berlaku perwujudan sikap meminta maaf baik dari laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki. Akan tetapi, sikap meminta maaf ini nampaknya berbeda dengan presepsi masyarakat Thailand tempat dimana pangeran Chulalangkorn tinggal. Perwujudan sikap meminta maaf dalam budaya Thailand hanya berlaku bagi kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Nilai ini berangkat bahwa permohonan maaf hanya dilakukan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang tinggi kedudukannya sehingga raja Thailand yang adalah laki-laki tidak akan pernah meminta maaf pada masyarakatnya. Dengan kata lain, dalam masyarakat Thailand raja selalu dianggap benar. Hal ini dikarenakan raja mempunyai kedudukan yang paling tinggi di masyarakat sehingga raja tidak pernah merasa punya salah dan meminta maaf kepada masyarakat. Disamping itu, berangkat dari nilai yang tertanam dalam masyarakat Thailand dimana kaum laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada kaum perempuan dalam status sosial masyarakatnya maka wujud permintaan maaf hanya berlaku bagi orang perempuan terhadap orang laki-laki dan tidak sebaliknya. Dengan demikian, ucapan permintaan maaf yang mempunyai perbedaan presepsi ini berangkat dari proposisi kekuasaan bahwa relasi kekuasaan bersifat intensional sehingga hal ini memungkinkan adanya perbedaan presepsi yang terjadi antara nilai yang dianut oleh setiap budaya. Dari kasus diatas dapat diamati bahwa adanya diskriminasi gender dalam kekuasaan. Raja yang adalah kaum laki-laki mempunyai strata sosial yang berbeda dengan kaum perempuan. Terlebih lagi, raja selalu dianggap benar dan tidak pernah meminta maaf. Hal ini tentunya akan berakibat bahwa kaum laki-laki adalah layaknya raja yang tidak pernah mempunyai kesalahan atas kaum perempuan.
283 Dalam adegan adegan diatas nampak bahwa ketika Anna bertemu dengan perdana menteri Thiland, Anna disapa dengan kata ‖Sir‖ atau ―tuan‖. Dalam interaksi masyarakat Thailand mengharuskan bahwa hanya kaum laki-lakilah yang diperkenankan untuk beremu raja atau para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan seorang raja dalam masyarakat Thailand mempunyai kehormatan yang tinggi. Melalui ucapan perdana menteri Thiland yang menyapa Anna dengan kata ‖Sir‖ atau ―tuan‖ secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa hanya kaum laki-lakilah yang diperkenankan untuk bertemu raja. Dengan kata lain, ada diskriminasi gender dalam hak bertemu raja bagi masyarakat Thailand. Lebih dari itu, melalui pembatasan kaum yang boleh bertemu raja secara langsung mengindikasikan bahwa seorang raja di masyarakat Thailand menginginkan penghormatan yang sangat tinggi dalam pelaksanaan interaksi sosialnya. Hal ini tentunya sesuai dengan proposisi kekuasaan dimana Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. Oleh karena itu, perbedaan nilai sistem kekuasaan yang dianut antara budaya Inggris dan Thailand mengakibatkan adanya perbedaan nilai yang mereka anut terkait dengan sistem kekuasaan.
284
Cara pandang yang ditunjukkan melalui sikap bahwa laki-laki tidak hanya puas dengan satu perempuan mengindikasikan bahwa ada hak untuk laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Presepsi ini sekali lagi muncul dari nilai yang berlaku pada masyarakat Thailand yang memandang bahwa untuk dapat meneruskan garis keturunan masyarakat harus mempunyai anak yang banyak yang diwujudkan dengan memiliki banyak istri. Sementara itu, hal ini tidak berlaku pada budaya masyarakat Inggris dimana Anna berasal. Dalam nilai yang dianut oleh masyarakat Inggris dapat dilihat bahwa seseorang hanya menikah dengan satu orang perempuan. Apabila seseorang tersebut akan menikah dengan perempuan lain, maka dia akan meceraikan istrinya. Lebih lanjut, hal ini juga dapat diamati dari penguasa Inggris yaitu Ratu Elisabeth yang mana ratu Inggris tersebut hanya mempunyai satu suami. Hal ini muncul tentunya bukan tanpa alasan. Nilai equality yang masyarakat inggris pegang teguh menjadi alasan utama yang mendasari masalah tersebut. Dengan demikian, sekali lagi simbol kekuasaan muncul dalam deskriminasi gender. Kesimpulan
Dari paparan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa deskriminasi gender sebagai refleski kekuasaan raja dan masyarakat Thailand muncul dalam beberapa hal. Munculnya deskriminasi gender sebagai refleski kekuasaan raja dan masyarakat Thailand dapat diamati melalui permintaan maaf yang hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan terhadap laki-laki dan tidak berlaku untuk sebaliknya. Selanjutnya, terkait dengan deskriminasi gender sebagai refleksi kekuasaan juga muncul dalam bentuk pembedaan gender dalam bertemu raja atau orang yang berkuasa. Disini dapat dilihat bahwa sekali lagi kaum perempuan mengalami deskriminasi sebagai bentuk dari simbol kekuasaan. Sementara itu, bentuk deskriminasi yang terakhir dapat dilihat dari adanya hak laki-laki untuk menikah dengan banyak wanita atas dasar untuk meneruskan garis keturunannya. Munculnya deskriminasi gender yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budaya yang berbeda. Dimana hal ini akan mengakibatkan adanya perbedaan sistem kepercayan, nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat.
285 Daftar Referensi
Devito, Joseph A. (2011). Komunikasi antar manusia. Tangerang: Kharisma Publishing Group
Mudhoffir, A.M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 75-100
Mulyana, D. Rakhmat, J.(2001). Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Ting-Toomey, S. & Chung, L.C. (2005). Understanding intercultural communication. New York: Oxford University Press
Samovar, L.A., Porter, R.E & McDaniel E.R. (2010). Komunikasi lintas budaya (communication between cultures) (Indri Margaretha Sidabalok, Trans.). Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
286 PEREMPUAN DAN POLITIK: PENGALAMAN INDONESIA-JEPANG
Elly Malihah; Idrus Affandi; Diani Risda; Leni Anggraeni
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung ellyms70@gmail.com; ellyms@upi.edu
Abstrak
Kebijakan setiap negara dalam memberdayakan, menempatkan dan memandang posisi perempuan berbeda beda, meskipun hasil konferensi perempuan sedunia telah memberi arahan yang jelas tentang bagaimana keharusan negara menempatkan perempuan dalam posisi yang sejajar dengan pria.
Indonesia dan Jepang merupakan dua negara yang turut meratifikasi hasil konferensi tersebut, namun dalam implementasi kebijakan pemerintahnya masih terdapat ketidakadilan tentang kedudukan, fungsi dan peran perempuan terutama dalam mengakses bidang politik. Makalah ini dilatarbelakangi dari hasil penelitian tim yang mengkaji tentang faktor sosial budaya partisipasi politik perempuan dalam parlemen, baik di Indonesia maupun di Jepang. Penelitian ini merupakan studi komparatif, pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan diskusi terpumpun (focus group discussion).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di kedua negara masih terjadi ketidakseimbangan peran perempuan terutama dalam bidang politik, dikotomi peran publik dan privat masih ditemukan, kesempatan menduduki kursi politik masih terbatas. Hal tersebut dilatar belakangi antara lain masih berkembangnya budaya patriarki dan faktor internal dari dalam diri perempuan di kedua negara tersebut.
Kata Kunci : Perempuan, Politik, Indonesia, Jepang
Pendahuluan
Gerakan mendorong ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan baik langsung maupun tidak langsung terus dilakukan sejak masa pemerintahan orde baru hingga reformasi. Upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik tersebut menghasilkan dinamika yang menggembirakan, terbukti ramainya setiap ajang pemilu/pemilukada dilaksanakan baik meningkatnya minat menjadi kepala daerah, meningkatnya keinginan menjadi wakil rakyat untuk duduk di legislatif maupun gerakan massa para pendukungnya untuk ikut serta dalam kampanye, dan lain-lain. Namun demikian, gerakan tersebut tidak serta merta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lembaga politik. Partisipasi perempuan umumnya sebatas sebagai pemilih (voters), meskipun ada diantara mereka menjadi kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dengan memenangkan pilkada.
287 Perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini masih terjadi. Kedudukan perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari pria dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini karena adanya norma masyarakat yang masih menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan belum ada pengakuan secara operasional terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki perempuan. Namun demikian, dewasa ini tampaknya telah dilakukan upaya untuk memperbaiki kedudukan perempuan dalam masyarakat menurut lingkup hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam setiap kehidupan masyarakat. Karena pada prinsipnya, perempuan mempunyai hak, kewajiban dan peluang yang sama dengan laki-laki dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terlibat dalam proses pembangunan menyeluruh.
Dalam konteks itulah tulisan ini mengeksplorasi secara mendalam mengenai bagaimana keikutsertaan perempuan dalam Parlemen di Indonesia dan Jepang? dan sejauh mana faktor sosial budaya mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Jepang.
Keikutsertaan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia dan Jepang
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa perbandingan keterlibatan antara perempuan dan laki-laki dalam parlemen di kedua negara (Indonesia dan Jepang) masih pada angka minimal, yakni masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar masih berpandangan bahwa perempuan mempunyai keterbatasan dalam bergerak, tidak seperti laki-laki. Dunia politik masih dimaknai sebagai bidang yang dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya bertugas dan berkewajiban untuk mengurusi urusan rumah tangga.
Sekalipun pergeseran paradigma mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah mengalami peningkatan, akan tetapi secara kuantitas perbandingan jumlah anggota parlemen perempuan dan laki-laki masih jauh dari tataran ideal. Di Indonesia, undang-undang yang mensyaratkan kuota perempuan adalah 30% belum berhasil secara optimal untuk mendongkrak jumlah partisipasi perempuan di parlemen. Bahkan, pada pemiliu 2014 terjadi penurunan jumlah perempuan di parlemen sebanyak 0.34 % dari tahun 2009. Padahal, keikutsertaan perempuan dalam parlemen secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu amanat yang tertuang dalam kedua pasal tersebut adalah diharuskannya partai politik peserta pemilu untuk melibatkan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari daftar calon legislatif yang diusulkan.
Adanya ketimpangan jumlah perwakilan perempuan dalam parlemen dapat berimplikasi munculnya ketimpangan gender dalam berbagai bidang, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan bidang lainnya. Padahal jika telisik lebih jauh, negara telah memberikan perlakukan khusus agar setiap warga negara (termasuk perempuan) untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai keadilan sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 E ayat 3 dan pasal 28 H ayat 2.
288 menyebabkan prestasi kaum perempuan kurang dibandingakan potensi sesungguhnya yang dimiliki. Kedua, cinderella complex dimana dalam diri perempuan terdapat sifat ketergantungan akan perlindungan yang muncul berkat pola asuh yang diterimanya bahwa perempuan akan selalu dilindungi selama hidupnya, dimulai dari orang tuanya, saudara laki-lakinya maupun suaminya.
Keterlibatan perempuan dalam parlemen di rasa amat menunjang kemajuan penghargaan terhadap perempuan sebagai individu yang mempunyai hak sama dalam pemerintahan, utamanya dalam memposisikan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Urgensi keterlibatan perempuan dalam politik menurut penuturan salah seorang narasumber adalah untuk menyeimbangkan dan menyalurkan berbagai aspirasi terkait dengan peningkatan posisi, hak, tugas, wewenang dan tanggungjawab perempuan terhadap bangsa dan negaranya.
Hal itu merupakan implementasi dari konsep demokrasi partisipatoris, dimana pemberian kesempatan dari arus bawah merupakan sebuah keharusan yang mutlak. Melalui penggunaan pendekatan secara bottom up, maka konsentrasi pengembangan masyarakat haruslah menjadi agenda utama pemerintah, termasuk didalamnya pengembangan kapasitas dan kompetensi perempuan. Karena itu, keterlibatan seluruh stakeholder dalam mengangkat hak perempuan amat diperlukan untuk membangun kesetaraan gender dalam bidang politik.
Para penggiat kesetaraan gender memandang bahwa jumlah keterwakilan perempuan yang memadai di lembaga pengambilan keputusan akan mampu memperbaiki masalah-masalah yang menghambat kesejahteraan warga negara. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri yang disebabkan oleh pengalaman hidup dan kondisi biologisnya. Masruchah (2009: 115-116) mencontohkan bahwa di Skandinavia, keterwakilan perempuan di parlemen yang melebihi 40 persen dari jumlah kursi yang ada telah mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan karena berimplikasi pada rendahnya tingkat korupsi, efisiensi perjalanan pemerintahan, serta terciptanya transparansi dalam penegakkan hukum.
Minimnya jumlah perempuan dalam parlemen disebabkan oleh beberapa tindakan diskriminasi terhadap gender. Para perempuan yang telah bergabung ke dalam partai politik mengemukakan beberapa kesulitan terkait perlakuan partai, di antaranya adalah pencalonan calon legislatif oleh partai yang lebih mengutamakan laki-laki tanpa menmpertimbangkan kualitas calon legislatif dari perempuan. Untuk melengkapi persyaratan itu, para aktivis partai politik banyak merekrut siapa saja asalkan berjenis kelamin perempuan untuk didaftarkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) ke KPU. Jika kondisi seperti ini terus terjadi di Indonesia maka kerangka demokrasi nasional akan menjadi kerangka yang fana dan minim partisipasi.
Dilihat dari sisi ini, maka keterwakilan yang dibangun hanya sebatas peningkatan keterwakilan secara kuantitatif yang berpeluang tidak tersalurkannya harapan-harapan konstituen (terutama perempuan) dengan baik. Sebaiknya, partai politik yang terkena aturan mengenai perlunya melibatkan perempuan untuk maju dalam parlemen itu tidak semata memenuhi tuntutan, melainkan dengan juga mempertimbangkan aspek kualitas para wakil perempuan yang duduk di parlemen.
289 merupakan sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada persamaan atau kemiripan antara wakil dan yang diwakili (konstituen atau pemilih).
Selanjtnya, Soeseno (2104) menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik yang hanya dilihat dari 30% keberadaan perempuan dalam daftar caleg Pemilu 2014 menunjukkan jenis keterwakilan yang masih bersifat deskriptif. Sedangkan apabila keterwakilan perempuan dalam parlemen tersebut sudah mencukupi kuota, maka jenis keterwakilan tersebut secara ideal akan berubah kerah substantif. Sistem kepartaian yang ada saat ini dan pilihan serta cara-cara rekruitmen kader perempuan oleh partai politik semakin menguatkan pesimisme terhadap munculnya keterwakilan substantif dari kuota 30% untuk perempuan.
Jika kita telisik lebih dalam, secara struktural memang sistem kepartaian di Indonesia belum memberikan peluang secara terbuka bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam partainya. Ketika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka didasarkan atas urutan suara terbanyak, maka calon perempuan membutuhkan energi ekstra, tidak hanya modal sosial berupa pengaruh, cara kampanye, popularitas, tetapi juga faktor modal materi, baik uang maupun benda lainnya yang tidak kecil jumlahnya.
Keterlibatan perempuan dalam kancah politik akhirnya lebih mencerminkan sebuah bentuk ―keterpaksaan‖ daripada ―kesadaran‖ yang pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi dari partai politik yang ingin ―memanfaatkan‖ perempuan dalam pemenuhan kuota yang dipersyaratkan. Aturan tersebut juga dapat memicu tindakan diskriminasi terhadap kaum laki-laki yang memiliki kapabilitas, namun harus tergusur oleh caleg perempuan yang mungkin kualitasnya jauh lebih rendah guna memenuhi tuntutan kuota.
Sebagaimana dijelaskan Susiana (2014) bahwa sistem kepartaian yang ada saat ini dan pilihan serta cara-cara rekrutmen caleg perempuan oleh parpol semakin menguatkan pesimisme terhadap munculnya keterwakilan substantif dari kuota 30% untuk perempuan. Ia menambahkan bahwa fakta dalam Pemilu 2014, perwakilan deskriptif masih menjadi fokus perhatian ketika melihat keterwakilan perempuan di parlemen yang persentasenya menurun. Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal itu adalah sistem pemilu yang tidak ramah terhadap hadirnya keterwakilan perempuan. Ketika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka didasarkan atas urutan suara terbanyak, maka calon perempuan membutuhkan energi ekstra, tidak hanya modal sosial berupa pengaruh, cara kampanye, popularitas, tetapi juga faktor modal materi, baik uang maupun benda lainnya yang tidak kecil jumlahnya.
Dengan sistem suara terbanyak tersebut, kebijakan 30% dalam hal pencalonan melalui aturan 1 di antara 3 calon harus perempuan tetap tidak cukup membantu keterpilihan calon perempuan. Selain faktor tersebut, menurut Susiana (2014) yang harus diperhatikan adalah bagaimana perempuan menghadapi persaingan secara kualitatif dengan calon laki-laki. Hal itulah yang tidak mudah diwujudkan dan membutuhkan perhatian khusus dari parpol serta lembaga nonpemerintah dalam mendorong perempuan agar mempunyai keinginan untuk terjun ke dunia politik praktis disertai bekal pengetahuan dan energi yang cukup. Dengan demikian ke depan akan terwujud cita-cita keterwakilan perempuan minimal 30% atau bahkan lebih di parlemen.
290 peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Keberadaan organisasi-organisasi perempuan ini senantiasa berupaya untuk mengantarkan perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.
Komitmen perempuan sebagai bagian dari sebuah komunitas untuk membangun demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan transformasi sosial. Bersamaan dengan hadirnya komitmen gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politik kaumnya, keterlibatan seluruh stakeholder dalam mengangkat hak perempuan juga diperlukan. Karena itu, diperlukan kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat bahwa permasalahan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia bukan hanya persoalan perempuan menginginkan kesetaraan. Namun, harus disadari penuh bahwa keterlibatan yang seimbang serta kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga legislatif adalah bentuk demokratisasi.
Sebagaimana dijelaskan Fleschenberg (Tersedia dalam http://www.niaspress.dk/files/excerpts/Iwanaga-2extract.pdf tanggal 14 April 2013) bahwa korelasi antara partisipasi perempuan dalam politik dan good governance adalah kebanyakan tokoh politik perempuan yang hadir dalam situasi politik yang kacau atau pada saat-saat transisi politik menuju kepemerintahan yang lebih baik, menghadirkan diri mereka sebagai agen-agen transnasional dengan mengusung agenda politik untuk menata ulang rezim politik yang ada, karenanya kehadiran tokoh perempuan dalam lembaga politik seringkali dilihat sebagai "transformational leaders".
Rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen juga terjadi dalam politik nasional di Jepang, dimana sebagai negara yang menganut paham patriarki, dominasi laki-laki dalam kehidupan politik menjadi besar peranannya. Sekalipun dalam konstitusi pasca perang Jepang memberikan hak dan peluang yang besar bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kancah politik yang setara dengan laki-laki, namun dalam kenyataannya partisipasi perempuan dalam politik di Jepang tidak lebih dari sekedar pemilih.
Perlunya kesamarataan posisi perempuan dan laki-laki terkait pemenuhan hak-hak politiknya dijelaskan Kymlicka (1990: 238-239) sebagai ―dataran egalitarian‖, yakni gagasan mengenai perlakuan yang sama dan setara bagi semua anggota masyarakat. Sekalipun dalam faktanya dikedua negara (Indonesia dan Jepang) tersebut diskriminasi terhadap gender masih menjadi permasalahan utama dalam kehidupan politik kenegaraan. Melalui pelibatan perempuan dalam parlemen, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kondisi ideal dalam pembangunan demokratisasi di kedua negara. Analog dengan Held (1993: 172) yang menjelaskan bahwa esensi dari demokratisasi ideal adalah keadaan yang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan.
291 Jika dikaji lebih jauh, keikutsertaan perempuan Jepang dalam dunia politik dalam level menengah keatas, dalam arti kata kelas tertentu. Rendahnya ketertarikan perempuan Jepang dalam dunia politik, selain disebabkan oleh kentalnya budaya patriarki, juga merupakan dampak dari kekaisaran. Sistem sosial budaya Jepang yang tidak mendukung untuk berkarier dalam dunia politik, dimana kenderungan wanita Jepang memilih pengembangan anak-anaknya dikeluarga turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi perempuan di parlemen. Selain itu, dukungan pemerintah jepang juga tidak menciptakan kuota untuk komponen perempuan, yakni mengalir dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat.
Faktor Sosial Budaya Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia dan Jepang Keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam parlemen amat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ditinjau dari segi sosial kultural, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas di parlemen di Indonesia dan Jepang. Di Indonesia, hal utama berkaitan dengan kondisi sosial budaya yang turut berkontribusi terhadap besar kecilnya keterlibatan perempuan dalam parlemen terdiri dari beberapa faktor.
Pertama, ditinjau dari konteks budaya yang berkembang di Indonesia dimana asas patriarkal masih melekat kental dalam seluruh dimensi kehidupan. Terkait dengan keterlibatan dalam parlemen, prinsip atau persepsi yang selalu dipegang adalah bahwa kehidupan politik merupakan arena yang keras dan cenderung kelaki-lakian, karena itu tidaklah cocok diikuti oleh wanita untuk menjadi anggota parlemen. Sekalipun demikian, parlemen sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi sebuah negara memerlukan sentuhan halus dari para perempuan. Karena itu, keberadaan perempuan dalam parlemen merupakan suatu hal yang diniscayakan.
Secara umum laki-laki memegang kekuasaan di semua lembaga penting dalam masyarakat patriarkal, tetapi ini tidak berarti bahwa perempuan sepenuhnya tidak berdaya atau sepenuhnya tidak mempunyai hak, pengaruh, dan sumber daya di dalam patriarki. Perempuan sebagai bagian dari sistem sosial (terutama keluarga) menghayati nilai-nilai yang ada dalam tata kehidupan, karena itu ia tidak bebas dari ideologi patriarkal. Selama dalam perlindungan seorang laki-laki, perempuan menikmati sebagian hak istimewa laki-laki. untuk mendapatkan hak istimewa itu, perempuan terus menerus merundingkan kembali daya tawar-menawarnya, yang kadang-kadang dengan mengorbankan perempuan lain (Kamla, 1996:19).
Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai tokoh utama dalam keluarga dan masyarakat. Budaya ini, mengabadikan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat yang selanjutnya menghambat perempuan memasuki ranah politik. Sebaliknya, jika kita merujuk pada gagasan Malinowski (dalam Ihromi (1984: 59) bahwa sebetulnya fungsi dari unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar atau kebutuhan sekunder dari para warga masyarakat. Misal, kebutuhan dasar terhadap pangan (makan, minum) menimbulkan kerja sama untuk memproduksi bahan, mengadakan organisasi-organisasi politik dan pengawasan sosial guna menjamin kelangsungan kerja sama.