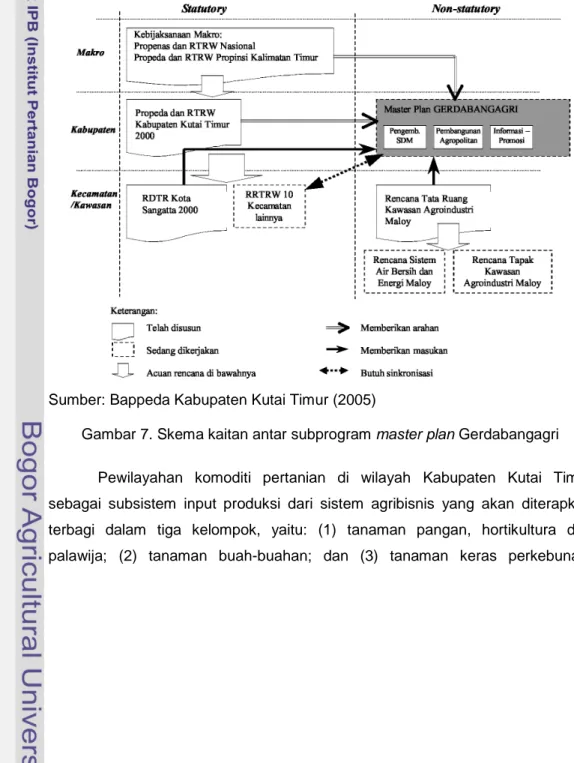2.1 Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi, seperti modal, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Dalam hal penyediaan bahan baku dan proses produksi kegiatan pembangunan dapat membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya (transmigran), yang pada gilirannya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga pilar tujuan yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe, 1993). Pilar pertama adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi. Pilar kedua adalah pembangunan sosial yang bertujuan pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pilar ketiga adalah pembangunan lingkungan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan seperti sanitasi lingkungan, industri yang lebih bersih dan rendah emisi, dan kelestarian sumberdaya alam. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan dengan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan (Munasinghe, 1993)
Pendekatan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan didasarkan pada maksimisasi pendapatan yang dapat digeneralisasikan saat pemeliharaan aktiva (modal) yang menghasilkan keuntungan (manfaat). Hal ini merupakan konsep optimalisasi dan penerapan efisiensi ekonomi dalam menggunakan sumberdaya alam. Dimensi ekonomi merupakan bagian yang penting dan selalu berkontradiksi dengan kepentingan pelestarian sumberdaya alam. Pendekatan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan difokuskan pada keseimbangan sistem biologi dan sistem fisik, terutama pentingnya kelangsungan hidup subsistem yang kritis untuk keseimbangan global dari ekosistem yang menyeluruh. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati adalah aspek kunci.
Sistem alami dapat diinterpretasikan ke dalam seluruh aspek biosfer, termasuk lingkungan buatan manusia seperti pemukiman transmigrasi. Pendekatan sosial budaya dalam pembangunan berkelanjutan adalah berusaha untuk memelihara stabilitas sistem sosial dan budaya, yang mempunyai bentuk-bentuk dan perilaku yang sudah terpolakan, menciptakan kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang dirancang untuk memberi makna bagi tindakan kolektif.
Pandangan pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Moffatt dan Hanley (2001), bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting yang harus mengintegrasikan komponen-komponen sumberdaya, yaitu komponen ekonomi, komponen sosial budaya dan komponen lingkungan secara serasi dan seimbang. Pemanfaatan komponen-komponen sumberdaya secara serasi dan seimbang dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pada saat sekarang tanpa mengurangi kesempatan dan pemenuhan kehidupan generasi pada saat mendatang.
Harger dan Meyer (1996) menyatakan bahwa, dari masing-masing dimensi utama dalam pembangunan berkelanjutan tersebut diuraikan dalam beberapa kategori yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Dimensi ekologi dengan kategori: penggunaan energi; atmosfir; iklim; sistem yang berhubungan dengan air (aquatic system); sistem terestrial; natural hazard dan biosfer. Dimensi sosial dengan kategori: pertanian; penduduk; kesehatan; urban system; kemiskinan; politik; pengelolaan lingkungan; pendidikan; rural system; fasilitas publik dan infrastruktur dan masyarakat dan budaya. Dimensi ekonomi dengan kategori: pertambangan; pertimbangan militer; telekomunikasi; perdagangan; industri; transportasi; bantuan luar negeri dan alih teknologi. Gilbert (1996) menyatakan bahwa pada prinsipnya indikator pembangunan berkelanjutan mempunyai dua
jenis atau tipe utama, yaitu: pemanfaatan sumberdaya alam yang bersifat pressure of environment dan akibat atau dampak dari pemanfaatan sumberdaya alam yang bersifat impact of environment.
Dari berbagai pendapat mengenai pembangunan berkelanjutan, nampak bahwa setiap pembangunan harus memenuhi ketiga pilar dan ketiga indikator pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia adalah tujuan utama pembangunan. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan dipenuhinya kebutuhan dasar bagi semua generasi dan diberinya kesempatan kepada semua generasi untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan yang wajar ditentukan secara sosial dan kultural, dan pembangunan berkelanjutan menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berada dalam batas-batas kemampuan ekologi.
Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (2005) menyatakan, kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan yang digunakan dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu: keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan teknologi. Tiga kriteria pertama adalah mengenai dampak lokal, sehingga batas wilayah adalah lokal. Lebih spesifik lagi, lingkup untuk kategori kriteria keberlanjutan lingkungan adalah wilayah yang mengalami dampak ekologis langsung akibat pembangunan. Sementara lingkup untuk kategori kriteria keberlanjutan ekonomi dan sosial adalah batas administratif kabupaten. Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas kabupaten maka batas administratsi yang digunakan adalah semua kabupaten yang terkena dampak. Berbeda dengan ketiga kategori kriteria lainnya, batas dari keberlanjutan teknologi adalah di tingkat nasional.
Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan pada banyak negara dan oleh berbagai lembaga dengan mengembangkan indikator keberlanjutan antara lain: Center for International Forestry Research - Cifor (1999) mengembangkan sistem pembangunan kehutanan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Food and Agriculture Organization - FAO (1995) mengembangkan indikator keberlanjutan untuk pembangunan wilayah pesisir berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, dan pertahanan keamanan.
Charles (1994) menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan haruslah mengakomodasikan ketiga aspek yaitu: ecological sustainability (keberlanjutan ekologi), socioeconomic sustainabilty (keberlanjutan
sosio-ekonomi), community sustainability (keberlanjutan masyarakat). Prasyarat untuk mencapai keberlanjutan ketiga aspek tersebut maka diperlukan institutional sustainability (keberlanjutan kelembagaan) yang menyangkut memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat. Dengan demikian jika setiap komponen dilihat sebagai komponen yang penting untuk menunjang keseluruhan proses pembangunan berkesinambungan, maka kebijakan pembangunan yang berkesinambungan haruslah mampu memelihara tingkat yang reasonable dari setiap komponen sustainable tersebut. Dengan kata lain keberlanjutan sistim akan menurun melalui kebijakan yang ditujukan hanya untuk mencapai satu elemen keberlanjutan saja.
Pembangunan berkelanjutan mempunyai indikator-indikator: culture-ecology interface, didefinisikan bahwa, pembangunan berkelanjutan merupakan fungsi yang integratif dari nilai-nilai sosial budaya yang menyatu terhadap ekosistem. Indikator yang termasuk dalam perubahan etika lingkungan, komitmen untuk menjaga keseimbangan political-cultural dan ecoturism; culture-economy interface, menggambarkan fungsi tujuan di dalam nilai-nilai non market dan keputusan untuk menjaga konservasi lingkungan untuk tujuan budaya. Nilai-nilai kultural ekonomi lebih tinggi, demikian juga refleksinya terhadap politik, institusi dan struktur hukum; dan economy-ecology interface, menggambarkan fungsi tujuan dalam termin dari nilai-nilai ekonomi dan cost benefit analysis (Rustiadi et al., 2004).
Pembangunan selain memperhatikan aspek keberkelanjutan, juga harus didekati dengan pendekatan yang menyeluruh yang menyangkut berbagai dimensi. Alder et al. (2000) melihat bahwa pendekatan yang holistik tersebut harus mengakomodasi berbagai komponen yang menentukan keberlanjutan pembangunan. Komponen tersebut menyangkut aspek ekologi, ekonomi teknologi, sosiologi dan aspek etis. Dari setiap komponen atau dimensi ada beberapa atribut yang harus dipenuhi yang merupakan indikator keragaan sumberdaya sekaligus indikator keberlanjutan.
Dalam kaitan dengan pengembangan kawasan, khususnya di wilayah yang terisolasi, maka dimensi aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Aspek aksesibilitas menjadi penting dalam pengembangan kawasan didukung oleh prinsip penetapan sistem jaringan transportasi di Kalimantan telah dijelaskan dalam naskah akademis penyusunan RTR pulau Kalimantan dan Kajian Ekonomi Wilayah Kalimantan yakni menghubungkan
pusat-pusat pertumbuhan (kota-kota) secara hirarki dan sistemik sesuai UU No 38 tahun 2004 tentang jalan, untuk mewujudkan efisiensi struktur wilayah, dan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pergerakan melalui pemanfaatan sistem intermoda jaringan jalan dan angkutan sungai sesuai koridor masing-masing (Djakapermana, 2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi pada pasal 13 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa salah satu syarat kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah mempunyai kemudahan hubungan antar kota atau wilayah yang sedang berkembang.
Kriteria keberlanjutan lingkungan adalah dengan menerapkan konservasi atau diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan indikator: (a) terjaganya keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis; (b) tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan yang berlaku, nasional dan lokal (tidak menimbulkan pencemaran udara, air, tanah); (c) terjaganya keanekaragaman hayati (genetik, spesies, dan ekosistem) dan tidak terjadi pencemaran genetika; (d) dipatuhinya peraturan tata guna lahan atau tata ruang.
Kriteria keselamatan dan kesehatan masyarakat lokal, dengan indikator : (a) tidak menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan; (b) dipatuhinya peraturan keselamatan kerja; (c) adanya prosedur yang terdokumentasi yang menjelaskan usaha-usaha yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan mengatasi bila terjadi kecelakaan.
Keberlanjutan ekonomi dengan kriteria kesejahteraan masyarakat lokal dan indikatornya adalah : (a) tidak menurunkan pendapatan masyarakat lokal; (b) adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (c) adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan dampak penurunan pendapatan bagi sekolompok masyarakat; (d) tidak menurunkan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat lokal.
Keberlanjutan sosial dengan kriteria partisipasi masyarakat dengan indikator yaitu adanya proses konsultasi ke masyarakat lokal dan adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap komentar, keluhan masyarakat lokal. Kriteria lain yaitu pembangunan yang dilakukan tidak merusak integritas sosial masyarakat dengan indikator tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat lokal.
Keberlanjutan teknologi dengan kriteria terjadi alih teknologi dan indikatornya adalah tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dalam hal pengetahuan dan pengoperasian alat (know-how), tidak menggunakan teknologi yang masih bersifat percobaan dan teknologi usang dan mengupayakan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan teknologi lokal.
2.2 Pengembangan Wilayah
Paradigma pembangunan selama beberapa dekade terakhir terus mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan mendasar. Dalam pengkajian kebutuhan pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam kerangka normatif perencanaan pembangunan daerah, GTZ (2000) memberikan pendapat, bahwa berbagai pergeseran akibat adanya distorsi berupa kesalahan di dalam menerapkan model-model pembangunan selama ini adalah: (1) kecenderungan dengan pendekatan melihat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diukur secara makro menuju pendekatan lokal (regional), (2) pergeseran dari situasi yang harus memilih antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pada keharusan melakukan pembangunan secara berimbang, dan (3) pergeseran asumsi tentang peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian).
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang diinginkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan kondisi yang lebih baik dari pada sebelum pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Syahroni, 2002). Dengan demikian pembangunan harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual (Rustiadi et al., 2004).
Dalam perspektif kewilayahan, kesadaran akan perubahan pemikiran dan konsepsi pembangunan juga lahir akibat terjadinya ketidakadilan yang begitu menonjol antar wilayah. Terjadinya disparitas pembangunan wilayah berupa dikotomi pedesaan (rural) dengan perkotaan (urban), Kawasan Timur Indonesia
(KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), Jawa dengan luar Jawa adalah sebagai bukti adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.
Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menjadi signifikan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Pembangunan wilayah berbeda dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata dan menyeluruh secara nasional, dan bukan pendisagregasian dari pembangunan nasional karena memiliki peranan dan tujuan yang berbeda (Budiharsono, 2001). Berbeda pula dengan pendekatan pembangunan sektoral yang hanya bertujuan untuk mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan satu sektor tertentu, tanpa memperhatikan kaitannya dengan sektor lain.
Konsep pengembangan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu terapan seperti geografi, ekonomi, sosiologi, statistika, ilmu politik, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Hal ini karena pembangunan itu merupakan fenomena multifaset yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu (Budiharsono, 2001). Pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya secara harmonis, serasi melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan (Misra, 1982).
Pengembangan wilayah walaupun secara eksplisit dapat memiliki tujuan-tujuan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, namun secara umum akan meliputi satu atau lebih dari tujuan-tujuan pembangunan yang saling berkaitan antar wilayah. Menurut Syahroni (2002), tujuan-tujuan pembangunan wilayah adalah: (1) mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar sub-wilayah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan), (2) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, (3) menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan, (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, dan (5) mempertahankan
atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa mendatang (pembangunan berkelanjutan).
Tap MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam menetapkan langkah yang harus dilakukan dalam optimasi pengelolaan sumberdaya alam yaitu: (1) mewujudkan optimasi pemanfaatan sumberdaya alam harus melalui tahapan identifikasi dan investasi kualitas sumberdaya alam sebagai potensi pembangunan nasional dan (2) perlu disusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk perencanaan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir) yang didasarkan pada optimasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.
Konsep pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu strategi untuk pengembangan wilayah baru. Menurut Rustiadi et al. (2004), strategi pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di luar pulau Jawa menjadi sangat penting, secara teoritis strategi tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori strategi, yaitu: (1) demand side strategy dan (2) supply side strategy. Strategi pertama, demand side adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan permintaan akan barang-barang dan jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. Contoh dari strategi demand side adalah program transmigrasi yang diharapkan akan meningkatkan permintaan barang-barang non pertanian. Efek dari peningkatan permintaan barang non pertanian tersebut adalah menarik industri barang dan jasa. Dalam strategi ini diharapkan masyarakat mampu mengelola sumberdaya alam (lahan) yang ada melalui insentif (rangsangan kegiatan).
Konsep pengembangan wilayah transmigrasi dengan strategi demand side didasarkan pada 6 (enam) stadia pengembangan yaitu: (1) stadia sub-subsisten, pada tahap ini para transmigran belum mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan untuk produksi sehingga kebutuhan sehari-hari masih harus dibantu oleh pemerintah; (2) stadia subsisten, pada tahap ini transmigran mampu memenuhi kebutuhan pokok saja; (3) stadia marketable surplus, pada tahap ini transmigran telah memperolah surplus dari kegiatan pertanian. Seiring dengan kondisi surplus ini terjadi situasi dimana timbul permintaan terhadap
barang dan jasa (kebutuhan sekunder), sehingga memungkinkan perkembangan sektor-sektor non-pertanian khususnya yang didasarkan pada output pertanian. Pada stadia ini mulai terdapat diversifikasi pekerjaan; (4) stadia industri pertanian, merupakan stadia yang diharapkan tumbuhnya industri pedesaan seiring dengan perkembangan spesialisasi pekerjaan didasarkan pada comparative advantage atas wilayah-wilayah lainnya; (5) stadia industri non-pertanian, pada stadia ini diusahakan terdapat peningkatan permintaan barang-barang mewah; dan (6) stadia industrialisasi (Rustiadi et al., 2004).
Model strategi pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi dengan pola demand side, dalam kenyataannya sering kali tertahan sampai pada stadia ke dua. Namun ada yang sampai pada stadia ke tiga. Keuntungan digunakan strategi demand side adalah strategi ini sangat stabil, tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di luar daerah yang berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan yang mantap. Sedangkan kerugian strategi ini memerlukan waktu yang relatif lama, karena tiap stadia membutuhkan transformasi teknologi dan transformasi struktur kelembangaan (Rustiadi et al., 2004).
Pengertian dari strategi kedua, supply side adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan produksi yang berorientasi keluar. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan suplai dari komoditi yang pada umumnya di proses dari sumberdaya alam lokal. Adanya peningkatan penawaran akan meningkatkan ekspor wilayah yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan lokal. Hal ini akan menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah tersebut (Rustiadi et al., 2004).
2.3 Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, menyatakan tujuan program transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarkat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran utamanya adalah: (1) pemerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia melalui usaha pemindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat seperti pulau Jawa, pulau Madura dan Bali ke daerah yang berpenduduk masih jarang, (2) mengembangkan wilayah-wilayah yang
potensial yang masih terbelakang melalui pemaduan sumberdaya alami yang potensial di daerah tersebut dengan sumberdaya manusia sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, (3) mempercepat tercapainya kehidupan yang layak bagi penduduk, baik penduduk setempat maupun transmigran melalui peningkatan pendapatan yang lebih besar dari kebutuhannya sehingga dapat mendorong perkembangan pemukiman lebih maju dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian wilayah, (4) menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah di seluruh Indonesia, dan (5) meningkatkan ketahanan nasional.
Pembangunan permukiman transmigrasi yang selama ini dibangun oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu mencapai tingkat perkembangan secara optimal, yang mampu menopang perkembangan wilayah, baik wilayah itu sendiri atau wilayah lain yang sudah ada (Anharudin et al., 2003). Pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) memang dirancang agar secara ekonomi dapat menopang pertumbuhan kawasan di sekitarnya dan memberikan kontribusi terhadap wilayah lain melalui distribusi barang dan jasa. Namun dalam realitasnya banyak UPT atau kawasan transmigrasi belum sepenuhnya mampu menopang perkembangan wilayah, bahkan banyak lokasi transmigrasi yang dibangun justru berada pada posisi terpencil (Danarti, 2003). Dengan demikian pembangunan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya mampu mempercepat proses pembangunan wilayah dengan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dimasa depan, prinsip yang dipegang dalam pembangunan kawasan transmigrasi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RTRWK) dan memungkinkan bagi pengembangan spasial secara menyeluruh (Priyono, 2003).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi pada pasal 13 ayat (1) dan (2), kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus sesuai dengan tata ruang wilayah/ daerah. Selain itu, juga harus memenuhi syarat: (a) memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomi, (b) mempunyai kemudahan hubungan antar kota atau wilayah yang sedang berkembang, dan (c) tingkat kepadatan penduduk masih rendah. Penggunaan istilah kawasan di Indonesia digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah (Rustiadi et al., 2004). Karena itu definisi konsep kawasan adalah adanya karakteristik hubungan dari
fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Dengan demikian setiap kawasan atau sub-kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut.
Pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan secara terencana. Hal ini disebabkan pembangunan kawasan transmigrasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena di dalam satu kawasan transmigrasi terdapat tiga sampai lima unit permukiman transmigrasi dan satu unit permukiman transmigrasi merupakan embrio dari satu desa atau satu kelurahan. Dengan demikian dalam satu kawasan transmigrasi memerlukan luasan lahan yang cukup luas untuk membangun permukiman, lahan-lahan usaha pertanian, sarana dan prasarana permukiman, baik sarana dan prasarana di unit permukiman transmigrasi, antar unit permukiman di dalam satu kawasan maupun antar kawasan.
Dalam suatu proses pembangunan terdapat pentahapan perencanaan pembangunan. Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat mempunyai makna sebagai upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi et al., 2004). Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.
Perencanaan merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan dapat didefinisikan secara berbeda-beda, namun dalam pengertian yang sederhana, perencanaan adalah suatu cara untuk mempersiapkan masa depan (Syahroni, 2002). Sedangkan menurut Rustiadi et al, (2004), perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Berbeda dengan batasan ini, Hayashi (1976), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses bertahap dari tindakan yang terorganisasi untuk menjembatani perbedaan antara kondisi yang ada dan aspirasi organisasi.
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka suatu perencanaan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) harus menyangkut masa yang akan datang, (2) menyangkut tindakan, dan (3) terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau
organisasi, yakni serangkaian tindakan untuk masa yang akan datang yang diambil oleh perencana. Dari berbagai pendapat dan definisi yang dikembangkan mengenai perencanaan secara umum hampir selalu terdapat dua unsur penting, yaitu: (1) unsur yang ingin dicapai dan (2) unsur cara untuk mencapainya (Rustiadi et al., 2004). Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan kawasan transmigrasi, maka unsur yang ingin dicapai adalah pembangunan wilayah dan cara untuk mencapainya adalah dengan pemanfataan sumberdaya lahan untuk usahatani secara optimal.
Program transmigrasi telah terbukti mampu meminimalisir permasalahan kependudukan. Pulau-pulau yang kepadatan penduduknya sangat tinggi seperti Jawa, Madura dan Bali, lambat-laun kepadatan penduduk mulai turun dan daya dukungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk mulai meningkat. Sedangkan pulau-pulau yang potensi sumberdaya alamnya melimpah, namun potensi sumberdaya manusianya kurang, telah berkembang dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya setelah diterapkannya program transmigrasi (Pasaribu, 2004).
Pembangunan transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi, terutama perubahan pada tata pemerintahan Pada kurun waktu 2004-2009, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung maupun tidak langsung.
Kebijakan transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: (1) penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak; (2) memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja; (3) memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk (Anharudin et al., 2003). Untuk kawasan timur Indonesia pembangunan transmigrasi diarahkan untuk: (1) mendukung pembangunan wilayah yang masih tertinggal, (2) mendukung pembangunan wilayah perbatasan, dan (3) mengembangkan permukiman transmigrasi yang
telah ada, pembangunan permukiman baru secara selektif, dan pengembangan desa-desa/permukiman transmigrasi potensial.
Di era otonomi daerah, tatacara penyelenggaraan transmigrasi dan pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan terhadap tuntutan perkembangan keadaan saat ini. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah (Anharudin et al., 2003).
Pembangunan transmigrasi pada masa otonomi daerah lebih diutamakan kearah pembangunan dan pengembangan wilayah (pembangunan kewilayahan) dengan upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan transmigrasi berkaitan dengan upaya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam (lahan). Transmigrasi dipandang sebagai sektor pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan upaya pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah (Saleh, 2005).
Konsep pengembangan wilayah mengacu pada kemajuan. Kemajuan suatu wilayah ditandai dengan banyak hal, tapi yang paling penting adalah semakin banyaknya kegiatan bisnis (usaha) dan produktifitas masyarakatnya, yang kemudian berimplikasi pada peningkatan pendapatan, daya beli, dan akumulasi kapital, baik pada tingkat lokal maupun regional. Kemajuan ekonomi ini kemudian membawa implikasi pada kemajuan sosial dan kultural, yang ditandai oleh semakin bertambahnya infrastruktur dan layanan jasa masyarakat (Saleh, 2005). Ujung dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan transmigrasi adalah pembinaan/ pemberdayaan masyarakat transmigrasi, sehingga seringkali dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Penekanan pembinaan/ pemberdayaan masyarakat transmigrasi adalah pada kegiatan ekonomi dan sosial budaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui tingkat pendapatan yang layak untuk hidup di Unit Pemukiman, masyarakat hidup secara harmonis tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan atau kawasan ekonomi sehingga mampu memberi konstribusi bagi pembangunan dan pengembangan wilayah (Tulie, 2001).
Alisadono et al. (2006) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan transmigrasi yang diawali dengan perencanaan, pembangunan permukiman, pembinaan/ pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar, serta pemberdayaan lokasi transmigrasi, akan melibatkan dan memperhatikan
banyak dimensi. Seperti: instansi yang terlibat dalam pembangunan transmigrasi, penduduk (transmigran) yang berpindah dari satu tempat lama ke tempat yang baru, kondisi lahan, komoditi pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan infrastruktur di lokasi transmigrasi, maka diperlukan suatu tinjauan kebijakan dengan pendekatan secara holistik, yaitu melalui pendekatan sistem. Dalam sistem transmigrasi terdapat keterkaitan dan hubungan satu dimensi dengan dimensi lainnya. Manusia di satu pihak dan tanaman, hewan serta lingkungan di lain pihak menunjukan keterkaitan yang rumit dan bersifat multi dimensi. Namun demikian kerumitan-kerumitan tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi dan ditangani untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
Dalam perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi perlu memperhatikan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan yang sudah ada (kota kecamatan, kota kabupaten) dengan permukiman transmigrasi yang akan dibangun. Dengan demikian dapat diharapkan akan terdapat hubungan saling ketergantungan antara pemukiman transmigrasi yang merupakan daerah pinggiran dengan kota sebagai daerah inti (core areas) (Sitorus dan Nurwono, 1998). Hubungan saling ketergantungan ini dimaksudkan untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di pemukiman transmigrasi yang merupakan hunian dari komunitas baru dengan basis usaha pertanian.
Pada tahun 1979 diperkenalkan konsepsi pengembangan wilayah di Indonesia dalam kaitannya dengan penyusunan landasan kerja untuk program transmigrasi dengan gagasan pengembangan tata ruang nasional (Sitorus dan Nurwono, 1998). Intinya adalah penempatan satuan permukiman (SP) baru akan dapat hidup jika unsur-unsur manusia, sumberdaya alam dan sarana-sarana pengusahaan dengan kegiatan manusia dapat diorganisir. SP ini berada dalam satuan kawasan permukiman (SKP) yang berada dalam wilayah pengembangan partial (WPP) dari tata ruang nasional. Beberapa WPP berada dalam satuan-satuan wilayah pengembangan (SWP). Pola SP, SKP dan WPP juga menganut pola aliran barang dan jasa dalam struktur pewilayahan pengembangan transmigrasi mengikuti mekanisme pasar dan berjenjang, yaitu dari SP ke pusat SKP, dari pusat SKP menuju pusat WPP dan selanjutnya dikumpulkan di pusat SWP yang merupakan pintu gerbang pemasaran kearah luar wilayah, baik untuk lingkup regional, nasional maupun internasional. Begitu pula arus barang dan jasa dari luar pertama kali masuk pintu gerbang SWP untuk kemudian didistribusikan ke pusat-pusat yang lebih rendah.
Struktur perencanaan pembangunan kawasan transmigarsi diwujudkan dalam satuan-satuan interaksi terkecil hingga terbesar secara berjenjang (Sitorus dan Nurwono 1998), yang mempunyai ciri-ciri berupa:
(1) Satuan Permukiman (SP), merupakan satuan interaksi terkecil dengan kepentingan utama permukiman sebagai tempat tinggal (hunian), tempat usaha dan kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
(2) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), merupakan kumpulan beberapa SP, dimana SP utama berfungsi sebagai pusat koleksi pemasaran produk maupun distribusi kebutuhan lingkungan permukiman SKP. Pada skala ini kegiatan perdagangan baru berlangsung pada tingkat pedagang pengumpul skala kecil atau menengah, sehingga belum memadai bagi pembentukan simpul jasa industri/ produksi manufaktur.
(3) Wilayah Pengembangan Partial (WPP), merupakan kumpulan beberapa SKP, dimana SKP utama mempunyai keuntungan aksesibilitas dalam arti orientasi geografis pemasaran yang memenuhi pembentukan simpul jasa koleksi dan distribusi. Pada skala ini telah memenuhi persyaratan suatu interaksi yang cukup lengkap bagi berlangsungnya pertumbuhan kegiatan produksi manufaktur, sehingga merangsang berkumpulnya pedagang besar/ grosir pada suatu lokasi.
(4) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), merupakan kumpulan beberapa WPP, dimana WPP utama berfungsi sebagai pintu gerbang ekspor komoditas transmigran yang bertumpu pada fungsinya sebagai simpul jasa industri, sedangkan kota-kota dan pusat-pusat WPP lainnya mempunyai kedudukan yang umum, yaitu sebagai penunjang pintu gerbang terhadap kota-kota lainnya.
Konsep satuan-satuan wilayah pengembangan parsial lebih memperhatikan mekanisme ketergantungan hubungan ekonomi dan sosial dalam kondisi pasar terbuka dari pada peran pemerintah, dan batas administrasi bukan merupakan kendala. Pada kenyataanya mekanisme ketergantungan sosial ekonomi terbentuk karena peran campur tangan pemerintah cukup besar. Terlebih-lebih pada daerah yang baru sebagai wilayah frontier , untuk investasi sarana dan prasarana sosial ekonomi hampir tidak ada swasta yang mampu membangun baru dengan biaya investasinya sendiri. Karena itu, pendekatan mekanisme ketergantungan sosial ekonomi di dalam perencanaan pengembangan wilayah transmigrasi lebih banyak berfungsi sebagai wawasan
penataan tata ruang yang dianut para perencana daripada dianut oleh para pelaksana, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Secara skematik pola perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi di lahan kering disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Pola perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi di lahan kering
Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi pada wilayah pengembangan kawasan transmigrasi komponen-komponen yang harus diperhatikan adalah: (1) komponen optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan, misalnya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, (2) komponen pemanfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan upaya-upaya pencegahan kecenderungan pada kerusakan alam, dan (3) komponen sarana, prasarana utama dan penunjang untuk permukiman dan usaha pertanian, untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari komoditi yang dihasilkan dari ekstraksi sumberdaya alam. Hal ini karena secara hirarki dalam setiap wilayah pengembangan kawasan transmigrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi pasal
Catatan : Pusat pertumbuhan ekonomi (PPE) dapat berada di dalam atau di luar kawasan Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2003.
Batas Imaginer Kawasan Transmigrasi
Batas Imaginer Unit Permukiman Transmigrasi
Permukiman transmigrasi yang ada (Transmigran Penduduk Setempat)/ TPS
Lokasi Transmigran Penduduk Pendatang/ TPP
Jalan yang ada
Jalan baru yang akan dibangun
Keterangan :
Sentra Fasilitas Unit / Satuan
Permukiman
PPE yang ada/ baru
Wilayah Pengembangan Kawasan Transmigrasi TPS TPP Satuan Kawasan Pengembangan
16 ayat (1), (2), (3), beberapa satuan kawasan pengembangan mempunyai daya tampung sekurang-kurangnya 9.000 kepala keluarga. Setiap SKP terdiri dari beberapa SP dan mempunyai daya tampung 1.800 sampai 2000 kepala keluarga. Setiap SP mempunyai daya tampung 300 sampai dengan 500 kepala keluarga.
Dari segi sarana dan prasarana didisain secara berjenjang (berhirarki) sesuai dengan tingkat pelayanannya. Hal ini seperti disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 pasal 17, 18 dan 19, dalam setiap wilayah pengembangan kawasan transmigrasi harus dilengkapi dengan pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan tingkat menengah, dan pusat pemerintahan. Pada setiap SKP harus terdapat sarana industri kecil/ industri rumah tangga, pasar harian, pertokoan, pelayanan jasa perbankan, perbengkelan, pelayanan pos, pendidikan tingkat pertama, puskesmas pembantu, dan pelayanan pemerintahan.
Di tingkat SP harus dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti: warung atau koperasi, pasar, sekolah dasar, balai pengobatan, balai desa dan tempat ibadah. Setiap SP tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi desa dan dapat diwujudkan sebagai desa utama. Elemen-elemen pada perencanaan permukiman seperti sarana dan prasarana permukiman merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Hal ini penting mendapat pertimbangan dalam pemanfaatan lahan yang efektif dan efisien (optimasi pemanfaatan lahan). Seperti dikemukakan dalam The Development of Resettlement Policy in China: Two Case Studies in Sichuan and Hebei Provinces, bahwa elemen-elemen fasilitas umum dan fasilitas sosial serta sarana dan prasarana untuk permukiman kembali (resettlement) merupakan suatu pertimbangan yang utama dalam merencanakan permukiman, karena hal ini akan meningkatkan kualitas kehidupan yang baru, dan aktifitas kehidupan di komunitas yang baru akan menjadi lebih aktif dan lebih hidup (Armstrong, 2000). Tujuan utama merencanakan permukiman untuk transmigrasi, adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan (Bizer et al., 1997).
Pusat-pusat pelayanan pemerintahan, sosial-budaya, ekonomi/ pasar, kesehatan, air (air bersih untuk konsumsi dan rumah tangga serta air untuk pertanian), pendidikan, prasarana perhubungan (terminal, jalan, dermaga) dibuat
dan disesuaikan dengan tingkat pelayanan permukiman secara berhirarki pada pusat-pusat kegiatan. Hal ini disebutkan dalam Guidelines for Rural Centre Planning (UN, 1979). Pada perencanaan kawasan permukiman transmigrasi, selain itu juga harus memiliki potensi untuk pengembangan usaha primer, sekunder dan atau tersier; tersedia prasarana dan sarana permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, seperti potensi luasan lahan kering yang belum termanfaatkan secara optimal serta tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah, maka peluang pembangunan kawasan transmigrasi cukup terbuka. Oleh karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi yang didahului dengan suatu sistem perencanaan yang komprehensif dan holistik dengan suatu kebijakan yang operasional, diharapkan akan menghasilkan suatu pembangunan kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.
Dalam perspektif holistik, pada saat penyusunan kebijakan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi menurut Bastian (2001) perencanaan tata ruang kawasan permukiman transmigrasi harus difokuskan pada tiga aspek, yaitu: (1) struktur, proses, dan kesempatan, (2) aspek alokasi ruang (pemanfaatan ruang) beserta hirarkinya, (3) aspek kompleksitas dari berbagai faktor perbedaan dari suatu lansekap. Prinsip holistik dalam perencanaan kawasan transmigrasi harus menjadi pegangan utama, karena dalam proses perencanaan melibatkan banyak sektor dan banyak pihak serta implikasi ruangnya tidak hanya dibatasi dalam satu kawasan, tetapi sering lintas kawasan dan atau lintas wilayah.
Proses perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi mempunyai implikasi terhadap perencanaan pembangunan wilayah disekitarnya. Dengan kata lain bahwa perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi berkaitan dengan suatu perencanaan pembangunan wilayah yang telah dituangkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota. GTZ (2000) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: (1) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, (2) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, (3) menyusun konsep
strategi-strategi bagi pemecahan masalah dan, (4) melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara keseluruhan.
Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi dan perencanaan wilayah merupakan bentuk pengkajian yang sistematik dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Rustiadi et al. (2004), sasaran utama dari perencanaan wilayah pada dasarnya untuk menghasilkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan, yang dapat dikelompokkan dalam tiga sasaran umum yaitu: efisiensi dan produktifitas, pemerataan dan akseptibilitas masyarakat, dan keberlanjutan. Sasaran efisiensi merujuk pada manfaat ekonomi dalam konteks kepentingan publik, pemanfaatan sumberdaya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Wilayah sebagai suatu matrik fisik harus merupakan perwujudan keadilan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, perencanaan yang disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Perencanaan wilayah juga harus berorientasi pada keseimbangan fisik, lingkungan dan sosial, sehingga akan menjamin peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan.
Pada umumnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi akan meliputi tiga tahapan proses mendasar yang saling terkait, yaitu: (1) perumusan dan penentuan tujuan, (2) pengujian dan analisis pilihan-pilihan yang tersedia, dan (3) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Syahroni, 2002). Salah satu elemen penting lainnya dalam perencanaan adalah selalu berorientasi pada masa depan. Perencanaan tidaklah statis dalam tahap tersebut melainkan dinamis karena berjalan sebagai suatu rangkaian proses (siklus) yang terus menerus.
Tahapan dalam pembangunan transmigrasi pada dasarnya tidak berbeda dengan tahapan pembangunan pada umumnya, yang terdiri dari atas empat tahap kegiatan, yaitu: tahap perencanaan, tahap konstruksi dan pengadaan, tahap operasi, dan tahap evaluasi kinerja (Yudohusodo, 1998). Perencanaan pembangunan transmigrasi dilakukan mulai tahun ke lima sampai dengan tahun ke tiga sebelum penempatan transmigran (T-5 sampai T-3). Tahap ini disebut perencanaan makro, menyangkut antara lain: kebijakan umum penyelenggaraan transmigrasi, perencanaan lima tahunan, studi perencanaan wilayah (termasuk di
dalamnya penyediaan tanah dan penyelesaian statusnya), perencanaan jangka menengah untuk penyiapan permukiman, pengerahan dan penempatan, pemberdayaan masyarakat transmigran dan penduduk lokal disekitarnya.
Perencanaan yang bersifat mikro, dilakukan pada tahun ke dua sampai dengan tahun ke satu sebelum penempatan (T-2 sampai T-1), meliputi: rencana teknis satuan pemukiman (RTSP), rencana teknis jalan (RTJ), rencana teknis pengerahan dan penempatan transmigran, rencana teknis pemberdayaan masyarakat transmigran dan masyarakat penduduk sekitar, serta penyusunan program tahunan (menurut jenis, pola, lokasi dan tahun pembinaan).
Prosedur standar perencanaan permukiman transmigrasi (Depnakertrans, 2003a), khususnya perencanaan permukiman transmigrasi dibagi dalam tiga tahap utama dengan tahap perencanaan serta jenis dan keluaran peta seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Jenis dan keluaran peta dan tahap perencanaan permukiman transmigrasi
Tahap Perencanaan No Jenis dan keluaran
peta I II III
1 Jenis peta Rencana Kerja
WPP Rencana Kerja SKP Rencana Teknis SP 2 Skala peta 1:100.000 1:50.000 1:10.000
3 Luasan areal (ha) 20.000-30.000 4.000-6.000 1.500-3.000
4 Jumlah KK 10.000 2000 500
Perencanaan Tahap I
Pada tahap ini perencanaan dibagi dalam dua bagian. Pertama, yang bersifat makro, sehingga pertimbangan yang digunakan bersifat makro, seperti konteks pembangunan nasional dan regional. Perencanaan ini lebih menggambarkan struktur Satuan Wilayah Pengembangan, untuk itu peta yang digunakan masih bersifat makro dengan skala peta 1 : 250.000 seperti peta dan data dasar yang dihasilkan oleh RePPProT. (Regional Physical Planning Project for Transmigration). Kedua, melihat lingkup yang lebih kecil (mikro) dengan memperhatikan areal yang secara fisik benar-benar potensial (peta skala 1 : 100.000) berupa Rencana Kerangka Wilayah Pengembangan Partial (RKWPP). Selanjutnya rencana ini dikaitkan dengan aspek-aspek lain, seperti: aspek sosial,
ekonomi dan pengembangan tata ruang wilayahnya. Aspek pengembangan tata ruang wilayah juga sangat berkait dengan pusat-pusat pelayanan regional yang ada atau yang akan dikembangkan. Keluaran dari dari perencanaan tahap satu ini adalah perkiraan daya tampung transmigran beserta dengan tahapan pengembangannya untuk dijadikan masukan bagi perencanaan tahap berikutnya.
Perencanaan Tahap II
Studi perencanaan tahap dua merupakan langkah yang menekankan proses penyaringan untuk menghasilkan Rencana Kerangka Satuan Kawasan Permukiman (RKSKP), yang mempertimbangkan kesesuaian lahan, kondisi sosial ekonomi dan sosial-budaya, serta wawasan lingkungannya. Rencana tersebut disajikan dalam peta berskala 1 : 50.000 dengan dukungan peta RePPProT, foto udara dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan kondisi fisik (iklim, hidrologi), pertanian dan kehutanan. Indikasi tentang kemungkinan dikembangkannya pola usaha baru seperti PIR-Trans, HTI-Trans, juga akan ditunjukkan dalam studi ini. Oleh karena itu rencana ini harus sudah melalui pembahasan dan koordinasi yang lebih luas. Keluaran dari perencanaan ini sudah dapat menggambarkan batas masing-masing SKP dan SP yang ada di dalamnya, disertai dengan pusat SKP, perkiraan alinemen jalan poros dan jalan penghubung serta daya tampung setiap SKP yang berkaitan dengan pola usaha yang ada di dalamnya.
Perencanaan Tahap III
Perencanaan tahap III meliputi dua bagian, yaitu Tahap IIIA yang dikenal dengan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Tahap IIIB, yang dikenal dengan Studi Perwujudan Manfaat Ruang. Perencanaan tahap IIIA dilakukan sebelum kegiatan pembukaan lahan, sedangkan perencanaan tahap IIIB dilakukan setelah lahan dibuka. Keluaran dari perencanaan tahap IIIA adalah informasi umum (mengenai pencapaian lokasi, iklim dan kondisi sosial ekonomi), kelayakan fisik, rencana pengembangan pemukiman dan informasi kelayakan usaha transmigran. Sedangkan keluaran perencanaan tahap IIIB adalah peta detail tata ruang Satuan Pemukiman Transmigrasi dengan skala peta 1 : 5.000.
Peta detail tata ruang SPT mencakup: batas masing-masing blok lahan untuk Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha I (LU I) beserta penomoran untuk pemilikannya dan lokasi fasilitas umum serta alinemen jalan, rencana lahan
usaha II (LU II) yang digambarkan dalam bentuk blok dan mencantumkan luas serta daya tampung, dan kelengkapan lain pada peta sesuai standar kartografi yang telah ditentukan. Gambar detail ini dibuat berdasarkan peta As Built Drawing (ABD) pembukaan lahan dan penyiapan lahan, jalan poros/penghubung dan jalan desa, serta kapling-kapling yang terikat dalam satu sistem pengukuran yang lebih luas, sehingga tidak terlepas dari konteks perencanaan tahap IIIA.
Pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan melalui tahapan perencanaan pembangunan permukiman, tahapan konstruksi pembangunan permukiman, dan tahapan pembinaan permukiman. Dalam tahapan konstruksi pembangunan permukiman secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam berbagai bidang kegiatan seperti berikut:
1. Bidang penyiapan permukiman berupa kegiatan pembukaan lahan dan penyiapan lahan pekarangan dan lahan usaha, pembangunan prasarana/ infrastruktur permukiman, penyiapan bangunan perumahan dan fasilitas umum serta uji coba pertanaman (test farm). Kegiatan pembukaan lahan dan penyiapan lahan meliputi kegiatan pengolahan lahan dengan pembajakan dan penggaruan di Lahan Pekarangan (LP) seluas 0,25 ha/ KK dengan kondisi siap tanam dengan maksud pada saat transmigran datang sudah dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk usahatani. Sedangkan Lahan Usaha I (LU-I) seluas 0,75 ha/ KK, penyiapan lahannya sampai dengan kondisi siap olah dan Lahan Usaha II (LU-II) seluas 1 ha/ KK tidak dibuka. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tapak rumah di lahan pekarangan dengan maksud diatasnya akan dibangun rumah transmigran ukuran 36 m2 dengan konstruksi dinding dari papan kayu dan atap dari asbes gelombang atau seng gelombang. Juga dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdiri dari balai desa, rumah dan kantor petugas, tempat ibadah, puskesmas pembantu, sekolah dan gudang. Pembangunan prasarana/ infrastruktur permukiman yang terdiri dari pembangunan jalan penghubung, jalan poros dan jalan desa beserta jembatan dan gorong-gorong.
2. Bidang pengerahan transmigran antara lain berupa penyiapan sarana transit, angkutan, kesehatan, peralatan dan logistik, penempatan lokasi sasaran dan penyiapan bahan penyuluhan, penyuluhan umum dan kampanye, penyuluhan spesifik dan selektif, pendaftaran dan seleksi serta pelatihan dasar umum bagi para transmigran.
3. Bidang penempatan transmigran antara lain berupa kegiatan pembuatan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP), penampungan di transito, pemberangkatan dengan moda angkutan darat, laut, dan/ atau udara, penampungan sementara di unit pemukiman transmigrasi (UPT), serta penempatan dan pembagian lahan pekarangan yang di atasnya telah dibangun rumah transmigran dan Lahan Usaha I (LU-I) dan Lahan Usaha II (LU-II).
4. Bidang pembinaan, tahapan ini dilaksanakan mulai tahun pertama penempatan transmigran yang juga merupakan tahun pertama pemberdayaan masyarakat transmigran dan pemberdayaan lingkungan permukiman yang dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah penempatan (T+1 sampai dengan T+5). Dalam kenyataannya tahap operasi ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat transmigran dan penduduk lokal di sekitarnya, yang utamanya dilakukan melalui upaya membantu mereka mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penghasilan. Untuk itu ditempuh upaya 3 strategi inti (Yudohusodo 1998), yaitu; (a) Pembangunan manusia berupa: penyediaan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan, (b) Kebutuhan untuk hidup berupa pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan sosial, dan (c) Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, antara lain berupa prasarana kegiatan ekonomi dan prasarana kegiatan sosial.
2.4 Pengembangan Pertanian Lahan Kering
Pada tahun 1970-an mulai banyak digunakan oleh beberapa kalangan istilah lahan, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam makna yang ekivalen dengan makna land. Dalam hubungan ini lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di juga hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang, seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinisasi (FAO, 1976). Dengan demikian maka lahan mengandung makna yang lebih luas dari tanah atau topografi. Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan (Sitorus, 2003a). Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang dan tempat.
Lahan kering dapat didefinisikan sebagai hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam waktu setahun atau sepanjang waktu (Hidayat dan Mulyani 2005). Berdasarkan penggunaan lahan untuk pertanian, lahan kering secara umum dikelompokkan menjadi pekarangan, tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, lahan untuk kayu-kayuan, perkebunan, dengan total luas 53.963.705 ha atau sekitar 28,67 % dari total luas Indonesia, luas tersebut belum termasuk Maluku dan Papua karena tidak tersedia data (BPS, 2003). Dari luasan lahan kering tersebut, seluas 16,3 juta ha digunakan untuk perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan negara dan swasta.
Lahan kering merupakan salah satu ciri lahan, yang apabila diusahakan untuk pertanian, pengairannya hanya mengandalkan dari curah hujan untuk kelembaban tanahnya. Kondisi lahan kering mengalami periode masa kering dapat berupa kering musiman atau kering dalam satu waktu periode tertentu saja dan selanjutnya mengalami periode hujan atau basah (Barrow, 1991). Lahan kering disamping mengandalkan curah hujan untuk kelembaban tanah, juga dicirikan dengan terbatasnya kandungan unsur hara (miskin unsur hara). Ciri pertanian lahan kering diantaranya adalah jenis tanaman yang diusahakan tidak memerlukan air yang banyak, pengairannya dari air hujan dan kebutuhan airnya tergantung pada kapasitas lapang (Knapp, 1979).
Ketersediaan air di lahan kering merupakan masalah utama untuk pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Pada musim kemarau, tanaman kekurangan air, sedangkan pada musim hujan terjadi aliran permukaan dan erosi yang besar karena sedikitnya air yang dapat diinfiltrasikan ke dalam tanah. Gejala ini berkaitan dengan buruknya sifat fisika tanah, seperti tekstur kasar pada lapisan atas dan padatnya lapisan bawah. Rendahnya bahan organik pada lahan kering, menyebabkan tanah tidak gembur sehingga perakaran terganggu. Selain itu pada lapisan padat gerakan air ke dalam tanah menjadi lambat seperti terlihat dari rendahnya laju permeabilitas tanah. Dengan demikian tanah akan cepat jenuh sehingga aliran permukaan menjadi besar (Sitorus, 2002)
Berdasarkan ketinggian tempat (elevasi) (Hidayat dan Mulyani, 2005), lahan kering dibedakan menjadi dataran rendah (elevasi < 700 m dpl) dan dataran tinggi (elevasi > 700 m dpl). Di Kalimantan lahan kering dataran rendah dan dataran tinggi terluas terdapat di Kaltim, Kalbar dan Kalteng. Lahan kering di dataran rendah pada umumnya telah banyak digunakan terutama untuk
perkebunan (24,7 juta ha), Hutan Tanaman Industri/ hutan produksi terbatas (27,8 juta ha), tegalan/ ladang/ huma (13,3 juta ha), lahan yang tidak diusahakan (10,6 juta ha) (BPS, 2003). Pola pemanfaatan lahan kering dataran rendah dan dataran tinggi umumnya berbeda dalam jenis komoditas sesuai dengan persyaratan tumbuh masing-masing dan kondisi iklim. Jenis tanaman pangan dan perkebunan di dataran tinggi lebih terbatas, sebaliknya tanaman hortikultura lebih dominan.
Karakteristik lahan kering di Indonesia mempunyai sifat sebagai tanah masam (pH < 5,0) dan sekitar 69 % dari luasan lahan kering bersifat masam (Hidayat dan Mulyani 2005). Menurut Dipokusumo et al. (2004) disamping bersifat masam, lahan kering di Indonesia juga di miskin akan unsur hara (tanah marginal), oleh karena itu pemanfaatan lahan kering untuk pertanian harus di kelola dengan baik secara terintegrasi antar pihak-pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal secara berkelanjutan. Pengelolaan lahan kering utamanya adalah pengelolaan hara tanaman.
Untuk mengembangkan usahatani pada lahan kering yang cenderung bersifat masam di Indonesia akan dihadapkan pada berbagai kendala. Menurut Hakim et al. (1994) kendala utama dalam pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan pertanian adalah rendahnya kandungan bahan organik tanah dengan daya pegang air yang rendah, sehingga air tanah tidak tersedia bagi tanaman. Adanya berbagai faktor pembatas pertumbuhan seperti rendahnya kesuburan tanah dan tidak tersedianya air sepanjang tahun merupakan kendala utama rendahnya produktivitas lahan. Kebutuhan air pada lahan kering umumnya setara dengan laju evapotranspirasi potensial (pada kondisi air tanah tersedia), yang nilainya di Indonesia berkisar 2,7 - 7,0 mm/ hari.
Secara praktis berbagai pakar menetapkan kebutuhan air pada lahan kering adalah 75 - 100 mm/ bulan dengan asumsi bahwa laju evapotranspirasi hanya 2,5 - 3,0 mm/ hari (FAO, 1981). Kemudian oleh Oldeman et al. (1980), disetarakan dengan curah hujan 100 - 200 mm per bulan setelah mempertimbangkan peluang kejadian hujan dan tidak semua curah hujan efektif digunakan. Periode bulan-bulan yang mempunyai curah hujan lebih besar dari 100 mm per bulannya merupakan periode air tersedia bagi tanaman pangan lahan kering. Selain itu, suhu yang tinggi dan ketidak merataan curah hujan serta kerentanan tanah terhadap erosi telah menambah kompleksitas permasalahan. Untuk meningkatkan produktivitas lahan
kering masam, selain dengan pengapuran dan pemupukan juga dapat dilakukan dengan optimalisasi pola tanam, yang dapat mengurangi aliran permukaan/ erosi, dan evaporasi tanah oleh adanya penutupan tanaman dan sisa hasil panen yang dapat berfungsi sebagai mulsa dan menambah bahan organik tanah (Syam, 2003).
Dalam konteks pengembangan pertanian di lahan kering, maka Solahudin dan Ladamay (1997) mendefinisikan pertanian lahan kering sebagai suatu sistem pertanian yang dilaksanakan di atas lahan tanpa menggunakan irigasi, dimana kebutuhan air hanya bergantung pada curah hujan. Beberapa ciri biofisik pertanian lahan kering diantaranya tingkat kesuburan tanah yang rendah, pH tanah yang masam, kandungan bahan organik dan unsur hara terbatas, berada pada wilayah hulu (upland) dan topografi berlereng.
Ciri pengelolaan yang penting adalah pembukaan lahan biasanya hanya dilakukan dengan cara tebas bakar, pembersihan lahan dengan cara pembersihan dan pengangkutan sisa-sisa tanaman, kondisi tanah relatif terbuka sepanjang tahun, terbatasnya penggunaan pupuk dan bibit unggul serta belum diterapkan teknik-teknik konservasi. Perpaduan ciri biofisik dan cara-cara pengelolaan lahan kering tersebut mengakibatkan sistem pertanian lahan kering sangat peka terhadap kerusakan lingkungan.
Ciri utama lahan kering lainnya yang menonjol dalam sistem usahatani lahan kering adalah terbatasnya air, makin menurunnya produktivitas lahan, tingginya variabilitas kesuburan tanah dan jenis tanaman yang ditanam serta variabilitas kondisi sosial ekonomi dan budaya usahatani yang dilaksanakan sangat tergantung pada curah hujan (Semaoen et al., 1991). Dengan melihat ciri-ciri lahan kering yang diantaranya adalah bersifat masam dan tingkat kesuburan yang rendah, maka lahan kering dapat dikategorikan pada lahan marginal (Mastur, 2002).
Di Indonesia lahan marginal dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu: (1) lahan dengan tanah mineral masam dan kesuburan rendah atau biasa dikenal sebagai lahan bertanah masam, (2) lahan basah yang biasanya dapat memiliki satu atau beberapa tipe tanah antara lain adalah tanah gambut, tanah aluvial berpirit (sulfat masam), tanah salin, tanah-tanah hidromorfik (gley), dan (3) lahan pada wilayah beriklim kering. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka lahan kering pada umumnya dapat dikategorikan sebagai lahan yang bersifat masam dan marginal.
Di Indonesia lahan kering terdapat di daerah berikllim basah, seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sebagian Sulawesi dan di daerah beriklim kering seperti di sebagian Sulawesi, NTB dan NTT. Curah hujan yang tinggi di pulau-pulau yang terdapat di Kawasan Barat Indonesia menyebabkan terjadinya erosi yang intensif yang akan mempercepat terjadinya kerusakan tanah. Sebaliknya, di Kawasan Timur Indonesia, kondisi curah hujan yang terbatas akan membatasi pertumbuhan tanaman, bahkan seringkali menyebabkan kegagalan panen. Di samping itu, kondisi curah hujan yang terkonsentrasi pada suatu waktu dan kondisi tanah yang peka erosi menyebabkan erosi yang sangat besar pada musim penghujan dan kekeringan yang parah pada musim kemarau di wilayah bagian timur Indonesia (Nugroho, 2002).
Pengembangan usahatani di lahan kering di Indonesia saat ini ternyata telah diikuti oleh semakin besarnya luas kerusakan lahan yang ada. Kondisi demikian disebabkan belum diterapkannya teknik-teknik konservasi tanah secara tepat dan benar, khususnya lahan kering yang diusahakan di daerah hulu dengan kemiringan lereng yang cukup besar. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas lahan dan penanggulangan kerusakan lahan yang terjadi pada pertanian lahan kering merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan kegiatan pertanian lahan kering dimasa mendatang.
Pembangunan pertanian lahan kering di masa mendatang perlu diarahkan untuk melestarikan kondisi biofisik lahan, meningkatkan produktifitas dan mampu memberikan pendapatan yang cukup tinggi serta berkelanjutan bagi petani. Oleh karena itu pengembangan pertanian tersebut selain berorientasi pada agribisnis juga harus dibarengi dengan penggunaan teknologi yang berfungsi untuk mengoptimalkan produktifitas lahan dan meminimalkan tingkat kerusakan lahan.
Sistem pertanian lahan kering di masa mendatang perlu dikembangkan dengan sistem pertanian konservasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) sistem usahatani yang dilakukan pada lahan tersebut harmoni secara ekologi, yang artinya sistem produksi dilakukan dengan tidak menyebabkan kerusakan secara ekologi atau tidak merusak/mengganggu keseimbangan ekosistem, (2) produksi yang dihasilkan cukup tinggi dengan menggunakan teknologi tepat guna, (3) produksi yang dihasilkan memberikan pendapatan dan kesejahteraan secara ekonomi, (4) sistem produksi yang dilakukan dapat diterima dan dilakukan oleh petani dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia sesuai dengan
perkembangan teknologi, (5) kerusakan akibat sistem produksi yang dilakukan dapat diminimumkan, dan kerusakan tersebut juga dapat diimbangi oleh proses pemulihan sumberdaya lahan secara alami, sehingga tingkat produksi yang tinggi, pendapatan dan kesejahteraan petani dapat dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan (Nugroho, 2002).
Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas pertanian serta meminimumkan terjadinya kerusakan lahan, kegiatan usahatani yang dilakukan harus direncanakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi suatu wilayah. Menurut Dudung (1991) sistem budidaya pertanian di lahan kering dapat dilakukan dengan sistem talun, tegal pekarangan, budidaya lorong, agroforestri, usaha tani konservasi terpadu dan penanaman tanaman pionir.
Sistem talun, yaitu suatu cara bercocok tanam dari berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman yang paling rendah, merambat, pohon yang tingginya sedang sampai pohon yang mahkotanya tinggi, yang diatur sedemikian rupa sehingga seluruh permukaan tanah tertutup rapat dan hasilnya dapat dipanen secara terus menerus. Sistem tegal pekarangan, yaitu suatu pengelolaan lahan dengan budidaya tanaman untuk mencukupi kebutuhan pangan dengan menanam tanaman semusim tanpa meninggalkan tanaman tahunan/ keras, yang dapat memberikan hasil tanaman tahunan yang ditanam sepanjang guludan dan disebagian bidang tanah. Sistem budidaya lorong (alley cropping), yaitu sistem pertanaman dalam lorong yang dibatasi oleh tanaman pagar/ tegakan berupa tanaman pupuk hijau yang ditanam menurut garis kontur. Tanaman dalam lorong dapat berupa tanaman pangan, hortikultur maupun tanaman perkebunan.
Sistem agroforestri, yaitu sistem pengelolaan lahan secara optimal dengan cara menanam kayu-kayuan yang dikombinasikan dengan tanaman pangan (tanaman semusim dan tahunan) dengan atau tanpa ternak. Tanaman ditanam secara bersama-sama atau berurutan pada unit-unit lahan yang sama akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada jika hanya ditanam tanaman pertanian saja atau tanaman kehutanan saja. Usahatani konservasi terpadu, yaitu suatu cara pengelolaan lahan usahatani yang menggunakan kombinasi tanaman pangan dengan tanaman tahunan (tanaman buah-buahan) agar permukaan tanah tertutup terus sepanjang tahun. Penanaman tanaman pioner, yaitu suatu cara untuk memulihkan/merehabilitasi tanah dengan
menggunakan tanaman pioner pada lahan kering yang keadaan tanahnya tergolong kritis dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk usaha pertanian yang intensif.
Melihat kondisi lahan kering yang mempunyai karakteristik sebagai lahan marjinal dan bersifat masam serta cenderung mudah terdegradasi apabila pengelolaannya kurang tepat, maka pemanfaatannya untuk usaha-usaha pertanian di kawasan transmigrasi lahan kering diperlukan suatu strategi. Menurut Mastur (2002), strategi yang dipilih dalam pemanfaatan lahan kering marjinal yang ideal, haruslah mempertimbangkan sumberdaya lokal terutama kondisi sosial, budaya dan ekonomi petani, ketersediaan teknologi, ketersediaan dana, serta akses dan peluang pasar. Strategi-strategi pemanfaatan lahan-lahan marjinal tersebut diantaranya adalah untuk berbagai komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai berikut:
1. Komoditas pertanian, padi, palawija dan sayuran merupakan kebutuhan pokok masyarakat transmigran. Ketiga komoditas ini sangat berarti sebagai sumber pangan pokok. Lahan-lahan marjinal bertanah gambut, sulfat masam dan berdrainase buruk, sangat cocok untuk padi. Pengelolaan tanah gambut dan sulfat masam untuk tanaman padi relatif beresiko kecil terhadap kerusakan lingkungan, karena adaptasi tanaman padi yang sangat baik terhadap lingkungan basah (tergenang). Pada tanah bermasam tadah hujan dan beriklim kering, padi yang ditanam adalah jenis padi gogo.
2. Komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan lada sangat sesuai pada lahan marjinal berlahan masam. Kelapa, kelapa sawit dan rami merupakan tanaman perkebunan yang cocok pada beberapa jenis tanah gambut. Dibandingkan dengan tanaman pangan, seharusnya komoditas-komoditas perkebunan perlu dikembangkan di lokasi-lokasi transmigrasi khususnya di lahan kering, karena secara agronomis tidak memerlukan teknologi yang rumit. Sedangkan pengembangan tanaman pangan pada tanah kering marjinal menghasilkan produktifitas yang rendah jika tanpa diberi input, seperti kapur dan pupuk dan ini harganya cukup mahal.
3. Komoditas kehutanan, mempertahankan lahan-lahan marjinal yang secara alamiah bervegetasi hutan alam primer merupakan tindakan yang sangat baik bagi lingkungan. Tetapi pada kenyataannya kebutuhan ekonomi masyarakat dan pemerintah lebih dominan untuk mendorong penebangan hutan untuk dimanfaatkan kayunya. Oleh karena itu pemanfaatan lahan