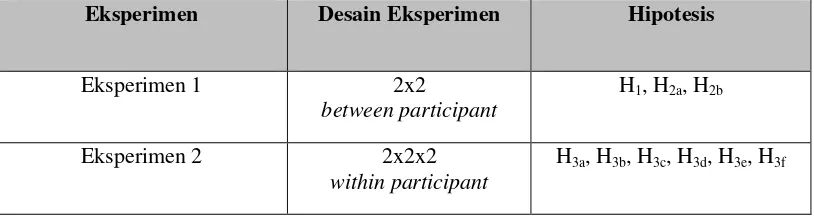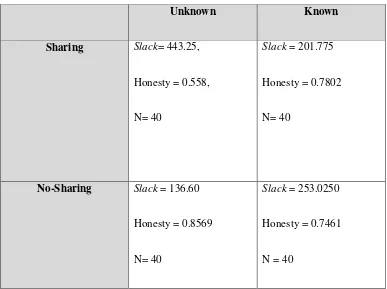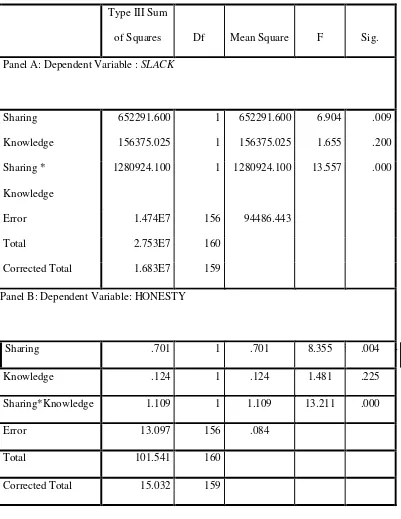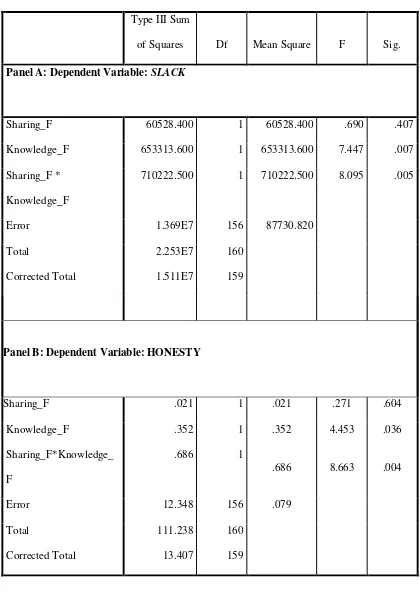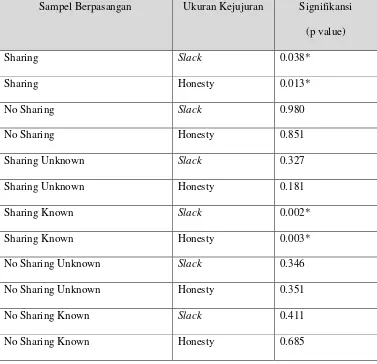1 SHARED FINANCIAL INTEREST, FAIRNESS, DAN KEJUJURAN DALAM
PELAPORAN ANGGARAN
Dini Rosdini
Universitas Padjadjaran
ABSTRACT
This study uses two experiments to investigate the honesty of manager’s budget reports when the financial benefit resulting from budgetary slack is shared by the manager and other non-reporting employees and when managers consider the fairness of budget participation. Drawing on moral disengagemnet theory, I predict that the shared financial interest in slack creation makes misreporting more self-justifiable to the manager and, therefore, leads to lower honesty. Consistent with my prediction, the result of first experiment show that managers report less honestly when the benefit of slack is shared than when it is not shared, regardless of whether others are aware of the misreporting.
The second experiment investigates whether the fairness concern will affect the honesty of manager’s budget reports in all condition as in first experiment. The result of second experiment confirming that fairness concern effects the honesty of manager’s budget reprots when the financial benefit resulting from budgetary slack is shared and when others are aware of the misreporting.
Keywords: shared financial interest, fairness, honesty, budget reporting
1. Pendahuluan
Anggaran memiliki peran yang penting dalam organisasi untuk perencanaan,
mengkoordinasikan aktivitas, mengalokasikan sumber daya dan menyediakan insentif
yang tepat (Covaleski et al, 2003). Biasanya, manajer level bawah memiliki informasi
superior mengenai kondisi sub unit atau divisi, misalnya informasi mengenai biaya dan
kapabilitas produksi. Terkait dengan adanya asimetri informasi ini, manajemen yang
lebih tinggi dalam suatu organisasi seringkali mengandalkan manajer sub-unit untuk
mengkomunikasikan informasi tersebut selama proses penganggaran. Informasi tersebut
2 (Antle dan Fellingham, 1990) dan berguna bagi perancangan insentif kinerja berbasis
anggaran (Shields dan Shields, 1998). Manajer sub-unit seringkali menyampaikan
anggaran yang mengandung slack , yaitu underestimation yang disengaja atas pendapatan
dan kapabilitas produksi dan atau overestimation atas biaya dan sumber daya yang
diperlukan menyelesaikan tugas yang dianggarkan (Dunk dan Nouri, 1998).
Penelitian ini menginvestigasi bagaimana shared financial interest dan fairness
concern dalam slack anggaran mempengaruhi kejujuran dalam pelaporan anggaran.
Secara khusus, penelitian ini menginvestigasi bagaimana pembagian manfaat dalam
bentuk uang atas slack anggaran antara manajer sub-unit dengan karyawan lain dan juga
bagaimana situasi yang menimbulkan fairness concern bagi manajer sub-unit dapat
mempengaruhi kejujuran dalam pelaporan anggaran kepada kantor pusat. Terminologi
pelaporan anggaran dalam penelitian ini adalah pengajuan anggaran dari sub-unit kepada
kantor pusat untuk mendanai biaya produksi yang dilakukan di sub-unit, dimana dalam
pengajuan anggaran ini, manajer dapat menciptakan slack.
Keuntungan dari slack dapat diperoleh dengan cara mengajukan anggaran secara
tidak jujur melalui dua cara. Pertama, biaya dibuat melebihi nilai yang seharusnya
(overstated) sehingga manajer sub-unit menerima excess resources (Merchant, 1985), dan
manfaat sub-unit akibat dari excess resources ini dapat dikonsumsi sebagai perquisite dan
atau sebagai leisure. Cara kedua adalah membuat target yang menjadi ukuran kinerja
sub-unit lebih rendah dari seharusnya (understated) dan manfaat sub-sub-unit akibat dari
rendahnya target ini dapat menyebabkan tingginya penghasilan yang berbasis kinerja dan
atau sebagai leisure.
Variasi di antara sistem pengendalian organisasi termasuk kebijakan pembayaran
insentif, cenderung mempengaruhi tingkat pembagian manfaat atas slack antara manajer
3 pendelegasian hak untuk memutuskan bervariasi antar organisasi, yang berdampak
kemampuan manajer sub-unit untuk menyetujui beban-beban yang bisa dikonsumsi
sebagai perquisite bagi karyawan lain pun menjadi beragam. Organisasi akhir-akhir ini
banyak menggunakan rencana pembayaran insentif berbasis grup yang merupakan
rencana pembayaran insentif dimana jumlah kompensasi merupakan fungsi dari kinerja
yang dicapai oleh suatu kelompok karyawan (Hollensbe dan Guthrie, 2000). Fitur yang
membedakan rencana pembayaran insentif tersebut dibanding yang lain adalah setiap
anggota grup memiliki bagian atas manfaat yang timbul dari pencapaian grup tersebut
(Bohlander dan Snell, 2007), artinya ketika manajer sub-unit membuat target yang lebih
rendah (understate targets) maka manfaat dari rendahnya target tersebut akan dibagi
dengan karyawan-karyawan dalam sub-unit tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah shared financial
interest dalam penciptaan slack, kesadaran karyawan lain mengenai apakah manajer
melakukan misreporting atau tidak dan fairness concern mempengaruhi kejujuran
manajer dalam pengajuan anggaran. Pertanyaan penelitian ini penting bagi peneliti di
bidang management control dan juga bagi para praktisi karena penelitian ini memberikan
pandangan untuk memahami ketika manajer cenderung untuk memasukkan slack dalam
anggaran mereka, sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan sistem
pengendalian, misalnya pelaksanaan audit atas anggaran yang diajukan manajer sub-unit.
Penelitian ini juga penting karena mencoba mengidentifikasi ketika mekanisme
pengendalian yang berguna di suatu domain bisa jadi memberikan dampak negatif pada
domain yang berbeda. Khususnya, apabila rencana pembayaran insentif berbasis grup
ternyata mengurangi efektifitas penganggaran, maka dampak tersebut harus benar-benar
dicermati karena dapat mengubah rancangan optimal dari sistem pengendalian
manajemen secara keseluruhan. Artinya, manajemen perlu membobot biaya versus
4 yang paling efektif. Peneliti melaksanakan dua eksperimen untuk menjawab tujuan
penelitian ini.
Eksperimen pertama menguji perilaku manajer dalam mengajukan anggaran
ketika keuntungan dari slack yang diciptakan dibagi dengan karyawan lain. Dalam
eksperimen ini, partisipan berperan sebagai manajer divisi dan asisten manajer. Manajer
divisi menyusun laporan anggaran yang berisi permintaan atas sejumlah dana untuk
membiayai biaya produksi divisi, sedangkan peranan asisten manajer benar-benar pasif.
Penelitian ini menggunakan pengaturan hirarkis, dimana manajer memiliki otoritas penuh
untuk melakukan pelaporan anggaran yang berisi anggaran yang diajukan kepada kantor
pusat, dan asisten manajer tidak memiliki otorisasi sama sekali, hal ini bertujuan untuk
mengurangi efek perancu yang mungkin timbul dari suatu difusi tanggung jawab (Darley
dan Latane, 1968; Mynatt dan Sherman, 1975). Dua faktor yang dimanipulasi dalam
eksperimen pertama ini adalah: apakah keuntungan dari budgetary slack dibagi dengan
asisten (ya versus tidak) dan apakah asisten mengetahui adanya misreporting (ya versus
tidak). Konsisten dengan prediksi peneliti, manajer-partisipan mengajukan anggaran
dengan kejujuran yang lebih rendah ketika manfaat dari slack dibagi dengan asisten
dibandingkan dengan apabila keuntungan dari slack tidak dibagi. Namun, tidak sesuai
dengan prediksi, kesadaran asisten mengenai apakah manajer melakukan misreporting
atau tidak, ternyata tidak mempengaruhi kejujuran manajer dalam mengajukan anggaran.
Eksperimen kedua menguji perilaku manajer dalam mengajukan anggaran ketika
keuntungan atas slack yang diciptakan dibagi dengan karyawan lain dan ketika adanya
fairness concern bagi manajer. Eksperimen yang dilakukan sama dengan eksperimen
pertama, tetapi ditambahkan partisipan yang berperan sebagai manajer kantor pusat yang
menerima laporan pengajuan anggaran dan kemudian memberikan sejumlah dana sesuai
dengan yang diajukan oleh manajer sub-unit. Eksperimen kedua ini memberikan hasil
5 kejujuran manajer dalam mengajukan anggaran ternyata tidak dipengaruhi apakah
keuntungan dari budgetary slack dibagi dengan asisten atau tidak. Selain itu, bertolak
belakang dengan hasil eksperimen pertama, kejujuran manajer ternyata dipengaruhi oleh
kesadaran karyawan lain mengenai misreporting yang dilakukan manajer tersebut ketika
adanya fairness concern. Jadi, ketika terdapat faktor fairness concern yang
dipertimbangkan oleh manajer sub-unit ketika akan menciptakan slack, ternyata variabel
yang mempengaruhi perilaku manajer adalah variabel kesadaran karyawan lain mengenai
terjadinya misreporting, tanpa mempertimbangkan apakah slack tersebut dibagi atau tidak
dengan karyawan lain.
Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap riset dan praktik akuntansi
manajemen. Penelitian ini mengidentifikasikan bagaimana sistem pengendalian memiliki
eksternalitas positif dan negatif, misalnya rencana pemberian insentif berbasis grup
banyak digunakan dalam organisasi (DeMatteo, Eby dan Sundstrom, 1998; Fisher, Peffer
dan Sprinkle, 2003) dipercaya memiliki dampak positif terhadap hasil yang diciptakan
organisasi (Hollensbe dan Guthrie, 2000). Namun yang perlu dipertimbangkan adalah
apabila rencana pemberian insentif berbasis grup tersebut menurunkan efektivitas
penganggaran yang salah satunya disebabkan munculnya budgetary slack, dampak
tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis biaya-manfaat oleh manajemen sebagai
bagian dari usaha keras mereka dalam memaksimalkan efektivitas sistem pengendalian
manajemen.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari experimental study yang dilakukan
Church, Hannan, dan Kuang (2012). Kontribusi penelitian ini adalah mengisi gap pada
penelitian tersebut yang tidak memasukkan fairness concern dalam eksperimen mereka.
6 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
2.1. Kejujuran Manajer dalam Pelaporan Anggaran
Beberapa penelitian eksperimental telah menguji kejujuran manajer dalam
pelaporan anggaran, seperti Evans et al (2001), Hannan et al (2006), Krishnan, Marinich
dan Shields (2011), dan Newman (2011). Semua penelitian ini menguji kejujuran manajer
dalam pelaporan anggaran tanpa memasukkan faktor shared interest dalam misreporting
tersebut. Pada kondisi dasar, manajer yang memiliki informasi pribadi mengenai biaya
produksi sub-unit menyampaikan pengajuan anggaran kepada kantor pusat. Permohonan
anggaran yang diajukan manajer sub-unit tesebut disetujui dan manajer memperoleh dan
menyimpan manfaat dari slack yang diciptakan. Hasil penelitian Evans et al (2001)
menyatakan bahwa manajer seringkali tidak menaikkan anggaran yang diajukan pada
batas maksimal yang memungkinkan, karena manajer memiliki preferensi kejujuran.
Beberapa penelitian telah menemukan faktor-faktor yang meningkatkan
kejujuran, antara lain ethical concerns (Rankin et al, 2008); tekanan sosial untuk bersikap
jujur (Hannan et al, 2006), preferensi untuk memenuhi tujuan organisasi (Newman,
2011) dan pemenuhan kontrak psikologis (Khrishnan et al, 2011).
2.2. Shared Financial Interest
Bandura (1990, 1999, 2002) menjelaskan mengenai moral disengagement theory
yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa individu menggunakan standar moral yang
berterima umum untuk melakukan self-regulate lingkungan mereka, mereka biasanya
menahan diri dari bertindak melanggar standar moral karena tindakan seperti itu akan
menimbulkan biaya psikologis. Namun, perilaku yang melanggar standar moral tetap
mungkin terjadi karena individu dapat melepaskan diri dari perilaku tersebut. Secara
7 dan individu dapat menonaktifkannya dengan rasionalisasi perilaku mereka secara
ego-defensif (Aronso, 1995, 1999).
Bandura (1999) menyatakan bahwa individu-individu tidak terlibat dalam
tindakan kejahatan kecuali pada suatu kondisi dimana mereka menjustifikasi moralitas
dari tindakan mereka. Satu teknik penting yang seorang individu gunakan untuk
self-justify adalah meredefinisikan atau mereinterpretasikan suatu tindakan menjadi
permissible secara moral. Individu akan menjadikan tindakan mereka sebagai suatu
tindakan yang merepresentasikan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri.
(Ashford dan Anand, 2003).
Konteks dalam penelitian ini, apabila budgetary slack hanya menguntungkan
bagi manajer, maka misreporting dalam penganggaran hanya memiliki satu dampak,
yaitu melayani kepentingan sendiri, dimana secara moral merupakan tindakan negatif dan
tidak dapat dijustifikasi. Di sisi lain, apabila keuntungan dari budgetary slack dibagi
dengan karyawan lain, maka misreporting dalam penganggaran memiliki dampak
tambahan, yaitu melayani kepentingan orang lain. Karena membantu orang lain dianggap
positif dan diharapkan secara sosial (Brief dan Motowidlo, 1986), maka shared financial
interest ini berpotensi untuk memitigasi atau meng-offset efek negatif dari pengejaran
kepentingan sendiri. Sehingga, moral disengagement menyediakan suatu alat untuk
membingkai keputusan untuk melakukan misreporting sebagai salah satu usaha yang
melayani kepentingan umum, sehingga berkurang ke-tidaketis-annya, yang pada
gilirannya mengurangi perasaan bersalah (Bandura et al, 1996).
Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini
adalah:
H1: Kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran lebih rendah ketika slack dibagi
8 2.3. Kesadaran karyawan lain mengenai misreporting
Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa seorang individu
memperhatikan kesan orang lain terhadap dirinya yang akan menggiring perilaku
individu tersebut agar sesuai dengan kesan yang tercipta meskipun tidak ada konsekuensi
ekonomi. (Hannan et al, 2006; Leary, 1995; Schlenker, 1980).
Di dalam konteks penganggaran, manajer akan memperhatikan misreporting, jika
diketahui oleh stafnya, maka sub-ordinate nya akan memiliki kesan negatif tentang
dirinya. Dalam penelitian ini ingin juga dilihat bagaimana apabila misreporting yang
dilakukan oleh manajer diketahui oleh anak buahnya, namun anak buah tersebut
memperoleh bagian keuntungan dari misreporting tersebut. Ketika keuntungan dari
misreporting tidak dibagi dengan karyawan lain, manajer akan menyadari bahwa
pandangan orang lain mengenai misreporting adalah suatu tindakan yang egois dan
oportunis. Tindakan tersebut dipandang melanggar kejujuran dan kesan negatif dari
bawahan mereka. (Alexander dan Knight, 1971). Karena manajer memperhatikan apa
yang orang lain pikirkan mengenai dirinya, maka keinginan manajer untuk
memaksimalkan kepentingan pribadinya akan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk
memberikan kesan positif, sehingga manajer akan melaporkan anggaran lebih jujur ketika
orang lain mengetahui misreporting yang dilakukan manajer.
Sejalan dengan hasil penelitian (Marks dan Miller, 1987; Ross et al, 1977), maka
ketika keuntungan dari misreporting dibagi dengan karyawan lain, awareness dari
karyawan lain mengenai misreporting tidak akan berpengaruh terlalu besar pada perilaku
manajer, karena manajer merasa bahwa karyawan lain akan meng-excuse tindakan
misreporting yang dia lakukan, karena keuntungan dari tindakan tersebut dinikmati juga
oleh karyawan lain. Manajer akan beralasan bahwa dengan memasukkan slack dalam
9 Sehingga, kesadaran karyawan lain mengenai misreporting yang dilakukan manajer
cenderung akan mempengaruhi kejujuran manajer dalam pelaporan anggaran ketika
keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam
penelitian ini adalah:
H2a: Jika keuntungan dari slack tidak dibagi dengan karyawan lain, kejujuran manajer
dalam melaporkan anggaran lebih tinggi ketika karyawan lain tersebut
mengetahui perilaku manajer dalam melaporkan anggaran daripada ketika mereka
tidak mengetahuinya.
H2b: Jika keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain, kejujuran manajer tidak
terpengaruh oleh kesadaran karyawan lain mengenai perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran.
2.4. Fairness Concern
Organizational justice (fairness) theory menyatakan bahwa terdapat dua bentuk
fairness, yaitu: distributive fairness dan procedural fairness (Lau dan Tan, 2005).
Variabel atas pentingnya pemahaman proses dimana partisipasi anggaran mempengaruhi
kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah procedural fairness. Teori distributive
fairness menekankan bahwa terkait dengan alokasi keterlibatan pengambilan keputusan,
individu-individu akan memperhatikan dan sekaligus juga dipengaruhi oleh hasil yang
adil. Artinya, selama hasil yang dicapai adalah fair (equitable), maka individu-individu
tersebut akan puas (Lissak et al, 1983; Alexander dan Ruderman, 1987). Sedangkan teori
procedural fairness menekankan bahwa selama prosedur dan proses bersifat fair, maka
10 Apabila manajer sub-unit dalam melakukan pengajuan anggaran memperhatikan
aspek fairness, maka disinyalir dapat mempengaruhi kejujuran mereka, baik dalam
kondisi ketika keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain atau tidak, maupun
dalam kondisi karyawan lain mengetahui misreporting yang dilakukan oleh manajer atau
tidak. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini
adalah:
H3a: Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggarannya ketika keuntungan dari slack dibagikan kepada
karyawan lain dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern.
H3b: Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggarannya ketika keuntungan dari slack tidak dibagikan kepada
karyawan lain dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern.
H3c: Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack tidak dibagi dengan karyawan
lain dan karyawan lain tersebut mengetahui perilaku manajer dalam melaporkan
anggaran dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern.
H3d: Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain
dan karyawan lain tersebut mengetahui perilaku manajer dalam melaporkan
anggaran dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern.
H3e: Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain
dan karyawan lain tersebut tidak mengetahui perilaku manajer dalam melaporkan
11 H3f: Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack tidak dibagi dengan karyawan
lain dan karyawan lain tersebut tidak mengetahui perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini melakukan dua eksperimen untuk pengujian hipotesis. Eksperimen
pertama adalah untuk menginvestigasi kejujuran manajer divisi dalam pelaporan
anggaran yang dipengaruhi oleh shared financial interest dan kesadaran karyawan lain
mengenai misreporting yang dilakukan manajer. Sedangkan eksperimen kedua adalah
untuk menginvestigasi kejujuran manajer divisi dalam pelaporan anggaran yang
dipengaruhi oleh shared financial interest, kesadaran karyawan lain mengenai
misreporting yang dilakukan manajer, dan fairness concern.
Desain eksperimen pertama adalah 2 x 2 between-participant. Sedangkan desain
eksperimen kedua adalah 2x2x2 within participant. Dalam eksperimen ini digunakan
budget reporting setting sebagai “trust contract” seperti dalam Evans et al (2001).
Kelebihan dari tipe kontrak ini adalah dapat membiarkan peneliti untuk menginvestigasi
pengaruh faktor-faktor perilaku ketika partisipan memiliki insentif ekonomi yang kuat
untuk bertindak oportunis (Church et al, 2012).
Untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan eksperimen yang
dilakukan dengan hipotesis yang akan diuji, dapat dilihat pada matriks yang disajikan
12 Tabel 1
Matriks Hubungan antara Eksperimen dan Hipotesis
Eksperimen Desain Eksperimen Hipotesis
Eksperimen 1 2x2
between participant
H1, H2a, H2b
Eksperimen 2 2x2x2
within participant
H3a, H3b, H3c, H3d, H3e, H3f
3.1. Pengaturan dan Desain Eksperimen
Partisipan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa Magister Akuntansi sebanyak
32 orang dan mahasiswa S1 Akuntansi sebanyak 32 orang, sehingga total partisipan
yang berperan dalam eksperimen adalah sebanyak 64 orang.
Manajer - partisipan dan Asisten Manajer - partisipan dibagi menjadi 4 (empat)
kelompok dengan jumlah yang sama. Pembagian kelompok ini dilakukan secara random,
dengan cara mengundi kode dan nomor identitas masing-masing partisipan.
Alat eksperimen yang digunakan adalah:
1. Kode dan angka identitas partisipan
2. Soal pre-test untuk menguji sejauh mana pemahaman partisipan mengenai
peranan mereka dalam eksperimen ini dan pemahaman mengenai pelaporan
anggaran.
3. Cost Sheet, berisi nilai actual cost (diisi oleh eksperimenter) dan nilai budget cost
yang harus diisi manajer-partisipan yang kemudian disampaikan pada kantor
pusat. Selisih antara budget cost yang diajukan dengan actual cost merupakan
13 4. Kertas berisi kasus yang dibacakan kepada partisipan di masing-masing
kelompok / kelas.
5. Uang kertas dengan mata uang “Money”.
6. Honor dan souvenir bagi partisipan.
Kasus yang dibacakan kepada partisipan pada awal eksperimen merupakan
asumsi kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan, khususnya suatu divisi pada
perusahaan. Divisi tersebut diasumsikan hanya terdiri dari manajer divisi dan asisten.
Manajer menyampaikan laporan anggaran kepada kantor pusat untuk meminta sejumlah
dana untuk membiayai biaya produksi divisi tersebut. Manajer mengetahui dengan pasti
biaya produksi aktual sebelum menyampaikan laporan anggaran kepada kantor pusat.
Kantor pusat hanya mengetahui distribusi dari biaya produksi dan akan menyediakan
dana sejumlah anggaran yang diminta oleh manajer divisi sepanjang tidak melebihi batas
anggaran yang ditetapkan, yaitu antara 4000 Money sampai dengan 6000 Money. Apabila
terjadi perbedaan antara dana yang diberikan oleh kantor pusat dengan biaya aktual, maka
slack tersebut menjadi milik divisi dan kantor pusat tidak mengetahui jumlah biaya aktual
dari aktivitas produksi, sehingga tidak mengetahui bila terdapat slack.
Setelah dibagi kelompok secara random, maka partisipan ditempatkan pada ruang
kelas untuk setiap kelompok yang terdiri dari 8 manajer-partisipan dan 8 asisten manajer-
partisipan. Pada masing-masing kelas, case story dan penjelasan mengenai peranan
mereka sebagai partisipan dibagikan, dan dibacakan oleh experimenter serta diberikan
penjelasan mendetail mengenai penghasilan mereka sebagai manajer dan asisten manajer
14 3.2. Eksperimen Pertama: Shared Financial Interest, Kesadaran Karyawan Lain Mengenai Misreproting, dan Kejujuran Manajer dalam Pelaporan Anggaran
Para partisipan dijelaskan bahwa eksperimen yang dilakukan adalah sebanyak 5
periode pelaporan anggaran dengan jumlah estimated actual cost berbeda-beda pada tiap
periode. Actual cost untuk masing-masing manajer-partisipan di setiap periode dan di
setiap kelompok nilainya sama.
Kelompok partisipan dibagi menjadi:
1. No-sharing-Unknown untuk kondisi dimana keuntungan slack tidak dibagi
dengan asisten manajer dan asisten manajer tidak mengetahui bahwa manajer
memasukkan slack dalam anggaran yang diajukan.
2. No-sharing-Known untuk kondisi dimana keuntungan slack tidak dibagi dengan
asisten manajer dan asisten manajer mengetahui bahwa manajer memasukkan
slack dalam anggaran yang diajukan.
3. Sharing-Unknown untuk kondisi dimana keuntungan slack dibagi dengan asisten
manajer dan asisten manajer tidak mengetahui bahwa manajer memasukkan slack
dalam anggaran yang diajukan.
4. Sharing-Known untuk kondisi dimana keuntungan slack dibagi dengan asisten
manajer dan asisten manajer mengetahui bahwa manajer memasukkan slack
dalam anggaran yang diajukan.
Setelah instruksi dibacakan, partisipan mengisi pre-test yang bertujuan untuk
meyakinkan eksperimenter bahwa partisipan sepenuhnya memahami eksperimen yang
akan dilakukan. Selama proses eksperimen, di masing-masing ruang kelas,
manajer-partisipan dan asisten manajer-manajer-partisipan duduk terpisah. Setelah 5 periode diselesaikan,
cost sheet disusun berdasarkan identifikasi kondisi kasus. Kemudian, partisipan mengisi
15 3.2.1. Kondisi Sharing vs No-sharing (Shared Financial Interest)
Berikut ini adalah langkah-langkah dan asumsi dalam eksperimen pertama untuk
kondisi sharing dan no-sharing:
Pada setiap awal periode, setiap manajer diberi cost sheet. Bagian atas dari sheet
tersebut terdapat biaya produksi aktual untuk satu periode.
Manajer memasukkan kode identifikasi masing-masing untuk masing-masing
periode, dan mengisi nilai budgeted cost yang akan disampaikan pada kantor
pusat di bagian bawah cost sheet, partisipan diberi penjelasan bahwa budgeted
cost yang diajukan kepada kantor pusat akan langsung disetujui dan diberikan
uang sesuai dengan yang diajukan selama dalam batas pagu antara 4000 Money
sampai dengan 6000 Money. Kemudian eksperimenter memberikan kode
identifikasi asisten manajer secara random di setiap cost sheet.
Untuk kondisi No-sharing, apabila terdapat slack pada cost sheet, maka slack
tersebut tidak dibagi kepada asisten manajer.
Untuk kondisi Sharing, apabila terdapat slack pada cost sheet, maka slack
tersebut dibagi rata kepada asisten manajer.
Untuk kondisi No-sharing, gaji manajer sebesar 1000 Money, gaji asisten
manajer sebesar 800 Money, conversion rate adalah 120 Money = $1
Untuk kondisi Sharing, gaji manajer sebesar 500 Money, gaji asisten manajer
sebesar 400 Money, conversion rate adalah 60 Money = $1
Karena penelitian ini menginvestigasi perilaku para partisipan yang berperan
sebagai manajer divisi dalam proses pelaporan anggaran, maka sangat penting untuk
16 no-sharing dan sharing. Peneliti telah memastikan ekuivalensi ekonomi antar dua kondisi
tersebut dengan cara mengatur secara sistematis gaji dasar manajer divisi dalam mata
uang Money dan conversion rate dari mata uang Money terhadap dollar. Untuk kedua
kondisi No-sharing dan Sharing, gaji yang diperoleh manajer adalah sebesar $8.33
(1000/120 untuk kondisi No-sharing dan 500/60 untuk kondisi Sharing) dan manajer
memperoleh $0.83 untuk setiap 100 Money slack yang diciptakan (100/120 untuk kondisi
No-Sharing dan (100x ½)/ 60 untuk kondisi Sharing).
3.2.2. Kondisi Known vs Unknown (Kesadaran Karyawan lain atas Misreporting)
Berikut ini adalah langkah-langkah dan asumsi dalam eksperimen pertama untuk
kondisi known dan unknown:
Pada setiap awal periode, setiap manajer diberi cost sheet. Bagian atas dari sheet
tersebut terdapat biaya produksi aktual untuk satu periode.
Untuk kondisi Unknown:
Manajer memasukkan kode identifikasi masing-masing untuk masing-masing
periode, dan mengisi nilai budgeted cost yang akan disampaikan pada kantor
pusat di bagian bawah cost sheet, lalu eksperimenter memberikan kode
identifikasi asisten manajer secara random di setiap cost sheet (asisten manajer
tidak melihat cost sheet yang diisi oleh manajer).
Untuk kondisi Known:
Manajer memasukkan kode identifikasi masing-masing untuk masing-masing
periode, dan mengisi nilai budgeted cost yang akan disampaikan pada kantor
pusat di bagian bawah cost sheet, lalu eksperimenter membagikan cost sheet yang
17 manajer mereview cost sheet yang mereka terima dan menuliskan kode
identifikasi mereka pada cost sheet.
3.3. Eksperimen Kedua: Shared Financial Interest, Kesadaran Karyawan Lain Mengenai Misreproting, Fairness Concern, dan Kejujuran Manajer dalam Pelaporan Anggaran
Dalam eksperimen kedua, semua langkah yang dilakukan sama dengan
eksperimen pertama untuk empat kondisi: No sharing-Unknown, No sharing-Known,
Sharing-Unknown, dan Sharing-Known. Namun, untuk memasukkan faktor fairness
concern yang dapat mempengaruhi kejujuran manajer dalam pelaporan anggaran, maka
dimunculkan sosok manajemen kantor pusat yaitu partisipan yang berperan sebagai
manajer kantor pusat.
Partisipan yang berperan sebagai manajer kantor pusat ini bertugas untuk
menerima cost sheet yang diajukan oleh manajer divisi kemudian memberikan sejumlah
uang sesuai yang tertera dalam budgeted cost pada cost sheet. Peran manajer kantor pusat
yang dimunculkan dalam eksperimen kedua tidak menimbulkan perbedaan keputusan
pemberian dana dari kantor pusat kepada divisi, kunci dari munculnya peran manajer
kantor pusat ini adalah untuk menimbulkan faktor fairness concern yang diduga akan
mempengaruhi kejujuran manajer divisi dalam proses pelaporan anggaran.
4. Hasil
4.1. Pengukuran Kejujuran dan Statistik Deskriptif
Untuk memastikan komparabilitas antar manajer, peneliti menentukan actual cost
secara random untuk masing-masing periode selama lima periode dan menggunakan nilai
actual cost per periode ini untuk seluruh manajer-partisipan. Peneliti menggunakan dua
ukuran untuk menilai kejujuran manajer dalam pelaporan anggaran. Ukuran pertama
adalah “slack” yang dihitung dengan budgeted cost - dengan actual cost. Ukuran kedua
18 cost)]. Nilai yang diperoleh akan berkisar dari nol sampai dengan satu dan
merepresentasikan apakah manajer berperilaku jujur versus berperilaku mengejar
kepentingan pribadi. Jika manajer berperilaku jujur dengan mengajukan anggaran persis
sebesar estimated actual cost, maka nilai yang diperoleh adalah satu. Jika manajer
memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan mengajukan anggaran sebesar nilai
maksimum yaitu 6000 Money, maka nilai yang diperoleh adalah nol. Apabila nilai yang
diperoleh berkisar di antara nol dan satu, artinya manajer tersebut mengajukan anggaran
di atas actual cost tetapi di bawah nilai maksimum. Tabel 2 memperlihatkan rata-rata
slack dan honesty berdasarkan masing-masing kondisi.
[ Mohon letakkan Tabel 2 di sini]
Slack tertinggi dan honesty terendah adalah dalam kondisi Sharing-Unknown,
sedangkan slack terendah dan honesty tertinggi adalah pada kondisi No Sharing-
Unknown.
4.2. Pengujian Hipotesis Pertama
Untuk menguji hipotesis pertama, peneliti melakukan dua set two-way ANOVA
untuk hasil eskperiman pertama. Variabel dependen dalam pengujian tersebut adalah
Slack dan Honesty selama 5 periode. Tabel 3 menunjukkan hasil tes ANOVA untuk
eksperimen pertama.
[ Mohon letakkan Tabel 3 di sini]
Hipotesis pertama memprediksi kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran
lebih rendah ketika slack dibagi dengan karyawan lain daripada ketika slack tersebut
tidak dibagi. Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada Tabel 3, pada baris
Sharing. Panel A dan B menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari sharing
19 menciptakan lebih banyak slack ketika keuntungan slack tersebut dibagi dengan asisten
manajer (322.5125) dibandingkan dengan ketika keuntungan slack tidak dibagi dengan
asisten manajer (194.8125). Begitu pun dengan ukuran yang menggunakan “honesty”,
kejujuran manajer-partisipan secara signifikan (p= 0.004) lebih rendah ketika keuntungan
dari slack dibagi dengan asisten manajer (0.6691) dibandingkan dengan ketika
keuntungan dari slack tidak dibagi dengan asisten manajer (0.8015). Data slack dan
honesty untuk masing-masing kondisi terdapat dalam lampiran.
Kesimpulannya, hasil eksperimen pertama ini mendukung Hipotesis 1, yaitu
kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran lebih rendah ketika slack dibagi dengan
karyawan lain daripada ketika slack tersebut tidak dibagi.
4.3. Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua memprediksi: (a) Jika keuntungan dari slack tidak dibagi dengan
karyawan lain, kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran lebih tinggi ketika
karyawan lain tersebut mengetahui perilaku manajer dalam melaporkan anggaran
daripada ketika mereka tidak mengetahuinya, dan (b) Jika keuntungan dari slack dibagi
dengan karyawan lain, kejujuran manajer tidak terpengaruh oleh kesadaran karyawan lain
mengenai perilaku manajer dalam melaporkan anggaran. Hasil pengujian hipotesis kedua
dapat dilihat pada Tabel 4. Kesadaran karyawan lain mengenai adanya misreporting tidak
mempengaruhi kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran (p=0.200 untuk slack, dan
p=0.225 untuk honesty). Hasil ini tidak mendukung hipotesis (2a). Interaksi antara
sharing dan knowledge signifikan (p=0.000) mempengaruhi slack dan honesty. Hal ini
tidak mendukung hipotesis (2b).
20 Kesimpulannya, hasil eksperimen pertama tidak mendukung hipotesis kedua,
baik hipotesis (2a) maupun hipotesis (2b), hal ini dapat diinterpretasikan secara kasar
bahwa manajer-partisipan tidak peduli terhadap kesan anak buahnya mengenai kejujuran
mereka, dan cenderung tak acuh dengan image mengenai kejujuran mereka, hal ini perlu
dilakukan pengujian lanjutan, apakah karena dipengaruhi oleh faktor budaya atau faktor
lainnya.
4.4. Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga pada dasarnya memprediksi bahwa dengan adanya variabel
fairness concern, maka terjadi perbedaan kejujuran manajer divisi dalam melaporkan
anggaran untuk setiap kondisi (no unknown, no known,
sharing-unknown, sharing-known). Untuk menguji hipotesis ketiga, peneliti melakukan dua set
two-way ANOVA untuk hasil eskperiman kedua, kemudian untuk menguji signifikansi
perbedaan antara hasil pengujian two-way ANOVA antara eksperimen pertama dan
kedua dilakukan uji t sampel berpasangan (paired sample t test). Variabel dependen
dalam pengujian tersebut adalah Slack dan Honesty selama 5 periode. Tabel 4
menunjukkan hasil tes ANOVA untuk eksperimen kedua.
Hasil pengujian two way ANOVA untuk eksperimen kedua menunjukkan bahwa
kejujuran manajer tidak dipengaruhi oleh pembagian keuntungan slack oleh manajer
kepada asistennya, hal ini ditunjukkan oleh p value atas sharing pada panel A sebesar
0.407, dan p value atas sharing pada panel B sebesar 0.604. Kesadaran karyawan lain
mengenai misreporting yang dilakukan manajer ternyata mempengaruhi kejujuran
manajer dalam pelaporan anggaran pada eksperimen kedua ini (p=0.007 untuk slack dan
p=0.036 untuk honesty), begitupun untuk interaksi antara kesadaran karyawan lain
21 signifikan berpengaruh terhadap kejujuran manajer dalam pelaporan anggaran (p=0.005
untuk slack dan p=0.004 untuk honesty).
Hasil uji t sampel berpasangan untuk menguji perbedaan hasil eskperimen
pertama dan hasil eksperimen kedua dapat dilihat pada Tabel 5.
[ Mohon letakkan Tabel 5 di sini]
Perbedaan yang signifikan antara hasil eksperimen pertama dan eksperimen
kedua adalah kondisi sharing (p=0.038 untuk slack dan p=0.013 untuk honesty). Hasil ini
mendukung Hipotesis (3a) yaitu adanya fairness concern menyebabkan perbedaan
perilaku manajer dalam melaporkan anggarannya ketika keuntungan dari slack dibagikan
kepada karyawan lain dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern. Slack yang
diciptakan oleh manajer-partisipan lebih rendah ketika adanya fairness concern dalam
kondisi keuntungan slack tersebut dibagi dengan karyawan lain (234.8) dibandingkan
dengan ketika tidak adanya fairness concern (322.15). Hasil yang senada terjadi pada
tingkat kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran dimana kejujuran manajer lebih
tinggi ketika adanya fairness concern dalam kondisi keuntungan dari slack tersebut dibagi
dengan karyawan lain (0.7704) dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern
(0.6691).
Perbedaan lain yang signifikan antara hasil eksperimen pertama dan eksperimen
kedua adalah kondisi sharing-known (p=0.002 untuk slack dan p=0.003 untuk honesty).
Hasil ini mendukung hipotesis (3d) yaitu adanya fairness concern menyebabkan
perbedaan perilaku manajer dalam melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack
dibagi dengan karyawan lain dan karyawan lain tersebut mengetahui perilaku manajer
dalam melaporkan anggaran dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern. Slack
yang diciptakan lebih rendah ketika adanya fairness concern dalam kondisi
22 Kejujuran manajer lebih tinggi ketika adanya fairness concern dalam kondisi
sharing-known (0.8828) dibanding dengan ketika tidak adanya fairness concern (0.7802).
Kesimpulannya, fairness concern berpengaruh terhadap kejujuran manajer dalam
melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain dan
ketika karyawan lain mengetahui adanya misreporting yang dilakukan oleh manajer
divisi. Sedangkan dalam kondisi selain itu, fairness concern tidak mempengaruhi
kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran.
5. Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian
5.1. Kesimpulan
Hasil dari dua eksperimen yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh shared
financial interest, kesadaran karyawan lain mengenai misreporting, dan fairness concern
terhadap kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran adalah:
1. Kejujuran manajer dalam melaporkan anggaran lebih rendah ketika slack dibagi
dengan karyawan lain daripada ketika slack tersebut tidak dibagi.
2. Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggarannya ketika keuntungan dari slack dibagikan kepada
karyawan lain dibandingkan dengan tidak adanya fairness concern.
3. Adanya fairness concern menyebabkan perbedaan perilaku manajer dalam
melaporkan anggaran ketika keuntungan dari slack dibagi dengan karyawan lain
dan karyawan lain tersebut mengetahui perilaku manajer dalam melaporkan
23 5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain eksperimen yang dilakukan tidak
memasukkan unsur budaya, kebiasaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi
kejujuran seseorang. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan faktor-faktor yang
mempengaruhi kejujuran seorang, misalnya memilih partisipan yang berbeda kebudayaan
atau berbeda negara.
DAFTAR REFERENSI
Alexander, S., & Ruderman, M. (1987). The role of procedural and distributive justice in
organizational behavior. Social Justice Research, 1, 117–198.
Antle, R., & Fellingham, J. (1990). Resource rationing and organizational slack in a
two-period model. Journal of Accounting Research, 28(1), 1–24.
Aronson, E. (1995). The social animal. New York, NY: W.H. Freeman and Company.
Aronson, E. (1999). Dissonance, hypocrisy, and the self-concept. In E. Harmon-Jones, &
J. Mills (Eds.), Cognitive dissonance. Progress on a pivotal theory in social
psychology. Washington DC: American Psychological Association.
Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. In
R. M. Kramer, & B. M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (Vol.
25).
Bandura, A. (1990). Selective activation and disengagement of moral control. Journal of
Social Issues, 46(1), 27–46.
Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.
Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209.
Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency.
24 Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of
moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and
Social Psychology, 71(2), 364–374.
Bohlander, G., & Snell, S. (2007). Managing human resources (14th ed.). Mason, OH:
Thomson South-western.
Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of
Management Review, 11(4), 710–725.
Church, B.K, Hannan, R.L, & Kuang, X.J. (2012). Shared interest and honesty in budget
reporting. Accounting, Organizations and Society 37, 155–167.
Covaleski, M. A., Evans, J. H., III, Luft, J. L., & Shields, M. D. (2003). Budgeting
research: Three theoretical perspectives and criteria for selective integration.
Journal of Management Accounting Research, 15, 3–49.
Darley, J. M., & Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of
responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4), 377–383.
DeMatteo, J. S., Eby, L. T., & Sundstrom, E. (1998). Team-based rewards: Current
empirical evidence and directions for future research. In B.M.Staw, & L.L.
Cummings (Eds.), Research in organizational behavior (Vol. 20). JAI Press Inc.
Dunk, A. S., & Nouri, H. (1998). Antecedents of budgetary slack: A literature review and
synthesis. Journal of Accounting Literature, 17, 72–96.
Evans, J. H., III, Hannan, R. L., Krishnan, R., & Moser, D. V. (2001). Honesty in
managerial reporting. The Accounting Review, 76(4), 537–559.
Fisher, J. G., Peffer, S., & Sprinkle, G. B. (2003). Budget-based contracts, budget levels,
25 Hannan, R. L., Rankin, F. W., & Towry, K. L. (2006). The effect of information systems
on honesty in managerial reporting: A behavioral perspective. Contemporary
Accounting Research, 23(4), 885–918.
Hollensbe, E. C., & Guthrie, J. P. (2000). Group pay-for-performance plans: The role of
spontaneous goal setting. Academy of Management Review, 25(4), 864–872.
Krishnan, R., Marinich, E., & Shields, M. D. (2011). Participative budgeting,
psychological contracts, and honesty of communication. Working paper, Michigan
State University.
Lau, C.M. & Tan, S.L.C. (2005). The importance of procedural fairness in budgeting.
Advances in Accounting (Vol.21), 333–356.
Lissak, R. I., Mendes, H., & Lind, E. A. (1983). Organizational and non organizational
influences on attitudes toward work. Champaign: University of Illinois.
Merchant, K. A. (1985). Budgeting and the propensity to create budgetary slack.
Accounting, Organizations and Society, 10(2), 201–210.
Mynatt, C., & Sherman, S. J. (1975). Responsibility attribution in groups and individuals:
A direct test of the diffusion of responsibility hypothesis. Journal of Personality
and Social Psychology, 32(6), 1111–1118.
Newman, A. H. (2011). The behavioral effect of cost targets on managerial cost reporting
honesty. Working paper, University of Pittsburgh.
Rankin, F. W., Schwartz, S. T., & Young, R. A. (2008). The effect of honesty and
superior authority on budget proposals. The Accounting Review, 83(4), 1083–1099.
Shields, J. F., & Shields, M. D. (1998). Antecedents of participatory budgeting.
26 LAMPIRAN
Tabel 2
Rata-rata Slack dan Honesty pada Eksperimen 1
Unknown Known
Sharing Slack= 443.25,
Honesty = 0.558,
N= 40
Slack = 201.775
Honesty = 0.7802
N= 40
No-Sharing Slack = 136.60
Honesty = 0.8569
N= 40
Slack = 253.0250
Honesty = 0.7461
27 Tabel 3
Hasil Tes ANOVA untuk Eksperimen 1
Type III Sum
of Squares Df Mean Square F Sig.
Panel A: Dependent Variable : SLACK
Sharing 652291.600 1 652291.600 6.904 .009
Knowledge 156375.025 1 156375.025 1.655 .200
Sharing *
Knowledge
1280924.100 1 1280924.100 13.557 .000
Error 1.474E7 156 94486.443
Total 2.753E7 160
Corrected Total 1.683E7 159
Panel B: Dependent Variable: HONESTY
Sharing .701 .701 1 1 .701 .701 8.355 8.355 .004 .004
Knowledge .124 1 .124 1.481 .225
Sharing*Knowledge 1.109 1 1.109 13.211 .000
Error 13.097 156 .084
Total 101.541 160
28 Tabel 4
Hasil Tes Two Way ANOVA untuk Eksperimen 2
Type III Sum
of Squares Df Mean Square F Sig.
Panel A: Dependent Variable: SLACK
Sharing_F 60528.400 1 60528.400 .690 .407
Knowledge_F 653313.600 1 653313.600 7.447 .007
Sharing_F *
Knowledge_F
710222.500 1 710222.500 8.095 .005
Error 1.369E7 156 87730.820
Total 2.253E7 160
Corrected Total 1.511E7 159
Panel B: Dependent Variable: HONESTY
Sharing_F .021 1 .021 .271 .604
Knowledge_F .352 1 .352 4.453 .036
Sharing_F*Knowledge_
F
.686 1
.686 8.663 .004
Error 12.348 156 .079
Total 111.238 160
29 Tabel 5
Hasil Uji T Sampel Berpasangan antara Eksperimen 1 dan Eksperimen 2
Sampel Berpasangan Ukuran Kejujuran Signifikansi
(p value)
Sharing Slack 0.038*
Sharing Honesty 0.013*
No Sharing Slack 0.980
No Sharing Honesty 0.851
Sharing Unknown Slack 0.327
Sharing Unknown Honesty 0.181
Sharing Known Slack 0.002*
Sharing Known Honesty 0.003*
No Sharing Unknown Slack 0.346
No Sharing Unknown Honesty 0.351
No Sharing Known Slack 0.411
No Sharing Known Honesty 0.685