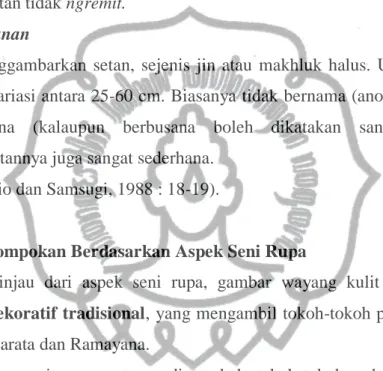BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Pengertian Wayang Kulit Purwa dan Asal - Usulnya
Berbicara mengenai pengertian dan asal-usul wayang kulit purwa memang sangat sulit sekali untuk dipastikan. Namun begitu banyak para ahli yang tertarik dan berusaha untuk mengetahuinya lewat penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukannya. Mereka tersebut antara lain adalah: Dr. G.A.J Hazeu, Crawfutr, Hageman, Poensen, Brandes, dan lain-lain.
Dr. G.A.J Hazeu dalam Disertasinya yang berjudul “Bydrage tot de kennis van het javaansche tooneel” yang diselesaikan di Leiden tahun 1857, mengupas secara ilmiah tentang pertunjukan wayang kulit purwa yaitu: wayang, kelir, blencong, kothak, kecrek, dalang, dan cempala. Dia secara lebih jauh menjelaskan tentang istilah-istilah tersebut sebagai berikut:
a. Wayang
Dalam bahasa Jawa kata wayang berarti “bayangan”. Pada waktu itu boneka- boneka yang dipergunakan dalam pertunjukan itu berbayangan atau memberi bayang-bayang (silhouette), maka dinamakan wayang.
b. Kelir
Kata ini berarti “tabir”. Semua kata dengan lir, lar dan sebagainya mengandung pengertian “sesuatu yang terbentang memanjang”. Demikian juga kelir adalah “sesuatu yang dibentangkan memanjang”.
c. Blencong
Sebuah lampu minyak dengan cerat yang menjulurkan sumbu tebal. Blencong berasal dari akar kata cang, ceng, cong, dan sebagainya yang berarti “miring atau mencong”. Oleh karena itu blencong diletakkan dalam posisi miring di atas dalang.
commit to user
d. Kothak
Sebuah peti yang tutupnya diberi pinggiran agar mudah dibuka dan ditutup.
Kothak berasal dari akar kata tik, tak dan sebagainya adalah tiruan bunyi dari benda yang bersentuhan.
e. Keprak, Kepyak, atau Kecrek
Kata-kata ini dibentuk dari akar kata yang merupakan tiruan bunyi yang ditimbulkan oleh alat tersebut.
f. Dalang
Kata ini berarti: “Orang yang melakukan pertunjukan wayang kulit purwa“.
Kata dalang dianggap sebagai bentuk pengulangan dari akar kata lang.
Bahasa Melayu lalang berarti “berkeliling memutari, mengelilingi” sesuai juga dengan kata Jawa lalang. Jadi dalang berarti: “seseorang yang berkeliling melakukan pertunjukan wayang kulit purwa di sana-sini“
Dari uraian seperti tersebut di atas ia berkesimpulan bahwa istilah-istilah itu hanya ada di Pulau Jawa, jadi termasuk Bahasa Jawa asli kecuali kata cempolo (Cempala) berasal dari Bahasa Sansekerta. (Hazeu dalam Sri Mulyono, 1978: 11- 12).
Hageman berkesimpulan bahwa wayang kulit purwa diciptakan oleh R.
Panji Kertapati dalam abad XII yaitu dalam masa kejayaan kebudayaan yang dipengaruhi Hindu.
Poensen menyatakan bahwa pertunjukan wayang kulit purwa mula-mula lahir di Jawa dengan bantuan dan bimbingan orang Hindu.
Dr. Brandes mengemukakan beberapa kenyataan bahwa orang Hindu mempunyai teater yang sama sekali berbeda dengan teater Jawa dan hampir seluruh istilah teknis yang terdapat dalam wayang kulit purwa adalah khas Jawa, bukan Sansekerta. (Sri Mulyono, 1978 : 8).
Selain beberapa pendapat dari para sarjana luar negeri tersebut, beberapa sarjana kita juga ada yang turut berpendapat, karena didorong oleh kebuntuan mereka pada wayang kulit purwa.
Pendapat tersebut antara lain adalah : commit to user
Wayang dalam bahasa Jawa berarti “bayangan” dalam bahasa Melayu disebut “bayang-bayang”, dalam bahasa Aceh “bayeng”, dalam bahasa Bugis
“wayang atau bayang”. Akar kata dari wayang adalah “Yang”, akar kata ini bervariasi dengan Yung, Yong dan Ying, antara lain terdapat dalam kata layang
“terbang”, doyong “miring”, tidak stabil “royong” selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, poyang-payungan “berjalan sempoyongan, tidak tenang” (Sri Mulyono, 1978: 9).
Awalan “Wa” di dalam bahasa Jawa modern tidak mempunyai fungsi lagi, tetapi dalam bahasa Jawa kuno awalan tersebut masih jelas memiliki fungsi tata bahasa. Jadi dalam bahasa Jawa Wayang, mengandung pengertian “berjalan kian- kemari, tidak tetap, sayup-sayup (bagi substansi bayang-bayang) telah terbentuk pada waktu yang amat tua ketika awalan Wa masih mempunyai fungsi tata bahasa. Oleh karena itu boneka-boneka yang digunakan dalam pertunjukan itu berbayangan atau memberi bayang-bayang, maka dinamakan Wayang. Awayang atau hawayang pada waktu itu berarti “bergaul dengan wayang, mempertunjukkan wayang”. Lambat laun wayang menjadi nama dari pertunjukan bayang-bayang (Sri Mulyono, 1978: 10).
“Wayang adalah berasal dari kata “Hyang” yang berarti persembahan pada Hyang Widhi”. Nenek moyang bangsa Indonesia beberapa puluh tahun sebelum Masehi telah mengenal wayang yaitu suatu bentuk pentas sebagai sarana upacara keagamaan yang bersifat ritual dengan menggunakan bayangan (wayang) dalam membawakan acara-acaranya (Adhiman Sajuddin Rais, 1970: 8).
Wayang kulit purwa merupakan dongeng, khayal dan mitos yang dapat membangkitkan daya mistik dalam diri penghayatnya. Penafsiran orang Barat bahwa wayang kulit purwa hanya “Shadow Play” belaka adalah kurang tepat, karena wayang kulit purwa bukanlah obyek visual belaka (S. Haryanto, 1988: 4).
Masih banyak lagi tulisan-tulisan dan pendapat mengenai wayang kulit purwa yang masih memerlukan penyelidikan-penyelidikan seksama mengenai kebenarannya. Bila ditelaah dengan seksama maka kata wayang tersebut berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Karena pengaruh warga-aksara, maka
commit to user
kata wayang menjadi bayang, wesi menjadi besi dan watu menjadi batu (S.
Haryanto, 1988: 28).
B.M Goshings dalam bukunya “De Wayang On Java End On Bali”, mengatakan : “Wayang is not a shadow play. The common conception of wayang as a shadow play originated as a result of faulty European perception”. (B.M Goshings dalam R.L. Mellena, 1954: 5). Artinya: Wayang kulit purwa bukanlah sebuah permainan bayang-bayang belaka. Pengertian umum yang mengatakan bahwa wayang kulit purwa sama halnya dengan permainan yang ditimbulkan oleh bayang-bayang adalah akibat dari pendapat orang-orang Eropa yang salah. Bagi masyarakat penghayatnya (Jawa), pagelaran wayang kulit purwa adalah pengungkap “wewayanganing ngaurip” (gambaran dari hidup dan kehidupan) yang tidak ada hubungannya dengan bayang-bayang hitam, (silhoutte) pada kelir (layar). (S. Haryanto, 1995: 161).
Wayang kulit purwa dalam budaya Jawa biasanya disebut juga dengan wayang purwa atau ringgit. Maksud dari wayang kulit purwa adalah wayang yang dibuat dari bahan kulit binatang, biasanya kulit kerbau. Kata “wayang” menurut Hazeu berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti bayangan, yang bisa mempunyai pengertian berjalan kian kemari, tidak tetap, sayup-sayup, sebagai substansi dari bayang-bayang sehingga bisa disebut wayang. (Sri Mulyono, 1995 : 9).
Secara umum, pengertian wayang kulit purwa adalah suatu bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang dengan menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan. Wayang kulit purwa merupakan alat untuk menggambarkan kehidupan umat manusia. Sedang bentuknya sangat berbeda dari tubuh manusia pada umumnya. Seno Sastroamidjojo (1964 : 37) menyatakan bahwa wayang kulit purwa ini diukir menurut sistem tertentu.
Perbandingan (proporsi) antara bagian badannya masing-masing tidak seimbang satu sama lain. Segala sesuatu mengenai hal itu dibuatnya menurut cara-cara dan anggapan tertentu.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wayang kulit purwa adalah boneka yang dibuat dari kulit, ditatah dan disungging sedemikian rupa sehingga commit to user
menggambarkan bentuk-bentuk yang proporsinya tidak sama dengan manusia, tetapi dipergunakan sebagai alat untuk menggambarkan kehidupan manusia.
Apabila dipergunakan di dalam pakeliran (pertunjukan) dapat menimbulkan bayang-bayang pada layar (kelir) dan dapat digerakkan kian kemari.
Kata “purwa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “pertama”, yang terdahulu atau yang dulu. Jaman purwa berarti jaman dahulu dan wayang purwa berarti wayang pada jaman dahulu. Menurut Brandes, kata purwa berasal dari kata puruwa yang merupakan mata rantai dari kata parwa (berarti bab-bab dalam Mahabarata). Hazeu menyetujui hal tersebut, karena perkataan parwa sesuai dengan gejala metatesis, dapat dikatakan purwa. (Sri Mulyono, 1995 : 149). Dari hal tersebut Sujamto (1992) mengartikan wayang kulit purwa dengan “wayang kulit purwa yang mengambil tema cerita dari epos Mahabarata dan Ramayana”.
Sedang wayang kulit purwa baru adalah wayang kulit purwa yang diciptakan oleh seniman wayang kulit purwa pada jaman sekarang untuk melengkapi dan menambah tokoh-tokoh wayang purwa yang sudah baku.
2. Perkembangan Wayang Kulit Purwa
Meskipun asal-usul wayang kulit purwa belum dapat ditentukan pasti, penulis Indonesia cenderung mengakui teori Hazeu yang mengatakan wayang kulit purwa berasal dari suatu upacara keagamaan untuk memuja arwah nenek moyang yang disebut “Hyang” yang kemudian menyebabkan munculnya pertunjukan bayang-bayang. Pertunjukan wayang kulit purwa bersumber pada upacara agama terhadap pemujaan “Hyang” timbulnya pada awal jaman Neolithikum atau akhir jaman Mesolithikum atau pasti terjadi sesudah tahun 2000 sebelum Masehi (Sri Mulyono, 1978: 55).
Demikianlah saat mula adanya pertunjukan wayang kulit purwa sebagai awal mula adanya pertunjukan wayang kulit purwa di Indonesia (Jawa). Wayang kulit purwa tersebut kemudian terus berkembang setahap demi setahap dalam waktu yang cukup lama, namun tetap mempertahankan fungsi intinya sebagai suatu kegiatan gaib yang berhubungan dengan kepercayaan dan pendidikan (magis, religious dan didaktis). commit to user
Selama kurun waktu lebih dari 2000 tahun tersebut, perkembangan wayang kulit purwa di bagi menjadi beberapa periodesasi, yakni :
a. Jaman Prasejarah
Pada Jaman Prasejarah, alam pikiran nenek moyang kita masih sangat sederhana. Mereka mempunyai anggapan bahwa semua benda yang ada dikelilingnya itu bernyawa dan semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau mempunyai roh yang berwatak baik maupun jahat (Koentjaraningrat, 1954: 103).
Antara dunia manusia dan dunia roh ada suatu jembatan yang hanya dapat dilihat oleh beberapa orang yang dianggap sakti, perbuatan-perbuatan untuk mengadakan hubungan gaib ini disebut Upacara. Upacara ini dianggap sebagai suatu kejadian yang sangat angker (sakral), oleh karena itu diperlukan persyaratan pokok untuk melakukannya. Syarat-syarat tersebut meliputi: tempat khusus, waktu khusus dan orang sakti (Sri Mulyono, 1978: 43).
Selain syarat-syarat juga diperlukan sarana atau alat-alat khusus yang diperlukan oleh Syaman/ perewangan untuk mengadakan hubungan dengan roh- roh nenek moyang tersebut. Alat-alat tersebut misalnya:
- Patung dari nenek moyang yang telah meninggal.
- Patung Korwar (patung yang diberi tengkorak nenek moyang).
- Mummi, yaitu mayat nenek moyang yang telah dikeringkan.
- Gambar roh nenek moyang yang dipahat di atas kulit binatang, dengan diberi penerangan atau disoroti dengan lampu, agar gambar tesebut menimbulkan bayangan. Bayangan ini dianggap sebagai wujud kedatangan roh nenek moyang.
- Saji-sajian dan bau-bauan yang digemari oleh nenek moyang di waktu masih hidup.
(Sri Mulyono, 1978: 43).
Berpedoman pada pemikiran dan anggapan tentang roh-roh seperti tersebut di atas yang kemudian mendorong para pendahulu untuk menghasilkan perwujudan bayangan sehingga orang dapat membayangkan roh orang yang telah
meninggal. commit to user
Kepercayaan pada wajah/gambar leluhurnya tersebut mempengaruhi cara- cara pembuatan bayang-bayang, gambar dari bayang-bayang, oleh karena itu orang meniru bentuk bayang-bayang seperti yang diletakkan mengelilinginya setiap hari. Bentuk bayang-bayang itu harus tidak berbentuk manusia, oleh karena itu sekarang wayang kulit purwa memperlihatkan bentuk yang aneh seperti itu.
Tidak menyamai manusia sesungguhnya. Ukuran lengan tangannya memanjang, telapak kakinya panjang dan sebagainya. Perupaan wayang kulit purwa yang seperti inilah yang menjadi dasar perupaan wayang kulit purwa pada jaman-jaman periode berikutnya (Sri Mulyono, 1978: 46).
b. Jaman Pengaruh Hindu
Sejarah Indonesia dimulai sejak datangnya pengaruh kebudayaan Hindu.
Karena pengaruh itu berakhirlah jaman pra-sejarah Indonesia. Pada jaman sejarah ini mulai ada keterangan-keterangan tertulis yang berupa prasasti yaitu batu bersurat atau bertulisan berisi keterangan adanya upacara-upacara atau peringatan berkorban. Tulisan yang dipergunakan biasanya berhuruf Pallawa yang berasal dari India Selatan dan dalam bahasa Sanskerta, bahasa resmi India.
Penduduk asli mengalami perubahan yang sedikit demi sedikit menerima pengaruh Hindu. Kitab Mahabharata dan Kitab Ramayana mulai dikenal dan meluas di Indonesia. Pertunjukan bayangan atau upacara agama yaitu upacara pemujaan Hyang pun tidak luput dari pengaruh Hindu. Perwujudan wayang kulit purwa pada jaman Hindu ini diawali dari kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 732 di desa Canggal di daerah Magelang Jawa Tengah, dibuat suatu prasasti dengan memakai huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta berbentuk syair yang berbunyi çruti indria rasa (732 M/654 çaka). Prasasti ini menyebutkan bahwa yang memerintah kerajaan Mataram pada waktu itu bernama Sanjaya (Sri Mulyono, 1978: 59).
Pada waktu itu pertunjukan bayangan/wayang kulit purwa adalah penting dan mempunyai latar belakang kepercayaan dan merupakan pertunjukan penduduk asli yang langsung mempengaruhi pandangan hidup penduduk asli, oleh karena itu tidaklah mustahil bahwa para ahli agama Hindu pada waktu itu commit to user
menempuh kebijaksanaan dengan jalan memasukkan cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana ke dalam suatu pertunjukan yang mempunyai peranan dan kedudukan penting dalam pandangan hidup penduduk asli, yaitu pertunjukan wayang kulit purwa.
Pengaruh kebudayaan Hindu yang datang dengan damai di Indonesia bisa diterima dengan senang hati oleh nenek moyang kita, sehingga orang-orang Hindu tidak menjadi sulit untuk memasukkan pengaruh Hindu ke dalam pandangan hidup penduduk Indonesia. Cerita yang semula merupakan mitos nenek moyang yang pada prinsipnya memuja-muja Dewa/Hyang itu ternyata pada prinsipnya hampir sama dengan epos Mahabharata dan Ramayana yang juga memuja dewa- dewa. (Sri Mulyono, 1978: 64).
c. Jaman Islam
Pada masa akhir kerajaan Majapahit pengaruh Islam mulai tertanam dalam masyarakat. Masuknya Islam, khususnya di Tanah Jawa bersama-sama dengan para pedagang atau saudagar yang di samping berdagang juga berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Para pedagang umumnya orang-orang muslim dengan tekun melakukan penyebaran ajaran baru ini yang telah dilakukan jauh sebelum kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak pada sekitar abad ke 15. Kerajaan Islam yang berdiri pada permulaan Islam masuk di Indonesia berada di daerah Sumatera Utara, yang dikenal dengan Kerajaan Samudra Pasai (tahun 1292). Pada mulanya daerah tersebut merupakan pelabuhan dagang yang banyak didatangi oleh pedagang-pedagang Gujarat, pedagang tangguh dari daerah pesisir India (Soekmono, 1985: 52). Dari para pedagang atau saudagar itulah Islam masuk ke Indonesia, kemudian pusat perdagangan itu berkembang menjadi suatu kerajaan yang berpengaruh dalam perkembangan Islam selanjutnya. (Sunarto, 1991: 3).
Dalam Babad Demak dijelaskan bahwa Raden Patah atas bantuan para bupati pesisir utara Demak dapat merobohkan Majapahit, kemudian memindahkan peralatan upacara kerajaan dan pusaka Majapahit ke Demak sebagai lambang tetap berlangsungnya kerajaan Majapahit tetapi dalam bentuk baru di Demak. (Soekmono, 1985: 52). Runtuhnya Majapahit ditandai dengan commit to user
sengkalan “Sirna ilang kertaning bumi” (1400 Caka). Pada waktu itu Wayang Beber Majapahit beserta seluruh perlengkapannya atau gamelannya diangkut ke Demak yang kemudian wayang kulit purwa tersebut mengalami perubahan besar.
(S. Haryanto, 1988: 31).
d. Jaman Penjajahan Belanda
Belanda datang di Indonesia ± tahun 1598, tetapi Belanda baru berhasil memasuki lingkungan istana kerajaan Mataram pada jaman pemerintahan Raja Amangkurat II pada tahun 1680 M. Dengan bantuan Belanda, ibukota kerajaan dipindahkan ke Kartasura.
Pada jaman ini tercatat juga ada kemajuan di bidang kesenian wayang kulit purwa, diantaranya:
- Muncul Punakawan Bagong.
- Bentuk wayang kulit purwa disempurnakan.
Pada waktu pemerintahan Paku Buwana I (1704 M-1719 M) dibuat:
- Wayang Kulit Purwa Sabrangan.
- Wayang Kulit Purwa Kenya Wandu.
- Membuat buku pakem lakon wayang kulit purwa Menak.
Pada masa Paku Buwana II (1719-1749), banyak membuat wayang- wayang kulit purwa baru yang sampai sekarang disimpan di Keraton Surakarta dan dianggap sebagai wayang kulit purwa pusaka serta menjadi babon wayang kulit purwa. Wayang kulit purwa tersebut diberi nama Kyahi Pramukanya. Paku Buwana III (1749-1788) dengan menggunakan babon Kyahi Pramukanya, berhasil membuat wayang kulit purwa dua kothak dan diberi nama Kyahi Mangu dan Kyahi Kanyut.
Pada masa pemerintahan Paku Buwana IV (1788-1820) wayang-wayang kulit purwa yang dihasilkan adalah: Kyahi Jimat, Kyahi Kadung dan Kyahi Dewa Katong. Sejak pemerintahan Paku Buwana V (1820-1823 M) kesenian wayang kulit purwa sudah sangat umum dan tersebar luas ke seluruh daerah Jawa, sehingga setiap selesai pembuatan wayang kulit purwa tidak lagi diberi nama secara khusus, namun demikian, ini tidak berarti bahwa kesenian wayang kulit commit to user
purwa sudah tidak mendapat perhatian, bahkan kesenian wayang kulit purwa pada saat itu mulai menjadi perhatian para sarjana sebagai obyek kajian ilmiah.
Belanda menjajah Indonesia sejak 1596-1942 tidak banyak berkepentingan dengan pertunjukan wayang kulit purwa, tetapi banyak para pakar budaya Belanda khusus datang ke Indonesia untuk mempelajari seni tradisi, salah satunya adalah kesenian wayang kulit purwa. Antara lain: Poensen, Dr. Rassers, Dr.
Brandes, Prof. Dr. Kern.J.Kats, Prof. Dr. Hazeu, Prof. Dr. Gonda, Dr. Th Pigeaud, Dr. Yuynbowl dan sebagainya (Sri Mulyono, 1978: 93).
e. Jaman Kemerdekaan
Pada jaman kemerdekaan, seni pedalangan wayang kulit purwa tidak lagi dibina oleh Pemerintah Kerajaan, tetapi tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai kesenian daerah dan diurus serta dibina oleh masyarakat itu sendiri. Para seniman sudah berani berapresiasi dengan wayang kulit purwa untuk menunjang kepentingan-kepentingan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan terciptanya berbagai bentuk wayang kulit purwa, misalnya: wayang Krucil, wayang Perjuangan, wayang Jawa, wayang Suluh, wayang Wahyu, dan sebagainya (Sri Mulyono, 1978: 99).
3. Fungsi Wayang Kulit Purwa
Sesuai dengan apa yang telah ditulis dimuka, bahwa wayang kulit purwa diperkirakan telah ada di bumi Indonesia ini sudah sejak ± 1500 SM, dan ternyata sampai saat ini keberadaannya masih tetap eksis di bumi Indonesia terutama di pulau Jawa. Selain dari segi perupaannya, fungsi wayang kulit purwa juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Pada perkembangan terakhir ini, fungsi wayang kulit purwa tidak lagi terfokus pada upacara-upacara ritual dan keagamaan, bahkan bergeser sebagai konsumsi hiburan: sehingga lakon dan pakem banyak disesuaikan dengan selera penggemarnya (S. Haryanto, 1991:
1).
commit to user
a. Religio Magis
Sejarah perkembangan Religi orang Jawa telah dimulai sejak jaman Pra- sejarah (± 1500 SM), dimana pada waktu itu nenek moyang orang Jawa sudah beranggapan bahwa: semua benda yang ada di sekelilingnya itu bernyawa, dan semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau mempunyai roh yang berwatak baik maupun jahat. Dengan dasar bayangan dan anggapan mereka bahwa di samping segala roh yang ada tentulah ada roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Untuk menghindarkan gangguan dari roh itu maka mereka memujanya dengan jalan mengadakan upacara.
(Koentjaraningrat, 1954: 103).
Wayang kulit purwa dipahami dan dipercaya sebagai hasil kebudayaan Bangsa Indonesia asli yang bersumber dari kepercayaan nenek moyang jaman purba yang bertujuan untuk kegiatan Religio Magis, pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Prijohutomo sebagai berikut:
“Sebagian dari upacara kuno berupa wayangan, yang pada waktu itu masih berwujud lukisan atau boneka yang amat sederhana buatannya seperti gambaran punakawan sekarang ini. Upacara yang berupa pertunjukan itu baru kelak kemudian mendapat pengaruh dari kesenian Hindu sehingga bentuknya seperti yang kita kenal sekarang. Pertunjukan wayang kulit purwa itu antara lain untuk melepaskan (ngruwat) orang dari malapetaka, Karena lukisan atau boneka tadi merupakan tempat untuk arwah nenek moyang yang dipanggil supaya turun dari surga atau kayangan. Adanya lukisan atau boneka itu sudah dapat menjauhkan malapetaka”
(Prijohutomo, 1953: 15).
Pemujaan arwah nenek moyang inilah sebagai agama mereka yang pertama (animisme). Arwah nenek moyang yang pernah hidup sebelum mereka telah banyak jasa dan pengalamannya, sehingga perlu dimintai berkah dan petunjuk. Sarana yang ditempuh untuk mendatangkan arwah nenek moyangnya ialah:
1) Mengundang orang yang sakti dan ahli dalam bidang itu, yang disebut perewangan untuk memimpin upacara.
2) Membuat patung nenek moyang, agar arwahnya bersemayam dalam patung tersebut, atas tuntunan dan upaya perewangan tersebut. commit to user
3) Membuat sesaji dan membakar kemenyan atau bau-bauan lainnya yang digemari oleh nenek moyang.
4) Mengiringi upacara tersebut dengan bunyi-bunyian dan tarian agar arwah nenek moyang yang dipanggil gembira dan berkenan memberikan rakhmatnya.
Sisa-sisa upacara religius seperti tersebut di atas, sampai sekarang masih ada dalam kehidupan masyarakat Jawa, hanya telah berubah fungsinya menjadi kesenian rakyat tradisional, misalnya: Sintren, Nini Thowok, Barongan, tari Topeng dan pertunjukan wayang kulit purwa (B. Heru Satoto, 1984: 99).
Kedatangan kebudayaan Hindu di Jawa semakin menambah perbendaharaan cara dan pengertian dalam tindakan religius manusia Jawa.
Penghormatan dan pemujaan kepada Dewa-Dewi Hindu menimbulkan fantasi akan adanya Dewa-Dewi lainnya yang asli Jawa. Hal ini adalah hasil asimilasi paham animisme dan paham Hindu.
Lambat laun orang Indonesia “mengadopsi” dewa-dewa dan epos dari India itu kemudian dicampur dengan mitologi kuno. Bahkan kemudian pulau Jawa dianggap oleh pendahulu kita sebagai setting alam dewa dan pahlawan- pahlawan dalam Ramayana tersebut. Akhirnya pahlawan-pahlawan dalam Ramayana ini juga dianggap sebagai nenek moyangnya sendiri. Cerita-cerita ini sampai sekarang pengaruhnya masih kita rasakan, misalnya: sebuah kepercayaan bahwa raja-raja di Jawa adalah keturunan Arjuna, Brahma dan seterusnya (Sri Mulyono, 1978: 64).
Pada jaman Hindu ini wayang kulit purwa berfungsi untuk memvisualisasikan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kepahlawanan yang bersumber pada Kitab Mahabharata dan Ramayana dari India, yang kemudian melahirkan bentuk wayang kulit purwa. Melihat kandungan nilai dalam wayang kulit purwa, masyarakat dididik dapat hidup dengan baik berdasar ajaran agama, karena pesan dan nilai yang ada sesuai dengan citra masyarakat tersebut, semakin lama wayang kulit purwa digemari dan membudaya dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa (Sunarto, 1991: 12).
Fungsi religio magis ini masih bisa kita lihat implementasinya di jaman modern ini, meskipun pagelarannya semakin jarang. Fungsi pertunjukan wayang commit to user
kulit purwa yang masih bernuansa mistik ini antara lain: Murwakala (ruwatan), Bersih Desa/ Merti Desa, Sadranan (penghormatan arwah nenek moyang/
pendahulu) dan Nadar.
b. Pragmatis
Memasuki periode Islam di pulau Jawa wayang kulit purwa mengalami pergeseran dasar konsepsi. Wayang kulit purwa tidak lagi berfungsi sebagai upacara religio magis, melainkan berfungsi pragmatis yaitu sebagai alat dakwah, pendidikan, komunikasi/informasi, sumber sastra dan budaya, juga seni hiburan;
meskipun suasana magis kadang masih terasa. Para Wali memodifikasi legenda dunia wayang kulit purwa menjadi cerita-cerita babad, yakni percampuradukkan antara epos Ramayana, Mahabharata versi Indonesia dengan cerita-cerita Islami (H. Amir, 1994: 35).
1) Media Dakwah
Penggunaan wayang kulit purwa untuk media dakwah oleh para Wali ini karena pada waktu itu para Wali melihat betapa kuatnya budaya wayang kulit purwa ini melekat pada hati sanubari rakyat pada waktu itu. Melihat keadaan itu para Wali juga berusaha memanfaatkan wayang kulit purwa sebagai media dakwah agama Islam. Hal ini dimulai dari penyesuaian bentuk rupanya terlebih dahulu karena bentuk rupa wayang kulit purwa pada jaman Hindu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam maka diadakanlah berbagai perubahan bentuk rupa.
Pendapat dari Dr. G.A.J Hazeu dalam bukunya Javanesse Volsuertonungen yang diterjemahkan oleh R.M Mangkudimejo mengatakan:
“Mulainya wayang dibuat dari kulit kerbau dimulai pada jaman Raden Patah yang bertahta tahun 1437 Caka. Dahulunya lukisan seperti bentuk manusia serupa apa yang terdapat pada Candi Panataran. Oleh karena hal itu ada pertalian dengan hukum agama Islam, yaitu bertentangan dengan syara’, sedangkan raja dan rakyat sangat suka pada wayang. Maka Wali merubahnya dari lukisan yang methok (menghadap) jadi miring.
Sedangkan anggota badannya sangat panjang. Dahulu sebenarnya memakai gambaran pahatan di dalam mata, telinga, dan lain-lain. Hanya digambar saja, tetapi oleh Wali dilukis dengan pahatan. Disitu kalau orang mau tahu betapa pandainya para Wali” (Effendi Zarkasi, 1996: 61). commit to user
Selain bentuk perupaannya yang dirubah dan disesuaikan dengan Islam, dalam segi lakonpun dibuatkan beberapa lakon carangan yang bernuansa Islam.
“Pada pedalangan wayang kulit purwa itupun diberikannya lakon-lakon ciptaaan yang maksudnya ialah untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran ajaran Islam. Lakon-lakon demikian itu antara lain ialah Dewa Ruci, Petruk dadi Ratu, Semar barang Jantur, Pandu Bergola, Mustaka Weni dan sebagainya.
Bahkan apa yang dinamakan Jimat Kalimasada dengan segala kemahasaktiannya, ialah yang jadi pokok lakon Mustaka Weni, dan itupun terang sekali adalah ciptaan Islam. Nama barang itu tegas-tegas mengingatkan orang kepada ajaran Islam, yaitu Kalimat Syahadat”
(Effendi Zarkasi, 1996: 63).
Dalam perkembangan selanjutnya walaupun para muslim Jawa mengetahui hal-hal non Islamik dalam pertunjukan wayang kulit purwa, tetapi ternyata sulit untuk melepas diri dari dasar filosofi wayang kulit purwa. Usaha menggunakan wayang kulit purwa sebagai sarana dakwah Islamik dengan segala dalih kiranya akan berakibat fatal. Hal ini disebabkan karena inti filosofi wayang kulit purwa memang bukan Islamik. Barangkali sebagai pengenalan ajaran Islam, wayang kulit purwa adalah media adaptif bagi masyarakat Jawa, tetapi untuk pendalaman ajaran jelas beresiko, karena ajaran suatu agama adalah dogmatis yang tidak sembarang sinkron dengan unsur lain (S. Haryanto, 1995: 182-183).
2) Media Pendidikan
Wayang kulit purwa tidak saja merupakan salah satu sumber pencarian nilai-nilai yang amat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa, tetapi wayang kulit purwa juga merupakan salah satu wahana atau alat pendidikan watak yang baik sekali. Pertama, pertunjukan wayang kulit purwa itu sendiri merupakan alat pendidikan watak yang menawarkan metode pendidikan yang amat menarik.
Karena wayang kulit purwa mengajarkan ajaran dan nilai-nilainya tidak secara dogmatis sebagai suatu indoktrinasi, tetapi ia menawarkan ajaran dan nilai-nilai itu; terserah kepada penonton (masyarakat dan individu-individu) sendiri untuk menafsirkannya, menilai dan memilih ajaran dan nilai-nilai mana yang sesuai commit to user
dengan pribadi atau hidup mereka. Selanjutnya wayang kulit purwa mengajarkan ajaran dan nilai-nilai itu tidak secara teoritis saja (berupa ajaran dan nilai-nilai) melainkan secara konkret dengan menghadirkan kehidupan tokoh-tokohnya yang konkret sebagai teladan. Wayang kulit purwa juga tidak mengajarkan ajaran dan nilai-nilai itu secara kaku atau akademis, melainkan di samping mengajak penonton untuk berpikir dan mencari sendiri (sebagai dilambangkan adegan wayang golek di akhir pertunjukan), ia juga mendidik penonton melalui hati/
rasanya dengan jalan adegan-adegan lucunya, adegan mengharukan atau menyentuh hati, membikin hati geram dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan, metode pendidikan watak yang dipakai dalam pertunjukan wayang kulit purwa adalah metode nonformal (H. Amir, 1994: 19-20).
3) Media Hiburan
Sumber lama yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari pergelaran wayang kulit purwa sebagai hiburan dapat dilacak pada “Kakawin Arjuna Wiwaha”, sebuah karya sastra gubahan Mpu Kanwa pujangga Keraton pada masa pemerintahan Raja Erlangga di Jawa Timur tahun 1019-1042 yang sebagian kalimatnya menyebutkan:
“Hananonton ringgit manangis asekel muda hidepan, huwus wruh tuwin yan walulanginukir molah angucap hatur ning wang tresneng wisaya malaha tawihikana ri tatwa nyan maya sahana-nana ning bawa siluman”.
Artinya: “Orang yang menonton ringgit (wayang kulit purwa) menangis, terpesona dan sedih, meskipun sudah tahu bahwa yang ditonton hanyalah belulang yang dipahat, diberi bentuk manusia, dapat bertingkah dan berbicara.
Yang menonton ibarat orang yang tamak akan harta dunia yang nikmat, akibatnya mereka terjerat hatinya, tidak tahu bahwa sebenarnya hanya bayangan yang tampil laksana siluman belaka” (S. Haryanto, 1988: 18-19).
Sebagai seni pertunjukan terbuka (panggung) wayang kulit purwa tidak bisa lepas dari unsur hiburan dalam setiap pementasannya. Unsur-unsur ini menjadi daya tarik penonton untuk menghayati lebih jauh, sehingga muatan-
commit to user
muatan isinya secara tidak langsung ikut terserap dalam proses penghayatan yang telah berlangsung berabad-abad.
c. Estetik
Wayang kulit purwa sebagai pertunjukan multi perspektif memiliki beragam sudut kajian. Antara lain adalah bidang studi filsafat, sejarah, teaterologi, psikologi, maupun sosiologi. Wayang kulit purwa sebagai bentuk seni multimedia juga merangkum sekian jenis seni, antara lain adalah: Seni sastra dan teater, seni pedalangan, seni karawitan (musik), seni tari dan seni rupa pada wujud wayang kulit purwanya.
1) Estetik Rupa
Wayang kulit purwa dalam perlambangan bentuknya mengalami evolusi beratus-ratus tahun. Kini telah memperoleh perupaan yang paling canggih dari segala aspek dengan ikonografi dan karakteristik yang dibawakannya. Berikut gaya stilasi serta unsur-unsur seni rupa, sehingga seni tradisi ini mencapai titik klasik sebagai puncak perkembangannya (S. Haryanto, 1991: 18).
Beberapa gaya terwadahi dalam aspek rupa wayang kulit purwa, seperti ekspresif, dekoratif, tradisional dan kadang humoris. Perupaan Wayang kulit purwa diperkaya dengan “wanda” pada masing-masing tokohnya, sebagai cara pembeda penggambaran karakteristik masing- masing tokoh dalam konteks adegan tertentu wanda-wanda tersebut memvisualisasikan watak dasar, lahir batin wayang kulit purwa pada kondisi mental atau emosi tertentu, dilukiskan dengan pola pada mata, hidung, mulut, wajah, posisi dan perbandingan ukuran tubuh (S.
Haryanto, 1991: 25).
Dalam penggambaran wayang kulit purwa yang paling nampak adalah postur dari tokoh-tokohnya, seperti wayang kulit purwa sebelum Islam penggambarannya berdasar wujud yang dilihat dengan sedikit stilasi sesuai dengan materi dan tekniknya, sehingga hasilnya masih sangat dekat wujud manusia. Berdasarkan kepada pengalaman dan analisis terhadap wayang kulit purwa sebelum Islam, maka para ahli yang didukung oleh para penguasa, commit to user
membuat wayang kulit purwa baru dengan stilasi dan deformasi berdasar pada pengertian tentang manusia. Oleh karena itu muncul penggambaran yang dipanjang-panjangkan, hidung lancip yang berlebihan untuk tokoh alusan, leher dibuat sebesar lengan dan panjang, kemudian tangannya panjang sekali hingga menyentuh kaki. Kemudian penggambaran mulut dibuat berliku-liku, yang tidak dijumpai pada manusia. Stilasi dan deformasi yang dilakukan hingga berhasil menggambarkan bentuk wayang kulit purwa yang kemudian dikenal seperti sekarang ini (Sunarto, 1991: 11-12).
2) Estetik Teater
Sejak abad XI pertunjukan wayang kulit purwa yang berasal dari kepentingan upacara religi telah berkembang menjadi toonel (tonil) yang teratur (sistematik) struktur dramatiknya. Pada dasarnya struktur dramatik inilah yang menciptakan konvensi struktural wayang kulit purwa sehingga mampu bertahan dari jaman ke jaman, karena dalam konvensi ini, apa yang dinamakan pakem, ugeran wayang kulit purwa, atau kaidah dasar pakeliran dapat dilihat secara jelas untuk mempermudah upaya pelestarian, pengembangan dan revitalisasinya (S.
Haryanto, 1991: 12-13).
4. Proses Penciptaan Wayang Kulit Purwa
Siapa yang pertama kali menciptakan wayang kulit purwa, sampai saat ini belum diketahui orangnya. Penciptaan wayang kulit purwa pada jaman dahulu, seperti halnya penciptaan jenis kesenian yang lain, yang tidak pernah berdiri lepas dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menyangga kesenian itulah yang menciptakan bentuk wayang kulit purwa dan masyarakat itu pula yang memeliharanya, menularkannya dan mengembangkan wayang kulit purwa.
Akan tetapi masyarakat adalah suatu perserikatan manusia. Apa yang disebut kreativitas masyarakat berasal dari manusia-manusia pendukungnya, yang akhirnya ciptaan itu diakui menjadi milik masyarakat. Kalau demikian pada mulanya wayang kulit purwa dimulai dari seorang pencipta. Tetapi kenyataannya commit to user
ada yang mengatakan bahwa pencipta wayang kulit purwa baru muncul namanya pertama kali oleh Sunan Giri pada tahun 1541 menciptakan wayang Bhatara Guru Wanda Karna. (Seno A. Sastroamidjojo, 1964 : 21). Setelah itu nama-nama pencipta wayang kulit purwa mulai bermunculan.
Proses penciptaan wayang kulit purwa, seperti halnya proses penciptaan kesenian Jawa pada umumnya, pernah dikemukakan Seno A. Sastroamidjojo sebagai berikut :
Buah karya budaya itu disebut “Kagunan” (hal yang berguna) yang tercipta atas dasar kecerdasan atau pengetahuan (kawruh). Al hasil
“kawruh” itu adalah suatu alat atau “perabot budaya” belaka.
Untuk menghasilkan “Kagunan” yang baik, rasa perasaan tadi harus diselaraskan dengan hasrat atau kehendak (kayun) masing-masing. (1964 : 119).
Dari pendapat tersebut kita dapat mengetahui bahwa kesenian (kagunan) bermula dari kecerdasan atau pengetahuan (kawruh atau ngelmu). Artinya untuk mencari ilmu pengetahuan (ngelmu) harus diupayakan dengan tindakan (laku).
Pada masa itu yang disebut laku adalah laku batin, yaitu mensucikan diri dengan mengurangi makan, minum dan tidur, disertai berdoa atau bersemedi untuk memperoleh ide, ilham atau wisik dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ide, ilham atau wisik dari Tuhan Yang Maha Kuasa harus dipadukan dengan rasa atau perasaan yang ada di dalam dirinya, agar dapat menimbulkan keindahan (estetis). Dengan demikian, bentukan dari ide akan menjadi semakin jelas. Meskipun demikian, tanpa adanya karsa atau kehendak (kayun) yang kuat, ide hanya tetap menjadi ide. (Suwaji Bastomi, 1993 : 95). Dengan cara demikian ide tersebut bila dapat terbabar dalam karya, akan menjadi karya yang indah dan memiliki nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penciptaan kesenian di Jawa termasuk didalamnya wayang kulit purwa pada jaman dahulu, diawali dengan upaya mencari ide dasar lewat “tapa brata” atau pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan suci. Apabila ide dasar telah diperoleh, maka ide itu di padu dengan perasaan agar menjadi bentuk yang indah. Lewat kemauan
commit to user
yang kuat, bentuk itu diwujudkan ke dalam bentuk yang kasat mata dengan tujuan
“memayu hayuning bawana”.
5. Penggolongan Wayang Kulit Purwa
Dalam hubungannya dengan pembuatan wayang kulit purwa, yang meliputi pemahatan dan pewarnaan (penyunggingan) ternyata cukup sulit bila wayang kulit purwa yang akan dibuat tidak dibeda-bedakan atau digolong- golongkan/ dikelompokkan. Belum lagi dalam hal menyimpan/ merawatnya.
Seandainya wayang kulit purwa yang berukuran kecil dicampur dengan wayang kulit purwa yang berukuran besar bukan hal yang mustahil jika sampai terjadi kerusakan. Untuk itu dalam pembuatan wayang kulit purwa ada penggolongan/
pengelompokan tersendiri, diantaranya:
a. Pengelompokan berdasarkan ukuran
b. Pengelompokan berdasarkan aspek Seni Rupa
c. Pengelompokan wayang kulit purwa berdasarkan posisi kaki, dan lain- lain.
a. Pengelompokan Berdasarkan Ukuran
Berdasarkan ukurannya, wayang kulit purwa dikelompokkan menjadi 8 yakni:
1) Buta (Denawa atau Raksasa)
Kelompok buta berukuran tubuh paling besar dibandingkan dengan kelompok lain. Tingginya hampir mencapai 100 cm. Biasanya posisi kakinya memencar atau melebar (njangkah). Buta tidak dipahat ngremit (kecil-kecil), karena tidak ada bagian busana yang harus dipahat demikian.
Contoh antara lain: Kumbakarna, Suratrimantra, Dewa mambang atau Kala Sekipu.
2) Gagahan
Kelompok gagahan berukuran sekitar 60-80 cm tingginya. Seperti halnya dengan kelompok buta, posisi kakinya juga melebar. Tatahannya ada yang ngremit, ada yang tidak. Suyudana termasuk kelompok gagahan yang commit to user
dipahat secara ngremit, sedangkan Dasamuka adalah contoh gagahan yang tatahannya tidak ngremit.
3) Katongan
Termasuk ke dalam kelompok katongan adalah wayang kulit purwa yang tingginya berkisar antara 50-60 cm, pada umumnya menyerupai wayang kulit purwa gagahan dalam hal pakaian atau busana yang dikenakannya.
Pahatan tidak ngremit. Posisi kaki melebar. Contoh tokoh dalam kelompok katongan adalah Gathutkaca, Anoman, Setyaki dan Udawa.
4) Bambangan
Dalam kelompok bambangan, kebanyakan bentuk wayang kulit purwanya tidak melebar kakinya, melainkan sempit jarak antara kedua kakinya.
Ukurannya pun kecil, hamper sama dengan tokoh dalam kelompok katongan, berkisar antara 45-50 cm. Contohnya antara lain: Arjuna, kresna, Wibisana, Nakula dan Sadewa.
5) Bambang Jangkah
Dalam hal ukuran tinggi badan, kelompok ini hampir sama dengan kelompok bambangan. Perbedaannya dalam hal posisi kaki, rata-rata posisi kakinya melebar seperti gagahan. Motif busana bagian bawah menyerupai busana kelompok gagahan, denawa atau katongan.
Contohnya antara lain Wisanggeni, Bambang Irawan, Raden Sumitra, Batara Penyarikan dan Pancawala.
6) Putren
Kelompok putren berukuran tinggi sekitar 25-30 cm dengan tatahan ngremit. Sebagian besar kelompok ini terdiri atas tokoh putri/perempuan.
Posisi kaki merapat, tidak melebar. Misalnya Srikandi, Wara Sumbadra, Dewi Sinta dan Trijatha. Wayang kulit purwa yang ukuran tingginya sama dengan putri/perempuan juga dikategorikan ke dalam kelompok ini, walaupun posisi kakinya melebar. Contohnya antara lain: Dewa Ruci, Sang Hyang Wenang dan Bayen.
commit to user
7) Dhagelan
Sesuai namanya, sebagian tokoh dalam kelompok ini bersifat humoristis dalam pementasan. Ukuran tinggi kelompok dhagelan berkisar antara 35- 45 cm, kecuali pada tokoh Petruk, tingginya sekitar 70 cm. Contoh lain:
Semar, Gareng, Bagong, Bilung, Togog dan Cantrik. Macam pahatan pada busana tokoh dalam kelompok ini boleh dikatakan sederhana, dengan pahatan tidak ngremit.
8) Setanan
Menggambarkan setan, sejenis jin atau makhluk halus. Ukuran tingginya bervariasi antara 25-60 cm. Biasanya tidak bernama (anonym) serta tanpa busana (kalaupun berbusana boleh dikatakan sangat sederhana).
Pahatannya juga sangat sederhana.
(Sagio dan Samsugi, 1988 : 18-19).
b. Pengelompokan Berdasarkan Aspek Seni Rupa
Di tinjau dari aspek seni rupa, gambar wayang kulit purwa, bergaya ekspresif dekoratif tradisional, yang mengambil tokoh-tokoh pelaku bersumber pada Mahabarata dan Ramayana.
Dalam cerita pementasan di tambah tokoh-tokoh pelaku humor yaitu gambar wayang kulit purwa bergaya ekspresif dekoratif humoris karikaturis, atau tokoh dagelan, seperti: Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togog, Sarawita, Cantrik, Cangik dan Limbuk.
Gambar ekspresif yaitu gambar yang terjadi karena cetusan (ekspresi) angan-angan seniman, berupa gambar hiasan dekor atau hiasan bidang.
Perwujudan dan sifat ekspresi dekoratif ini dalam wayang kulit purwa (terutama versi Jawa Tengah), diwujudkan dalam bentuk tangan panjang dan badan panjang.
Wayang kulit purwa atau gambar wayang kulit purwa satu kotak yang terdiri dari kurang lebih 300 buah itu dapat digolongkan menjadi 6 golongan.
1) Wayang kulit purwa ekspresif dekoratif, yaitu wayang kulit purwa yang mengekspresikan perwujudan watak-watak manusia.
Perwujudan watak ini terletak pada: commit to user
- Bentuk posisi dan raut muka.
- Bentuk perbandingan dan posisi tubuh.
Berdasarkan perwatakan ini dogolongkan pada:
- Watak baik.
- Watak buruk.
- Watak setengah baik.
Wayang kulit purwa ekspresif dekoratif, berdasarkan perlengkapan, perabot dan pakaiannya dapat diklasifikasikan lagi menurut kelasnya, yaitu:
- Golongan dewa.
- Golongan pendeta.
- Golongan ksatria.
- Golongan raja.
- Golongan putran (nom-noman), yaitu putera raja semasih muda.
- Golongan putri
- Golongan punggawa/rampekan - Golongan raksasa
- Golongan kera
dan kombinasinya seperti: Raja dewa, Raja kera, Raja raksasa, Raja pendeta, dan sebagainya.
2) Wayang kulit purwa ekspresif dekoratif humoris karikatur, yaitu wayang kulit purwa yang menggambarkan rasa humor (lucu). Jadi gambarnya saja sudah lucu dan dalam bentuk karikatur dapat dibedakan:
- Humoris karikaturis pengikut Ksatria, yaitu: Semar, Gareng, Petruk, Bagong.
- Humoris karikaturis pengikut Raksasa, yaitu: Togok, Sarawito.
- Humoris karikaturis pengikut Dewa, yaitu: Patuk dan Temboro.
- Humoris karikaturis pengikut Pendeta, yaitu: Cantrik Janaloka.
- Humoris karikaturis Wanita, yaitu Cangik dan Limbuk.
3) Wayang kulit purwa merupakan kelompok atau suatu kompleks yang menggambarkan kelompok pasukan atau kompleks tumbuh-commit to user
tumbuhan, binatang dan bangunan, yaitu Perampogak (Ampyakan) dan Gunungan.
4) Wayang kulit purwa yang melukiskan atau menggambarkan binatang dan kendaraan, seperti: kuda, kereta kencana, gajah, naga, burung garuda, dan sebagainya.
5) Wayang kulit purwa yang melukiskan senjata seperti: panah, keris, gada, alugara, senjata cakra, dan sebagainya.
6) Wayang kulit purwa yang melukiskan roh halus berupa siluman, setan, seperti: Jurumeya, Jarameya Keblok, dan sebagainya.
(Soekatno, 1992 : 8-13).
c. Pengelompokan Wayang Kulit Purwa Berdasarkan Posisi Kaki
Berdasarkan posisi kaki, dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut:
1) Wayang Kulit Purwa Jangkahan
Posisi kaki melebar (njangkah) dan biasanya siten-siten (atau lemahan) tampak lebih panjang. Sebagian besar wayang kulit purwa jangkahan merupakan wayang kulit purwa gagahan, buta atau bambang jangkah.
Jarang sekali wayang kulit purwa bambangan yang posisi kakinya njangkah. Contoh wayang kulit purwa yang termasuk dalam kelompok ini misalnya Baladewa, Dasamuka, Bambang Irawan atau Kumbakarna.
2) Wayang Kulit Purwa Bokongan
Wayang kulit purwa dalam kelompok ini posisi kakinya merapat tertutup oleh kain. Biasanya wayang kulit purwa bokongan memang kakinya tidak njangkah, dan pantatnya tampak nyata. Dalam wayang kulit purwa bokongan, sebagian besar merupakan wayang kulit purwa bambangan atau putren. Wayang kulit purwa bokongan ini mempunyai ciri khas, yakni pahatannya kecil-kecil (ngremit) penuh dengan motif rumpilan.
(Sagio dan Samsugi, 1988 : 22).
commit to user
6. Perlambangan/Makna Simbolik dari Wayang Kulit Purwa
Dunia pewayangan adalah paradigma lambang yang tak pernah habis untuk dibicarakan, karena wayang kulit purwa adalah akumulasi penggambaran bentuk lain dari hidup dan kehidupan tidak hanya lakon pokok Ramayana dan Mahabharata, dalam lakon-lakon sempalan dan carangan pun padat akan nilai- nilai perlambangan. Dalam setiap unsur rupa wayang kulit purwa tak ada satupun yang tanpa muatan lambang, bahkan perangkat pendukung juga sarat akan perlambangan, seperti: kelir (layar putih) yang melambangkan denyut jantung, kotak merupakan sangkan paran, cempala lambang jantung dan kecrek atau kepyak melambangkan urat nadi atau jalan darah, kayon atau gunungan lambang hidup dan kehidupan, gamelan bermakna kebutuhan hidup, dalang merupakan cipta sir atau gerak mula kehendak hidup, sedangkan yang nanggap wayang kulit purwa adalah sang Hyang Atina atau jiwa manusia (S. Haryanto, 1995: 176).
Pertunjukan wayang kulit purwa juga mempunyai hubungan erat, sekaligus Mikro dan Makrokosmos. Kita tahu, bahwa manusia (mikro) dan dunia (makro) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena merupakan satu kesatuan.
Dengan kata lain manusia tanpa dunia tidak mungkin, sebaliknya dunia tanpa manusia bukanlah dunia manusia. Hubungan antara dunia (makro) dan manusia (mikro) dalam pewayangan dilukiskan dengan gamblang yaitu: kesatuan antara (kelir beserta gamelan sebagai makro) dengan (wayang kulit purwa beserta dalang sebagai mikro). Artinya, tidak mungkin disebut wayangan apabila kelir (dunia) tanpa wayang (manusia). Sebaliknya wayang tanpa kelir juga tidak dapat disebut wayangan.
Dunia dan manusia itu semula diciptakan dari “tiada” oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dalam dunia pewayangan dilambangkan dengan pendhapa suwung yang kosong tetapi berisi. Begitu juga setelah kelir dibentangkan dan wayangnya disimping (dijajar) maka ditengah-tengah kelir pun masih kosong, tak ada satu wayang pun yang ditancapkan. Tetapi di dalam kosong/suwung itu sudah ada gunungan atau kayon yang berarti kayun atau hidup. Ini pun lambang kosong tetapi berisi. Setelah kayon ditarik ke bawah, maka muncullah wayang kulit purwa pertama yang berwujud parekan disusul wayang kulit purwa raja, kemudian adik commit to user
atau ari-ari raja. Ini semua secara kosmis merupakan suatu lambang kelahiran atau mulainya ada “lakon” (Sri Mulyono, 1979: 111).
7. Proses Kreativitas
Pengertian ataupun definisi kreativitas sangat sulit untuk dibakukan, mengingat banyaknya sudut pandang yang membahas persoalan ini. Sedemikian beragamnya definisi tentang kreativitas hingga menghasilkan anggapan bahwa kreativitas bisa dimaknai bergantung pada bagaimana orang mendefinisikan.
Begitu banyaknya definisi tentang kreativitas tersebut, namun di antara yang banyak tersebut ada benang merah yang merujuk bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas adalah suatu kondisi mental yang sangat khusus sifatnya dan hampir tak mungkin dirumuskan. Kreativitas adalah kegiatan mental yang sangat individual yang merupakan manifestasi kebebasan manusia sebagai individu. (Tjahjo Prabowo & Margono, 2008 : 21-22).
“Manusia kreatif bukanlah manusia kosong mental. Manusia kreatif adalah manusia yang memilih gambaran suatu sikap baru, pandangan baru, konsep baru dan sesuatu yang sifatnya essensial. Manusia kreatif adalah manusia yang mempunyai kemampuan kreatif.
Kemampuan kreatif antara lain ditunjukkan lewat kesigapan menghasilkan gagasan baru. Gagasan baru tersebut akan muncul bila seseorang telah mengenal secara jelas dan tersedia dalam lingkungannya.
Artinya, untuk dapat menghasilkan yang baru orang perlu terlebih dahulu menghayati, memaknai yang lama yang ada disekitar lingkungannya.
Tanpa mengenal dan menguasai budaya di tempat di mana dia hidup tak mungkin muncul gagasan baru. Itulah sebabnya kreativitas tidak mungkin dari sebuah kehampaan atau kekosongan”. (Tjahjo Prabowo & Margono, 2008 : 23-24).
B. Kerangka Berpikir
Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan fisik, kemampuan rasio dan kemampuan kreatif, hanya perbedaannya di batasi oleh gradasi, level, periode dan degree-nya. Kreativitas dimiliki, baik oleh manusia primitif maupun commit to user
manusia modern, baik anak-anak maupun orang dewasa. Untuk menemukan definisi kasta kreatif memang sangatlah sulit, karena kata kreatif sering disinonimkan dengan kata fantasi, imajinasi, orisinal, inventif, intuisi, estetis dan lain sebagainya, namun seiring dengan perkembangan jaman dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli dari jaman ke jaman akhirnya di peroleh kesimpulan sementara (hipotesa) bahwa yang di maksud dengan istilah kreatif adalah sesuatu yang berhubungan dengan proses penciptaan. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang dapat mencipta dan karenanya berkebudayaan. (Primadi, T, 2006 : 50).
“Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang lengkap, yang memiliki kreativitas pasif dan aktif. Kemampuan kreatif manusia adalah kemampuan yang membantunya untuk dapat berbuat lebih dari kemungkinan rasional dari data dan pengetahuan yang dimilikinya”. (Primadi. T, 2006 : 34).
Ki Margono, S.Sn adalah termasuk salah satu manusia kreatif, karena beliau mempunyai kemampuan kreatif dan mempunyai ciri-ciri seperti itu. Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga seniman dalang. Sejak kecil ia sudah mengenal wayang kulit purwa, baik itu dari segi cerita maupun dari segi bentuk visual wayang kulit purwanya, karena selain bapaknya sebagai seorang dalang, bapaknya juga mendirikan tempat kerajinan pembuatan wayang kulit purwa di kampung halamannya di Dusun Bulu, Desa Punduhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Kota tersebut memang sangat terkenal sebagai sentra kerajinan wayang kulit purwa.
Di tempa dengan keadaan lingkungan masa kecilnya yang sudah sangat akrab dengan berbagai bentuk visual wayang kulit purwa, kemudian ia bersekolah ke SMSR Surakarta jurusan Seni Rupa sehingga bertambahlah wawasannya mengenai keindahan-keindahan/estetik Seni Rupa. Hal ini menjadikan salah satu alasan mengapa ia berani berkreasi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru dari wayang kulit purwa yang sudah ada. Sewaktu menciptakan, ia memiliki ide-ide yang akan dituangkan dalam bentuk karyanya. Berbekal dengan ilmu yang dimilikinya ia berusaha berkreativitas dengan ide-ide yang dimilikinya tersebut.
commit to user
Dalam proses pelaksanaan pengerjaan wayang kulit purwa kreasi barunya tersebut kadang berjalan lancar tanpa hambatan hingga dapat mewujudkan sebuah karya, tetapi kadang juga mengalami hambatan karena adanya sesuatu hal, untuk itu ia harus mengolah pikir/menemukan ide kembali agar karyanya dapat berhasil dengan lancar/baik.
Agar kerangka berpikir ini menjadi lebih jelas, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:
Bagan 2. 1. Kerangka Berpikir Latar Belakang Ki Margono, S.Sn
Ide
Proses Kreativitas
Tanpa Hambatan/ada faktor pendukung
Ada Hambatan
Karya
commit to user