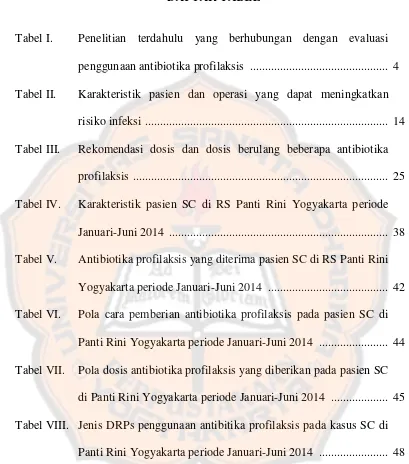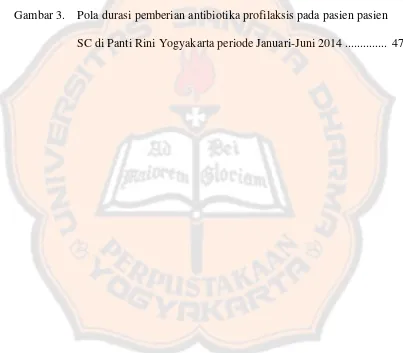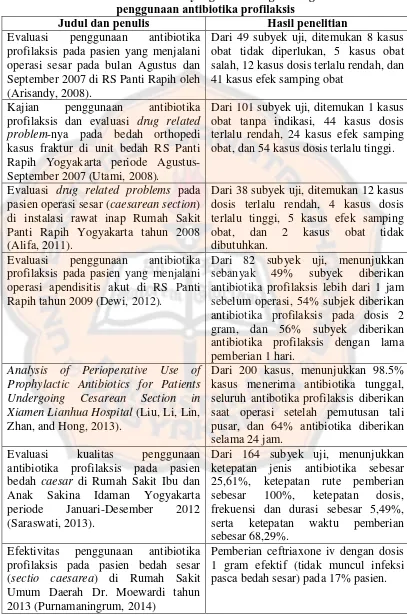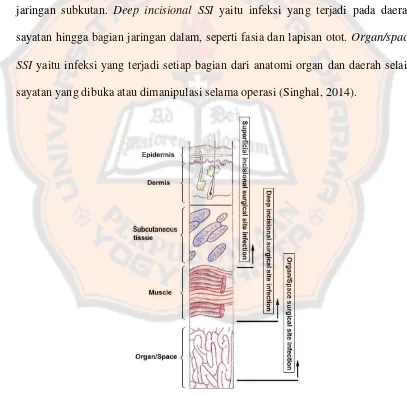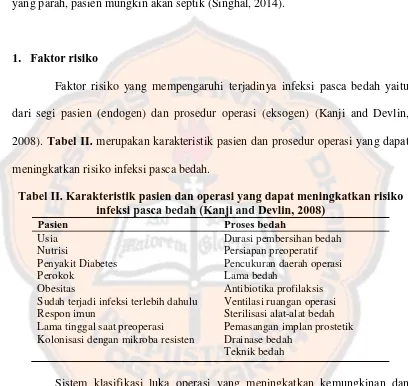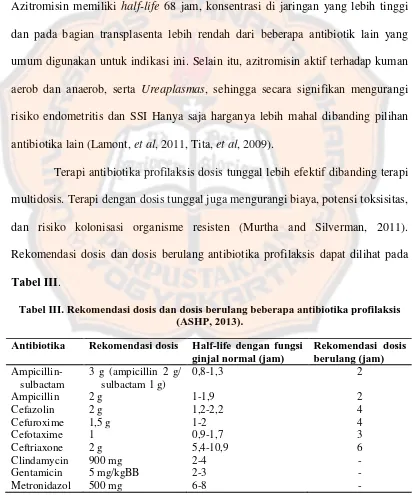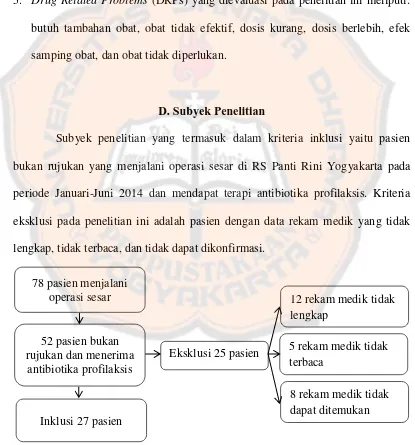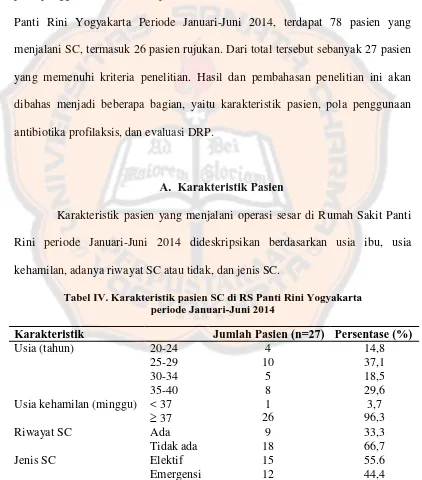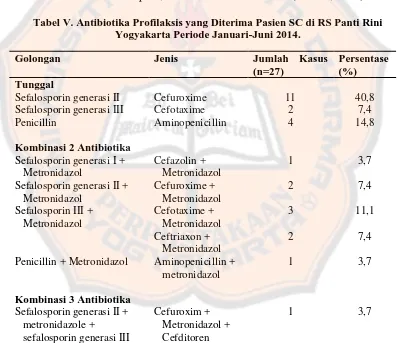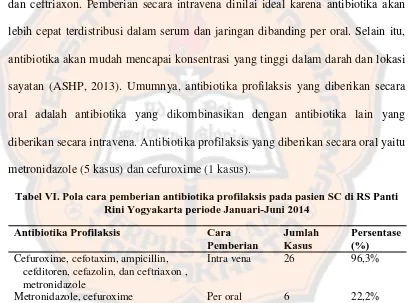INTISARI
Peningkatan kejadian operasi sesar (sectio caesarea) diikuti pula dengan tingginya risiko infeksi pasca operasi. Ketepatan penggunaan antibiotika profilaksis menjadi salah satu kunci penting untuk meminimalkan infeksi tersebut. Tingginya penggunaan antibiotika sebagai profilaksis bedah khususnya pada operasi sesar memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi drug related problems (DRPs) pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus operasi sesar.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan case series yang bersifat retrospektif dengan menggunakan lembar rekam medik. Kriteria inklusi penelitian ini yaitu pasien bukan rujukan yang menjalani operasi sesar di RS Panti Rini Yogyakarta pada bulan Januari hingga Juni 2014 dan mendapat terapi antibiotika profilaksis. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan data rekam medik yang tidak lengkap, tidak terbaca, dan tidak dapat dikonfirmasi. Adanya drug related problems diidentifikasi menggunakan metode SOAP (Subyek, Obyek, Assessement, Plan/ recommendation). Faktor-faktor pemilihan antibiotika profilaksis diperoleh dengan melakukan wawancara.
Terdapat 27 pasien yang memenuhi kriteria penelitian sebagai subjek penelitian. Evaluasi DRPs penggunaan antibiotika profilaksis menunjukkan adanya 1 kasus obat tidak diperlukan, 7 kasus obat tidak efektif, 27 kasus dosis kurang, 27 dosis berlebih, 14 kasus butuh tambahan obat, dan 13 kasus efek samping obat.
ABSTRACT
An increasing of caesarean section (sectio caesarea) is followed by a high risk of infection that came after surgery. Accuracy of the use of prophylaxis antibiotic becomes one important key to minimize the infection. The high use of antibiotic as surgical prophylaxis especially in caesarean section may leads to some problems. This research aimed to identify drug related problems (DRPs) of the use prophylaxis antibiotics in caesarean section cases.
This research was an observational research with case series design, retrospectively using medical record sheets. Inclusion criteria of this research were patients who had caesarean section at RS Panti Rini Yogyakarta in January to June 2014 and received prophylaxis antibiotics. Exclusion criteria were incomplete and difficult to read medical records. Analyze of DRPs was identified using SOAP (Subject, Object, Assessment, and Plan/ recommendation) method. Factors of prophylaxis antibiotic selection were obtained by interviews.
There were 27 patients to be subjects which according to the criteria. Evaluation DRPs of the use of prophylaxis antibiotic showed one case of unnecessary drug, 7 cases of ineffective drug, 27 cases of dose to low, 27 cases of dose to high, 14 cases of need additional therapy, and 13 cases of potential adverse drug reaction.
EVALUASI DRUG RELATED PROBLEMS (DRPs) PADA PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PROFILAKSIS
UNTUK KASUS SECTIO CAESAREA (SC)
DI RS PANTI RINI YOGYAKARTA PERIODE JANUARI-JUNI 2014
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)
Program Studi Farmasi
Oleh:
Jessica Christy Sitio
NIM: 118114140
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
i
EVALUASI DRUG RELATED PROBLEMS (DRPs) PADA PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PROFILAKSIS
UNTUK KASUS SECTIO CAESAREA (SC)
DI RS PANTI RINI YOGYAKARTA PERIODE JANUARI-JUNI 2014
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)
Program Studi Farmasi
Oleh:
Jessica Christy Sitio
NIM: 118114140
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
ii
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Sebab Aku ini mengetahui rancangan
-rancangan apa yang
ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman TUHAN,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang
penuh harapan.
Yeremia 29:11
“I tried to do my best To do the best I could I had to give my all It's what I had to do And I'd do it all again
And that's the honest truth I did it for you” (I Did It For You –Westlife)
Kupersembahkan untuk: Tuhanku Yesus Kristus Babe, Mama, dan kakak terkasihku
vii
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Evaluasi Drug Related Problems (DRPs) pada Penggunaan Antibiotika
Profilaksis untuk Kasus Sectio Caesarea (SC) di RS Panti Rini Yogyakarta
Periode Januari-Juni 2014” sebagai salah salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) program studi Farmasi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan dari banyak pihak. Karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada:
1. Direktur RS Panti Rini Yogyakarta atas ijin yang telah diberikan kepada
penulis untuk melakukan penelitian di RS Panti Rini Yogyakarta
2. Kepala Apoteker, Kepala Personalia, dan Kepala Rekam Medik berserta
seluruh masing-masing staf bagian di RS Panti Rini Yogyakarta atas arahan
dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengambilan
data.
3. Ibu Aris Widayati, M.Si., Apt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma sekaligus dosen pembimbing skripsi atas
bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan
viii
4. Ibu dr. Fenty, M.Kes., Sp.PK, dan Ibu Dita Maria Virginia, S.Farm., Apt.,
M.Sc. sebagai dosen penguji atas kritik dan saran yang membangun yang
diberikan selama penyelesaian skripsi.
5. Kedua orangtua, Sudirman Sitio, S.H. dan Osna Simatupang serta kakak
tercinta, Eva Yulia Janice atas kasih sayang, doa, dukungan, arahan, dan
pengertian serta berbagai bantuan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
ini.
6. Teman-teman seperjuangan DeRealPrincesses, Adel, Anes, dan Lulik atas
kerjasama, bantuan, dan informasi yang selalu dibagikan dalam proses
penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Dodi Setiawan atas doa, dukungan, pengertian dan bantuan yang diberikan
selama penyusunan skripsi ini.
8. Rika Nofitasari, AMd.Keb. dan Almas Azifa Dina, AMd.Keb. atas
informasi, semangat, dan bantuan yang diberikan selama penyelesaian
skripsi ini.
9. Teman-teman FSM D, FKK B, dan angkatan 2011, serta teman-teman
lainnya yang menemani penulis dalam berbagai kegiatan selama menempuh
perkuliahan jenjang S1 yang telah berbagi cerita, semangat, dan berbagai
ilmu yang mendukung dalam penyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang secara
langsung maupun tidak langsung turut serta membantu kelancaran penulis
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi
PRAKATA ... vii
DAFTAR ISI ... x
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ... xv
INTISARI ... xvi
ABSTRACT ... xvii
BAB I PENGANTAR ... 1
A. Latar Belakang ... 1
1. Perumusan Masalah ... 3
2. Keaslian Penelitian ... 3
3. Manfaat Penelitian ... 5
B. Tujuan Penelitian ... 5
1. Tujuan Umum ... 5
xi
BAB II PENELAAHAN PUSTAKA ... 7
A. Sectio Caesarea ... 7
B. Infeksi Pasca SC ... 8
1. Faktor Risiko ... 14
2. Pencegahan ... 15
C. Antibiotika Profilaksis ... 16
1. Prinsip Penggunaan ... 17
2. Klasifikasi Antibiotika Profilaksis ... 21
3. Rekomendasi Penggunaan Antibiotika Profilaksis Untuk Sectio Cesarea ... 22
D. Drug Related Problems (DRPs) ... 26
E. Keterangan Empiris ... 28
BAB III METODE PENELITIAN ... 29
A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 29
B. Variabel ... 29
C. Definisi Operasional ... 29
D. Subjek Penelitian ... 30
E. Bahan Penelitian ... 31
F. Instrumen Penelitian ... 31
G. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 31
H. Tata Cara Penelitian ... 32
1. Tahap Persiapan ... 32
xii
3. Tahap Pengumpulan ... 33
4. Tahap Analisis Data ... 33
I. Tata Cara Analisis Hasil ... 34
1. Karakteristik Pasien ... 34
2. Profil Penggunaan Antibiotika Profilaksis ... 34
3. Drug Related Problems (DRPs) ... 36
J. Keterbatasan Penelitian ... 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 38
A. Karakteristik Pasien ... 38
B. Pola Penggunaan Antibiotika Profilaksis ... 40
C. Evaluasi Drug Related Problems (DRPs) ... 47
1. Obat tidak diperlukan ... 48
2. Obat tidak efektif ... 48
3. Dosis kurang ... 50
4. Dosis berlebih ... 52
5. Perlu tambahan obat ... 53
6. Efek samping obat ... 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 56
A. Kesimpulan ... 56
B. Saran ... 57
DAFTAR PUSTAKA ... 59
LAMPIRAN ... 64
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel I. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan evaluasi
penggunaan antibiotika profilaksis ... 4
Tabel II. Karakteristik pasien dan operasi yang dapat meningkatkan
risiko infeksi ... 14
Tabel III. Rekomendasi dosis dan dosis berulang beberapa antibiotika
profilaksis ... 25
Tabel IV. Karakteristik pasien SC di RS Panti Rini Yogyakarta periode
Januari-Juni 2014 ... 38
Tabel V. Antibiotika profilaksis yang diterima pasien SC di RS Panti Rini
Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 42
Tabel VI. Pola cara pemberian antibiotika profilaksis pada pasien SC di
Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 44
Tabel VII. Pola dosis antibiotika profilaksis yang diberikan pada pasien SC
di Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 45
Tabel VIII. Jenis DRPs penggunaan antibitika profilaksis pada kasus SC di
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Surgical Site Infection berdasarkan tempat terjadinya infeksi ... 12
Gambar 2. Pola waktu pemberian antibiotika profilaksis pada pasien pasien
SC di Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 46
Gambar 3. Pola durasi pemberian antibiotika profilaksis pada pasien pasien
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Analasis Drug Related Problems (DRPs) pada Penggunaan
Antibiotika Profilaksis untuk Kasus Sectio Caesarea (SC) di RS
Panti Rini Yogyakarta Periode Januari-Juni 2014 ... 65
Lampiran 2. Hasil Wawancara Peneliti dengan Apoteker Di Rumah Sakit
Panti Rini Mengenai Peresepan Antibiotika Profilaksis untuk
SC ... 92
Lampiran 3. Hasil Wawancara Peneliti dengan Salah Satu Dokter Bedah SC
Di Rumah Sakit Panti Rini Mengenai Peresepan Antibiotika
xvi
INTISARI
Peningkatan kejadian operasi sesar (sectio caesarea) diikuti pula dengan tingginya risiko infeksi pasca operasi. Ketepatan penggunaan antibiotika profilaksis menjadi salah satu kunci penting untuk meminimalkan infeksi tersebut. Tingginya penggunaan antibiotika sebagai profilaksis bedah khususnya pada operasi sesar memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi drug related problems (DRPs) pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus operasi sesar.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan case series yang bersifat retrospektif dengan menggunakan lembar rekam medik. Kriteria inklusi penelitian ini yaitu pasien bukan rujukan yang menjalani operasi sesar di RS Panti Rini Yogyakarta pada bulan Januari hingga Juni 2014 dan mendapat terapi antibiotika profilaksis. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan data rekam medik yang tidak lengkap, tidak terbaca, dan tidak dapat dikonfirmasi. Adanya drug related problems diidentifikasi menggunakan metode SOAP (Subyek, Obyek, Assessement, Plan/ recommendation). Faktor-faktor pemilihan antibiotika profilaksis diperoleh dengan melakukan wawancara.
Terdapat 27 pasien yang memenuhi kriteria penelitian sebagai subjek penelitian. Evaluasi DRPs penggunaan antibiotika profilaksis menunjukkan adanya 1 kasus obat tidak diperlukan, 7 kasus obat tidak efektif, 27 kasus dosis kurang, 27 dosis berlebih, 14 kasus butuh tambahan obat, dan 13 kasus efek samping obat.
xvii
ABSTRACT
An increasing of caesarean section (sectio caesarea) is followed by a high risk of infection that came after surgery. Accuracy of the use of prophylaxis antibiotic becomes one important key to minimize the infection. The high use of antibiotic as surgical prophylaxis especially in caesarean section may leads to some problems. This research aimed to identify drug-related problems (DRPs) of the use prophylaxis antibiotics in caesarean section cases.
This research was an observasional research with case series design, retrospectively using medical record sheets. Inclusion criteria of this research were patients who had caesarean section at RS Panti Rini Yogyakarta in January to June 2014 and received prophylaxis antibiotics. Exclusion criteria were incomplete and difficult to read medical records. Analyze of DRPs was identified using SOAP (Subject, Object, Assessement, and Plan/ recommendation) method. Factors of prophylaxis antibiotic selection were obtained by interviews.
There were 27 patients to be subjects which according to the criteria. Evaluation DRPs of the use of prophylaxis antibiotic showed one case of unnecessary drug, 7 cases of ineffective drug, 27 cases of dose to low, 27 cases of dose to high, 14 cases of need additional therapy, and 13 cases of potential adverse drug reaction.
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Angka kejadian sectio caesarea (SC) di seluruh dunia tinggi dan terus
mengalami peningkatan terutama pada negara-negara berkembang. Di Indonesia,
secara umum proporsi kelahiran dengan SC yaitu sebesar 9,8%. Untuk daerah
provinsi DI Yogyakarta sendiri proporsi kelahiran melalui SC mencapai
15%-20%. Angka ini menempati urutan keempat tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta,
Kepulauan Riau, dan Bali (Kemenkes RI, 2013; Lauer, et al., 2010).
Sectio caesarea atau yang lebih dikenal dengan operasi sesar merupakan
operasi yang memiliki potensi yang besar dalam proses kelahiran khususnya
untuk kasus kelahiran yang tidak memungkinkan melalui jalur vaginam. Akan
tetapi, jalur ini juga tidak lepas dari risiko mortalitas dan morbiditas yang besar
bagi ibu dan bayi. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien pasca SC
adalah infeksi (Khan, 2006). Persalinan dengan SC memiliki risiko infeksi hingga
80 kali lebih tinggi dari persalinan per vaginam. Pencegahan infeksi pada luka
operasi tersebut dapat dilakukan dengan pemberian antibiotika profilaksis
(Pernoll, 2001).
Penggunaan antibiotika sebanyak 33%-50% di rumah sakit ditujukan
sebagai profilaksis bedah. Sebanyak 30%-90% penggunaan tersebut tidak tepat,
terutama pada waktu pemberian dan durasi. Intensitas penggunaan antibiotika
Selain risiko morbiditas dan mortalitas, permasalahan resistensi bakteri terhadap
antibiotika juga menjadi ancaman. Tingginya insiden resistensi antibiotika di
seluruh dunia memiliki dampak yang signifikan terhadap masalah kesehatan
masyarakat, terutama pada masalah dalam terapi (Radji, Aini, and Fauziyah,
2014; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
Masalah yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu pencapaian
tujuan terapi dikenal dengan drug related problems (DRPs). Masalah tersebut
dapat terjadi secara aktual maupun potensial. DRPs aktual merupakan masalah
yang sedang terjadi berkaitan dengan terapi yang sedang diberikan pada pasien.
DRPs potensial merupakan masalah yang diperkirakan akan terjadi berkaitan
dengan terapi yang sedang diberikan pada pasien. Kategori DRPs meliputi obat
tidak diperlukan, perlu obat tambahan, obat tidak efektif, dosis rendah, efek
samping obat, dosis berlebih, dan kepatuhan pasien (Cipolle, Strand, Morley,
Ramsey, and Lamsam 2004).
Rumah Sakit Panti Rini merupakan rumah sakit swasta tipe D yang
terletak di kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rumah sakit ini melayani persalinan
dengan operasi sesar dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk operasi
sesar. Setidaknya pada bulan Januari hingga Juni 2014 tercatat ada 78 kejadian
operasi sesar termasuk pasien rujukan (Surveilans RS Panti Rini, 2014).
Evaluasi DRPs merupakan bagian dari tugas kefarmasian sebagai
penerapan pharmaceutical care. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan
evaluasi DRPs pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus (SC) di RS
dapat membantu memaparkan sekaligus memecahkan masalah terkait antibiotika
profilaksis khususnya pada kasus persalinan dengan cara operasi sesar.
1. Perumusan masalah
a. Seperti apakah karakteristik pasien sectio caesarea (SC) yang meliputi
usia ibu, usia kehamilan, riwayat SC, dan jenis SC?
b. Seperti apakah pola penggunaan antibiotika profilaksis untuk pasien SC
yang meliputi jenis antibiotika, waktu pemberian, cara pemberian, dosis,
dan durasi pemberiannya?
c. Apakah terdapat drug related problems (DRPs) meliputi butuh tambahan
obat, obat tidak diperlukan, obat tidak efektif, dosis kurang, dosis berlebih,
dan efek samping obat?
2. Keaslian penelitian
Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penelitian mengenai
evaluasi drug related problem pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk
kasus sectio caesarea di Rumah Sakit Sakit Panti Rini Yogyakarta periode
Januari-Juni 2014 belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian sejenis dan
berhubungan dengan evaluasi penggunaan antibiotika profilaksis yang pernah
Tabel I.Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan evaluasi penggunaan antibiotika profilaksis
Judul dan penulis Hasil penelitian
Evaluasi penggunaan antibiotika
profilaksis pada pasien yang menjalani operasi sesar pada bulan Agustus dan September 2007 di RS Panti Rapih oleh (Arisandy, 2008).
Dari 49 subyek uji, ditemukan 8 kasus obat tidak diperlukan, 5 kasus obat salah, 12 kasus dosis terlalu rendah, dan 41 kasus efek samping obat
Kajian penggunaan antibiotika
profilaksis dan evaluasi drug related problem-nya pada bedah orthopedi kasus fraktur di unit bedah RS Panti Rapih Yogyakarta periode Agustus-September 2007 (Utami, 2008).
Dari 101 subyek uji, ditemukan 1 kasus obat tanpa indikasi, 44 kasus dosis terlalu rendah, 24 kasus efek samping obat, dan 54 kasus dosis terlalu tinggi.
Evaluasi drug related problems pada pasien operasi sesar (caesarean section) di instalasi rawat inap Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2008 (Alifa, 2011).
Dari 38 subyek uji, ditemukan 12 kasus dosis terlalu rendah, 4 kasus dosis terlalu tinggi, 5 kasus efek samping
obat, dan 2 kasus obat tidak
dibutuhkan.
Evaluasi penggunaan antibiotika
profilaksis pada pasien yang menjalani operasi apendisitis akut di RS Panti Rapih tahun 2009 (Dewi, 2012).
Dari 82 subyek uji, menunjukkan
sebanyak 49% subyek diberikan
antibiotika profilaksis lebih dari 1 jam sebelum operasi, 54% subjek diberikan antibiotika profilaksis pada dosis 2 gram, dan 56% subyek diberikan antibiotika profilaksis dengan lama pemberian 1 hari.
Analysis of Perioperative Use of Prophylactic Antibiotics for Patients Undergoing Cesarean Section in Xiamen Lianhua Hospital (Liu, Li, Lin, Zhan, and Hong, 2013).
Dari 200 kasus, menunjukkan 98.5% kasus menerima antibiotika tunggal, seluruh antibotika profilaksis diberikan saat operasi setelah pemutusan tali pusar, dan 64% antibiotika diberikan selama 24 jam.
Evaluasi kualitas penggunaan
antibiotika profilaksis pada pasien bedah caesar di Rumah Sakit Ibu dan
Anak Sakina Idaman Yogyakarta
periode Januari-Desember 2012
(Saraswati, 2013).
Dari 164 subyek uji, menunjukkan ketepatan jenis antibiotika sebesar 25,61%, ketepatan rute pemberian
sebesar 100%, ketepatan dosis,
frekuensi dan durasi sebesar 5,49%, serta ketepatan waktu pemberian sebesar 68,29%.
Efektivitas penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien bedah sesar (sectio caesarea) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tahun 2013 (Purnamaningrum, 2014)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Perbedaan
terletak pada tempat penelitian, periode data yang diteliti, hal yang diteliti, dan
metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di RS Panti Rini dengan menggunakan
data rekam medik periode Januari-Juni 2014. Hal yang diteliti pada penelitian ini
adalah evaluasi DRPs penggunaan antibiotika profilaksis pada SC. Perbedaan
metode penelitian pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas yaitu
pada metode penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan adalah case
series dan terdapat tahap uji coba instrumen.
3. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber
informasi mengenai penggunaan antibiotika profilaksis khususnya pada
prosedur SC.
b. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi bagi farmasis dan tenaga kesehatan lainnya terkait penggunaan
antibiotika profilaksis untuk SC sehingga dapat meningkatkan kualitas
terapi.
B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi drug related problems
(DRPs) pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus sectio caesarea (SC)
2. Tujuan Khusus
a. Memberi gambaran karakteristik pasien SC yang meliputi usia ibu, usia
kehamilan, riwayat SC, dan jenis SC.
b. Mengidentifikasi pola peresepan antibiotika pada pasien meliputi jenis,
waktu pemberian, cara pemberian, dosis, dan durasi pemberian.
c. Mengevaluasi DRPs meliputi butuh tambahan obat, obat tidak diperlukan,
7
BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Sectio Caesarea
Operasi sesar atau sectio caesarea (SC) adalah prosedur pembedahan di
mana sayatan dibuat melalui perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk
mengeluarkan bayi. Sayatan dibuat baik secara horisontal maupun vertikal di
dalam rahim. Pada beberapa kondisi, kecil kemungkinannya untuk mencoba
melahirkan melalui vagina di kehamilan berikutnya (Thapa, et al., 2012).
Operasi sesar dapat dilakukan atas permintaan pasien dengan
pertimbangan tenaga medis. Pada umumnya operasi sesar dilakukan bila
persalinan tidak dapat dilakukan melalui vagina. Disproporsi sefalopelvik, sudah
pernah melakukan operasi sesar sebelumnya, gawat janin, dan prolaps tali adalah
beberapa indikasi umum dari kelahiran sesar (Shamna, Kalaichelvan, Marickar,
and Deepu, 2014).
Keputusan untuk melakukan SC didasarkan pada pertimbangan
keamanan. Pada kondisi tertentu, operasi sesar lebih aman untuk ibu dan bayi
daripada persalinan normal. Beberapa pertimbangan sehingga dokter memutuskan
untuk melakukan operasi sesar menurut Mayo Clinic Staff (2012), yaitu:
1. Persalinan normal tidak berjalan dengan lancar.
2. Bayi tidak mendapatkan cukup oksigen.
4. Bayi kembar; kembar tiga atau lebih.
5. Ada masalah dengan plasenta pasien
6. Ada masalah dengan tali pusar.
7. Ibu memiliki masalah kesehatan, seperti penyakit jantung yang tidak stabil
atau tekanan darah tinggi, dan infeksi yang dapat ditularkan kepada bayi
selama persalinan pervaginam seperti herpes genital atau HIV.
8. Bayi memiliki masalah kesehatan, misalnya hidrosefalus.
9. Riwayat sesar sebelumnya.
Risiko yang mungkin terjadi setelah persalinan dengan operasi sesar
adalah infeksi. Infeksi pada atau di sekitar lokasi sayatan umum terjadi pasca
operasi, termasuk operasi sesar. Infeksi pasca operasi sesar dapat berupa infeksi
endometritis yang merupakan peradangan dan infeksi pada selaput yang melapisi
rahim (Mayo Clinic Staff, 2012).
B. Infeksi Pasca SC
Infeksi adalah masuknya mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan
jamur yang mampu menyebabkan trauma atau kerusakan pada tubuh atau
jaringan. Mikroorganisme penginfeksi dapat muncul pada kulit atau jaringan
lunak. Bakteri dapat menimbulkan beberapa efek patogennya dengan melepaskan
beberapa senyawa, antara lain enzim (misalnya hemolisin, streptokinase,
hialuronidase), eksotoksin yang dilepaskan terutama Gram positif (misalnya
tetanus, difteri), atau endotoksin berupa lipopolisakaridase (LPS) dilepaskan dari
Infeksi pasca persalinan umum terjadi setelah operasi sesar. Infeksi dapat
terjadi pada luka bekas sayatan operasi yang disebut dengan surgical site infection
(SSI) yang ditandai dengan gejala inflamasi seperti, demam, kemerahan, nyeri,
dan bengkak khususnya pada daerah bekas sayatan. Adanya nanah atau pus,
purulen dari luka, ditemukannya bakteri yang diisolasi dari cairan tersebut, dan
kenaikan nilai leukosit dalam darah, khususnya netrofil juga menjadi tandab
adanya infeksi (Singhal, 2014).
Sumber infeksi utama pada sebagian besar kejadian infeksi luka operasi
adalah mikroorganisme endogen yang ada pada pasien itu sendiri. Semua pasien
memiliki koloni bakteri, jamur dan virus sampai dengan 3 juta kuman per
sentimeter persegi kulit, namun tidak semua pasien memiliki koloni bakteri,
jamur dan virus dalam jumlah berimbang. Setiap luka operasi akan terkontaminasi
oleh mikroorganisme selama operasi, tetapi hanya sebagian kecil yang akan
mengalami infeksi. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasien memiliki
pertahanan dalam mengendalikan dan mengeleminasi mikroorganisme penyebab
infeksi (Guyton, 2007).
Dengan adanya sayatan bedah melalui kulit dan masuk ke jaringan
subkutan, prekursor inflamasi manusia diaktifkan. Protein koagulasi dan trombosit
pada awalnya diaktifkan sebagai bagian dari mekanisme hemostatik manusia,
selanjutnya keduanya menjadi penanda timbulnya peradangan. Sel mast beserta
protein pelengkap, bradikinin, prostaglandin, dan prekursor inflamasi lainnya
diaktifkan. Efek dari faktor-faktor ini adalah vasodilatasi dan peningkatan aliran
dan gejala hangat lokal. Prostaglandin sendiri menciptakan gejala nyeri pada
daerah sayatan. Terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan
vasodilatasi lokal menyebabkan terbentuknya edema dan peningkatan ruang
antara sel-sel endotel. Peningkatan permeabilitas vaskuler memfasilitasi akses
fagosit pada jaringan lunak yang terluka, sementara edema menyediakan saluran
cairan untuk navigasi fagosit melalui jaringan ekstraseluler. Produk aktivasi dari 5
peristiwa inisiasi (kemerahan, hangat, nyeri, bengkak, dan kehilangan fungsi)
adalah hasil produksi sinyal chemoattractant spesifik, sementara sel-sel mast
menghasilkan sinyal kemokin tertentu yang menarik neutrofil tertentu, monosit,
dan leukosit ke daerah sayatan. Jadi, cedera jaringan dari sayatan telah
memobilisasi fagosit ke dalam luka sebelum kontaminasi bakteri dari operasi
terjadi. Proses ini merupakan pertahanan host bawaan sebelum kontaminasi
intraoperatif terjadi, dan memberikan pasien keuntungan terhadap pertahanan
infeksi (Fry, 2003).
Dalam beberapa jam setelah peradangan dimulai, sejumlah besar netrofil
dari darah mulai menginvasi daerah yang meradang. Hal ini disebabkan oleh
produk yang berasal dari jaringan yang meradang dan memicu beberapa reaksi.
Pertama, produk tersebut mengubah permukaan bagian dalam endotel kapiler,
menyebabkan netrofil melekat pada dinding kapiler di area yang meradang. Efek
ini disebut marginasi. Produk tersebut juga menyebabkan longgarnya perlekatan
interseluler antara sel endotel kapiler dan sel endotel vanula kecil sehingga
terbuka cukup lebar, dan memungkinkan netrofil untuk melewatinya dengan cara
lainnya juga menyebabkan kemotaksis netrofil menuju jaringan yang cedera.
Dalam waktu beberapa jam setelah dimulainya kerusakan jaringan, tempat
tersebut akan diisi oleh netrofil yang siap untuk membunuh mikroorganisme dan
menyingkirkan bahan-bahan asing. Dalam waktu beberapa jam sesudah
dimulainya radang akut yang berat, jumlah netrofil di dalam darah kadang-kadang
menigkat sebanyak 4-5 kali lipat menjadi 15.000-25.000 netrofil per mikroliter.
Keadaan ini disebut netrofilia (Guyton, 2007).
Bersama dengan invasi netrofil, monosit dari darah akan memasuki
jaringan yang meradang dan membesar menjadi makrofag. Setelah menginvasi
jaringan yang meradang, monosit masih merupakan sel imatur, dan memerlukan
waktu 8 jam atau lebih untuk berkembang ke ukuran yang jauh lebih besar dan
membentuk lisosom dalam jumlah yang sangat banyak, barulah kemudian
mencapai kapasitas penuh sebagai makrofag jaringan untuk proses fagositosis.
Setelah beberapa hari hingga minggu, makrofag datang dan mendominasi sel-sel
fagositik di area yang meradang (Guyton, 2007).
Perjalanan infeksi baru dimulai jika ada jalur masuk (port d’entry). Lalu
setelah melewati masa inkubasi yaitu waktu dimana agen infeksi masuk ke dalam
tubuh sampai munculnya gejala awal infeksi maka penderita akan mengalami fase
inflamasi akut. Makrofag dan netrofil yang merupakan hasil dari inflamasi serta
antibodi yang hadir setelah bakteri menginfeksi mampu melisiskan bakteri dengan
mengikutsertakan komplemen, atau mengakibatkan fagositosis (Fry, 2003).
Bila netrofil dan makrofag menelan sejumlah besar bakteri dan jaringan
Sesudah beberapa hari, di dalam jaringan yang meradang akan terbentuk rongga
yang mengandung berbagai bagian jaringan nekrotik, netrofil mati, makrofag
mati, dan cairan jaringan. Campuran itu disebut pus (Guyton, 2007).
Berdasarkan tempat terjadinya, SSI diklasifikasikan menjadi tiga yaitu
superficial incisional, deep incisional, dan organ/space. Superficial incisional SSI
yaitu infeksi yang terjadi pada daerah sayatan namun hanya pada bagian kulit dan
jaringan subkutan. Deep incisional SSI yaitu infeksi yang terjadi pada daerah
sayatan hingga bagian jaringan dalam, seperti fasia dan lapisan otot. Organ/space
SSI yaitu infeksi yang terjadi setiap bagian dari anatomi organ dan daerah selain
sayatan yang dibuka atau dimanipulasi selama operasi (Singhal, 2014).
Risiko infeksi pasca operasi sesar selain SSI adalah endometritis.
Endometritis merupakan infeksi pada lapisan rahim yang biasanya diidentifikasi
dengan demam, malaise, takikardi, nyeri perut, nyeri pada uterus, terkadang lokia
yang abnormal atau berbau busuk. Demam juga bisa menjadi satu-satunya gejala
endometritis. Endometritis telah dilaporkan terjadi pada 24% pasien SC elektif
dan 60% pada pasien SC non-elektif atau emergensi (ASHP, 2013).
Cairan vagina dengan flora bakteri ditarik ke dalam rahim ketika rileks
antara kontraksi selama proses persalinan. Yang termasuk flora normal vagina
tersebut yaitu streptokokus, enterokokus, laktobasil, diphtheroid, E.coli, spesies
Bacteroides (misalnya, Bacteroides Vibius, B. fragilis), dan spesies
Fusobacterium. Endometritis sering disebabkan oleh polimikroba biasanya
streptokokus aerobik (terutama kelompok basil streptokokus dan enterokokus),
aerob Gram negatif (terutama E.coli), basil anaerob Gram negatif (terutama B.
bivius), dan kokus anaerob (spesies Peptococcus dan Peptostreptococcus) (ASHP,
2013).
Infeksi pada endometrium biasanya merupakan hasil dari infeksi yang
berasal dari saluran kelamin yang posisinya lebih rendah dari endometrium.
Endometritis lebih sering terjadi sebagai infeksi akut. Endometritis akut ditandai
dengan adanya neutrofil dalam kelenjar endometrium. Endometritis kronis
ditandai dengan adanya sel-sel plasma dan limfosit dalam stroma endometrium
(Rivlin,2015).
Gejala dan tanda infeksi endometrium pada obstetrik diantaranya demam
nyeri perut bagian bawah, takikardia, nyeri rahim, suhu oral 38°C dalam 10 hari
pertama postpartum atau 38,7°C dalam 24 jam pertama postpartum. Dalam kasus
yang parah, pasien mungkin akan septik (Singhal, 2014).
1. Faktor risiko
Faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya infeksi pasca bedah yaitu
dari segi pasien (endogen) dan prosedur operasi (eksogen) (Kanji and Devlin,
2008). Tabel II. merupakan karakteristik pasien dan prosedur operasi yang dapat meningkatkan risiko infeksi pasca bedah.
Tabel II.Karakteristik pasien dan operasi yang dapat meningkatkan risiko infeksi pasca bedah (Kanji and Devlin, 2008)
Pasien Proses bedah
Sistem klasifikasi luka operasi yang meningkatkan kemungkinan dan
tingkat kontaminasi bakteri selama prosedur pembedahan dibagi menjadi empat
kelas operasi, yaitu operasi bersih, operasi bersih terkontaminasi, operasi
terkontaminasi, dan operasi kotor. Operasi bersih yaitu operasi pada keadaan
prabedah tanpa adanya luka atau operasi yang melibatkan luka steril dan
dilakukan dengan memerhatikan prosedur aseptik dan antiseptik. Pada operasi ini,
Kemungkinan terjadi infeksi pasca bedah ini yaitu 2-4%. Operasi bersih
terkontaminasi mirip dengan operasi bersih namun daerah saluran napas dan
kemih terlibat dalam pembedahan. Operasi terkontaminasi yaitu operasi yang
dikerjakan pada daerah dengan luka yang telah terjadi 6-10 jam dengan atau tanpa
benda asing. Telah jelas terdapat kontaminasi karena saluran napas, cerna, atau
kemih dibuka. Tindakan darurat yang mengabaikan prosedur aseptik-antiseptik
termasuk dalam klasifikasi operasi ini. Kemungkinan terjadinya infeksi pada
prosedur seperti ini 16-25%. Operasi kotor merupakan operasi yang melibatkan
daerah dengan luka terbuka yang telah terjadi lebih dari 10 jam dan biasanya
merupakan tindakan darurat (Darmadi, 2008).
Faktor risiko lain penyebab SSI setelah bedah sesar adalah penyakit
sistemik, kebersihan yang buruk, obesitas, dan anemia. Faktor risiko endometritis
diantaranya termasuk kelahiran sesar itu sendiri, pecahnya selaput pelindung
rahim yang berkepanjangan, persalinan yang lama dengan berbagai pemeriksaan
vagina, demam intrapartum, dan status sosial yang rendah. Membrane
chorioamniotic berfungsi sebagai pelindung rahim dari infeksi bakteri. Pecahnya
membran ini juga menjadi penyebab permukaan rahim mudah terinfeksi (ASHP,
2013).
2. Pencegahan
Perencanaan pra operasi dan teknik intraoperatif menjadi penting dalam
pencegahan SSI. Meningkatkan nutrisi, penghentian merokok, penggunaan
meminimalkan infeksi. Pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadi infeksi
pasca operasi antara lain operasi dilakukan sesingkat mungkin, prosedur operasi
dilakukan dengan teknik aseptik-antiseptik, filtrasi terhadap udara pada kamar
operasi, dan pemberian antibiotika profilaksis (Grace dan Borley, 2007; Pear,
2013).
C. Antibiotika Profilaksis
Antibiotika profilaksis merupakan antibiotika yang diberikan sebelum
terjadi kontaminasi pada jaringan atau cairan pada tubuh. Indikasi penggunaan
antibiotika profilaksis didasarkan kelas operasi, yaitu operasi bersih dan bersih
kontaminasi. Tujuan pemberian antibiotika profilaksis pada kasus pembedahan
menurut Kanji and Devlin (2008) dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
(2011), yaitu:
a. Penurunan dan pencegahan kejadian SSI.
b. Penurunan morbiditas dan mortalitas pasca operasi.
c. Penghambatan muncul flora normal resisten.
d. Meminimalkan biaya pelayanan kesehatan.
Penggunaan antibiotika profilaksis terbukti mampu menurunkan risiko
infeksi pasca bedah secara signifikan. Hasil tersebut bergantung pada pemilihan
jenis antibiotika, cara pemberian, waktu dan durasi pemberian yang tepat dan
sesuai dengan kontaminasi bakteri pada prosedur bedah yang terkait. Penggunaan
namun juga meningkatkan risiko resistensi bakteri, biaya yang dikeluarkan, lama
tinggal dan jumlah kunjungan rumah sakit (Ongom and Kijjambu, 2013).
1. Prinsip penggunaan
Agar hasil terapi antibiotika profilaksis bedah dapat maksimal, maka
penggunaannya sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip penggunaan antibiotika
sebagai profilaksis berdasarkan pedoman dan penelitian-penelitian terdahulu.
Secara umum, prinsip penggunaan antibiotika profilaksis menurut Anderson, et al.
(2014) dan Doherty and Way (2006) adalah sebagai berikut:
a. Antibiotika yang dipilih efektif mampu mengatasi tipe kontaminasi yang
terkait.
b. Penggunaan antibiotika hanya digunakan pada prosedur dengan risiko infeksi.
c. Pemberian antibiotika harus sesuai dosis dan waktu pemberian. Antibiotika
diberikan dalam waktu 1 jam sebelum pembedahan (2 jam diperbolehkan
untuk vankomisin dan fluoroquinolon).
d. Dosis dihentikan dalam waktu 24 jam setelah operasi, sebelum terjadi risiko
munculnya efek samping yang lebih besar dibanding keuntungannya.
Pemberian dosis lebih dari 24 jam setelah operasi berkontribusi terhadap
terjadinya resistensi bakteri.
e. Dosis dapat diulang bila prosedur operasi terlalu panjang atau adanya
kehilangan darah yang berlebihan selama operasi. Dosis diulang jika sudah
Antibiotika yang digunakan untuk profilaksis dipilih yang paling aman
dan efektif sesuai prosedur bedah. Dasar pemilihan jenis antibiotika untuk tujuan
profilaksis menurut Kanji and Devlin (2008) dan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia (2011), yaitu:
a. Sesuai dengan sensitivitas dan pola bakteri patogen terbanyak pada prosedur
operasi. Bakteri ini dapat berasal dari endogen (dari flora normal pasien
sendiri) atau eksogen (dari kontaminasi selama prosedur bedah).
b. Spektrum sempit untuk mengurangi risiko resistensi bakteri.
c. Toksisitas rendah.
d. Tidak menimbulkan reaksi merugikan terhadap pemberian obat anestesi.
e. Bersifat bakterisidal.
f. Harga terjangkau.
Pada beberapa kondisi, pasien diberikan antibiotika lebih dari satu jenis
jenis yang disebut antibiotika kombinasi. Tujuan dari pemberian antibiotika
kombinasi yaitu memberi efek sinergis dengan meningkatkan aktivitas antibiotika
pada infeksi spesifik, dan memperlambat serta mengurangi risiko timbulnya
bakteri resisten. Antibiotika kombinasi dapat memperluas spektrum aktifitas
sehingga dapat mengatasi infeksi yang disebabkan oleh polibakteri. Antibiotika
kombinasi juga diberikan dengan indikasi abses intraabdominal, hepatik, infeksi
campuran aerob dan anaerob, dan sebagai terapi empiris pada infeksi berat
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
Kombinasi antibiotika yang bekerja pada target yang berbeda dapat
antibiotika bersamaan dengan antibiotika lainnya dapat menimbulkan atau
meningkatkan toksisitas yang bersifat aditif atau superaditif. Untuk mendapatkan
kombinasi rasional dengan hasil efektif, diperlukan pengetahuan jenis infeksi serta
data mikrobiologi terkait antibiotika (Cunha, 2010).
Agar terapi profilaksis optimal, maka antibiotika profilaksis harus
diberikan dalam dosis yang adekuat. Dosis yang digunakan adalah dosis
maksimum. Dosis minimum tidak efektif karena tidak mampu mencapai
konsentrasi dalam darah yang dibutuhkan saat pembedahan dimulai. Administrasi
harus diulang intraoperatif jika operasi masih berlangsung 2 kali waktu paruh
antibiotika profilaksis yang digunakan setelah dosis pertama untuk memastikan
antibiotika masih cukup adekuat untuk mencegah infeksi sampai pada proses
penutupan luka. Pemberian ulang antibiotika juga diindikasikan bila saat operasi
terjadi kehilangan darah yang berlebihan yaitu berkisar antara >1000-1500 mL
(ASHP, 2013; Ongom and Kijjambu, 2013).
Diperlukan penyesuaian dosis berdasarkan berat badan pasien, atau
indeks massa tubuh (BMI) khususnya untuk pasien obesitas. Dengan pemberian
antibiotika dengan dosis yang sama, konsentrasi antibiotika pada serum pasien
dengan BMI yang tinggi lebih rendah dibanding pada pasien dengan BMI yang
lebih rendah. Untuk pasien dengan BMI yang tinggi perlu mendapat dosis ganda.
Penyesuaian ini diperlukan pada pasien dengan BMI >35 (ASHP, 2013; SOGC,
2010).
Pemilihan jenis, serta waktu dan durasi pemberian antibiotika profilaksis
mempertimbangkan risiko keamanan ibu melainkan juga keamanan janin/bayi.
Faktor lain yang menjadi perhatian adalah terkait dosis, rute pemberian, dan
adanya resistensi dan/ atau alergi terhadap antibiotika yang digunakan.
Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan farmakodinamik dan farmakokinetik dari tiap
antibiotika (Ongom and Kijjambu, 2014; Doherty and Way, 2006).
Profilaksis yang efektif harus bisa mengantarkan antibiotika pada daerah
sayatan sesaat sebelum terjadi kontaminasi. Kadar antibiotika profilaksis dalam
darah dan jaringan harus mencapai kadar hambat minimum (KHM) untuk
mencegah terjadinya infeksi saat dan selama pembedahan. Ada dua rekomendasi
waktu pemberian antibiotika profilaksis yang berbeda pada kasus SC. Beberapa
penelitian menunjukkan sebaiknya waktu pemberian antibiotika profilaksis
ditunda, bukan sebelum operasi dimulai seperti pada prosedur operasi lainnya,
tetapi baru diberikan segera setelah tali pusar dipotong. Alasan utama penundaan
administrasi adalah menghindari penekanan flora normal pada bayi yang baru
lahir yang bisa mendorong terjadinya resistensi bakteri. Timbul pula kekhawatiran
bahwa antibiotika tersebut berpotensi menutupi infeksi neonatal, sehingga
evaluasi sepsis pada neonatal menjadi sulit. Data yang lebih modern mendukung
administrasi antibiotika profilaksis sebelum sayatan bedah untuk melindungi
pasien terhadap risiko infeksi. Hasil penilaian terapi cefazolin 2 g dosis tunggal
sebagai profilaksis yang diberikan sebelum prosedur SC dan yang diberikan
setelah tali pusar dipotong memberikan perbedaan yang tidak signifikan (ASHP,
Antibiotika profilaksis pada SC sebaiknya diberikan 30-60 menit
sebelum operasi dimulai. Pemberian antibiotika profilaksis yang terlalu awal
dapat menyebabkan konsentrasi antibiotika tidak memadai dalam jaringan saat
dan selama operasi berlangsung. Efektifitas antibiotika dalam melindungi pasien
dari bakteri penyebab infeksi pun menjadi berkurang sehingga risiko terjadinya
infeksi postpartum akan meningkat. Begitu pula pada pasien yang baru menerima
antibiotika profilaksis setelah operasi. Tidak ada antibiotika profilaksis yang dapat
melindungi pasien dari infeksi bakteri selama operasi berlangsung hingga selesai
(ASHP, 2013; Sullivan, et al., 2007).
Rekomendasi durasi pemberian antibiotika profilaksis yaitu maksimal 24
jam setelah pembedahan. Hal ini dikarenakan belum ditemukan bukti mendukung
bahwa perpanjangan durasi antibiotika profilaksis memberikan manfaat yang baik.
Kekhawatiran justru muncul karena durasi yang panjang terkait dengan
munculnya resistensi (ASHP, 2013).
2. Klasifikasi antibiotika
Berdasarkan mekanisme aksinya, antibiotika dapat diklasifikasikan
menjadi 3 kelompok besar. Pertama, antibiotika dengan target dinding sel, yaitu
golongan betalaktam, glikopeptida, daptomisin, dan kolistin. Kedua, antibiotika
yang memblok produksi protein. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah
rifampisin, aminoglikosida, makrolida dan ketolida, tetrasiklin dan glisisiklin,
kloramfenikol, klindamisin, streptogramin, linezolid, dan nitrofurantoin. Ketiga,
antibiotika dengan target DNA atau replikasi DNA. Golongan sulfa, kuinolon, dan
3. Rekomendasi penggunaan antibiotika profilaksis untuk sectio caesarea
Rekomendasi antibiotika yang digunakan sebagai profilaksis bedah
adalah antibiotika golongan sefalosporin generasi I dan generasi II. Pada kasus
tertentu yang dicurigai melibatkan bakteri anaerob dapat dikombinasikan dengan
metronidazol. Tidak dianjurkan menggunakan sefalosporin generasi III dan IV,
golongan karbapenem, dan golongan kuinolon untuk profilaksis bedah (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
Sefalosporin adalah golongan antibiotika yang paling sering diresepkan
untuk profilaksis bedah karena memiliki spektrum luas, profil farmakokinetik
yang menguntungkan, efek samping jarang terjadi, dan murah. Cefazolin
merupakan sefalosporin generasi pertama dan antibiotika profilaksis pilihan untuk
SC. Rekomendasi penggunaan cefazolin sebagai profilaksis yaitu 2 g dosis
tunggal dan diberikan 30-60 menit sebelum pembedahan. Kombinasi klindamisin
dan aminoglikosida menjadi pilihan terapi untuk pasien yang alergi dengan
betalaktam (ASHP, 2013; Kanji and Devlin, 2008).
Cefuroxime merupakan sefalosporin generasi II yang lebih poten
melawan E. coli, K. pneumoniae, dan P. mirabilis dibanding dengan sefalosporin
generasi I. Generasi II ini juga mampu melawan Neisseria spp., dan H. influenzae
(Hauser, 2013). Cefuroxime memiliki keamanan dan efektifitas yang sama dengan
ampicillin yang dikombinasikan dengan sulbaktam sebagai antibiotika profilaksis
pada prosedur SC (Ziogos, et al., 2010).
Cefotaxime, ceftriaxon, dan cefditoren merupakan sefalosporin generasi
dapat meningkatkan penetrasi agen antibiotika untuk menembus membran luar
bakteri, meningkatkan afinitas dan meningkatkan stabilitas saat melawan bakteri.
Generasi ini dapat melawan E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Neisseria spp.,
and H. influenzae. Selain itu dapat pula melawan Enterobacteriaceae, termasuk
Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Providencia spp., Morganella morganii,
dan Serratia spp.. Karena kemampuannya yang tidak sesuai untuk mencegah dan
mengatasi bakteri yang biasa mengkontaminasi pada prosedur bedah, maka
sefalosporin generasi III, IV, dan V tidak digunakan sebagai profilaksis bedah
(Hauser, 2013).
Tidak ada bukti bahwa sefalosporin generasi III lebih efektif dibanding
sefalosporin generasi I dan II sebagai profilaksis pada bedah. Sefalosporin
generasi III dan IV sebaiknya tidak digunakan untuk profilaksis karena beberapa
alasan diantaranya yaitu harganya yang lebih mahal, kurang aktif dibanding
cefazolin dalam mengatasi staphylococci, memiliki spektrum yang tidak spesifik
untuk mikroorganisme pada bedah elektif, dan penggunaannya sebagai profilaksis
dapat meningkatkan risiko resistensi (McEvoy, 2005).
Ampicillin atau aminopenicillin diketahui memiliki efikasi yang sama
dengan antibiotika golongan sefalosporin generasi I dan II. Golongan antibiotika
tersebut merupakan antibiotika spektrum luas yang memiliki aktifitas baik
terhadap bakteri Gram negatif maupun Gram positif. Waktu paruh ampicillin
pendek dan spektrumnya yang lebih sempit dibanding sefalosporin generasi I.
Ampicillin dapat mengatasi bakteri Gram positif (Streptococcus pyogenes,
monocytogenes), Gram negatif (Neisseria meningitides, Haemophilus influenzae,
Enterobacteriaceae), dan bakteri anaerob (Clostridia spp. kecuali C. difficile dan
Actinomyces israelii). Ampicillin tidak dapat mengatasi bakteri yang
memproduksi enzim betalaktamase yang dapat menyebabkan bakteri menjadi
resisten terhadap antibiotika golongan ini. Oleh karena itu, ampicillin perlu
dikombinasikan dengan antibiotika golongan inhibitor beta-laktamase, seperti
klavulanat dan sulbaktam. Kombinasi ini memperlebar spektrum antibiotika.
Bakteri yang dapat diatasi dengan kombinasi ini adalah bakteri-bakteri yang dapat
diatasi oleh ampicillin tunggal dan diperluas sehingga juga dapat mengatasi
bakteri lain seperti Streptococcus pyogenes dan Bacteroides spp (Gyte, Dou1, and
Vazquez, 2014; Hauser, 2013).
Tidak seperti ampicillin, antibiotika golongan sefalosporin generasi I dan
II lebih poten untuk mengatasi bakteri yang memiliki enzim beta laktamase.
Sefalosporin generasi I dan II dapat melindungi struktur betalaktamnya sehingga
tidak mudah dirusak oleh bakteri. Ketiganya memiliki kelemahan yang sama yaitu
lemah melawan bakteri anaerob (Hauser, 2013).
Untuk meningkatkan hasil terapi khususnya pada kasus yang melibatkan
bakteri anaerob, maka penggunaan sefalosporin dan ampicillin dapat
dikombinasikan dengan agen antibiotika lain seperti metronidazol, klindamisin
atau doxycycline, atau azitromisin (ASHP, 2013; Hopkins and Smaill, 2000).
Metronidazol efektif melawan hampir semua bakteri Gram negatif anaerob,
termasuk Bacteroides fragilis, dan bakteri gram positif yang paling anaerob,
antibiotik yang memiliki aktivitas terhadap C. difficile dan merupakan pilihan
perawatan untuk infeksi yang disebabkan oleh organisme ini (Hauser, 2013).
Antibiotika yang memperluas spektrum antibiotik untuk terapi profilaksis
pada SC lainnya adalah azitromisin. Azitromisin lebih baik digunankan sebagai
antibiotika profilaksis untuk memperluas spektrum dibanding antibiotika lainnya.
Azitromisin memiliki half-life 68 jam, konsentrasi di jaringan yang lebih tinggi
dan pada bagian transplasenta lebih rendah dari beberapa antibiotik lain yang
umum digunakan untuk indikasi ini. Selain itu, azitromisin aktif terhadap kuman
aerob dan anaerob, serta Ureaplasmas, sehingga secara signifikan mengurangi
risiko endometritis dan SSI Hanya saja harganya lebih mahal dibanding pilihan
antibiotika lain (Lamont, et al, 2011, Tita, et al, 2009).
Terapi antibiotika profilaksis dosis tunggal lebih efektif dibanding terapi
multidosis. Terapi dengan dosis tunggal juga mengurangi biaya, potensi toksisitas,
dan risiko kolonisasi organisme resisten (Murtha and Silverman, 2011).
Rekomendasi dosis dan dosis berulang antibiotika profilaksis dapat dilihat pada
Tabel III.
Tabel III. Rekomendasi dosis dan dosis berulang beberapa antibiotika profilaksis (ASHP, 2013).
D. Drug related problems (DRPs)
Permasalahan dalam farmasi klinis terutama muncul karena pemakaian
obat yang disebut dengan drug related problems (DRPs) adalah kejadian atau efek
yang tidak diinginkan yang dialami pasien dalam proses terapi dengan obat dan
secara aktual atau potensial bersamaan dengan outcome yang diharapkan pada
saat mendapat perawatan akibat dari suatu penyakit. Masalah–masalah dalam
kajian DRP menurut Cipolle, Strand, Morley, Ramsey, and Lamsam (2004) antara
lain:
a. Memerlukan obat tambahan, yaitu jika kondisi baru yang membutuhkan obat,
kondisi kronis yang membutuhkan kelanjutan terapi obat, kondisi yang
membutuhkan kombinasi obat, dan kondisi yang mempunyai risiko kejadian
efek samping dan membutuhkan obat untuk pencegahannya.
b. Obat tidak diperlukan, yaitu jika obat yang diberikan tidak sesuai dengan
indikasi pada saat itu, pemakaian obat kombinasi yang seharusnya tidak
diperlukan, kondisi yang lebih cocok mendapat terapi non farmakologi,
meminum obat dengan tujuan untuk mencegah efek samping obat lain yang
seharusnya dapat dihindari, dan penyalahgunaan obat.
c. Obat tidak efektif, yaitu jika obat yang diberikan kepada pasien kurang sesuai
dengan indikasinya, pasien mempunyai alergi terhadap obat tersebut, obat
yang diberikan mempunyai kontraindikasi dengan obat lain, dan antibiotika
d. Dosis kurang, jika dosis obat terlalu rendah, interval dosis tidak cukup, durasi
terapi obat terlalu pendek untuk dapat menghasilkan respon, serta interaksi
obat yang dapat mengurangi jumlah obat yang tersedia dalam bentuk aktif.
e. Dosis berlebih, yaitu jika dosis obat terlalu tinggi untuk memberikan efek,
dosis obat dinaikkan terlalu cepat, frekuensi pemberian obat terlalu pendek,
dan durasi terapi pengobatan terlalu panjang.
f. Efek samping obat, yaitu jika obat menimbulkan efek yang tidak diinginkan
tetapi tidak ada hubungannya dengan dosis, interaksi obat yang menyebabkan
reaksi yang tidak diharapkan tetapi tidak ada hubungannya dengan dosis, ada
obat lain yang lebih aman ditinjau dari faktor resikonya, regimen dosis yang
telah diberikan atau diubah terlalu cepat, dan hasil laboraturium berubah
akibat penggunaan obat.
g. Ketidaktaatan pasien, yaitu jika pasien tidak memahami aturan pemakaian,
pasien tidak menerima regimen obat yang tepat, pasien lupa untuk
menggunakan obat, pasien tidak membeli obat yang disarankan karena mahal,
pasien tidak menggunakan obat karena ketidaktahuan cara memakai obat,
pasien tidak menggunakan obat karena ketidakpercayaan dengan produk obat
yang dianjurkan.
Farmasis diharapkan dapat mengidentifikasi DRPs. Tidak berhenti
sampai di situ, farmasis juga harus mampu membuat solusi terhadap DRPs
tersebut, sehingga tercapainya obat yang diharapkan yaitu: tepat indikasi, efektif,
E. Keterangan Empiris
Penggunaan antibiotika profilaksis pada operasi sesar penting untuk
mencegah terjadinya infeksi. Penelitian ini diharapkan dapat mengevalusasi DRP
pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus sectio caesarea di RS Panti
29
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah observasional karena peneliti hanya
mengamati sejumlah dari variabel subjek penelitian tanpa adanya intervensi
peneliti (Imron dan Munif, 2010). Rancangan penelitian yang digunakan yaitu
case series karena penelitian ini menggambarkan sekelompok kasus dengan
diagnosa yang sama dalam periode tertentu. Masing-masing kasus tersebut tidak
berhubungan dan dievaluasi terpisah (Bhandarin and Joensson, 2009). Penelitian
ini bersifat retrospektif karena pengambilan data dilakukan dengan melakukan
penelusuran dokumen terdahulu berupa lembar rekam medik pasien (Chandra,
2006).
B. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah pola peresepan dan DRP pada
penggunaan antibiotika profilaksis untuk pasien SC.
C. Definisi Operasional
1. Sectio caesarea (SC) yaitu operasi sesar yang berlangsung pada periode
Januari-Juni 2014
2. Antibiotika profilaksis yaitu antibiotika yang diberikan sebelum pasien
3. Karakteristik pasien SC yang dideskripsikan pada penelitian ini meliputi usia
ibu, usia kehamilan, adanya riwayat SC atau tidak, dan jenis SC.
4. Pola penggunaan antibiotika profilaksis yang dideskripsikan pada penelitian
ini meliputi golongan dan jenis antibiotika, rute pemberian, dosis, serta waktu
dan durasi pemberian.
5. Drug Related Problems (DRPs) yang dievaluasi pada penelitian ini meliputi:
butuh tambahan obat, obat tidak efektif, dosis kurang, dosis berlebih, efek
samping obat, dan obat tidak diperlukan.
D. Subyek Penelitian
Subyek penelitian yang termasuk dalam kriteria inklusi yaitu pasien
bukan rujukan yang menjalani operasi sesar di RS Panti Rini Yogyakarta pada
periode Januari-Juni 2014 dan mendapat terapi antibiotika profilaksis. Kriteria
eksklusi pada penelitian ini adalah pasien dengan data rekam medik yang tidak
lengkap, tidak terbaca, dan tidak dapat dikonfirmasi.
Penelitian ini juga melibatkan apoteker yang merupakan kepala Instalasi
Farmasi RS Panti Rini Yogyakarta dan salah satu dari dua dokter penulis resep
antibiotika profilaksis untuk pasien SC yang bersedia diwawancarai sebagai
subjek penelitian. Wawancara tersebut bermaksud untuk melengkapi pembahasan
pada hasil evaluasi DRPs.
E. Bahan Penelitian
Bahan penelitian yang digunakan adalah berupa lembar rekam medik
pasien SC di RS Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan berupa formulir pengumpulan data.
Ada dua macam formulir pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu formulir
data rekam medis dan formulir wawancara. Formulir data rekam medis mencakup
karakteristik pasien, profil penggunaan antibiotika profilaksis, dan masalah yang
terjadi selama proses terapi. Formulir data wawancara mencakup aspek-aspek
yang berkaitan dengan latar belakang peresepan antibiotika profilaksis pada SC.
G. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada 29 September-3 November 2014.
Pengambilan data dilakukan di bagian rekam medis Rumah Sakit Panti Rini, Jalan
H. Tata Cara Penelitian 1. Tahap persiapan
Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengurusan izin di bagian
personalia RS Panti Rini. Kemudian dilakukan pencarian informasi jumlah pasien
SC yang ada di RS Panti Rini periode Januari-Juni 2014.
2. Tahap uji coba instrumen penelitian
Instrumen yang diuji coba dalam penelitian ini adalah formulir data
rekam medik. Tujuan dari uji coba instrumen formulir data rekam medik adalah
agar formulir pengumpulan data yang digunakan mudah diisi, mudah diolah untuk
analisis, dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini
diawali dengan menyusun variabel-variabel yang dianalisis ke dalam bentuk
formulir. Kemudian dilakukan pengumpulan data dengan formulir tersebut dan
dianalisis. Langkah selanjutnya ditentukan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk
analisis namun belum diperoleh, dan menambahkannya pada formulir. Ditentukan
pula data apa saja yang tidak terpakai, lalu menghilangkannya dari formulir.
Pengumpulan data dan analisis diulang hingga data-data yang diperoleh sudah
sesuai untuk dianalisis.
Langkah terakhir pada uji coba instrumen formulir data rekam medik
yaitu pengembangan formulir agar lebih mudah diisi. Formulir disusun kembali
dengan memperhatikan ukuran formulir, urutan data, dan waktu yang dibutuhkan
dalam pengisian formulir. Formulir data rekam medik yang digunakan sebagai
3. Tahap pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan di bagian penyimpanan rekam medik pasien
RS Panti Rini Yogyakarta. Dalam proses ini data diperoleh dengan menelusuri
data dari lembar rekam medik yang didasarkan pada nomor rekam medik pasien
SC di RS Panti Rini Yogyakarta. Dari penelusuran data, ditentukan pasien yang
masuk dalam kriteria inklusi maupun eksklusi. Data pada rekam medik pasien
yang masuk dalam kriteria inklusi disalin ke dalam formulir pengumpulan data
rekam medik. Data yang disalin meliputi nomor rekam medik, usia ibu, usia
kehamilan, riwayat SC, jenis SC, data laboratorium, keluhan yang tertulis pada
catatan keperawatan, tanggal operasi sesar, jam operasi sesar, diagnosis sebelum
operasi, dan lama rawat inap. Selain itu, disalin pula data terkait dengan
antibiotika profilaksis yang digunakan meliputi jenis, rute pemberian, dosis, serta
waktu dan lama pemberian. Dilakukan pula wawancara dengan kepala Instalasi
Farmasi dan salah satu dokter penulis resep antibiotika profilaksis pada pasien SC
di RS Panti Rini Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor pemilihan antibiotika profilaksis.
4. Tahap analisis data
Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan karakteristik pasien
dan pola penggunaan antibiotika profilaksis. Tahap terakhir yang dilakukan
mengevaluasi DRPs terkait penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien kasus
sectio caesarea di RS Panti Rini pada periode Januari-Juni 2014. Hasil evaluasi
H. Tata Cara Analisis Hasil 1. Karakteristik pasien
Analisis data jumlah pasien operasi sesar dilakukan dengan menganalisis
data karakteristik pasien berdasarkan usia ibu, usia kehamilan, riwayat SC, dan
jenis SC. Analisis karakteristik pasien dilakukan dengan menghitung jumlah
pasien pada setiap kelompok dibagi jumlah pasien yang dianalisis dikali 100%.
2. Profil penggunaan antibiotika profilaksis
Profil penggunaan antibiotika profilaksis dibagi menjadi jenis antibiotika,
waktu pemberian, rute pemberian, dosis, dan durasi pemberian. Profil penggunaan
antibiotika profilaksis berdasarkan jenis antibiotika dibagi menjadi 3 kelompok
besar yaitu tunggal, kombinasi 2 antibiotika, dan kombinasi 3 antibiotika. Profil
penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan waktu pemberian dikelompokkan
menjadi sebelum operasi (>240, 240-121, 120-61, <60 menit), saat operasi, dan
setelah operasi (<60, 61-120, 121-240 menit dan 8-12 jam ). Profil penggunaan
antibiotika profilaksis berdasarkan rute pemberian dikelompokan menjadi oral dan
intravena. Profil penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan durasi pemberian
dikelompokkan menjadi 12-24, 24-48, 48-72, dan >72 jam.
Persentase profil penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan jenis
antibiotika, waktu pemberian, rute pemberian, dan durasi pemberian dihitung
dengan cara menghitung jumlah kasus yang termasuk pada setiap kelompok
kemudian dibagi dengan jumlah kasus keseluruhan (n=27) dikali 100%. Profil
mengidentifikasi masing-masing dosis dari setiap jenis antibiotika profilaksis
yang diberikan.
Sejumlah pasien mendapatkan lebih dari satu jenis antibiotika profilaksis.
Walaupun tujuan terapinya sama, waktu pemberian, rute pemberian, dan durasi
pemberian setiap antibiotika yang diberikan pada satu pasien bisa berbeda-beda.
Hal tersebut menyebabkan satu kasus dapat dikategorikan ke dalam lebih dari satu
kelompok waktu pemberian, rute pemberian, dan durasi pemberian.
Contoh pada kasus 7, pasien mendapat 3 jenis antibiotika profilaksis
yaitu Celocid® 250 mg 2x/hari, Trogyl® 500 mg 3x/hari, dan Meiact® 2x/hari.
Ketiganya diberikan 12 jam setelah operasi. Celocid® dihentikan 36 jam setelah
operasi, sedangkan Trogyl® dan Meiact® baru dihentikan 48 jam setelah operasi.
Pada kasus ini, waktu pemberian ketiga antibiotika sama, namun jenis, rute, dan
durasi pemberiannya berbeda. Perhitungan presentasi profil penggunaan
antibiotika profilaksis pada kasus seperti ini yaitu dengan mengkategorikan kasus
ke dalam lebih dari satu kelompok, namun tetap dihitung sebagai satu kasus, yaitu
kasus 7.
Untuk kasus 7, pada profil penggunaan antibiotika profilaksis
berdasarkan rute pemberian, kasus ini masuk ke dalam kelompok intravena karena
pasien menerima Meiact® secara iv, dan juga masuk ke dalam kelompok oral
karena pasien menerima Celocid® dan Trogyl® secara oral. Begitu pula pada
profil penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan durasi pemberian, kasus ini
masuk ke dalam kelompok 24-48 dan 48-72 jam. Karena satu kasus dapat masuk