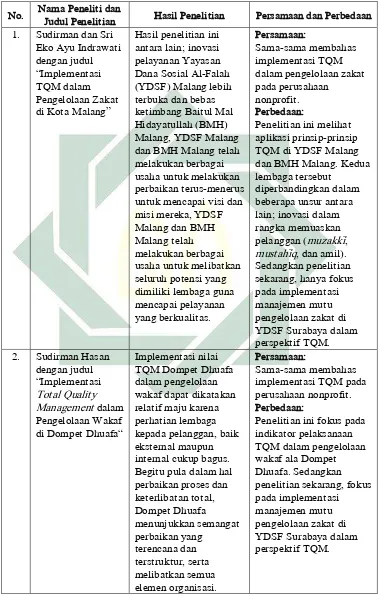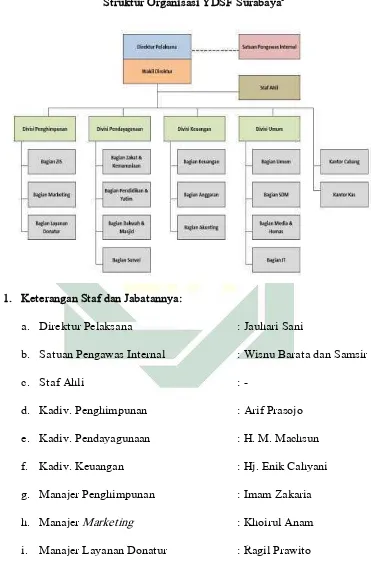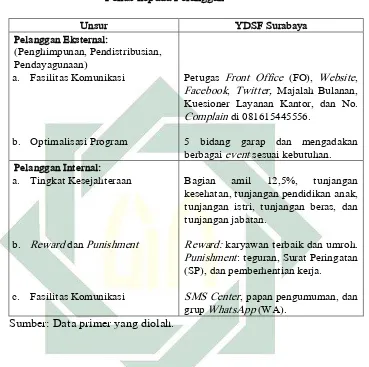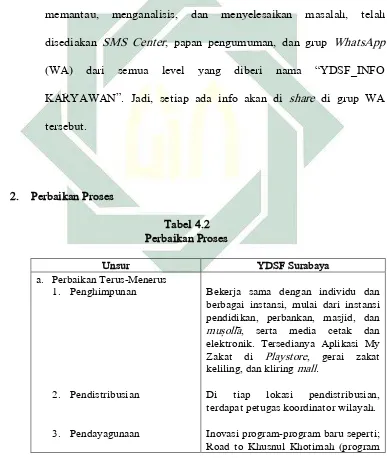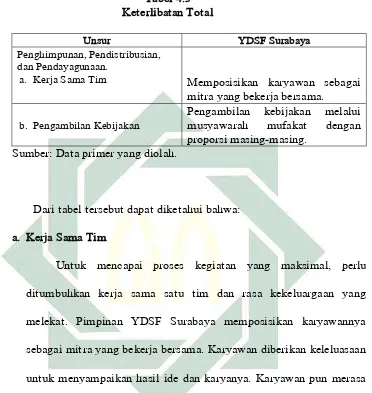i
MANAGEMENT
(TQM)
SKRIPSI
OLEH:
KHOLISHOTUN NAFSIYAH NIM: C94213180
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Mutu Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam Perspektif Total Quality
Management (TQM)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan
menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam perspektif Total Quality Management (TQM).
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan (4 orang karyawan YDSF Surabaya), observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya dianalisis dengan menggunakan konsep TQM yang dikemukakan oleh Arthur Tenner melalui tiga prinsip yaitu: fokus kepada pelanggan, perbaikan proses, dan keterlibatan total. Dipilihnya konsep Tenner tersebut, karena tiga prinsip itu dianggap mewakili indikator keberhasilan penerapan TQM di sebuah lembaga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa YDSF Surabaya telah sukses melaksanakan TQM dalam manajemen mutu pengelolaan zakatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang mengacu pada 3 prinsip TQM yang dikemukakan oleh Arthur Tenner tersebut. Namun, tidak secara langsung menyebut bahwa manajemen mutu pengelolaan zakat yang digunakan adalah TQM.
YDSF Surabaya dalam menerapkan 3 prinsip TQM Arthur Tenner, terlihat pada: pelayanan prima yang diberikan kepada pelanggan, baik eksternal maupun internal cukup bagus. Begitu pula dalam hal perbaikan proses, YDSF Surabaya menunjukkan semangat perbaikan yang tak ada hentinya. Dalam hal keterlibatan total, tidak semua elemen lembaga terlibat dalam pengambilan kebijakan. Para karyawan mempunyai proporsi masing-masing dalam hal pengambilan kebijakan. Misalnya, jika kebijakan program, maka karyawan turut terlibat dalam pengambilan kebijakan dari hasil rapat di masing-masing divisi, sedangkan untuk kebijakan lembaga, maka dirapatkan oleh level divisi ke atas.
viii
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DALAM ... i
PERNYATAAN KEASLIAN ... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii
PENGESAHAN ... iv
ABSTRAK ... v
KATA PENGANTAR ... vi
DAFTAR ISI ... viii
DAFTAR TABEL ... x
DAFTAR GAMBAR ... xi
DAFTAR TRANSLITERASI ... xii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ... 7
C. Rumusan Masalah ... 8
D. Kajian Pustaka ... 8
E. Tujuan Penelitian ... 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian ... 12
G. Definisi Operasional ... 13
H. Metode Penelitian ... 15
I. Sistematika Pembahasan ... 24
BAB II KERANGKA TEORETIS ... 25
A. Manajemen Mutu ... 25
B. Pengelolaan Zakat ... 27
ix
BAB III DATA PENELITIAN ... 43
A. Sejarah YDSF ... 43
B. Visi dan Misi YDSF Surabaya ... 47
C. Struktur Organisasi YDSF Surabaya ... 48
D. 5 Bidang Garap YDSF Surabaya ... 49
E. Manajemen Pengelolaan Zakat di YDSF Surabaya ... 51
BAB IV ANALISIS DATA ... 57
A. Implementasi Manajemen Mutu Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) ... 57
BAB V PENUTUP ... 67
A. Kesimpulan ... 67
B. Saran ... 68
DAFTAR PUSTAKA ... 69
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak
sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Islam
memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang membahayakan akidah,
akhlak, akal sehat, keluarga, dan masyarakat. Sebab seseorang yang terjerat
kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang
yang kaya. Perasaan ini mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan
kehinaan, dan mendorong seseorang melakukan apapun untuk mencapai
ambisinya. Islam sebagai al-di>>>>>>>>>>>>>>n telah menawarkan beberapa doktrin bagi
manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.1
Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang
mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat
kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan ajaran yang melandasi
tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti
empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi
yang kompleks, meliputi; nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta
ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan
1 Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq
kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang
terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan
menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju
kebangkitan kembali peradaban Islam.2
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Indonesia, potensi
ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran zakat demi
menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang
saat ini sedang melanda Indonesia. Pada Maret 2016, jumlah penduduk
miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen),
berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September
2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).3
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama
yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Di
dalam Alquran, kata zakat disebut sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan
dengan s}alat yang merupakan rukun Islam kedua.4 Seperti yang ada di dalam
Alquran surah At-Taubah [9]: 103.
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
2 Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, “Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota
Malang”, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Desember 2011), 135-136.
3 Badan Pusat Statistik, (Diakses pada 19 September 2016).
Sesungguhnya doa (s}alat) kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”6
Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa penunaian zakat berarti
membersihkan harta yang tinggal, sebab pada harta seseorang terdapat hak
para mustahi>q. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada harta
yang tersisa. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta
seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.7
Menurut Mannan, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral,
sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan
keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk
menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat
mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan
merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara,
karena tujuan zakat adalah transfer kekayaan dari masyarakat yang kaya
kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga setiap kegiatan yang
merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.8
Pembahasan seputar zakat tidak akan terlepas dari aktivitas manajemen
yang menjadi suatu topik menarik. Pada umumnya, zakat dipahami sebagai
ibadah yang tidak perlu menggunakan jasa perantara, karena bisa langsung
diberikan kepada pihak yang berhak. Bahkan, sebagian masyarakat menilai
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema, 2012), 203.
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 199-200. 8 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima
bahwa pemberian secara langsung dapat memberikan kepuasan tersendiri
bagi para muzakki>. Mereka merasa gembira karena zakatnya diterima
langsung oleh mustahi>q, berbeda halnya dengan zakat yang diberikan melalui
Lembaga Pengelola Zakat. Distribusi zakat melalui lembaga tidak dapat
dipantau oleh muzakki> dan bahkan mereka khawatir zakat mereka
disalahgunakan untuk pos-pos yang tidak semestinya.
Adanya dukungan pemerintah melalui lahirnya UU No. 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) dengan Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38
tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Zakat, maka mulai dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga menjadikan masyarakat
berangsur-angsur percaya akan kredibilitas penyaluran zakat oleh BAZ maupun LAZ.9
LAZ diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan S>}adaqah (ZIS) di Indonesia. Dana
yang telah terkumpul harus didistribusikan sesuai sasaran yang telah
direncanakan sebelumnya. Mereka yang mendapat santunan memang
orang-orang yang harus disantuni.10 Tentu hal ini memberikan peluang kepada
lahirnya sejumlah LAZ di Indonesia, seperti Yayasan Baitul Mal Umat Islam
9 Mustolih Siradj, “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. 3 (2014), 417.
10 Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial”, Jurisdictie:
Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada 5 Oktober 1967 di Jakarta,
Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) pada 1 Maret 1987 di Surabaya, dan
Dompet Dhuafa Republika pada 14 September 1994 di Jakarta.
Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen yang handal
dengan menerapkan salah satu konsep manajemen yang dikenal dengan Total
Quality Management (TQM), atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah
MMT (Manajemen Mutu Terpadu).
TQM merupakan salah satu terobosan manajemen yang umumnya
dilakukan oleh perusahaan besar, seperti Xerox, IBM Rochester, dan
Motorola dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang pada muaranya
dapat memuaskan konsumen. Semakin banyak konsumen yang puas dengan
produk yang ditawarkan, maka akan semakin sering mereka menggunakan
produk tersebut. Feedbacknya, perusahaan itu akan meraih keuntungan yang
besar. TQM pada fase berikutnya banyak dilirik oleh perusahaan penyedia
jasa, misalnya FedEx (jasa pengiriman). Fokus kepada pelanggan yang
menjadi ciri khas TQM membuat perusahaan-perusahaan yang bergerak di
bidang layanan kepada masyarakat itu memperoleh manfaat yang tidak kalah
semakin menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam kompetisi global yang
kian ketat.11
TQM mulai diterapkan di lembaga-lembaga filantropi yang bergerak di
bidang pelayanan pengelolaan zakat dan wakaf. Sebagai contoh, Islamic
Relief Amerika yang berdiri pada tahun 1993 telah mendapatkan bintang 4
(four stars) dari Charity Navigator dalam manajemen filantropinya. Lembaga
yang bermarkas di Alexandria, Virginia ini bergerak di bidang pengelolaan
ZIS.12
Tahap-tahap yang dilakukan dalam manajemen menurut James Stoner,
seperti dikutip Eri Sudewo, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan. Berbeda dengan manajemen tradisional yang
dianggap sebagai penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat, manajemen
modern menjadikan profesi pengelola zakat sebagai salah satu pilihan
pekerjaan dengan level “white collar (pekerjaan terhormat)” bukan lagi “blue
collar (pekerjaan rendahan).”13
Dalam konteks TQM, salah satu LAZ Nasional yang terus-menerus
berupaya mengembangkan pola manajemen mutunya adalah YDSF. Hal ini
terlihat dalam visi dan misi, paradigma organisasi, sistem manajemen, dan
paradigma program YDSF tersebut.14 Menurut Arthur Tenner, ada tiga
indikator prinsip yang harus diimplementasikan untuk mencapai standar
11 Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, “Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota
Malang”, 137.
12 Ibid. 13 Ibid., 136.
14 Miftahul Huda, “Model Manajemen Fundraising Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
TQM, yakni fokus kepada pelanggan (focus on customer), perbaikan proses
(process improvement), dan keterlibatan total (total involvement).15
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di
YDSF Surabaya yang akan dikupas berdasarkan analisis konsep TQM yang
dikemukakan oleh Arthur Tenner yang telah disebutkan di atas. Dipilihnya
teori Tenner tersebut, karena tiga prinsip itu dianggap mewakili indikator
keberhasilan penerapan TQM di sebuah lembaga. YDSF dipilih sebagai tempat
penelitian karena visinya yaitu; sebagai lembaga sosial yang benar-benar
amanah serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat
dan martabat umat Islam, khususnya di Jawa Timur.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Untuk mengimplementasikan sebuah manajemen yang handal yaitu
TQM, tentu diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari semua pihak
yang terlibat dalam suatu lembaga, baik pimpinan maupun karyawan.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan timbul beberapa
identifikasi masalah sebagai berikut:
a. Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di
Indonesia.
15 Arthur R Irving J. DeToro Tenner, “Total Quality Management, Three Steps to Continuous
b. Upaya YDSF dalam mengembangkan manajemen mutu pengelolaan
zakat.
c. Implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya
dalam perspektif TQM.
2. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah pada:
Implementasi Manajemen Mutu Pengelolaan Zakat di YDSF Surabaya
dalam Perspektif TQM.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF
Surabaya dalam perspektif TQM?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Diharapkan tidak adanya
pengulangan materi secara mutlak, seperti beberapa penelitian yang sudah
Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang
No. Nama Peneliti dan
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan
fokus amilin, fokus
1. Untuk mengetahui implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di
F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah
ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang
implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya
dalam perspektif TQM dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
pada kajian penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Para Praktisi di Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para
praktisi di LAZ, khususnya di YDSF Surabaya dalam menerapkan
prinsip-prinsip TQM pada setiap kegiatannya.
b. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan memperkaya pengetahuan penulis tentang implementasi
prinsip-prinsip TQM, khususnya dalam pengelolaan zakat di YDSF
Surabaya.
c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada
UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam untuk lebih mengembangkan kajian keilmuan ekonomi
G. Definisi Operasional
Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat
operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan
dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui
penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap suatu
konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata per
kata.16 Untuk memahami dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu
dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:
1. Manajemen Mutu
Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan.17 Mutu mengacu pada dua pengertian pokok, yaitu
sejumlah keistimewaan produk dan segala sesuatu yang bebas dari
kekurangan.18
Pada dasarnya, konsep mutu baik pada perusahaan jasa maupun non
jasa mencakup berbagai hal yang terfokus pada pelanggan. Sebuah
produk barang atau jasa dibuat, didesain, diproduksi, layanan yang
diberikan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Suatu
produk atau jasa dikatakan bermutu apabila dapat dimanfaatkan,
digunakan, dinikmati sesuai dengan kebutuhan atau bahkan melebihi
harapan pelanggan.
16 Tim Penyusun, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, 2014), 9.
2. Pengelolaan Zakat di YDSF Surabaya
Pengelolaan Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.19 Zakat secara spesifik hanya
diperuntukkan bagi 8 golongan saja sebagaimana yang terdapat dalam
Alquran surah At-Taubah [9]: 60. Pengelolaan zakat di YDSF Surabaya
disalurkan melalui 5 program yaitu; pendidikan, peduli yatim, dakwah,
masjid, dan kemanusiaan.20
3. Total Quality Management (TQM)
Dalam penelitian ini, TQM adalah manajemen kinerja prima dari
YDSF Surabaya yang berhubungan dengan masalah pengelolaan zakat.
Arthur Tenner mengemukakan tiga prinsip utama dalam TQM yaitu:21
a. Pertama, fokus kepada pelanggan (focus on customer). Pelanggan
internal adalah para karyawan (amil) yang bekerja di YDSF
Surabaya. Adapun pelanggan eksternal YDSF Surabaya adalah para
muzakki> dan mustahi>q. Perhatian yang diberikan oleh YDSF
Surabaya kepada pelanggan misalnya dengan tersedianya fasilitas
komunikasi yang cepat dan tanggap seperti; SMS Center, Nomor
Complain, Grup WhatsApp, dan lainnya.
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 20 Yayasan Dana Sosial Al-Falah, “Menengok Sejenak Perjalanan YDSF”, dalam www.ydsf.org,
diakses pada 19 April 2016.
21 Arthur R Irving J. DeToro Tenner, “Total Quality Management, Three Steps to Continuous
b. Kedua, perbaikan proses (process improvement). Upaya YDSF
Surabaya dalam perbaikan proses yang berkesinambungan misalnya
melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta
penyelenggaraan pelatihan bagi karyawan.
c. Ketiga, keterlibatan total (total involvement). Keterlibatan antara
pimpinan dengan seluruh karyawan ditunjang dengan saling
berhubungan baik dan lancar dalam mengembangkan manajemen
dianggap penting oleh YDSF Surabaya.
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
metode studi kasus (case study). Studi kasus merupakan tipe pendekatan
dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan
secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.22 Pendekatan
studi kasus pada hakikatnya terfokus kepada kasus tertentu.
Adapun studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah
bahwa pada awalnya, konsep TQM hanya digunakan untuk organisasi
yang berorientasi laba (profit), terutama yang merupakan perusahaan
besar. Namun dalam perkembangannya, konsep TQM pun relevan untuk
diimplementasikan pada organisasi nonprofit, baik organisasi sektor
22 M. Syahran Jailani, “Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded
publik serta perusahaan/organisasi yang berukuran kecil (termasuk pada
LAZ).23 Dari pernyataan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana
implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya
dalam perspektif TQM.
Langkah-langkah penelitian pada studi kasus sama dengan
penelitian kualitatif karena pada hakikatnya penelitian studi kasus
adalah bagian dari penelitian kualitatif.\ Adapun langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian studi kasus menurut Denzin adalah sebagai
berikut: (a) membatasi kasus, menentukan objek dari penelitian, (b)
menyeleksi fenomena-fenomena, tema atau isu (sebagai pertanyaan
penelitian, (c) menentukan pola data untuk mengembangkan isu, (d)
observasi triangulasi, (e) menyeleksi alternatif interpretasi, (f)
mengembangkan kasus yang telah ditentukan.24
2. Data yang Dikumpulkan
Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu
fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.25 Penelitian ini
membutuhkan data primer, yaitu berupa data dari informan yang terdiri
beberapa karyawan YDSF Surabaya. Sedangkan data sekunder
23 Aprita Nur Rahmadany, “Analisis Implementasi Total Quality Management pada Organisasi
Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa”, 4.
24Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.). “The Handbook of Qualitative Research
Thousand Oaks” (CA: Sage, 1994), 49.
dikumpulkan dari studi pustaka seperti; dokumen-dokumen lembaga,
buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya.
3. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.26 Dalam
penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan
oleh peneliti dari sumber pertamanya.27 Sumber data primer adalah
suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku
yang disebut first-hand information.28 Adapun yang menjadi sumber
data primer dalam penelitian ini adalah 4 orang karyawan YDSF
Surabaya yang diambil dari 1 orang Divisi Penghimpunan, 2 orang
Divisi Pendayagunaan, dan 1 orang Divisi Umum yang paham akan
penelitian ini. Jika informasi yang terkumpul masih kurang, maka
penggalian data selanjutnya akan dilakukan dengan teknik snowball
yaitu teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya
kecil tetapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi
yang didapatkan dinilai telah cukup.29
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktikCet.13 (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), 129.
27 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
28 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Revika Aditama, 2010), 239.
29 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan
oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga
dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.30
Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari
seminar, buku-buku, media cetak/elektronik, artikel, dan penelitian
terdahulu yang relevan. Adapun yanng menjadi sumber data
sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen
lembaga yang berisi data sejarah berdiri, informasi lokasi, struktur
organisasi, dan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik yang
digunakan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.31 Penelitian ini
menggunakan wawancara terstruktur kepada direktur dan beberapa
karyawan YDSF Surabaya. Wawancara terstruktur yaitu wawancara
30 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, 93.
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun
sebelumnya agar pertanyaan lebih terfokus. Saat melakukan
wawancara, selain membawa pedoman untuk wawancara, peneliti
juga menggunakan instrumen pendukung yang berupa alat perekam,
kamera, gambar, brosur, dan lainnya.
b. Observasi
Observasi merupakan kegiatan mengamati secara cermat dan
seksama terhadap fakta, data yang mengandung anasir-anasir
pemahaman yang tergali dan menjadi penyusun objek peristiwa
yang diteliti.32 Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi
pasif. Jadi, peneliti datang di tempat kegiatan untuk mengamati
kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, tetapi tidak ikut
terlibat dalam kegiatan tersebut.33
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui
dokumen.34 Dokumentasi dapat berupa buku profil lembaga, brosur,
foto kegiatan yang relevan dengan penelitian, dan lainnya.
32 Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), 205.
5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan
antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.35 Dalam hal
ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan
rumusan masalah saja.
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam
penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah
direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.36 Penulis
melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis
dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan
penulis dalam menganalisa data.
c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah
diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai
kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah
jawaban dari rumusan masalah.37
6. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian
yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 243. 36 Ibid., 245.
untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan data dalam
penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang terdiri dari:
a. Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber
data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.
Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan
sumber akan terjalin semakin akrab, terbuka, dan saling timbul
kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak
dan lengkap. Perpanjangan pengamatan difokuskan pada pengujian
terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah
dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau
masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah
diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan (benar) berarti
kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.
b. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian
Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan
agar kepastian data dan kronologis peristiwa dapat dicatat atau
direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan
merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah
data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau
dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian
terdahulu, dan dokumen-dokumen yang relevan.
c. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai
pengecekan data. Terdapat dua teknik triangulasi yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu:38
1) Triangulasi Sumber
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan
kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.39
2) Triangulasi Teknik
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui
wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik
pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang
berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada
sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana
yang dianggap benar.40
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain.41
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau
menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus
menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di balik fakta
dari yang terlihat atau terdengar tersebut. Dalam penelitian ini,
digunakan teknik induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap
hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui
dokumentasi, baru kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Pada
teknik induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.
Pada penelitian ini, manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF
Surabaya dianalisis dengan menggunakan konsep TQM yang
dikemukakan oleh Arthur Tenner melalui tiga prinsip yaitu: fokus
kepada pelanggan, perbaikan berkesinambungan, dan keterlibatan total.
Dipilihnya konsep Tenner tersebut, karena tiga prinsip itu dianggap mewakili
indikator keberhasilan penerapan TQM di sebuah lembaga.
I. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa
bab atau bagian bab yaitu sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang: latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
serta sistematika pembahasan.
Bab II Kerangka Teoretis memuat penjelasan teoretis mengenai
manajemen mutu, pengelolaan zakat, dan TQM.
Bab III Data Penelitian, memuat gambaran umum lembaga YDSF
Surabaya yang berisikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, 5 bidang
garap, serta potret manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya.
Bab IV Analisis Data, memuat tentang hasil analisis dan pembahasan
mengenai implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF
Surabaya dalam perspektif TQM.
BAB II
KERANGKA TEORETIS
A. Manajemen Mutu
Kata mutu atau kualitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “quality”.
Menurut KBBI, kualitas berarti: tingkat baik buruknya sesuatu; 2) derajat
atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); dan 3) mutu.1
Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan.2 Mutu mengacu pada dua pengertian pokok, yaitu sejumlah
keistimewaan produk dan segala sesuatu yang bebas dari kekurangan.3
Untuk memahami makna kualitas, dapat dilihat dari perspektif produsen
dan konsumen. Dalam pikiran pelanggan, kualitas mempunyai banyak
dimensi dan mungkin diterapkan dalam satu waktu. Pelanggan melihat
kualitas dari dimensi sebagai berikut:
1. Conformity to Specifications (Kesesuaian dengan Spesifikasi)
Pelanggan mengharapkan produk/jasa yang mereka beli memenuhi
atau melebihi tingkat kualitas tertentu seperti yang diiklankan. Kualitas
ditentukan oleh kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditawarkan.
Dalam sistem jasa, kesesuaian dengan spesifikasi juga perlu, walaupun
tidak menghasilkan sesuatu yang dapat disentuh. Spesifikasi untuk
1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 655.
operasi jasa berkaitan dengan pengiriman barang pada waktunya atau
kecepatan dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan pelanggan.
2. Value (Nilai)
Nilai menunjukkan seberapa baik produk/jasa mencapai tujuan yang
dimaksudkan pada harga pelanggan bersedia membayarnya. Kualitas
diukur dari harga yang dibayar untuk produk/jasa. Berapa nilai
produk/jasa dalam pikiran pelanggan tergantung pada harapan pelanggan
sebelum membelinya.
3. Fitness for Use (Kecocokan untuk Digunakan)
Kecocokan untuk digunakan menunjukkan seberapa baik produk/jasa
mewujudkan tujuan yang dimaksudkan, pelanggan mempertimbangkan
fitur mekanis produk atau kenyamanan pelayanan. Kualitas ditentukan
oleh seberapa jauh kecocokan produk/jasa untuk dipergunakan. Aspek lain
termasuk penampilan, gaya, daya tahan, keandalan, keahlian, dan
kegunaan.
4. Support (Dukungan)
Seringkali dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap
produk/jasa sangat penting bagi pelanggan, seperti halnya kualitas
pelayanan purna jual. Pelanggan bingung jika neraca keuangan salah,
respons atas klaim jaminan terlambat, atau iklan menyesatkan.
5. Psychological Impressions (Kesan Psikologi)
Orang sering mengevaluasi kualitas produk/jasa atas dasar kesan
psikologis: iklim, citra, atau estetika. Dalam pelayanan, di mana terdapat
kontak langsung dengan penyelenggara, penampilan dan tindakan
penyelenggara sangat penting. Pegawai yang berpakaian rapi, sopan,
bersahabat, dan simpatik dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap
kualitas pelayanan.
American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas
sebagai fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari sebuah produk/jasa
secara keseluruhan yang berpusat pada kemampuan produk/jasa tersebut
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah dinyatakan atau
tersirat.4
B. Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat
dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ).5 BAZNAS merupakan organisasi yang mengelola zakat yang
dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap kabupaten/kota.
Sedangkan LAZ adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh
masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. LAZ
dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang
bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk badan hukum,
umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZNAS.6 Eksistensi
BAZNAS dan LAZ diartikan sebagai fastabiqul khoira>t (berlomba-lomba
dalam kebaikan) dengan cara mengajak orang membayar zakat.
Dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa
pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian
serta pendayagunaan zakat.7 Penghimpunan zakat adalah suatu upaya atau
proses kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dana ZISWA, dan sumber
dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi,
perusahaan ataupun pemerintah) yang akan didistribusikan dan diberdayakan
untuk mustahi>q.8 Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat
haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa
serta memiliki sifat jujur dan amanah.
Jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw. dan para
sahabat kemudian diaplikasikan pada zaman sekarang, kita dapati bahwa
pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu berupa
bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat bukan berarti bahwa
6 Ibid.
zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan
sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahi>q tidak disertai
target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahi>q. Hal ini
dilakukan karena mustahi>q yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri
seperti pada diri para orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat
yang tidak memungkinkan untuk mandiri.9
Adapun pendistribusian zakat yang memberdayakan adalah
pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih
dikhususkan golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahi>q menjadi
kategori muzakki>. Ini merupakan target besar yang tidak dapat dicapai
dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, pendistribusian
zakat disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang
ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus
diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi
yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.10
Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan inti dari seluruh kegiatan
pengelolaan dana zakat. Jadi, harus disadari bahwa keberhasilan Organisasi
Pengelola Zakat (OPZ) bukan semata-mata terletak pada kemampuannya
dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan
mendistribusikan dan memberdayakannya.11
9 Iffatul Auliyaa’ Alwi, “Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang
Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 76.
Masalah pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam
masyarakat. Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan bagian terpenting
dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Pendistribusian zakat yang
baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional, seperti yang telah
dipraktikkan Rasulullah Saw. pada masa pemerintahannya.12
Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar
zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari
orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya. Kemudian mulailah dibuat
sistem pendistribusian dari wilayah tempat zakat itu diambil. Maka, daerah
itulah yang pertama mendapatkan jatah pendistribusiannya.13 Jumhur
Fuqaha᾽ sepakat bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (as}naf)
sebagaimana dalam Alquran surah At-Taubah [9]: 60.
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”15
Kesalahan terjadi ketika zakat diserahkan kepada orang yang tidak
berhak menerimanya, maka pembayaran zakat tersebut wajib dilakukan
12 Ibid., 74.
13 Yusuf Qardawi, Spektrum Zakat (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 141. 14 Alquran, 9: 60.
kembali. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu instrumen
pembangunan dalam ekonomi Islam, sehingga penerimanya haruslah tepat
sasaran berdasarkan syariat Islam.
Fatwa ulama, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Islam mewajibkan
agar dana zakat harus dibagikan segera dan tidak boleh ditunda-tunda
pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Karena pada zaman
Rasulullah Saw, beliau selalu mengutus para pekerja dan pengumpul zakat
untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban
untuk membayar zakat agar segera dibagikan pada orang-orang yang berhak.
Mereka tidak pernah menunda dan melambat-lambatkan.16
C. Total Quality Management (TQM)\
1. Definisi TQM
TQM adalah suatu pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh
organisasi masa kini untuk memperbaiki outputnya, menekan biaya
produksi, serta meningkatkan produksi.17 Total mempunyai konotasi
seluruh sistem, yaitu seluruh proses, seluruh pegawai, termasuk pemakai
produk dan jasa, serta supplier. Quality berarti karakteristik yang
memenuhi kebutuhan pemakai. Sedangkan Management berarti proses
16 Nurul Huda, et al., Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jakarta: Kencana,
2012), 173.
17 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha
komunikasi vertikal dan horizontal, top down dan buttom up, guna
mencapai mutu dan produktivitas.
Definisi TQM ada bermacam-macam. Berikut adalah beberapa
definisi TQM yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya yaitu:
a) Menurut Tjiptono dan Diana, TQM adalah suatu pendekatan dalam
menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing
organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa,
manusia, proses, dan lingkungannya.18
b) Menurut Vincent Gasperz, TQM didefinisikan sebagai suatu cara
meningkatkan performasi secara terus-menerus (continuous
performance improvement) pada setiap level operasi atau proses,
dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan
menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang
tersedia.19
c) Menurut Soewarso Hardjosoedarmo, TQM adalah penerapan
metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk
memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi,
memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, dan
memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan
jasa pada masa kini dan di waktu yang akan datang.20
18 Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management, 120. 19 Vincent Gasperz, Total Quality Management , 5.
20 Soewarso Hardjosoedarmo, Total Quality ManagementEdisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset,
TQM yang didefinisikan oleh para ahli pada dasarnya sama, yaitu
merupakan sistem manajemen prima suatu organisasi sebagai upaya
memperoleh keunggulan kompetitif dengan melibatkan seluruh anggota
organisasi melalui fokus kepada pelanggan, perbaikan menyeluruh dan
berkesinambungan, serta keterlibatan total.
2. Perbedaan TQM dengan Metode Manajemen Lainnya
Ada empat perbedaan pokok antara TQM dengan metode
manajemen lainnya yaitu:21
a. Asal Intelektualnya
Sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari
ilmu-ilmu sosial. Ilmu ekonomi mikro merupakan dasar dari sebagian
besar teknik-teknik manajemen keuangan (misalnya analisis
discounted cash flow, dan penilaian sekuritis); ilmu psikologi
mendasari teknik pemasaran dan decision support system; dan
sosiologi memberikan dasar konseptual bagi desain organisasi.
Sementara itu, dasar teoretis dari TQM adalah statistika. Inti dari
TQM adalah pengendalian proses statistikal (SPC/ Statistical
Process Control) yang didasarkan pada sampling dan analisis varian.
b. Sumber Inovasinya
Bila sebagian besar ide dan teknik manajemen bersumber dari
sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka,
maka inovasi TQM sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang
pada umumnya adalah insinyur teknik industri dan ahli fisika yang
bekerja di sektor industri dan pemerintah.
c. Asal Negara Kelahirannya
Kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen keuangan,
pemasaran, menajemen strategi, dan desain organisasi berasal dari
Amerika Serikat dan kemudian tersebar ke seluruh dunia.
Sebaliknya, TQM semula berasal dari Amerika Serikat, kemudian
lebih banyak dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang ke
Amerika Utara dan Eropa. Jadi, TQM mengintegrasikan
keterampilan teknikal dan analisis dari Amerika, keahlian
implementasi dan pengorganisasian Jepang, serta tradisi keahlian
dan integritas dari Eropa dan Asia.
Di Indonesia, konsep TQM pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1980-an dan saat ini, sudah cukup populer terutama di sektor
swasta antara lain dengan adanya program ISO-9000. Sampai saat
ini, ISO-9000 telah diterapkan oleh 53 negara termasuk MEE dan
negara-negara di Asia Selatan/Timur seperti Singapura, Malaysia,
ISO-9000 di mana dalam PP No. 15/1991 tentang Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan Keppres No 12/1991 tentang penyusunan,
penerapan dan pengawasan SNI, juga mengarah pada persyaratan
yang diterapkan oleh standar ISO-9000. Dengan adanya standar
nasional, pemerintah menginginkan perusahaan-perusahaan di
Indonesia dapat bersaing di dunia internasional dengan
produk-produk yang berkualitas sesuai standar internasional.22
d. Proses Diseminasi atau Penyebaran
Penyebaran sebagian besar menajemen modern bersifat
hirarkis dan top-down. Yang mempelopori biasanya adalah
perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Electric, IBM, dan
General Motors. Sedangkan gerakan perbaikan kualitas merupakan
proses buttom-up, yang dipelopori perusahaan-perusahaan kecil.
Dalam implementasi TQM, penggerak utamanya tidaklah selalu
CEO, tetapi seringkali malah manajer departemen atau manajer
divisi.
TQM ditinjau dari berbagai sudut memang memiliki
perbedaan orientasi dan landasan jika dibandingkan dengan
manajemen tradisional. Dari sudut pandang tujuan sebuah
organisasi atau perusahaan, misalnya TQM menekankan tujuan
22 N. Oneng Nurul Bariyah, “Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga
perusahaan pada melayani kebutuhan pelanggan dengan memasok
barang dan jasa yang memiliki kualitas setinggi mungkin. Ini berarti
bahwa filosofi yang mendasari cara kerja TQM adalah bagaimana
memberikan yang terbaik bagi orang lain.
Bila dirunut ke belakang, akan ditemukan landasan
normatifnya. Dalam keyakinan Islam misalnya, sebaik-baik manusia
(individu atau kelompok) adalah yang memberikan manfaat lebih
baik bagi orang lain. Berbeda dengan manajemen tradisional yang
menekankan sudut pandang perusahaan sebagai sebuah organisasi
yang bertujuan untuk memaksimumkan laba atau memaksimalkan
kemakmuran para pemilik.
Menurut Edward Deming, TQM merupakan jalan menuju
perolehan competitive advantage yang pada intinya terdiri dari
beberapa poin, di antaranya:23
1) Ciptakan keajegan tujuan dalam menuju perbaikan produk dan
jasa dengan maksud menjadi lebih dapat bersaing dan tetap
berada dalam bisnis dan untuk menciptakan lapangan kerja.
2) Mengadopsi falsafah baru. Kita berada dalam perekonomian
baru. Manajemen gaya baru harus bangun dan menghadapi
tantangan, harus belajar bertanggung jawab dan mengambil alih
kepemimpinan guna menghadapi perubahan.
3) Hentikan ketergantungan pada inspeksi atau mempertahankan
mutu.
4) Hentikan mempraktikkan bisnis berdasarkan daftar harga (price
list) sebaiknya usahakan adanya suatu pemasok untuk satu
barang, dengan tujuan adanya hubungan yang langgeng
berdasarkan loyalitas dan rasa saling percaya.
5) Perbaiki secara konstan dan terus-menerus mutu dan produksi
barang dan jasa untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.
6) Lembagakan on the job training.
7) Tujuan dari kepemimpinan harus untuk membantu orang lain
dan komponen lain sehingga dapat berkinerja lebih baik.
8) Galakkan pendidikan dan “self empowerment” bagi setiap
orang.
9) Mengadakan action agar transformasi berhasil.
4. Prinsip-Prinsip TQM
Arthur Tenner mengemukakan tiga prinsip utama dalam TQM.
Ketiga hal tersebut adalah:24
a. Fokus kepada Pelanggan (focus on customer). Kualitas didasarkan
kepada konsep bahwa setiap orang mempunyai pelanggan.
Keinginan dan harapan pelanggan harus dipenuhi setiap saat oleh
24 Arthur R Irving J. DeToro Tenner, “Total Quality Management, Three Steps to Continuous
sebuah organisasi. Oleh sebab itu, untuk menentukan keinginan
pelanggan, sejumlah analisis harus dilakukan agar tidak salah
langkah. Pihak lembaga harus melakukan penyesuaian terhadap
kebutuhan pelanggan atas kualitas serta melakukan langkah-langkah
yang tepat dan sesuai. Indikator fokus kepada pelanggan adalah:
1) Pelanggan diberikan pelayanan prima oleh lembaga.
2) Lembaga selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan.
3) Pelanggan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan
dan masukan kepada lembaga.
4) Lembaga selalu menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan
cepat dan tepat.
5) Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada
pelanggan.
b. Perbaikan proses (process improvement). Konsep peningkatan
kualitas secara terus-menerus berawal dari asumsi bahwa sebuah
hasil kerja merupakan akumulasi dari serangkaian langkah kerja
yang saling terakit hingga muncullah output. Perhatian yang
berkelanjutan terhadap setiap langkah dalam proses kerja
merupakan satu hal yang harus dilakukan demi mengurangi output
yang berbeda-beda dan meningkatkan kepercayaan proses. Tujuan
pertama dari perbaikan yang berkesinambungan adalah proses yang
akan sama dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Apabila
variasi output telah diperkecil namun hasilnya belum dapat
diterima, tujuan kedua dari perbaikan proses adalah mendesain
ulang proses produksi sehingga memperoleh hasil yang lebih baik
dan sesuai dengan harapan pelanggan. Indikator perbaikan proses
adalah:
1) Selalu berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus.
2) Strategi perbaikan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
3) Setiap karyawan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang
dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan
layanan yang berkualitas tinggi.
4) Selalu meningkatkan sarana dan prasarana lembaga.
c. Keterlibatan Total (total involvement). Pendekatan ini dimulai
dengan adanya pemimpin yang aktif dari manajemen senior dan
mencakup usaha untuk menggunakan keahlian karyawan dari
organisasi tersebut untuk meraih keuntungan persaingan di pasar.
Karyawan di setiap jenjang diberi bekal untuk meningkatkan hasil
kerja dengan bekerja sama dalam struktur bekerja yang fleksibel
dalam penyelesaian masalah, peningkatan proses, dan memberikan
kepuasan pada pelanggan. Begitu pula mitra kerja luar harus
terdidik untuk memberikan keuntungan bagi organisasi. Indikator
keterlibatan total adalah:
1) Pimpinan dan karyawan bersama-sama memajukan lembaga.
2) Pimpinan selalu melakukan pengecekan secara langsung dan
rutin atas kinerja karyawan.
3) Karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
5. Tujuan Penerapan TQM
Menerapkan TQM dapat dipahami sebagai upaya organisasi bisnis
untuk menjaga seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan
operasional usaha, baik pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan
aspek-aspek lainnya agar mampu bekerja secara harmonis dalam rangka
untuk memenuhi harapan-harapan dan keinginan-keinginan konsumen
atau melebihi ekspektasi mereka. Menurut Samdin, terdapat beberapa
alasan mengapa TQM perlu diterapkan dalam pengelolaan zakat oleh
LAZ di antaranya:25
a. Untuk meningkatkan daya saing dan unggul dalam persaingan.
b. Menghasilkan output/kinerja LAZ yang terbaik.
c. Meningkatkan kepercayaan muzakki>.
d. Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan dana zakat sehingga
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
25Samdin, “Pengembangan Manajemen BAZIS” (Makalah--Disajikan dalam Simposium Nasional
6. Manfaat TQM
Menurut Nasution, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari
penerapan TQM yang berhasil yaitu:26
a) Perbaikan kepuasan pelanggan.
b) Penghapusan kesalahan-kesalahan dan pemborosan.
c) Peningkatan dorongan semangat kerja dan tanggung jawab
karyawan.
d) Peningkatan profitabilitas dan daya saing.
7. TQM dalam Perspektif Islam
Konsep TQM memberi penekanan pada kepuasan pelanggan,
peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan, dan keterlibatan
tim. Hal ini melibatkan komitmen manajemen dan karyawan secara total
dalam usaha mencapai mutu yang lebih baik. Menurut konsep Islam,
memberi manfaat bagi orang lain merupakan sesuatu yang bernilai, di
mana salah satunya adalah dengan memberikan mutu yang terbaik
dalam bentuk barang atau jasa maupun pelayanan.27
Jika kita memperhatikan seluruh aspek dalam TQM, maka akan
tampak bahwa TQM adalah aplikasi dari ajaran Islam.28 Inti sari dari
26 Nasution, M. N., Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), 36.
27 Veithzal, Rivai, Islamic Human Capital (Jakarta: PT Raja Grafindo), 535.
28 Mohamad Toyyib Wibiksana, “Analisis Hubungan Implementasi Total Quality Management
TQM berupa perbaikan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam
Alquran surah Ar-Ra’du [13]: 11.
“…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”30
Dalam ayat tersebut, Islam megajarkan kepada manusia untuk selalu
berusaha memperbaiki suatu keadaan. Ajaran ini didukung pula dalam
Alquran surah Al-Insyirah [94]: 5-7 yang berbunyi:
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”32
Dalam ayat tersebut, terlihat jelas bahwa pentingnya melakukan
pekerjaan dengan berulang-ulang dan bersungguh-sungguh, sehingga
diperoleh hasil yang lebih baik dari pengalaman pekerjaan. Artinya,
untuk awal melakukan pekerjaan pasti ada kesulitannya, kemudian
dilakukan perbaikan berkesinambungan dan bersungguh-sungguh akan
diperoleh hasil yang lebih baik dan bermutu.
29 Alquran, 13: 11.
30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya , 250. 31 Alquran, 94: 5-7.
BAB III DATA PENELITIAN
A. Sejarah YDSF
Gagasan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya
bermula dari keinginan beberapa pengurus Yayasan Masjid Al-Falah, untuk
meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Falah
yang pertama, H. Abdul Karim (Alm).
Hampir setiap hari selepas menunaikan s}olat s}ubuh, beliau mempunyai
kebiasaan berkeliling di daerah pinggiran kota Surabaya untuk melihat
keadaan masjid/mus}olla> yang sedang dibangun. Apabila beliau menjumpai
pembangunan yang nampak terbengkalai, beliau segera menghubungi
beberapa hartawan muslim untuk diajak bersama-sama menuntaskan
kesulitan pembangunan tersebut.
Dari kebiasaan beliau yang mulia ini, muncullah ide untuk
melembagakannya dan mengelolanya secara baik. Ide tersebut segera
memperoleh dukungan dari beberapa pengurus dan aktivis muda Masjid
Al-Falah. Setelah melalui proses rapat dan persiapan yang cukup matang, pada
tanggal 1 Maret 1987 secara resmi didirikanlah YDSF Surabaya yang
diketuai oleh H. Abdul Karim.
Akan tetapi YDSF Surabaya belum lagi beroperasi, nampaknya Allah
Swt. berkehendak lain, karena H. Abdul Karim berpulang terlebih dahulu ke
pengurus lainnya, bahkan menjadi pemicu untuk segera melaksanakan ide
beliau yang sangat baik ini. Mereka, kawan-kawan beliau segera
melembagakan YDSF Surabaya dan menunjuk Ir. H. Abdul Kadir Baraja
sebagai ketuanya, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua.
YDSF Surabaya adalah lembaga sosial keagamaan yang memiliki
legalitas hukum, hal ini diperkuat dengan Akta Notaris Abdul Razaq
Ashiblie, S.H. Nomor 31 tanggal 14 April 1987. Dua tahun setelah lembaga
ini beroperasi, dikuatkan lagi dengan mendapatkan rekomendasi dari Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor B.IV/02/HK.03/6276/1989.
Agar yayasan yang baru dibentuk ini dapat segera beroperasi, maka
ditempatilah untuk sementara ruang lantai II Masjid Al-Falah sebagai kantor
YDSF Surabaya. Sistem operasional YDSF Surabaya pada awalnya belum
banyak menggunakan tenaga. Saat itu, YDSF Surabaya hanya ditangani oleh
3 (tiga) orang full time yang secara aktif memikirkan perkembangannya.
Mereka adalah Drs. H. Hasan Sadzili (Alm) sebagai Kepala Kantor, H. Nur
Hidayat sebagai Sekretaris, dan Syahid Haz (Alm) sebagai Koordinator Juru
Penerang dan Juru Pungut Infaq.
Sejalan dengan perkembangan kegiatan yayasan, kantor operasional pun
berpindah ke Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 Surabaya dengan mengambil salah
satu ruangan di lingkungan Lembaga Pendidikan Al-Falah (LPF). Dalam
waktu yang tidak lama, kegiatan YDSF Surabaya semakin hari semakin
bertambah. Jumlah donatur yang semula hanya beberapa ratus orang
yang semula hanya tiga orang bertambah menjadi belasan orang. Karena
dinilai kantor di Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 ini sudah tidak representatif
lagi, maka pada bulan Juni 1992 kantor operasional YDSF Surabaya
berpindah ke Jl. Darmokali 23A Surabaya.
Di kantor Darmokali ini, kegiatan YDSF Surabaya semakin bertambah
banyak. Kepala Kantor pun mengalami beberapa pergantian. Dari Drs. H.
Hasan Sadzili dialihkan ke Ir. Bimo Wahyu Wardoyo, dan kemudian
digantikan oleh Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (mantan Menteri
Pendidikan & Kebudayaan RI). Pada periode Dr. Ir. H. Mohammad Nuh,
DEA, istilah Kepala Kantor diganti dengan Direktur. Dengan masuknya Dr.
Ir. H. Mohammad Nuh, DEA sebagai Direktur YDSF, profesionalisme kerja
YDSF Surabaya semakin nyata. Semangat para pelaksana (karyawan YDSF
Surabaya) semakin bertambah, kegiatan kantor dengan program-programnya
pun semakin bertambah. Pada pertengahan tahun 1995, karena
pemikiran-pemikiran beliau sangat dibutuhkan untuk pengembangan YDSF Surabaya,
beliau diminta menjadi salah seorang pengurus, sedangkan jabatan Direktur
diamanahkan kepada Kasim Achmad (Alm).
Karena perkembangan donatur YDSF semakin hari semakin bertambah
jumlahnya, ditambah lagi dengan kegiatan layanan YDSF Surabaya yang
semakin banyak jumlahnya, maka diputuskan untuk segera mencari lokasi
baru yang tidak saja representatif bagi mobilisasi kegiatan kantor YDSF
Surabaya, tapi juga berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan
Pada tanggal 31 Mei 1996, kantor YDSF Surabaya berpindah ke Jl.
Manyar Kertoarjo V-23 Kav. 1 Surabaya, yaitu sebuah ruko berlantai 3 milik
salah seorang pengurus YDSF Surabaya. Sekitar 8 tahun di kantor Manyar
Kertoarjo ini, terjadi beberapa kali pergantian Direktur. Dari Kasim Achmad
ke Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. (Alm), dan kemudian ke drh. H. Hamy
Wahjunianto.
Pada tanggal 25 Desember 2004, YDSF Surabaya berpindah menempati
gedung kantor milik sendiri hingga kini di Jl. Kertajaya VIII-C/17 Surabaya.
Empat tahun setelah berpindah ke lokasi ini (2008) jabatan Direktur dari drh.
Hamy Wahjunianto dipercayakan kepada Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. Status
jabatan tersebut ’sementara’ karena Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. juga
menjabat sebagai Sekretaris Pengurus YDSF Surabaya.
Kini, amanah Direktur Pelaksana YDSF Surabaya diserahkan kepada
Jauhari Sani sejak 1 Mei 2011. Sebelumnya beliau menjabat Kepala Divisi
Pendayagunaan YDSF. Jauhari meniti karir di YDSF sejak 1993 sebagai staf
Data. Lalu berturut-turut menempati posisi sebagai Manajer Data (1997),
Senior Manajer Area III Data dan Media (2002), Direktur Pusat Layanan
Sosial Masyarakat YDSF (2005) dan Kepala Divisi Pendayagunaan (2008).1
Bulan Desember 2016 ini, YDSF Surabaya didukung oleh 270.622 donatur2
dan dana hasil penghimpunannya diberdayakan untuk 5 prgram (bidang
garap) yaitu; Pendidikan, Yatim, Dakwah, Masjid, dan Kemanusiaan.
1 Yayasan Dana Sosial Al-Falah, “Menengok Sejenak Perjalanan YDSF”, dalam www.ydsf.org,
diakses pada 19 April 2016.
B. Visi dan Misi YDSF Surabaya
1. Visi
YDSF Surabaya sebagai lembaga sosial yang benar-benar amanah
serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan
martabat umat Islam, khususnya di Jawa Timur.
2. Misi
Mengumpulkan dana masyarakat/umat baik dalam bentuk zakat,
infaq, s}adaqah, maupun lainnya dan menyalurkannya dengan amanah,
serta secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan:
a. Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam;
b. Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar;
c. Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkannya;
d. Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para dai,
khususnya yang berada di daerah pedesaan/terpencil;
e. Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang
C. Struktur Organisasi YDSF Surabaya
Gambar 3.1
Struktur Organisasi YDSF Surabaya3
1. Keterangan Staf dan Jabatannya:
a. Direktur Pelaksana : Jauhari Sani
b. Satuan Pengawas Internal : Wisnu Barata dan Samsir
c. Staf Ahli : -
d. Kadiv. Penghimpunan : Arif Prasojo
e. Kadiv. Pendayagunaan : H. M. Machsun
f. Kadiv. Keuangan : Hj. Enik Cahyani
g. Manajer Penghimpunan : Imam Zakaria
h. Manajer Marketing : Khoirul Anam
i. Manajer Layanan Donatur : Ragil Prawito
j. Manajer Zakat dan Kemanusiaan : Imron Wahyudi
k. Manajer Pendidikan dan Yatim : M. Guruh Hanafia
l. Manajer Dakwah dan Masjid : A. Basuki
m. Manajer Survei : Herman Khoirul
n. Manajer Keuangan : M. Mastur
o. Manajer Perencanaan Anggaran : Katon Basuki
p. Manajer Akuntansi : Ikhwan Trimaryono
q. Manajer Umum : Eko Agus
r. Manajer SDM : Affi Nurhadian
s. Manajer IT : Eko Sutrisno
D. 5 BIDANG GARAP YDSF4
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
a. Bantuan Fisik Pendidikan
b. Pena (Peduli Anak) Bangsa
c. Pembinaan Guru Islam
d. Pembinaan SDM Strategis
e. Kampung Alquran
2. Memberikan Santunan Yatim Piatu
a. Pemberdayaan Keluarga Yatim
b. Pembinaan Panti Yatim