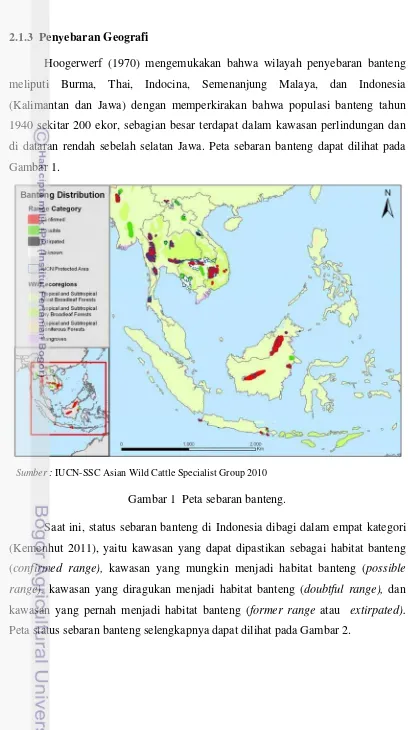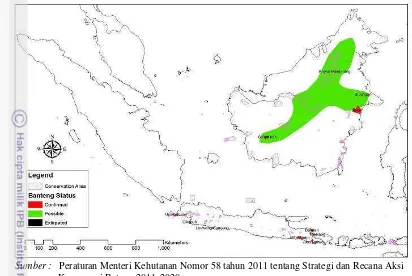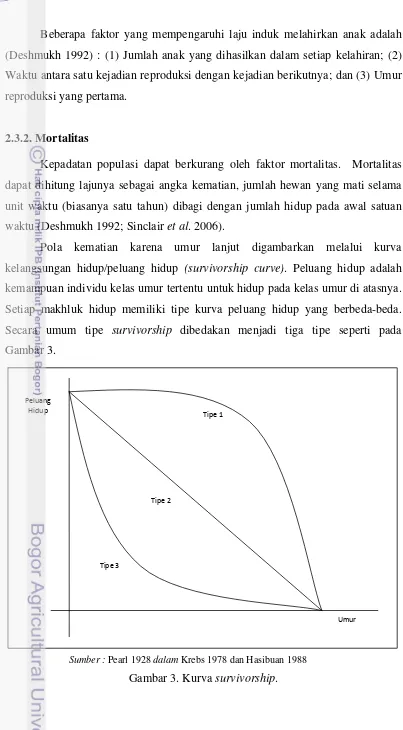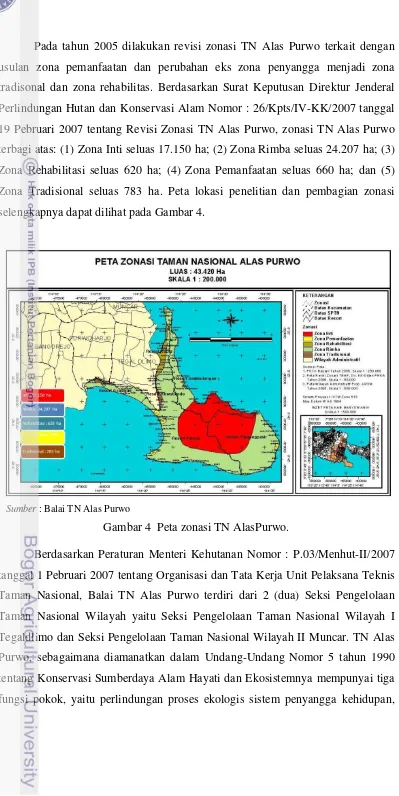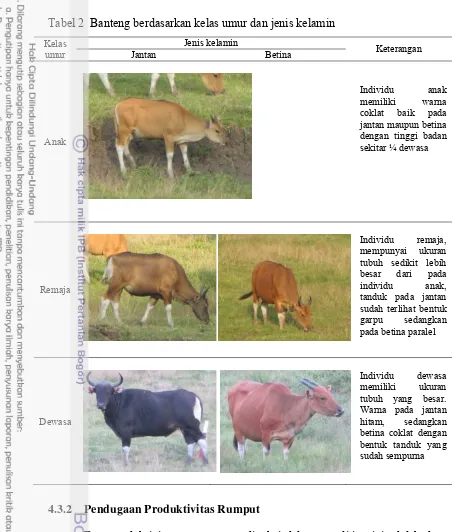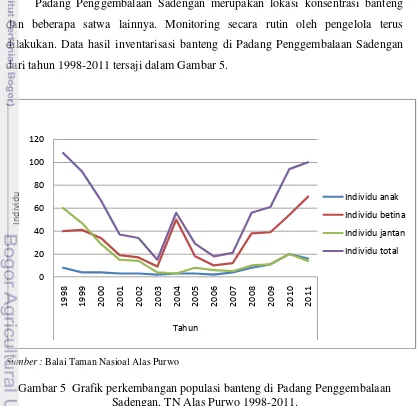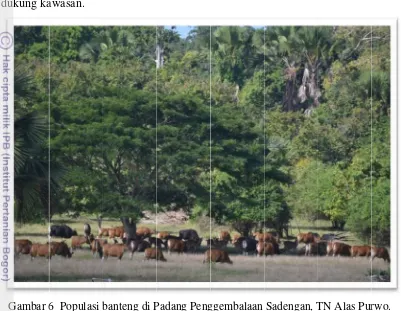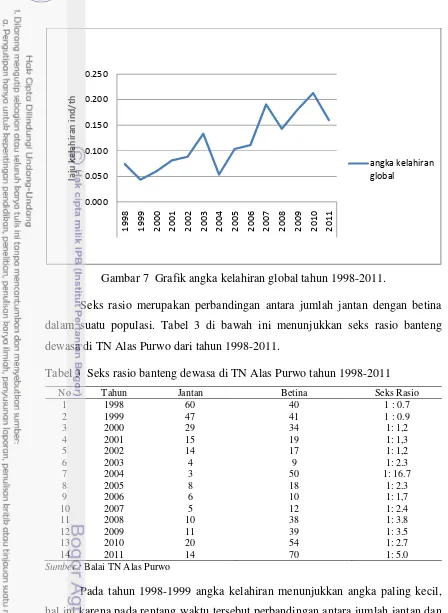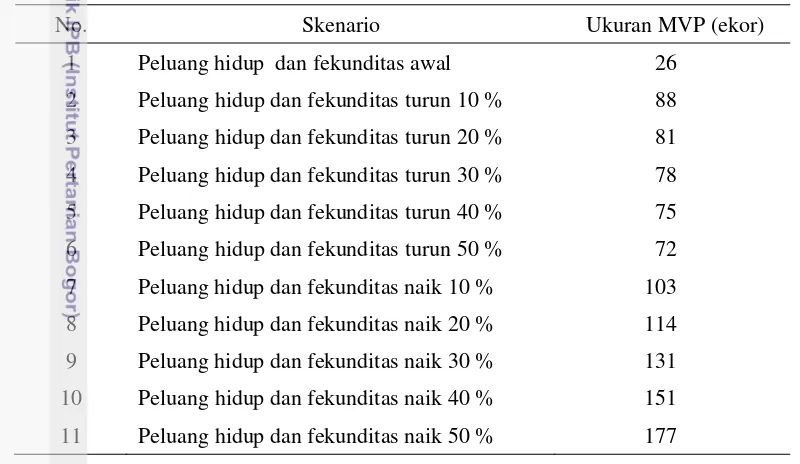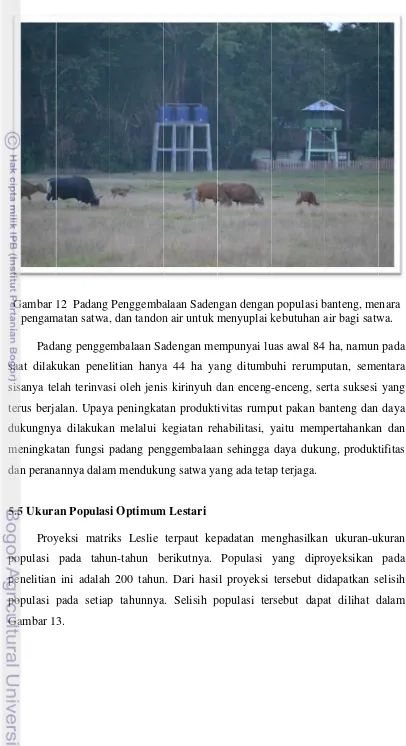PE
BERD
NASIO
ENENTUA
OPTIMU
DASARK
ONAL AL
IN
AN UKUR
UM LEST
KAN PARA
LAS PUR
SEKOLA
NSTITUT
RAN POP
TARI BAN
AMETER
RWO, BAN
MASUDAH PASC
T PERTA
BOGO
2012
PULASI M
NTENG (
R DEMO
NYUWAN
DAHCA SARJA
ANIAN BO
OR
2
MINIMU
(
Bos javan
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Penentuan Ukuran Populasi Minimum dan Optimum Lestari Banteng (Bos javanicus) berdasarkan Parameter Demografi di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Oktober 2012
Masudah
MASUDAH. Determining Minimum and Optimum Viable Population Size of Banteng (Bos javanicus) Based on Demographic Parameters at Alas Purwo National Park, Banyuwangi, East Java. Under direction of YANTO SANTOSA and ABDUL HARIS MUSTARI
One of the main goals of conservation is to maintain sustainability and to increase the population size of living species. In order to conserve an important wildlife population, Minimum Viable Population (MVP) and Optimum Viable Population (OVP) are the main population parameters that must be known. Banteng (Bos javanicus) are protected by the conservation law yet on the other hand has a great economic value for human. Research on MVP of banteng has not yet been performed up until now, and this was the main reason for undertaking a certain study. The aims of this study were to determine MVP and OVP of banteng as a basic point of wildlife management. To obtain the actual condition of the population (population size, sex ratio and age classes) an inventory method of Concentration Count was used, performed in Sadengan grazing field. Based on the assumption that all banteng would gather at this certain location, the counting was performed within 18 repetition and the largest counted number was then considered as the population size. The Algebra linear equation system from Leslie’s matrix was used to determine MVP, while the density dependence of Leslie’s matrix was used to determine the OVP. The population size used as base of calculation was the size of female population, and as for the male population size was predicted using the initial population’s sex ratio. The result showed that the MVP of banteng in Alas Purwo National Park was 94 with the domination of females in each of age classes, which predicted would occur in a year ahead (2013). As for the OVP was 149, also dominated by females and predicted to be occured in the next 30 years (2024).
MASUDAH. Penentuan Ukuran Populasi Minimum dan Optimum Lestari Banteng (Bos javanicus) berdasarkan Parameter Demografi di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dibimbing oleh YANTO SANTOSA dan ABDUL HARIS MUSTARI
Sebagai kawasan konservasi di mana kategori wilayah penyebaran banteng berstatus Confirmed Range, TN Alas Purwo merupakan salah satu kawasan prioritas pada Program Pengelolaan Populasi Banteng di Pulau Jawa. Selain itu, TN Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang telah menerapkan sistem pengelolaan kawasan berbasis resort sehingga manajemen pengelolaannya sudah berbasis kinerja petugas di level terendah dalam pengelolaan taman nasional.
Salah satu tolok ukur dari kelestarian adalah ukuran populasi minimum lestari atau Minimum Viable Population (MVP). Penentuan ukuran populasi minimum lestari sangat penting dalam manajemen populasi terutama dalam penyusunan rencana pengelolaan spesies. Selain ukuran populasi minimum lestari, ukuran populasi optimum lestari atau Optimum Viable Population (OVP) juga penting untuk dikaji. Ukuran populasi optimum lestari merupakan kondisi di mana pada ukuran populasi tersebut laju pertumbuhan populasi akan maksimal. Dengan laju pertumbuhan maksimal, populasi akan bertambah dengan cepat.
Penelitian dilaksanakan di TN Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dan pengolahan data dilaksanakan selama 6 bulan yaitu pada bulan Maret s.d Agustus 2012. Data demografi banteng yang diperlukan meliputi: ukuran populasi, kelas umur, seks rasio, peluang hidup, fekunditas, dan usia kawin. Data yang dikumpulkan di lapangan berupa ukuran populasi, kelas umur dan sex rasio. Peluang hidup dan fekunditas didapatkan dari hasil analisis data lapangan sedangkan usia kawin didapatkan dari hasil studi pustaka. Penghitungan populasi dilakukan dengan metode penghitungan terkonsentrasi dengan asumsi bahwa pada saat pengamatan, banteng berkumpul di Padang Penggembalaan Sadengan. Pengamatan dilakukan selama 18 kali ulangan. Ukuran populasi tertinggi merupakan ukuran populasi pada saat pengamatan.
didapatkan dari perbandingan seks rasio.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran populasi minimum lestari banteng di TN Alas Purwo adalah 94 ekor dengan jumlah betina anak 21 ekor, jantan anak 7 ekor, betina remaja 28 ekor, jantan remaja 9 ekor, betina dewasa 23 ekor, dan jantan dewasa 6 ekor dan diprediksi akan tercapai satu tahun mendatang. Ukuran Populasi optimum lestari banteng di TN Alas Purwo adalah 149 ekor dengan jumlah anak betina 23 ekor, anak jantan 8 ekor, betina remaja 39 ekor, jantan remaja 12 ekor, betina dewasa 53 ekor, dan jantan dewasa 14 ekor dan diprediksi akan tercapai 30 tahun yang akan datang atau pada tahun 2042.
© Hak cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
OPTIMUM LESTARI BANTENG (
Bos javanicus)
BERDASARKAN PARAMETER DEMOGRAFI DI TAMAN
NASIONAL ALAS PURWO, BANYUWANGI, JAWA TIMUR
MASUDAH
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada
Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Banteng (Bos javanicus) berdasarkan Parameter Demografi di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur
Nama : Masudah
NRP : E.353100035
Disetujui,
Komisi Pembimbing
Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA. Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, M.Sc.F
Ketua Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana
Konservasi Keanekaragaman Hayati
Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur sejak Maret 2012.
Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:
1. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, yang telah memberikan izin dan kesempatan melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor;
2. Bapak Ir. Sri Winenang, MM dan Ir. Sahabuddin (Kepala BKSDA Sulawesi Tengah) yang mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar;
3. Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA (ketua komisi pembimbing) dan Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, M. Sc. F (anggota komisi) atas curahan pemikiran, waktu, kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini;
4. Dr. Ir. Burhanuddin Masy’ud, MSselaku penguji luar komisi pada ujian sidang tesis yang telah menyediakan waktu untuk memberikan koreksi, masukan dan saran dalam penyempurnaan tesis ini;
5. Bapak Rudijanta Tjahja Nugraha, S.Hut, M. Sc beserta Staf Balai Taman Nasional Alas Purwo yang telah membantu selama pengumpulan data;
6. Suami tercinta Agus Yulianto, S.Si. MIDS; anak-anakku tersayang Afiqah Husnayani Almas, Afnan Huwaiza Almas, dan Athifa Huriyah Almas juga ayah, ibu dan saudara-saudaraku atas doa dan dukungannya selama penulis menjalani studi;
7. Lugi Hartanto, S.P, M.Sc, Dian Sulastini, S.Si, M. Sc, Kusmardiastuti S.Hut, MP, dan Astri Yuliawati, S.Si, M.Si atas bantuannya selama penelitian;
8. Teman-temen seperjuangan Program Magister Profesi KKH 2010 (Nyoto, Yusuf, Teguh, Septi, Mbah Parjoni, Desi, Hendra, Mas nDok, Sri Mina, Ferdi, Mbak Leni, Lintang, Pak Yarman, Mirta, Mbak Lusi, Via, Cahyo, dan Mas Buday) atas kebersamaan, kekompakan dan kerjasama dalam suka dan duka; 9. Pak Sofwan dan Bi Uum yang selalu siap membantu dengan pelayanan
terbaiknya.
Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini, maka hanya penulis yang bertanggung jawab. Kiranya Allah SWT yang memberi balasan dan ahir kata semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Oktober 2012
Penulis dilahirkan di Dukuhturi, Tegal pada tanggal 2 Agustus 1974 dari suami istri Bapak Tarya dan Ibu Taripah (Almh). Penulis merupakan anak kesepuluh dari dua belas bersaudara.
Tahun 1993 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Slawi, Kabupaten Tegal dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan dan lulus pada tahun 1998.
Sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 penulis bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I Yogyakarta, tahun 2003 sampai dengan 2006 penulis bekerja di Balai Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dan tahun 2006 hingga sekarang penulis bekerja di Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah sebagai pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Tahun 2010 penulis ditugaskan sebagai karyasiswa Kementerian Kehutanan pada Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati (Program Magister Profesi), Sekolah Pasca Sarjana IPB.
xvii
Halaman
DAFTAR TABEL ... xix
DAFTAR GAMBAR ... xxi
DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii
I. PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Tujuan ... 2
1.3 Kegunaan ... 2
II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3
2.1 Bioekologi Banteng ... 3
2.1.1 Taksonomi ... 3
2.1.2 Morfologi dan Anatomi ... 3
2.1.3 Penyebaran Geografi ... 4
2.1.4 Habitat ... 5
2.1.5 Perilaku ... 8
2.2 Status Perlindungan Banteng ... 8
2.3 Parameter Demografi ... 9
2.3.1 Natalitas ... 9
2.3.2 Mortalitas ... 10
2.3.3 Perkembangbiakan dan Reproduksi ... 11
2.3.4 Struktur Umur dan Seks Rasio ... 12
2.3.5 Penentuan Kelas Umur Banteng ... 12
2.4 Populasi Minimum Lestari ... 13
2.5.1 Pengertian ... 13
2.5.2 Pendekatan untuk Menentukan MVP ... 15
2.5 Populasi Optimum Lestari ... 16
2.6 Produktivitas Rumput dan Daya Dukung ... 17
III. KONDISI UMUM LOKASI ... 19
3.1 Letak, Luas, dan Status Kawasan ... 19
3.2 Topografi, Geologi, Iklim, dan Hidrologi ... 21
3.3 Flora, Fauna, dan Ekosistem ... 23
3.4 Padang Penggembalaan Sadengan ... 24
IV. BAHAN DAN METODE ... 27
4.1 Lokasi dan Waktu ... 27
4.2 Alat dan Bahan ... 27
4.3 Metode Pengumpulan Data ... 27
4.3.1 Pengumpulan Data Demografi Banteng ... 27
xviii
4.4.3 Peluang Hidup ... 29
4.4.4 Fekunditas dan Usia Kawin ... 30
4.4.5 Daya Dukung ... 30
4.4.6 Ukuran Populasi Minimum Lestari ... 30
4.4.7 Penentuan Laju Pertumbuhan Finit ... 31
4.4.8 Ukuran Populasi Optimum Lestari ... 32
V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35
5.1 Perkembangan Populasi Banteng di TN Alas Purwo ... 35
5.2 Ukuran Populasi Minimum Lestari ... 40
5.3 Analisis Sensitivitas terhadap Peluang Hidup dan Fekunditas... 46
5.4 Produktivitas dan Daya Dukung ... 46
5.5 Ukuran Populasi Optimum Lestari ... 49
5.6 Pertumbuhan Populasi berdasarkan Matriks Leslie Terpaut Kepadatan ... 53
VI. SIMPULAN DAN SARAN ... 57
6.1 Simpulan ... 57
6.2 Saran ... 57
DAFTAR PUSTAKA ... 59
xix
Halaman
1. Hubungan antara umur banteng, tinggi sampai pundak,dan
panjang tanduk ... 13
2. Banteng berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin ... 28
3. Seks rasio banteng dewasa di TN Alas Purwo 1998-2011 ... 38
4. Ukuran populasi, struktur umur, dan seks rasio banteng hasil
pengamatan ... 40
5. Ukuran populasi minimum lestari banteng di TN Alas Purwo ... 45
6. Analisis sensitivitas peluang hidup dan fekunditas terhadap
ukuran populasi minimum lestari ... 46
7. Produktivitas hijauan pakan di Padang Penggembalaan
xxi
Halaman
1. Peta sebaran banteng ... 4 2. Peta status sebaran banteng di Indonesia ... 5
3. Kurva survivorship ... 10 4. Peta zonasi TN Alas Purwo ... 20
5. Grafik perkembangan populasi banteng di Padang
Penggembalaan Sadengan TN Alas Purwo 1998-2011 ... 35
6. Populasi banteng di Padang Penggembalaan Sadengan, TN Alas
Purwo ... 37
7. Grafik angka kelahiran kasar tahun1998-2011 ... 38
8. Grafik angka kematian kasar banteng tahun 1998-2011 ... 39
9. Struktur umur banteng di TN Alas Purwo ... 41
10. Grafik peluang hidup banteng di TN Alas Purwo ... 42
11. Padang Penggembalaan Sadengan, TN Alas Purwo ... 48
12. Padang Penggembalaan Sadengan dengan populasi banteng, menara pengamatan satwa, dan tandon air untuk menyuplai
kebutuhan air bagi satwa ... 49
13. Grafik selisih jumlah individu banteng setiap tahun di TN Alas
Purwo ... 50
14. Kirinyuh dan enceng-enceng ... 52
xxiii
Halaman
1. Contoh perkalian Matriks Leslie Terpaut Kepadatan. ... 67
2. Perhitungan ukuran populasi minimum lestari dengan sistem
persamaan aljabar linier dengan metodeeliminasi ... 69
3. Tabel perkembangan populasi banteng di TN Alas Purwo ... 73
4. Akar ciri proyeksi matriks M ... 77
5. Hasil analisis sensitivitas peluang hidup dan fekunditasterhadap
1.1 Latar belakang
Banteng sebagai salah satu jenis satwa liar memiliki nilai ekonomi dan
budaya yang penting bagi umat manusia sejak dahulu, yaitu sebagai sumber
protein, bahan untuk membuat peralatan (baik dari tulang maupun tanduknya),
kepercayaan, dan alat penutup tubuh (Alikodra 1983). Sejak tahun 1996, banteng
dikategorikan “Endangered” atau “Terancam Kepunahan” dalam Red Data List
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Banteng juga dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan
Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa.
Di Indonesia, populasi dan habitat banteng terus menurun. Ancaman utama
adalah konversi lahan dan kerusakan habitat, perburuan liar dan predator.
Populasi banteng hanya terkonsentrasi di kawasan hutan, terutama di kawasan
konservasi. Beberapa lokasi yang masih bisa dijumpai adanya banteng antara lain
di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, TN Baluran, TN Meru Betiri, dan TN Alas
Purwo, serta di beberapa kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan
kawasan konservasi tersebut.
Sebagai kawasan konservasi berstatus Confirmed Range untuk penyebaran banteng di Indonesia, TN Alas Purwo merupakan salah satu kawasan prioritas
pada Program Pengelolaan Populasi Banteng di Pulau Jawa (Kemenhut, 2011).
Selain itu, TN Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang telah menerapkan
sistem pengelolaan kawasan berbasis resort sehingga manajemen pengelolaannya
sudah berbasis kinerja petugas di level terendah dalam pengelolaan taman
nasional yang sudah mengcover pengelolaan banteng sebagai unit tersendiri.
Salah satu tolok ukur dari kelestarian pengelolaan banteng adalah ukuran
populasi minimum lestari atau Minimum Viable Population (MVP). Penentuan ukuran populasi minimum lestari sangat penting dalam manajemen populasi
terutama dalam penyusunan rencana pengelolaan spesies. Ukuran populasi
Soule 1995; Wielgus 2001). Keberhasilan upaya pelestarian dicirikan oleh ukuran
populasi yang mencapai MVP, di mana dipastikan tidak akan terjadi penurunan
ukuran populasi. Ukuran populasi optimum lestari atau Optimum Viable Population (OVP) menunjukkan keadaan pertumbuhan populasi maksimal, di mana populasi akan bertambah dengan cepat. Kondisi ini perlu dipertahankan jika
pengelolaan satwa bertujuan untuk pemanfaatan. Penelitian tentang MVP dan
OVP banteng sampai saat ini belum dilakukan.
Pada umumnya ukuran populasi minimum lestari maupu ukuran optimum
lestari yang diperoleh merupakan ukuran populasi secara keseluruhan dan belum
menunjukkan komposisi/perbedaan kelas umur, padahal peluang hidup pada
masing-masing kelas umur berbeda. Data dan informasi ini sangat penting dalam
rangka pengaturan populasi agar kelestariannya terjamin dalam jangka panjang
(Wielgus 2001). Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai penentuan
ukuran populasi minimum dan optimum lestari banteng berdasarkan parameter
demografi untuk setiap kelas umur dan jenis kelamin.
1.2 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menentukan ukuran populasi minimum lestari banteng pada setiap kelas
umur dan jenis kelamin;
2. Menentukan ukuran populasi optimum lestari banteng pada setiap kelas umur
dan jenis kelamin.
1.3 Kegunaan
Hasil penghitungan nilai populasi minimum dan optimum lestari ini
diharapkan dapat dijadikan target pengelolaan banteng sehingga kelestariannya
terjaga. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penentuan kuota
tangkap dan acuan waktu pemanenan. Selain itu, data yang diperoleh bermanfaat
II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Bioekologi Banteng
2.1.1 Taksonomi
Lekagul dan McNeely (1977) mengklasifikasikan banteng ke dalam dunia
Animalia, filum Choerdata, kelas Mammalia, orda Artiodactyla, Famili Bovidae,
genus Bos, spesies Bos javanicus dan sub species Bos javanicus javanicus
(terdapat di Jawa, Madura, dan Bali, Indonesia), Bos javanicus lowi (terdapat di Kalimantan) dan Bos javanicus birmanicus (terdapat di Indocina).
2.1.2 Morfologi dan Anatomi
Banteng memiliki morfologi tubuh yang tegap, besar dan kuat dengan
bahu bagian depannya lebih tinggi dari pada bagian belakang tubuhnya. Tinggi
pundak banteng mencapai 120-70 cm. Bagian dada banteng terdapat gelambir
yang dimulai dari pangkal kaki depan sampai bagian leher, tetapi tidak mencapai
daerah kerongkongan. Maryanto et al. (2008) menyatakan bahwa bentuk tubuh betina banteng lebih kecil dibandingkan dengan jantan. Tinggi jantan mencapai
1.9 m dengan bobot badan 825 kg, sedangkan tinggi betinanya 1.6 m dengan
bobot badan 635 kg. Banteng asal Kalimantan umumnya mempunyai ukuran lebih
pendek atau kecil.
Banteng juga memiliki warna kulit dan sepasang tanduk yang dapat
membedakan jenis kelamin dan umur banteng. Banteng jantan memiliki warna
kulit hitam, semakin tua umurnya semakin hitam warna tubuhnya. Banteng betina
tubuhnya berwarna coklat kemerah-merahan, semakin tua umurnya, maka
warnanya akan semakin gelap menjadi coklat tua. Anak banteng baik yang jantan
maupun betina berwarna coklat, sehingga sulit untuk dibedakan jenis kelaminnya.
Tanduk pada banteng jantan berwarna hitam mengkilap, runcing dan melengkung
simetris ke dalam, sedangkan pada banteng betina bentuk tanduknya lebih kecil
2.1.3 Penyebaran Geografi
Hoogerwerf (1970) mengemukakan bahwa wilayah penyebaran banteng
meliputi Burma, Thai, Indocina, Semenanjung Malaya, dan Indonesia
(Kalimantan dan Jawa) dengan memperkirakan bahwa populasi banteng tahun
1940 sekitar 200 ekor, sebagian besar terdapat dalam kawasan perlindungan dan
[image:30.595.76.484.76.806.2]di dataran rendah sebelah selatan Jawa. Peta sebaran banteng dapat dilihat pada
Gambar 1.
Sumber : IUCN-SSC Asian Wild Cattle Specialist Group 2010
Gambar 1 Peta sebaran banteng.
Saat ini, status sebaran banteng di Indonesia dibagi dalam empat kategori
(Kemenhut 2011), yaitu kawasan yang dapat dipastikan sebagai habitat banteng
(confirmed range), kawasan yang mungkin menjadi habitat banteng (possible range), kawasan yang diragukan menjadi habitat banteng (doubtful range), dan kawasan yang pernah menjadi habitat banteng (former range atau extirpated).
Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 58 tahun 2011 tentang Strategi dan Recana Aksi
[image:31.595.98.510.94.370.2]Konservasi Bateng 2011-2020
Gambar 2 Peta status sebaran banteng di Indonesia.
2.1.4 Habitat
Habitat merupakan suatu rangkaian interkasi antara komponen biotik
dengan komponen abiotik yang ditempati oleh suatu komunitas atau populasi
kehidupan. Komponen biotik terdiri dari berbagai organisme yang hidup,
sedangkan komponen abiotik terdiri dari berbagai benda mati atau faktor-faktor
lingkungan yang mendukung atau sering berinteraksi dengan komponen biotik,
seperti iklim, suhu, kelembaban, tanah dan sebagainya. Keberadaan kedua
komponen tersebut akan mempengaruhi kelengkapan suatu habitat bagi suatu
spesies di segala musim ataupun pada musim-musim tertentu. Alikodra (2002)
menyatakan bahwa ukuran dari kelengkapan suatu habitat adalah mampu
menyediakan berbagai keperluan bagi suatu spesies termasuk sumber makanan,
minum dan perlindungan (cover), dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan oleh spesies hidupan liar untuk bertahan hidup dan melangsungkan reproduksinya
2.1.4.1 Pakan
Hoogerwerf (1970) berdasarkan hasil pengamatannya di TN Ujung Kulon
menunjukkan bahwa komposisi pakan banteng terdiri atas 20 spesies rumput, dan
70 spesies non rumput yang hampir semuanya adalah jenis-jenis tumbuhan hutan
sekunder, dan hanya enam jenis yang merupakan spesies hutan primer. Pairah
(2007) berdasarkan hasil penelitian di TN Alas Purwo bahwa makanan banteng
terdiri dari 22 jenis rumput dan 55 jenis non rumput.
Banteng jika dilihat dari komposisi pakan di atas, sebagai hewan herbivora
lebih dominan memakan rumput-rumputan (grazer). Akan tetapi Hoogerwerf (1970) juga menambahkan hasil penelitiannya pada lambung beberapa banteng
jantan yang tertembak di Cianjur Selatan ditemukan bahwa pakan banteng hampir
seluruhnya terdiri dari non rumput, yaitu daun-daun Trema orientale, Passiflora foetida, Lygodium sp., dan Musa sp., bahkan ada satu banteng yang pakannya hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan yaitu Passiflora foetida. Penelitian Muntasib dan Masy’ud (2000) juga menguatkan bahwa banteng diperkirakan
telah mengalami perubahan pola makan dari grazer menjadi peragut (pemakan daun dan semak), karena dari proporsi jenis non rumput termasuk jenis hijauan
yang relatif memiliki serat kasar tinggi yang dimakan banteng lebih besar dari
pada jenis rumput, yaitu mencapai 48,2%.
2.1.4.2 Ketersediaan Air
Kebutuhan air yang digunakan banteng tidak hanya air tawar, tetapi
diperlukan juga air laut untuk memenuhi kebutuhan garam/mineralnya.
Kebutuhan banteng akan air tawar biasanya dapat dipenuhi dari sumber-sumber
air alami, seperti sungai, kawasan karst, genangan-genangan air pada musim
hujan dan sebagainya. Sumber air lainnya, yaitu dari sumber air buatan yang
biasanya ditampung dalam bak penampungan. Santosa dan Delfiandi (2007)
berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa banteng di TN Alas Purwo
memenuhi kebutuhan airnya berasal dari 2 sumber, yaitu sumber alami dari aliran
sungai gua-gua yang mengalir sepanjang tahun dan sumber air buatan yang
untuk memenuhi kebutuhan airnya hanya bersumber dari Sungai Cidaun dan
Sungai Cijungkulon (Alikodra 1983).
Peranan air ini sangat penting dalam tubuh agar dapat memperlancar reaksi
kimia dan merupakan medium ionisasi dan hidrolisa zat makanan yang sangat
baik. Asam-asam amino yang terdapat dalam air akan mengalami ionisasi
sehingga zat makanan akan lebih reaktif. Selain itu, Alikodra (1983) menyatakan
bahwa air merupakan faktor pembatas bagi kehidupan banteng dan satwa liar
lainnya. Oleh karena itu, apabila ketersediaan air berkurang, akan sangat
mempengaruhui kelangsungan kehidupan satwa liar. Dengan demikian, kebutuhan
banteng akan air pun sangat penting untuk pertumbuhannya.
2.1.4.3 Cover
Habitat utama banteng adalah di hutan tropis atau sub tropis kering dan
savana. Banteng tinggal pada dataran terbuka dan kering di daerah hutan sekunder
akibat penebangan maupun kebakaran, dan jarang ditemukan pada dataran tinggi,
sehingga banteng ini termasuk satwa dataran rendah. Alikodra (1983) menyatakan
bahwa tempat yang ideal bagi banteng merupakan suatu kesatuan (ekosistem)
yang terdiri dari hutan, padang penggembalaan dan sumber-sumber air.
Banteng merupakan satwaliar yang menyukai tipe habitat yang lebih
terbuka (Hoogerwerf 1970). Akan tetapi Lekagul & McNeely (1977) menjelaskan
bahwa sebelum perang dunia II banteng selalu merumput di tempat terbuka
selama pagi hari dan sore hari, dan beristirahat di bawah hutan pada saat matahari
bersinar sangat terik.
Hoogerwerf (1970) menyatakan bahwa hutan yang tertutup tidak cocok
sebagai habitat banteng, areal terbuka di dalam atau di pinggiran hutan lebih
cocok sebagai habitat banteng. Sebagai contoh di Jawa, Banteng tidak termasuk
ke dalam jenis yang hidup di dalam hutan, namun hidup pada areal terbuka
berumput atau ditumbuhi rumput yang mirip tanaman (grasslike plants), dan memiliki hutan yang tertutup di salah satu bagian kawasan seperti di TN Ujung
2.1.5 Perilaku
Alikodra (2002) menyatakan bahwa perilaku adalah semua gerakan atau
kegiatan satwa untuk melestarikan atau mempertahankan hidupnya dan dapat
diartikan sebagai ekspresi suatu binatang yang disebabkan atau ditimbulkan oleh
semua faktor yang mempengaruhinya. Alikodra (1983) menyatakan bahwa
banteng merupakan satwa liar yang kurang selektif terhadap jenis tumbuhan yang
dimakannya dan lebih bersifat sebagai satwa pemakan rumput (grazer) dibandingkan dengan pemakan daun dan atau semak (browzer).
Banteng merupakan satwa herbivora yang lebih sebagai pemakan rumput
(grazer) daripada sebagai pemakan semak (browzer) sehingga lebih menyukai habitat yang terbuka untuk mencari makan. Menurut Priyatmono (1996)), banteng
kurang menyukai hutan primer yang tidak terdapat semak-semak atau tumbuhan
bawah yang merupakan makanannya, sedangkan menurut Alikodra dan
Sastradipradja (1983), hutan dataran rendah dijadikan sebagai tempat
bersembunyi dari berbagai macam gangguan dan dijadikan sebagai tempat
berlindung dari kondisi cuaca yag tidak menentu.
2.2 Status Perlindungan Banteng
Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan terhadap banteng sejak
tahun 1931 melalui Peraturan Perlindungan Binatang Liar 1931 yang tertulis
dengan nama Bos sondaicus. Penurunan populasi banteng yang terus terjadi menyebabkan pemerintah mengambil salah satu langkah untuk melestarikan
banteng dengan menetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi undang-undang
(SK Menteri pertanian No.327/Kpts/Um/7/1972) yang dilakukan di sejumlah
kawasan konservasi di Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah kembali
menguatkan bahwa banteng merupakan salah satu satwa yang dilindungi melalui
Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa.
minimal 50% berdasarkan pengamatan langsung, penurunan tingkat kejadian,
perdagangan ilegal tingkat tinggi bagian Banteng (terutama tanduk), dan karena
adanya perdagangan daging secara tak terkendali di Asia Tenggara dan dari
berburu untuk perdagangan tanduk, serta hilangnya habitat dan degradasi di Jawa
(IUCN 2004). Ancaman utama terhadap kelestarian banteng menurut IUCN
(2004) adalah :
1. Hilangnya atau rusaknya habitat yang disebabkan oleh kegiatan pertanian dan
perkebunan serta pembangunan pemukiman penduduk;
2. Spesies asing invasive (yang berpengaruh secara langsung terhadap spesies
dan munculnya kompetitor);
3. Perburuan, yaitu pengambilan berlebihan terhadap spesies yang dilakukan
oleh manusia;
4. Perubahan dalam dinamika spesies asli, yaitu dengan adanya domestikasi dan
hibridisasi serta adanya penyakit/pathogen.
2.3 Parameter Demografi
2.3.1 Natalitas
Populasi meningkat karena natalitas. Tingkat natalitas setara dengan angka
kelahiran, natalitas hanya menjadi kata yang lebih luas yang mencakup produksi
individu baru dengan kelahiran, penetasan, perkecambahan, atau fisi. Tingkat
natalitas dapat dinyatakan sebagai jumlah organisme lahir per wanita per satuan
waktu. Pengukuran tingkat natalitas atau kelahiran sangat tergantung pada jenis
organisme yang dipelajari (Krebs 1978).
Natalitas merupakan jumlah individu baru (anak) yang lahir dalam suatu
populasi yang dapat diyatakan dalam beberapa cara yaitu produksi individu baru
dalam suatu populasi, laju kelahiran per satuan waktu atau laju kelahiran per
satuan waktu per individu (Odum 1971). Natalitas dapat dinyatakan dalam laju
kelahiran kasar (crude birth rate), yaitu perbandingan antara jumlah individu yang dilahirkan dengan jumlah seluruh anggota populasi pada satu periode waktu; dan
laju kelahiran pada umur spesifik yang merupakan perbandingan antara jumlah
individu yang dilahirkan dengan jumlah induk yang melahirkan yang termasuk
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju induk melahirkan anak adalah
(Deshmukh 1992) : (1) Jumlah anak yang dihasilkan dalam setiap kelahiran; (2)
Waktu antara satu kejadian reproduksi dengan kejadian berikutnya; dan (3) Umur
reproduksi yang pertama.
2.3.2. Mortalitas
Kepadatan populasi dapat berkurang oleh faktor mortalitas. Mortalitas
dapat dihitung lajunya sebagai angka kematian, jumlah hewan yang mati selama
unit waktu (biasanya satu tahun) dibagi dengan jumlah hidup pada awal satuan
waktu (Deshmukh 1992; Sinclair et al. 2006).
Pola kematian karena umur lanjut digambarkan melalui kurva
kelangsungan hidup/peluang hidup (survivorship curve). Peluang hidup adalah kemampuan individu kelas umur tertentu untuk hidup pada kelas umur di atasnya.
Setiap makhluk hidup memiliki tipe kurva peluang hidup yang berbeda-beda.
[image:36.595.80.483.58.788.2]Secara umum tipe survivorship dibedakan menjadi tiga tipe seperti pada Gambar 3.
Sumber : Pearl 1928 dalam Krebs 1978 dan Hasibuan 1988
Gambar 3. Kurva survivorship.
Tipe 3
Tipe 2
Tipe 1 Peluang
Hidup
Kurva tipe 1 merupakan gambaran populasi yang setelah kelahiran tidak
mengalami penurunan, akan tetapi menjelang periode umur tertentu mengalami
penurunan yang drastis. Beberapa populasi mamalia besar dan manusia termasuk
kedalam kurva tipe 1. Kurva tipe 2 menggambarkan angka kematian yang relatif
tetap untuk setiap kelas umur dari suatu populasi, kurva tersebut membentuk garis
diagonal. Kurva tipe ini merupakan ciri dari kurva survivorship pada binatang pengerat, beberapa jenis burung dan populasi invertebrata. Kurva tipe 3
menyatakan suatu keadaan laju kematian sangat tinggi pada awal hidupnya,
seperti yang terjadi pada ikan, kemudian berangsur-angsur menurun sampai tahap
akhir dari satu periode hidup (Krebs 1978; Hasibuan 1988; Deshmukh 1992).
Beberapa faktor yang mempengaruhi kematian antara lain karena adanya predator,
penyakit, dan bahaya lain yang mengancam jauh sebelum organisme mencapai
usia tua (Krebs 1978).
2.3.3 Perkembangbiakan danReproduksi
Kemampuan berkembang biak menentukan kelestarian suatu populasi.
Banteng melakukan perkawinan dalam suatu periode waktu tertentu yang
tergantung dari lokasinya. Menurut Lekagul dan McNeely (1977), musim kawin
banteng di Thailand adalah dalam bulan Mei dan Juni. Hoogerwerf (1970)
menyatakan bahwa musim kawin banteng di Suaka Alam Ujung Kulon adalah
dalam bulan Juli, September, dan Oktober, kadang-kadang juga dalam bulan
Nopember dan Desember. Perkawinan tersebut biasanya dilakukan pada waktu
malam hari.
Lamanya bayi dalam kandungan adalah 9,5-10 bulan, jumlah anak setiap
induk berkisar antara 1-2 ekor, namun kebanyakan 1 ekor setiap induk. Anaknya
dilahrkan dalam satu menit, 40 menit kemudian anaknya sudah dapat berdiri, 60
menit kemudian menyusu induknya. Selanjutnya anaknya akan disapih dalam
umur 10 bulan. Banteng liar menurut Hoogerwarf (1970) termasuk monoestrus,
artinya mempunyai satu musim kawin dalam satu tahun. Umur termuda banteng
betina untuk mulai berkembang biak adalah 3 tahun, sedangkan untuk jantan lebih
dari 3 tahun. Banteng dapat mencapai umur 21-25 tahun, sehingga seekor banteng
2.3.4Struktur Umur dan Seks Rasio
Penyebaran umur merupakan ciri atau sifat penting populasi yang
mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Biasanya populasi yang sedang
berlangsung cepat akan mengandung bagian besar individu-individu muda,
populasi yang stasioner memiliki pembagian kelas umur yang lebih merata, dan
populasi yang menurun akan mengandung bagian besar individu-individu yang
berusia tua (Odum 1993).
Individu-individu dalam populasi mencakup berbagai tingkatan umur.
Struktur umur adalah proporsi individu dalam setiap kelas umur dari suatu
populasi (Deshmukh 1992). Struktur umur dapat digunakan untuk menilai
keberhasilan perkembangan satwa liar, sehingga dapat dipergunakan pula untuk
menilai prospek kelestarian satwa liar (Alikodra 2002).
Tarumingkeng (1994) menggolongkan struktur umur pada populasi dalam
tiga pola, yaitu :
1. Struktur umur menurun yaitu struktur umur yang memiliki kerapatan populasi
kecil pada kelas-kelas umur yang sangat muda dan muda, paling besar pada
kelas umur sedang dan kecil pada kelas umur tua. Perkembangan populasi
tersebut terus menurun dan jika keadaan lingkungan tidak berubah, populasi
akan punah setelah beberapa waktu;
2. Struktur umur stabil, bentuk piramida sama sisi, dengan sisi-sisi yang
kemiringannya mengikuti garis lurus; dan
3. Struktur umur meningkat dengan populasi yang terus meningkat, merupakan
piramida dengan sisi-sisi yang cekung dengan dasar yang lebar.
Seks ratio adalah perbandingan jumlah jantan dengan betina dalam satu
populasi. Hoogerwerf (1970) menyatakan bahwa seks rasio banteng adalah 1:3
sampai 1:4; sedangkan Alikodra (1983) menyatakan seks rasio banteng di padang
penggembalaan Cijungkulon adalah 1:6.
2.3.5 Penentuan Kelas Umur Banteng
Identifikasi umur satwa liar di lapangan mengalami banyak kesulitan, oleh
dan perilaku satwa di lapangan. Kelas umur hanya dibagi dalam tiga kelas yaitu
anak, remaja, dan dewasa.
Hoogerwerf (1970) menyatakan bahwa perkembangan tanduk dapat
dipergunakan untuk mengetahui kelas umur dari banteng sampai mencapai umur
kurang lebih 30 bulan. Tabel hubungan antara umur banteng, tinggi sampai
pundak dan panjang tanduk dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Hubungan antara umur banteng, tinggi sampai pundak, dan panjang tanduk
Kelamin Umur Tinggi sampai pundak (cm) Panjang tanduk (cm)
Jantan 4.0 Hari 75 Tidak ada tanda-tanda
Jantan 23.0 Hari 84 Benjolan kecil
Jantan 36.0 Hari 92 Tanduk muncul di
permukaan kulit
Jantan 63.0 Hari 85 2
Jantan 70.0 Hari - 3
Jantan 6.5 Bulan 110 8
Jantan 9.5 Bulan 120 15
Jantan 12.0 Bulan 125 23
Jantan 20.5 Bulan 125 35
Jantan 2.5 Bulan 90 2
Betina 17.0 Bulan 118 9
Sumber : Hoogerwerf 1970
2.4 Populasi Minimum Lestari
2.4.1 Pengertian
Menurut Soule (1995), MVP dapat diartikan sebagai seperangkat penduga
yang merupakan hasil dari suatu proses sistematik untuk menduga spesies, lokasi
dan kriteria kelestarian populasi. Proses tersebut mengacu pada analisis populasi
atau Population Viability Analysis (PVA).
PVA merupakan tahap lanjut dari analisis demografi yang bertujuan untuk
mempelajari apakah suatu spesies mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup
di suatu lingkungan (Bessinger & McCullough 2002, Morris & Doak 2002).
Sebagai alat bantu yang penting bagi PVA diterapkan berbagai metode
matematika dan statistika. Lebih lanjut PVA bermanfaat memantau fluktuasi
ukuran populasi dari suatu spesies (Indrawan et al. 2007).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih spesies dalam analisis
1. Spesies yang aktivitasnya dapat menimbulkan gangguan habitat pada beberapa
spesies lainnya;
2. Spesies mutualistik yang perilakunya dapat meningkatkan fitness (misalnya reproduksi, penyebaran) bagi spesies lainnya;
3. Spesies predator atau parasit yang mengganggu spesies lain dan keberadaanya
akan menyebabkan penurunaan keragaman spesies lain;
4. Spesies yang memiliki nilai spiritual, estetika, rekresional atau memiliki nilai
ekonomi bagi manusia;
5. Spesies yang langka dan terancam punah.
Ukuran populasi minimum lestari menyatakan ambang batas ukuran
populasi suatu spesies dalam satuan individu yang memastikan bahwa populasi
tersebut akan terus bertahan hidup sampai jangka waktu tertentu (Rai 2003).
Shaffer (1981) mendevinisikan MVP untuk berbagai jenis spesies yang terdapat di
setiap habitat sebagai populasi terkecil yang terisolasi yang mempunyai
kemungkinan 99% untuk bertahan hidup atau lestari selama 1000 tahun setelah
mendapatkan pengaruh demografi, lingkungan, genetik, dan juga bencana alam.
Sedangkan menurut Reed (2000) MVP adalah populasi terkecil dari suatu spesies
yang mempunyai kemungkinan 99% untuk tetap ada selama 40 generasi.
MVP merupakan istilah yang umum digunakan dalam konservasi biologi
(Soule 1995). Lemkhul (1984) menyatakan definisi MVP sebagai populasi
terkecil yang terisolasi yang memiliki peluang 95,1% untuk dapat bertahan
selama 100 tahun meskipun diketahui ada pengaruh dari demografi, lingkungan,
genetic dan katastrop. Lebih lanjut Shaffer (1981) menyatakan bahwa istilah MVP
merupakan kemungkinan peluang hidup suatu spesies dikatakan tinggi jika jumlah
spesies tersebut dapat dipertahankan di atas ukuran tertentu. Sama halnya dengan
penggunaan istilah ‘optimum’, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu
memberikan suatu rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pengelola dalam
manajemen populasi. Hal yang harus digarisbawahi adalah MVP mengandung
2.4.2 Pendekatan untuk Menentukan MVP
Ewens et al. (1995) dan Boyce (1992) menyatakan secara umum terdapat dua konsep penentuan MVP. Konsep yang pertama adalah penentuan MVP
berdasarkan genetik yang menekankan pada laju kehilangan genetik dari suatu
populasi termasuk di dalamnya penurunan fitness dan genetic drift. Konsep yang kedua adalah penentuan MVP berdasarkan demografi yang menekankan pada
kemungkinan terjadinya kepunahan populasi akibat dari tekanan demografi. Nilai
MVP akan dipengaruhi oleh ciri yang umum dari model misalnya struktur
geografi, ukuran populasi maksimum, laju kematian dan laju kelahiran (absolut
atau terpaut kepadatan) dan lainnya. Selain itu, nilai MVP juga tergantung pada
ciri-ciri yang lebih detail seperti nilai numerik dari parameter-parameter dalam
kerangka yang lebih luas (Boyce 1992). Kedua konsep di atas, penentuan nilai
MVP tergantung pada dua asumsi, yang pertama kriteria yang dipilih untuk
mendefinisikan istilah MVP. Sebagai contoh dengan menggunakan konsep
demografi maka ukuran populasi yang dapat menjamin peluang kelestarian
sampai 95% peluang hidup untuk y tahun tergantung pada nilai yang dipilih untuk y. Asumsi yang kedua menekankan pada model yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dari suatu populasi. Sebagai hasilnya adalah akan
diperoleh nilai MVP dengan selang yang luas yang dapat digunakan untuk semua
situasi dan sebuah standard nila numerik yang dapat digunakan sebagai ‘rule’
untuk MVP. Untuk mendapatkan nilai MVP berdasarkan demografi, simulasi
komputer akan sangat membantu.
Lemkhul (1984) merupakan orang pertama yang menyatakan argumen
penggunaan genetik sebagai dasar dalam penentuan MVP. Selanjutnya Franklin
(1980) menyatakan bahwa setidaknya diperlukan 50-500 individu untuk
mempertahankan keragaman genetik. Angka tersebut diperoleh dari pengalaman
praktis Franklin dalam membiakkan hewan budidaya (domestikasi) dan dalam
meriset laju mutasi pada lalat buah. Jumlah minimun tersebut diperkirakan cukup
efektif untuk menghindari tekanan silang dalam jangka pendek serta cukup efektif
untuk mempertahankan variasi genetik dalam populasi. Selanjutnya Lande (1995)
menyatakan setidaknya dibutuhkan 5.000 individu untuk mempertahankan variasi
tersebut. Aturan 50/500 sulit diterapkan karena asumsi tidak selalu didukung oleh
kenyataan. Dalam aturan 50/500 diasumsikan bahwa suatu populasi terdiri dari N
individu di mana setiap individu memiliki kemungkinan yang sama untuk kawin
serta menghasilkan keturunan. Pada kenyatannya, berbagai faktor termasuk umur,
kesehatan, sterilisasi, kekurangan makanan, ukuran tubuh yang kecil, dan struktur
sosial bekerja mencegah perkawinan sehingga banyak individu yang bersifat
steril, tidak memproduksi keturunan. Banyak di antara faktor tersebut
dipengaruhi degradasi dan fragmentasi habitat (Lemkhul 1984).
Beberapa penelitian untuk menentukan MVP berdasarkan parameter
demografi dan genetik diantaranya Wielgus (2001) menentukan minimum viable population grizzly bears di British Columbia, Brito (2002) dengan penelitian penentuan MVP dan status konservasi dari spiny rat di Atlantic Forest. Selain itu
Reed et al. (2003) melakukan pendugaan MVP untuk berbagai vertebrata, Leech
et al. (2008) yang melakukan pendugaan MVP untuk kaka (Nestor meridionalis) yang merupakan flagship dan indicator spesies di New Zealand, Goldingay (1995) melakukan penelitian mengenai penentuan luas kawasan bagi kelestarian
Australian Gilding marsupial dengan dasar parameter demografi seperti kematian,
sex ratio dan kelas umur, dan Howels & Jones (1996) melakukan penelitian
penentuan luasan hutan yang tersisa untuk mendukung MVP wild boar di Scotlandia.
2.5 Populasi Optimum Lestari
Populasi optimum lestari adalah populasi yang menunjukkan keadaan riap
maksimum atau nilai dN/dt tertinggi. Populasi optimum lestari tercapai pada saat
laju pertumbuhan intrinsik (r) maksimal dan bernilai positif (r > 0). (Hasibuan
1988; Alikodra 2002; Tarumingkeng 1994). Pada sistim pengelolaan yang
bertujuan untuk keperluan pemungutan satwa liar, pemungutan dilakukan pada
kondisi ini. Pada kondisi ini sering disebut dengan tingkat kepadatan pemanenan
maksimal (maximum harvest density).
Tingkat kepadatan panenan maksimum adalah jumlah satwa liar yang
mampu ditampung oleh suatu habitat pada kondisi hasil pemanenan yang
kesejahteraanya, seperti kualitas pakan maupun kuantitas pelindungnya secara
intensif. Jika tidak didukung oleh kecukupan faktor-faktor kesejahteraannya,
keadaan prodiktivitas populasinya akan menjadi terbatas (Bolen 2003). Pada
kondisi ini kualitas dan performance populasi sangat bagus, karena populasi satwa dipertahankan di bawah daya dukung lingkungan.
Kesulitan dalam menetapkan angka maksimal hasil pemanenan sering
dijumpai. Untuk mengatasinya sering kali dipergunakan pendekatan-pendekatan
tertentu, misalnya dengan cara memantau kecenderungan kondisi habitat dan
populasi satwa liar, khususnya keadaan reproduksi. Hasil panenan maksimum
yang tepat didapatkan dari berbagai fakta, misalnya model populasi dengan
tabel-tabel kehidupan yang menggunakan simulasi komputer (Adam 1971 dalam
Alikodra 2010).
2.6 Produktivitas Rumput dan Daya Dukung
Produktivitas rumput tergantung pada beberapa faktor (McIlroy 1976)
yaitu :
1. Persistensi (daya tahan), yaitu kemampuan bertahan untuk hidup dan
berkembang biak secara vegetatif;
2. Daya saing, yaitu kemampuan untuk memenangkan persaingan dengan
spesies-spesies lain yang tumbuh bersama;
3. Kemampuan tumbuh kembali setelah injakan dan penggembalaan berat;
4. Sifat tahan kering atau tahan dingin;
5. Penyebaran produksi musiman;
6. Kemampuan menghasilkan cukup banyak biji yang dapat tumbuh baik atau
dapat dikembangbiakan secara vegetatif dengan murah;
7. Kesuburan tanah (terutama kandungan nitrogen);
8. Iklim.
Beberapa pengertian dari daya dukung antara lain : 91) Jumlah satwa liar
yang dapat ditampung oleh suatu habitat; (2) Batas (limit) atas pertumbuhan suatu populasi yang di atasnya jumlah populasi tidak dapat berkembang lagi; dan (3)
kesejahteraannya (Dasman 1964, Moen 1973, Boughey 1973 dalam Alikodra 2002).
Deshmukh (1992) mengatakan bahwa sebagian besar ekosistem
mengandung banyak jenis dan mempunyai berbagai kondisi abiotik dan hal
tersebut menyebabkan suatu populasi tertentu akan memiliki batas ukuran atas
yang secara permanen tak dapat dilampaui. Garis batas tersebut adalah daya
dukung suatu lingkungan untuk populasi itu. Daya dukung ditentukan oleh
III. KONDISI UMUM LOKASI
Penelitian penentuan ukuran populasi minimum dan optimum lestari
dilaksanakan di TN Alas Purwo. Secara umum, kondisi lokasi penelitian adalah
sebagai berikut :
3.1. Letak, Luas, dan Status Kawasan
Secara geografis kawasan TN Alas Purwo terletak pada 8o 26' 45’’ - 8 o 47'
00’’ LS dan 114o 20’ 16’’ - 114o 36’ 00’ BT.Ketinggian tempat bervariasi dari
0-322 mdpl. Menurut administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah
Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.
Taman Nasional Alas Purwo berbatasan dengan Teluk Grajagan, kawasan hutan
produksi Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Selatan,
Desa Grajagan, Desa Purwoagung, Desa Sumberasri, di sebelah Barat. Sebelah
Timur berbatasan dengan Selat Bali dan Samudera Indonesia, sebelah Utara
berbatasan dengan Teluk Pangpang, Selat Bali, desa Sumber Beras, desa
Kedungrejo, desa Wringinputih, Kecamatan Muncar serta desa Kedungasri,
Kecamatan Tegaldlimo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera
Indonesia.
Kawasan Alas Purwo, sebelum ditetapkan sebagai taman nasional semula
berstatus Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor stbl 456 tanggal 1 September 1939
dengan luas areal 62.000 ha. Berdasarkan berita acara pengukuran tanggal 27 Mei
1983 luasan tersebut diubah menjadi 43.420ha. Melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992, status suaka
margasatwa berubah menjadi taman nasional.
Kawasan TN Alas Purwo, berdasarkan pembagian zonasi sesuai Surat
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor:
51/Kpts/Dj-IV/1987 tanggal 12 Desember 1987 terbagi atas:
1. Zona Inti seluas 17.200 ha;
2. Zona Rimba seluas 24.767 ha;
3. Zona Pemanfaatan seluas 250 ha;
Pada tahun 2005 dilakukan revisi zonasi TN Alas Purwo terkait dengan
usulan zona pemanfaatan dan perubahan eks zona penyangga menjadi zona
tradisonal dan zona rehabilitas. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 26/Kpts/IV-KK/2007 tanggal
19 Pebruari 2007 tentang Revisi Zonasi TN Alas Purwo, zonasi TN Alas Purwo
terbagi atas: (1) Zona Inti seluas 17.150 ha; (2) Zona Rimba seluas 24.207 ha; (3)
Zona Rehabilitasi seluas 620 ha; (4) Zona Pemanfaatan seluas 660 ha; dan (5)
Zona Tradisional seluas 783 ha. Peta lokasi penelitian dan pembagian zonasi
selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.
[image:46.595.87.486.46.842.2]Sumber : Balai TN Alas Purwo
Gambar 4 Peta zonasi TN AlasPurwo.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007
tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Taman Nasional, Balai TN Alas Purwo terdiri dari 2 (dua) Seksi Pengelolaan
Taman Nasional Wilayah yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I
Tegaldlimo dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Muncar. TN Alas
Purwo, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mempunyai tiga
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam
bentuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan
pariwisata alam.
3.2 Topografi, Geologi, Iklim, dan Hidrologi
3.2.1 Topografi
Kawasan TN Alas Purwo terdiri dari daerah pantai (perairan, daratan dan
rawa), daerah daratan hingga daerah perbukitan dan pegunungan, dengan
ketinggian mulai antara 0–322 mdpl dengan puncak tertinggi Gunung Lingga
Manis. Daerah pantai melingkar mulai dari Segoro Anak (Grajagan) sampai
daerah Muncar dengan panjang garis pantai sekitar 105 Km. Kelerengan kawasan
mulai daerah datar (0-8%) seluas 10.554 ha;landai (8-15%) seluas 19.474 ha; agak
curam (15-25%) seluas 11.091 ha; serta curam (25-40%) seluas 2.301 ha.
3.2.2 Geologi
Formasi geologi pembentuk kawasan berumur Meosen atas, terdiri dari
batuan berkapur dan batuan berasam. Pada batuan berkapur terjadi proses
karstifikasi yang tidak sempurna, karena faktor iklim yang kurang mendukung
(relatif kering), serta batuan kapur yang diperkirakan terintrusi oleh batuan lain.
Di kawasan ini terdapat banyak gua, dan menurut hasil inventarisasi terdapat 44
buah gua. Diantara gua-gua tersebut yang selama ini banyak dikunjungi adalah
Gua Istana, Gua Padepokan dan Gua Basori.
Jenis tanah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu (1) tanah komplek
Mediteran Merah-Litosol seluas 2.106 ha, (2) tanah Regosol Kelabu seluas 6.238
ha, (3) tanah Grumosol Kelabu seluas 379 ha, dan (4) tanah Aluvial Hidromorf
seluas 34.697 ha.
3.2.3 Iklim
Kawasan TN Alas Purwo dan sekitarnya memiliki curah hujan yang tidak
dari 15 hari hujan. Curah hujan tahunan mencapai 1.079 mm (Tegaldlimo), 1.491
mm (Purwoharjo), 1.554 mm (Muncar) dan 2.147 mm (Glagah), masing-masing
dengan hari hujan sebanyak 55 hari, 71 hari, 79 hari, dan 112 hari. Menurut sistem
klasifikasi Schmidth dan Ferguson daerah ini memiliki tipe iklim sekitar D (agak
lembab) sampai E (agak kering). Secara umum, bulan basah terjadi pada bulan
Nopember sampai April, dan bulan kering terjadi pada bulan Mei sampai Oktober.
Kisaran penyinaran matahari bulanan di Banyuwangi dan sekitarnya adalah 52%
(bulan Januari) hingga 89% (bulan September), dengan rata-rata sebesar 75%.
Suhu udara maksimum bulanan di Banyuwangi antara 31,2oC–34,5oC dan suhu
udara minimumnya antara 20,7oC–22,5oC, sedangkan suhu udara rata-rata
bulanan berkisar antara 25,9oC–28,2oC. Fluktuasi kelembaban udara juga
tergolong kecil, yaitu berkisar antara 75%-81%. Arah angin terbanyak yang
bertiup di daerah Banyuwangi adalah arah Selatan dengan kecepatan antara 2,3–
4,2 knot.
3.2.4 Hidrologi
Jaringan sungai di kawasan TN Alas Purwo berpola radial karena leher
semenanjungnya menyempit. Aliran airnya langsung mengarah ke laut (Samudera
Hindia dan Selat Bali). Sungai secara umum berupa sungai kecil (aliran kurang
dari 10 m dengan panjang kurang dari 5 Km), namun jumlahnya sangat banyak
(sekitar 70 buah). Beberapa sungai, seperti Sunglon Ombo dan Sungai Pancur,
berhubungan dengan sungai bawah tanah yang mengalir di bawah kompleks
perbukitan/lipatan kapur (daerah karst). Sungai Pancur mengalir dari sungai
bawah tanah gua Istana dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan taman
nasional, terutama pos Rowobendo, Pesanggrahan, Triangulasi dan pos Pancur.
Sungai yang ukurannya relatif besar (Sungai Kemiri, Sungai Pail dan Sungai
Paluh Agung dan Sungai Segoro Anak) terdapat di daerah Bedul sampai
Rowobendo, di mana aliran airnya mengumpul di bagian hilir Sungai Segoro
Anak, memiliki lebar lebih dari 500 m di bagian hilirnya dan membentuk daerah
berawa. Sungai yang mengalir sepanjang tahun hanya terdapat di bagian Barat,
yaitu Sungai Segoro Anak dan Sunglon Ombo. Pada musim penghujan muara
tahun yang pada musim kemarau airnya berasa sadah dan pada musim penghujan
berasa tawar. Di beberapa tempat sumber air dalam jumlah kecil dapat diperoleh
dari sistim rekahan atau celahan dari lapisan lapuk tebal serta endapan aluvium
yang tipis. Sumber air semacam ini dapat ditemui di blok hutan Pecari Kuning dan
Sadengan. Mata air banyak terdapat di daerah Gunung Kucur, Gunung Kunci,
Goa Basori dan Sendang Srengenge.
3.3Flora, Fauna, dan Ekosistem
3.3.1 Flora
Keanekaragaman jenis flora darat di kawasan TN Alas Purwo termasuk
tinggi. Hasil inventarisasi tumbuhan oleh TN Alas Purwo mencatat 158 jenis
tumbuhan (59 famili) mulai dari tingkat tumbuhan bawah sampai tumbuhan
tingkat pohon dari berbagai tipe/formasi vegetasi (Hutan Pantai-Mangrove-Hutan
Dataran Rendah). Secara keseluruhan, TN Alas Purwo merupakan taman nasional
yang memiliki formasi vegetasi yang lengkap, di mana hampir semua tipe formasi
vegetasi dapat dijumpai. Formasi vegetasi yang dimiliki mulai dari pantai (hutan
pantai) sampai hutan hujan tropika dataran rendah.
3.3.2 Fauna
Satwa liar yang terdapat di TN Alas Purwo terdiri dari 31 jenis mamalia,
236 jenis burung dan 20 jenis reptil. Mamalia besar yang terdapat di TN Alas
Puwo antara lain Banteng, (Bos javanicus), macan tutul (Panthera pardus), anjing hutan (Cuon alpnus), kijang (Muntiacus muntjak), dan rusa timor (Rusa timorensis). Jenis primata yaitu lutung budeng (Trachypithecus auratus) dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis).
Jenis burung yang terdapat di TN Alas Purwo dan termasuk langka, yaitu
Merak (Pavo muticus), ayam hutan (Gallus sp), rangkong (Buceros rhinoceros),
kangkareng perut putih (Anthracoeros sp) dan julang (Anthracoeros convecus). Di TN Alas Purwo juga dapat dijumpai 16 jenis burung migran dari Austarlia yang
biasa ditemui di sekitar Segoro Anak pada bulan November sampai akhir Januari.
adalah penyu hijau (Chelonia mydas), penyu belimbing (Dermochelys coriacea),
penyu sisik (Erithmochelys imbricate) dan penyu abu-abu (Lepidochelys olivacea). Penyu-penyu tersebut memanfaatkan pantai sekitar TN Alas Purwo sebagai tempat mendarat dan bertelur (BTNAP 2005).
3.3.3 Ekosistem
Keadaan ekosistem khas TN Alas Purwo secara alami didominasi oleh tipe
ekosistem hutan tropis dataran rendah yang merata di seluruh kawasannya.Selain
itu, dijumpai juga ekosistem yang sangat beragam baik alami maupun buatan di
antaranya terdiri dari (1) Ekosistem hutan pantai; (2) Ekosistem hutan mangrove;
(3) Ekosistem hutan dataran rendah; (4) Ekosistem padang penggembalaan; (5).
Ekosistem hutan jati hasil pembinaan habitat (BTNAP 2011).
3.4 Padang Penggembalaan Sadengan
Upaya pembinaan populasi satwa, khususnya bantenngan pembuatan
padang penggembalaan. Pada tahun 1975 dilakukan pembuatan padang
penggembalaan di tiga tempat, yaitu padang penggembalaan Payaman seluas ±25
Ha, Pancur ±5 Ha, dan Sadengan 75 Ha. Padang Penggembalaan Payaman
ternyata hanya jalur lintas satwa untuk mengasin dan tidak tersedia air minum,
sehingga keberadaan satwa sangat jarang. Padang Penggembalaan Payaman
dihutankan kembali dengan permudaan jambu mente, nangka dan lain sebagainya,
setelah dinilai tidak layak. Padang penggembalaan yang kedua adalah Pancur
seluas ±5 Ha. Perkembangannya hampir sama dengan Payaman sehingga
difungsikan sebagai camping ground.
Sadengan dibuka sebagai padang penggembalaan dengan luas 75 Ha
menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal PPA tahun 1978, namun dalam
kenyataan di lapangan ditemukan luas ± 84 Ha. Pembukaan Padang
Penggembalaan Sadengan dilakukan dengan sistem tumpang sari yang melibatkan
masyarakat sekitar hutan.
Di dalam areal Padang Penggembalaan Sadengan terdapat 3 (tiga) sumber
air utama yang permanen, yaitu sungai Basori, sungai Tengah, dan Sungai
Panjang Sungai Tengah ±1.716,00 km dengan debit 5,0 l/s, sedangkan Sungai
Selatan memiliki panjang ±1.552,95 km dengan debit 3,7 l/s (BTNAP 2008). Satu
sungai utama, yaitu sungai Tengah yang terletak di tengah padang penggembalaan
Sadengan airnya mengalir sepanjang tahun/musim. Pada musim kemarau masih
ada sedikit aliran air yang kontinyu. Sungai Selatan yang terletak pada arah
tenggara Padang Penggembalaan Sadengan mempunyai aliran sungai yang
bersifat tidak permanen.
Untuk memenuhi kebutuhan air bagi satwa di musim kemarau dibuatlah 4
buah bak air minum satwa. Sumber air berasal dari mata air Goa Basori yang
dialirkan ke Padang Penggembalaan Sadengan melalui pipa paralon yang ditanam
dalam tanah. Fluktuasi debit air tanah tidak terlalu besar sehingga diharapkan
dapat menyuplai air ke Padang Penggembalaan Sadengan secara kontinyu.
Sumber mata air di Goa Basori mempunyai vegetasi yang rapat dan lebat,
sehingga fungsi tangkapan air oleh tajuk-tajuknya dapat dijalankan dengan baik
dan menjamin keberlangsungan sumber air. Secara perlahan-lahan tangkapan air
ini dikeluarkan melalui mata air/spring. Dengan demikian fluktuasi air tanah
antara musim kemarau dan musim penghujan tidak terlalu besar.
Vegetasi tingkat pohon yang terdapat di dalam Padang Penggembalaan
Sadengan antara lain : Apak (Ficus sundalca), Ketangi (Lagerstomia sp.), Gebang (Corypha utan), Gintungan (Bischoffla javanica), Awar-awar (Ficus septica), Bendo (Arthocarpus elasticus) dan Winong (Tetranales nudiflora). Untuk pengelolaan satwa liar di padang penggembalaan Sadengan akan menguntungkan
dengan adanya dominasi dari bambu, karena jenis ini merupakan pelindung yang
baik dari predator dan gangguan pemburu liar. Vegetasi tingkat semak, jenis yang
ada antara lain : Sontoloyo (Hyptis capitata), Kerinyu (Eupatorium odoratum), wedusan (Ageratum conyzoldes), serut (Strablus asper) dan tembelekan (Lantana camara).
Ekosistem padang penggembalaan Sadengan dihuni oleh berbagai satwa
liar dari kelas Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves dan Mamalia. Jenis-jenis fauna
yang dapat dijumpai secara langsung di padang penggembalaan Sadengan
sebagian besar dari kelompok aves dan mamalia. Jenis-jenis yang banyak
rhinoceros), Kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris), bangau tongtong (Leptoptilus javanicus), elang ular (Spilornis cheela), elang alap nipon (Accipiter gularis), elang jawa (Spizaetus bartelsi) dan jalak putih (Sturnus melanopterus).
Mamalia yang dapat dijumpai di padang penggembalaan Sadengan antara
IV. BAHAN DAN METODE
4.1 Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di TN Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur. Penelitian dan pengolahan data dilaksanakan selama 6 bulan
yaitu pada bulan Maret sampai Agustus 2012.
4.2Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Alat tulis,
gunting, jam tangan, kamera digital, kompas, peta kawasan, tally sheet, teropong
binokuler, populasi banteng, perangkat lunak Microsoft Excel 2007 dan Wolfram
Mathematica 8.
4.3Metode Pengumpulan Data
4.3.1 Pengumpulan Data Demografi Banteng
Data demografi banteng yang diperlukan meliputi: ukuran populasi, kelas
umur, seks rasio, peluang hidup, fekunditas, dan usia kawin. Data yang
dikumpulkan di lapangan berupa ukuran populasi, kelas umur dan seks rasio.
Peluang hidup dan fekunditas didapatkan dari hasil analisis data lapangan
sedangkan usia kawin didapatkan dari hasil studi pustaka.
Pengambilan data menggunakan metode terkonsentrasi. Pengamatan di
Padang Penggembalaan dilakukan dengan cara menghitung semua individu
banteng di areal padang penggembalaan. Pengamatan dilakukan sebanyak dua kali
yaitu pada pagi hari (05.00-08.00) dan sore hari (15.00-18.00) selama 9 hari atau
18 kali ulangan.
Data yang dicatat meliputi jumlah individu pada setiap kelas umur dan
jenis kelamin. Sehubungan sulitnya mengetahui secara pasti umur banteng di
lapangan, maka penentuan umur banteng didasarkan pada morfologinya,
kemudian dikategorikan menjadi kelas umur anak, remaja dan dewasa. Ciri-ciri
Tabel 2 Banteng berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin
Kelas umur
Jenis kelamin
Keterangan Jantan Betina
Anak
Individu anak memiliki warna coklat baik pada jantan maupun betina dengan tinggi badan sekitar ¼ dewasa
Remaja
Individu remaja, mempunyai ukuran tubuh sedikit lebih besar dari pada individu anak, tanduk pada jantan sudah terlihat bentuk garpu sedangkan pada betina paralel
Dewasa
Individu dewasa memiliki ukuran tubuh yang besar. Warna pada jantan hitam, sedangkan betina coklat dengan bentuk tanduk yang sudah sempurna
4.3.2 Pendugaan Produktivitas Rumput
Data produktivitas rumput yang dipakai dalam penelitian ini adalah data
sekunder produktivitas rumput hasil pengukuran selama dua tahun pada musim
hujan dan kemarau, yaitu tahun 2009 dan 2010 oleh Garsetiasih (2012).
Pengukuran masing-masing dilakukan 3 kali ulangan setiap musim pada setiap
4.4 Analisis Data
4.4.1 Ukuran Populasi
Ukuran populasi banteng di padang penggembalaan merupakan jumlah
tertinggi pada saat pengamatan dengan kelas umur anak, remaja, dan dewasa
dengan jenis kelamin jantan dan betina, kecuali anak yang belum dapat dibedakan
jantan dan betinanya.
4.4.2 Struktur Umur dan Seks rasio
Jumlah individu pada setiap kelas umur disusun dalam piramida populasi.
namun untuk mendapatkan gambaran pola pertumbuhan populasi yang
sebenarnya, jumlah individu dalam kelas umur dibagi selang umurnya. Seks rasio
didapatkan dari perbandingan jumlah individu jantan dan betina pada tiap kelas
umur. Untuk kelas umur anak seks rasio yang digunakan adalah seks rasio kelas
umur satu tingkat di atasnya yaitu kelas umur remaja. Seks rasio merupakan
perbandingan antara jumlah jantan dan betina. Seks rasio dihitung dengan rumus
berikut ini:
Seks rasio YX
Dimana: Y = Jumlah individu jantan; X = Jumlah individu betina
4.4.3 Peluang Hidup
Peluang hidup dihitung pada setiap kelas umur. Data peluang hidup
didapatkan dari jumlah individu yang hidup pada kelas umur x+1 dibagi dengan
jumlah individu pada kelas umur dibawahnya (x). Peluang hidup dapat dihitung
dengan rumus berikut ini:
Di mana : Px = Peluang hidup kelas umur x
Lx+1 = Jumlah individu yang hidup pada KU X+1
Lx = Jumlah individu yang hidup pada KUx
x x x
L L
4.4.4 Fekunditas dan Usia Kawin
Fekunditas merupakan jumlah bayi yang mampu dilahirkan oleh seekor
induk pada satu tahun. Usia kawin banteng didapatkan dari studi literatur dari
berbagai penelitian terdahulu. Fekunditas dalam penelitian ini dihitung dengan
rumus berikut ini:
Dimana : F = Fekunditas
x = jumlah anak
B = jumlah betina produktif
4.4.5 Daya Dukung
Untuk mengetahui daya dukung habitat banteng dihitung dengan rumus
berikut ini:
K = P/C x A
Di mana : K = Daya dukung habitat
P = produktivitas hijauan (kg/ha/th)
A = luas seluruh areal (ha)
C = kebutuhan makan banteng (kg/ekor/tahun)
4.4.6 Ukuran Populasi Minimum Lestari
Kelestarian dicapai ketika setidaknya populasi akhir sama dengan populasi
awal atau mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan. Pada
penelitian ini populasi awal adalah populasi pada saat dilakukan penelitian.
Dengan kata lain:
N0 = N1 =N2 = Nt
Di mana :
N0 = jumlah individu anak (A0) + jumlah individu remaja (R0) + Jumlah Individu
Dewasa (D0)
N1 = jumlah individu anak (A1) + jumlah individu remaja (R1) + Jumlah Individu
N2 = jumlah individu anak (A2) + jumlah individu remaja (R2) + Jumlah Individu
Dewasa (D2)
Jumlah individu pada setiap kelas umur ditentukan berdasarkan matriks
Leslie yang telah dimodifikasi (Priyono 1998) sebagai berikut :
A1 δA Fm Fd A 0
R1 = p1 δR 0 X R0
D1 0 P2 δD D0
Di mana :
Fx = fecunditas kelas umur
Px = peluang hidup bagi individu kelas umur x untuk melangsungkan kehidupan
pada kelas umur berikutnya (age specific survival)
δx = proporsi anggota populasi yang tidak mengalami peningkatan kelas umur
Dari matriks Leslie tersebut, dibangun persamaan aljabar linear. Ukuran
populasi minimum lestari ditentukan dengan metode eliminasi pada persamaan
tersebut. Persamaan yang dibangun adalah:
N0 = A + R + D ………..(1)
N1 = {(F.R+F.D+(δA + {(A.P1)+(δR)}+ {(1-δR .P2)+ δDD}……...(2)
N2 = [F. {(A.P1)+(δR )}+F. {(1-δR .P2)+ δDD}+ δA F. R F. D δA ] +
[{P1. (F.R+F.D+(δA }+ δR{(A.P1)+(δRR)}] +
[P2. (1-δR {(A.P1)+(δR )}+ δD{(1-δR .P2)+ δDD}]…...(3)
Keterangan : notasi δ didapatkan dari selang umur pada setiap kelas umur.
4.4.7 Penentuan Laju Pertumbuhan Finit
Laju pertumbuhan finite (λ) dihitung dengan menggunakan perkalian
matriks transisi B= H x M x H-1. Dari matriks tersebut akan terlihat unsur-unsur
matriksnya yang selanjutnya ditentukan akar ciri dari matriks tersebut yag
dengan Software Wolfram Mathematic 8. Nilai Eigen (λ) yang digunakan adalah yang bernilai paling besar dan positif, karena akar ciri yang bernilai negatif dan
imajiner tidak bermakna dalam biologi, khususnya model pertumbuhan spesies.
4.4.8 Ukuran Populasi Optimum Lestari
Populasi awal diproyeksikan pertahun dengan menggunakan matriks
Leslie terpaut kepadatan (Density Dependent) sehingga dapat dilihat pertumbuhan
populasinya. Populasi optimum lestari adalah ukuran populasi pada tahun ke-t
dimana selisih antara Nt dengan Nt+1 merupakan selisih terbesar di antara tahun-
tahun lainnya. Waktu yang digunakan pada proyeksi populasi ini adalah 200
tahun, hal ini dilakukan karena proyeksi pertumbuhan dilakukan untuk
mendapatkan pertumbuhan populasi atau r=0, di mana tidak ada lagi pertumbuhan
atau populasi mendekati daya dukungnya. Populasi yang digunakan sebagai
populasi awal dalam proyeksi matriks Leslie ini hanya populasi jenis kelamin
betina. Ukuran populasi pada jantan akan didapatkan dari perbandingan seks
rasio.
Persamaan matrik Leslie terpaut kepadatan yang digunakan adalah sebagai
berikut:
,,
,
/
/
/
Dimana: Fx = Fekunditas setiap kelas umur
Px = Peluang hidup
Nt = Jumlah populasi pada setiap kelas umur
Q = Faktor pembatas pertumbuhan
qt = 1 + α. Nt
α = (λ-1)/ K
λ = Akar ciri matriks M
Dalam menyusun matriks Leslie, selang waktu antar kelas umur haruslah
sama. Karena sulitnya menentukan umur satwa di lapangan maka dalam
penelitian ini populasi awal pada setiap kelas umur dibagi oleh selang waktu pada
masing-masing kelas umur. Sehin