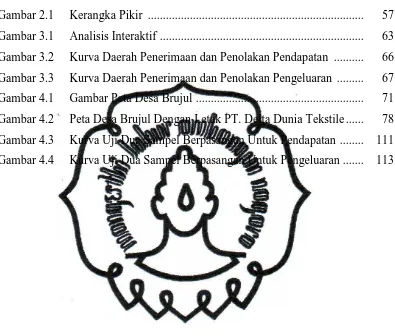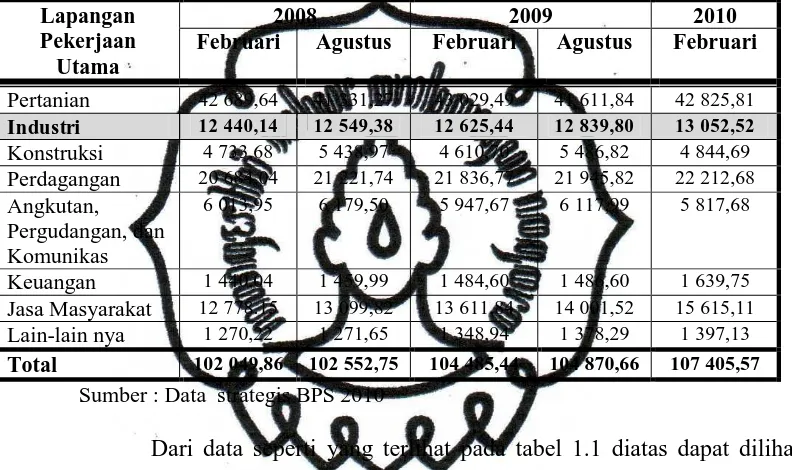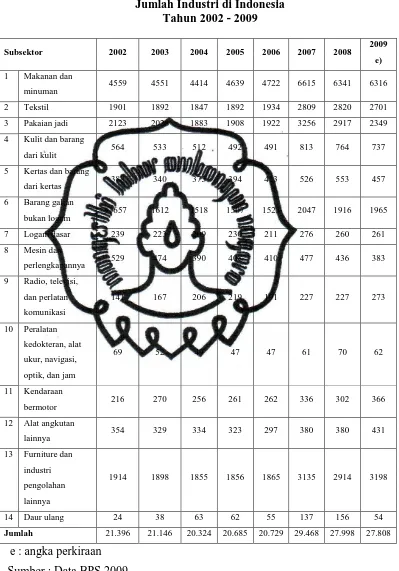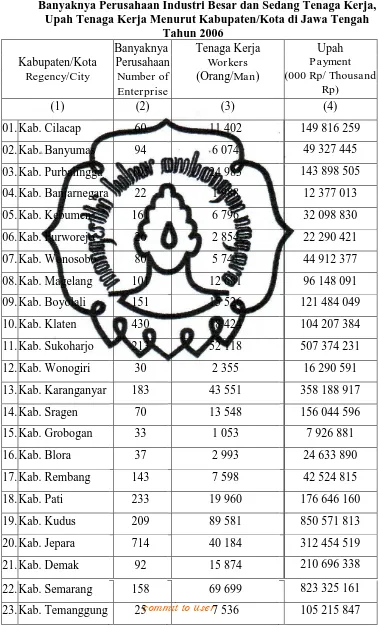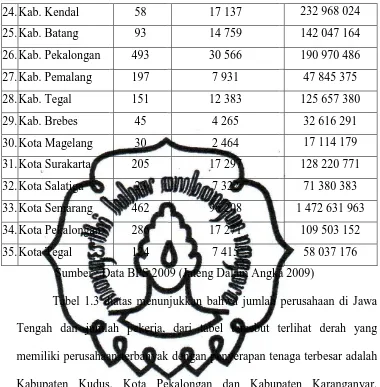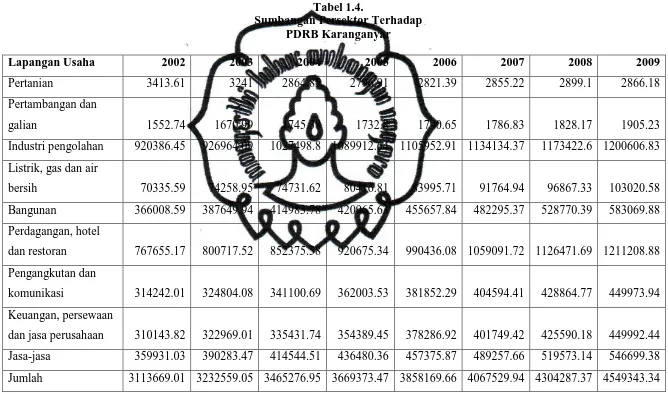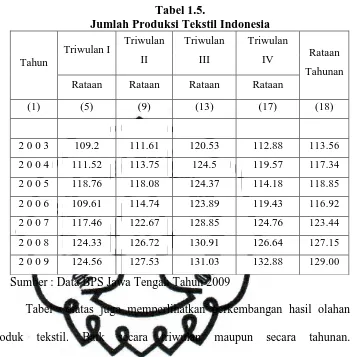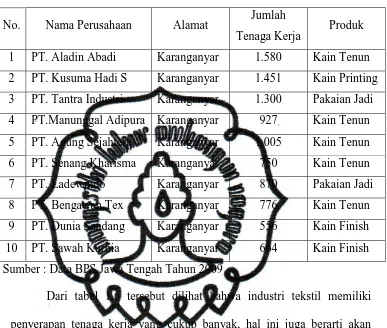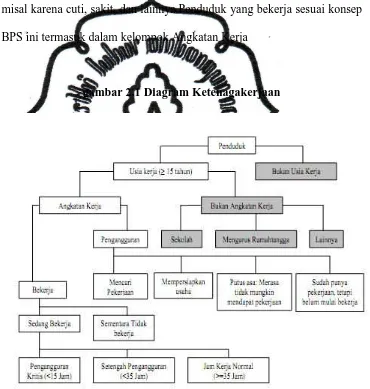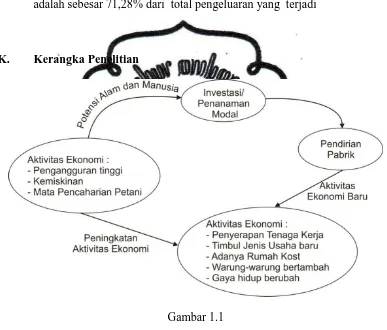commit to user
i
DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI TEKSTIL
PT. DELTA DUNIA TEXTILE TERHADAP AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA BRUJUL KABUPATEN KARANGANYAR
Penyusunan Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh:
INDRA SETYO NUGROHO
NIM. F0106046
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
commit to user
commit to user
commit to user
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk : Ø Orang tuaku tercinta yang selalu memberi
dukungan dan mendo’akan ku.
Ø Pacar saya tersayang Alifa Nurmalasari yang telah membatu dalam pengerjaan skripsi ini Ø Teather Gadhang tercinta
Ø Sahabat dan teman-teman Site, Warih, Melon, Onggo, Avit yang selalu menyemangati saya .
commit to user
v
MOTTO
Berjuanglah untuk apa yang diinginkan, berdoalah agar apa yang
diperjuangkan mendapat restu-Nya, yakinlah bahwa semua
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penelitian dengan judul ”Dampak Keberadaan Industri Tekstil PT. Delta Dunia Textile Terhadap Aktifitas Ekonomi Masyarakat Desa Brujul Kabupaten Karanganyar” bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini:
1. Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah Memberikan ijin menyusun skripsi.
2. Bapak Kresno selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.
3. Nurul Istiqomah SE.M,Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu teori maupun terapan.
commit to user
vii
6. Saudara-saudaraku yang telah memberikan support dan kasih sayang kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
Semoga budi baik yang telah Bapak, Ibu dan saudara berikan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat di masa sekarang dan yang akan datang.
Surakarta, Januari 2011
commit to user
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Utama Pembangunan ... 17
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi ... 20
C. Pengertian Umum Pengangguran ... 24
D. Konsep Perubahan Sosial ... 31
E. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat ... 45
F. Konsep Masyarakat Desa ... 46
G. Teori Industri ... 52
H. Ekonomi Industri ... 53
commit to user
ix
J. Penelitian Terdahulu ... 56
K. Kerangka Penelitian ... 57
BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian ... 59
B. Jenis Dan Sumber Data ... 60
C. Teknik Pengumpulan Data ... 60
D. Lokasi Penelitian ... 61
E. Teknik Analisa Data ... 61
F. Definisi Operasional ... 63
G. Definisi Operasional Variabel ... 66
H. Uji Dua Sampel Berpasangan ... 66
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Objek Penelitian ... 69
B. Hasil Analisis ... 77
C. Pembahasan ... 87
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 114
B. Saran ... 117 DAFTAR PUSTAKA
commit to user
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja ... 5
Tabel 1.2 Jumlah Industri Di Indonesia Tahun 2002 – 2009 ... 6
Tabel 1.3 Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tenaga Kerja ... 8
Tabel 1.4 Sumbangan Persektor Terhadap PDRB karanganyar ... 11
Tabel 1.5 Jumlah Produksi Tekstil Indonesia ... 12
Tabel 1.6 Daftar 10 Industri Tekstile Terbesar Berdasarakan Jumlah Tenaga Kerja ... 13
Tabel 4.1 Karateristik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... 72
Tabel 4.2 Karakteristik Pendudukn Berdasarakan Agama ... 73
Tabel 4.3 Karakteristik Pendudukn Berdasarakan Tingkat Pendidikan ... 74
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Brujul ... 75
Tabel 4.5 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Gulunan ... 80
Tabel 4.6 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Soko ... 81
Tabel 4.7 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Purworejan ... 83
Tabel 4.8 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Sobayan ... 84
Tabell 4.9 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Brujul ... 85
Tabel 4.10 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Duwet ... 86
Tabel 4.11 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Gulunan dan Dusun Soko ... 88
Tabel 4.12 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Brujul dan Dusun Duwet ... 99
Tabel 4.13 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Purworejan dan Dusun Sobayan ... 101
Tabel 4.14 Data Jumlah Penduduk Desa Brujul Yang Bekerja di PT. Delta Dunia Tektile ... 105
Tabel 4.15 Hasil Uji Dua Sample Untuk Pendapatan ... 110
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pikir ... 57
Gambar 3.1 Analisis Interaktif ... 63
Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Pendapatan ... 66
Gambar 3.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Pengeluaran ... 67
Gambar 4.1 Gambar Peta Desa Brujul ... 71
Gambar 4.2 Peta Desa Brujul Dengan Letak PT. Delta Dunia Tekstile ... 78
Gambar 4.3 Kurva Uji Dua Sampel Berpasangan Untuk Pendapatan ... 111
Gambar 4.4 Kurva Uji Dua Sampel Berpasangan Untuk Pengeluaran ... 113
commit to user
commit to user
DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI TEKSTIL
PT. DELTA DUNIA TEXTILE TERHADAP AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA BRUJUL KABUPATEN KARANGANYAR
Oleh :
INDRA SETYO NUGROHO NIM. .F0106046
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebeberadaan industri tekstil terhadap aktivitas ekonomi, untuk mengetahui dampak keberadaan industri tekstil terhadap angka pengangguran dan untuk mengetahui pengaruh keberadaan pendatang terhadap masyarakat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul secara apa adanya dan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan diketahui terdapat pengaruh keberadaan industri pada aktivitas ekonomi, terdapat pengaruh keberadaan industri terhadap pengurangan angka pengangguran di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini juga didapat bahwa terdapat pengaruh keberadaan pendatang terhadap lingkungan sosial masyarakat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
Keberadaan industri yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan angka pengangguran dan dampak sosial yang diterima masyarakat Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabbupaten Karanganyar, sehubungan dengan adanya pendatang perlu disikapi dengan kepedulian pemerintah terhadap hal-hal negatif yang perlu timbul. Keberadaan industri tidak saja memberikan pengaruh postifi namun juga memberikan pengaruh negatif.
commit to user
IMPACT OF EXISTENCE TEXTILE INDUSTRY
PT. DELTA DUNIA TEXTILE COMMUNITY TO ECONOMIC ACTIVITY VILLAGE DISTRICT BRUJUL KARANGANYAR
INDRA SETYO NUGROHO NIM. .F0106046
The purpose of this study was to determine the impact of the textile industry kebeberadaan of economic activity, to determine the effect of the textile industry against unemployment and to determine the effect the presence of immigrants on society Brujul Village, District of Jaten, Karanganyar District.
This research is a quantitative descriptive. In this study, researchers describe and illustrate the data already collected as it is and make conclusions based on these data.
Based on the analysis and discussion that researchers do know there are significant industrial presence in economic activity, there are significant industrial presence to the reduction in unemployment in the Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. In this study also found that there are significant presence of immigrants on the social environment society Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
The existence of industries that have significant economic activity and unemployment and social impacts of village community has received Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, in connection with the newcomer needs to be addressed by government concern of the negative things that need arise. The existence of the industry not only give effect postifi but also provide a negative influence.
commit to user
59
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan suatu proses perombakan struktur dalam
perimbangan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga
membawa kemajuan dalam arti meningkatkan taraf hidup masyarakat yang
bersangkutan (Dumairy, 1996 : 13). Pembangunan menampilkan
perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyelarasan
keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan
keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam
sistem tersebut, berpindah dari suatu kondisi kehidupan yang dianggap
lebih baik secara mental maupun spiritual.
Oleh karena itu pembangunan yang terjadi dalam masyarakat
paling tidak harus mempunyai tiga sasaran, antara lain : peningkatan
ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok
seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan ; peningkatan taraf
hidup yaitu peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja,
pendidikan yang lebih baik dan juga perhatian yang lebih besar terhadap
nilai-nilai budaya dan kemiskinan yang nantinya akan memperbaiki
kesejahteraan material dan rasa percaya diri sebagai individu maupun
commit to user
bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari
perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan
orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebutuhan dan kesenjangan
manusia (Todaro, 2000 : 23-24).
Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang
seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita
dicapai melalui pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi
disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk
meningkatkan produktivitas. Kegiatan pembangunan ekonomi pada
hakekatnya merupakan kegiatan produksi, dimana untuk memproduksi
dibutuhkan input. Atas dasar teknologi tertentu, akan mempengaruhi
berapa jumlah input yang diperlukan seirama dengan dinamika
pembangunan yang sedang berjalan. Sementara kita dihadapkan pada
tatanan kehidupan perekonomian yang mengarah pada situasi global
dimana persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan kuat.
Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati
seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin
secara adil dan merata. Untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi,
yang terutama akan dilaksanakan dengan industrialisasi. Proses
industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan satu jalur
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat
commit to user
Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha
dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian
pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan
mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari kelompok sektor primer
kesektor sekunder dan tersier.
Struktur ekonomi Indonesia telah mengalami pergeseran selama
tiga dekade terakhir ini. Pergeseran struktur ekonomi yang semula berbasis
agraris (pertanian) beralih menuju ke sektor industri. Hal ini dapat dilihat
dari turunnya pangsa sektor pertanian dalam pendapatan nasional dari
51,8% pada tahun 1967 menjadi 16,6% pada tahun 1995 dan naiknya
pangsa sektor industri dalam pendapatan nasional dari 8,4% pada tahun
1967 menjadi 23,3% pada tahun 1995. Sejak tahun 1993 sumbangan
sektor pertanian memang tidak pernah melebihi sektor industri
manufaktur. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian hanya
berperan 17,4% terhadap PDB, sementara ekspansi pada hampir semua
komoditi industri menyebabkan sektor industri menyumbang 23,9%
terhadap PDB. Pertumbuhan sektor industri Indonesia yang cukup tinggi
ini merupakan dampak dari adanya perubahan orientasi industri dari
substitusi impor menjadi promosi ekspor. Ekspor sektor industri
menyumbang sekitar 85% ekspor nonmigas dan sekitar 67% dari total
ekspor Indonesia sejak 1994. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah
1990-commit to user
an. Singkatnya, sektor industri muncul menjadi penyumbang nilai tambah
yang dominan dan telah tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan sektor
pertanian. Pada 2008 sektor pertanian hanya menyumbang 14,67%
terhadap PDB, sementara sector industri pengolahan menyumbang 27,29%
terhadap PDB (www.mudrajad.com).
Salah satu sektor industri yang memiliki peran penting dalam
perekonomian adalah industri tekstil (TPT). Industri ini mempunyai
peranan penting sebagai sektor pemimpin (leading sector). Leading sector
ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan
memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti
sektor pertanian dan sektor jasa misalnya.
Keberadaan pembangunan industri dalam berbagai sektor akan
mendorong terjadinya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi, menurut
Purwa Darminta (2008;258) aktivitas adalah semua kegiatan yang
bertujuan untuk mengubah segala sesuatu menjadi berbeda dari awal,
aktivitas juga dapat disebut sebagai pergeraan, jadi aktivitas ekonomi
adalah semua perubahan atau pergerakan yang bertujuan untuk
menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan atau uang.
Aktivitas ekonomi juga dapat dilakukan misalnya dengan jual-beli,
memasarkan suatu produk atau menyediakan suatu jasa.
Indonesia sebagai salah satu negara dengan produk tekstil dan
olahan terbanyak didunia, diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja
commit to user
Indonesia, banyaknya industri tekstile dan bahan hasil tekstil juga
menyediakan lapangan kerja informal yang biasanya terletak diperumahan
dan perkampungan penduduk (www.mediaekonomi.blogspot.com).
Tabel 1.1Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,
2008–2010(dalam ribuan)
Sumber : Data strategis BPS 2010
Dari data seperti yang terlihat pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat
bahwa sektor industri dapat menampung sekitar 12% dari jumlah tenaga
kerja yang ada. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor industri
merupakan penyerap lapangan kerja terbesar ke tiga dari keseluruhan jenis
lapangan pekerjaan yang ada.
Pulau Jawa sebagai pusat pemerintah dan industri, sehingga
sebagaian besar industri baik tekstil ataupun industri lainnya juga terletak
di Pulau Jawa. Keberadaan dua pelabuhan utama ekspor impor yaitu
Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok di Jakarta, juga
menjelaskan kenapa sebagaian besar industri terletak di Pulau Jawa. Lapangan
Pekerjaan Utama
2008 2009 2010
Februari Agustus Februari Agustus Februari
commit to user
Secara umum perkembangan industri di Indonesia pada tahun
2002-2009 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, hampir
seluruh sektor perindustrian di Indonesia mengalami perkembangan yang
cukup siginifikan terutama pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dimana
pertumbuhan yang terjadi hampir 50% dari jumlah pada tahun 2006.
Sebagai contoh adalah sektor tektil yang tumbuh dari jumlah 1.934 pada
tahun 2006 menjadi 2.809 tahun 2007, 2.820 tahun 2008. Pada sektor
makanan dan minuman juga terjadi petumbuhan yang cukup signifikan
pada tahun yang sama, jika semua berkisar pada angka 4.722 tahun 2006
tumbuh menjadi 6.341 tahun 2007 dan perkembang lagi pada tahun
berikutnya sebesar 6.341. contoh lainnya terjadi pada industri daur ulang
yang semula 55 industri pada tahun 2006 terus tumbuh menjadi 137 tahun
2007 dan menjadi 156 pada tahun 2008. Dengan pertumbuhan industri
hampir dalam semua bidang maka dikatakan bahwa bertumbuhan industri
terus menerus akan mengalami kenaikan, sehingga kebutuhan akan tenaga
kerja juga akan terus meningkat. Dan pada akhirnya akan meningkatkan
perekonomian pada daerah tersebut.
Seperti halnya pada pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan
industri di Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti,
commit to user Tabel 1.3.
Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tenaga Kerja, Upah Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2006
Banyaknya Tenaga Kerja Upah
Payment (000 Rp/ Thousand
Rp)
Kabupaten/Kota Perusahaan Workers
commit to user
memiliki perusahaan terbanyak dengan penyerapan tenaga terbesar adalah
Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan dan Kabupaten Karanganyar.
Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak
dan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.
Dari Tabel 1.3 juga didapat bahwa potensi Kabupaten Karanganyar
dengan jumlah industri yang mencapai 183 industri menunjukkan bahwa
perkembangan industri cukup signifikan di Jawa Tengah. Dengan potensi
tersebut maka perkembangan sektor industri Kabupaten Karanganyar akan
sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah secara regional.
Tabel 1.2 dan 1.3 tersebut diatas memperlihatkan perkembangan
commit to user
menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa industri tekstil
dan bahan olahan hail industri tektil memiliki prospek yang bagus sebagai
penyerap tenaga kerja.
Menurut tabel 1.4 dibawah Kabupaten Karanganyar sendiri sektor
industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB di Kabupaten
Karanganyar yaitu sebesar 52,88%. Dari pembentukan sektor industri
tersebut didominasi oleh kelompok industri besar dan sedang dimana
59
Tabel 1.4.
Sumbangan Persektor Terhadap PDRB Karanganyar
Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pertanian 3413.61 3241 2864.85 2796.91 2821.39 2855.22 2899.1 2866.18
Pertambangan dan
galian 1552.74 1670.99 1745.38 1732.8 1790.65 1786.83 1828.17 1905.23
Industri pengolahan 920386.45 926964.09 1027498.8 1089912.64 1105952.91 1134134.37 1173422.6 1200606.83 Listrik, gas dan air
bersih 70335.59 74258.95 74731.62 80416.81 83995.71 91764.94 96867.33 103020.58
Bangunan 366008.59 387649.94 414983.78 420965.63 455657.84 482295.37 528770.39 583069.88
Perdagangan, hotel
dan restoran 767655.17 800717.52 852375.58 920675.34 990436.08 1059091.72 1126471.69 1211208.88
Pengangkutan dan
komunikasi 314242.01 324804.08 341100.69 362003.53 381852.29 404594.41 428864.77 449973.94
Keuangan, persewaan
dan jasa perusahaan 310143.82 322969.01 335431.74 354389.45 378286.92 401749.42 425590.18 449992.44
Jasa-jasa 359931.03 390283.47 414544.51 436480.36 457375.87 489257.66 519573.14 546699.38
commit to user Rataan Rataan Rataan Rataan
(1) (5) (9) (13) (17) (18) Sumber : Data BPS Jawa Tengah Tahun 2009
Tabel diatas juga memperlihatkan perkembangan hasil olahan
produk tekstil. Baik secara triwulan maupun secara tahunan.
Perkembangan hasil produk yang terus meningkat juga menunjukkan
bahwa pasar tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri tektil akan terus
bertambah, dan hal tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian
daerah. Dari tiap triwulan yang ada dan dilihat secara pertahun rata-rata
pertumbuhan hasil industri tekstil akan selalu mengalami peningkatan.
Jumlah rataan hasil produk tektil yang selalu berkisar diatas 115
menunjukkan bahwa hingga saat ini industri tekstil dapat dijadikan salah
satu industri penggerak perekonomian di Indonesia, maupun regional Jawa
commit to user Tabel 1.6
Daftar 10 Industri Tesktile Terbesar Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
No. Nama Perusahaan Alamat Jumlah
Tenaga Kerja Produk
1 PT. Aladin Abadi Karanganyar 1.580 Kain Tenun
2 PT. Kusuma Hadi S Karanganyar 1.451 Kain Printing
3 PT. Tantra Industri Karanganyar 1.300 Pakaian Jadi
4 PT.Manunggal Adipura Karanganyar 927 Kain Tenun
5 PT. Agung Sejahtera Karanganyar 1.005 Kain Tenun
6 PT. Senang Kharisma Karanganyar 750 Kain Tenun
7 PT. Ladewindo Karanganyar 870 Pakaian Jadi
8 PT. Bengawan Tex Karanganyar 776 Kain Tenun
9 PT. Dunia Sandang Karanganyar 556 Kain Finish
10 PT. Sawah Kurnia Karanganyar 664 Kain Finish
Sumber : Data BPS Jawa Tengah Tahun 2009
Dari tabel 1.6 tersebut dilihat bahwa industri tekstil memiliki
penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, hal ini juga berarti akan
menggerakkan roda ekono pada daerah yang bersangkutan. Dan secara
umum juga akan mengubah pola perekonomian masyarakat. Tabel diatas
adalah untuk perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 500 orang,
dan belum industri kecil dan menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja
kurang dari 500 orang yang hingga data tersebut dikeluarkan jumlah
keseluruhan industri tekstil di Karanganyar baik industri besar, menengah
maupun kecil berjumlah 114 industri.
Di salah satu wilayah daerah Kabupaten Karanganyar yaitu
commit to user
yang bergerak dalam bidang pengolahan kapas menjadi benang (spinning)
yaitu PT. DELTA DUNIA TEXTILE. Dengan keberadaan industri tekstil
tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi kegiatan perekonomian
di daerah tersebut. Keberadaan industri tekstil ini berakibat meningkatnya
aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar industri tersebut. Industri tersebut
menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, misalnya dengan berdirinya
industri tersebut maka akan banyak pula pendatang baru dari luar daerah
untuk bekerja, seiring dengan itu permintaan tempat tinggal dan pangan
pun bertambah pula, hal ini berdampak positif bagi masyarakat di sekitar
lokasi industri tersebut, yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh
tani, sekarang banyak yang beralih membuka warung kelontong dan
warung makanan. Sementara itu, lahan-lahan yang dulunya hanya
dijadikan sebagai kebun atau kandang ternak sekarang beralih menjadi
bangunan kos-kosan. Dari segi pengangguran pun sekarang banyak sekali
berkurang, dengan keberadaan industri tersebut banyak lulusan-lulusan
SMA dan SMEA yang masuk sebagai karyawan industri tersebut.
Keberadaan industri tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar
bagi aktivitas ekonomi masyarakat di daerah sekitar.
Berdasarkan latar belakang datas maka penelitian ini mengambil
judul: “Dampak Keberadaan Indutri Tekstil PT. Delta Dunia Textile
Terhadap Aktifitas Ekonomi Masyarakat Desa Brujul Kabupaten
commit to user B. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah keberadaan industri tekstil di daerah Brujul Kecamatan
Jaten Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan aktivitas
ekonomi daerah di sekitar industri tersebut?
2. Apakah keberadaan industri tekstil di daerah Brujul Kecamatan
Jaten Kabupaten Karanganyar dapat mengurangi jumlah
pengangguran yang ada di sekitar industri tersebut?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan pendatang terhadap kehidupan
sosial masyarakat di daerah Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten
Karanganyar?
4. Apakah terdapat perbedaan terhadap pendapatan dan pengeluaran
pendududk Desa Brujul setelah adanya industri tekstil PT. Delta
Dunia Tekstile ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang peniliti yang diharapkan dapat tercapai dalam
penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui dampak keberadaan industri tekstil terhadap
aktivitas ekonomi masyarakat Desa Brujul, Kecamatan Jaten
commit to user
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat keberadaan industri
tekstil terhadap pengurangan angka pengangguran pada masyarakat
Desa Brujul, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan pendatang terhadap
kehidupan sosial masyarakat di daerah Brujul, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganya.
4. Untuk mengetahui adanya perbedaan terhadap pendapatan dan
pengeluaran pendududk Desa Brujul setelah adanya industri tekstil
PT. Delta Dunia Tekstile
D. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berharap agar hasil
penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai
berikut :
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan dalam
membahas dan memperdalam masalah yang ada hubungannya
dengan penelitian ini.
2. Sebagai aplikasi dan teori yang pernah dipelajari, sehingga
merupakan proses belajar lanjutan bagi penulis.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk
commit to user
59
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Utama Pembangunan
Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena
ekonomi semata, tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan
ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu
pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering
terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat
tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan,
selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga
mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial
masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya
yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih
baik.
Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan terdapat empat
teori yang dominan yaitu :
1. Teori Pertumbuhan Linear
Model pertumbuhan linear mendominasi perkembangan
teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam
Smith dan mengalami puncak kejayaan dengan lahirnya teori
commit to user
ini adalah evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu
negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan yang
paling awal adalah pertanian, pada tahapan ini pemerintah akan
mencoba membangun dan memperkuat infrastruktur yang
berhubungan dengan pertanian, yang juga akan mendukung
infrastruktur bidang perindustrian. Dalam tahapan ini negara
tersebut masih dapat digolongkan menjadi negara miskin. Tahapan
kedua adalah negara berkembang, dalam tahapan ini pertanian
masih mendominasi namun perkembangan sektor industri mulai
bergerak dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan yang
terakhir adalah negara maju, dimana pada tahapan ini sektor
pertanian tetap ada namun sudah dilakukan dengan penggunaan
teknologi yang lebih baik dan maju.
2. Teori Pertumbuhan Struktural
Teori ini menitikberatkan pembahasan pada mekanisme
trasformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang
berkembang, yang semula lebih bersifat subsistem dan menitik
beratkan pada sektor pertanian menuju struktur ekonomi yang lebih
modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa
commit to user
3. Teori Dependensia.
Pencetus dasar teori ini adalah Paul Baran, yang
menciptakan model dasar tesis alternatif mengenai keterbelakangan
ekonomi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Teori ini
berusaha menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang
dialami oleh negara-negara berkembang. Asumsi dasar teori ini
adalah pembagian perekonomian negara-negara maju dan kedua
adalah perekonomian negara-negara sedang berkembang.
Negara maju dalam hal ini adalah digambarkan suatu
negara yang sebagaian besar pendapatan negara tersebut berasal
dari sektor industri atau sektor yang telah dijadikan sebagai
industri. Sedangkan negara-negara sedang berkembang adalah
negara yang menuju proses industrisasi namun juga masih
mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pemasukan.
4. Teori Neo Klasik Penentang Revolusi
Teori ini disebut juga sebagai teori penawaran, teori ini
merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran
perencanaan dan menetapkan regulasi ekonomi yang menciptakan
iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam
pembangunan. Besarnya derajat campur tangan pemerintah dalam
aktivitas ekonomi, dan kurangnya intensif ekonomi, serta kesaahan
dalam mengalokasikan sumberdaya, merupakan sumber utama
commit to user
perekonomian menjadi lebih lambat, sementara di sisi lain
kesalahan sistem alokasi sumberdaya tidak menunjang terhadap
tujuan pemerataan “kue pembangunan” (Koentjaraningat, 1990).
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan ekonomi berbeda dengan teori pertumbuhan
ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi melibatkan aspek sosial yang
terabaikan dalam teori pertumbuhan ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa
teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari teori pertumbuhan
ekonomi.
Dalam garis besar teori pertumbuhan ekonomi dapat digolongkan
menjadi tiga teori yaitu (Sadono Sukirno, 2002):
1. Ekonomi Klasik
Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan
abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu
merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu
itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik,
ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara
kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.
Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah
penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian
commit to user
disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain
kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan capital.
Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi
rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini
akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang
semakin berkurang (low of diminishing returus) karena sumber
daya alam itu terbatas.
Beberapa ahli yang memberikan pengaruh yang kuat dalam
aliran klasik adalah :
1) Adam Smith
Menurut Adam Smith, perkembangan ekonomi
memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja agar
produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian kerja
harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi
kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitikberatkan
pada Luas Pasar, luas pasar harus dapat menampung hasil
produksi sehingga menarik perhatian perdagangan
internasional karena hubungan perdagangan internasional
itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar
negeri dan pasar dalam negeri. Sekali pertumbuhan itu
dimulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada
commit to user
terjadi dan akan menaikan tingkat produktivitas tenaga
kerja .
2) David Ricardo dan Mill
Kedua ahli ekonomi ini berpendapat bahwa di
dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat
yaitu:
a) Golongan kapital adalah golongan yang memimpin
produksi dan memegang peranan yang penting
karena mereka selalu mencari keuntungan dan
menginvestasikan kembali pendapatannya dalam
bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan
naiknya pendapatan nasional.
b) Golongan buruh ini tergantung pada golongan
kapital dan merupakan golongan yang terbesar
dalam masyarakat.
c) Golongan tuan tanah ini mereka hanya memikirkan
sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah
yang di sewakan. David Ricardo mengatakan bahwa
bila jumlah penduduk bertambah terus dan
akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah
yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin
commit to user
Dengan adanya tiga golongan tersebut maka pembangunan
ekonomi akan memberikan pengaruh dan melakukan
pemberdayaan yang berbeda pada tiap golonga tersebut. Golongan
kapital akan selalu berada didepan karena kekuatan modal yang
mereka miliki. Dengan modal terebut mereka mampu dan dapat
menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Golongan buruh sebagai pekerja, dapat disebut sebagai
lapisan terbawah dalam teori ini. Ketiadaan modal menjadikan
mereka hanya kelas pekerja. Berbeda dengan golongan tuan tanah
yang lebih memiliki kekuatan untuk melakukan penawaran.
2. Teori Schumpeter Mengenai Peranan Pengusaha Dalam
Pembangunan
Schumpeter berpendapat bahwa sistem yang paling efisien
untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat.
Schumpeter tidak sependapat dengan pandangan ahli-ahli ekonomi
klasik yang menganggap bahwa pembangunan ekonomi
merupakan suatu proses yang bersifat gradual dan berjalan secara
harmonis. Menurutnya pertambahan pendapatan negara dari masa
ke masa, perkembangannya sangat tidak stabil dan keadaannya
ditentukan oleh besarnya kemungkinan untuk menjalankan
pembentukan modal yang menguntungkan yang akan dilakukan
commit to user
3. Analisis Harrod dan Domor Mengenai Pertumbuhan yang mantap
(Steady Growth)
Harrod dan Damor menekankan pentingnya peranan
akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Jadi akumulasi
kapital itu mempunyai peranan ganda yaitu menimbulkan
pendapatan yang lebih besar dan disamping itu juga menaikan
kapasitas produksi dengan cara memperbesar jumlah kapital. Maka
pertumbuhan alat-alat kapital baru mempunyai beberapa akibat.
Kapital yang baru akan tetap belum dapat digunakan, sebab
bila digunakan tidak memberikan hasil karena pendapatan tetap.
Kapital baru itu akan digunakan dengan pengorbanan dari kapital
yang telah ada sebelumnya . Kapital yang baru akan menggantikan
tenaga kerja. Jadi pembentukan kapital bila tidak dibarengi dengan
kenaikan pendapatan yang sudah ada akan membuat kapital dan
tenaga menganggur.
C. Penganguran (Ketenagakerjaan)
Dalam konsep yang digunakan BPS, bekerja adalah melakukan
pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh
pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam
secara terus menerus selama seminggu yang lalu (mengacu pada tanggal
pencacahan), termasuk pekerja keluarga/tak dibayar yang ikut membantu
commit to user
mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus
bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha seperti sewa, bunga, dan
keuntungan, baik berupa uang maupun barang bagi pengusaha. Kegiatan
bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja, maupun yang punya
pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja,
misal karena cuti, sakit, dan lainnya.Penduduk yang bekerja sesuai konsep
BPS ini termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja
gambar 2.1 Diagram Ketenagakerjaan
Sumber : Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan
commit to user
Selain penduduk yang bekerja, pengangguran juga termasuk dalam
kelompok Angkatan Kerja. Penduduk yang termasuk dalam kategori
pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk
yang sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan
karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk
yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara
itu, penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang
hanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.
Pengangguran atau Tuna Karya - yang dikutip dari Wikipedia edisi
Bahasa Indonesia di http://id.wikipedia.org/wiki/pengangguran - adalah
istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja,
bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang
berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena
jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan
yang mampu menyerapnya.
Konsep dan definisi yang digunakan BPS dalam Sakernas mengacu
pada konsep yang berlaku secara internasional dari ILO (ILO Concept
Approach). Hal ini bertujuan agar indikator ketenagakerjaan Indonesia
bersifat internasional sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain.
Menurut konsep ini, penduduk usia kerja dibedakan berdasarkan kegiatan
utamanya menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan
Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke
commit to user
pengangguran. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia
kerja yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan
kegiatan lainnya. Sementara itu, bekerja didefinisikan sebagai kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau
membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan berlangsung paling
sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut
termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu
usaha/kegiatan ekonomi.
Definisi standar untuk penganggur adalah mereka yang tidak
mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari
pekerjaan. Sedangkan, mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang
tidak bekerja dan pada saat pencacahan orang tersebut sedang mencari
pekerjaan, misalnya : orang yang belum pernah bekerja tetapi sedang
berusaha mendapatkan pekerjaan atau orang yang sudah pernah bekerja
tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha
untuk mendapatkan pekerjaan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi
tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.
Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah
penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai
berikut :
commit to user
Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam
satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi
pembukaan lapangan kerja baruSelain itu, perkembangannya dapat
menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke
tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi
keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka
kemiskinan. Oleh karena itu, indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun
pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah
Indonesia.
Setengah pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang
telah bekerja, tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang
dilakukannya. Di Indonesia, setengah pengangguran didefinisikan sebaga
penduduk bekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35
jam seminggu). Dari keadaan tersebut, maka konsep setengah pengangguran
dibedakan menjadi dua, yaitu:
(1) Setengah Pengangguran Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di
bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih
mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain
(visible underem-ployment).
(2) Setengah Pengangguran Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di
bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi
commit to user
lain, sering disebut juga sebagai pekerja paruh waktu (part time
worker).
Indikator setengah pengangguran ini dapat digunakan sebagai
acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan,
dan produktivitas pekerja.
Selain pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, ada
beberapa konsep pengangguran lainnya yang terkait dengan pendidikan,
lapangan usaha, jenis pekerjaan/jabatan, dan status pekerjaan. Oleh karena
itu, terlebih dahulu perlu diketahui beberapa konsep berikut :
1) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan
yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas
tertinggi suatu tingkatan sekolah dan mendapatkan surat tanda tamat
belajar (ijazah)
2) Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam yang
digunakan oleh seseorang untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja
istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di
luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling,
jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba
kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja,
seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.
3) Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan
commit to user
Sakernas 1986-2005, pengelompokan lapangan usaha mengalami
beberapa kali perubahan.
4) Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan
oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang
bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
5) Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan
pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
Jenis pengangguran lainnya yang juga digunakan di beberapa
negara di dunia adalah (dikutip dari http://organisasi.org) :
1) Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment), adalah
pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya
kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar
kerja dan pembuka lapangan kerja.
2) Pengangguran Struktural (Structural Unemployment), adalah
keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan
tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka
lapangan kerja. Semakin maju keadaan perekonomian di suatu
daerah maka akan terjadi peningkatan kebutuhan akan sumber daya
manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
3) Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment), adalah keadaan
seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi
jangka pendek. Sebaga contoh, petani yang menanti musim tanam,
commit to user
4) Pengangguran Bersiklus (Siclical Unemployment), adalah
pengangguran yang terjadi akibat imbas dari naik turunnya siklus
ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada
penawaran tenaga kerja
D. Konsep Perubahan Sosial
1. Definisi Perubahan Sosial
Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan
struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi
sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh
para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Proses perubahan
sosial biasa tediri dari tiga tahap:
a. Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan
dikembangkan.
b. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu
dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.
c. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi
dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau
penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau
penolakan ide baru itu mempunyai akibat.
Dalam menghadapi perubahan sosial budaya tentu masalah
utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau
commit to user
Essay in Comparative Sosiology, New York, John Wiley & Sons,
1967 : 3. perubahan kebudayaan) itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi
dan antropologi telah banyak membicarakannya.
Menurut Max Weber dalam Licolyn Arsyad (2004), bahwa,
tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan
dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh
pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam
tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu
tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai
tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan
pada adat kebiasaan (tradisi).
Anonim dalam Media Intelektual (2008) mengungkapkan
bahwa, aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut
kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau
suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji,
menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial
adalah aksi yang dilakukan dengan syarat-syarat yang lebih mudah
dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah
digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi
permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial,
massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik.
Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian
commit to user
kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan
kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik.
Selanjutnya Netting, Ketther dan McMurtry dalam Boedionan
(2004) berpendapat bahwa, aksi sosial merupakan bagian dari
pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau
sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah
untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.
Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan
sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses.
Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang
diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok
menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan
sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan,
karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang
secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah.
Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi
sebagai model power-based karena menekankan adanya
kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena
munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau
organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving
forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk
berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving
commit to user
Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola
perubahan, yaitu: (1) Unfreezing, merupakan suatu proses
penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk
berubah, (2) Changing, merupakan langkah tindakan, baik
memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan
(3) Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan
yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku
manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur
tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian
individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi,
formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan
perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam
organisasi.
Sumodisastro (1985) mencoba mengembangkan teori yang
disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap
yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap
perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide
dasar dari Lewin. Tahap-tahap perubahan menurut Lewin adalah
sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2)
penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan
perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5)
commit to user
Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan
dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme
interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya
tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia
berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan
berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah.
Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan
melemahkan resistences to change. Peran agen perubahan menjadi
sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.
Atkinson (1987) dan Brooten (1978), dalam Boediono
menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses
yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan
sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan
pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan
yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual,
dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang
kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan
dan siklus perubahan akan dapat berguna.
Robert Laur (2001) mengungkapkan bahwa, perkembangan
masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi.
Proses evolusi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung
sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil
commit to user
pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu
bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte.
Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi
pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear
menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan
mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk
“kesempurnaan” masyarakat.
Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah
sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi
antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh
kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan
masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan
integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen
menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa
masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern
justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara
mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi
dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang
damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya
perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan
pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya
commit to user
Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat
dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang
dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat
harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing
tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu.
Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap
baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran
tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana
Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk
hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja,
masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan
terspesialisasi.
Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya
dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan
social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural
merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu.
Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di
masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat.
Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah
dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan
struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang
commit to user
Beratha (1985), berusaha memberikan suatu pengertian
tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi
unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial.
Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan
material terhadap unsur-unsur immaterial. Sehingga perubahan
sosial dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi
dalam struktur dan fungsi masyarakat.
Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan
yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu
masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada
definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai
himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi
struktur masyarakat lainnya (Sadono, 2002). Perubahan sosial
terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang
mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya
perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan
kebudayaan.
Anonim (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari
perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua
bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi,
filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak
mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup
commit to user
Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis
perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan
(Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap
perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan
bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau
sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan
berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi
berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang
ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk
bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial.
Akhirnya dikutip definisi Selo Soemardjan yang akan
dijadikan pegangan dalam pembicaraan selanjutnya. Perubahan–
perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga
kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi
sistem sosialnya, termasuka didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan
pola-pola per-kelakukan diantara kelompok-kelompok dalam
masyarakat” (Soekanto, 1990). Definisi ini menekankan perubahan
lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain
struktur masyarakat. Lembaga social ialah unsur yang mengatur
pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.
Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan
yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu
commit to user
definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai
himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi
struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial
terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang
mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya
perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan
kebudayaan. Beratha (1985), berpendapat bahwa segenap usaha
untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap
dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.
Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya.
Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang
meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan
lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi
organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan
kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun
demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan
perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).
2. Perubahan Sosial
Sedangkan perubahan sosial terbatas pada aspek-aspek
hubuingan sosial dan keseimbangannya. Meskipun begitu perlu
disadari bahwa sesuatu perubahan di masyarakat selamanya
memiliki mata rantai diantaranya elemen yang satu dan eleman
commit to user
dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan diktator dan
demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan
analisis organisasi sebagai subsistem sosial. Berikut ini adalah
teori-teori yang berhubungan dengan perubahan sosial :
a. Teori Barrington Moore
Teori yang disampaikan oleh Barrington Moore
berusaha menjelaskan pentingnya faktor struktural dibalik
sejarah perubahan yang terjadi pada negara-negara maju.
Negara-negara maju yang dianalisis oleh Moore adalah
negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari
negara berbasis pertanian menuju negara industri modern.
Secara garis besar proses transformasi pada negara-negara
maju ini melalui tiga pola, yaitu demokrasi, fasisme dan
komunisme.
Demokrasi merupakan suatu bentuk tatanan politik
yang dihasilkan oleh revolusi oleh kaum borjuis.
Pembangunan ekonomi pada negara dengan tatanan politik
demokrasi hanya dilakukan oleh kaum borjuis yang terdiri
dari kelas atas dan kaum tuan tanah. Masyarakat petani atau
kelas bawah hanya dipandang sebagai kelompok
pendukung saja, bahkan seringkali kelompok bawah ini
menjadi korban dari pembangunan ekonomi yang dilakukan
commit to user
kelompok masyarakat bawah melalui revolusi atau perang
sipil. Negara yang mengambil jalan demokrasi dalam
proses transformasinya adalah Inggris, Perancis dan
Amerika Serikat.
Berbeda halnya demokrasi, fasisme dapat berjalan
melalui revolusi konserfatif yang dilakukan oleh elit
konservatif dan kelas menengah. Koalisi antara kedua kelas
ini yang memimpin masyarakat kelas bawah baik di
perkotaan maupun perdesaan. Negara yang memilih jalan
fasisme menganggap demokrasi atau revolusi oleh
kelompok borjuis sebagai gerakan yang rapuh dan mudah
dikalahkan. Jepang dan Jerman merupakan contoh dari
negara yang mengambil jalan fasisme.
Komunisme lahir melalui revolusi kaum proletar
sebagai akibat ketidakpuasan atas usaha eksploitatif yang
dilakukan oleh kaum feodal dan borjuis. Perjuangan kelas
yang digambarkan oleh Marx merupakan suatu bentuk
perkembangan yang akan berakhir pada kemenangan kelas
proletar yang selanjutnya akan mwujudkan masyarakat
tanpa kelas. Perkembangan masyarakat oleh Marx
digambarkan sebagai bentuk linear yang mengacu kepada
hubungan moda produksi. Berawal dari bentuk masyarakat
commit to user
masyarakat modern tanpa kelas (scientific communism).
Tahap yang harus dilewati antara lain, tahap masyarakat
feodal dan tahap masyarakat borjuis. Marx menggambarkan
bahwa dunia masih pada tahap masyarakat borjuis sehingga
untuk mencapai tahap “kesempurnaan” perkembangan
perlu dilakukan revolusi oleh kaum proletar. Revolusi ini
akan mampu merebut semua faktor produksi dan pada
akhirnya mampu menumbangkan kaum borjuis sehingga
akan terwujud masyarakat tanpa kelas. Negara yang
menggunakan komunisme dalam proses transformasinya
adalah Cina dan Rusia (Rachbini, 2002).
b. Teori Perilaku Kolektif
Teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan
tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan
sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah
norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada
sistem sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari
dalam sistem atau luar sistem. Ketegangan ini dapat
berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi
struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan
sebagai variabel antara yang menghubungkan antara
hubungan antar individu seperti peran dan struktur
commit to user
Perubahan pola hubungan antar individu
menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa
kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau
kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang
mengakibatkan adanya perubahan melalui aksi sosial
bersama untuk merubah norma dan nilai (Rachbini, 2002).
c. Teori Inkonsistensi Status
Stratifikasi sosial pada masyarakat pra-industrial
belum terlalu terlihat dengan jelas dibandingkan pada
masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh masih
rendahnya derajat perbedaan yang timbul oleh adanya
pembagian kerja dan kompleksitas organisasi. Status sosial
masih terbatas pada bentuk ascribed status, yaitu suatu
bentuk status yang diperoleh sejak dia lahir. Mobilitas
sosial sangat terbatas dan cenderung tidak ada. Krisis status
mulai muncul seiring perubahan moda produksi agraris
menuju moda produksi kapitalis yang ditandai dengan
pembagian kerja dan kemunculan organisasi kompleks.
Perubahan moda produksi menimbulkan masalah
yang pelik berupa kemunculan status-status sosial yang
baru dengan segala keterbukaan dalam stratifikasinya.
Pembangunan ekonomi seiring perkembangan kapitalis
commit to user
pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal inilah yang
menimbulkan inkonsistensi status pada individu (Rachbini,
2002).
E. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat
Kehidupan dalam bermasyarakat meliputi berbagai macam bidang
kehidupan, mulai dari bidamg ekonomi, sosial maupun budaya. Beberapa
hal dalam bidang sosial dan ekonomi tidak terlepas dari peran budaya
dikarenakan ada tujuh unsur kebudayaan universal yang merupakan isi
dari semua kebudayaan yang ada di dunia.
Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia
dan masyarakat pendukungnya. Berbagai macam kekuatan yang harus
dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun
kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat tidak selamanya baik
untuk mereka. Disamping itu masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik
dibidang spritual maupun materiil (Koentjaraningrat,1990).
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh
kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Manusia
mempunyai kemampuan terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.
Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat bahwa budaya terbagi dalam tiga
bentuk yaitu budaya yang bersifat non fisik dan abstrak berupa ide (sistem