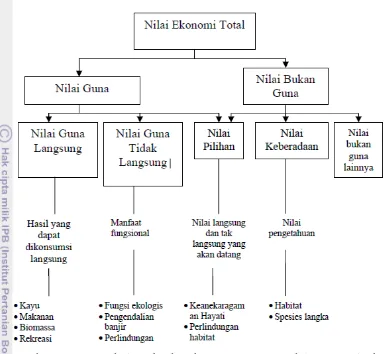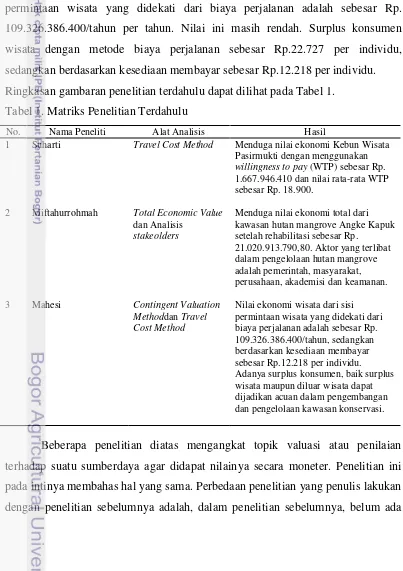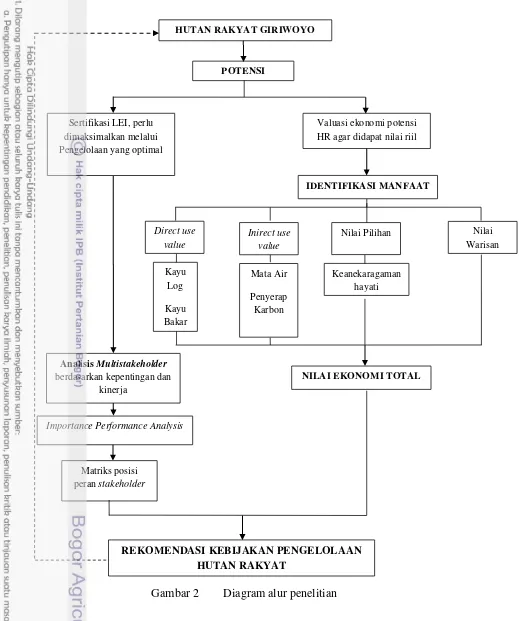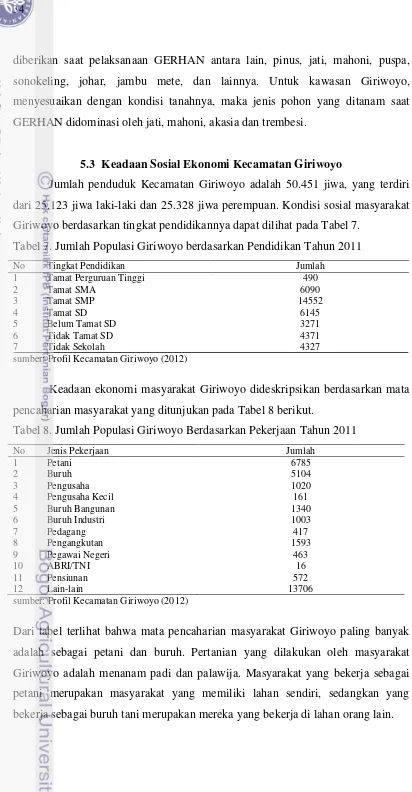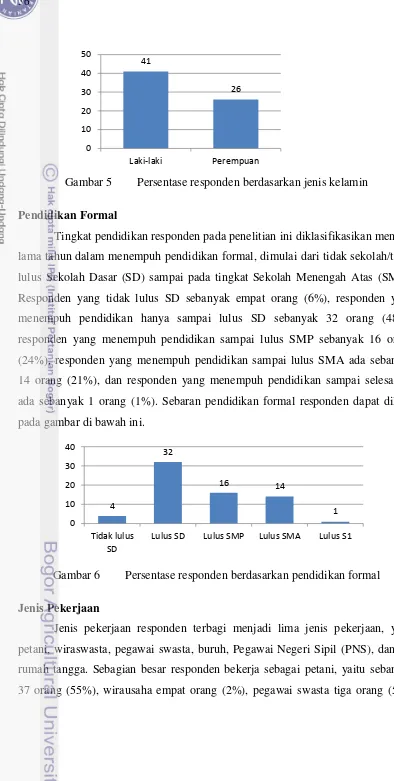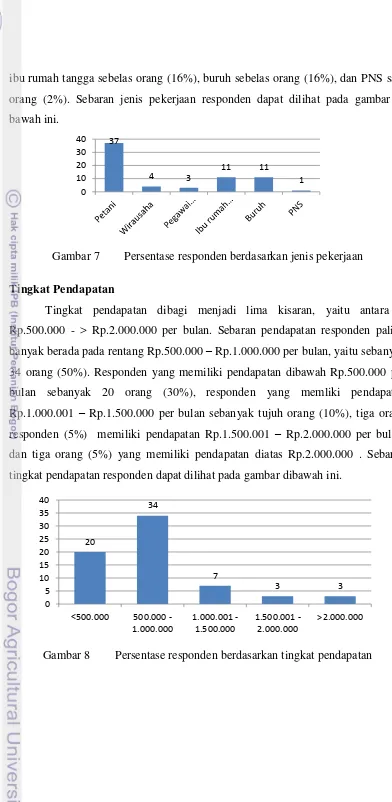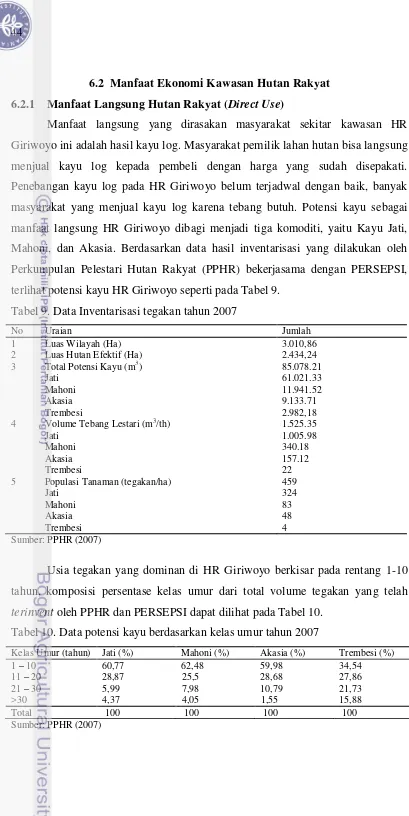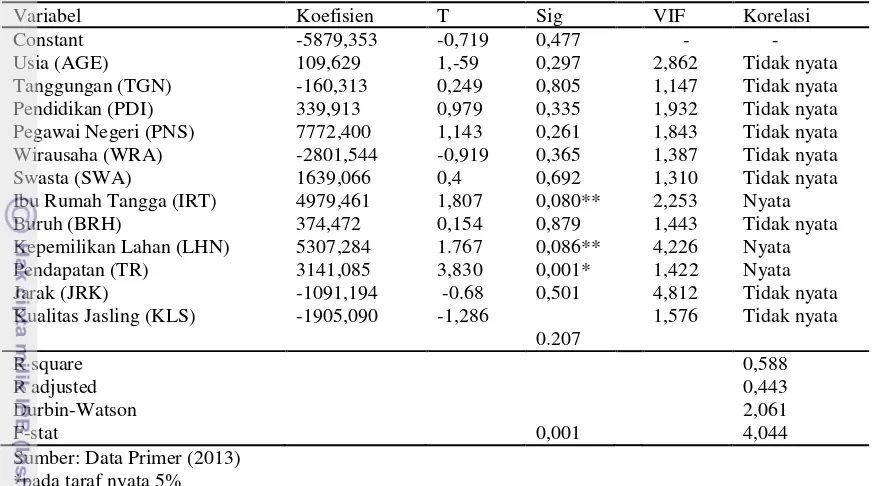NILAI EKONOMI TOTAL DAN ANALISIS
MULTISTAKEHOLDER
HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN GIRIWOYO,
KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH
HILMAN FIRDAUS
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutan Rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, November 2013
Hilman Firdaus
ABSTRAK
HILMAN FIRDAUS. Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutar Rakyat di Kabupaten Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dibimbing oleh EKA INTAN KUMALA PUTRI
Hutan Rakyat memiliki fungsi ekonomi dan fungsi ekologi. Fungsi ekonomi dari hutan rakyat seperti kayu log dan kayu bakar dapat dikatakan sebagai fungsi tangible, sedangkan fungsi ekologi hutan rakyat seperti penyerap karbon dan penghasil mata air dapat disebut juga fungsi intangible. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi aktual dari hutan rakyat, mengestimasi nilai ekonominya, menganalisis kelembagaan pengelolaan dan merumuskan rekomendasi pengelolaan yang lebih baik. Kondisi aktual dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Manfaat dari hutan rakyat Giriwoyo diestimasi dengan menggunakan metode Nilai Ekonomi Total (NET). Analisis kelembagaan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Hutan rakyat Giriwoyo memiliki NET sebesar Rp. 17.622.296.440/tahun. Kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dilihat dari struktur dan infrastruktur internal terlihat cukup baik. Berdasarkan hasil analisis IPA, fungsi petani dalam melakukan pemupukan dan peran pemerintah dalam melakukan koordinasi adalah yang harus diprioritaskan.
Kata kunci: Giriwoyo, hutan rakyat, IPA, NET
ABSTRACT
HILMAN FIRDAUS. Total Economics Value and Multistakeholders Analysis of Smallholder Forest at Giriwoyo District, Wonogiri, East Java. Supervised by EKA INTAN KUMALA PUTRI
Smallholder Forest have economic and ecological functions. The economic function of smallholder forest, such as timber and firewood can be called as tangible values. The ecological functions which are called intangible values are absorbing carbons and retaining waters. The objectives of this research are to identify the actual condition of Giriwoyo smallholder forest, to estimate its economic value, to analyze its institutional management and to formulate recommendations for better management. The method used to identify the actual condition of Giriwoyo smallholder forest is descriptive analysis. The benefits of Giriwoyo smallholder forest are calculated using Total Economic Value (TEV) approach. Institutional management are analyzed using Importance Performance Analysis (IPA). The result of this research shows that Total economic value of Giriwoyo smallholder forest is about IDR 17.622.296.440 per annum. Its management institution seemed quite good because there was clear division of labour. Based on analysis of IPA, the function of farmers in doing a fertilization and the role of government in coordination must be prioritized.
Keywords: Giriwoyo, IPA, private forest, TEV.
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada
Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan
NILAI EKONOMI TOTAL DAN ANALISIS
MULTISTAKEHOLDER
HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN GIRIWOYO,
KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH
HILMAN FIRDAUS
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
Judul Skripsi : Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutan Rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
Nama : Hilman Firdaus
NIM : H44090076
Disetujui oleh
Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MS Pembimbing
Diketahui oleh
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T Ketua Departemen
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Judul skripsi ini adalah “Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutan Rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.”
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:
1. Kedua orang tua yaitu Iwan Kuswandi (Alm) dan Siti Hanifah, serta Johan Apriandi, Anthi Dwi Putriani Anugrah, Tari Aprilia, dan Anindya Putriani Anugrah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan perhatiannya. 2. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MS selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT selaku penguji utama dan Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc selaku penguji wakil departemen yang telah memberikan berbagai masukan dan saran yang berguna bagi penulis.
4. Novindra, SP, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri, Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR) Catur Giri Manunggal, Kantor Kecamatan Giriwoyo, serta Badan Pusat Statistik Pusat yang telah membantu selama pengumpulan data.
6. Bapak Rujimin, Masyarakat Giriwoyo, Ibu Wahyu Ida Riyani, S.Hut, dan Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.
7. Bapak Rujimin beserta keluarga yang telah memberikan tempat tinggal selama penulis melakukan survei lapang.
8. Teman terdekat penulis, Adila Ahmad, Fajar Cahya Nugraha, Galuh Mutdaman, Yulis Diana, Siti Annisa Putri, Sri Kuncoro, Irfan Nugraha atas bantuan semangat yang luar biasa.
9. Abida Hadi, Adinna Astrianti, Aulia Isnaini, Annisia Nifkiayu, Adinda Virantika, Lusi Dara Mega, Akmi Retno, Bahroin Idris, Dear Rahmatullah dan Petrus Romil sebagai teman berdiskusi selama penulis menyusun skripsi ini.
10.Keluarga besar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) FEM IPB khususnya dosen, staff dan seluruh rekan-rekan ESL terutama angkatan 46 atas semua arahan, masukan, dan bantuannya.
11.Teman-teman sebimbingan, Ario Bismoko Sandjoyo, Agustina Rahayu, Rahayu Eka Putri, Lailatussayidah, Nurul Silmi, Akmal Hartanto, Aisya Nadhira, serta Febriana Adiya Rangkuti yang selalu memberikan bantuan dan semangat.
13.Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak.
Bogor, November 2013
DAFTAR ISI
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 6
II. TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Hutan Rakyat 7
2.2 Pengertian Nilai 7
2.3 Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 8 2.4 Konsep Nilai Sumberdaya dan WTP Terhadap Jasa
Lingkungan 9
2.5 Nilai Ekonomi Total 10
2.6 Metode Kontingensi 13
2.7 Teori Kelembagaan 13
2.8 Analisis Multistakeholder 14
2.9 Tinjauan Studi Terdahulu 15
III. KERANGKA PEMIKIRAN 18
IV. METODE PENELITIAN 21
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 21
4.2 Penentuan Responden 21
4.3 Pengambilan Data 21
4.4 Metode Analisis Data 22
4.4.1 Analisis Tata Kelola Kelembagaan 23
4.4.2 Nilai Ekonomi Total Kawasan Hutan 23
4.4.3 Importance Performance Analysis 28
V. GAMBARAN UMUM 31
5.1 Sejarah Perkembangan Hutan Rakyat Giriwoyo 31
5.1 Keadaan Umum Kecamatan Giriwoyo 32
5.2 Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Giriwoyo 34 5.3 Karakteristik Responden WTP Nilai Warisan 35
5.3.1 Usia 35
5.3.2 Jenis Kelamin 36
5.3.3 Pendidikan Formal 37
5.3.4 Jenis Pekerjaan 37
5.3.5 Tingkat Pendapatan 37
6.1 Kondisi Aktual Hutan Rakyat Giriwoyo 38 6.1.1 Kepemilikan, Penebangan dan Prasarana Hutan 40
6.1.2 Kualitas SDM 41
6.1.3 Tata Kelola dan Manfaat Hutan 42
6.2 Manfaat Ekonomi Kawasan Hutan Rakyat 44
6.2.1 Manfaat Langsung Hutan Rakyat 44
6.2.2 Manfaat Guna Tidak Langsung Hutan Rakyat 48
6.2.3 Nilai Pilihan Hutan Rakyat 50
6.2.4 Nilai Warisan Hutan Rakyat 50
6.2.5 Nilai Ekonomi Total Hutan Rakyat Giriwoyo 54
VII. KELEMBAGAAN PPHR DALAM PENGELOLAAN HUTAN
RAKYAT GIRIWOYO 56
7.1 Struktur dan Infrastruktur Kelembagaan 56
7.1.1 Aturan Informal 58
7.1.2 Boundary Rule 61
7.1.3 Monitoring dan Sanksi 61
7.1.4 Penyelesaian Konflik 62
7.2 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan HR Giriwoyo 62
7.2.1 Peran PPHR Catur Giri Manunggal 66
7.2.2 Peran DISHUTBUN 67
7.2.3 Peran Akademisi 68
7.2.4 Peran Masyarakat 69
7.2.5 Rekomendasi Pengelolaan HR Giriwoyo 69
7.2.6 Kebijakan Tingkat Makro 71
VIII. SIMPULAN DAN SARAN 73
8.1 Simpulan 73
8.1 Saran 74
DAFTAR TABEL
1 Matriks Penelitian Terdahulu. 16
2 Matriks Analisis Data 22
3 Ukuran Kuantitatif Nilai Kinerja 29
4 Ukuran Kuantitatif Nilai Kepentingan 29
5 Penggunaan Lahan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 33
6 Penggunaan Lahan Kecamatan Giriwoyo Tahun 2010 33
7 Populasi Giriwoyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 34
8 Populasi Giriwoyo Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2011 34
9 Data Inventarisasi Jumlah Volume Tegakan Tahun 2007 44
10 Data Potensi Kayu Berdasarkan Kelas Umur Tahun 2007 44
11 Data Pengguna Mata Air Tahun 2007 49
12 Sebaran Nilai WTP Warisan HR Giriwoyo 52
13 Hasil Regresi Nilai WTP Warisan HR Giriwoyo 53
14 Nilai Ekonomi Total HR Giriwoyo 54
15 Jadwal Pertemuan Tingkat KPHR Desa Sejati 58
16 Jadwal Pertemuan Tingkat KPHR Desa Guwotirto 59
17 Jadwal Pertemuan Tingkat KPHR Kelurahan Girikikis 60
DAFTAR GAMBAR
1 NET dari sumberdaya hutan 11
2 Diagram alur penelitian 20
3 Diagram kartesius tingkat kepentingan dan kinerja 29
4 Presentase responden berdasarkan usia 35
5 Presentase responden berdasarkan jenis kelamin 36
6 Presentase responden berdasarkan pendidikan formal 36
7 Presentase responden berdasarkan pekerjaan 37
8 Presentase responden berdasarkan tingkat pendapatan 37
9 Tingkatan organisasi pengelola hutan rakyat 39
10 Struktur organisasi PPHR Catur Giri Manunggal 56
11 Diagram garis hasil analisis IPA 64
DAFTAR LAMPIRAN
1 Peta Kecamatan Giriwoyo 83
2 Uji Statistik WTP Nilai Warisan 83
3 Kuisioner analisis WTP 86
4 Kuisioner analisis IPA 89
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang
garis pantai lebih dari 81.000 km, memiliki lebih dari 17.508 pulau dan luas laut
sekitar 3,1 juta km2. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan
keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar ke-2 di dunia, yang ditandai dengan
luasan hutan Indonesia lebih dari 130 juta hektar pada tahun 20111. Kekayaan
yang berasal dari sumberdaya hutan menjadi salah satu sumber pendapatan
negara. Produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Non Kayu)
menjadi komoditi yang memiliki nilai jual tinggi merupakan sumber devisa yang
tidak kecil bagi negara.
Hutan secara ekologi merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa
hamparan lahan, berisi sumberdaya alam hayati dan didominasi oleh pepohonan
yang lebat. Secara ekonomi, sumberdaya hutan di Indonesia memiliki manfaat
yang sangat besar yang dapat dibedakan atas manfaat tangible dan manfaat
intangible. Manfaat tangible merupakan manfaat yang dirasakan dalam bentuk
fisik, seperti kayu, rotan, buah-buahan, madu, tanaman obat,dan lain-lain yang
dapat bersifat ekonomis, sedangkan manfaat intangible merupakan manfaat yang
berbentuk immaterial atau dapat dirasakan namun tidak nampak secara fisik,
seperti fungsi hidrologi, rekreasi, penghasil oksigen, penyerap carbon, penyedia
sumber air, habitat bagi berjuta flora dan fauna, sebagai penyeimbang lingkungan,
serta mencegah timbulnya pemanasan global. Potensi sumberdaya alam hayati dan
ekosistem dari hutan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan
dan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan upaya konservasi sehingga
tercapai keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan yang lestari.
Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan
terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati serta keseimbangan ekosistem
1
Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Sk Menteri Kehutanan.
sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan mutu kehidupan manusia.
Hutan Rakyat (HR) merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan
oleh masyarakat dalam membantu mengembangkan potensi hutan yang ada di
Indonesia. Hutan Rakyat dapat memberikan manfaat secara luas, tidak hanya bagi
pemiliknya, namun juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Manfaat HR secara
langsung dapat dirasakan masing-masing rumah tangga para pelakunya dan secara
tidak langsung berpengaruh pada perekonomian desa2. Hutan rakyat, menurut
UUD No 41 Tahun 1999 merupakan jenis hutan yang dikelompokkan ke dalam
hutan hak. Ini berarti bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah
yang telah dibebani hak milik, yang konsekuensi logisnya adalah bahwa hutan
rakyat diusahakan tidak pada lahan negara. Potensi hutan rakyat di Indonesia
diperkirakan sebanyak 262.929.193 batang atau setara 65.732.298 m2 (rata-rata
per batang/pohon mempunyai volume 0,25 m3), yang terdiri dari jenis pohon jati,
sengon, mahoni, bambu, akasia, pinus, dan sonokeling (BPS 2003)
Hampir 50% dari total luas HR di Indonesia berada di Jawa-Madura.
Potensi sebaran HR di Pulau Jawa–Madura diperkirakan seluas 2.585.014,06 ha, dengan taksiran volume kayu HR di Pulau Jawa-Madura sebesar kurang lebih
74.763.601,06 m3 atau 28,92 m3/ha (Mugiono 2009). Hutan rakyat di Jawa sudah
dikenal sejak dahulu dan dipraktekan secara turun temurun, serta mempunyai
karakteristik yang berbeda dari segi budidaya maupun status kepemilikannya
dibanding dengan HR di luar Jawa. Budidaya dan manajemen pengelolaan HR di
Jawa relatif lebih intensif dan lebih baik dibanding dengan di luar Jawa, hal ini
disebabkan karena opportunity cost pengembangan HR diluar jawa lebih besar
dibanding dengan tanaman perkebunan. Masyarakat luar jawa cenderung
menanam tanaman perkebunan seperti karet dan sawit.
Hutan Rakyat yang cukup berkembang di Pulau Jawa adalah HR yang
berada di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
Perkembangan HR Giriwoyo dapat dikatakan cukup baik, pada tahun 2007 HR
Giriwoyo mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) atas
2
sistem pengelolaannya yang berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar HR
Giriwoyo merasakan betul manfaat dari keberadaan HR ini, baik berupa manfaat
tangible maupun intangible, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait
perhitungan nilai ekonomi sumberdaya hutan rakyat agar dapat memberikan bukti
yang riil terhadap besarnya potensi yang terkandung dalam HR Giriwoyo saat ini.
Perhitungan nilai ekonomi (valuasi ekonomi) merupakan suatu upaya
untuk mengkuantifikasikan manfaat barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
sumberdaya, dalam hal ini adalah sumberdaya hutan. Perhitungan Nilai Ekonomi
Total atau Total Economics Value merupakan salah satu pendekatan yang dapat
digunakan untuk valuasi ekonomi. Nilai ekonomi total sumberdaya hutan dapat
dikelompokkan ke dalam nilai guna dan nilai non-guna.
Pengelolaan dan pemanfaatan HR yang optimal dapat tercapai apabila
kebijakan yang dihasilkan mengarah kepada keberlanjutan. Perlu adanya
kerjasama dan pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder mengenai
pentingnya melestarikan HR, bukan hanya untuk menjaga nilai ekologinya saja,
tetapi menjaga nilai ekonominya juga, sehingga pengelolaan dan pemanfataan
yang berkelanjutan dapat tercipta. Hal itulah yang mendasari penulis untuk
melakukan penelitian mengenai valuasi ekonomi pada hutan rakyat di Kecamatan
Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
1.2 Perumusan Masalah
Hingga saat ini, tidak diketahui pasti jumlah potensi keragaman hayati
hutan yang dimiliki oleh Indonesia dan berapa besar manfaat yang bisa digali.
Bahkan, sebelum keragaman hayati di Indonesia teridentifikasi, telah terjadi
pemusnahan yang tak terhingga. Oleh karena itu, upaya konservasi sumberdaya
alam di Indonesia dan pemanfaatannya secara lestari harus segera ditingkatkan.
Adanya kerusakan sumberdaya hayati dapat menyebabkan dampak yang buruk
seperti menurunnya nilai ekonomi hutan dan fungsi ekosistem hutan.
Untuk menanggulangi hal tersebut, telah dilakukan upaya pemulihan dan
peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan. Departemen
Kehutanan telah menfasilitasi penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi
tanaman penghijauan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air serta
kegiatan RHL lainnya yang bersifat spesifik sesuai kebutuhan dan karakteristik
lokasi. Kegiatan GERHAN dilaksanakan di dalam kawasan hutan seperti
reboisasi, mangrove, dan lain-lain dan di luar kawasan hutan seperti penghijauan,
hutan rakyat, hutan pantai/mangrove dan lain-lain.
Hutan rakyat Giriwoyo di Kabupaten Wonogiri merupakan sumberdaya
alam yang memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat. Hutan rakyat yang ada saat
ini di Kab. Wonogiri mayoritas merupakan dampak dari GERHAN pada tahun
2003, disamping adanya kegiatan-kegiatan dari Dishutbun Kab. Wonogiri yang
mendukung pengembangan hutan rakyat, diantaranya terassering, penghijauan,
dan lainnya.
Masyarakat Giriwoyo sudah merasakan manfaat yang dihasilkan dari kayu
rakyat, yang umumnya dijadikan sebagai investasi jangka panjang, digunakan
untuk membiayai pendidikan anak, membiayai pernikahan dan hajatan-hajatan
lainnya yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbagai kayu yang ditanam
oleh masyarakat di Giriwoyo, antara lain Jati, Mahoni, Akasia, dan Sonokeling.
Wonogiri merupakan salah satu kabupaten penghasil kayu rakyat yang cukup
besar, dengan produksi kayu 12.000 m3/bulan atau 150.000 m3/tahun melalui
SKSHH (catatan dari Dishutbun Kab. Wonogiri 2012). Selama ini yang sudah
diperhitungkan oleh masyarakat masih terbatas pada tangible benefit. Sedangkan
HR memiliki manfaat intangible, yaitu manfaat ekonomi yang tidak dapat
dikuantifikasikan secara langsung karena tidak adanya nilai pasar untuk barang
tersebut.
Manfaat intangible bersumber dari fungsi ekologi seperti pengendali
banjir, penyerapan karbondioksida, dan penghasil oksigen. Apabila fungsi ekologi
terganggu dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Dengan
demikian, kawasan HR Giriwoyo butuh pengelolaan agar fungsi ekologi dapat
berjalan dengan baik.
Pengelolaan HR Giriwoyo belum dilakukan dengan baik karena dalam
pengelolaannya hanya melibatkan petanit itu sendiri, hal ini terjadi karena belum
ada bentuk hubungan antar kelembagaan yang baik. Kelembagaan yang baik
pengelolaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap para
stakeholder agar kelembagaan dapat berjalan dengan baik dan pengelolaan HR
pun dapat lestari. Jika hal ini tidak diatasi secara konsisten maka dapat
menurunkan kualitas lingkungan hutan.
Di sisi lain, valuasi ekonomi terhadap ekosistem HR diperlukan untuk
menghitung besarnya nilai ekonomi total atas manfaat barang dan jasa ekosistem
HR dan untuk mengetahui nilai dan pandangan masyarakat mengenai keberadaan
HR Giriwoyo, melalui manfaat tangible dan intangible. Nilai ekonomi total dari
ekosistem HR merupakan nilai moneter sumberdaya alam dan lingkungan yang
mencerminkan nilai fungsi yang dimiliki sumberdaya alam dan lingkungan dari
ekosistem hutan.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai
berikut.
1. Bagaimanakah kondisi aktual HR Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri?
2. Berapakah nilai ekonomi total yang terkandung di dalam HR Giriwoyo?
3. Bagaimana bentuk kelembagaan dalam pengelolaan HR Giriwoyo?
4. Bagaimana rekomendasi pengelolaan HR agar tercipta pengelolaan yang
lebih baik?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencari potensi atau nilai apa
saja yang dimiliki oleh HRGiriwoyo. Nilai tersebut dicari dan diklasifikasi mana
yang termasuk pada use value, yang terdiri dari direct, indirect, dan optional
value, serta mana yang termasuk pada non-use value yang terdiri dari bequest
value, existence value, dan other non-use value. Nilai yang didapat kemudian
digunakan untuk mengestimasi Nilai Ekonomi Total (NET) dari keseluruhan HR
Giriwoyo.
Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi kondisi aktual HR Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten
2. Menghitung Nilai Ekonomi Total yang terkandung pada HR Giriwoyo,
Kabupaten Wonogiri.
3. Menganalisis struktur dan infrastruktur kelembagaan dalam pengelolaan
HR Giriwoyo.
4. Merekomendasikan pengelolaan HR Giriwoyo yang lebih baik.
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang sudah diperoleh pada
kehidupan nyata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang fungsi hutan rakyat, sehingga nanti masyarakat dapat
berpartisipasi dalam pemeliharaannya.
3. Penilaian yang bersifat ekonomis dan kuantitatif dapat dijadikan dasar
dalam penentuan kebijakan mengenai alokasi sumberdaya.
4. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan rujukan terhadap aplikasi dan
metode-metode kuantitatif dalam menilai manfaat suatu kawasan yang bersifat
tangible maupun intangible.
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka
penelitian ini mempunyai beberapa ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai
berikut:
1. Dalam menduga nilai total ekonomi, use value didapat dari hasil hutan
kayu dan non kayu yang memiliki nilai pasar
2. Nilai guna langsung dari HR Giriwoyo yang diestimasi adalah potensi
kayu log, kayu bakar dan empon-empon (kunyit).
3. Nilai guna tidak langsung yang diestimasi dari HR Giriwoyo adalah nilai
penyerap karbon dan nilai mata air
4. Nilai guna pilihan yang diestimasi dari HR Giriwoyo adalah nilai manfaat
keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.
5. Nilai keanekaragaman hayati sumberdaya hutan sekunder yang terdapat
dalam penelitian Pranoto (2009) dapat digunakan untuk mengestimasi nilai
II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hutan Rakyat
Menurut Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan
berdasarkan statusnya dibagi ke dalam hutan negara dan hutan milik atau hutan
hak. Hutan hak berada pada tanah yang dibebani hak milik dan biasa disebut
hutan rakyat. Hutan rakyat sebagaimana yang tertulis dalam Keputusan Menteri
Kehutanan No. 49/kpts/II/1997 adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan
ketentuan luas minimum 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih
dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman.
Suharjito (2000) mendefinisikan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki
oleh masyarakat yang dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karena itu hutan rakyat
disebut juga hutan milik. Departemen Kehutanan (1993) mendefinisikan bahwa
hutan rakyat adalah suatu lapangan di luar hutan negara yang didominasi oleh
pohon-pohonan, sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan
persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya.
Tujuan pembangunan hutan rakyat adalah:
1. Meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal tidak produktif
secara optimal dan lestari.
2. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang dibutuhkan
masyarakat.
3. Membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan dan bahan
baku industri, serta kayu bakar.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan sekaligus
meningkatkan kesejahteraan.
5. Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik
rakyat yang berada pada kawasan perlindungan daerah hulu DAS.
2.2 Pengertian Nilai
Menurut Davis dan Johnson (1987), nilai merupakan persepsi manusia
tentang makna suatu objek (pada kasus ini sumberdaya hutan) pada tempat dan
persepsi dan lokasi masyarakat yang berbeda-beda. Nilai sumberdaya hutan
sendiri bersumber dari berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat. Masyarakat
yang menerima manfaat secara langsung akan memiliki persepsi yang positif
terhadap nilai sumberdaya hutan, dan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan
tingginya nilai sumberdaya hutan tersebut. Hal tersebut mungkin berbeda dengan
persepsi masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dan tidak menerima manfaat
secara langsung.
Davis dan Johnson (1987) juga mengklasifikasi nilai berdasarkan cara
penilaian, yaitu : (a) nilai pasar, yaitu nilai yang ditetapkan melalui transaksi
pasar, (b) nilai kegunaan, yaitu nilai yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya
tersebut oleh individu tertentu, dan (c) nilai sosial, yaitu nilai yang ditetapkan
melalui peraturan, hukum, ataupun perwakilan masyarakat. Pearce (1992) dalam
Munasinghe (1993) membuat klasifikasi nilai manfaat yang menggambarkan Nilai
Ekonomi Total (Total Economic Value) berdasarkan cara atau proses manfaat
tersebut diperoleh.
2.3 Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Menurut Fauzi (2004), sumberdaya didefinisikan sebagai sesuatu yang
dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumberdaya itu sendiri memiliki dua aspek
yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan
dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumberdaya
dan bagaimana teknologi digunakan. Dapat juga dikatakan bahwa sumberdaya
adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang
bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan tersebut
seperti ikan, kayu, air, bahkan pencemaran sekalipun dapat dihitung nilai
ekonominya karena diasumsikan bahwa pasar itu eksis (Market Based), sehingga
transaksi barang dan jasa tersebut dapat dilakukan.
Sumberdaya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat
dalam bentuk lain, misalnya manfaat seperti keindahan, ketenangan dan
sebagainya. Manfaat tersebut sering kita sebut sebagai manfaat fungsi ekologis,
dari sumberdaya. Nilai tersebut tidak saja nilai pasar barang yang dihasilkan dari
suatu sumberdaya melainkan juga nilai jasa lingkungan yang ditimbulkan oleh
sumberdaya tersebut (Fauzi 2004).
2.4 Konsep Nilai Sumberdaya dan WTP Terhadap Jasa Lingkungan Fauzi (2004) mengemukakan bahwa pengertian nilai atau value,
khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya
alam dan lingkungan memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin
ilmu. Dari sisi ekologi, misalnya nilai dari hutan mangrove bisa berarti pentingnya
hutan mangrove sebagai tempat reproduksi spesies ikan tertentu atau fungsi
ekologis lainnya. Dari sudut pandang teknis, hutan mangrove merupakan wateri
bank yang dapat mencegah banjir atau kenaikan air laut. Perbedaan mengenai
persepsi nilai tersebut tentu saja akan menyulitkan pemahaman mengenai
pentingnya suatu ekosistem, oleh sebab itu diperlukan suatu persepsi yang sama
untuk penilaian ekosistem tersebut.
Umumnya metode penilaian ekonomi sumberdaya dapat dilakukan melalui
pendekatan yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung.
Pendekatan langsung mencakup teknik memperoleh nilai secara langsung dengan
menggunakan percobaan dan survei. Teknik survei menggunakan kuisioner terdiri
dari dua tipe yaitu perolehan ranking dari nilai, berupa keinginan untuk membayar
dan kesediaan untuk menerima kompensasi. Secara umum nilai ekonomi
didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin
mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya, Secara
formal konsep ini disebut kemauan membayar seseorang terhadap barang dan jasa
yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan
pengukuran ini, nilai ekologis dapat diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi
dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa (Pearce dan Moran 1994).
Pendekatan barang dan jasa secara ekonomi biasanya melalui pendekatan
nilai pasar yaitu berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Namun para
pemerhati lingkungan dan juga para ahli ekonomi percaya bahwa sumberdaya
alam belum dapat dinilai secara memuaskan dalam perhitungan ekonomi. Masih
dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut, seperti manfaat terumbu karang,
keindahan bawah laut dan sebagainya. Jasa lingkungan adalah produk sumberdaya
alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung (tangible) dan/atau
manfaat tidak langsung (intangible) antara lain: jasa wisata alam/rekreasi, jasa
perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir,
keindahan, keunikan, penyerapan dan penyimpanan karbon (Pearce dan Moran
1994).
Disisi lain pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan melalui
pengukuran willingness to accept (WTA) yaitu jumlah minimum pendapatan
seseorang untuk mau menerima penurunan terhadap sesuatu, tetapi dalam
prakteknya pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan daripada
WTA, karena WTA bukan pengukuran berdasarkan insentif sehingga kurang tepat
untuk dijadikan studi yang berbasis perilaku manusia. Dalam pengukuran WTP
terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi yaitu : (1) WTP tidak memiliki batas
bawah yang negatif; (2) batas atas WTP boleh melebihi pendapatan; (3) adanya
konsistensi antara keacakan pendugaan dan keacakan perhitungan (Fauzi 2004).
2.5 Nilai Total Ekonomi
Pearce (1992) dalam Munasinghe (1993) membuat klasifikasi nilai
manfaat yang menggambarkan Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value)
berdasarkan cara atau proses manfaat tersebut diperoleh. Secara garis besar, NET
Gambar 1 NET dari sumberdaya hutan (Pearce, 1992 dalam Munasinghe
1993).
Nilai ekonomi total (NET) merupakan penjumlahan dari nilai guna
langsung, nilai guna tidak langsung dan nilai non guna. Nilai guna langsung
merupakan nilai dari manfaat yang langsung dapat diambil dari SDH. Sebagai
contoh manfaat penggunaan sumber daya hutan sebagai input untuk proses
produksi atau sebagai barang konsumsi. Berbeda dengan nilai guna tidak
langsung, yaitu nilai dari manfaat yang secara tidak langsung dirasakan
manfaatnya, dan dapat berupa hal yang mendukung nilai guna langsung, seperti
berbagai manfaat yang bersifat fungsional yaitu berbagai manfaat ekologis hutan.
Sedangkan nilai bukan guna yaitu semua manfaat yang dihasilkan bukan dari hasil
interaksi secara fisik antara hutan dan konsumen (pengguna).
Nilai pilihan, mengacu kepada nilai penggunaan langsung dan tidak
langsung yang berpotensi dihasilkan di masa yang akan datang. Hal ini meliputi
pemanenan yang akan datang), apabila terdapat ketidakpastian akan ketersediaan
SDH tersebut, untuk pemanfaatan yang akan datang. Contoh lainnya adalah
sumber daya genetik dari hutan tropis untuk kepentingan masa depan.
Nilai bukan guna meliputi manfaat yang tidak dapat diukur yang
diturunkan dari keberadaan hutan di luar nilai guna langsung dan tidak langsung.
Nilai bukan guna terdiri atas nilai keberadaan dan nilai warisan. Nilai keberadaan
adalah nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu SDH berupa nilai yang
diberikan oleh masyarakat kepada kawasan hutan atas manfaat spiritual, estetika
dan kultural. Sementara nilai warisan adalah nilai yang diberikan masyarakat yang
hidup saat ini terhadap SDH, agar tetap utuh untuk diberikan kepada generasi
akan datang. Nilai-nilai ini tidak terefleksi dalam harga pasar (Bishop 1999).
Pengukuran sumberdaya (Fauzi 2004):
1. Sumberdaya hipotetikal. Adalah konsep pengukuran deposit yang belum
diketahui namun diharapkan ditemukan pada masa mendatang berdasarkan
survei yang dilakukan saat ini. Pengukuran sumberdaya ini biasanya
dilakukan dengan mengekstrapolasi laju pertumbuhan produksi dan
cadangan terbukti (proven reserve) pada periode sebelumnya.
2. Sumberdaya spekulatif. Konsep pengukuran ini digunakan untuk
mengukur deposit yang mungkin ditemukan pada daerah yang sedikit atau
belum dieksploitasi, di mana kondisi geologi memungkinkan
ditemukannya deposit.
3. Cadangan kondisional (conditional reserves). Adalah deposit yang sudah
diketahui atau ditemukan namun dengan kondisi harga outputdan
teknologi yang ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara ekonomis
4. Cadangan terbukti (proven resource). Adalah sumberdaya alam yang
sudah diketahui dan secara ekonomis dapat dimaanfaatkan dengan
teknologi, harga dan permintaan yang ada saat ini.
NET = Nilai Guna Langsung + Nilai Guna Tidak Langsung + Nilai Pilihan +
2.6 Metode Kontingensi (Contingent Valuation Method)
Metode kontingensi (CVM) adalah suatu cara untuk menilai suatu manfaat
non-use dan mengkonversinya ke dalam nilai moneter dengan metode survei.
Metode CVM digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi dan berbagai macam
ekosistem dan jasa pelayanan lingkungan. CVM adalah suatu metode
mengumpulkan preferensi seseorang mengekspresikan kesediaan membayar
seseorang. Pada dasarnya CVM menanyakan berapa kesediaan membayar mereka
untuk memperoleh suatu manfaat (Garod dan Willis 1999).
Wawancara dilakukan dengan menanyakan WTP dan WTA terhadap
sumberdaya alam agar tetap terpelihara. CVM hanya dapat digunakan sebagai
metode untuk mengestimasi nilai bukan guna yang tidak diperdagangkan di pasar,
dan menilai barang yang tidak memiliki barang subtitusi, komplemen, dan
pengganti yang diperdagangkan di pasar. Untuk menghasilkan informasi yang
akurat maka diperlukan beberapa hal, yaitu rancangan kuisioner yang tepat,
survey yang tepat dan teliti serta perhitungan ekonometrika yang rumit untuk
menganalisis data.
2.7 Teori Kelembagaan
Soemardjan dan Soelaeman (1974), menuliskan bahwa lembaga
mempunyai fungsi sebagai alat pengamatan kemasyarakatan (social control)
artinya kelembagaan dapat bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat yang
berperan besar terhadap sirkulasi kelembagaan tersebut. Komponen dari
kelembagaan antara lain; aturan formal, aturan informal dan mekanisme
penegakan (enforcement). Soemardjan dan Soelaiman (1974), memperinci ciri-ciri
lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:
1. Merupakan unit yang fungsional, merupakan organisasi pola pemikiran
dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan
hasil-hasilnya.
2. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu, yaitu telah teruji dan berupa
himpunan norma-norma pencapaian kebutuhan pokok yang sewajarnya
harus dipertahankan.
4. Mempunyai perangkat peralatan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut,
misalnya: bangunan gedung, mesin-mesin, alat-alat lain.
5. Mempunyai alat pengebor semangat, misalnya: lambang-lambang,
panji-panji, slogan-slogan, semboyan-semboyan dan lain sebagainya.
6. Mempunyai tradisi atau tata-tertib sendiri.
Soemardjan dan Soelaiman (1974) secara umum menyimpulkan bahwa
lembaga sosial merupakan suatu tatanan sosial yang mempunyai tiga fungsi pokok
dalam kehidupan masyarakat, yaitu:
1. Sebagai pedoman (patokan) bagi para anggota masyarakat tentang cara
bagaimana harus bersikap dan berperilaku dalam setiap usaha memenuhi
kebutuhan hidupnya.
2. Sebagai pertahanan atau penangkal (kekuatan) dalam melestarikan
keutuhan masyarakat.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka usaha memelihara suatu
ketertiban dan sekaligus memberantas segala perilaku anggota masyarakat
yang menyimpang
2.8 Analisis Multistakeholder
Analisis Multistakeholder akan mengklasifikasi pihak-pihak yang terlibat
dalam pengelolaan. Menurut Colfer et al. (1999), untuk menentukan siapa yang
perlu dipertimbangkan dalam analisis multistakeholder yaitu dengan
mengidentifikasi dimensi yang berkaitan dengan interaksi masyarakat terhadap
HR, dimana stakeholders dapat ditempatkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu:
1. Kedekatan dengan hutan, merupakan jarak tinggal masyarakat yang
berhubungan dengan kemudahan akses terhadap hutan.
2. Hak masyarakat, hak-hak yang sudah ada pada kawasan hendaknya diakui
dan dihormati.
3. Ketergantungan, merupakan kondisi yang menyebabkan masyarakat tidak
mempunyai pilihan yang realistis untuk kelangsungan hidupnya sehingga
4. Kemiskinan, mengandung implikasi serius terhadap kesejahteraan manusia
sehingga masyarakat yang miskin menjadi prioritas tujuan pengelolaan.
5. Pengetahuan lokal, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat
dalam menjaga kelestarian hutan.
6. Integrasi hutan/budaya, berkaitan dengan tempat-tempat keramat dalam
hutan, sistem-sistem simbolis yang memberi arti bagi kehidupan dan
sangat erat dengan perasaan masyarakat tentang dirinya. Selama cara
hidup masyarakat terintegrasi dengan hutan, kelangsungan budaya mereka
terancam oleh kehilangan hutan, sehingga mempunyai dampak
kemerosotan moral yang berakibat pada kerusakan hutan itu sendiri.
7. Defisit kekuasaan, berhubungan dengan hilangnya kemampuan
masyarakat lokal dalam melindungi sumberdaya atau sumber penghidupan
mereka daritekanan luar sehingga mereka terpaksa melakukan
praktik-praktik yang merusak.
2.9 Tinjauan Studi Terdahulu
Suharti (2007) menduga permintaan dan manfaat kunjungan rekreasi
dengan menggunakan metode biaya perjalanan di Kebun Wisata Pasirmukti. Nilai
surplus konsumen sebesar Rp. 7.478 dengan menggunakan jumlah kunjungan
selama satu tahun (Juli 2006 – Juni 2007). Nilai lokasi dihitung dengan menggunakan WTP Rp. 1.667.946.410 dan nilai rata-rata WTP sebesar Rp.
18.900. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap WTP adalah biaya perjalanan,
pendapatan, jumlah rombongan, jarak tempuh, lama mengetahui Kebun Wisata
Pasirmukti, jumlah rekreasi selama satu tahun, daya tarik, tempat rekreasi
alternatif, jenis kelamin dan status hari.
Miftahurrohmah (2012) mengestimasi nilai manfaat ekonomi total dari
hutan mangrove Angke Kapuk pasca rehabilitasi adalah sebesar
Rp.21.020.913.790,80, dengan rincian sebagai berikut; nilai manfaat langsung
berupa kayu, ikan, bibit dan arang adalah sebesar Rp. 8.689.724.000,00, nilai
manfaat tidak langsung sebesar Rp. 12.285.357.670,80, dan manfaat pilihan
sebesar Rp. 45.832.122,00. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan kelembagaan
dan keamanan. Hubungan aktor dalam pengelolaan kelembagaan hutan mangrove
berjalan harmonis dan sinergis.
Mahesi (2008) menyatakan bahwa nilai jasa lingkungan di Kebun Raya
Cibodas (KRC) lebih besar dari nilai jual pohon atau tanaman (dalam tahun).
Yang menjadi permasalahan adalah nilai jasa lingkungan tidak langsung dirasakan
secara ekonomi. Nilai sumberdaya hayati dapat dikelompokkan berdasarkan nilai
ekologi, nilai komersial dan nilai rekreasi. Nilai ekonomi wisata dari sisi
permintaan wisata yang didekati dari biaya perjalanan adalah sebesar Rp.
109.326.386.400/tahun per tahun. Nilai ini masih rendah. Surplus konsumen
wisata dengan metode biaya perjalanan sebesar Rp.22.727 per individu,
sedangkan berdasarkan kesediaan membayar sebesar Rp.12.218 per individu.
Ringkasan gambaran penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu
No. Nama Peneliti Alat Analisis Hasil 1
Menduga nilai ekonomi Kebun Wisata Pasirmukti dengan menggunakan willingness to pay (WTP) sebesar Rp. 1.667.946.410 dan nilai rata-rata WTP sebesar Rp. 18.900.
Menduga nilai ekonomi total dari kawasan hutan mangrove Angke Kapuk setelah rehabilitasi sebesar Rp.
21.020.913.790,80. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove adalah pemerintah, masyarakat, perusahaan, akademisi dan keamanan.
Nilai ekonomi wisata dari sisi permintaan wisata yang didekati dari biaya perjalanan adalah sebesar Rp. 109.326.386.400/tahun, sedangkan berdasarkan kesediaan membayar sebesar Rp.12.218 per individu. Adanya surplus konsumen, baik surplus wisata maupun diluar wisata dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi.
Beberapa penelitian diatas mengangkat topik valuasi atau penilaian
terhadap suatu sumberdaya agar didapat nilainya secara moneter. Penelitian ini
pada intinya membahas hal yang sama. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan
yang meneliti tentang nilai ekonomi total dan analisis struktur kelembagaan
dengan obyek Hutan Rakyat. Selain itu, studi diatas lebih melihat jasa lingkungan
dari segi permintaan wisata sehingga objeknya merupakan tempat wisata.
III KERANGKA PEMIKIRAN
3.1 Kerangka Pemikiran Operasional
Perbaikan atau rehabilitasi pada suatu sumberdaya akan memberikan
perubahan terhadap kondisi sumberdaya tersebut setelah dilakukan perbaikan.
Kabupaten Wonogiri pada umumnya dan Kecamatan Giriwoyo pada khususnya
awalnya merupakan kondisi yang gersang. Gerakan Penghijaunan Nasional
(GERHAN) yang dilakukan oleh pemerintah setempat pada tahun 2003
merupakan upaya penghijauan dan penyelamatan lahan-lahan kritis. Pelaksanaan
GERHAN di Kecamatan Giriwoyo mendorong berkembangnya Hutan Rakyat
yang ada saat ini
Keberadaan HR Giriwoyo merupakan hasil dilakukannya GERHAN,
keberhasilan ini tentu meningkatkan kualitas dan tentu saja nilai ekonomi yang
terkandung dalam sumberdaya hutan tersebut. Keberadaan HR Giriwoyo saat ini
memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat Giriwoyo, air yang pada
awalnya kering sekarang cukup melimpah, bahkan tetap mengalir pada saat
musim kemarau. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh nilai ekonomi total
dari HR Giriwoyo. Nilai ekonomi total dari HR Giriwoyo yang didapat dari
penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk
penentuan kebijakan. Hal ini kemudian akan berimplikasi kepada kebijakan
pemerintah untuk memperoleh HR yang bernilai ekonomi tinggi dan
berkelanjutan.
Tahap pertama dalam melakukan penelitian ini adalah mengidentifikasi
kondisi aktual HR Giriwoyo. Identifikasi dilakukan dengan cara suvey langsung
ke lapangan yang berlokasi di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa
Tengah, serta menggunakan metode analisis deskriptif hasil dari wawancara
dengan key person setempat. Selanjutnya dilakukan identifikasi manfaat hutan
melalui pendekatan Total Economic Value (TEV) dengan mewawancarai
responden melalui panduan kuisioner.
Nilai guna langsung (Direct Use Value) dari HR Giriwoyo yang dirasakan
oleh masyarakat adalah hasil kayu log, kayu bakar dan empon-empon. Nilai guna
Giriwoyo adalah manfaat penyerap karbon dan manfaat mata air. Nilai pilihan
dari HR giriwoyo merupakan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung
didalamnya, didapat dengan menggunakan metode benefit transfer. Nilai warisan
(Bequest Value) diperoleh berdasarkan analisis Willingness to Pay (WTP) atau
kesediaan membayar masyarakat untuk melestarikan hutan demi kelestarian di
masa yang akan datang.
Nilai dari manfaat hutan yang diperoleh tersebut kemudian dimoneterkan
untuk menghitung nilai ekonomi total dari seluruh kawasan HR Giriwoyo.
Informasi nilai ekonomi total ini kemudian dapat digunakan oleh pemerintah
dalam pengelolaan hutan yang lestari dan penentuan kebijakan yang efektif.
Selain menghitung nilai ekonomi total dari HR Giriwoyo, penelitian ini
juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan dan menganalisis aktor /
stakeholders yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan HR
Giriwoyo. Identifikasi ini dirasa perlu dilakukan karena besarnya manfaat atau
nilai ekonomi total yang terkandung dalam HR Giriwoyo, pasti ditentukan oleh
kualitas kelembagaan dalam pengelolaannya. Analisis kelembagaan meliputi
analisis struktur dan infrastruktur kelembagaan seperti aturan formal, informal,
boundary rule, monitoring dan sanksi.
Output dari suatu studi sebaiknya memberikan rekomendasi yang sesuai
dengan kondisi lapangan, oleh karena itu dilakukan pula analisis Importance
Performance Analysis untuk melihat kinerja dari fungsi atau peran stakeholder
yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan HR Giriwoyo.
Analisis ini dapat menggambarkan peran apa saja dari stakeholder yang perlu
dipertahankan bahkan dimaksimalkan, sehingga hal ini dapat menjadi
Gambar 2 Diagram alur penelitian
IDENTIFIKASI MANFAAT
REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
POTENSI
Kayu Log
Kayu Bakar
Mata Air
Penyerap Karbon
Keanekaragaman hayati Nilai Pilihan HUTAN RAKYAT GIRIWOYO
Nilai Warisan Direct use
value
Inirect use value
NILAI EKONOMI TOTAL Analisis Multistakeholder
berdasarkan kepentingan dan kinerja
Matriks posisi peran stakeholder
Valuasi ekonomi potensi HR agar didapat nilai riil Sertifikasi LEI, perlu
dimaksimalkan melalui Pengelolaan yang optimal
IV METODE PENELITIAN
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di kawasan HR yang berada di Giriwoyo, Kab.
Wonogiri. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena dinilai dengan
adanya kawasan HR di Giriwoyo ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar,
sehingga harapannya setelah dilakukan valuasi maka pemegang keputusan dapat
membuat kebijakan yang sesuai untuk tujuan pelestarian kawasan HR. Waktu
pengambilan data dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan April 2013.
4.2 Penentuan Responden
Pengambilan data dilakukan dengan cara menemui masyarakat sekitar
lokasi penelitian. Objek penelitian adalah masyarakat Wonogiri yang berdomisili
di sekitar kawasan HR Giriwoyo, sehat jasmani dan rohani dengan kriteria cukup
dewasa, yaitu yang telah berumur 17 tahun, dan mampu berkomunikasi dengan
baik. Untuk mengidentifikasi kondisi HR Giriwoyo, penulis mewawancari
responden yang merupakan key person dari Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat
(PPHR), Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
(DISHUTBUN) setempat, untuk analisis Willingness to Pay dipilih sebanyak 67
orang, sedangkan terkait Analisis Kinerja dan Kepentingan penulis mewawancarai
key person dari masing-masing stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan
HR Giriwoyo, yaitu PPHR, DISHUTBUN, Masyarakat dan Akademisi.
4.3 Pengambilan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. studi literatur untuk mendapatkan data sekunder tentang karakteristik
hutan rakyat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian;
2. observasi dengan cara mengamati dan mencatat hasil pengamatan di
lapangan;
3. wawancara dengan menggunakan kuisioner untuk memperoleh data yang
antara rumah dengan lahan hutan, dan kesediaan responden untuk
membayar (WTP) agar jasa-jasa lingkungan di kawasan HR Giriwoyo
tetap terjaga.
4. Penilaian responden terhadap kawasan HR tentang makna ekologis,
kelestarian, dan keindahan HR Giriwoyo.
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini seperti gambaran umum dan
kondisi wilayah hutan di Kecamatan Giriwoyo diperoleh dari lembaga setempat,
Dinas Kehutanan setempat, studi literatur, dan fasilitas internet.
4.4 Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini data yang terkumpul diolah secara manual dan
menggunakan komputer dengan Software SPSS, Graph dan Microsoft Excel 2007.
Tabel 2. Matriks Analisis Data
4.4.1 Analisis Tata Kelola Kelembagaan
Karakteristik kelembagaan dan aturan Perkumpulan Pelestari Hutan
Rakyat (PPHR) diidentifikasi dengan menggunakan analisis deskriptif.
Karakteristik kelembagaan yang dianalisis meliputi beberapa hal yang bersifat
kualitatif, yaitu: pertama, aktor dalam kelembagaan yang terdapat dalam PPHR
Catur Giri Manunggal. Kemudian aktor tersebut diidentifikasi perannya dalam
kelembagaan PPHR. Kedua, aturan main atau infrastruktur kelembagaan yang
dibagi menjadi lima bagian yaitu: (1) aturan formal, yang dapat dibagi menjadi
aturan eksternal dan internal; (2) aturan informal; (3) aturan keluar masuknya
anggota atau boundary rules ; (4) aturan monitoring dan sanksi; dan (5) aturan
dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kelembagaan.
4.4.2 Nilai Total Ekonomi Kawasan Hutan
Pendugaan nilai manfaat dari seluruh kawasan hutan dapat dihitung
berdasarkan nilai ekonomi totalnya. Total Economic Value (TEV) dalam hal ini
merupakan total dari penjumlahan nilai kegunaan langsung dari hutan rakyat dan
nilai kegunaan tak langsungnya.
TEV = DUV + NDV + NP + NW...(1)
dimana:
TEV = Total Economic Value
DUV = Direct Use Value
NDV = Non-Direct Use Value
NP = Nilai Pilihan
NW = Nilai Warisan
Dalam hal ini, nilai kegunaan langsung dapat dicari dari nilai ekonomis
atau nilai pasar produk hutan kayu dan non-kayu, sedangkan nilai kegunaan tak
langsung dapat dicari dengan kemampuan pohon menyerap karbon, serta sebagai
daerah resapan air yang belum tergantikan fungsinya, lalu fungsi-fungsi tersebut
dikonversi ke dalam nilai moneter yang berlaku pada nilai saat ini. Untuk
menduga nilai TEV, terlebih dahulu kita harus melakukan beberapa pekerjaan
seperti menentukan kekayaan keanekaragaman hayati di kawasan hutan Giriwoyo
Selanjutnya, melakukan valuasi terhadap manfaat-manfaat tersebut dengan
pendekatan TEV.
1. Nilai Guna Kayu Log
Nilai kayu log yang diestimasi adalah jenis kayu Jati, Mahoni dan Akasia,
dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
NKLi = Ei x HKLi...(2)
Keterangan:
NKLi = Nilai Total Kayu Log jenis-i (Rp/tahun)
Ei = Etat volume tebang lestari kayu jenis-i (m3/tahun)
HKLi = Harga kayu log per kubik jenis-i (Rp/m3)
i = Jenis kayu (Jati, Mahoni, dan Akasia)
2. Nilai Ekonomi Kayu Bakar
Nilai kayu bakar dihitung dengan cara pendekatan harga pasar. Untuk
menghitung nilai ekonomi kayu bakar dari HR Giriwoyo digunakan harga kayu
bakar yang berlaku di lokasi penelitian, lalu harga tersebut dikalikan dengan
jumlah populasi penduduk pra-sejahtera yang ada di Kecamatan Giriwoyo.
Asumsinya yang memanfaatkan kayu bakar tersebut adalah masyarakat
pra-sejahtera karena mereka tidak memiliki cukup dana untuk menggunakan kompor
gas. Nilai kayu bakar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
NKB = Jkb x Pkb x KPS...(3)
Keterangan:
NKB = Nilai Ekonomi Kayu Bakar (Rp/tahun)
Jkb = Jumlah penggunaan kayu bakar (ikat/tahun)
Pkb = harga kayu bakar yang berlaku (Rp/ikat)
KPS = jumlah keluarga pra-sejahtera
3. Nilai Ekonomi Empon-empon
Untuk mendapatkan nilai ekonomi empon-empon di lokasi penelitian,
produktivitas empon-empon (kunyit) di HR Desa Selopuro adalah sebesar 305
kg/ha/tahun, maka nilai kunyit dapat dihitung dengan persamaan matematis:
NE = PE x HE x LA...(4)
Dimana :
NE = Nilai Empon-empon/kunyit (Rp/tahun)
PE = Potensi Empon-empon (kg/ha/tahun)
HE = Harga Empon-empon (Rp/kg)
LA = Luas areal HR (ha)
4. Nilai Penyerap Karbon
Untuk menentukan nilai penyerap karbon di lokasi penelitian digunakan
pendekatan benefit transfer. Menurut Mugiono (2009) perkiraan kandungan
karbon dari kayu HR di Jawa-Madura adalah sebesar 40.724.689,34 ton, atau
15,75 ton/ha, maka nilai penyerap karbon dapat dihitung dengan persamaan
dibawah ini:
NPK = CO x PC x LA...(5)
Keterangan:
NPK = nilai total penyerap karbon (Rp/tahun)
CO = kandungan karbon dalam kayu/ha (15,75 ton/ha)
PC = harga karbon, US$12/ton
LA = Luas area penelitian (ha)
5. Nilai Ekonomi Mata Air
Untuk mendapatkan nilai ekonomi mata air di lokasi penelitian, digunakan
pendekatan dengan persamaan matematis:
NMA = nKK x USE x Pair...(6)
Keterangan:
NMA = Nilai Ekonomi Mata Air (Rp/tahun)
nKK = jumlah kepala keluarga yang memanfaatkan mata air
USE = rata-rata penggunaan air per rumah tangga (m3/tahun)
6. Nilai Keanekaragaman Hayati
Nilai keanekaragaman hayati dihitung berdasakan pendekatan benefit
transfer. Berdasarkan Ministry of State for Population and Environment (1993)
dalam Pranoto (2009), nilai manfaat keanekaragaman hayati untuk hutan sekunder
adalah sebesar US $32,5/ha/tahun, maka nilai keanekaragaman hayati dapat
dihitung dengan persamaan dibawah ini:
NFF = NKH x LA...(7)
Keterangan:
NFF = nilai total keanekaragaman hayati (Rp/tahun)
NKH = nilai keanekaragaman hayati per hektar (Rp/ha)
LA = luas areal penelitian (ha)
7. Analisis Nilai WTP Responden terhadap Nilai Warisan
Tahap-tahap dalam melakukan penelitian untuk menentukan WTP sebagai
nilai warisan HR Giriwoyo adalah sebagai berikut:
1. Membuat Pasar Hipotetik
Pasar hipotetik dibentuk atas dasar menurunya kualitas lingkungan
kawasan hutan Giriwoyo yang memiliki jasa lingkungan sebagai penyedia udara
bersih dan penghasil mata air. Selanjutnya pasar hipotetik yang ditawarkan
dibentuk dalam skenario sebagai berikut:
Skenario:
“Jika manfaat jasa lingkungan dari kawasan hutan rakyat Giriwoyo ini ingin tetap lestari dan dapat dirasakan selama mungkin, maka perlu adanya upaya
pelestarian dari masyarakat sekitar. Suatu saat nanti kualitas lingkungan akan
menurun yang dikarenakan berbagai penyebab antara lain, pemanfaatan
lingkungan yang tidak ramah lingkungan dan keterbatasan dana untuk tetap
Dengan skenario ini maka responden mengetahui gambaran tentang situasi
hipotetik mengenai rencana pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya
konservasi untuk pelestarian hutan rakyat Giriwoyo. Nilai pembayaran jasa
lingkungan yang akan diberlakukan akan ditanyakan kepada responden mengenai
WTP. Kepada setiap responden akan ditanyakan apakah mereka bersedia atau
menolak terhadap pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya pelestarian yang
akan diberlakukan. Alat survei yang digunakan adalah berupa kuisioner. WTP
didapat dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat dengan metode Open
Ended dimana responden dapat bebas menjawab berapa saja jumlah yang ingin
mereka bayarkan. Starting point atau batas minimal besarnya WTP ditentukan
berdasarkan harga bibit pohon jati di lokasi penelitian, yaitu Rp.3.000.
2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTP
Jika kuisioner telah dibuat, maka survey dilakukan dengan wawancara
langsung. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan nilai penawaran pada
penelitian ini yaitu dengan menawarkan kepada responden sejumlah uang tertentu
dan menanyakan apakah responden mau membayar atau tidak sejumlah uang
tersebut untuk memperoleh perbaikan kualitas lingkungan melalui pembayaran
jasa lingkungan.
3. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTP
WTP dapat diduga dengan melakukan nilai rata-rata dari penjumlahan
keseluruhan nilai WTP dibagi dengan jumlah responden. Dugaan rataan WTP
dicari dengan rumus:
EWTP =
∑ ...(8) dimana:
EWTP = Dugaan rataan WTP
Wi = Nilai WTP ke-i
Pfi = Frekuensi Relatif
n = Jumlah responden (67 orang)
4. Menduga Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Nilai WTP Pendugaan akan dilakukan menggunakan analisis regresi linear dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:
WTP = f (AGE, TGN, PDI, JOB, LHN, TR, JRK, KLS)...(9)
dimana:
WTP = Nilai WTP responden (Rp/orang)
AGE = Usia responden (Tahun)
TGN = Jumlah tanggungan responden (orang)
TR = Rata-rata pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)
PDI = Tingkat pendidikan responden (tahun)
JOB = Pekerjaan responden (dummy)
JRK = Jarak rumah ke lokasi pemanfaatan jasa lingkungan (m)
LHN = Kepemilikan lahan hutan (dummy)
KLS = Persepsi kualitas jasa lingkungan (1=baik, 2=biasa, 3=jelek)
5. Menjumlahkan Data
Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai tengah penawaran
dikonversi terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai tengah
WTP maka milai WTP kemudian dijumlah sehingga didapat nilai WTP total yang
penulis asumsikan sebagai nilai warisan dari HR Giriwoyo.
4.4.3 Importance Performance Analysis (IPA)
Metode IPA dapat digunakan untuk menentukan kebjakan apa yang perlu
dilakukan untuk pengelolaan HR Giriwoyo yang lebih baik. Responden yang
merupakan stakeholder terkait pengelolaan HR Giriwoyo, yaitu PPHR, Dinas
Kehutanan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri, Masyarakat dan Akademisi diminta
untuk menjawab pertanyaan terkait kinerja dan kepentingannya dari peran atau
fungsi yang mereka kerjakan dalam proses pengelolaan HR Giriwoyo. Penentuan
tingkat kinerja dan kepentingan dilakukan dengan menggunakan pembobotan
Tabel 3. Ukuran kuantitatif nilai kinerja
Persepsi Responden Nilai
Tidak baik 1
Cukup Baik 2
Baik 3
Sangat Baik 4
Tabel 4. Ukuran kuantitatif nilai kepentingan
Persepsi Responden Nilai
Tidak penting 1
Cukup penting 2
Penting 3
Sangat penting 4
Sumber : Journal of Theorical Applied Electronic Commerce Research (2011)
Bobot penilaian kinerja peran masing-masing stakeholder dan bobot
penilaian tingkat kepentingannya kemudian digambarkan ke dalam Diagram
Cartesius. Masing-masing indkator diposisikan dalam sebuah bagan yang
menunjukan tingkat kinerja dan kepentingan indikator tersebut. Indikator peran
atau fungsi tersebut diletakan pada sebuah bagan yang dibagi menjadi empat
kuadran. Secara jelas bangunan diagram cartesius tersebut dapat dilihat pada
Gambar 3.
Sumber : Journal of Theorical Applied Electronic Commerce Research (2011)
Gambar 3 Diagram Cartesius tingkat kepentingan dan kinerja
Keterangan:
Prioritas Utama (high importance & low importance)
Prioritas Utama, kuadran ini memuat atribut-atribut yang dianggap penting
oleh stakeholders, tetapi kinerja dari stakeholders belum sesuai sehingga belum
Prioritas Utama Pertahankan prestasi
Prioritas Rendah Berlebihan
tinggi tinggi
NILAI KEPENTINGAN
rendah
berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan HR Giriwoyo. Oleh karena itu
penentu kebijakan perlu melakukan perbaikan pada atribut-atribut yang berada
pada kuadran ini.
Pertahankan Prestasi (low importance & high performance)
Pertahankan prestasi, kuadran ini menunjukan atribut-atribut yang
kinerjanya sangat baik sesuai dengan yang seharusnya sehingga berpengaruh
nyata terhadap pengelolaan HR Giriwoyo.
Prioritas Rendah (low importance & low performance)
Prioritas rendah, kuadran ini menunjukan atribut yang dirasa kurang begitu
penting untuk dilakukan.Kinerja atribut yang berada pada kuadran ini pun dirasa
rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja.
Berlebihan (low importance & high performance)
Berlebihan, kuadran ini menunjukan atribut yang dirasa kurang penting
namun memiliki kinerja yang sangat tinggi, oleh karena itu tidak perlu untuk
meningkatkan kinerja pada atribut yang berada pada kuadran ini karena akan
V GAMBARAN UMUM
5.1 Sejarah Perkembangan Hutan Rakyat Giriwoyo
Pada tahun 1956, pasca masa penjajahan banyak hutan negara dalam
kondisi rusak dan gundul, hal ini melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan
penanaman tanaman penghijauan di daerah tegalan dan pekarangan. Jenis
tanaman yang ditanam oleh masyarakat saat itu adalah jenis tanaman jati, mahoni,
akasia dan nangka. Kegiatan penanaman penghijauan saat itu dinamakan KBD
(Kebun Bibit Dusun). Pengembangan KBD dilakukan secara swadaya oleh
masyarakat dengan dikoordinir oleh Kepala Dusun masing-masing. Masyarakat
pernah mendapat bantuan bibit pohon jenis akasia dari World Food Program
(WFP) dengan insentif sarden, susu, dan minyak goreng sebagai upah melakukan
penanaman. Penghijauan terus dilakukan di Giriwoyo, terutama saat pemerintah
mengeluarkan anjuran untuk menanam tanaman di lahan yang masih kosong
guna menanggulangi banjir di Waduk Gajah Mungkur.
Perkembangan penanaman di Giriwoyo dilatarbelakangi juga oleh kondisi
yang dirasakan masyarakat saat itu, lahan kritis yang berbatu sehingga membuat
masyarakat kesulitan air, udara yang panas dan gersang ketika musim kemarau
dan banjir serta longsor ketika musim hujan membuat masyarakat berinisiatif
untuk melakukan penanaman. Pada tahun 2003 dilaksanakan kegiatan GERHAN
oleh Dinas Kehutanan seperti kegiatan reboisasi, penghijauan, hutan rakyat, hutan
pantai/mangrove dan lain-lain. Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat
besar bagi masyarakat Giriwoyo, melalui penyuluhan dan pemberian bibit
menjadikan HR Giriwoyo semakin berkembang. Masyarakat mulai menyadari
besarnya manfaat hasil hutan baik tangible maupun intangible sehingga merasa
bahwa pengelolaan HR harus mulai dilakukan dengan baik, maka ada inisiatif dari
petani HR untuk membentuk Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR)
sebagai Forest Management Unit (FMU) yang bertugas mengelola HR Giriwoyo.
Melihat terus berkembangnya penanaman HR Giriwoyo, petani HR
melalui PPHR dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PERSEPSI
melakukan pengajuan sertifikasi hutan berbasis PHBML (Pengelolaan Hutan