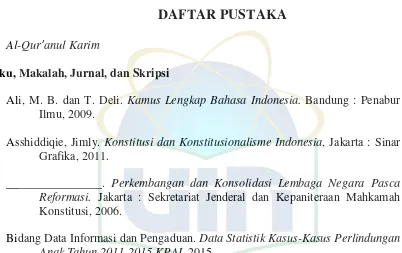Informasi Dokumen
- Penulis:
- Ryan Chandra Ardhiyanto
- Pengajar:
- Dr. H. Asroru Ni'am Sholeh, Lc, MA
- Sekolah: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Mata Pelajaran: Hukum Kelembagaan Negara
- Topik: Optimalisasi Peran KPAI Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar
- Tipe: Skripsi
- Tahun: 1436 H/ 2015 M
- Kota: Jakarta
Ringkasan Dokumen
I. PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan latar belakang permasalahan sosial di Indonesia yang kompleks, yang memerlukan intervensi dari lembaga negara. Dalam konteks ini, KPAI sebagai lembaga negara bantu berperan penting dalam perlindungan anak telantar. Penulis membahas urgensi penelitian ini, termasuk fokus pada kasus-kasus penelantaran anak yang mencolok, seperti di Cibubur dan kasus Angeline di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas KPAI dalam melindungi hak-hak anak, khususnya anak telantar, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menguraikan pentingnya peran lembaga negara dalam menangani masalah sosial anak di Indonesia. Penulis menyajikan konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi pembentukan KPAI, serta tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak telantar.
1.2 Pembatasan dan Rumusan Masalah
Bagian ini membatasi fokus penelitian pada peran KPAI dalam penanganan anak telantar. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian untuk mengeksplorasi usaha KPAI dan efektivitasnya dalam konteks perlindungan anak.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan penulisan dijabarkan untuk mendalami permasalahan terkait KPAI dan anak telantar. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, praktis, dan akademis dalam bidang hukum kelembagaan dan perlindungan anak.
II. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGANS DI INDONESIA
Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai KPAI sebagai lembaga negara bantu di Indonesia. Penulis menjelaskan peran KPAI dalam konteks Trias Politica dan bagaimana lembaga ini berfungsi sebagai pengawas dalam perlindungan anak. Penjelasan juga mencakup latar belakang pembentukan KPAI dan kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
2.1 Gambaran Umum Tentang State Auxiliary Organs
Penjelasan mengenai konsep state auxiliary organs dan peranannya dalam sistem ketatanegaraan. KPAI diidentifikasi sebagai lembaga independen yang muncul untuk mengatasi masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga primer.
2.2 Latar Belakang Pembentukan KPAI
Menguraikan komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi konvensi internasional dan pembentukan KPAI berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis menekankan pentingnya KPAI dalam konteks hukum dan sosial.
2.3 Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan KPAI sebagai lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dijelaskan, termasuk peran dan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak.
2.4 Struktur Kepengurusan KPAI
Menjelaskan struktur organisasi KPAI dan bagaimana pengurusannya berfungsi untuk menjalankan tugas dan wewenang lembaga dalam perlindungan anak.
2.5 Tugas dan Wewenang KPAI
Menguraikan tugas dan wewenang KPAI dalam melindungi anak, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.
III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK TELANTAR
Bagian ini membahas definisi anak telantar, bentuk tindakan penelantaran, faktor penyebab, dampak penelantaran, serta hukuman bagi pelaku. Penjelasan ini penting untuk memahami konteks di mana KPAI beroperasi dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak telantar.
3.1 Pengertian Anak Telantar
Menjelaskan definisi anak telantar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan sosial. Anak telantar dijelaskan sebagai anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara wajar.
3.2 Bentuk-Bentuk Tindakan yang Dapat Dikategorikan Penelantaran Anak
Menguraikan berbagai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak, termasuk pengabaian fisik dan emosional.
3.3 Faktor Penyebab Penelantaran Anak
Membahas faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran anak, termasuk kemiskinan, ketidakmampuan orang tua, dan masalah sosial lainnya.
3.4 Dampak Tindakan Penelantaran Bagi Anak
Menjelaskan dampak negatif penelantaran terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta implikasinya bagi masyarakat.
3.5 Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Anak
Menguraikan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penelantaran anak, serta peran penegak hukum dalam menegakkan hukum tersebut.
IV. KONTRIBUSI KPAI DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TELANTAR
Bagian ini membahas kontribusi KPAI dalam perlindungan anak telantar, termasuk tugas dan wewenang dalam penanganan kasus. Penulis juga menjelaskan beberapa kasus penelantaran anak yang menjadi sorotan, serta hambatan yang dihadapi KPAI dalam menjalankan tugasnya.
4.1 Tugas dan Wewenang KPAI dalam Penanganan Anak Telantar
Menguraikan tugas dan wewenang KPAI dalam menangani kasus anak telantar, serta bagaimana lembaga ini berperan dalam perlindungan hak anak.
4.2 Peran KPAI pada Penanganan Kasus Penelantaran Anak
Membahas secara rinci dua kasus penelantaran anak, yaitu di Cibubur dan kasus Angeline di Bali, serta respon KPAI terhadap kasus-kasus tersebut.
4.3 Hambatan dan Kendala KPAI
Mengidentifikasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi KPAI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk keterbatasan anggaran dan kewenangan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bagian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas KPAI dalam perlindungan anak telantar. Penulis menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menangani masalah anak telantar.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan penemuan utama terkait peran KPAI dalam perlindungan anak telantar.
5.2 Saran
Memberikan saran-saran yang konstruktif untuk perbaikan dan optimalisasi peran KPAI dalam melindungi hak-hak anak, khususnya anak telantar.
Referensi Dokumen
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Ali, M. B. dan T. Deli )
- Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia ( Asshiddiqie, Jimly )
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ( Asshiddiqie, Jimly )
- Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Budiardjo, Miriam )
- Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ( Chang, Andreas Ristanto )