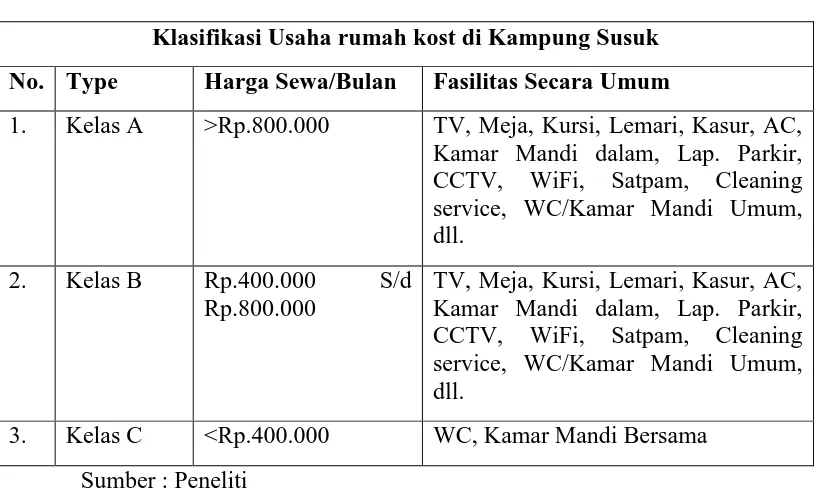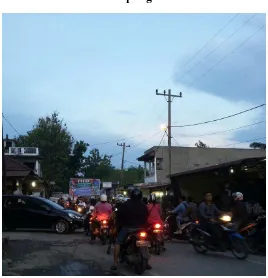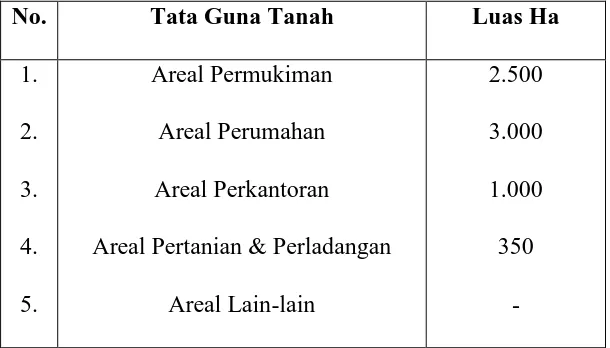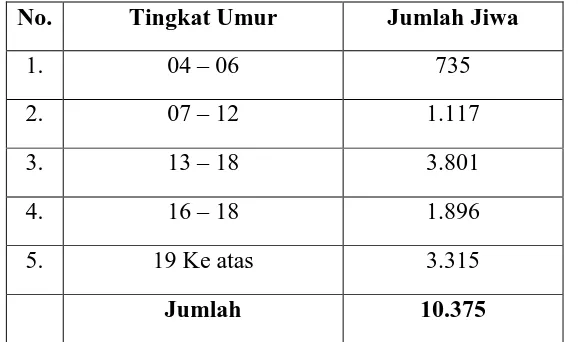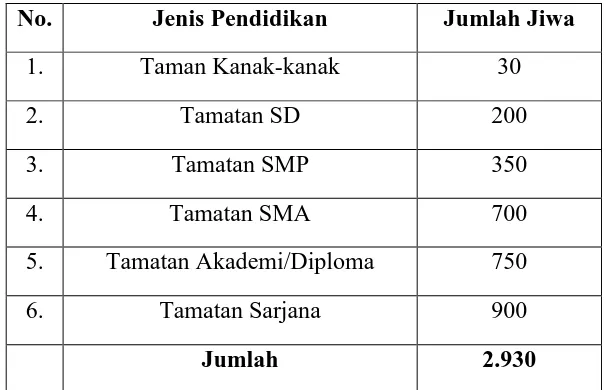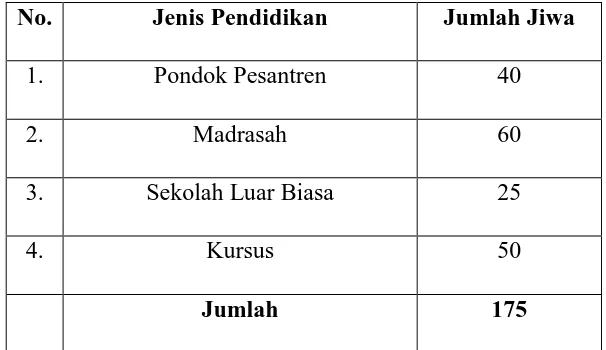DAFTAR PUSTAKA
Coombe, Rosemary J. “The Cultural Life Of Things: Anthropological Approaches To
Law And Society In Conditions Of Globalization”. Amerika: University Washington College.
Delliarnov. “Sejarah Pemikiran Ekonomi”. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2005.
Dinariana, D., Santun, R.P.S., Hartrisari, H., Nurisyah, S., dan Tarigan, S.D. “Model
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Daerah Resapan di Wilayah Jakarta Utara”. Jurnal Menara. 1(8): 1-10. 2007
Dwidjoseput, D. “Ekologi Manusia dan Lingkungan”. Jakarta :Penerbit Erlangga. 1991
Fanny, Anugrah. “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Tangerang”. Skripsi S1 Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor. 2005.
Geertz, Clifford. “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. alih bahasa Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
Geertz, Clifford. “Involusi Pertanian (Proses Perubahan Ekologi di Indonesia”.
Jakarta, Penerbit Bhratara K.A. 1976.
Geertz, Clifford. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture". In
The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.
Gufron, M. “Peranan Daerah Resapan Terhadap Sumberdaya Air Di Surabaya
Provinsi Jawa Timur”. Institut Teknologi Surabaya, Surabaya. 2002
Harminto, A.D. “Analisis Kebijakan Tentang Penanganan Alih Fungsi Lahan Kota
Semarang (Daerah Resapan Air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)” [Skripsi]. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang. 2002.
Ilham, dkk. “Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya”. IPB Press. Bogor. 2003.
Keesing, Roger M. Antropologi Budaya Jilid I, Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga. 1989.
Keesing, Roger M. Antropologi Budaya Jilid II, Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga. 1989.
Koentjaraningrat. “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. Jakarta : Gramedia.
1974.
Koentjaraningrat. “Metode-metode Penelitian Masyarakat”, Jakarta Gramedia. 1985.
Koentjaraningrat. ” Sejarah Teori Antropologi 1”. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1987.
Koestoer,dkk.1995.Prespektif Lingkungan Desa Kota. UI Press, Jakarta
Koestoer. Perspektif Lingkungan Desa Kota, Teori dan Kasus, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. 1997.
Lestari, S. “Analisis Kerugian Banjir Dan Biaya Penerapan Teknologi Modifikasi
Cuaca Dalam Mengatasi Banjir Di Dki Jakarta”. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca. 3(2): 155-159. 2002.
Lestari. “Faktor-faktor Terjadimya Alih Fungsi Lahan”. Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara. 2009.
Prawiro, Ruslan H. “Kependudukan (Teori, fakta dan masalah)”. Bandung : Penerbit Alumni. 1983.
Purwaningsih, Sri, dkk “Pengaruh Keberadaan Perguruan Tinggi Di Tembalang
terhadap Kepedulian Penduduk Desa Sekitar Kampus akan Pendidikan Anak‟.
Laporan Penelitian. Semarang: UNDIP. 1994.
Saifuddin, Achmad Fedyani. “Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma”. Jakarta :Kencana. 2005.
Sanderson, Stephen. Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
Sastrosupomo, Suprihadi. “Menghampiri Kebudayaan”. Bandung : Penerbit Alumni.
1982.
Suparlan, Dr. Parsudi (penyunting): “Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan”. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia. 1984.
Soekanto, Soerjono 2003. Judul Buku : Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Steward, Julian H. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana: University of Illinois Press. 1955.
Steward, Julian H. “Ecology: Cultural Ecology.” International Encyclopedia of the Social Science. 1972.
Todaro, Michael dan Stephen C Smith. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga. 2002.
Utomo. “Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan”. Lampung: Universitas Lampung. 1992.
Wahyunto. (Dalam Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara) “Pengertian Alih Fungsi Lahan”. USU. 2001
Widjanarko. “Dampak Alih Fungsi Lahan”.Universitas Sumatra Utara. 2006.
Widiyanti, Ninik. “Masalah Penduduk Kini dan Mendatang”. Jakarta: Pradnya
Paramita. 1987
Wiranata, I Gede A.B “Antropologi Budaya”. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
2011.
Wolf, Eric. Petani “Suatu Tinjauan Antropologis” , Jakarta : Yayasan Ilmu – Ilmu Sosial. 1983.
Sumber lain
http://pinterdw.blogspot.com/2012/01/pengertian-lahan.html
http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/penyebaran-penduduk-migrasi.html
http://imahagiregion3.wordpress.com/2012/06/04/permasalahan-pertumbuhan-penduduk/
BAB III
KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG SUSUK
3.1. Kehidupan Pertanian Di Kampung Susuk
Bertani merupakan pekerjaan sampingan warga Kampung Susuk. Sebagian
besar yang berprofesi sebagai petani tersebut adalah kaum wanita (istri). Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk menambah penghasilan keluarga. Sedangkan kaum
lelaki (suami) memiliki pekerjaan lain yaitu menarik becak, buruh bangunan,
wirausaha, dan lain-lain. Kegiatan bertani di sawah dimulai dari pagi hari hingga sore
hari dengan membawa bekal makanan untuk dimakan pada siang hari.
Namun, kebanyakan petani umumnya pulang ke rumah pada siang hari karena
jarak sawah ke rumah mereka tidak terlalu jauh. Hasil pertanian dari kegiatan bertani
digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dan bukan merupakan
mata pencaharian pokok. Oleh karena itu, para petani di Kampung Susuk telah
memiliki kesiapan apabila suatu saat lahan yang dikelola diambil alih oleh pemilik
tanah dengan beberapa tujuan diantaranya pembangunan perumahan, jalan dan
fasilitas lainnya.
Adapun bentuk mata pencaharian lainnya adalah wirausaha yaitu warung dan
toko. Pemilik warung-warung tersebut adalah penduduk setempat yang berasal dari
mahasiswa di daerah ini, maka bentuk usaha yang mendominasi diantaranya terdiri
dari toko alat-alat tulis, warung internet, fotokopi, warung nasi dan warung yang
menyediakan bahan mentah kebutuhan sehari-hari.
Ibu M.Sembiring (usia 40 tahun, Petani) yang merupakan petani di Kampung
Susuk lebih lanjut menjelaskan bahwa :
“ . . . kalau kami para petani di Kampung Susuk ini enggak terlalu khawatirlah bakalan digusur sama pembangunan gedung-gedung baru. Yang penting harganya sepadan kalau dijual. Lagi pula kami pun uda capek bertani sawah ini. Lebih bagus usaha kos-kosan atau laundry. Karena kan lebih menguntungkan . . . ”
Pendapat ibu M. Sembiring tadi merupakan suatu fenomena yang disebut
Marvin Harris sebagai materialisme budaya. Marvin Harris sebagai penganjur paling
cermat dan sangat teoritis mengenai materialisme budaya, telah mengajukan
penafsiran materialisme yang mengisyaratkan adanya rasionalitas tersembunyi,
berupa adaptasi ekologis, bagi seperangkat praktek kehidupan budaya, yang pada
permukaannya melambangkan ketidakrasionalitasan manusia dalam selubung budaya
(Keesing, 1989). Hal ini menegaskan bahwa adanya tujuan tertentu oleh masyarakat
dalam melakukan segala hal, meski terkadang hal yang ditonjolkan merupakan
sebuah hal yang tidak rasional. Masyarakat Kampung Susuk sebagai petani juga
memiliki pilihan-pilihan rasional terhadap langkah kedepan yang akan mereka ambil
terkait pemanfaatan lahan pertaniaannya. Apakah keputusan tersebut untuk menjual
lahan pertanian tersebut atau tidak itu merupakan suatu proses penafsiran lingkungan
Jenis sawah yang dikelola oleh petani di Kampung Susuk adalah sawah tadah
hujan. Hal ini berarti bahwa sumber pengairan sawah hanya diperoleh dari air hujan.
Petani benar-benar tergantung kepada datangnya hujan untuk menentukan masa
tanam. Di Susuk 8 terdapat sebuah sungai kecil yaitu aliran air dari Sungai
Sei-Semayam, namun sungai tersebut juga hanya mengalir jika dimusim hujan.
Gambar 1 : Sungai Semayam Yang Mengaliri Persawahan
Sumber : Peneliti
Bapak Sitepu (50 tahun, petani) yang merupakan salah satu petani di
Kampung Susuk juga menuturkan bahwa :
“. . . biasanya untuk mengairi sawah kami disini ya cuma
mengandalkan air hujan aja sama air irigasi yang ada di sekeliling sawah. Itu makannya petani disini enggak sembarangan untuk
Adaptasi ekologi ini penting dilakukan oleh masyarakat agar dapat survive
dengan kondisi lingkungan alamnya. Kenyataan ekologi dimana suatu masyarakat
tinggal akan melahirkan suatu budaya tertentu terkait dengan sistem pengelolaan
lingkungan alamnya. Bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang
berhubungan dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan
beradaptasi dengan lingkungannya di dalam pendekatan materialisme budaya Marvin
Harris dikategorikan sebagai komponen infrastuktur material yaitu terdiri dari
teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi (Sanderson, 1995, hal: 60).
Jikalau musim kemarau, sungai tersebut juga akan kering. Sungai kecil
tersebut hanya bisa dipergunakan oleh petani yang lahannya berada di dekat sungai
tersebut. Sekalipun demikian, petani tetap melakukan masa tanam dua kali dalam
setahun yaitu setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Petani belum pernah mengalami
keterlambatan masa tanam yang terlalu lama. Kalaupun terjadi perubahan masa tanam
biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan masa tanam seperti biasanya.
Seiring dengan berkembangnya pembangunan pemukiman di Kampung Susuk
terkhusus pembangunan kompleks perumahan, luas lahan pertanian semakin lama
semakin menyempit. Hal ini juga menyebabkan semakin sedikit jumlah petani di
Kampung Susuk karena tidak memiliki lahan lagi untuk dikelola. Jenis tanaman yang
ditanam di sawah petani adalah padi. Sekitar 15 tahun yang lalu, petani pernah
mencoba menanam palawija setelah panen untuk mengisi kekosongan lahan sampai
Gambar 2 : Sawah yang terhimpit perumahan
Sumber : Peneliti
Menurut petani, jenis tanah dan cuaca kurang mendukung untuk menanam
palawija di lahan tersebut. Sejak saat itu, petani hanya menggunakan lahan ini untuk
menanam padi. Namun, adakalanya petani menanam sayur sawi, kacang kedelai,
kacang hijau dan kacang tanah di pinggiran jalan Kampung Susuk dekat lahan
mereka. Umumnya tanaman tersebut tidak terlalu banyak dan hanya mereka
manfaatkan untuk dikonsumsi keluarga.
Bapak Sitepu lebih lanjut juga menjelaskan :
“ . . . sebenarnya petani juga sudah berusaha untuk mengambil
keuntungan semaksimalnya dalam mengolah lahan ini. Cuman, mau gimana lagi petani udah pernah mencoba nanam palawija. Tapi
Dilihat dari pendekatan materialisme budaya Mevin Harris ( dalam Sanderson,
1995) maka pendapat dari bapak Sitepu dapat digolongkan dalam faktor ekonomi
dalam materialisme budaya. Faktor ekonomi adalah apa yang menjadi bentuk
adaptasinya misalnya petani, bagaimana sistem ekonomi pada petani terkait dengan
barang yang dihasilkan, distribusi dan dipertukarkan. Demikian juga
demografi/kependudukan dilihat sebagai komponen dalam infrastruktur material yang
akan mempengaruhinya. Dalam hal ini adalah para petani sudah berusaha untuk
mendiversifikasi jenis tanamannya. Namun, kendala yang dihadapi memang adalah
pendapatan yang tidak maksimal dari jenis tanaman tersebut.
Sejak awal bertani, petani hanya bisa memanen padi satu kali dalam setahun.
Pada saat itu petani menanam jenis padi Pulo. Pada saat itu tidak terlalu banyak
masalah yang dihadapi petani termasuk diantararnya masalah hama dan penyakit
padi. Namun, setelah tahun 1980 petani mulai panen dua kali dalam setahun. Hal ini
disebabkan karena petani sudah mulai mengganti jenis bibit mereka dengan bibit padi
IR 64. Sejak tahun tersebutlah hama mulai banyak dihadapi para petani padi.
Penerapan aplikasi revolusi pertanian di era orde baru membawa banyak
perkembangan teknologi pertanian didalamnya. Teknologi dalam pengertian ini
adalah terdiri dari informasi, peralatan, teknik yang dengannya manusia beradaptasi
dengan lingkungan fisiknya (Lenski dalam Sanderson, 1995). Teknologi juga bukan
hanya berisikan peralatan atau objek yang bersifat fisik atau kongkrit saja tapi juga
Berdasarkan data dari informan dapat dilihat bahwa rata-rata petani bertempat
tinggal di Susuk 5 (lima) yaitu sebanyak 57 petani. Pada tahun 2008 saat data tersebut
di buat, semua petani yang tertera masih mengelola lahan pertanian. Namun pada saat
melakukan wawancara dengan ketua Kelompok Tani, didapati data bahwa petani
yang masih terus bertani hanya tinggal 26 petani.
Hal ini disebabkan karena lahan milik 31 petani lagi sudah ditimbun untuk
dijadikan bangunan kompleks perumahan. Hampir semua petani yang bertani di
Kampung Susuk merupakan petani penyewa. Dari data di atas, hanya 2 (dua) orang
petani yang mengelola lahan sendiri yaitu : Jenda Ngenda dan Prorama Ginting.
Selebihnya, lahan yang dikelola petani bukanlah milik sendiri melainkan disewa dari
PT IRA (BUMI MANSUR) dan pemilik yang lainnya. Pada umumnya lahan yang
dikelola petani tidak terlalu luas.
Seorang ketua Kelompok Tani yaitu bapak A.P. (65 tahun) menjelaskan
bahwa :
“ . . . kalau disini dek bisa kita hitungnya berapa tahun lagi sawah
disini ada. Abis itu rata ini semua nanti dibangun gedung-gedung perkantoran sama perumahan. Karena petani pun nanam padi bukannya banyak kali untungnya. Memang lebih bagus lagi dijual
tanahnya itu kalau memang lahannya itu punya dia kan . . .”
Menurut Lenski (dalam Sanderson, 1995) Sumber daya alam, dalam hal ini
adalah lahan pertanian berada dalam bentangan tanah yang terus akan mengalami
pengelola lahan. Desakan itu terkait dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri
apakah karena bertambahnya penduduk maka diperlukan lahan untuk pemukiman,
pertambahan lahan untuk perkantoran atau pemanfaatan lain dalam rangka
keberlangsungan hidupnya. Di samping karena ada kebutuhan masyarakat juga ada
kepentingan lain yakni dari sudut pandang para pengusaha.
Rata-rata petani hanya mengelola sawah seluas 0,76 Ha. Sistem sewa lahan di
Kampung Susuk yaitu setiap kali panen petani harus membayar 10 kaleng padi per
seribu meter tanah dan biasanya 10 kaleng padi tersebut dibayar dalam bentuk uang.
Namun demikian, adakalanya biaya sewa lahan disesuaikan dengan kondisi hasil
panen petani. Jika hasil penen petani tidak terlalu bagus (gagal panen), maka pihak
penyewa tanah memberikan keringanan kepada petani.
3.1.2. Sejarah Pertanian Kampung Susuk
Berdasarkan pembagian tanah yang telah dilakukan oleh 50 KK maka
kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan tanah menjadi lahan
persawahan (tingkat penyerapan air yang tinggi), topografinya datar dan berada di
daerah aliran sungai. Faktor-faktor yang mendukung areal Kampung Susuk menjadi
lahan persawahan diantaranya adalah bulan basah yang lebih banyak dibandingkan
bulan kering, kondisi tanah yang lembab Tahun 1950-1952 pengolahan tanah
dilakukan dengan menggunakan sistem manual (tenaga manusia) dan jenis tanaman
Tahun 1953-1968 pengolahan sawah sudah dibantu dengan irigasi (tali air)
dan membajak menggunakan tenaga hewan (sapi). Irigasi ini berasal dari sungai
Bekala yang berada di Simpang Kuala. Namun, pada tahun 1968, ditemukan adanya
ledakan yang menyebabkan pecahnya areal pembuangan. Masyarakat mengantisipasi
kebocoran tersebut dengan membuat “rocok” atau patok dan penimbunan dengan
tanah. Akan tetapi, hal ini tidak bertahan lama karena adanya peluapan air sungai dan
menghanyutkan patok dan timbunan tanah. Tahun 1970 pemerintah Kota Medan
tidak menghendaki adanya areal persawahan sehingga masyarakat mengubah sistem
pertanian menjadi sawah tadah hujan.
Masing-masing KK membentuk cetakan sawah berupa galangan-galangan
sawah dengan tujuan untuk menutupi parit-parit aliran air yang dahulu digunakan
pada areal perkebunan tembakau. Jenis padi yang digunakan adalah padi lokal yaitu
“padi anak bado” dan “padi simbo”. Petani Kampung Susuk dahulu menggunakan
sistem gotong-royong yang dinamakan “aron” dengan jumlah anggota 8-10 orang per kelompok gotong royong. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi
pengalihan fungsi lahan menjadi lahan pemukiman dan perkebunan sawit di sekitar
persawahan. Hal ini berdampak terhadap hasil pertanian sawah petani karena adanya
hama pengganggu yaitu tikus yang berasal dari areal perkebunan sawit.
Selain varietas tanaman padi, masyarakat Kampung Susuk juga pernah
mencoba menanam tanaman palawija berupa kacang hijau, kacang tanah, akcang
kedelai, dan jagung. Namun, kondisi tanah yang lembab (tingkat penyerapan air
ini disebabkan karena tingkat penyerapan air yang tinggi oleh tanah sehingga terjadi
pembusukan akar.
3.1.2. Organisasi Di Bidang Pertanian
Organisasi pertanian/Kelompok Tani pertama kali dibentuk pada tahun 1975.
Organisasi ini didirikan oleh walikota di bawah Dinas Pertanian Tingkat I dan II.
Adapun kegiatan yang dilakukan berupa kelompok tani nelayan, kelompok tani
unggas, kelompok tani hewan dan kelompok tani pangan. Pada tahun 1976 juga
dibentuk koperasi masyarakat dengan nama “Loh Ji Nawi”. Namun tidak berfungsi
dengan baik karena saham dari anggota tidak berjalan, kurangnya keterlibatan
anggota yang dilihat dari kurangnya partisipasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh
pengurus koperasi. Kegiatan dari koperasi ini meliputi penerapan tanggal pembibitan
dan penanaman secara serentak.
Petani di Kampung Susuk memiliki suatu perkumpulan yaitu Kelompok Tani
Harapan yang diketuai oleh Bapak Purba hingga tahun 1997. Kemudian kelompok
tani ini berganti nama menjadi Kelompok Tani Mulia dan diketuai oleh Ibu Sabarmin
Bangun. Namun, pada saat ini kelompok tani ini kurang berjalan dengan baik. Ketua
kelompok tani selalu aktif mendata setiap perubahan luas lahan, jenis tanaman pada
petani dan setiap kebutuhan akan pupuk yang nantinya akan dibuat dalam Rencana
Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Praktek Penyuluh Lapangan (PPL) bersama dengan Ketua Kelompok Tani
penyuluhan-penyuluhan pertanian kepada masyarakat Kampung Susuk. Adapun kegiatan PPL
adalah meninjau kegiatan bertani secara langsung ke persawahan dan membicarakan
tentang gangguan dan serangan hama serta gangguan-gangguan pertanian lainnya.
Setelah itu, PPL akan memberikan penyuluhan untuk membantu masyarakat dalam
mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Namun, kegiatan PPL saat ini tidak
semaksimal dahulu karena kegiatan penyuluhan dan peninjauan secara langsung ke
lapangan tidak lagi dilakukan.
3.2. Kehidupan Tukang Becak
Penduduk daerah Kampung Susuk mayoritas bekerja sebagai tukang becak
dan buruh tani. Dikatakan tukang becak karena bila memasuki daerah lokasi daerah
Kampung Susuk maka akan langsumg menemukan pangkalan tukang becak yang
sedang menunggu sewa di sekitar areal pinggiran jalan. Lain halnya dengan buruh
tani, karena daerah Kampung Susuk adalah daerah persawahan walaupun sawah
tersebut mereka garap dan menyewa dari orang lain, bukan milik sendiri lagi.
Banyak para pegawai swasta/negeri yang merangkap juga sebagai buruh tani.
Selain sawah, ada juga ladang yang mereka garap untuk menanam tanaman jagung,
cabai, terong, tebu, singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya. Jadi bila memasuki
wilayah daerah Kampung Susuk maka akan terlihat seakan-akan berada di daerah
pedesaan, karena masih banyak yang menggarap sawah yang merupakan salah satu
Lain halnya dengan tukang becak, masyarakat setempat dalam hal ini suku
bangsa Karo sebagai masyarakat asli di sini mempunyai aturan dalam menarik becak.
Banyaknya para pendatang dari berbagai suku bangsa yang datang dan tinggal di
daerah Kampung Susuk membuat mereka juga mencari pekerjaan yang serupa
dengan masyarakat setempat. Aturan tersebut bersifat uname law (hukum tak tertulis)
bersifat lisan, namun sanksinya sangat berat bila tidak mematuhi peraturan tersebut.
Salah seorang informan yang bernama Feri Andani Zebua (40 tahun)
menjelaskan bahwa :
“ . . . aturan yang selama ini ada mau tidak mau harus diikuti oleh
kami tukang becak dari Nias. Karena kalau kami tidak mau nurutin
aturan yang ada di sini, bisa bahaya nanti . . .”
Aturan tersebut adalah bahwa setiap suku bangsa di luar suku bangsa Karo
seperti Nias, Toba, Jawa hanya mempunyai wilayah tarikan di daerah tembok dekat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan di pintu gerbang 4 (empat) USU.
Sedangkan suku bangsa Karo boleh bebas mengambil sewa dari wilayah USU.
Termasuk wilayah yang ramai, seperti daerah Sumber.
Menurut Coombe (1995) hal tersebut merupakan fenomena penerapan hukum
dalam sebuah hubungan kemasyarakatan, dimana ia menjelaskan bahwa :
“ . . . Scholars of law and society have long argued for new paradigms
for imagining relationships between law and society, including the necessity to stop conceiving these terms as separate entities that require the expo- sition of relationship as the adequate term of address
Coombe menjelaskan bahwa secara sadar ataupun tidak masyarakat telah
membuat aturannya sendiri untuk menjaga kestabilan hubungan antar mereka.
Konsep unname law yang terjadi pada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak
tersebut merupakan perwujudannya.
Sanksi yang akan digunakan, apabila seseorang tidak menaati peraturan
tersebut mereka akan dipukuli, dicaci, diusir dari wilayah Kampung Susuk bila
mereka pendatang dan tinggal di daerah tersebut. Ada yang menarik dari peraturan
uname law disini bahwa mereka boleh menarik dari wilayah mana saja seperti
layaknya suku bangsa Karo, apabila mereka menyewa becak mesin suku bangsa
Karo. Dari aturan seperti ini terlihat adanya kekuasaan mayoritas kepada minoritas
dalam hal ini kekuasaan dalam wilayah mata pencaharian.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh informan yang bernama bapak Ginting (40
tahun) yang sudah menarik becak selama 5 tahun. Beliau mengatakan bahwa :
“ . . . aturan itu udah dibikin sejak dulu, karena kalau tidak dibikin
begitu pasti penarik becak yang orang Karo berkurang penghasilannya. Karena semakin banyak orang Nias ini yang datang narik becak. Karena kita disini sama-sama nyari nafkah istilahnya, dan kami orang Karo pun orang asli di sini, jadi kami buat lah peraturan itu untuk
menjaga biar tidak konflik sesame tukang becak ini . . .”
Aturan tersebut suka tidak suka harus ditaati dan biasanya suku bangsa Nias
mentaati hal tersebut. Mereka sadar mereka di sini hanyalah pendatang oleh karena
itu, mereka sadar akan status mereka di Kota Medan. Penghasilan yang mereka
sudah termasuk bensin dan lain sebagainya. Lain halnya dengan penghasilan yang
menyewa dari orang dan tergantung dari warna plat nomor becak sewaan tersebut.
Jika plat nomer becak warna kuning dikenakan sebesar Rp.25.000,-/hari
kepada penyewa dan Rp.20.000,-/hari bila becaknya berplat hitam. Perbedaan
tersebut dikarenakan oleh jenis warna plat yang dipakai. Bila warna kuning daerah
wilayah tarikannya bisa sampai jalan besar/raya dan sebaliknya untuk becak berplat
hitam. Jadi tidak heran bila uang setorannya berbeda karena wilayah tarikannya juga
berbeda.
Gambar 3 : Penarik Becak Di Kampung Susuk
Sumber : Peneliti
Aturan-aturan tersebut suku bangsa Nias taati sebagai pola adaptasi mereka
menarik becak suku bangsa Nias lebih akrab dengan suku bangsa Batak Toba yang
lebih sepaham dan asyik diajak untuk kerja sama. Adanya rasa kebersamaan mereka
dalam menarik becak, menunggu sewa dan lain sebagainya.
Bila dibandingkan dengan suku bangsa Karo bisa dihitung dengan jari
kedekatan antara suku bangsa Karo dengan suku bangsa Nias. Adanya masalah
sejarah hidup antara suku bangsa Karo dengan suku bangsa Nias yang membuat
mereka tidak bebas untuk berinteraksi maupun dalam hal kerjasama. Itu diakibatkan
oleh adanya kekuasaan dalam berinteraksi, jenis mata pencaharian dan lain
sebagainya.
Kekuasaan dalam hal mata pencaharian memang sangat menonjol sekali di
daerah Kampung Susuk. Suku bangsa Nias memilih mata pencaharian tukang becak
diakibatkan sempit atau tertutupnya akses mereka untuk dapat memiilih mata
pencaharian di bidang informal lainnya. Dalam mata pencaharian selain para suami,
sebagian isteri juga ikut membantu dan anak-anakpun juga mempunyai andil besar
dalam membantu perekonomian dalam keluarga.
Banyak para anak-anak suku bangsa Nias membantu para orang tuanya
dengan cara mengamen di sekitar wilayah kampus USU. Selain daripada mengamen
mereka juga ada yang berprofesi sebagai penyemir sepatu dan lain-lainnya.
3.3. Perkembangan Usaha Kos-Kosan di Kampung Susuk
Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan setiap
individu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan
bisnis, tiap individu dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk berbisnis
demi memperoleh keuntungan, termasuk memanfaatkan rumah menjadi lahan bisnis,
seperti rumah kost atau yang disebut juga Indekost untuk memenuhi kebutuhan
tempat tinggal sementara bagi konsumennya.
Kost atau indekost adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau
tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode
tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Kata "kost" sebenarnya adalah turunan
dari frasa bahasa Belanda "In de kost". Definisi "In de kost" sebenarnya adalah
"makan di dalam" namun bila frasa tersebut dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti
"tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.
(id.wikipedia.org/wiki/Indekost)
Menurut kamus besar bahasa indonesia, indekos adalah tinggal di rumah
orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok.
Usaha rumah kost umumnya banyak ditemukan di daerah yang berdekatan dengan
pusat kegiatan rutinitas, salah satunya di lingkungan Kampung Susuk sekitar
Universitas Sumatera Utara (USU). Karena rumah kost adalah kebutuhan tersendiri
bagi mahasiswa USU, maupun mahasiswa universitas lain, bahkan
karyawan-karyawan yang bekerja di daerah berdekatan dengan lokasi tersebut. Hal ini membuat
permintaan konsumen meningkat sehingga pertumbuhan jumlah usaha rumah kost di
Mahasiswa banyak yang memilih menjadi anak kos disebabkan oleh jarak
yang begitu jauh antara keberadaan rumah tempat tinggalnya dengan
universitas/kampus tempat dia menempuh pendidikan. Kemudian ada juga faktor
keinginan untuk mandiri, rasa ingin bebas tanpa terikat dengan keluarga di rumahnya
membuat mahasiswa memutuskan untuk hidup menjadi anak kos. Kebanyakan
mahasiswa yang menjadi anak kos ini berasal dari luar kota dan luar daerah.
Hal itulah yang membuat keberadaan anak kos semakin menjamur, terutama
pada kawasan disekitar universitas/kampus. Pada kawasan di lingkungan universitas
ini lah banyak dijumpai tempat-tempat kos seperti rumah yang disewakan atau
dikontrakkan, kamar-kamar kos dan ada juga keluarga yang menyisakan sebagian
dari ruang rumahnya untuk disewakan pada anak kos. Mahasiswa pun memiliki
banyak pilihan untuk menempati tempat kos sesuai keinginan dan kemampuan
ekonomi mereka.
Seorang informan peneliti yang merupakan pemilik kos-kosan di Kampung
Susuk yang bernama ibu Heni (34 tahun) menjelaskan bahwa :
“ . . . di Kampung Susuk ini sudah hampir semuanya jadi rumah kos
atau pun tempat usaha lainnya. Karena kan masyarakat melihat kalau usaha kos-kosan ini sangat menjanjikan, karena ada USU di samping ini. Jadi otomatis banyak mahasiswa rantau yang butuh tempat tinggal, jadi penduduk sini pun berlomba-lomba lah membangun tempat
kos-kosan . . .”
Pada awalnya, usaha rumah kost dipandang sebagai usaha sampingan dimana
seiring perkembangan zaman dan permintaan yang meningkat, usaha ini kebanyakan
menjadi rumah yang khusus dibangun seluruhnya untuk dijadikan kamar-kamar yang
nantinya untuk disewakan. Sehingga membuat usaha ini menjadi lebih memiliki
prospek penghasilan yang cukup tinggi.
Pengelolaan yang baik pada usaha ini dapat menciptakan suatu usaha bisnis
yang berprofitabilitas cukup tinggi, untuk itu perlu diadakannya suatu pengembangan
strategi bisnis demi terciptanya hal tersebut. Karena dengan pengelolaan yang baik
pada usaha rumah kost ini, dapat meningkatkan pendapatan usaha tersebut.
Berdasarkan pengamatan, penulis mencoba untuk mengelompokkan suatu klasifikasi
dari usaha rumah kost yang ada di daerah Padang Bulan. Ada pun tujuan penulis
dalam pengelompokkan tersebut untuk dapat menganalisa jenis-jenis dari usaha
rumah kost yang ada di sekitar daerah tersebut.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam memilih
kost-kostan adalah desain bangunan, harga sewa, lokasi, fasilias, dan lainnya. Namun
faktor yang paling menonjol pada rumah kost yang ada di Kampung Susuk adalah
harga sewa yang ditawarkan, diikuti dengan fasilitas yang merupakan faktor yang
juga berperan dalam mengelompokkan rumah kost ini. Sehingga faktor-faktor ini
digunakan untuk mengklasifikasikan usaha rumah kost, diklasifikasikan sebagai
Tabel 11 : Klasifikasi Harga Sewa Rumah Kos
Klasifikasi Usaha rumah kost di Kampung Susuk No. Type Harga Sewa/Bulan Fasilitas Secara Umum
1. Kelas A >Rp.800.000 TV, Meja, Kursi, Lemari, Kasur, AC,
3. Kelas C <Rp.400.000 WC, Kamar Mandi Bersama
Sumber : Peneliti
Sesuai dengan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa Kelas A merupakan
usaha kost yang harga sewanya tertinggi yaitu lebih dari Rp.800.000/bulan, harga
tersebut diikuti dengan fasilitas yg disediakan seperti; TV, meja, kursi, lemari, kasur,
AC, kamar mandi didalam kamar yang disewakan. dan memiliki sarana umum,
seperti; lapangan parkir, CCTV, WiFi, satpam, cleaning service, dan lainnya di dalam
usaha rumah kostnya. Kemudian pada Kelas B, harga sewa yang ditawarkan lebih
rendah dari Kelas A. Sedangkan pada Kelas C, memiliki harga sewa paling rendah
yaitu kurang dari Rp. 400.000/bulan, diikuti dengan menyediakan kamar kosong
tanpa fasilitas kamar dan memiliki sarana umum berupa WC/kamar mandi umum.
Harga-harga sewa yang tertera pada tiap Kelas pada tabel di atas
diperhitungkan dalam jangka waktu bulanan. Adapun klasifikasi ini dipertimbangkan
kecamatan Medan Selayang, Medan. Tetapi pada kenyataannya cukup banyak
pengusaha rumah kost yang berada di daerah sekitar USU kurang memperdulikan
masalah pengelolaan yang lebih lanjut untuk mengembangkan usahanya tersebut,
sehingga membuat usahanya tertinggal dari pesaingnya.
Sama halnya dalam kasus ini, beberapa usaha rumah kost yang berada di
daerah kelurahan Padang Bulan. Banyak dari mereka yang telah cukup lama bergelut
dibidang usaha ini, namun tidak melakukan pengembangan terhadap usahanya
tersebut. Sehingga usahanya ini memperoleh pendapatan yang sama pada tiap
periodenya, dan melewatkan kesempatan untuk menigkatkan pendapatan dari usaha
yang berprospek cukup tinggi ini. Oleh karena itu, banyak rumah kost yang berada di
daerah kelurahan Padang Bulan masih berada dalam Kelas C.
Di sisi lain telah muncul beberapa usaha rumah kost besar yang didirikan oleh
pemilik modal yang besar. Keberadaan rumah kost baru, menjadi pesaing dalam
mendapatkan sewa bagi para pengusaha rumah kost kecil yang berada di daerah
tersebut. Sehingga dengan begitu usaha rumah kost di Kampung Susuk yang masih
berada di Kelas C perlu mengembangkan strategi bisnis, untuk meningkatkan daya
saingnya. Sehingga untuk meningkatkannya, perlu dilakukan pengembangan usaha
pada masing-masing usaha rumah kost Kelas C tersebut.
Namun, jika dalam pengembangan atau pun pengelolaan usaha tersebut tidak
dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi usahanya di masa yang akan
datang. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengembangan juga pada strategi
Mahasiswa yang memilih untuk bertempat tinggal atau menyewa kamar atau rumah
di daerah Kampung Susuk berdekatan dengan kampus dan lebih mudah dijangkau.
Alasan pemilihan tempat kos bagi kebanyakan orang disekitar wilayah
kampus adalah karena masalah biaya, ongkos dan jarak. Jarak yang dekat antara
tempat kampus dengan kampus tentu menghemat biaya dan hemat ongkos
transportasi. Ada juga mahasiswa yang tinggal di kos-kosan karena tempat tinggalnya
yang sangat berjauhan dari kampus sehingga mengharuskan mereka untuk tinggal di
kos-kosan. Dalam hal ini orang tua mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya
kepada anak-anaknya yang menginginkan untuk tinggal di tempat kos, akan tetapi
sering kepercayaan yang diberikan oleh orang tua tersebut telah disalahgunakan oleh
mereka (mahasiswa).
Namun bagi mahasiswa yang asalnya dari luar kota atau kampung yang
memilih tinggal di tempat kos cenderung lebih mudah terpengaruh dengan gaya
hidup masyarakat kota, misalnya saja dari cara berpakaian orang kota yang cenderung
mengenakan busana-busana seksi dan memiliki alat-alat tekhnologi canggih dan
modern sehingga membuat kebiasaannya pun ikut berubah termasuk pola pikir
mahasiswa tersebut. Dalam kesehari-hariannya mahasiswa yang tinggal di kos,
setelah selesai kuliah dari kampus mereka tidak langsung pulang ke rumah melainkan
mereka pergi menyempatkan diri untuk bergabung bersama teman-temannya di suatu
tempat seperti nongkrong di kantin dan diluar kampus misalnya di mall, café-café dan
Mereka justru lebih senang menghabiskan waktunya untuk
berkumpul-kumpul di kos temannya sendiri. Hal ini yang sering peneliti perhatikan
kesehari-harian anak kos yang ada di Kampung Susuk. Lingkungan merupakan situasi atau
kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap
perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Karena dari sinilah
kepribadian individu dapat terbentuk, dan mahasiswa dapat menentukan mana
lingkungan yang baik sebagai tempat bergaul atau bersosialisasi dengan masyarakat,
sehingga mahasiswa mempunyai pegangan agar tidak terbawa arus kedalam
pergaulan bebas (Abu Ahmadi, 1979 : 122 ).
3.4. Banyaknya Usaha Laundry Dalam Melihat Peluang Bisnis Di Kampung Susuk
Kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap gaya hidup
masyarakat sekarang terutama di kota besar yang mana masyarakat
menginginkan agar semua hal yang dilakukan serba praktis dan cepat. Sama halnya
dengan mahasiswa yang disibukkan dengan kegiatan perkuliahan mereka yang
menuntut mereka terkadang tidak dapat membagi waktu antara pekerjaan kampus
dengan pekerjaan rumah. Perubahan gaya hidup yang demikian menyebabkan
adanya tuntutan kepraktisan dalam menjawab kebutuhan pribadi mereka, misalnya
dalam hal mencuci pakaian dan menyetrika.
Dalam hal ini dengan adanya berbagai macam masalah tersebut, maka
perlahan-lahan mulai berkembanglah suatu pelayanan jasa yang memberikan
Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau
rumah kontrakan, dimana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa
melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Dalam penelitian ini usaha laundry ini
menjamur di daerah Kampung Susuk.
Gambar 4 : Salah Satu Tempat Usaha Laundry di Kampung Susuk
Sumber : Peneliti
Keberadaan jasa laundry bagi masyarakat dinamis di perkotaan terutama di
daerah kontrakan atau kos-kosan sudah merupakan gaya hidup tersendiri, bukan
karena malas tetapi mereka memprioritaskan mana yang bisa didelegasikan dan mana
yang bisa mereka lakukan sendiri karena faktor tenaga, waktu dan tuntutan hidup.
Kota Medan khususnya kawasan Universitas Sumatera utara banyak sekali dihuni
memiliki waktu yang cukup untuk mencuci pakaian mereka, ditambah lagi dengan
kondisi cuaca saat ini yang sering hujan, mengakibatkan pakaian lebih mudah
menjadi kotor sehingga mencuci pakaian secara manual akan sulit menjadi kering
karena tidak adanya sinar matahari.
Melihat fenomena ini maka banyak pengusaha mulai melirik usaha laundry
karena diharapkan dapat memberikan keuntungan serta tingkat pengembalian modal
yang tinggi. Maka tidak salah apabila laudry merupakan salah satu bisnis jasa yang
pasti akan terus berkembang. Tidak hanya di Medan, di kota-kota besar lainnya pun,
pasarnya cukup menggiurkan. Di Jogjakarta misalnya yang tercatat memiliki
300.000 mahasiswa dan pelajar, konon bisa menghasilkan perputaran omset tidak
kurang dari Rp 1,5 miliar per bulan dan ini hanya dinikmati 300-an laundry.
Secara garis besar, saat ini berkembang dua jenis binatu berdasarkan model
penghitungan biaya. Hal yang terlebih dahulu ada yakni berdasarkan jumlah pakaian
per potong, kemudian menyusul model laundry dengan mengitung berat cucian atau
laundry kiloan yang belakangan mulai marak. Usaha laundry sebagai alternative
mencuci bagi mahasiswa, membuat bisnis ini cukup menjanjikan.
Hampir tiap tempat di daerah Medan khususnya sekitar kampus Universitas
Sumatera Utara banyak berdiri usaha-usaha mandiri jasa laundry. Karena teramat
banyak nya bisnis ini, hingga konsumen pun di hadirkan dengan banyak pilihan.
Apalagi konsumen dari kalangan mahasiwa yang tentu nya mencari harga jasa yang
terjangkau bagi kantongnya. Pilihan-pilihan yang ditawarkan antara lain, Misalnya
hingga kebersihan nya. Banyak laundry yang telah ada sekarang ini, menggunakan
cuci mesin. Hal ini di karenakan lebih efisien, lebih cepat, dan tidak memakan banyak
tenaga.
Usaha laundry di daerah Universitas Sumatera Utara terutama di Kampung
Susuk sangat menjanjikan, namun tidak jarang para pengusaha laundry juga
menghadapi hambatan dalam menjalani usaha mereka. Seperti banyaknya kompetitor
atau pesaing yang sudah membuka usaha serupa serta waktu yang lebih cepat dalam
pengerjaan yang diminta oleh konsumen dan lain sebagainya. Dari gambaran di atas,
dapat kita lihat bahwa trend mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya
hidup masyarakat, selain dapat meringankan pekerjaan cuci dan setrika, usaha
laundry juga memberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau.
3.5. Warkop (Warung Kopi) Sebagai Wadah Pergaulan Masyarakat Kampung Susuk
Warung kopi bagi masyarakat di Medan khususnya di Kampung Susuk
merupakan tempat dimana masyarakat berkumpul untuk sekedar melepas lelah,
tempat mengawali hari sebelum melaksanakan aktivitas rutin, atau menghabiskan
waktu yang dianggap bermanfaat dibandingkan melakukan kegiatan seperti tidur,
jalan-jalan tanpa tujuan dan sebagainya. Kebiasaan masyarakat Kampung Susuk yang
sering berada di warung kopi menimbulkan opini negatif dari kebanyakan orang ada
di Kampung Susuk khususnya kaum perempuan dalam hal ini mahasiswi yang
Dalam hal ini peneliti mencoba untuk datang langsung dan mengamati sambil
menghabiskan waktu di warung kopi melihat bahwa aktifitas di warung kopi
merupakan sebuah dinamika yang menjelaskan bahwa disana telah terbentuk berbagai
opini publik, salah satunya adalah aktifitas warung kopi terhadap masyarakat di
Kampung Susuk. Warung kopi merujuk kepada sebuah organisasi yang secara pokok
menyediakan kopi atau minuman panas lainnya. Dari suatu pengamatan langsung,
warung kopi banyak memberikan layanan sebagai pusat-pusat interaksi sosial,
warung kopi dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkumpul,
berbicara, bermain, menghibur satu sama lain, atau membuang waktu, baik secara
individu atau dalam kelompok kecil. Bahkan warung kopi menjadi tempat tidur yang
nyaman bagi pengunjungnya. Ngopi adalah ungkapan terhadap orang yang ingin
menikmati kopi atau minuman lainnya atau sekedar duduk-duduk diwarung kopi dan
mengobrol sesama pengunjung warung kopi.
Melihat kejadian yang ada di warung kopi kini muncul menjadi sebuah
identitas yang melekat bagi para penikmatnya, tidak hanya tingkat kenikmatan
semata, gaya hidup dan gaya yang khas, tetapi kini fungsinya semakin mendapatkan
hati masyarakat. Selain terjangkau harganya, nilai yang nyata di warung kopi juga
menjadi hiburan yang tak tergantikan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya di
Simalingkar saja warung kopi dijadikan sebagai wadah atau tempat yang nyaman
selain rumah untuk berkomunikasi, bersenang-senang, santai ataupun beristirahat
Di lain daerah di kota Medan juga memiliki penilaian tersendiri terhadap
warung kopi bahkan di daerah Indonesia lainnya. Warung kopi menjadi tanda yang
mengukuhkan keberadaan baru bagi masyarakat, melalui bertemunya beragam orang,
suku, agama, lembaga, status sosial dan bahkan identitas yang multikultur. Dalam
pandangan yang lebih luas, warung kopi juga bagian dari subkultur yang
mempertemukan berbagai budaya dan identitas baru. Tetapi ngopi juga bukan sekadar
soal keakraban, didalamnya kerap terjadi pertukaran informasi, wacana, dan
pengembangan wawasan, bahkan hiburan sekalipun.
Pada awalnya ngopi “hanyalah aktifitas mengisi waktu luang dan tempat
untuk istirahat dari kepenatan”. Namun, perkembangannya kini warung kopi menjadi sebuah tempat yang penting untuk menghabiskan waktu luang maupun waktu
beraktifitas sehari-hari. Dari berbagai suku yang berbeda warung kopi memiliki peran
yang benar-benar memberikan ruang untuk berkreasi, berdiskusi, hiburan walaupun
muncul konflik–konflik kecil didalamnya. Tetapi dalam beberapa hal, warung kopi juga didirikan dengan latar belakang yang berbeda.
Lebih jauh lagi, aktifitas warung kopi ini, membentuk kultur dan kebiasaan
baru dalam berbagai sektor kehidupan, misalnya ekonomi dan sosial. Bagi sebagian
pecinta kopi, menikmati secangkir kopi mungkin hal yang biasa dilakukan di waktu
senggang dan bisa dilakukan dimana saja. Namun bagi kalangan tertentu menikmati
kopi bukan hanya bagaimana merasakan sensasi manis dan pahit, tetapi bagaimana
muatan yang menyertai aktifitas itulah yang akan berdampak lebih luas. Misalnya
dengan relasi bisnisnya. Begitu juga dengan mahasiswa, menikmati secangkir kopi
hanya bermakna jika dilakukan di warung kopi yang diselingi dengan diskusi kecil.
Orang tua sekalipun menjadikan warung kopi salah satu daya tarik yang tidak lepas
dari kehidupan sehari-hari bahkan warung kopi menjadi rumah kedua bagi mereka.
Penikmat kopi juga beragam, mulai dari buruh bangunan hingga para pejabat.
Tidak ada sekat dalam hal siapa peminat kopi. Ini membuktikan bahwa warung kopi
mempunyai potensi kultural yang dapat menggiring masyarakat ke arah pembauran
sosial. Ini tidak lepas dari salah satu manfaat warung kopi yaitu sebagai tempat
menemukan ide dan gagasan. Bahkan, bagi para penikmat kopi, warung kopi adalah
sumber informasi dan inspirasi.
Bagi pecinta kopi, menikmati kopi dengan racikan sendiri di rumah atau di
tempat kerja akan terasa berbeda ketika mereka menikmati kopi di warung kopi.
Entah karena racikannya atau suasananya, kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan, faktor
kejadian ini adalah bagaimana situasi dan kondisi dalam menikmati kopi
mempengaruhi rasa dalam ngopi itu sendiri. Dan yang aneh lagi adalah
masing-masing warung kopi memiliki kekhasan rasa tersendiri yang tidak bisa ditemukan di
tempat lain.
Berangkat dari realitas itulah, kebiasaan ngopi bagi masyarakat Indonesia
bukanlah menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan
tetapi, lebih dari itu ngopi menjadi sebuah gaya hidup (life style) masyarakat.
Kebiasaan masyarakat yang seiring waktu telah berubah menjadi kebutuhan
masyarakat Indonesia. Apalagi interaksi sosial yang terjadi di warung kopi membuat
suasana menjadi hidup dan malahan membuat betah meskipun terjadi konflik kecil
yang mewarnai aktifitas yang ada di warung kopi . Dari obrolan kecil hingga obrolan
yang memanas kerap terjadi di warung kopi . Permainan kartu dan catur menjadi
hiburan tersendiri bagi penikmat warung kopi untuk mengisi kekosongan. Bahkan
tidak jarang orang yang baru pulang kerja menyempatkan waktu nya terlebih dahulu
di warung kopi hanya sekedar minum kopi dan ngobrol sesama pengunjung.
Hal yang tak kalah menariknya yaitu keberadaan warung kopi secara tidak
langsung mempunyai efek terhadap kegiatan masyarakat di suatu tempat, misalnya
dalam hal etos kerja . Memang bila di kaji lebih jauh, tinggi rendahnya etos kerja
masyarakat ditentukan oleh pribadi demi pribadi dari masyarakat tersebut. Namun,
jika kita mau jujur, keberadaaan warung kopi bagi sebahagian masyarakat akan
berakibat turunnya etos kerja. Selain sisi negatifnya, warung kopi juga mempunyai
sisi positif. Banyak contoh yang bisa diurutkan sebagai sisi positif warung kopi.
Program pemerintah, obrolan politik, obrolan ekonomi, dan sosial dijadikan bahan
obrolan dan perdebatan di warung kopi .
Warung kopi pada dasarnya adalah tempat dimana penjual minuman kopi dan
pembeli minuman kopi ataupun sesama pembeli minuman kopi bertemu, bubuk kopi
dan gula telah diseduh dan dihidangkan di meja, maka warung kopi memperlihatkan
peranan dan fungsinya, bukan hanya sekedar mendapatkan segelas kopi yang
media interaksi antara sesama pengunjung warung kopi ataupun dengan penjual
minuman kopi .
Di pasar atau di toko, penjual dan pembeli ataupun sesama pembeli saling
bertemu. Tapi pertemuan dan interaksi berlangsung dalam waktu relatif singkat.
Setelah semua selesai belanja dipesan dan dibayar, maka berakhirlah interaksi
mereka. Tidak lah demikian halnya dengan di warung kopi, yang antara pembeli dan
penjual dan antara sesama pembeli terlibat komunikasi yang relatif panjang, dan
bahkan ada kemungkinan perbincangan tersebut terulang lagi untuk esok harinya.
Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penjual dan pembeli dan
antara pembeli dan pembeli membuat warung kopi mempunyai keunikan tersendiri.
Warung kopi dengan segala kesederhanaannya telah memperlihatkan peranan dan
fungsinya sebagai sarana interkasi sosial yang sangat potensial. Fungsi sosial warung
kopi sebagai pusat kegiatan ekonomi dapat dilihat dalam perubahan-perubahan yang
terjadi dibidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Warung kopi dapat juga
dikatakan sebagai pusat kebudayaan dalam lingkup yang sederhana, dalam hal ini
dapat dilihat pada perubahan-perubahan sosial budaya sebagai akibat dari pembaruan
dan pembauran. Dengan demikian terlihat bahwa warung kopi bukan hanya tempat
berjual beli semata, namun juga mempunyai fungsi lain bagi masyarakat yang
bersangkutan. Alasan-alasan itu lah menjadi daya tarik warung kopi yang begitu
mempesona bagi penikmatnya. Dari siang hingga malam warung kopi membuat
Istilah ruang publik (public space) pernah dilontarkan Lynch Ruang publik
diartikan sebagai ruang bagi diskusi kritis yang terbuka bagi semua orang. Pada ruang
publik ini, warga privat (private person) berkumpul untuk membentuk sebuah publik
dimana nalar publik ini akan diarahkan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan negara. Ruang publik mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan
berkumpul, pers bebas, dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik
dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, ruang publik dalam hal ini terdiri dari
media informasi seperti surat kabar dan jurnal. Juga termasuk dalam ruang publik
adalah tempat minum dan warung kopi, balai pertemuan, serta ruang publik lain
dimana diskusi sosio-politik berlangsung.
Dengan menyebutkan bahwa ruang publik adalah nodes dan landmark yang
menjadi alat navigasi didalam kota . Gagasan tentang ruang publik kemudian
berkembang secara khusus seiring dengan munculnya kekuatan civil society. Dalam
hal ini filsuf Jerman, Jurgen Habermas, dipandang sebagai penggagas munculnya ide
ruang publik. Jurgen Habermas memperkenalkan gagasan ruang publik pertama kali
melalui bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere:
an Inquire Into a Category of Bourjuis Society yang diterbitkan sekitar tahun 1989.
Menurut (Koentjaraningrat 1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia
yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu
dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
Dalam menganalisa proses proses interaksi antara individu dalam masyarakat,
individu juga tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya berhadapan
muka,namun juga bisa menggunakan alat kebudayaan seperti tulisan,buku ,surat
kabar ataupun telepon. Sedangkan komunikasi muncul setelah kontak terjadi
(Koentjaraningrat, 2002 : 162).
Sejalan dengan itu Koentjaraningrat memperjelas bahwa (dalam Sartini
2009:30) nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran
sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat
mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan
dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang
mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara, alat, dan tujuan pembuatan
yang tersedia.
Hal inilah yang peneliti lihat bahwa warung kopi disinyalir sebagai fenomena
kultural yang hidup di masyarakat. Fenomena ini sesuai dengan paham budaya yang
dikemukakan oleh Spredley (1997) Kebudayaan yang merupakan pengetahuan yang
diperoleh dan digunakan manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dalam
menghadapi dunianya. Di warung kopi merupakan tempat bagi mereka yang
BAB IV
PERKEMBANGAN KAMPUNG SUSUK
4.1. Aspek-Aspek Yang Mendukung Perkembangan Kampung Susuk
Kampung Susuk sebagai daerah yang berada di Kelurahan Tanjung Sari
merupakan salah satu daerah yang paling padat jumlah penduduknya di Kecamatan
Medan Baru. Perkembangan Kampung Susuk telah mencapai beberapa sektor yakni
ekonomi, kependudukan, pendidikan dan sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari
beberapa aspek yang mendorongnya. Berikut merupakan beberapa aspek yang
mendukung perkembangan Kampung Susuk Tersebut.
4.1.1. Munculnya Kampus USU Dan Pengaruhnya Terhadap Kampung Susuk
Kampus USU merupakan sebuah Universitas Negeri yang berada persis di
samping wilayah Kampung Susuk. Berdirinya Kampus USU di samping Kampung
Susuk secara drastis menjadi semacam pelecut berkembangnya wilayah Kampung
Susuk baik dari segi infrastruktur, kependudukan maupun ekonomi. Sejarah
Universitas Sumatera Utara (USU) dimulai dengan berdirinya Yayasan Universitas
Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. Pendirian yayasan ini dipelopori oleh
Gubernur Sumatera Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Utara
Pada zaman pendudukan Jepang, beberapa orang terkemuka di Kota Medan
termasuk Dr. Pirngadi dan Dr. T. Mansoer membuat rancangan perguruan tinggi
Kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Dr. Mohd.
Djamil di Bukit Tinggi sebagai ketua panitia. Setelah pemulihan kedaulatan akibat
clash pada tahun 1947, Gubernur Abdul Hakim mengambil inisiatif menganjurkan
kepada rakyat di seluruh Sumatera Utara mengumpulkan uang untuk pendirian
sebuah universitas di daerah ini. Pada tanggal 31 Desember 1951 dibentuk panitia
persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Dr. Soemarsono yang
anggotanya terdiri dari Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro dan sekretaris Mr. Djaidin
Purba.
Sebagai hasil kerjasama dan bantuan moril dan material dari seluruh
masyarakat Sumatera Utara yang pada waktu itu meliputi juga Daerah Istimewa
Aceh, pada tanggal 20 Agustus 1952 berhasil didirikan Fakultas Kedokteran di Jalan
Seram dengandua puluh tujuh orang mahasiswa diantaranya dua orang wanita.
Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
(1954), Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan (1956),dan Fakultas Pertanian
(1956). Pada tanggal 20 November 1957, USU diresmikan oleh Presiden Republik
Indonesia Dr. Ir. Soekarno menjadi universitas negeri yang ketujuh di Indonesia.
Pada tahun 1959, dibuka Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di
Kutaradja (Banda Aceh) yang diresmikan secara meriah oleh Presiden R.I. kemudian
disusul berdirinya Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (1960) di Banda
fakultas di Banda Aceh. Selanjutnya menyusul berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi
(1961), Fakultas Sastra (1965), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(1965),Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1982), Sekolah Pascasarjana
(1992), Fakultas Kesehatan Masyarakat (1993), Fakultas Farmasi (2006), dan
Fakultas Psikologi (2007), serta Fakultas Keperawatan (2009).
Pada tahun 2003, USU berubah status dari suatu Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) menjadi suatu perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Perubahan status USU dari PTN menjadi BHMN merupakan yang kelima di
Indonesia. Sebelumnya telah berubah status UI, UGM, ITB dan IPB pada tahun 2000.
Setelah USU disusul perubahan status UPI (2004) dan UNAIR (2006).
Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, sebuah area yang hijau dan rindang
seluas 120 ha yang terletak di tengah Kota Medan. Zona akademik seluas 90 ha
menampung hampir seluruh kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa. Dari
jumlah populasi mahasiswa, karyawan dan dosen ditambah dengan sejarah panjang
yang telah dilalui oleh USU tentunya cukup memberikan indikasi bahwa kondisi
tersebut seyogyanya akan mempunyai dampak terhadap proses perkembangan
wilayah di sekitarnya seperti Kampung Susuk. Sejak didirikan 4 Juni 1952 sampai
dengan sekarang, USU adalah merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang
menjadi favorit para calon mahasiswa di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan
sekitarnya.
Selain itu kehadiran suatu institusi atau suatu lembaga pendidikan seperti
yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Susuk selain meningkatnya kualitas SDM,
tapi juga adanya multiplier efect dari keberadaan USU terhadap masyarakat
sekitarnya. Bentuk multiplier efect keberadaan USU terhadap masyarakat sekitar
dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Susuk umumnya dan
masyarakat yang berdomisili di sekitar USU pada khususnya. Dengan melihat kondisi
eksisting wilayah di sekitar kampus USU menunjukkan bahwa beberapa kegiatan
ekonomi yang berkembang antara lain adalah unit-unit usaha percetakan, jasa
perumahan atau rumah-rumah kos, rumah makan serta jasa-jasa lain.
Hal tersebut pula lah yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di Kampung
Susuk. Warga masyarakat yang tinggal berdekatan dengan wilayah Kampus USU
mengalami dinamika sosial. Dalam sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai
keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu.
Keterkaitan antara dinamika sosial dengan interaksi sosial adalah interaksi
mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat yang
akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara progresif
atau pun retrogresif (Soekanto : 2003)
Pembangunan pada suatu wilayah dapat mendatangkan dampak berupa
manfaat yang positif atau juga berupa kemudharatan (dampak negatife), terutama
kepada masyarakat yang tinggal di dekat sekitar kegiatan lokasi pembangunan
sebagai penerima akibat (dampak.) Dalam hal ini komunitas lokal harus
mencari/mendapat peluang agar terjadi penyesuaian terhadap perubahan karena
nafkah dari lahan sawahnya selama bertahun-tahun tentu saja harus mencari
pekerjaan lainnya akibat semakin menyempitnya lahan pertanian.
4.1.2. Pertemuan Penduduk Masyarakat Asli Dengan Para Pendatang
Kampung Susuk merupakan salah satu wilayah yang paling padat karena
ditinggali oleh para mahasiswa dari berbagai daerah yang kuliah di kampus USU.
Jaraknya yang sangat dekat dengan kampus USU membuat banyak mahasiswa yang
tinggal di daerah kos-kosan yang ada di Kampung Susuk.
Banyaknya mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia
membuat banyak macam suku berbaur dalam kehidupan di Kampung Susuk. Suku
Karo menjadi tuan rumah atau diklaim sebagai suku asli yang sudah lama mendiami
Kampung Susuk tersebut. Kemudian disusul dengan Batak Toba, Nias, Jawa dan
suku lainnya.
Dalam kesehariannya mereka tidak membatasi interaksinya dengan suku
lainnya. Bahkan untuk mahasiswa pendatang yang tinggal di Kampung Susuk tidak
akan lengkap hidupnya saat kembali ke kampung halamannya tanpa menguasai
bahasa Karo. Hal tersebut timbul karena dalam pergaulan sehari-hari mahasiswa dari
Karo selalu memakai bahasa Karo dalam berinteraksi dengan teman sesama suku
Karo nya. Atau terkadang juga mengeluarkan istilah-istilah dalam bahasa Karo ketika
berinteraksi dengan suku lainnya.
Young dan Raymond W. Mack (dalam Soekanto : 2003) mendefenisikan
hubungan-hubungan antar individu, baik antara individu dengan kelompok, maupun
antara kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi akan terjadi
perubahan-perubahan yang memungkinkan terbentuknya hal-hal baru sehingga dinamika
masyarakat menjadi hidup dan dinamis. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan
dasar terbentuknya dinamika sosial yang ada di masyarakat.
Bahasa yang kedengarannya unik di telinga suku pendatang membuat mereka
mencoba untuk belajar bahasa Karo. Begitu juga sebaliknya, masyarakat dan
mahasiswa Karo juga menyerap berbagai macam pengetahuan dari suku lainnya
untuk mereka pelajari dan terapkan. Hal yang menarik adalah bahwa ungkapan atau
istilah yang paling sering dihafal oleh para masyarakat dari suku lainnya adalah
istilah atau kata-kata kasar dari suku yang memiliki bahasa tersebut.
Satu hal yang menarik juga adalah kondisi Kampung Susuk yang begitu padat
ternyata tidak dibarengi dengan penataan dan kebersihan lingkungan yang memadai.
Sehingga harga kos di Kampung Susuk menjadi hampir sama dengan kos yang ada di
tempat lain yang lebih jauh dari kampus USU. Lingkungan yang kurang bersih
membuat Kampung Susuk menerima label sebagai tempat kos yang tidak disukai
oleh mahasiswa-mahasiswa kaya ataupun perempuan.
Biasanya mahasiswi akan lebih memilih tinggal di daerah luar Kampung
Susuk seperti daerah Pembangunan, Sei Padang dan Sembada sebagai tempat tinggal
sementara. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tersebut lebih bersih dan terjamin
keamanannya. Orang Karo sebagai warga asli juga tidak nyaman dengan keadaan
perbuatan dari mahasiswa-mahasiswa pendatang yang tiggal di Kampung Susuk yang
tidak mau menjaga lingkungannya.
4.1.3. Alih Fungsi Lahan Dari Lahan Pertanian Menjadi Gedung-Gedung
Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai
konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari
fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang berdampak
negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan
dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh
faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan
penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu
kehidupan yang lebih baik.
Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman
yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan dan juga lingkungan. Seperti
yang diketahui daerah Kampung Susuk merupakan daerah langganan bajir di musim
hujan. Fungsi sawah di Kampung Susuk bukan hanya untuk keperluan pangan saja,
tetapi juga sebagai daerah resapan air. Intensitas alih fungsi lahan di Kampung Susuk
masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralihfungsi tersebut
justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi – sangat tinggi. Lahan-lahan
tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di
kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang
Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa beberapa faktor yang memicu alih
fungsi lahan di Kampung Susuk diantaranya : (1) pembangunan kegiatan non
pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri
lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan tanah
kering; (2) akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan
produk padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada
daerah tanah kering; (3) daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah
konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah
tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan.
Terutama daerah persawahan masih sangat dekat dengan lingkungan kampus USU
sehingga memancing para pengembang untuk membangun gedung-gedung penunjang
pendidikan.
Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan
ataupun tidak langsung yakni oleh perusahaan PT IRA (Bumi Mansur) sebagai
pemilik sebagian besar sawah yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli
lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika
akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain
yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi (misalnya untuk
pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya) atau untuk
pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah,
atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan (Murniningtyas,
Secara ekonomi alih fungsi lahan yang dilakukan petani baik melalui transaksi
penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non padi merupakan
keputusan yang rasional. Sebab dengan keputusan tersebut petani berekspektasi
pendapatan totalnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan
meningkat (Ilham dkk, 2003). Dorongan-dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan
pertanian ke non pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada juga yang
secara langsung atau tidak langsung dihasilkan oleh proses kebijaksanaan pemerintah.
Dalam proses alih fungsi lahan, telah terjadi asimetris informasi harga tanah,
sehingga sistem harga tidak mengandung semua informasi yang diperlukan untuk
mendasari suatu keputusan transaksi. Kegagalan mekanisme pasar dalam
mengalokasikan lahan secara optimal disebabkan faktor-faktor lainnya dari
keberadaan lahan sawah terabaikan, seperti fungsi sosial, fungsi kenyamanan, fungsi
konservasi tanah dan air, dan fungsi penyediaan pangan bagi generasi selanjutnya
(Rahmanto dkk, 2008).
Tanah merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis.
Saat ini, jumlah luasan tanah pertanian di Kampung Susuk tiap tahunnya terus
mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat
dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan.
Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat. Pada akhirnya,
terjadilah konversi lahan pertanian ke non pertanian seperti perumahan, industri, dan