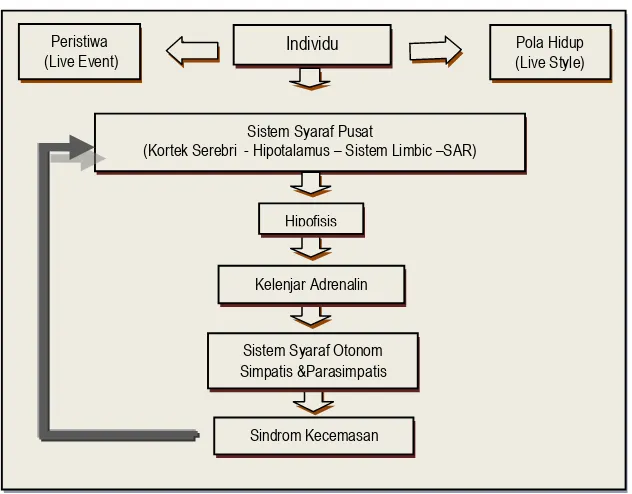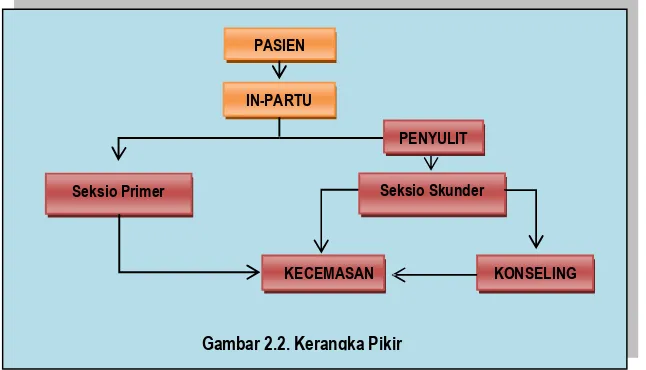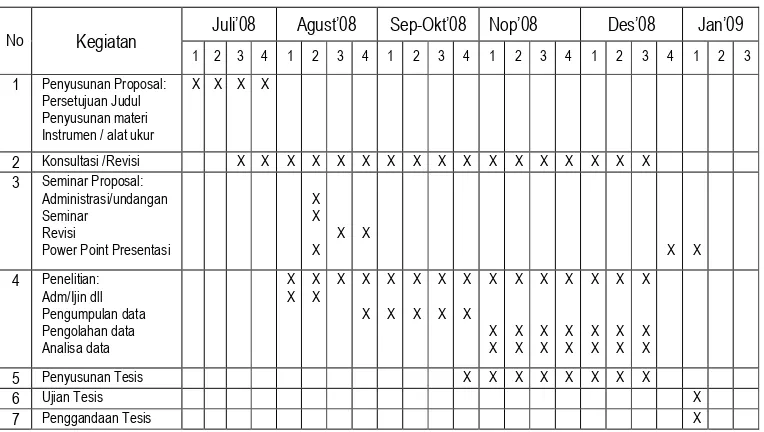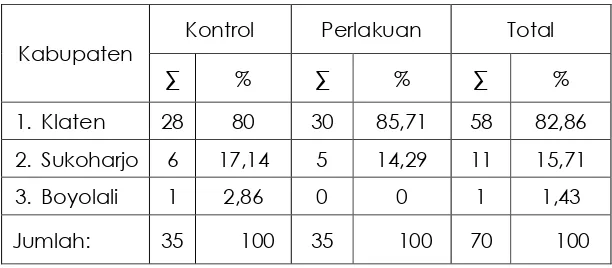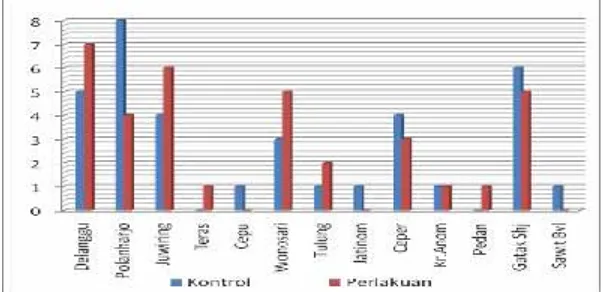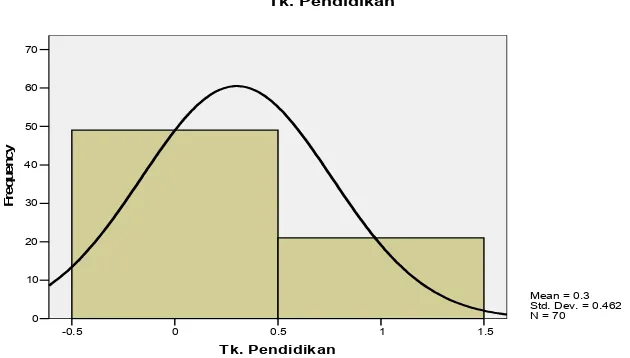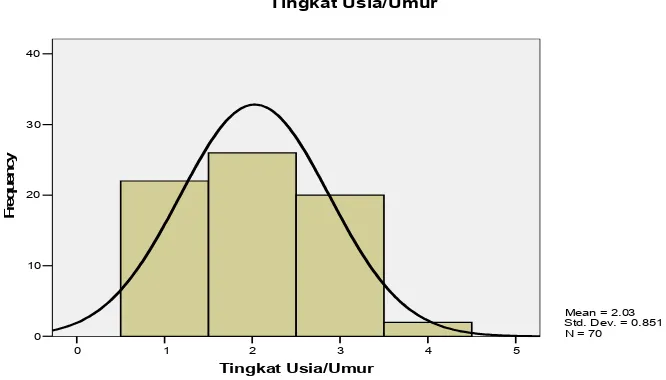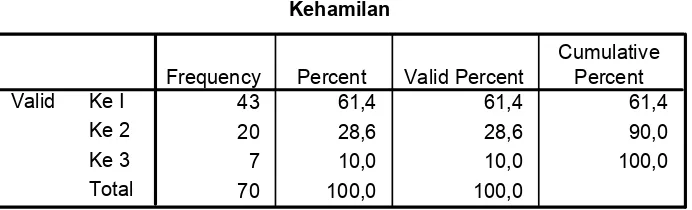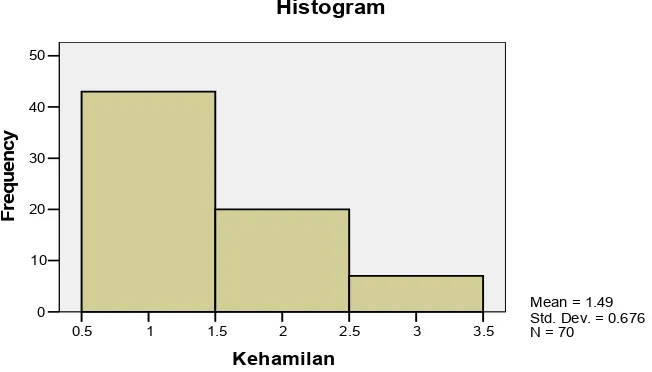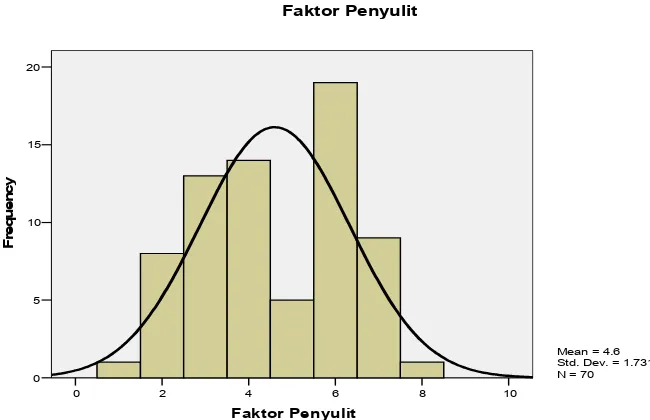i
Di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Kedokteran Keluarga
Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan
Oleh
Slamet Setyo Budi Utomo S54 090 7020
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
ii
PENGARUH KONSELING TERHADAP TINGKAT
KECEMASAN PASIEN SEKSIO SESAREA
Di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten
Disusun Oleh : Slamet Setyo Budi Utomo
NIM . S 54 090 7020
Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Pembimbing
Tim Pembimbing:
Jabatan Nama Tanda-Tangan Tanggal
Pembimbing I Prof. Dr. dr. H. Aris Sudyanto, Sp.KJ ... ... NIP. : 130 543 191
Pembimbing II Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. ... ... NIP. : 131 918 507
Mengetahui
Ketua Program Studi Kedokteran Keluarga
iii Oleh
Slamet Setyo Budi Utomo NIM . S 54 090 7020
Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Pada Tanggal : Januari 2009
Jabatan Nama Tanda Tangan
Ketua : Prof. Dr. dr. Didik Tamtomo, M.Kes.,MM.,PAK ...
Sekretaris : Prof. Dr. dr. Ambar Mudigdo, Sp.PA ...
Anggota : 1. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. ...
2. Prof. Dr. dr. Aris Sudyanto, Sp.KJ ...
Surakarta, Januari 2008 Mengetahui:
Direktur PPs UNS. Ketua Program Studi Kedokteran Keluarga
Prof. Drs. Suranto., M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. dr. Didik Tamtomo, PAK, MM, MKK.
iv Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Slamet Setyo Budi Utomo
NIM : S54 090 7020
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul PENGARUH KONSELING TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN SEKSIO SESAREA Di RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU KLATEN adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan dilanjutkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, 01 Desember 2008 Yang membuat pernyataan
v
dengan rahmat dan hidayah-Nya Tesis ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Kedokteran Keluarga.
Hambatan dan kendala yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuan, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Rektor, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S2);
2. Ketua Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Pendidikan Profesi Kesehatan;
3. Segenap dosen Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret yang telah membekali ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi peneliti;
4. Bapak Prof. Dr. H. Aris Sudyanto, dr., Sp.KJ. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan;
5. Ibu Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan;
6. Ketua, Sekretasis dan Anggota Tim Penguji Tesis, yang telah menguji dan memberikan masukan serta revisi tesis;
7. Direktur RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Bapak dr. Muhamad Ma’mun Sukri, yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam pengambilan data; 8. Bapak dr. Lilik Prasetyo, Sp.OG. RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, yang
telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan terhadap proses penelitian; 9. Rekan-rekan Kebidanan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, yang telah
membatu dan memberikan masukan atas pengambilan data;
vi
kaidah serta ahklak dalam kehidupan, hingga penulis dapat melanjutkan pendidikan;
12. Istriku tercinta, Nurwati Utomo dan anak-anakku tersayang, Rendra Perwira Aditama, Bima Achmad B. Nurutama dan Nurul Hidayah Utomo, yang dengan tulus dan ihklas memberikan dorongan semangat hingga terselesainya tesis ini; 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga atas bantuan dan kebaikan semua pihak, senantiasa memperoleh balasan kemulyaan dalam berkah dan rahmat Allah SWT. serta selalu teriring dalam kesucsesan.
Walaupun disadari dalam tesis ini masih ada kekurangan, namun diharapkan Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran keluarga.
vii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ... iii
PERNYATAAN ... iv
KATA PENGANTAR ... v
DAFTAR ISI ... vii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR ... x
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
ABSTRAK ... xii
ABSTRACT ... xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1
B. Rumusan Masalah... 4
C. Tujuan Penelitian... 4
D. Manfaat Penelitian... 5
E. Keaslian Penelitian... 5
BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Teori ... 6
1. Konseling... 6
2. Kecemasan ... 23
3. Seksio Sesarea ... 40
B. Kerangka Pikir... 51
C. Hipotesis ... 54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian... 55
B. Jenis Penelitian ... 55
C. Populasi dan Sampel Penelitian ... 55
viii
G. Pengolahan Data ... 61
H. Analisis Data ... 62
I. Jadwal Kegiatan... 63
BAB IV HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Hasil Penelitian... 65
B. Hasil Analisa Data... 84
C. Kesimpulan Hasil Analisa ... 89
D. Pembahasan ... 90
E. Keterbatasan ... 99
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 101
B. Implikasi ... 102
C. Saran ... 103
DAFTAR PUSTAKA ... 107
ix
1. Jadwal kegiatan penelitian ... 64
2. Distribusi responden menurut tempat tinggal (Kabupaten). ... 66
3. Distribusi responden menurut wilayah tempat tinggal ... 66
4. Distribusi data tingkat pendidikan responden ... 68
5. Distribusi data usia responden ... 69
6. Distribusi data kehamilan responden ... 70
7. Distribusi data faktor penyulit seksio sesarea ... 72
8. Distribusi kecemasan responden sebelum dan sesudah operasi... 76
9. Distribusi perubahan kecemasan responden ... 76
10. Distribusi kecemasan menurut tingkat pendidikan ... 78
11. Distribusi kecemasan menurut kelompok usia ... 79
12. Distribusi kecemasan menurut usia, objek, pre-post operasi ... 79
13. Distribusi kecemasan menurut jumlah persalinan ... 80
14. Distribusi kecemasan menurut faktor penyebab kelompok kontrol... 81
15. Distribusi kecemasan menurut faktor penyebab kelompok perlakuan. 81 16. Hasil Uji Normalisasi ... 84
x
Halaman
1. Patofisiologi Sindrom Kecemasan (Maslim). ... 31
2. Kerangka Pikir Penelitian. ... 54
3. Grafik distribusi wilayah tempat tinggal responden... 67
4. Grafik tingkat pendidikan responden ... .... 68
5. Grafik distribusi usia responden ... 69
6. Grafik kehamilan responden ... 71
7. Grafik distribusi faktor penyulit seksio sesarea ... 72
8. Grafik distribusi kecemasan pre operasi ... 73
9. Grafik distribusi kecemasan post operasi ... 74
10. Grafik kecemasan responden sebelum dan sesudah operasi ... 76
11. Grafik perubahan kecemasan responden ... 77
12. Grafik kecemasan menurut tingkat pendidikan ... 78
13. Grafik kecemasan menurut kelompok usia ... 79
14. Grafik kecemasan menurut kali persalinan ... 80
15. Grafik kecemasan menurut kelompok kontrol ... 82
xi
1. Petunjuk pengisian kuesioner ... 110
2. Kuesioner L-MMPI ... 111
3. Kuesioner T-MAS ... 112
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Konseling ... 114
5. Data koresponden ... 121
6. Hasil koding data koresponden. ... 124
7. Hasil analisa data dengan SPSS. ... 127
xii
Seksio Sesarea, di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Tesis Program Studi Magister Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2008.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh konseling terhadap tingkat kecemasan pasien sebelum dan sesudah operasi seksio sesarea.
Metode penelitian ini adalah metode analitik dengan pendekatan Randomized Controlled Trial (RCT), lokasi penelitian di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Populasi penelitian adalah pasien inpartum yang dirawat di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, dari bulan September 2008 sampai dengan Oktober 2008, subyek penelitian sebanyak 70 orang dari seluruh populasi penelitian, dengan alat uji T-MAS (Taylor Manifest Anxienty Scale) dan uji hipotesa analisis Uji t (t-Test) dan Analisis Varians satu jalan (One-Way ANOVA).
Hasil pengujian hipotesis dengan Uji t adalah sebelum operasi t hitung 2,850 dengan signifikasi 0,006 lebih kecil taraf alpha 0,05 maka t hitung signifikan. Dan pada sesudah operasi t hitung 2,480 dengan signifikasi 0,016 < 0,05 maka t hitung signifikan.
Hasil analisis dengan Varians datu jalan (one way anova), untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, usia, jumlah persalinan, dan faktor penyulit terhadap kecemasan yang diberi konseling didapatkan bahwa yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kecemasan hanya tingkat pendidikan yakni harga F hitung 4,641 dengan harga signifikansi 0,039 < 0,05.
Kesimpulan, Konseling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan pada pasien sebelum operasi seksio sesarea dengan harga t hitung sebesar 2,850 dengan harga signifikasi 0,006 < 0,05. Dan Konseling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan sesudah operasi seksio sesarea dengan t hitung 2,480 dengan harga signifikasi 0,016 < 0,05.
Saran, sesuai hasil penelitian ini: pada pasien seksio sesarea agar dilakukan konseling kususnya pada pasien berpendidikan rendah (< 9 tahun) oleh tenaga kesehatan atau tim konselor yang mempunyai kompetensi tentang konseling (ketrampilan komunikasi interpersonal, tehnik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik).
xiii
sesaria at Muhammadiyah Hospital Delanggu Klaten Regency. A Thesis for Master Program Family Medicine, Posy Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta 2008.
This study aim is to detects counselling influence existence towards patient anxiety level before and postoperative seksio sesaria.
This study analytic method with approaches Randomized Control Trial (RCT), this study location at Muhammadiyah Hospital Delanggu Klaten Regency. The population patient inpartum that cared at Muhammadiyah Hospital Delanggu Klaten Regency, from September until October 2008. The subject as much as 70 person from entire the study populations by means of test research T-MAS (Taylor Manifest Anxienty Scale) and test hipotesa test-T and test one way anova.
Hypothesis testing result with test-T before operation t count 2.850 with signifikasi 0.006 smaller than standard alpha 0,05 so t count significant. and in postoperative t count 2.480 with signifikansi 0,016 < 0,05 so t count significant.
Analysis result with one way anova, to detect education level influence, age, completely puerperal and factor heavy on hand towards anxiety that given counselling is got that has influence towards only education level that is f count 4.641 at the price of signifikansi 0,039, 0,05 conclusion, influential counselling significant towards anxiety level in patient before operation seksio sesaria at the price of t counts as big as 2.850 at the price of signifikansi 0,006 < 0,05 and influential counselling significant towards post operative anxiety level seksio sesaria with t counts 2.480 at the price of signifikansi 0.016 < 0,05.
Influential education level significant towards anxiety level in patient counselling with F counts 4.461 at the price of significant 0,039 < 0,05, while age level, pregnancy total, factor heavy on hand not influence significant towards anxiety level at the price of significant bigger 0,05.
Suggestion, appropriate this study result: in patient seksio sesarea so that done counselling especially in low educated patient (<9 year) by health team or team konselor that has competence about counselling (communication craft interpersonal, technics guidance and clinic erudition mastery).
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seksio sesarea (caesarean delivery) adalah satu cara melahirkan janin melalui
sayatan dinding abdomen (laparatomi) dan dinding uterus (histerotomi).
Kaisar Numa Pompilius dari kerajaan Romawi pada abad kedelapan SM
mengesahkan undang-undang yang mengijinkan tindakan seksio sesarea segera
pada ibu-ibu hamil tua yang baru saja meninggal untuk menyelamatkan janin.
Diduga dengan terbitnya undang-undang ini, istilah ”Caesarea Delivery” atau
Caesarean Section” atau seksio sesarea mulai dipakai untuk persalinan operatif
melalui luka sayatan dinding abdomen (perut) dan dinding uterus (rahim).
(ACOG.,1999).
Di negara-negara sedang membangun, seksio sesarea adalah merupakan
pilihan terakhir untuk menyelamatkan ibu dan janin pada saat kehamilan dan atau
persalinan yang kritis. Seksio sesarea yang diputuskan mendadak, tanpa perawatan
pre-operatif yang memadai, dan tanpa direncanakan sebelumnya disebut seksio
sesarea emergensi (ACOG.,1999).
Dengan majunya perkembangan dimasyarakat akhir-akhir ini, seksio sesarea
juga sudah dilakukan atas permintaan ibu atau keluarga tanpa indikasi obstetrik,
atau dengan indikasi obstetrik sebelum timbul tanda-tanda persalinan, atau dengan
indikasi obstetrik dengan perawatan pre-operatif yang baik. Seksio sesarea yang
direncanakan dan sudah mendapat perawatan pre-operatif yang baik disebut seksio
Angka morbiditas (kesakitan), angka mortalitas (kematian) maternal (ibu) dan
neonatal (bayi) pada seksio sesarea erat kaitannya dengan komplikasi kehamilan,
komplikasi persalinan, dan indikasi seksio sesarea, juga erat kaitannya dengan
ketersediaan sarana dan fasilitas, termasuk ketrampilan tim operator (White, S.M.,
Thorpe RG, Maine D., 1987).
Perlu disadari bahwa persalinan merupakan peristiwa alamiah tetapi banyak
pendapat masyarakat terutama kaum wanita memandang secara subyektif sebagai
proses yang menakutkan, tidak nyaman dan sangat menyakitkan sehingga banyak
ibu-ibu yang merasa cemas, gelisah, takut menghadapi proses persalinan
(Bobak-Jensen, 1993). tetapi persalinan pada manusia setiap saat dapat terjadi penyulit
yang membahayakan ibu atau janin, sehingga memerlukan pengawasan,
pertolongan dan pelayanan dengan fasilitas yang mamadai (Manuaba, 1998).
Kematian seorang ibu dalam proses persalinan atau akibat lain yang
berhubungan dengan kehamilan merupakan suatu pengalaman yang menyedihkan,
kadang meninggalkan trauma fisik maupun mental kepada ibu maupun keluarga.
Beban emosional terjadi gangguan perasaan ringan sampai depresi postpartum
atau psikosis (Sarwono P., 2002).
Perasaan cemas atau ketakutan yang dihadapi pasien dan keluarganya
merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, yang dimungkinkan dengan
keterbatasan informasi, pengetahuan dan pemahaman masalah kesehatan
disamping karena faktor lainnya. Hal tersebut diperlukan pemahaman melalui
proses konseling kepada pasien maupun keluarganya.
Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan
bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, yang bertujuan untuk membantu
seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan
menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Saifuddin,
2001).
Kecemasan dalam proses persalinan sering dianggap kurang penting bahkan
kurang diperhatikan oleh dirinya sendiri, keluarga ataupun tenaga kesehatan. Dan
bentuk perhatian hanya difokuskan pada keadaan patologis yang dapat
mengancam keselamatan ibu dan bayi, padahal keadaan psikologis ibu bersalin
merupakan hal yang penting dalam membantu proses persalinan. Dari hasil studi
pendahuluan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu yang di dapat dari data
primer diperoleh bahwa tahun 2007 terdapat kasus persalinan sebanyak 903
penderita yang terdiri dari: persalinan normal 10.41%, tindakan (stimulasi &
Induksi) 35,88%, vakum ektraksi 9.41% dan seksio sesarea 44.30% sebagaimana
dalam tabel 1. berikut ini:
Sesuai keterangan dari tenaga kesehatan bahwa kasus persalinan baik
persalinan normal maupun persalinan dengan faktor penyulit yang dilakukan
pada ibu maupun keluarganya menunjukkan adanya gangguan perasaan atau
perilaku yang mengarah pada kecemasan. seperti: terlihat wajah tegang, khawatir,
tidak tenang, gelisah dan mudah kaget.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka penulis memilih judul
dalam penelitian adalah Pengaruh Konseling Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien
Seksio Sesarea di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan dalam
latar belakang di atas maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
1) Adakah pengaruh pemberian konseling terhadap tingkat kecemasan pasien
sebelum dan sesudah seksio sesarea.
2) Adakah pengaruh konstribusi faktor : tingkat pendidikan, jumlah persalinan,
usia, dan faktor penyulit terhadap tingkat kecemasan pasien seksio sesarea
yang diberi konseling.
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Memperoleh gambaran sebab akibat tingkat kecemasan terhadap pasien
seksio sesarea di RSU. PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten.
2. Tujuan Khusus:
Untuk mengetahui :
a. Pengaruh pemberian konseling sebelum dan sesudah operasi terhadap
b. Pengaruh kontribusi faktor; tingkat pendidikan, jumlah persalinan, usia,
dan faktor penyulit terhadap tingkat kecemasan pasien seksio sesarea
yang diberi konseling.
D. Manfaat Penelitian
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuktikan
ada tidaknya pengaruh pemberian konseling pada pasien seksio sesarea sebelum
dan sesudah melakukan operasi sesarea terhadap tingkat kecemasan.
Manfaat praktis penelitian ini diharapkan:
1. Dapat dimanfaatkan untuk penelitian yang berikutnya.
2. Dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Institusi Negeri maupun
Swasta dilingkungan kesehatan seperti : Departemen Kesehatan, Institusi
Pendidikan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat pada
umumnya.
E. Keaslian Penelitian
Sejauh yang diketahui penulis sampai saat ini belum pernah ada penelitian
mengenai Pengaruh Konseling Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Seksio
Sesarea di RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten yang dilakukan dan
dipublikasikan dalam forum ilmiah, sehingga gagasan penulis mengenai hal ini
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Teori
1. Konseling
Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap,
dilakukan secara sistematik dengan paduan ketrampilan komunikasi
interpersonal, tehnik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, yang
bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah
yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk
mengatasi masalah tersebut (Saifuddin, 2001).
Kurtz (1998), menyatakan bahwa komunikasi efektif justru tidak
memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan lebih
sedikit waktu karena dokter terampil mengenali kebutuhan pasien (tidak
hanya ingin sembuh). Atas dasar kebutuhan pasien, dokter melakukan
manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien untuk tercapainya
pengertian yang sama dan kesepakatan yang dibangun bersama pada setiap
langkah penyelesaian masalah antara penyampai pesan dan penerima pesan.
Secara umum definisi komunikasi adalah sebuah proses penyampaian
pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu
cara tertentu, sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud
oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi, (Koontz dan Weihrich 1988;
Untuk mencapai tujuan komunikasi dalam melakukan konseling, adalah
untuk mengarahkan proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat dan lebih
memberikan dukungan pada pasien, dengan demikian lebih efektif dan efisien
bagi keduanya (Kurzt, 1998). Keberhasilan dalam konseling pada umumnya
akan melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak,
khususnya akan menciptakan terhadap kemampuan pemahaman, harapan,
kepentingan, kecemasan dan kebutuhan pasien. Sehingga dalam konseling
diperlukan berbagai pemahaman seperti pemanfaatan jenis komunikasi (lisan,
tulisan/verbal, non-verbal), menjadi pendengar yang baik (active listener),
adanya penghambat proses komunikasi (noise), pemilihan alat penyampaian
pikiran atau infomasi yang tepat (channel), dan mengenal mengekspresikan
perasaan dan emosi.
Dalam model proses komunikasi yang berfokus pada pengirim informasi
(sender/source), saluran yang dipakai (channel), untuk menyampaikan
informasi dan penerima informasi (receiver). Dalam model juga
mengilustrasikan adanya penghambat informasi sampai ke penerima (noise),
dan umpan baik (feedback) yang memfasilitasi kelancara komunikasi itu
sendiri.
Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti
sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, pesan ditindaklanjuti dengan
sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu
(Hardjana, 2003).
Komunikasi dalam proses konseling juga merupakan bimbingan yang
yang dihadapi untuk menentukan pilihan, indikator mutu pelayanan dan
memberikan rasa puas. Berdasarkan tahapan pemberian informasi, konseling
dibagi menjadi: konseling awal, konseling khusus atau pemantapan, dan
konseling kunjungan ulang.
Di dalam proses komunikasi, sikap profesional sangat penting untuk
membangun rasa nyaman, aman, percaya pada dokter, yang merupakan
landasan bagi berlangsungnya komunikasi secara efektif (Silverman, 1998).
Sikap profesional ini hendaknya dijalin terus-menerus sejak awal konsultasi,
selama proses konsultasi berlangsung dan diakhir konsultasi.
Sebagaimana yang tercantum dalam Konsil Kedokteran Indonesia (2006),
di dalam proses komunikasi ada dua sesi yang sangat penting yaitu sesi
pengumpulan informasi yang didalamnya terdapat proses anamnesis dan sesi
penyampaian informasi. Model proses komunikasi pada sesi penggalian
informasi telah dikembangkan oleh Van Dalen (2005) dan digambarkan
dalam sebuah model yang sangat sederhana dan aplikatif, sebagai berikut:
1 3
2 3
Kotak 1 : Pasien memimpin pembicaraan melalui pernyataan terbuka yang dikemukakan oleh dokter (Patient takes the lead through open ended question by the doktor).
Kotak 2 : Dokter memimpin pembicaraan melalui pertanyaan tertutup /
terstruktur yang telah disusunnya sendiri ( Doctors takes the lead through closed question by the doctor).
Kotak 3 : Kesepakatan apa yang harus dan akan dilakukan berdasarkan
Sesi penggalian informasi terdiri dari:
a. Mengenali alasan kedatangan pasien, belum tentu keluhan utama secara
medis (Silverman, 1998). inilah disebut dalam kotak pertama model Van
Dalen (2005). Pasien menceriterakan keluhan atau apa yang dirasakan
sesuai sudut pandangnya (illness perspective). Pasien berada pada posisi
sebagai orang yang paling tahu tentang dirinya karena mengalaminya
sendiri.
Sesi ini akan berhasil bila dokter mampu menjadi pendengar yang
aktif (active listerner). Pendengar yang aktif adalah fasilitator yang baik
sehingga pasien dapat mengungkapkan kepentingan, harapan,
kecemasannya secara terbuka dan jujur. Hal ini akan membantu dokter
dalam menggali riwayat kesehatannya yang merupakan data-data penting
untuk menegakkan diagnosis.
b. Penggalian riwayat penyakit (Van Thiel, 2000), penggalian riwayat
penyakit (anamnesis) dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan
terbuka dahulu, yang kemudian diikuti pertanyaan tertutup yang
membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak”. Inilah yang dimaksud dalam
kotak kedua dalam model Van Dalen (2005). Dokter sebagai seorang
yang ahli, akan menggali riwayat kesehatan pasien sesuai kepentingan
medis (disease perspective).
Selama proses ini, fasilitasi terus dilakukan agar pasien mengungkapkan
keluhannya dengan terbuka, serta proses negosiasi saat dokter hendak
melakukan komunikasi satu arah maupun rencana tindakan medis.
Bagaimana pusing tersebut anda rasakan, dapat diceriterakan lebih
jauh?
Menurut anda pusing tersebut reda bila anda melakukan sesuatu,
meminum obat tertentu, atau bagaimana menurut anda?
Sedangkan pertanyaan tertutup yang merupakan inti dari anamnesis:
Eksplorasi terhadap riwayat penyakit: dahulu, keluarga dan sekarang.
Contoh menggunakan pedoman Macleod’s clinical examination
seperti disebutkan dalam Kurtz (1998). yakni:
o Dimana dirasakan ? (site)
o Sampai di bagian tubuh mana hal tersebut dirasakan ?
(radiation)
o Bagaimana karakteristik dari nyerinya, berdenyut-denyut ?
Hilang timbul ? Nyeri terus menerus ? (character)
o Nyeri? Amat nyeri? Sampai tidak dapat melakukan kegiatan
mengajar? (severity)
o Berapa lama nyeri berlangsung? Sebentar? Berjam-jam?
Berhari-hari? (duration)
o Setiap waktu tertentu nyeri tersebut dirasakan? Berulang-ulang?
Tidak tentu? (Frequency)
o Apa yang membuatnya reda? Apa yang membuatnya kumat?
Saat istirahat? Ketika kerja? Sewaktu minum obat tertentu?
(aggravating and relieving factor)
o Apakah keluhan lain yang menyertainya? (associated
Sesi Penyampaian Informasi:
Setelah sesi sebelumnya dilakukan dengan akurat, maka dokter dapat
melanjutkan kepada sesi memberikan penjelasan. Secara ringkas ada 6 (enam)
hal yang penting diperhatikan agar efektif dalam berkomunikasi dengan
pasien, yaitu:
a. Materi Informasi apa yang disampaikan:
1) Tujuan anamnesis dan pemeriksaan fisik (kemungkinan rasa tidak
nyaman / sakit saat pemeriksaan).
2) Kondisi saat ini dan berbagai kemungkinan diagnosis.
3) Berbagai tindakan medis yang akan dilakukan untuk menentukan
diagnosis, termasuk manfaat, resiko, serta kemungkinan efek
samping / komplikasi.
4) Hasil dan interpretasi dari tindakan medis yang telah dilakukan untuk
menegakkan diagnosis.
5) Diagnosis, jenis atau tipe suatu penyakit
6) Pilihan tindakan medis untuk tujuan terapi (kekurangan dan
kelebihan masing-masing cara)
7) Prognosis.
8) Dukungan (support) yang tersedia.
b. Siapa yang diberi informasi:
1) Pasien, apabila dia menghendaki dan kondisinya memungkinkan.
3) Keluarganya atau pihak lain yang menjadi wali / pengampu dan
bertanggung jawab atas pasien kalau kondisi pasien tidak
memungkinkan untuk berkomunikasi sendiri secara langsung.
c. Berapa banyak atau sejauh mana:
1) Untuk pasien: sebanyak yang pasien kehendaki, yang dokter merasa
perlu untuk disampaikan, dengan memerhatikan kesiapan mental
pasien.
2) Untuk keluarga: sebanyak yang pasien / keluarga kehendaki dan
sebanyak yang dokter perlukan agar dapat menentukan tindakan
selanjutnya.
d. Kapan menyampaikan informasi:
1) Segera diinformasikan
2) Jika kondisi dan situasinya memungkinkan.
e. Di mana menyampaikannya:
1) Di ruang praktik dokter / ruang pemeriksaan pasien
2) Di bangsal, ruangan tempat pasien dirawat
3) di ruang diskusi
4) Di tempat lain yang pantas, atas persetujuan bersama (pasien,
keluarga dan dokter)
f. Bagaimana menyampaikannya:
1) Informasi penting sebaiknya disampaikan secara langsung, tidak
melalui telepon, juga tidak dalam bentuk tulisan yang dikirimkan
2) Persiapan meliputi:
o materi yang akan disampaikan (bila diagnosa, tindakan medis,
prognosis sudah disepakati oleh tim)
o ruangan yang nyaman, memperhatikan privasi, tidak terganggu
orang lalu lalang, suara gaduh dari tv/radio atau telepon.
o waktu yang cukup
o mengetahui orang yang akan hadir (sebaiknya pasien ditemani
oleh keluarga/orang yang ditunjuk; bila hanya keluarga yang hadir
sebaiknya lebih dari satu orang)
3) Jajaki sejauh mana pengertian / keluarga tentang hal yang akan
dibicarakan.
4) Tanyakan kepada pasien / keluarga, sejauhmana informasi yang
diinginkan dan amati kesiapan pasien / keluarga menerima informasi
Langkah-langkah komunikasi
Ada empat langkah yang terangkum dalam satu kata untuk melakukan
komunikasi yaitu SAJI (Poernomo, leda SS, Program Family Health
Nutrition, Depkes RI, 1999). yakni : S = Salam, A = Ajak Bicara, J =
Jelaskan, I = Ingatkan. Dengan penjelasan sebagai berikut:
Salam; Beri salam, sapa dia, tunjukkan bahwa Anda bersedia meluangkan
waktu untuk berbicara dengannya.
Ajak Bicara: Usahakan berkomunikasi secara dua arah, jangan bicara sendiri.
Dorong agar pasien mau dan dapat mengemukakan pikiran dan perasaannya.
Tunjukkan bahwa dokter menghargai pendapatnya, dapat memahami
kecemasannya, serta mengerti perasaannya. Dokter dapat menggunakan
pertanyaan terbuka maupun tertutup dalam usaha mengenali informasi.
Jelaskan: Beri penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatiannya, yang
ingin diketahuinya, dan yang akan dijalani / dihadapinya agar ia tidak terjebak
oleh pikirannya sendiri, Luruskan persepsi yang keliru. Berikan penjelasan
mengenai penyakit, terapi atau apapun secara jelas dan detil.
Ingatkan: Percakapan yang dokter lakukan bersama pasien mungkin
memasukkan berbagai materi secara luas, yang tidak mudah diingatkan
kembali. di bagian akhir percakapan ingatkan dia untuk hal-hal yang masih
belum jelas bagi kedua belah pihak serta mengulang kembali akan
pesan-pesan kesehatan yang penting.
Secara garis besar, kemampuan konseling untuk melaksanakan
komunikasi positif secara efektif merupakan syarat seorang konselor, ciri
a. Mampu menciptakan suasana nyaman dan aman bagi klien;
b. Menimbulkan rasa saling percaya diantara klien dan konselor;
c. Mampu mengenali hambatan sosio-kultur setempat
d. Mampu menyampaikan informasi objektif, lengkap dan jelas (bahasa
yang mudah dimengerti)
e. Mau mendengar aktif dan bertanya efektif dan sopan;
f. Memahami dan mampu menjelaskan berbagai aspek kesehatan
reproduksi;
g. Mampu mengenali keinginan klien dan keterbatasan penolong;
h. Membuat klien bertanya, berbicara dan mengeluarkan pendapat;
i. Menghormati hak klien, membantu dan memperhatikan.
Walaupun petugas pelayanan kesehatan belum mengikuti pelatihan
ketrampilan konseling, bukan berarti wahwa proses ini tidak dapat dilakukan,
karena masalah penting didalam konseling selain tehnik komunikasi dan
pemberian informasi juga isi dari informasi yang akan disampaikan. Semua
petugas dan staf klinik dapat mengerti tentang pengetahuan dan tindakan
klinik dalam kesehatan maternal dan berbagai resiko atau komplikasi yang
mungkin timbul.
Perlu diingat bahwa klien memilih dan membuat keputusan tentang
pilihan penatalaksanaan klinik yang diyakini sesuai dengan masalah
kesehatan yang mereka hadapi, kemudian dinyatakan dalam persetujuan
tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, akan lebih mantap untuk
menjalankan pengobatan atau tindakan klinik yang akan dijalankan serta
Disamping akronim SAJI (Poernomo,1999), Gellen dan Leitenmair
(1987), memberikan satu akronim yang dapat dijadikan panduan bagi petugas
klinik untuk melakukan konseling. Akronim tersebut adalah GATHER yang
merupakan singkatan dari:
a. G-Greet, memberikan salam, mengenalkan diri dan membuka
komunikasi;
b. A-Ask atau Assess, Menanyakan keluahan / kebutuhan pasien dan menilai
apakah keluahan / keinginan yang disampaikan memang sesuai dengan
kondisi yang dihadapi.
c. T-Tell, eritahukan bahwa persoalan pokok yang dihadapi oleh pasien
adalah seperti yang tercermin dari hasil tukar informasi dan harus
dicarikan upaya penyelesaian masalah tersebut;
d. H-Help, Bantu pasien untuk memahami masalah utamanya dan masalah
itu yang harus diselesaikan. Jalaskan beberapa cara yang dapat
menyelesaikan masalah tersebut, termasuk keuntungan dan keterbatasan
dari masing-masing cara tersebut. Minta pasien untuk memutuskan cara
terbaik bagi dirinya.
e. E-Explain, Jelaskan bahwa cara terpilih telah diberikan / dianjurkan dan
hasil yang diharapkan mungkin segera terlihat atau diobservasi beberapa
saat hingga menampakkan hasil yang diharapkan. Jelaskan pula siapa dan
dimana pertolongan lanjutan atau darurat dapat diperoleh.
f. R-Refer dan Return visit, Rujuk apabila fasilitas ini tidak dapat
memberikan pelayanan yang sesuai atau buat jadwal kunjungan ulang
Prinsip-prinsip umum dalam konseling seperti yang dikutip dalam Burnet
Indonesia (2005), adalah sebagai berikut:
1) Mendengarkan, ini berarti konselor harus diam beberapa saat dan biarkan
percakapan mengalir sehingga klien lebih banyak berbicara dibanding
konselor.
2) Menanyakan dengan pertanyaan yang efektif, ini merupakan suatu cara
agar klien bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan
membantu konselor untuk memahami situasi. Mengajukan pertanyaan
dalam konseling bukan seperti menginterogasi. Ada tiga bentuk
pertanyaan mengarahkan: pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup dan
pertanyaan mengarahkan.
a. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban
berupa penjelasan atau uraian dan biasanya tidak dalam satu atau dua
kata. Contoh: Jelaskan apa yang mengganggu perasaan anda.
b. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban
berupa kepastian dan biasanya singkat dalam satu atau dua kata.
Dengan pertanyaan tertutup klien tidak mendapatkan kesempatan
untuk berpikir tentang apa yang mereka katakan. Jawaban yang
singkat mengakibatkan konselor makin banyak mengajukan
pertanyaan selanjutnya. Contoh: apakah anda pernah melakukan
operasi seksio sesarea?.
c. Pertanyaan mengarahkan adalah pertanyaan yang telah mengarahkan
jawaban yang diberikan, contoh: anda selalu kontrol selama
Didalam konseling bentuk pertanyaan yang sering digunakan adalah
pertanyaan terbuka, karena dengan bentuk pertanyaan ini klien akan
memberi lebih banyak informasi, sedangkan pertanyaan tertutup lebih
terbatas, sedangkan pertanyaan mengarahkan sebaiknya jangan dipakai
dalam konseling karena lebih bersifat menghakimi dan jawaban yang
diberikan klien biasanya yang diinginkan konselor. Pertanyaan terbuka
umumnya dimulai dengan pertanyaan “Apa”, “Dimana”, “Bagaimana”,
“Kapan”. Pertanyaan ini mengundang klien untuk melanjutkan
pembicaraan dan memutuskan apa tujuan mereka ingin berbicara.
3) Memberikan informasi yang tepat, dalam hal ini sebaiknya konselor
mengakui dengan jujur apabila ada sesuatu hal yang belum dipahami dan
mencoba mencari informasi yang benar, daripada mengabaikan
pertanyaan itu atau memberikan informasi yang salah.
4) Menjaga kepercayaan klien, konselor harus menjaga kerahasiaan
informasi tentang klien. Bila tidak, klien merasa dirinya tidak dihargai
atau dihormati, dan akan merasa membuat kesalahan karena mencari
pertolongan atau berbagi rasa dengan konselor.
5) Menjawab pertanyaaan yang kadang sulit dijawab, tidak selalu konselor
dapat memberikan jawaban yang benar. Bila dapat memastikan bahwa
jawaban yang diberikan adalah benar, anda boleh menjawabnya, tetapi
bila ragu-ragu akan lebih baik bila anda melakukan konsultasi kepada
yang lebih memahami. Anda juga mencoba mencari jawabannya sendiri
6) Menghadapi perasaan tidak nyaman dan ketakutan, dalam beberapa
situasi, konselor kadang-kadang merasa membutuhkan pertolongan untuk
mengatasi perasaannya dalam menghadapi klien. Bila konselor
melakukan konseling pada klien, ia harus melihat raksi pada dirinya
sendiri. Sebagai contoh: seorang konselor menunda menyampaikan hasil
keputusan medis, karena takut tidak mampu menghadapi reaksi klien.
Bila konselor merasa tidak sabar atau marah, ini adalah tanda bahwa
konslor mengalami masalah dalam dirinya dan ini akan sangat tidak
membantu klien, maka konslor harus mencari orang lain atau konselor
lain untuk membantu anda memahami kebutuhan dan ketakutan klien.
7) Memilih tempat konsling yang cocok, di manapun konslor memberikan
konsling, hendaknya selalu memperhatikan hal-hal seperti kenyamanan,
aman dari gangguan fisik (bising, sempit, gelap), bersifat pribadi, ada alat
peraga, menyesuaikan keadaan ekonomi dan nilai budaya.
8) Menjalin hubungan, konselor harus menciptakan suasana yang membuat
klien merasa santai, tidak takut, merasa aman dan bebas mengungkapkan
perasaan dan pertanyaan yang ada dalam hatinya untuk didiskusikan. Hal
ini bisa dicapai dengan jalan;
a. Konselor harus memperkenalkan diri (bisa menjabat tangan,
merangkul, atau menepuk pundak klien)
b. Konselor membuat aturan permainan sebelum percakapan dimulai,
misalnya: soal waktu, kerahasiaan, maksud/tujuan percakapan.
c. Konselor bisa berbasa-basi sejenak, misalnya: menanyakan tentang
d. Memulai pertanyaan inti seperti berikut: apa yang membuat anda
datang ke sini?, apa yang ingin anda sampaikan atau bahas.
Selama proses ini konselor harus bisa mendengarkan keluhan klien
dengan penuh perhatian, menghargai klien sebagai sesama manusia, tidak
menilai ataupun menghakimi, memberi dorongan agar klien dapat
berbicara terbuka, dan menunjukkan ekspresi wajah atau tubuh yang
mengungkapkan minat dan kepedulian.
9) Eksplorasi, konselor berusaha mengetahui secara mendalam tentang
perasaan klien, situasi klien dan alasannya datang untuk meminta
bantuan. Untuk mencapai suasana tersebut dapat digunakan cara-cara
berikut:
a. Menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya: bagaimana ibu tahu
kalau ibu akan dioperasi?
b. Beritahu pemahaman kepada klien tentang apa yang dirasakan dan
yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana.
c. Ulangi dan perjelas apa yang diungkapkan oleh klien supaya
pembicaraan lebih terarah. Misalnya: jadi ibu ingin melakukan
operasi untuk melindungi bayi agar tetap sehat.
d. Bantu klien untuk memahami perasaannya sendiri, misalnya: Oh ya,
jadi ibu belum tahu persiapan operasi harus persiapan apa?
10) Pemahaman, konselor membantu klien mengidentifikasi masalah dan
penyebab masalah, serta membantu klien merancang alternatif
pemecahan masalah. Secara sepintas mengidentifikasi masalah hal yang
kadang-kadang suatu masalah sangat sulit dan rumit dari yang diduga.
Langkah awal, konselor harus mengetahui apakah benar ada maslah yang
dirasakan oleh klien. Biarkan klien yang menceriterakan dan
merumuskan, baru konselor melanjutkan menggali untuk mengetahui
apakah masalah ada pada klien sendiri atau orang lain (yang terkait
dengan klien). Gali kemungkinan adanya masalah lain. Cara-cara untuk
mencapai tujuan tersebut:
a. Pusatkan pembicaraan pada masalah yang paling utama.
b. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk
menggali informasi dan mendorong klien untuk mengungkapkan
riwayat masa lalunya.
c. Ungkapkan pemahaman anda tentang perasaan klien.
d. Rangkum semua yang sudah didiskusikan.
11) Perencanaan kegiatan, dalam langkah ini klien membuat rencana untuk
mengatasi masalahnya. Konselor membantu klien untuk mengetahui dan
memahami pilihannya. Konselor juga dapat menggali lebih banyak dari
klien beberapa pilihan yang meungkin belum dipertimbangkan oleh klien.
Klien dibantu oleh konselor dapat mencapai tujuan ini dengan cara:
a. Menentukan prioritas masalah yang hendak diatasi terlebih dahulu.
b. Konselor menyakinkan kesiapan klien lebih dahulu sebelum
melaksanakan keputusannya.
c. Merencanakan beberapa alternatif pemecahan masalah,
mendiskusikan keuntungan dan kendala dari setiap pemecahan
d. Konselor memberitahukan fakta-fakta yang relevan.
e. Konselor mendorong klien untuk mengambil keputusan sendiri.
Apabila klien ragu-ragu, fasilitasi hal-hal yang klien butuhkan.
f. Membuat rencana yang dapat dijalankan sesuai kemampuan klien.
g. Meninjau dan membahas setiap bagian rencana bersama-sama, bila
klien tidak yakin, buatlah penyesuaian.
12) Langkah-langkah kegiatan konseling: Model Penolong yang Trampil
Model penolong yang trampil dapat digunakan dalam setiap konseling
karena dalam model ini konselor bersama dengan klien akan membahas
langkah-langkah dari pengenalan permasalahan klien hingga realisasi
pemecahan masalah. Model ini terdiri atas tiga tahap utama yaitu: Tahap
1 : Apa yang sedang terjadi pada klien; Tahap 2 : Solusi apa yang berarti
bagi klien; dan Tahap 3 : Bagaimana klien bisamendapatkan apa yang ia
butuhkan atau kehendaki. Selanjutnya keseluruhan tahap ini akan
mengarah pada bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.
Dalam proses konseling bila konselor bersama klien belum dapat
mengenali dengan rinci permasalahan yang dihadapi klien kemungkinan besar
pada tahap-tahap berikutnya akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu tidak
mengherankan kalau konselor mengajak klien melihat kembali ke tahap awal
dan bersama menggali lebih dalam lagi informasi yang mempunyai kaitan
dengan permasalahan klien. Bila dalam tahap perwujudan penyelesaian
masalah klien ternyata semua strategi dan komitmen yang telah dilakukan
gagal, akan tetapi konseling belum sampai pada penyelesaian masalah klien
dengan tuntas.
Hal ini bisa disebabkan karena dalam perjalanan penyelesaian masalah
klien terjadi hal-hal baru sehingga keadaan berubah atau terjadinya masalah
baru yang tidak pernah terpikirkan selama perjalanan penyelesaian maslah
klien. Konselor dalam hal ini bersama-sama mendefinisikan kembali
bagaimana permasalahan sebenarnya sehingga jelas arah strategi
penyelesaiannya.
2. Kecemasan
Kecemasan adalah suatu pengalaman emosional yang bersifat universal,
akrab dengan kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, dari
bayi sampai usia lanjut. Merupakan hal wajar apabila seseorang merasa cemas
ketika menghadapi tekanan masalah, tetapi rasa cemas yang berlebihan bisa
menyebabkan seseorang merasa sakit (Infokes, 2000)
Kecemasan umumnya dilukiskan sebagai kekawatiran, kegelisahan, rasa
tidak tenang, was-was, yang biasanya dihubungkan dengan suatu ancaman
bahaya baik dari dalam maupun dari luar individu. Kecemasan perlu
dibedakan dari takut (fear) yang berhubungan dengan keadaan bahaya yang
nyata atau kongkret yang datang dari luar, dan asalnya dapat diketahui, jelas
atau bukan bersifat konflik. Sedangkan kecemasan adalah respon terhadap
suatu ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal, samar-samar, atau
konfliktual. Perbedaan antara dimana ketakutan dan kecemasan timbul secara
Menurut Freud kecemasan berhubungan dengan obyek yang diresapi dan
tidak disadari, sedangkan pada ketakutan berhubungan dengan obyek yang
diketahui dan ekternal. Perbedaannya kadang-kadang sulit dibedakan karena
ketakutan mungkin juga disebabkan oleh obyek internal, tidak disadari, dan
depresi yang dialihkan kepada obyek lain di dunia luar.
Menurut rumusan psikoanalitik pasca Freud, pemisahan ketakutan dan
kecemasan adalah dapat diterima secara psikologis, dimana perbedaan
psikologis utama antara kedua respon emosional tersebut adalah sifat akut
pada ketakutan dan kronis pada kecemasan. Kecemasn memperingatkan
adanya ancaman ekternal dan internal, dan memiliki kualitas dalam
menyelamatkan hidup. Pada tingkat yang lebih rendah kecemasan
memperingatkan ancaman cedera pada tubuh, rasa takut, keputusasaan,
kemungkinan hukuman, atau frustasi dari kebutuhan sosial atau tubuh,
perpisahan dari orang yang dicintai, gangguan pada keberhasilan atau status
seseorang, dan akhirnya ancaman pada kesatuan atau kebutuhan seseorang.
Kecemasan segera mengarahkan seseorang untuk mengambil langkah
yang diperlukan untuk mencegah ancaman atau meringankan akibatnya
(Kaplan, 1994). Kecemasan merupakan emosi dasar manusia disamping
gembira, sedih, marah, yang biasanya diikuti dengan perubahan-perubahan
somatik, fisiologik, otonomik, biokimia, dan perilaku yang spesifik
(Prawirohusodo, 1991).
Kadar kecemasan tertentu diperlukan dalam penampilan hidup manusia,
manusia dalam lingkungan yang serba berubah-ubah. Jenis kecemasan ini
disebut kecemasan normal. Apabila kecemasan makin berat intensitasnya
sehingga individu tidak mampu mengendalikan atau meramalkan situasi atau
lingkungannya, timbul sindroma klinik yang mengganggu kesehatan, kegiatan
sehari-hari dan kesejahteraan hidup. Kecemasan ini disebut kecemasan
patologik (Gelder, 1991; Prawirohusodo, 1991; Hunt, 1992).
Teori tentang gangguan kecemasan (Kaplan, 1994) adalah sebagai
berikut:
a. Teori psikologis
1) Teori Psikoanalitik
Kecemasan adalah suatu sinyal kepada ego bahwa suatu dorongan
yang tidak dapat diterima menekan untuk mendapatkan perwakilan
dan pelepasan sadar.
2) Teori Perilaku
Kecemasan adalah suatu respon yang dibiaskan terhadap stimuli
lingkungan spesifik.
3) Teori Eksistensial
Kecemasan adalah respon seseorang terhadap kehampaan eksistensi,
dimana tidak terdapat stimulus yang dapat diidentifikasikan secara
spesifik untuk suatu perasaan kecemasan yang kronis. Konsep inti
dari teori ini seseorang menjadi menyadari adanya kehampaan yang
menonjol di dalam dirinya, perasaan yang lebih mengganggu dari
b. Teori Biologis
Teori biologis dikembangkan dari penelitian praklinis dengan model
kecemasan pada binatang, peneliti pasien yang faktor biologisnya
dipastikan, berkembangnya pengetahuan tentang neorologi dasar, dan
kerja obat psikoterapik, macam-macam kecemasan adalah sebagai
berikut:
1) Fobia Sosial
Fobia Sosial juga disebut gangguan kecemasan sosial, ditandai
dengan ketakutan yang berlebihan terhadap penghinaan dan rasa
memalukan di berbagai lingkungan sosial, seperti berbicara di depan
publik. Tipe umum fobia sosial seringkali suatu keadaan yang kronis
dan menimbulkan ketidakberdayaan yang ditandai oleh penghindaran
fobik terhadap sebagaian besar situasi sosial.
2) Agorafobia
Agorafobia adalah ketakutan berada sendirian di tempat-tempat
publik. Agorafobia mungkin merupakan fobia yang paling
mengganggu kemampuan seseorang dalam lingkungan sosial di rumah
atau di dalam situasi kerja di kantor. Pasien agorafobia secara kaku
menghindari situasi dimana akan sulit untuk mendapatkan bantuan.
Mereka lebih suka disertai oleh sesorang teman atau anggota keluarga
di tempat-tempat tertentu seperti di jalan raya, toko yang sibuk, ruang
3) Gangguan Panik
Gangguan panik adalah gangguan yang ditandai dengan terjadinya
serangan panik yang spontan dan tidak diperkirakan. Serangan panik
adalah periode kecemasan atau ketakutan yang kuat dan relatif singkat
(biasanya kurang dari satu tahun), yang disertai oleh gejala somatik
tertentu seperti palpitasi dan takipnea. Serangan panik pertama
seringkali sama sekali spontan, walaupun serangan panik
kadang-kadang terjadi setelah luapan kegembiraan, kelelahan fisik, aktivitas
seksual, atau trauma emosional sedang.
4) Kecemasan Normal
Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia.
Perasaan tersebut ditandai oleh rasa ketakutan yang difus, tidak
menyenangkan, dan samar-samar serta seringkali disertai gejala
otonomik, seperti nyeri kepala, berkeringat, kekakuan pada dada, dan
gangguan lambung ringan. Kecemasan segera mengarahkan seseorang
untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah ancaman
atau meringankan akibatnya. Contoh menangkis ancaman di dalam
kehidupan sehari-hari adalah belajar giat untuk mempersiapkan diri
menghadapi ujian. Jadi kecemasan menyadarkan seseorang untuk
melakukan tindakan tertentu yang mencegah bahaya.
Pengukuran Tingkat Kecemasan
Tingkat kecemasan dapat diukur dengan menggunakan, Hamilton Rate
dari Taylor, dan Test Anxiety Quesionere dari Jarason, (Anwar, 1980), sebagai
berikut;
a. Hamillton Rate Scale For Anxiety (Tingkat Kecemasan)
Tingkat kecemasan dapat diukur dan dinilai dengan alat ukur yang
berupa kuesioner yaitu HRS For A (Hamillton Rating Scale For Anxiety)
yang telah dievaluasi reliabilitasnya dan validitasnya dapat dipercaya.
HRS-A bukan sebagai alat ukur diagnostik, melainkan untuk mengukur
intensitas kecemasan. Dimana terdapat 14 item pertanyaan yang
disesuaikan dengan tingkat keparahannya, bila jumlah skor minimum
hasil HRS-A = 18 maka disebut kecemasan ringan, skor minimum = 25
menderita kecemasan sedang dan bila lebih dari 30 maka disebut
kecemasan berat (Moses, 2000).
b. Manifes Anxiety Scale dari Taylor
Manifes Anxiety Scale dari Taylor (T-MAS), diciptakan dan
dikembangkan oleh Taylor pada tahun 1953, di Universitas Nortwestern.
Pada mulanya aitem-aitem T-MAS diambil dari mimpi, dari aitem 200
aitem mimpi, 60 aitem mimpi dipilih oleh Taylor dengan seleksi para ahli
psikologi klinis, akhirnya hanya 50 aitem yang digunakan untuk
mengungkapkan kecemasan, reliabilitas kuesioner ini telah diuji oleh
Taylor dengan menggunakan test-retest untuk tenggang waktu 3 minggu.
Indeks reliabilitas yang didapatkan ialah 89. Djuni Utari (1978) dan Sri
Hartati Yaman (1979), telah menerjemahkan T-MAS ke dalam bentuk
Kecemasan menurut T-MAS dibagi menjadi dua golongan, yaitu
seseorang dikatakan cemas menurut Taylor apabila jawaban ya yang
diperoleh setelah menjawab pertanyaan tersebut lebih dari atau sama
dengan 22, apabila responden menjawab ya lebih kecil dari 22 maka
dikatakan tidak cemas. dan apabila menjawab ya lebih dari atau sama
dengan 23 dinyatakan cemas. Pertanyaan ini diterangkan dalam T-MAS
yaitu Taylor Manifestasi Scale yang merupakan instrumen yang
digunakan untuk mengetahui keadaan kecemasan seseorang yang terdiri
dari 50 pertanyaan. Test ini merupakan test kecemasan standar dan dapat
diterima secara internasional. Sebagaimana juga telah dilakukan validitas
50 pertanyaan oleh Ino Wicaksono, 1993 dalam penelitian kecemasan
pada wartawan PWI Cabang Yogyakarta. dan keuntungan dari
pertanyaan tersebut adalah waktu pemeriksaan yang relatif cepat dan
penilaiannya dilakukan oleh responden sendiri.
Dampak dari Kecemasan
Prevalensi kecemasan sangat bervariasi pada berbagai macam populasi,
diperkirakan 2-4% penduduk pernah mengalami kecemasan (Sims, 1993).
Predisposisi terjadinya kecemasan adalah multifaktorial, sesuai dengan
pandangan bahwa manusia mahluk biopsikososial-spiritual (Hawari, 1992).
Kecemasan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh meliputi:
a. Akibat buruk terhadap aktifitas tubuh.
Istri yang cemas, yang bersumber pada gejala psikis dapat
mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Akibat buruk yang dapat terjadi
mengganggu aspek kehidupan lain adalah (Murtagh, 1998): terkurasnya
tenaga, pengendalian seksual, susah tidur, nafsu makan berkurang, dan
tidak ada semangat hidup.
b. Gejala psikis dan somatik
Manifestasi klinis kecemasan dapat berupa gejala psikis dan somatik.
Gejala psikis, misalnya : ketegangan, ketakutan, insomnia, gangguan
intelektual, emosi dan sikap. Sedangkan gejala somatik dikelompokan
menjadi:
1) Gejala ketegangan motorik: rasa gemetar, otot tegang atau kaku atau
pegel linu, tidak dapat diam, dan mudah lelah.
2) Gejala hiperaktivitas otonomik: nafas pendek atau nafas terasa berat,
jantung berdebar-debar, berkeringat atau telapak tangan basah
dingin, mulut kering, kepala pusing atau rasa melayang, mual,
mencret atau perut rasa tidak enak, muka rasa panas atau badan
menggigil, buang air kecil lebih sering, sukar menelan atau rasa
tersumbat di tenggorokan.
3) Gejala kewaspadaan berlebih dan penangkapan berkurang seperti:
perasaan menjadi peka, mudah terkejut atau kaget, sulit konsentrasi
atau pikiran menjadi kosong, sukar masuk masuk tidur atau sukar
mempertahankan tidur dan mudah tersinggung.
Patofisiolgi terjadinya kecemasan dapat digambarkan sebagaimana
dalam bagan Patofisiologi Sindrom Kecemasan (Maslim, 1991), berikut
Gambar 2.1. Bagan Patofisiologi Sindrom Kecemasan (Maslim,1991)
Menurut Maslim (1991), pada dasarnya hidup manusia selalu
berhubungan dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan alam
maupun lingkungan sosial budaya. Suatu kejadian di dalam lingkungan
(live event) dipersepsikan oleh panca indera, diberi arti dan dikoordinasi
respon terhadap kejadian tersebut oleh sistem syaraf pusat, proses
tersebut melibatkan jalur korteks serebri-sistem limbic-SAR (Sistem
Aktivasi Retikuler) hipotalamus yang memberikan impuls kepada
kelenjar hipofisis untuk mengekskresikan mediator hormonal yang lain
(Katekolamin).
c. Mengontrol Kecemasan
Untuk mengatasi kecemasan diperlukan kelompok kerja yang
menangani penderita kecemasan, meliputi:
Peristiwa
(Live Event) Individu
Pola Hidup (Live Style)
Sistem Syaraf Pusat
(Kortek Serebri - Hipotalamus – Sistem Limbic –SAR)
Sindrom Kecemasan Kelenjar Adrenalin
Sistem Syaraf Otonom Simpatis &Parasimpatis
1) Pelayanan informasi yang berhubungan dengan gejala kecemasan;
serangan panik, penyebab kecemasan, agorapobia, pengaruh
sampingan dari depresi, ketergantungan obat dan alkohol, dan
sebagainya.
2) Meditasi; yang berfungsi mengontrol emosi dan mencari ketenangan
batin.
3) Mempelajari bagaimana bekerja dan berpikir untuk menghindari
serangan panik dan kecemasan.
4) Konsultasi dengan dokter untuk dapat pengobatan yang tepat.
d. Terapi Kecemasan
Pada umumnya gangguan panik dan cemas adalah suatu gangguan
kronis. Dengan terapi, sebagian besar pasien mengalami perbaikan
dramatik pada gejala gangguan panik dan agorafobia. Dua terapi yang
efektif adalah farmakoterapi dan terapi kognitif dan perilaku. Terapi
keluarga dan kelompok dengan membantu pasien yang menderita dan
keluarganya untuk menyesuaikan dengan kenyataan bahwa pasien
menderita gangguan dan dengan psikososial yang telah dicetuskan oleh
gangguan (Kaplan, 1994). Terapi kecemasan dengan, sebagai berikut:
1) Farmakologi
Terapi dengan pemakaian obat-obatan sangat efektif untuk
menghilangkan kecemasan secara cepat, misalnya Benzodiazepine,
Inhibitor monoamin oksidase, trisiklik, dan tetasiklik. Jika efektif,
pengobatan farmakoterapi biasanya dilanjutkan selama 8 sampai 12
kronis dan kemungkinan seumur hidup akan kambuh jika pengobatan
dihentikan (Kaplan, 1994)
2) Kognitif dan perilaku
Terapi kognitif dan perilaku adalah terapi yang efektif untuk
gangguan panik. Berbagai laporan menyimpulkan bahwa terapi
kognitif dan perilaku dengan farmakologi adalah lebih efektif
dibandingkan pendekatan terapi masing-masing (Kaplan, 1994).
Dua pusat utama terapi kognitif untuk gangguan panik adalah
instruksi tentang kepercayaan salah satu pasien dan informasi tentang
serangan panik. Instruksi tentang kepercayaan yang salah berpusat
pada kecenderungan pasien untuk keliru menginterpertasikan sensasi
tubuh yang ringan sebagai tanda untuk ancaman penjelasan bahwa
serangan panik terjadi hanya terbatas dan tidak mengancam
kehidupan.
Relaksasi adalah untuk memasukkan suatu rasa pengendalian
pada pasien tentang tingkat kecemasan dan relaksasinya dengan
teknik relaksasi otot dan membayangkan situasi yang menimbulkan
relaksasi, pasien belajar teknik yang dapat membantu untuk melewati
serangan panik.
Hiperventilasi bersamaan dengan serangan panik kemungkinan
disertai dengan beberapa gejala, seperti rasa pening dan pingsan.
Satu pendekatan langsung untuk mengendalikan panik adalah
melatih pasien bagaimana mengendalikan dorongan untuk
3) Terapi Psikososial Lain
Terapi keluarga dengan gangguan panik dan agorafobia mungkin
terganggu selama perjalanan gangguan, sehingga terapi keluarga
yang diarahkan untuk mendidik dan mendukung seringkali
bermanfaat.
Psikoterapi berorientasi pada tilikan, terapi ini dapat bermanfaat
dalam pengobatan gangguan panik dan agorafobia. Pengobatan
memusatkan membantu pasien mengerti arti bahwa sadar dari
kecemasan, simbilisme situasi yang dihindari, kebutuhan untuk
merepresi impuls, dan tujuan sekunder dari gejala. Suatu pemecahan
konflik infatil awal dan oedipal dihipotesiskan berhubung dengan
resolusi stres sekarang (Kaplan, 1994)
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan
1) Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode
tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan
cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan
sebagian orang mengaitkan pendidikan dengan pengajaran atau
proses belajar mengajar. Pendidikan juga berlangsung secara formal
maupun nonformal (Syah, 1991). Dalam Dictionary of Psychology
pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan
perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan,
sikap dan sebagainya (Syah, 1991). Dengan demikian proses
pendidikan akan berpengaruh terhadap pengetahuan sikap dan
tingkah laku seseorang.
Kebiasaan seseorang dan pilihan gaya hidup seseorang sangat
berpengaruh terhadap kesehatannya. Terdapat pengaruh yang kuat
antara tingkat pendidikan dengan kesehatan. Dengan pendidikan
yang lebih baik memungkinkan seseorang secara ekonomi lebih
efisien dalam memanfatkan teknologi kesehatan dan pemeliharaan
kesehatan sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya (Grossman,
1999; Folland, 2001). Dengan demikian jika seorang ibu memiliki
pendidikan yang tinggi dia akan memelihara kesehatannya secara
baik, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk kesehatan lebih
efisien karena kemungkinan terhindar dari resiko sakit akibat lalai
menjaga kesehatannya.
Pendidikan bagi seorang individu merupakan pengaruh dinamis
dalam perkembangan jasmani, jiwa, perasaan dan susila. Sehingga
tingkat pendidikan yang berbeda akan memberikan jenis pengalaman
serta nilai-nilai hidup yang berbeda pula. Masalah ini dianggap
sebagai tekanan yang dapat menyebabkan krisis dan akan mengalami
kecemasan (Damaraji, 2001).
WHO dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan
tingkat pendidikan menengah keatas, hal ini dikarenakan responden
yang berpendidikan menengah ke atas berpikir lebih objektif dan
berwawasan luas, serta lebih mampu memikirkan penyelesaian
terhadap masalahnya.
Spielberger cit Slameto (1995) membedakan kecemasan menjadi
dua bagian; kecemasan sebagai suatu sifat (trait anxiety), yaitu
kecenderungan pada diri seseorang untuk merasa terancam oleh
sejumlah kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya, dan kecemasan
sebagai suatu keadaan (state enxiety), yaitu suatu keadaan atau
kondisi emosional sementara pada diri seseorang yang ditandai
dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang dihayati secara sadar
serta bersifat subyektif, dan meningginya aktifitas sistem saraf
otonom. Sebagai suatu keadaan, kecemasan biasanya berhubungan
dengan situasi-situasi lingkungan yang khusus, misalnya menghadapi
situasi tes.
2) Faktor Usia
Syaifudin (1998), menspesifikasikan umur ke dalam tiga
kategori, yaitu kurang dari 20 tahun (tergolong muda), umur 20-30
tahun (tergolong menengah) dan lebih dari 30 tahun (tergolong tua).
Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk
kehamilan dan persalinan adalah usia 20-30 tahun, atau mengandung
resiko yang rendah. Menurut Prawirohardjo (1997), mengemukakan
mencegah faktor predisposisi adanya kangker. Ada pula yang
berpendapat faktor umur yang lebih muda akan lebih mudah
menderita stres dari pada usia tua (Soewadi, 1987)
Hayles dan Feinlab (1980), menyatakan bahwa usia ikut
menentukan kecemasan yaitu kecemasan sering terjadi pada
golongan usia muda. Usia setengah tua menurut Roan (1979)
merupakan masa bebas. dan Prawirohusada (1989), menyatakan
bahwa banyak yang mempengaruhi timbulnya kecemasan pada diri
seseorang karena penyebab gangguan jiwa pada umumnya bersifat
multifaktorial.
3) Faktor Proses Persalinan
Kehamilan dan persalinan merupakan suatu masa kesetabilan
dan ketegangan emosional, serta suatu masa yang membahagiakan.
Hal utama yang mereka takutkan menjelang persalinan adalah rasa
sakit saat melahirkan, berapa lama berlangsungnya, komplikasi
penyulit seperti menggunakan vakum, operasi secsio caesaria,
perdarahan, bayi cacat dan kematian.
Wanita hamil yang akan mengalami proses persalinan baik
persalinan normal maupun dengan tindakan, pasti akan dihinggapi
campuran perasaan, yaitu: rasa takut, ragu-ragu, gelisah, bahagia,
dan cemas. Yang semuanya menjadi semakin intensif pada saat
mendekati masa-masa kelahiran. Adapun penyebab kegelisahan
(a) Takut Mati
Peristiwa kelahiran adalah suatu fenomena fisiologis yang
normal, namun tidak terlepas dari resiko dan bahaya kematian.
Bahkan pada proses kelahiran normal sekalipun disertai
kesakitan hebat. Peristiwa inilah yang menimbulkan ketakutan,
khususnya takut mati, baik kematian dirinya sendiri maupun
bayi yang akan dilahirkannya.
(b) Takut Riil atau Realistis
Setiap wanita hamil yang melahirkan bayinya merasakan
takut, hal ini bisa disebabkan oleh perasaan takut kalau bayinya
akan lahir dengan cacat atau lahir dengan kondisi yang
patologis. Segala macam ketakutan menyebabkan rasa
pesimistis, namun dibalik semua selalu ada harapan untuk bisa
menimang dan membelai bayinya, perasaan positif ini dilandasi
oleh pengetahuan intelektual. Pada umumnya persalinan dapat
diterima baik oleh ibu, bahkan diimbangi dengan harapan akan
memperoleh anak yang menjadi buah hatinya, menjadi pengikat
cinta kehidupan rumah tangga. Tetapi disisi lain ada wanita yang
menghadapi kehamilan dan persalinan dengan kecemasan.
4) Faktor penolong dan tempat persalinan
Ada beberapa pendapat yang dialami klien menurut Brice yaitu;
perasaan terhadap dokter dan bidan sering mendua. Mereka
dipercaya sekaligus dicurigai. Apakah mereka baik, bijaksana,
atau kurang pengetahuan. Apakah rumah sakit sebagai tempat
berlangsungnya kelahiran akan berfungsi sebagai tempat berlindung
atau akan menjadi semacam ban jalan yang digunakan dimana wanita
diproses melalui peralatan yang dikendalikan dari jarak jauh dalam
suatu kawasan yang asing dan peralatan yang menggelisahkan,
apakah wanita lain akan menjadi kawan atau mereka akan bersikap
masa bodoh dan tidak bersahabat (Brice, 1996).
Karena banyaknya persalinan dewasa ini berlangsung di rumah
sakit, maka ada kecemasan dengan berada di luar rumah. Dalam
suatu tempat yang asing dan dalam tangan-tangan orang asing,
rumah sakit adalah suatu tempat yang asing dan membingungkan
bagi orang yang belum biasa. Pikiran tentang pakaian seragam dan
keadaan darurat mungkin akan mengerikan, staff rumah sakit tidak
dikenal, mungkin menunjukkan sikap resmi dan sering ada rasa
ketakutan untuk tinggal sendiri (Brice, 1996). Pengaruh emosi setiap
kehamilan dan persalinan mempunyai sifat-sifat tersendiri