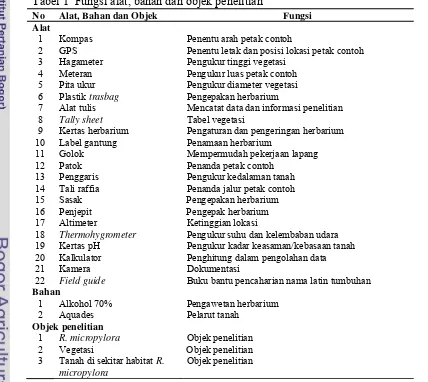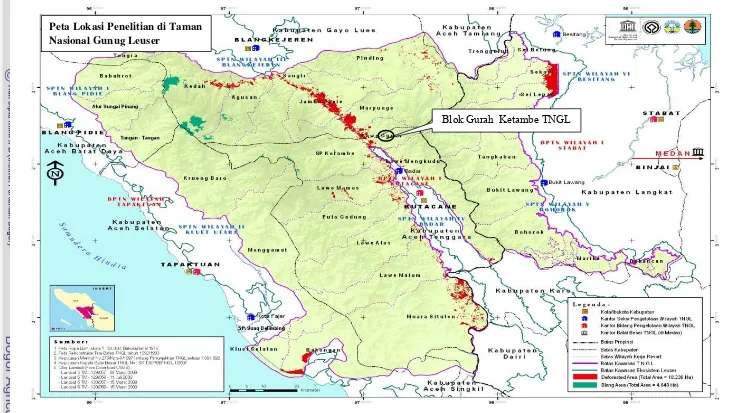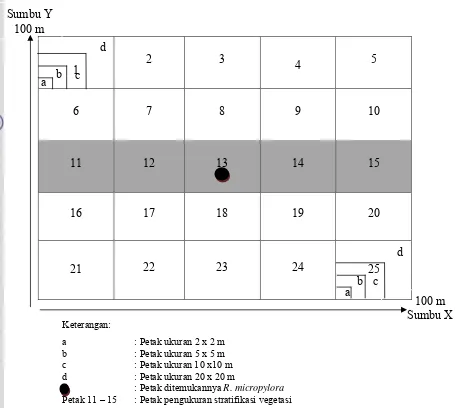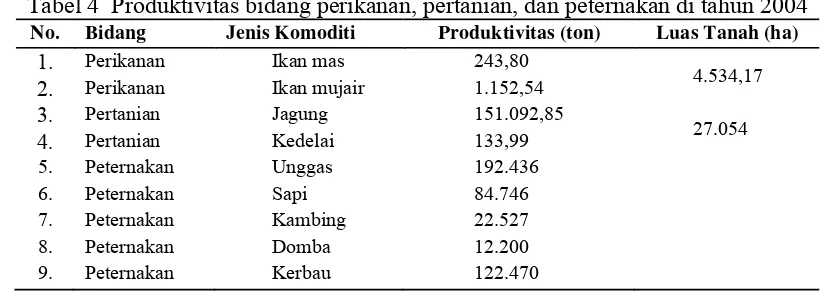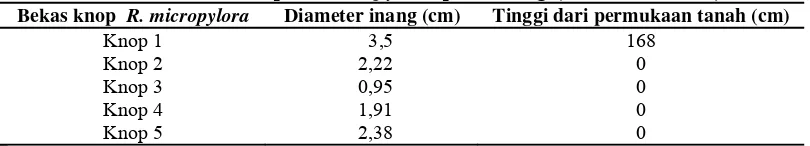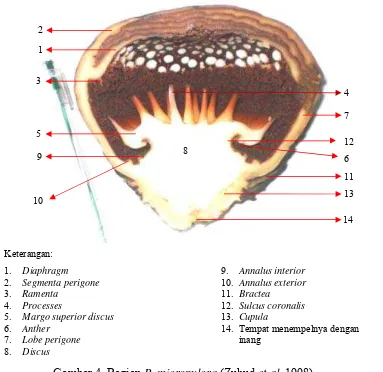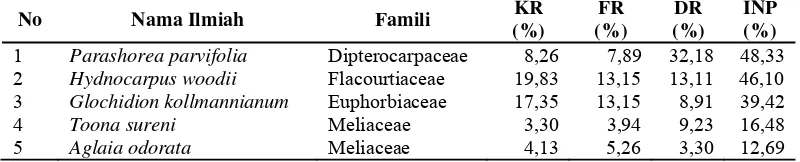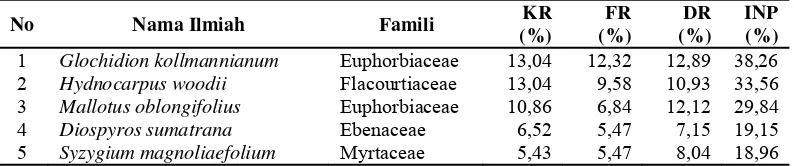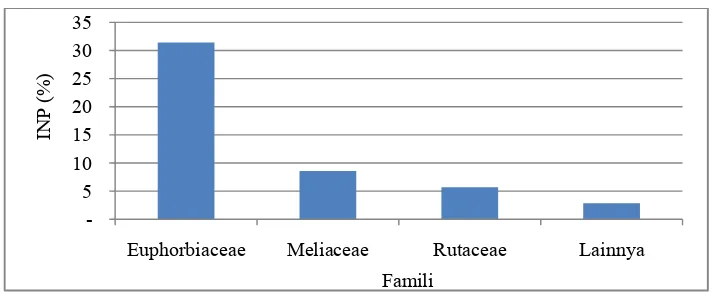NASIONAL GUNUNG LEUSER
MIKA ASRI
DEPARTEMEN
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN
NASIONAL GUNUNG LEUSER
MIKA ASRI
Skripsi
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Program Studi
Konservasi Sumberdaya Hutan
DEPARTEMEN
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN
Attitude toward the Conservation of Rafflesia micropylora Meijer in Gunung Leuser National Park. Under Supervision of AGUS HIKMAT and ERVIZAL A.M. ZUHUD.
Rafflesia micropylora Meijer is one of its protected plant species because of the scarcity and endemic in the Indonesian tropical rain forest. One of R. micropylora habitats found in Gunung Leuser National Park (GLNP), Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), is especially under the pressure and threat of human activity. Therefore, the presence of R. micropylora in nature must be preserved. The objective of this study was to determine the condition of R. micropylora, habitat conditions and communities attitudes to the conservation of R. micropylora. The expected benefits as input in the conservation efforts for R. micropylora in Southeast Aceh NAD GLNP.
The research was conducted in Block Gurah Ketambe GLNP serve from June to August 2010. The data was collected by using purposive sampling method with a single plot of 1 ha. The measurement of knob conditions, biotic and abiotic conditions, and communities attitudes were done in the block.
The results showed that the condition of R. micropylora was found one knob. The condition of vegetation in Block Gurah Ketambe GLNP included lowland forest vegetation which was dominated by Parashorea parvifolia species of Dipterocarpaceae. Canopy strata were A, B, and C with the coverage of title at 55.15%. R. micropylora grown on the host species Tetrastigma lanceolarium. The existing animals in this study are orangutans, wild boar, Capricornis sumatraensis, deer, and sun bears. Abiotic (physical) conditions R. micropylora habitat located at an altitude of 510 m.dpl with slope 0-45°. Soil has a pH neutral to slightly alkali with a texture-sandy clay loam with reddish-brown color. Daily temperatures are 27-28°C with a humidity of 85-97%. Community attitudes toward forest areas was that 30 respondents were more familiar with and know the information about R. micropylora from media and discussion of other people. Communities will support the conservation of R. micropylora although some have a little appreciation and don’t really feel the presence of R. micropylora. The habitat of R. micropylora was disturbed by activities of the jungle in form of path tracking and animal observation point. Management activities of R. micropylora habitat was considered ineffective related to the encroachment of forests and cutting T. lanceolarium.
The results mentioned above describe the condition of R. micropylora, which was in danger due to a variety of activities. The R. micropylora habitat was in the lowland forest vegetation types dominated by the species P. parvifolia. Public attitudes toward forests usually support the conservation of R. micropylora, it was necessary to give information to the communities so that they take care and monitor the population and R. micropylora habitat.
Terhadap Konservasi Rafflesia micropylora Meijer di Taman Nasional Gunung Leuser. Di bawah bimbingan AGUS HIKMAT dan ERVIZAL A.M. ZUHUD.
Rafflesia micropylora Meijer merupakan salah satu spesies tumbuhan yang dilindungi karena kelangkaan dan keendemikannya yang terdapat di hutan hujan tropika Indonesia. Salah satu habitat R. micropylora yaitu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengalami tekanan dan ancaman terutama aktivitas manusia. Oleh karena itu, keberadaan R. micropylora di alam harus dijaga kelestariannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi R. micropylora, kondisi habitat dan sikap masyarakat terhadap konservasi R. micropylora. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai masukan dalam upaya konservasi R. micropylora di TNGL Aceh Tenggara NAD.
Penelitian ini dilaksanakan di Blok Gurah Ketambe TNGL pada bulan Juni-Agustus 2010. Pengambilan data menggunakan metode purposive sampling dengan petak tunggal seluas 1 ha. Dalam petak tersebut dilakukan pengukuran kondisi knop, kondisi biotik dan abiotik, dan sikap masyarakat sekitar habitat R. micropylora.
Hasil penelitian menunjukkan kondisi R. micropylora hanya ditemukan satu knop yang lepas dari inangnya. Kondisi vegetasi di Blok Gurah Ketambe TNGL termasuk vegetasi hutan dataran rendah yang didominasi oleh spesies Parashorea parvifolia dari famili Dipterocarpaceae. Strata tajuk vegetasi meliputi strata A, B, dan C dengan nilai penutupan tajuk sebesar 55,15%. R. micropylora tumbuh pada spesies inang Tetrastigma lanceolarium. Satwa yang ada di lokasi penelitian berupa orangutan, babi hutan, kambing hutan, rusa, beruang madu baik ditemukan langsung maupun berdasarkan informasi masyarakat. Kondisi abiotik (fisik) habitat R. micropylora berada pada ketinggian 510 m dpl dengan kelerengan 0-45°. Tanah memiliki pH netral hingga agak basa dengan tekstur geluh lempungan-pasiran yang berwarna cokelat muda-kemerahan. Suhu harian 27-28°C dengan kelembaban 85-97%. Masyarakat sekitar hutan lebih banyak mengenal dan mengetahuai R. micropylora dari berbagai media dan pembicaraan sehari-hari. Sikap masyarakat umumnya mendukung terhadap konservasi R. micropylora. Aktivitas yang mengganggu habitat R. micropylora yaitu adanya jalur jungle tracking dan jalur pengamatan satwa. Aktivitas pengelolaan habitat R. micropylora dinilai belum efektif dilihat dari adanya perambahan hutan dan pemotongan T. lanceolarium.
Hasil tersebut di atas menggambarkan kondisi R. micropylora berada dalam keterancaman akibat berbagai aktivitas. Habitat R. micropylora berada dalam tipe vegetasi hutan dataran rendah yang didominasi oleh spesies P. parvifolia. Sikap masyarakat sekitar hutan secara umum mendukung konservasi R. micropylora. Maka perlu kiranya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, menjaga dan memantau populasi R. micropylora dan habitatnya.
Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Rafflesia micropylora Meijer di Taman Nasional Gunung Leuser adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, Maret 2011
Mika Asri
© Hak cipta milik IPB tahun 2011 Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
mencantumkan atau menyebut sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya
NIM : E34060577
Menyetujui:
Pembimbing I, Pembimbing II,
Dr. Ir. Agus Hikmat, M.Sc Prof. Dr. Ir. Ervizal A. M. Zuhud, MS NIP. 19620918 198903 1 002 NIP. 19590618 198503 1 003
Mengetahui:
Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor
Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS NIP. 19580915 198403 1 003
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul Kondisi Habitat dan Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Rafflesia micropylora Meijer di Taman Nasional Gunung Leuser. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Skripsi ini mengupas tentang kondisi R. micropylora, habitat R. micropylora, dan sikap masyarakat sekitar hutan terhadap R. micropylora yang
terdapat di Blok Gurah Ketambe TNGL Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengelolaan R. micropylora di TNGL. Akhirnya, tentu skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna dalam penyempurnaan skripsi ini.
Bogor, Maret 2011 Penulis
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 1 April 1988 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Jimidan dan Ibu Hamidah.
Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Kuta Pasir pada tahun 2000. Pada tahun 2003 penulis lulus dari SLTP Negeri 4 Badar. Kemudian pada tahun 2006 penulis lulus dari SMA Negeri Perisai Kuta Cane dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih dan diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.
Selama studi di IPB, penulis aktif di Organisasi Kemahasiswaan yakni sebagai Staf Biro Sosial Lingkungan, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) IPB (2007/2008), Staf Biro Informasi dan Komunikasi, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) IPB (2008/2009), Kelompok Pemerhati Flora “Rafflesia” HIMAKOVA (2007-2009), dan Anggota Ikatan Mahasiswa Tanah Rencong (IMTR) Aceh, serta penulis juga pernah mengikuti berbagai seminar dan kegiatan. Penulis melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Cagar Alam Leuweung Sancang dan Cagar Alam Kamojang Kabupaten Garut. Penulis juga melakukan Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Sukabumi, serta penulis melakukan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKL-P) di Taman Nasional Meru Betiri (Jember dan Banyuwangi) Jawa Timur.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmatnya dan syalawat beserta salam penulis hadiahkan pahalanya kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga terselesainya penulisan karya ilmiah ini. Selain itu, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:
1. Dosen pembimbing Dr. Ir. Agus Hikmat, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Ervizal A M Zuhud, MS atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing, membagi ilmu, dan dukungan materil maupun moril lainnya sampai penulis menyelesaikan tugas akhir.
2. Dosen penguji Ir. Muhdin, MSc.F.Trop dari Departemen MNH, Effendi Tri Bahtiar, S.Hut, M.Si dari Depertemen HHT, dan Dr. Ir. Istomo, MS dari Depertemen SVK yang telah menguji dan memberikan saran dalam penyempurnaan penulisan tugas akhir ini.
3. Orangtua tercinta Bapak Jimidan dan Ibu Hamidah beserta keluarga tercinta Abang Supian, Abang Pratu Robianto, adik tersayang Rela Daini, dan kepada Kakak Anita Ritawati serta Kakak Reza Maretha, S.Pd atas dukungan cinta, kasih sayang, dan motivasinya yang selama ini telah diberikan.
4. Pihak pengelola BTNGL Bapak Harijoko selaku kepala TNGL, Bapak ST Mangarahon, dan Abang Zulfan serta seluruh pegawai pengelola TNGL, terimakasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
5. Pihak BPKEL Bapak Isya, Bapak Usman, Bapak Mat Plin, Abang Anto, dan Saiful serta seluruh pihak BPKEL terimakasih atas bantuanya selama penulis melakukan penelitian.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Kehutanan khusnya Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata khususnya dan Dosen TPB yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bakti ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
DAFTAR ISI
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Taksonomi dan Morfologi Rafflesia micropylora ... 3
2.2 Ekologi dan Habitat R. micropylora ... 4
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 9
4.8.2 Fauna ... 22
4.8.3 Ekowisata ... 23
4.9 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat ... 24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Kondisi Populasi Rafflesia micropylora Meijer ... 27
5.2 Kondisi Habitat R. micropylora ... 30
5.2.1 Kondisi biotik ... 30
5.2.2 Kondisi abiotik (fisik) ... 45
5.3 Sikap Masyarakat TNGL Terhadap R. micropylora ... 49
5.3.1 Karakteristik responden ... 49
5.3.2 Sikap konservasi masyarakat terhadap R. micropylora ... 50
5.3.3 Aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap habitat R. micropylora ... 52
5.3.4 Aktivitas pengelolaan habitat R. micropylora ... 53
5.3.5 Usulan program konservasi R. micropylora ... 55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 58
6.2 Saran ... 58
DAFTAR PUSTAKA ... 59
2. Tingkat pertumbuhan dan kriteria vegetasi pada setiap petak contoh ... 12 3. Luas tanah berdasarkan fungsi pemanfaatan tanah khusus tanaman
padi ... 25 4. Produktivitas bidang perikanan, pertanian, dan peternakan di tahun
2004 ... 25 5. Kondisi bekas bunga R. micropylora pada inang (T. lanceolarium) .... 6. Lima spesies tingkat pohon yang memiliki tingkat INP tinggi ... 7. Lima spesies tingkat tiang yang memiliki tingkat INP tinggi ... 32 8. Lima spesies tingkat pancang yang memiliki tingkat INP tinggi ... 9. Lima spesies tingkat semai/tumbuhan bawah yang memiliki tingkat
INP tinggi ... 10.Keanekaragaman spesies tumbuhan pada petak habitat R. micropylora 35 11.Perbandingan spesies-spesies vegetasi tingkat pohon (diameter > 10
cm) pada berbagai habitat Rafflesia di Sumetera ... 37 12.Perbandingan spesies-spesies vegetasi tingkat permudaan anakan
12
12.Bentuk batang Tetrastigma lanceolarium ... 43
13.T. lanceolarium mati akibat pohon yang roboh ... 44
14.Orangutan sedang melakukan aktivitas di pohon-pohon ... 45
15.Jalur lintas jungle tracking pada habitat R. micropylora ... 16.Bentuk pembukaan lahan yang mengancam kehilangan R. micropylora 53 17.Bentuk pembukaan lahan kawasan TNGL untuk perkebunan ... 54
DAFTAR GAMBAR
No. Halaman 1. Peta lokasi penelitian TNGL ... 102. Bentuk petak contoh ... 3. Kondisi knop R. micropylora ... 28
4. Bagian R. micropylora (Zuhud et al. 1998). ... 29
5. Persentase famili tingkat pohon berdasarkan INP ... 31
6. Persentase famili tingkat tiang berdasarkan INP ... 33
7. Persentase famili tingkat pancang berdasarkan INP ... 34
8. Persentase famili tingkat semai/tumbuhan bawah berdasarkan INP .... 35
9. Bentuk profil hutan vertikal dan horizontal tingkat pohon ... 40
10.Kondisi habitat R. micropylora ... 41
11.Penyebaran T. lanceolarium pada petak contoh pengamatan ... 42
DAFTAR LAMPIRAN
No. Halaman
1. Hasil analisis vegetasi tingkat pohon di Blok Gurah TNGL ... 63 2. Hasil analisis vegetasi tingkat tiang di Blok Gurah TNGL ... 64 3. Hasil analisis vegetasi tingkat pancang di Blok Gurah TNGL ... 65 4. Hasil analisis vegetasi tingkat semai/tumbuhan bawah di Blok Gurah
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberadaan Rafflesia di alam yang memiliki keunikan merupakan warisan
dunia (world heritage) dari dunia tumbuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 7 tanggal 27 juni 1999 tentang pengawetan spesies tumbuhan dan satwa.
Semua spesies Rafflesia merupakan tumbuhan yang dilindungi karena kelangkaan
dan keendemikannya yang terdapat di hutan hujan tropika Indonesia. Salah satu
spesies Rafflesia adalah Rafflesia micropylora Meijer yang tumbuh di Taman
Nasional Gunung Leuser (TNGL), Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) (Nais 2001). Sriyanto (2005) melaporkan bahwa TNGL mengalami
tekanan dan ancaman berupa perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran
hutan, spesies invasif, tuntutan hak masyarakat, dan penggunaan lahan non
konservasi. Semakin berkurangnya luasan hutan TNGL maka keterancaman
habitat R. micropylora akan semakin tinggi.
Kehidupan R. micropylora dalam ekosistem ditentukan oleh faktor biotik
dan abiotik. Faktor biotik tersebut meliputi tumbuhan inangnya dari marga
Tetrastigma, tipe vegetasi, hewan penyerbuk dan penyebar, dan pengaruh
manusia. Faktor abiotik diantaranya topografi, iklim, dan tanah. Steenis (1971)
diacu dalam Syahbuddin (1981) menyebutkan biji Rafflesia secara alamiah dapat
tumbuh pada tumbuhan inangnya melalui infeksi pada luka-luka yang terjadi
karena injakan binatang berkuku, seperti gajah, tapir, badak dan lain sebagainya.
Tingginya kemungkinan kepunahan Rafflesia di alam dikarenakan
perusakan habitat melalui illegal logging, perambahan hutan, dan tuntutan hak
masyarakat. Spesies R. micropylora merupakan tumbuhan holoparasit yang
berumah dua, sehingga proses perkembangbiakannya cukup rumit. Disamping itu,
terjadinya gangguan pada tumbuhan inang dan knopnya mudah rusak akan
menyebabkan kematian Rafflesia (Ekawati 2001). Kondisi tersebut menyebabkan
populasi Rafflesia di alam semakin menjadi langka.
Keberadaan R. micropylora di alampatut dipertahankan kelestariannya dari
inang dan R. micropylora akan hidup dengan baik. Kelestarian hutan secara
keseluruhan membawa dampak pada berbagai tumbuhan lain maupun satwa yang
sangat mendukung kehidupan R. micropylora.
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1) Mengetahui kondisi populasi R. micropylora.
2) Mengetahui kondisi habitat R. micropylora.
3) Mengetahui sikap masyarakat sekitar TNGL terhadap konservasi R.
micropylora.
1.3 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan acuan dalam
konservasi spesies R. micropylora bagi pengelola dan masyarakat di TNGL, Aceh
Rafflesia memulai pertumbuhannya dengan pembentukan kecambah yang
terdapat di kulit akar dan berkembang menjadi benang-benang (hifa) yang
selanjutnya terjadi pembengkakan dan terbentuk knop pada permukaan tumbuhan
inang. Knop yang terbentuk dengan inang akan membesar dan robek yang berarti
bunga R. micropylora tersebut mekar. R. micropylora memiliki diameter bunga
30-60 cm, kelopak bunga berwarna jingga tua-merah gelap (Zuhud et al. 1998). Spesies : Rafflesia micropylora Meijer
Marga : Rafflesia
Suku : Rafflesiaceae Bangsa : Aristolochiales Anak Klas : Dicotyledone Klas : Angiospermae Divisi : Spermathophita
Marga Rafflesia pertama kali ditemukan tahun 1818 di Bengkulu oleh Dr.
Yoseph Arnold yang dinamai oleh Robert Brown tahun 1820 dalam Transaction
Linnean Society vol. XIII (Kooders 1981 diacu dalam Zuhud et al. 1993).
Selanjutnya dikatakan oleh Kuijt (1969) diacu dalam Zuhud et al. (1998) bahwa
genus Rafflesia termasuk ke dalam famili Rafflesiaceae yang terdiri dari delapan
marga (genera) yang beranggotakan sekitar 50 spesies, umumnya terdapat di
daerah tropik Indo-Malaysia. Spesies tersebut antara lain Rafflesia, Rhizanthes,
dan Sapria. Menurut klasifikasi dunia tumbuhan Taksonomi Rafflesia (Becker et
al. 1963 diacu dalam zuhud et al. 1998) yaitu:
2.1 Taksonomi dan Morfologi Rafflesia micropylora
TINJAUAN PUSTAKA
BAB II
R. micropylora dikenal sebagai tumbuhan holoparasit, yaitu tumbuhan yang
sepenuhnya tergantung pada tumbuhan lain untuk kebutuhan makanannya.
Tumbuhan inang dari R. micropylora adalah tumbuhan liana dari spesies
Tetrastigma lanceolarium. Rafflesia tidak mempunyai butir-butir klorofil, tetapi
mempunyai akar hisap (haustorium) yang berfungsi sebagai penyerap nutrisi yang
Spesies R. micropylora merupakan sebuah keajaiban di dunia tumbuhan
yang memiliki sifat dan cara hidup yang menakjubkan dengan keindahan, cara
hidup yang unik, dan ukuran bunga yang besar. Bunga R. micropylora memiliki
lima buah kelopak bunga, tanpa batang dan daun. Ukuran kuncup dan kelopak
bunga Rafflesia berbeda-beda setiap spesiesnya (Salleh 1991).
2.2 Ekologi dan Habitat R. micropylora
Secara umum ekologi R. micropylora ditentukan oleh dua komponen yaitu
komponen biotik termasuk aktivitas manusia dan komponen abiotik (fisik).
Komponen biotik dari habitat R. micropylora salah satunya adalah tumbuhan
inang. Faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan Rafflesia yaitu iklim, tanah
dan topografi. Rafflesia yang termasuk tumbuhan holoparasit hidup pada
perakaran dan batang tumbuhan liana dari spesies T. lanceolarium (Zuhud et al.
1998).
Rafflesia tumbuh di berbagai tipe habitat yang berbeda-beda mulai dari
vegetasi hutan pantai hingga pegunungan. Karakteristik vegetasi dapat dilihat dari
asosiasi vegetasi hutan hujan tropika primer dengan keanekaragaman yang tinggi
dan struktur vegetasi horizontal dan vertikal yang khas. Karakteristik tanah berupa
jenis tanah, pH tanah, kandungan zat hara, suhu, tekstur dan struktur tanah,
kapasitas tukar kation, organisme tanah, tebal dan berat serasah, kandungan bahan
organik dan kelembaban (Zuhud et al. 1998).
2.3 Penyebaran R. micropylora
Zuhud et al. (1998) mengatakan bahwa sampai saat ini telah berhasil di
identifikasi spesies Rafflesia sebanyak 17 spesies yang ada di dunia dan 12 spesies
memiliki penyebaran di Indonesia. Daerah yang menjadi habitatnya yaitu hutan
hujan tropika. Spesies Rafflesia yang tersebar di Pulau Sumatera yaitu R. arnoldii
var. atjehensis, R. hasseltii, R. gadutensis, R. micropylora, dan R. rochussenii.
Dari kelima spesies Rafflesia yang terdapat di Sumatera, ada tiga spesies yang
terdapat di daerah NAD yaitu R. arnoldii var. atjehensis, R. micropylora, dan R.
2.4 Tumbuhan Inang
Tumbuhan inang dari Rafflesia merupakan tumbuhan liana dari marga
Tetrastigma. Tetrastigma termasuk kedalam famili Vitaceae, memiliki 95 spesies
dengan penyebaran 57 spesies di Malesia, empat spesies di Taiwan, 12 spesies di
India, empat spesies di Thailand, 22 spesies di Indocina, dan 12 spesies di
Malaysia (Lattif 1984 diacu dalam Hikmat 1988). Tidak semua spesies
Tetrastigma merupakan tumbuhan inang dari Rafflesia.
Berdasarkan klasifikasi dunia tumbuhan Backer dan Bakhuizen van Den
Brink (1963) diacu dalam Jamil (1998), Tetrastigma lanceolarium dikelompokkan
dalam:
Divisi : Spermathophyta
Klas : Angiospermae
Anak Klas : Dicotyledonae
Bangsa : Rhamnales
Suku : Vitaceae
Marga : Tetrastigma
Spesies : T. lanceolarium
T. lanceolarium merupakan tumbuhan berbiji dan berumah dua, memiliki
anakan yang hampir mirip dengan semak-semak maupun pohon muda. Perbedaan
tersebut terlihat jika telah terjadi pemanjangan pada bonggol (internode) bagian
atas dan batang menjadi lentur sehingga mudah melengkung dan mulai
membutuhkan pohon penyokong untuk mendapatkan sinar matahari dengan cepat.
Penyokong membantu mempercepat pertumbuhan internode sehingga ketika
penyokong tidak tersedia maka pertumbuhannya akan mengalami perlambatan
dan kemungkinan akan jatuh ke tanah dan menjalar untuk mencari penyokong
kembali. Tetrastigma yang menjalar ke atas akan menempati posisi yang teratas
pada tajuk pohon. Penyokong yang digunakan dapat berupa pohon, semak
maupun batang liana lainnya (Hernidiah 1999).
Sistem pertumbuhan dan perkembangan perakaran Tetrastigma bersifat
horizontal, tidak jauh dari permukaan tanah dan termasuk ke dalam lapisan top
soil yang kaya akan zat hara, dan perakarannya memiliki percabangan yang
dicirikan seperti T. papilosum bentuk batang bulat dan T. lanceolarium batang
pipih yang sering menjadi habitat inang R. micropylora. Spesies T. lanceolarium
memiliki jaringan kayu yang lunak, berpori-pori dan besar, berkadar air tinggi,
kulit batang dan akar berserabut tebal dan mudah pecah-pecah membentuk alur,
sebagian besar inang banyak mengandung air (Jamil et al. 2002).
2.5 Status Konservasi R. micropylora
Kelangkaan Rafflesia di habitatnya menyebabkan Rafflesia dimasukkan
kedalam perlindungan spesies tumbuhan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pertanian No. 6/PMP/1961 tanggal 9 Agustus 1961 tentang larangan
penjualan spesies Rafflesia, serta melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 27
Juni 1999 tentang pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, dengan
bentuk-bentuk pemanfaatannya.
2.6 Sikap Masyarakat
Sikap adalah kondisi mental yang kompleks yang melibatkan keyakinan
dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Sikap terdiri
dari komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan dan
dipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi respon sesuai dan tidak sesuai),
dan emosi (menyebabkan respon-respon yang konsisten (Ramadhani 2006).
Menurut Rahayuningsih (2008), faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap
yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting
(Significant Others), media massa, institusi/lembaga pendidikan dan agama, dan
faktor emosional.
Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu
sama lain (Supsiloani 2008). Sehingga sikap masyarakat merupakan kondisi
mental masyarakat yang melibatkan keyakinan dan perasaan, serta disposisi untuk
bertindak dengan cara tertentu terhadap respon yang diterima.
2.7 Taman Nasional
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, taman nasional adalah kawasan
yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sistem zonasi pada taman nasional
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006, zona taman
nasional terdiri dari:
1) Zona inti, merupakan bagian kawasan taman nasional yang mutlak
dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh
aktivitas manusia.
2) Zona rimba, merupakan bagian taman nasional yang karena letak, kondisi
dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti
dan zona pemanfaatan.
3) Zona pemanfaatan, merupakan bagian dari kawasan taman nasional yang
dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
4) Zona lain, antara lain: zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi,
budaya dan sejarah, dan zona khusus.
Secara umum taman nasional memiliki fungsi dan peranan (Widada 2008),
antara lain:
1) Sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan
2) Sebagai wahana pendidikan lingkungan
3) Mendukung pengembangan budidaya tumbuhan dan penangkaran satwa
4) Wahana kegiatan wisata alam
5) Sumber plasma nutfah dan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa
6) Melestarikan ekosistem hutan sebagai pengatur tata air dan iklim mikro
serta sumber mata air bagi masyarakat di sekitar kawasan taman nasional
Kriteria pengelolaan taman nasional yang efektif (Ditjen PHKA 2006 diacu
dalam Widada 2008) antara lain:
1) Perencanaan, meliputi: kriteria perumusan tujuan pengelolaan taman
nasional, kriteria status hukum dan pemanfaatan kawasan, kriteria
pengelolaan data dan informasi, kriteria penataan zona taman nasional, dan
kriteria perencaan pengelolaan.
2) Pelaksanaan, meliputi: kriteria perlindungan dan pengamanan kawasan,
kriteria konservasi spesies dan ekosistem, kriteria rehabilitasi kawasan dan
kepentingan pengelolaan, pemanfaatan dan pengusahaan, kriteria
pemanfaatan taman nasional untuk penelitian dan ilmu pengetahuan,
kriteria pemanfaatan taman nasional untuk pendidikan dan kesadaran
konservasi, kriteria pemanfaatan taman nasional untuk pariwisata alam dan
rekreasi, kriteria pemanfaatan taman nasional untuk produk jasa
lingkungan, kriteria pemanfaatan taman nasional untuk menunjang
kepentingan religi, tradisional, budidaya/plasma nutfah/materi kimia aktif
dan bahan baku obat/hasil hutan non kayu, dan kriteria pengembangan
daerah penyangga.
3) Pengorganisasian, meliputi: kriteria administrasi pengelola, kriteria
pengembangan koordinasi dan integrasi, dan kriteria pengembangan
Tabel 1 Fungsi alat, bahan dan objek penelitian
Alat, bahan dan objek penelitian yang digunakan menurut fungsinya tersaji
pada Tabel 1.
3.2 Alat, Bahan dan Objek Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Blok Gurah Ketambe, Kawasan Taman
Nasional Gunung Leuser (TNGL), Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) (Gambar 1). Waktu penelitian dilaksanakan selama 2
bulan yaitu bulan Juni-Agustus 2010. 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
METODE PENELITIAN
BAB III
No Alat, Bahan dan Objek Fungsi Alat
1 Kompas Penentu arah petak contoh
2 GPS Penentu letak dan posisi lokasi petak contoh 3 Hagameter Pengukur tinggi vegetasi
4 Meteran Pengukur luas petak contoh 5 Pita ukur Pengukur diameter vegetasi
6 Plastik trasbag Pengepakan herbarium 7 Alat tulis Mencatat data dan informasi penelitian
8 Tally sheet Tabel vegetasi
9 Kertas herbarium Pengaturan dan pengeringan herbarium 10 Label gantung Penamaan herbarium
11 Golok Mempermudah pekerjaan lapang 12 Patok Penanda petak contoh 13 Penggaris Pengukur kedalaman tanah 14 Tali raffia Penanda jalur petak contoh
15 Sasak Pengepakan herbarium
16 Penjepit Pengepak herbarium 17 Altimeter Ketinggian lokasi
18 Thermohygrometer Pengukur suhu dan kelembaban udara 19 Kertas pH Pengukur kadar keasaman/kebasaan tanah 20 Kalkulator Penghitung dalam pengolahan data
21 Kamera Dokumentasi
22 Field guide Buku bantu pencaharian nama latin tumbuhan Bahan
1 Alkohol 70% Pengawetan herbarium
2 Aquades Pelarut tanah
Objek penelitian
1 R. micropylora Objek penelitian 2 Vegetasi Objek penelitian 3 Tanah di sekitar habitat R.
micropylora
10
Peta Lokasi Penelitian di Taman Nasional Gunug Leuser
Blok Gurah Ketambe TNGL
3.3 Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer berupa:
(1) Kondisi populasi R. micropylora.
(2) Kondisi habitat R. micropylora; berupa data biotik (kondisi vegetasi,
tumbuhan inang, aktivitas satwaliar) dan abiotik (penutupan serasah hutan,
tanah, suhu, kelembaban).
(3) Sikap masyarakat terhadap keberadaan R. micropylora di TNGL.
Data sekunder berupa keadaan lokasi penelitian, diperoleh dari literatur atau
pustaka yang telah ada.
3.4 Metode Pengambilan Data 3.4.1 Cara penetapan petak contoh
Pengambilan petak contoh ditetapkan secara purposive sampling
berdasarkan penemuan R. micropylora pada petak tunggal.
3.4.2 Bentuk dan ukuran petak contoh
Pengamatan dan pengumpulan data vegetasi sekitar R. micropylora
dilakukan pada petak tunggal dengan luas 1 ha (100 x 100 m), kemudian petak
tersebut dibagi-bagi lagi menjadi petak kecil berukuran 20 x 20 m (Gambar 2),
dengan kategori vegetasi dan luas petak ukur seperti tersaji pada Tabel 2.
a b c
: Petak ditemukannya R. micropylora Petak 11 – 15 : Petak pengukuran stratifikasi vegetasi
Gambar 2 Bentuk petak contoh.
Tabel 2 Tingkat pertumbuhan dan kriteria vegetasi pada setiap petak contoh
Petak
Permudaan dari kecambah sampai tinggi < 150 cm/tumbuhan yang ketika dewasa tidak akan setara atau di bawah tinggi pohon.
2 x 2
b Pancang dan semak Permudaan dengan tinggi ≥ 150 cm sampai anakan berdiameter < 10 cm.
5 x 5
3.4.3 Kondisi populasi R. micropylora
Kondisi yang diamati meliputi: jumlah knop/bunga R. micropylora yang
masih hidup dan yang telah mati, jumlah bunga mekar, diameter knop dan bunga
mekar, jenis kelamin bunga mekar, dan tempat tumbuh R. micropylora pada organ
inang akar/batang yang ditempelinya, dan posisi inang pada petak contoh.
Pengamatan dilakukan pada petak ukuran 1 ha.
3.4.4 Kondisi habitat R. micropylora
3.4.4.1 Data biotik
3.4.4.1.1 Kondisi vegetasi
Pengambilan data vegetasi dilakukan untuk tingkat pohon, tiang, pancang,
dan semai, serta pada liana, semak dan tumbuhan bawah. Data vegetasi berupa
nama spesies, diameter, jumlah individu. Nama ilmiah spesies tumbuhan yang
ditemukan diindentifikasi melalui buku field guide tumbuhan lapang, dan untuk
yang tidak teridentifikasi di lapang maka dibuatkan dalam herbarium untuk
diidentifikasi selanjutnya ke Herbarium Bogoriensis LIPI Bogor.
Selain itu dilakukan pembuatan diagram profil arsitektur hutan untuk
mengetahui lapisan-lapisan tajuk pohon (stratifikasi) dan penutupan tajuk dari
petak contoh yang diambil dengan ukuran 0,2 ha (20 x 100 m). Profil arsitektur
hutan yang digambarkan dan semua pohon berdiameter ≥ 20 cm diukur tinggi
pohon dan diameter proyeksi tajuk, serta kedudukannya dalam sumbu x dan y.
3.4.4.1.2 Tumbuhan inang (Tetrastigma lanceolarium)
Pengambilan data tumbuhan inang (T. lanceolarium) dilakukan pada petak
contoh yang ditemukan R. micropylora. Inang yang ditemukan dihitung
banyaknya batang, tinggi batang, diameter batang, spesies inang, spesies dan
tinggi pohon yang dipanjat serta pengamatan terhadap kondisi fisik batang dan
daun inang, dan letak posisi inang dalam petak contoh. Pengamatan dilakukan
pada petak ukuran 1 ha.
3.4.4.1.3 Aktifitas fauna/satwaliar
Data aktivitas fauna/satwaliar yang diamati ialah fauna/satwaliar yang
terdapat disekitar knop/bunga R. micropylora. Pengamatan tersebut meliputi
spesies satwa, jumlah satwa, dan aktivitas yang dilakukannya.
3.4.4.2 Data Abiotik (fisik)
Data fisik yang diambil meliputi data ketinggian tempat, kemiringan lahan,
tebal penutupan serasah hutan, komponen fisik tanah, suhu dan kelembaban
udara. Data ketinggian tempat diukur dengan memakai GPS berupa data
ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Kemiringan lahan dilihat besarnya
kemiringan lokasi penelitian dengan mengukur derajat kemiringan lahan.
Tebalnya penutupan serasah hutan diukur pada habitat yang ditemukannya R.
micropylora dari dasar tanah. Komponen fisik tanah diambil petak contoh tanah
dalam tiga petak contoh yang diletakkan pada petak 1, 13, dan 25 pada petak
contoh pengukuran vegetasi seluas 1 ha. Data komponen fisik tanah tersebut
berupa pH tanah, Kapasitas Tukar Kation (KTK), tekstur, struktur, dan warna
tanah. Untuk data kelembaban dan suhu udara diambil data kelembaban dan suhu
udara harian.
3.4.5 Sikap masyarakat sekitar hutan
Wawancara semi terstruktur dengan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar
kawasan habitat R. micropylora dilakukan untuk mengetahui sikap masyarakat
terhadap R. micropylora. Masyarakat yang diwawancarai terutama masyarakat
yang memiliki hubungan yang erat dengan hutan, khususnya dengan R.
micropylora. Informasi tersebut dapat berupa pandangan masyarakat, hubungan
keterikatan, dan manfaat R. micropylora bagi kehidupannya. Penetapan responden
dilakukan secara terpilih berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, dengan
mengambil 30 responden.
Aktivitas kunjungan wisatawan dan pengelolaan, serta hubungan
masyarakat dengan Rafflesia diamati untuk mengetahui aktivitas manusia yang
berpengaruh. Dari aktivitas tersebut dilihat dampak negatif yang ditimbulkan
terhadap habitat maupun R. micropylora. Aktifitas pengelolaan sendiri dilakukan
dengan wawancara dengan pengelola TNGL dan observasi lapang secara
langsung.
Sedangkan upaya konservasi R. micropylora dilihat dari permasalahan yang
terjadi di kawasan TNGL dan dihubungkan dengan harapan masyarakat sekitar
hutan melalui wawancara tertulis semi terstruktur. Penentuan pemberian solusi
dari permasalahan yang ada dilakukan melalui analisis masalah dan harapan
masyarakat sekitar hutan.
3.5 Analisis Data 3.5.1 Kondisi biotik
Data vegetasi hutan yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan dihitung
nilai-nilai: indeks nilai penting, indeks keanekaragaman spesies, indeks kekayaan
spesies, dan indeks kemerataan.
3.5.1.1 Indeks nilai penting
Analisis kerapatan, frekuensi dan dominansi untuk setiap spesies tumbuhan
dilakukan pada masing-masing petak contoh untuk mengetahui struktur dan
komposisi vegetasi (Soerianegara & Indrawan 1983). Perhitungan dilakukan
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Kerapatan suatu spesies (K)
Kerapatan relatif suatu spesies (KR) 100%
spesies
Frekuensi suatu spesies (F)
petak
Frekuensi relatif suatu spesies (FR) 100% spesies
Dominansi suatu spesies (D)
(ha)
Dominansi relatif suatu spesies (DR) ×100% spesies
Indeks Nilai Penting (INP)
Tingkat semai/tumbuhan bawah, liana dan pancang: INP = KR + FR Tingkat pohon/tiang: INP = KR + FR + DR
3.5.1.2 Keanekaragaman spesies tumbuhan
Keanekaragaman spesies dihitung dengan menggunakan Indeks
Keanekaragaman Shannon (H’), sebagai berikut :
H’ : Indeks Keanekaragaman Shannon Pi : Proporsi Nilai Penting
Ln : Logaritma Natural Ni : Jumlah INP suatu spesies N : Jumlah INP seluruh spesies
3.5.1.3 Kekayaan spesies (Species richness)
Pengukuran kekayaan spesies dalam petak pengamatan, pendekatan yang
digunakan adalah Indeks kekayaan spesies Margalef (Magurran 1988), dengan
persamaan sebagai berikut:
Dmg = Indeks kekayaan Margaleft S = Jumlah spesies
N = Jumlah individu
3.5.1.4 Indeks kemerataan (Evenness)
Pengukuran derajat kemerataan kelimpahan individu antara setiap spesies
digunakan indeks kemerataan spesies tumbuhan (Magurran 1988), dengan
persamaan sebagai berikut:
H’ = Indeks keanekaragaman spesies Shannon-Wiener S = Jumlah spesies
3.5.1.5 Stratifikasi dan penutupan tajuk vegetasi
Penentuan nilai persentase penutupan tajuk menggunakan rumus sebagai
berikut:
Penentuan stratifikasi tajuk hutan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai
berikut (Soerianegara & Indrawan 1983):
Strata A : Lapisan teratas, dengan tinggi pohon ≥ 30 m.
Strata C : Terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 4-20 m.
Strata D : Lapisan perdu dan semak, tingginya 1-4 m.
Strata E : Lapisan tumbuhan-tumbuhan penutup tanah, tingginya 0-1 m.
3.5.3 Kondisi abiotik (fisik)
Data abiotik (fisik) yang meliputi tanah, suhu dan kelembaban udara
disajikan melalui tabulasi, di analisis secara deskriptif kualitatif.
BAB IV
KONDISI UMUM LAPANGAN
4.1 Sejarah dan Status Kawasan
Perlindungan kawasan TNGL merupakan usulan dari tokoh-tokoh Aceh
sejak 93 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1912. Para tokoh itu meminta
kepada pemerintah kolonial untuk melindungi kawasan hutan di Singkil dan
Lembah Alas, dan tidak mengijinkan penebangan hutan di sana. Pada tahun 1928,
penanam karet Belanda, yaitu dr.F.C. van Heurn menyiapkan proposal yang
pertama. Tahun 1934, suaka alam Gunung Leuser ditetapkan dengan luas 416.500
ha. Tahun 1936 Lahan basah Kluet seluas 20.000 ha dimasukkan sebagai
tambahan suaka, dan dua tahun kemudian terjadi penambahan suaka di Sekundur
seluas 79.100 ha, Langkat Barat dan Langkat Selatan seluas 127.075 ha
ditetapkan. Pada tahun 1980, dideklarasikan 5 taman nasional pertama di
Indonesia, yaitu Leuser, Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango, Baluran, dan
Komodo. Menurut SK Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-II/91 tahun 1997 diacu
dalam Wiratno (2007) luas TNGL adalah 1.094.962 ha. Pada tahun 1981, Leuser
ditetapkan oleh UNESCO sebagai Biosphere Reserve atau Cagar Biosfer, atas
usulan dari pemerintah Indonesia. Pengakuan global ini pun berlanjut lagi dengan
ditetapkannya TNGL sebagai Tropical World Heritage Site of Sumatra,
bersama-sama dengan TN Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan pada tahun 2004
(Wiratno 2007).
4.2 Letak dan Luas Kawasan
TNGL secara geografis terletak di koordinat 02° 50' - 04° 10' LU dan 96°
35' - 98° 30' BT yang terdapat di dua provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan, dan Aceh
Barat Daya) dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat dan Karo). TNGL
dengan luas 1.094.692 ha terbagi ke dalam Provinsi NAD seluas ± 867.789 ha,
Kabupaten Aceh Tenggara-Kuta Cane (NAD) merupakan salah satu tempat
terdapatnya R. micropylora yang secara geografis terletak antara 3° 55' 23” - 4°
16' 37” LU dan 96° 43' 23’’ - 98° 10' 32” BT, dan secara administratif Kabupaten
Aceh Tenggara di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di
sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di
sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan
Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh
Selatan. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak diketinggian 25-1.000 m dpl,
berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Suhu udara berkisar antara 25ºC
sampai 32ºC (Anonim 2010).
4.3 Tanah
Pada kawasan TNGL minimal terdapat 11 macam jenis tanah. Tiga jenis
tanah mendominir kawasan ini, yaitu kompleks podsolik cokelat, podsolik dan
litosol (38,41%), kompleks podsolik merah kuning latosol dan litosol (31,97%),
dan andosol (13,76%). Jenis-jenis tanah tersebut mencakup organosol dan
gleihumus, regosol, podsolik merah kuning (batuan endapan), podsolik merah
kuning (batuan aluvial), regosol, andosol, litosol, podsolik merah kuning (bahan
endapan dan batuan beku), kompleks podsolik merah kuning latosol dan litosol,
kompleks podsolik cokelat, podsolik dan litosol, serta kompleks resina dan litosol
(TNGL 2010).
4.4 Hidrologi
Berdasarkan TNGL (2010), hidrologi di kawasan TNGL dicirikan oleh
sungai panjang, yaitu Sungai Alas dan oleh anak-anak sungai yang berhulu dari
banyak gunung diantaranya Gunung Leuser, Gunung Kemiri, Gunung Bendahara,
Gunung Parkinson dan lain-lain. Anak-anak sungai ini bermuara ke Samudera
Indonesia ataupun ke Selat Malaka.
Secara garis besar terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
airnya berasal dari kawasan TNGL, yaitu :
1) Bakongan, Krueng Kluet, Krueng Baro, Krueng Susoh, Krueng Batee dan
2) Krueng Tripa dan Lesten.
3) Lesten/Jampur/Amiang
4) Sekundur/Besitang, Sei Lepan, Sei Batang Serangan, Sei Musam, Sei
Bohorok, Sei Berkail, Sei Wampu, Sei Bekular, dan Sei Bingei.
5) Waihni Gumpang, Waihni Marpunga, Lawe Ketambe, Lawe Kompas, dan
Lawe Bengkung.
Disamping keberadaan sungai-sungai tersebut di kawasan ini juga terdapat 2
(dua) buah danau kecil, yaitu Danau Laot Bangko yang terdapat di daerah Kluet
(10 ha) dan Danau Marpunga (6 ha) di daerah Marpunga. Beberapa lokasi air
panas juga ditemukan disini, seperti di Lawe Gerger (hutan lindung Serbolangit),
dan Kappi serta lokasi air bergaram yang merupakan tempat pengasinan satwa liar
(di Alas, Kappi, Leuser, dan Muara Renun).
4.5 Iklim
Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Furguson (1958) diacu dalam TNGL
(2010), kawasan TNGL termasuk tipe iklim A yaitu musim kemarau terjadi pada
Bulan Maret-Agustus dan musim hujan pada Bulan September-Pebruari. Curah
hujan rata-rata berkisar antara 1.000 s/d 3.000 mm pertahun. Suhu rata-rata
minimum berkisar antara 23-25ºC dan rata-rata maksimum 30-33ºC, dan
kelembaban udara relatif antara 65-75%.
4.6 Topografi
Kawasan TNGL berada di pegunungan yang berbukit dan bergelombang.
Sebagian kecil saja areal yang berupa dataran rendah, yaitu di daerah
Sekundur-Langkat pantai Timur dan di daerah Kluet pantai Barat. Berbagai elemen
morfologi terlihat nyata, seperti rangkaian pegunungan dengan berbagai lipatan
patahan dan rengkahan, gugusan bukit terjal dan bergelombang, gunung-gunung,
kubah-kubah, dataran tinggi, plato, celah, lembah, jurang, lereng, dataran rendah,
pantai, kompleks, dan aliran sungai dengan berbagai bentukan dan sistem pola
sungai dengan cabang-cabangnya. Sedikitnya terdapat 33 bukit atau gunung dan
ada beberapa yang belum tercatat. Salah satu puncak tertinggi TNGL adalah
4.7 Geologi
Bagian utara kawasan TNGL adalah pegunungan Leuser Simpoli yang
terbentuk dari formasi "Munkap mata-sedimen dan Glanalei" yang diperkirakan
berasal dari periode Permo-Carboniferous dan baru sedikit mengalami pelapukan.
Jenis batuannya antara lain Phylite hitam dan kelabu, metasilstone,
meta-sandstone, fine graned quaatzite, dan marbble. Jenis batuan yang terdapat di
sekitar Lembah Alas, gugusan Bendara dan jalur Kluet - Rameh, antara lain
guartzbiolite schists banded, gneiss, cucocratic, fine granular gneiss,
amphibolete, banded dan massive marble. Formasi Alas Barat diperkirakan
berasal dari periode Nesozoic dengan jenis batuan blackshale to slate, siltstone,
hard sand stone, minor grey wache, conglomerate, banded, massive limestone,
dolomite, dan chert (TNGL 2010).
4.8 Potensi Kawasan 4.8.1 Flora
TNGL memiliki penyebaran vegetasi yang lengkap, mulai dari vegetasi
hutan pantai/rawa, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi dan hutan
pegunungan. Kawasan ini hampir seluruhnya ditutupi oleh lebatnya hutan
Dipterocarpaceae dengan beberapa sungai dan air terjun. Vegetasi dominan adalah
hutan tropis basah. Van Steenis (1937) diacu dalam TNGL (2010) membagi
wilayah tumbuh-tumbuhan di TNGL dalam beberapa zona, yaitu ;
- Zona Tropika (termasuk zona Collin, terletak 500-1.000 m dpl). Zona ini
merupakan daerah berhutan lebat yang ditumbuhi berbagai jenis tegakan yang
berdiameter besar yang tingginya bisa mencapai 40 meter, serta berbagai jenis
liana dan epifit yang menarik seperti anggrek.
- Zona Montane (termasuk zona sub montane, terletak 1.000-1.500 m dpl). Zona
ini merupakan hutan montane dengan tegakan kayu yang tidak terlalu tinggi,
yaitu berkisar antara 10 - 20 m, banyak dijumpai lumut yang menutupi tegakan
kayu atau pohon, dengan kelembaban udara yang tinggi.
- Zona Sub Alpine (2.900 - 4.200 m dpl); merupakan zona hutan Ercacoid yang
pohon-
pohon kerdil dan semak-semak serta beberapa spesies tundra, anggrek dan
lumut.
Berdasarkan TNGL (2010) diperkirakan TNGL memiliki 3.000 s/d 4.000
spesies tumbuhan, terutama di hutan dataran rendah, diantaranya terdiri dari
spesies kayu komersial, pohon buah-buahan, rotan (74 spesies), palem, jenis
tanaman obat, dan bumbu-bumbuan. Kayu komersial dari famili Dipterocarpaceae
terdapat 95 spesies, antara lain meranti, keruing, shorea, dan pohon kapur
(Dryobalanops aromatica). Pohon buah-buahan antara lain jeruk hutan (Citras
macroptera), durian hutan (Durio exeleyanus dan D. zibethinus), menteng
(Baccaurea montheyana dan B. racemosa), dukuh (Lansium domesticum),
mangga (Mangifera foetida dan M. guadrifolia), rukem (Flacourtia rukem), dan
rambutan (Nephelium lappaceum). Spesies lainnya, antara lain palem daun sang
(Johannesteijsmania altifrons) yang merupakan spesies yang hanya terdapat di
daerah Langkat, beberapa spesies bunga Rafflesia (R. micropylora, R. arnoldii
var. atjehensis, R. rochussenii, R. arnoldii ), dan Rhizanthes zippelii serta berbagai
tumbuhan pencekik (ara).
4.8.2 Fauna
TNGL (2010) mencatat sebanyak 34 ordo dari fauna yang terdiri dari 144
famili dengan 717 spesies dan 89 spesies diantaranya termasuk jenis satwa langka
dan tidak terdapat di taman nasional lain. Beberapa satwa yang hidup di TNGL,
yaitu:
a) Mamalia, antara lain orangutan (Pongo pygmaeus), serudung (Hylobates lar),
kedih (Presbytis thomasi), siamang (Hylobates sindactylus), musang congkok
(Prionodon linsang), kukang (Nycticebus coucang), kucing emas (Felis
temmincki), pulusuan (Arctonyx collaris), bajing terbang (Lariscus insignis),
harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), ajak (Cuon alpinus), harimau
dahan (Neofelis nebulosa), beruang madu (Helarctos malayanus), gajah
sumatera (Elephas maximus), rusa (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus
muntjak), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), kambing hutan
(Capricornis sumatraensis), tapir (Tapirus indicus),
b) Burung, antara lain kuntul kerbau (Bubulcus ibis), kuntul (Egretta sp.), itik liar
julang ekor abu-abu (Annorhinus gaeleritus), julang emas (Rhiticeros
undulatus), kangkareng (Anthracoceros convextus), dan beo nias (Gracula
religiosa).
c) Reptil, antara lain buaya muara (Crocodilus porosus), penyu belimbing
(Dermochelys sp.), kura-kura gading (Orlitia borneensis), dan senyulong
(Tomistoma sp.).
4.8.3 Ekowisata
Lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata, yaitu :
a) Gurah, melihat dan menikmati panorama alam, lembah, sumber air panas,
danau, air terjun, pengamatan satwa dan tumbuhan seperti bunga Rafflesia,
orangutan, burung, ular dan kupu-kupu.
b) Rehabilitasi orangutan Bohorok, melihat atraksi orang hutan di tempat
rehabilitasi orangutan dan wisata alam berupa panorama sungai, bumi
perkemahan dan pengamatan burung.
c) Kluet, bersampan di sungai dan danau, trekking pada hutan pantai dan wisata
goa. Daerah ini merupakan habitat harimau Sumatera.
d) Sekundur, berkemah, wisata goa dan pengamatan satwa.
e) Ketambe dan Suak Belimbing, penelitian primata dan satwa lain yang
dilengkapi rumah peneliti dan perpustakaan.
f) Gunung Leuser (3.404 m dpl), dan Gn. Kemiri (3.314 m dpl), memanjat dan
mendaki gunung.
g) Sungai Alas, kegiatan arung jeram dari Gurah-Muara Situlen-Gelombang,
selama 3 hari.
Atraksi budaya di luar TNGL antara lain Festival Danau Toba pada bulan
Juni di Danau Toba dan Festival Budaya Melayu pada bulan Juli di Medan.
Musim kunjungan terbaik yaitu bulan Juni sampai Oktober. Sarana dan Prasarana
yang dimiliki berupa kantor, radio komunikasi, pusat informasi, guest house, bumi
perkemahan, jalan setapak, menara pengamat, dan shelter (TNGL 2010).
Cara menuju lokasi (menggunakan kendaraan roda empat):
- Medan-Kutacane ± 240 km atau 8 jam
- Kutacane-Gurah/Ketambe ± 35 km atau 30 menit
- Medan-Sei Betung/Sekundur ± 150 km atau 2 jam
- Medan-Tapaktuan ± 260 km atau 10 jam
4.9 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Hingga tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara
adalah169.409 jiwa dengan kepadatan 37 jiwa/km . Komposisi penduduk terdiri
dari 77.385 laki-laki dan 92.024 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,67%
per tahun (Anonim 2010). Kabupaten Aceh Tenggara sering disebut dengan tanah
Alas didominasi oleh suku Alas. Suku Alas sebagian besar tinggal di pedesaan
dan hidup dari pertanian dan peternakan.
Desa yang dijadikan sebagai responden yaitu Desa Ketambe, Desa Simpur
Jaya pada Kecamatan Ketambe dan Desa Pulo Piku pada Kecamatan Darul
Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, NAD. Ketiga desa ini jika di tinjau dari
wilayah perbatasan kawasan TNGL termasuk ke dalam zona perbatasan dengan
TNGL. Disebutkan dalam data TNGL (2010) ada 37 desa yang berbatasan
langsung dengan kawasan TNGL. Diantara desa tersebut, ketiga desa yang
dijadikan sebagai responden dalam penelitian termasuk ke dalam desa yang
berbatasan langsung dengan kawasan TNGL. Namun demikian desa yang paling
erat dengan kawasan TNGL ialah Desa Ketambe dan Simpur Jaya. Dari ketiga
desa tersebut sebagian besar Desa Simpur Jaya seluruhnya bermata pencaharian
dari hasil berkebun, Desa Ketambe sudah banyak yang bermata pencaharian
sebagai pedagang, jasa penyedia, jasa wisata, dan sebagai masyarakat berkebun,
dan Desa Pulo Piku memiliki mata pencaharian sebagai petani dan berkebun.
Diantara ketiga desa yang terdapat, Desa Simpur Jaya merupakan desa yang
paling tertinggal yang terletak di kawasan Kecamatan Ketambe dan merupakan
salah satu desa yang masih sangat tergantung dengan keberadaan kawasan TNGL.
Selain itu pada saat wawancara dengan masyarakat Simpur Jaya (Agustus
2010) terjadi penangkapan terhadap warga Simpur Jaya oleh petugas keamanan
terkait masalah illegal logging dan perambahan hutan di kawasan TNGL.
Sebanyak 6 orang warga yang ditangkap berdasarkan informasi dari petugas
Simpur Jaya terhadap hutan, berarti seluruh kegiatan masyarakat Simpur Jaya
berada dalam kawasan TNGL.
Tanah Alas merupakan lumbung penghasil padi untuk daerah Aceh. Dari
luas keseluruhan wilayah Aceh Tenggara, hanya 9,74% yang dimanfaatkan
sebagai lahan budidaya. Luas lahan persawahan di wilayah Aceh Tenggara adalah
17.224 ha dengan pembagian tanah berdasarkan fungsinya seperti tersaji di Tabel
3.
Tabel 3 Luas tanah berdasarkan fungsi pemanfaatan tanah khusus tanaman padi
No. Fungsi Pemanfaatan Luas Tanah (ha) Produktivitas
1. Sawah beririgasi 2.500
107.153 ton gabah 2. Sawah berpengairan sederhana 13.972
3. Sawah tadah hujan 752
Sumber: Anonim (2010)
Selain ketersediaan air yang melimpah dan iklim Aceh Tenggara juga
sangat cocok untuk membudidayakan berbagai jenis ikan air tawar. Selama ini
yang sudah dibudidayakan adalah ikan mas dan mujair. Namun prospek yang
bagus juga ada pada pembudidayaan ikan jurung, lele, belut, dan gabus, yang
selama ini ditangkap dari sungai-sungai yang ada di wilayah Aceh Tenggara.
Selain bidang perikanan, ternak yang dibudidayakan masyarakat daerah Aceh
Tenggara dominannya adalah kerbau dan sapi, namun banyak juga yang
membudidayakan kambing, domba dan unggas. Produktivitas bidang perikanan,
pertanian, dan peternakan seperti tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4 Produktivitas bidang perikanan, pertanian, dan peternakan di tahun 2004
No. Bidang Jenis Komoditi Produktivitas (ton) Luas Tanah (ha)
1. Perikanan Ikan mas 243,80
4.534,17 2. Perikanan Ikan mujair 1.152,54
3. Pertanian Jagung 151.092,85
Spesies tanaman perkebunan potensial di wilayah Aceh Tenggara adalah
mengalami pertumbuhan sangat pesat adalah kakao karena penanaman kakao oleh
masyarakat baru dilakukan sekitar sepuluh tahun terakhir. Limpahan produksi
kakao ini sangat membantu perekonomian masyarakat karena harganya relatif
tinggi dan stabil. Tapi selain itu mereka juga mencari berbagai hasil hutan, seperti
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1Kondisi Populasi Rafflesia micropylora Meijer
Lokasi ditemukannya knop (kuncup) Rafflesia micropylora Meijer berada di
Blok Gurah Ketambe Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Namun
berdasarkan informasi dari masyarakat, terdapat empat lokasi tumbuh R.
micropylora yang biasa ditemukan di TNGL, Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD). Lokasi-lokasi tersebut yaitu di Stasiun Riset Ketambe, Blok
Gurah Ketambe, Desa Suka Rimbun Kecamatan Ketambe, dan di dekat kebun
masyarakat Ketambe. Selain itu, R. micropylora yang dekat dengan daerah
Ketambe dapat ditemui di Blok Air Panas, Desa Lawe Panas, Kecamatan Putri
Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi NAD. Dari keempat lokasi tersebut, R.
micropylora hanya ditemukan di blok Gurah Ketambe TNGL.
Knop R. micropylora yang ditemukan berjarak sekitar 6 m dari inangnya
yaitu akar reriang gana (Tetrastigma lanceolarium). Knop tersebut ditemukan
dalam keadaan utuh lepas dari inangnya. Diduga knop tersebut baru sehari atau
dua hari lepas dari inangnya akibat adanya gangguan.
Dari hasil bekas tumbuh R. micropylora pada inangnya ditemukan sejumlah
lima bekas tempelan tempat tumbuh. Pada kelima bekas tumbuh R. micropylora
tersebut satu diantarannya adalah bekas tumbuh knop R. micropylora yang
tercabut (Tabel 5).
Tabel 5 Kondisi bekas knop R. micropylora pada inang (T. lanceolarium)
Bekas knop R. micropylora Diameter inang (cm) Tinggi dari permukaan tanah (cm)
Knop 1 3,5 168
Knop 2 2,22 0
Knop 3 0,95 0
Knop 4 1,91 0
Knop 5 2,38 0
Berdasarkan Tabel 5, bekas knop R. micropylora memiliki diameter yang
berbeda-beda pada setiap ukuran diameter inang. Kisaran diameter inang dimulai
dari 0,95-3,5 cm. Ukuran diameter knop Rafflesia yang ditemukan terlepas dari
inangnya mencapai 14,96 cm (Gambar 3). R. micropylora mekar dengan diameter
Gambar 3 Kondisi knop R. micropylora.
Daun pelindung (bractea) yang mulai mengering dan berwarna cokelat
kehitaman merupakan ciri khas bagi R. micropylora pada tahapan
perkembangannya (Gambar 3). Disebutkan oleh Zuhud et al. (1998) bahwa knop
R. micropylora dengan ukuran kurang dari 10 cm warna pelindung berubah
menjadi cokelat kemerah-merahan sampai cokelat kehitam-hitaman, dan
pelindung sudah mengering serta warnanya berubah menjadi cokelat tua
kehitam-hitaman hingga hitam pada ukuran lebih kurang 15 cm.
Dilihat dari struktur penyusunnya (Gambar 4), knop R. micropylora yang
merupakan tumbuhan berumah dua ini adalah knop R. micropylora bunga jantan.
Jenis kelamin knop ini ditandai adanya anther pada bagian dalamnya dan tidak
memiliki ovarium. Processes pada knop ini memiliki 20 buah dengan tinggi
1,75-2,5 cm dari pangkal margo superior discus. Margo superior discusnya memiliki
Keterangan:
1. Diaphragm 2. Segmenta perigone 3. Ramenta
4. Processes
5. Margo superior discus 6. Anther
14. Tempat menempelnya dengan inang
Gambar 4 Bagian R. micropylora (Zuhud et al. 1998).
Sebagai spesies tumbuhan berumah dua, keberadaan bunga jantan dan
bunga betina pada R. micropylora sangat mempengaruhi proses
perkembangbiakannya. Proses penyerbukan dan pembuahan yang sempurna akan
terjadi jika terdapat dua spesies bunga jantan dan bunga betina R. micropylora
yang mekar dalam waktu yang bersamaan dan lokasi yang berdekatan. Proses
perkembangbiakan tersebut juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh bunga R.
micropylora melainkan melalui bantuan satwa, angin dan air terhadap inangnya
(Zuhud et al. 1998).
Satu knop R. micropylora tumbuh pada inangnya tidak memberikan
kerugian yang nyata. Keberadaan knop R. micropylora tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan inang T. lanceolarium, karena satu batang inang dapat
kerusakan pada inang (Misnawaty 2007). Namun berdasarkan Nais (2001)
menyatakan bahwa pengaruh tumbuhan parasit terhadap inangnya dapat
menyebabkan terjadinya kompetisi dalam memperoleh air, kompetesi dalam
memperoleh nutrisi organik maupun anorganik, terganggunya metabolisme inang,
terganggunya potensi reproduksi inang, dan kesehatan inang menurun/terganggu.
5.2 Kondisi Habitat R. micropylora 5.2.1 Kondisi biotik
Kondisi biotik habitat R. micropylora meliputi kondisi vegetasi di
sekitarnya, tumbuhan inang R. micropylora, aktivitas satwaliar di sekitar habitat
R. micropylora.
5.2.1.1 Kondisi vegetasi
Vegetasi adalah tingkat yang paling berperan dalam keberadaan hutan.
Keberadaan vegetasi dapat dibedakan berdasarkan tingkatan pertumbuhannya
yaitu tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai/tumbuhan bawah. Tingkatan
vegetasi menggambarkan banyaknya jumlah spesies, besarnya diameter batang,
dan tingginya vegetasi yang didapat pada suatu lokasi tersebut. Dari jumlah,
diameter, dan tinggi vegetasi yang didapat menggambarkan keberadaan vegetasi
tersebut dalam hal kedominanan spesies, kerapatan, dan penyebarannya yang
terdapat pada lokasi tersebut.
5.2.1.1.1 Tingkat pohon
Dari hasil analisis vegetasi, didapat 30 spesies tingkat pohon dengan 13
famili. Habitat R. micropylora merupakan tipe vegetasi hutan dataran rendah.
Ciri-ciri tipe vegetasi hutan dataran rendah yaitu adanya spesies kayu penting dari
famili Dipterocarpaceae antara lain: Shorea, Hopea, Dipterocarpus, Vatica, dan
Dryobalanops (Soerianegara & Indrawan 1983).
Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi didominasi oleh spesies Parashorea
parvifolia dari famili Dipterocarpaceae dan diikuti oleh Hydnocarpus woodii
(Flacourtiaceae), Glochidion kollmannianum (Euphorbiaceae), Toona sureni
(Meliaceae), dan Aglaia odorata (Meliaceae) sebagaimana tersaji di dalam Tabel
Tabel 6 Lima spesies tingkat pohon yang memiliki tingkat INP tinggi
1 Parashorea parvifolia Dipterocarpaceae 8,26 7,89 32,18 48,33
2 Hydnocarpus woodii Flacourtiaceae 19,83 13,15 13,11 46,10
3 Glochidion kollmannianum Euphorbiaceae 17,35 13,15 8,91 39,42
4 Toona sureni Meliaceae 3,30 3,94 9,23 16,48
5 Aglaia odorata Meliaceae 4,13 5,26 3,30 12,69
Spesies P. parvifolia memiliki nilai INP tertinggi dan diameter terbesar
dengan nilai Dominansi Relatif (DR) 32,18% dalam petak contoh. Dilihat dari
tingkat kerapatan menunjukkan bahwa spesies H. woodii memiliki kerapatan
paling tinggi yaitu Kerapatan Relatif (KR) mencapai 19,83%. Sedangkan untuk
nilai frekuensi H. woodii dan G. kollmannianum mempunyai nilai frekuensi
tertinggi dengan frekuensi relatif yang sama sebesar 13,15%. Hal ini
menunjukkan bahwa kedua spesies ini mempunyai tingkat penyebaran yang lebih
merata dibanding spesies lainnya. Namun selain lima spesies tingkatan pohon
yang tertinggi, spesies Trigonostemon sp. dari famili Euphorbiaceae merupakan
spesies yang memiliki INP terendah dengan nilai INP 2,36%.
Gambar 5 menunjukkan persentase famili berdasarkan INP. Persentase
famili tertinggi diperoleh Euphorbiaceae dengan nilai INP sebesar 28%, diikuti
oleh famili Meliaceae, Sapindaceae, Moraceae, dan Rutaceae. Hal ini disebabkan
famili Euphorbiaceae banyak ditemukan di petak pengamatan di antaranya spesies
G. kollmannianum, Mallotus oblongifolius, Macaranga hypoleuca, Cleistanthus
myrianthus, Koilodpas brevipes.
Berdasarkan penelitian Mukmin (2008) di Cagar Alam Penanjung
Pangandaran Jawa Barat, famili yang memiliki INP tertinggi tingkat pohon yaitu
Meliaceae dan Euphorbiaceae pada tingkat ke tiga. Hal tersebut menunjukkan
bahwa habitat Rafflesia pada hutan hujan dataran rendah masih memiliki
kemiripan famili vegetasi.
5.2.1.1.2 Tingkat tiang
Analisis tingkat tiang didapat 35 spesies dari 18 famili, dengan lima spesies
yang dominan berdasarkan INP yaitu Glochidion kollmannianum, Hydnocarpus
woodii, Mallotus oblongifolius, Diospyros sumatrana, dan Syzygium
magnoliaefolium, seperti tersaji pada Tabel 7 dan daftar lengkap spesies tingkat
tiang tersaji pada Lampiran 2.
Tabel 7 Lima spesies tingkat tiang yang memiliki tingkat INP tinggi
No Nama Ilmiah Famili KR 1 Glochidion kollmannianum Euphorbiaceae 13,04 12,32 12,89 38,26
2 Hydnocarpus woodii Flacourtiaceae 13,04 9,58 10,93 33,56
3 Mallotus oblongifolius Euphorbiaceae 10,86 6,84 12,12 29,84
4 Diospyros sumatrana Ebenaceae 6,52 5,47 7,15 19,15
5 Syzygium magnoliaefolium Myrtaceae 5,43 5,47 8,04 18,96
Pada lima spesies yang memiliki INP tertinggi tingkat tiang tidak semua
spesies menunjukkan dominansi yang sama dengan tingkat pohon, hanya dua
spesies saja yang sama dominan yaitu H. woodii dan G. kollmannianum. Spesies
G. kollmannianum menduduki nilai INP ketiga di tingkat pohon, namun pada
tingkat tiang G. kollmannianum memiliki nilai INP terbesar. Spesies P. parvifolia
tidak termasuk kedalam lima besar spesies yang memiliki INP terbesar pada
tingkat tiang, namun P. parvifolia memiliki INP tertinggi pada tingkat pohon.
Keberadaan tingkat vegetasi ditentukan oleh kemampuan vegetasi tersebut dalam
mendapatkan cahaya yang digolongkan ke dalam spesies toleran, semi toleran,
dan intoleran.
Jika dilihat dari persentase famili tingkat tiang berdasarkan nilai komulatif
INP menunjukkan famili Euphorbiaceae tertinggi dengan INP sebesar 31,42%
-Gambar 6 Persentase famili tingkat tiang berdasarkan INP.
5.2.1.1.3. Tingkat pancang
Jumlah spesies yang didapat pada vegetasi tingkat pancang yaitu 52 spesies
dengan 24 famili. Dari 52 spesies vegetasi tingkat pancang, Glochidion
kollmannianum merupakan spesies yang paling dominan dengan nilai INP
22,31%, dan diikuti oleh spesies Aglaia argentea, Hydnocarpus woodii,
Parashorea parvifolia, dan Aglai odorata sebagaimana yang tersaji pada Tabel 8.
Selain 5 spesies yang paling dominan terdapat 21 spesies lainnya yang memiliki
INP terendah dengan nilai INP 1,10% (Lampiran 3).
Tabel 8 Lima spesies tingkat pancang yang memiliki tingkat INP tinggi
No Nama Ilmiah Famili KR (%) FR (%) INP (%)
1 Glochidion kollmannianum Euphorbiaceae 10,54 11,76 22,31
2 Aglaia argentea Meliaceae 10,18 9,55 19,74
3 Hydnocarpus woodii Flacourtiaceae 11,27 6,61 17,89
4 Parashorea parvifolia Dipterocarpaceae 8 7,35 15,35
5 Aglaia odorata Meliaceae 6,18 8,08 14,27
Nilai kerapatan vegetasi tertinggi pada tingkat pancang dimiliki oleh H.
woodii dengan nilai KR 11,27% dan diikuti oleh spesies G. kollmannianum,
Aglaia argentea, P. parvifolia dan A. odorata. Spesies yang paling menyebar
ialah G. kollmannianum, A. argentea, A. odorata, P. parvifolia, dan H. woodii.
Salah satu kemampuan menyebarnya suatu spesies ditentukan oleh
kemampuannya dalam menyesuaikan habitatnya, terutama terhadap media tanah
dan kebutuhan unsur hara yang diperlukan. Spesies yang menyebar tidak selalu
menggambarkan penyebaran terhadap famili.
Gambar 7 menunjukkan famili Euphorbiaceae memiliki nilai INP tertinggi