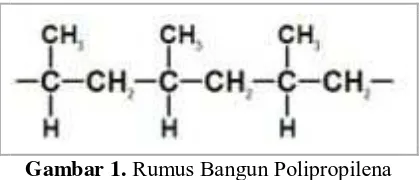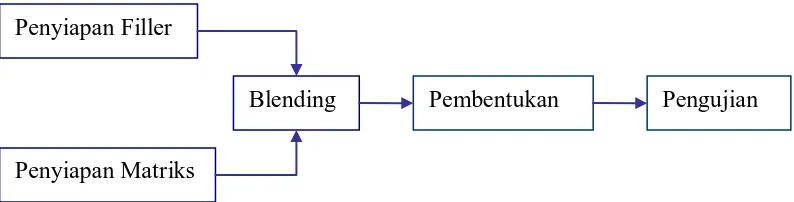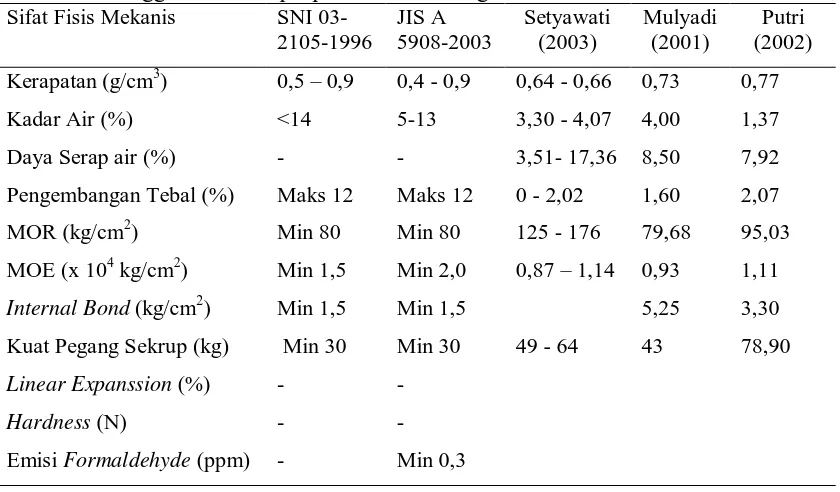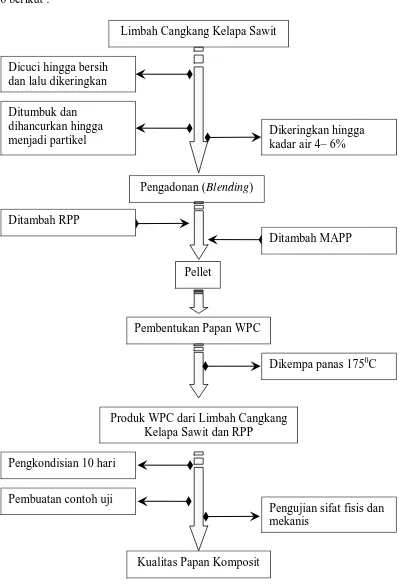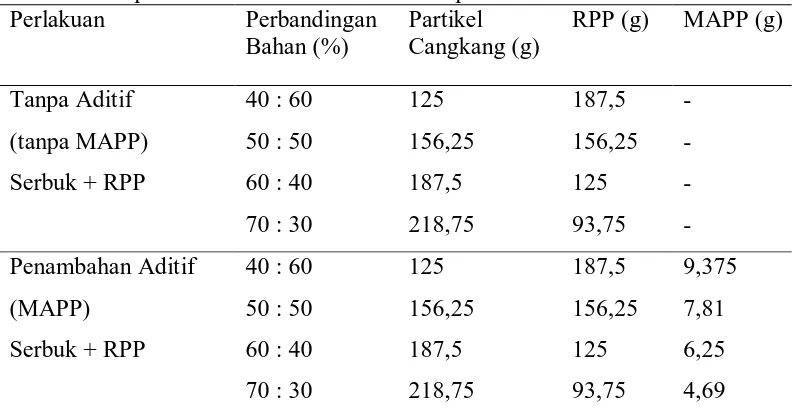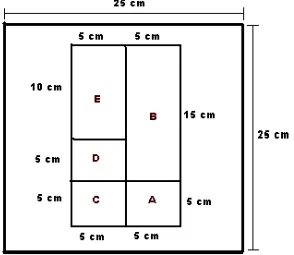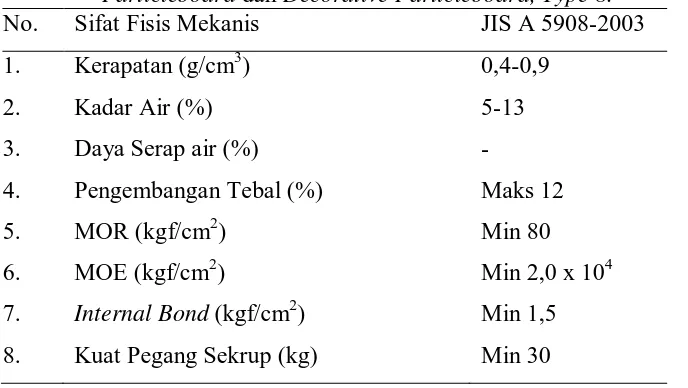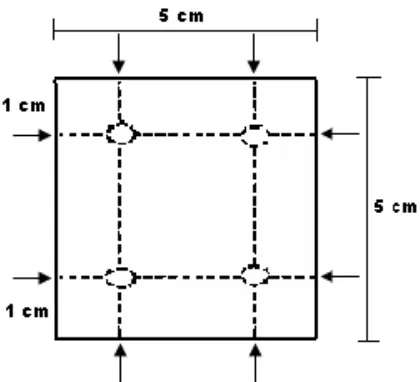PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) DAN PLASTIK DAUR ULANG
SEBAGAI PAPAN KOMPOSIT
SKRIPSI
Oleh:
HERI MUDA SETIAWAN
031203002/ TEKNOLOGI HASIL HUTAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) DAN PLASTIK DAUR ULANG
SEBAGAI PAPAN KOMPOSIT
SKRIPSI
Oleh:
HERI MUDA SETIAWAN
031203002/ TEKNOLOGI HASIL HUTAN
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara
DEPARTEMEN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ABSTRACT
The used of waste-palm shell and recycled plastic as composite board has been investigated. The recycled plastic was recycled polypropylene (RPP). The board samples target density was 1.00 g/cm3. Composition of palm shell-particle and plastic were 40 : 60, 50 : 50, 60 : 40 and 70 : 30 based on particle oven dry weight with adding maleated polypropylene (MAPP) and without MAPP treatment. Weight of MAPP was 5% of RPP weight. Pressing temperature, melting time, pressing time was 1750C, 10 minutes and 2 minutes respectively. The research results showed : (1). Generally, physical properties of the boards was fulfill with the JIS A 5908-2003 Standart. (2). Mechanical properties of the boards except MOE was fulfill with the JIS A 5908-2003 Standart. (3). The quality of boards with adding MAPP were better than boards without MAPP treatment. (4). The boards could be use to exterior application.
ABSTRAK
Pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit (Elaeis guineensis jacq) dan plastik daur ulang sebagai papan komposit telah diteliti. Plastik daur ulang yang digunakan adalah recycled polypropylene (RPP). Kerapatan sasaran papan komposit adalah 1,00 g/cm3. Komposisi bahan antara partikel cangkang sawit dengan plastik adalah 40 : 60, 50 : 50, 60 : 40 dan 70 : 30 berdasarkan berat kering oven partikel, dengan perlakuan penambahan maleated polypropylene (MAPP) dan tanpa MAPP. Banyaknya MAPP yang ditambahkan adalah 5% dari berat RPP. Suhu kempa yang digunakan adalah 1750C, sedangkan waktu pelunakan (melting time) adalah 10 menit dan waktu kempa (pressing time) adalah selama 2 menit. Hasil dari penelitian ini adalah : (1). Secara umum, sifat fisis dari papan komposit yang dihasilkan memenuhi standar JIS A 5908-2003. (2). Sifat mekanis papan komposit juga memenuhi standar JIS A 5908-2003, kecuali MOE. (3). Kualitas papan komposit dengan penambahan MAPP lebih baik dibandingkan dengan papan komposit tanpa penambahan MAPP. (4). Papan komposit dapat digunakan untuk keperluan eksterior.
Kata kunci : cangkang sawit, papan komposit, recycled polypropylene (RPP),
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan rahmat Allah SWT sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan Judul : “Pemanfaatan
Limbah Cangkang Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) dan Plastik Daur Ulang
Sebagai Papan Komposit”.
Dalam melaksanakan penelitian hingga penyelesaian skripsi, penulis
menyadari banyak mendapat bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai
pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang
sebesarnya kepada :
1. Orang tua tercinta, Ibunda Khairiah Lubis dan Ayahanda Sumantri serta
adik-adik tersayang Firman Adi Putra, Rizky Iskandar, Ridha Annisa dan
Aidil Nurul Ikhwan selaku keluarga penulis yang telah memberikan kasih
sayang, motivasi, dan dukungan serta doa untuk keberhasilan penulis,
semoga mereka selalu dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah
SWT. Amin.
2. Ibu Iwan Risnasari, S.Hut, M.Si dan Bapak Arif Nuryawan, S.Hut, M.Si
selaku Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu
untuk membimbing, mengarahkan dan membantu serta memberikan kritik
dan saran kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian hingga skripsi.
3. Seluruh Dosen dan Pegawai Departeman Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan,
wawasan dan bantuan akademis kepada penulis.
4. Teman-teman di Kehutanan, khususnya Riana Anggraini dan juga
Sri, Cut, Mona, Yuli serta seluruh teman-teman yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan
kebersamaannya.
5. Pihak-pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja telah membantu penulis
menyelesaikan karya ilmiah ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Medan, Desember 2008
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PENGESAHAN
ABSTRACT ... i
ABSTRAK ... ii
RIWAYAT HIDUP ... iii
KATA PENGANTAR ... iv
DAFTAR ISI ... vi
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR GAMBAR ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1
Tujuan... 4
Manfaat Penelitian ... 4
Hipotesis Penelitian ... 4
TINJAUAN PUSTAKA Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) ... 5
Sejarah Singkat ... 5
Klasifikasi Tanaman Sawit ... 6
Ciri Fisiologis... 6
Potensi Kelapa Sawit ... 8
Potensi Cangkang Sawit ... 10
Polimer ... 12
Plastik ... 14
Sejarah Singkat ... 14
Pengertian dan Penggolongan ... 14
Polipropilena ... 17
Sampah ; Limbah Plastik Menjadi Plastik Daur Ulang ... 19
Wood Polymer Composite (WPC) ; Plastik Daur Ulang sebagai Matriks . 23
METODOLOGI PENELITIAN Waktu dan Tempat ... 27
Alat dan Bahan... 27
Persiapan Bahan Baku ... 28
Proses Pembuatan Papan Komposit ... 29
Pembuatan Adonan (Pencampuran) ... 30
Pengempaan ... 30
Pengkondisian ... 31
Pembuatan Contoh Uji ... 31
Pengujian ... 32
Pengujian Sifat Fisis Papan Komposit ... 33
Analisis Data ... 37
HASIL DAN PEMBAHASAN Sifat Fisis Papan Komposit ... 38
Kerapatan ... 38
Kadar Air ... 40
Daya Serap Air ... 42
Pengembangan Tebal ... 46
Sifat Mekanis Papan Komposit... 48
Modulus of Rupture (MOR) ... 48
Modulus of Elasticity (MOE) ... 50
Internal Bond (Keteguhan Rekat Internal) ... 53
Screw Holding Power (Kuat Pegang Sekrup) ... 54
Perbandingan Kualitas Papan Komposit dengan Penelitian Terdahulu ... 57
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 58
Saran ... 58
DAFTAR PUSTAKA ... 59
DAFTAR TABEL
Halaman 1. Karakteristik Polipropilena ... 19
2. Sifat Fisis Mekanis Beberapa Hasil Penelitian Pembuatan Papan
Komposit dengan Menggunakan PolipropilenaDaur Ulang ... 26
3. Komposisi Kebutuhan Bahan Baku Papan Komposit... 30
4. Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel dengan Standar JIS A 5908-2003 .. 32
5.PerbandinganSifat Fisis Mekanis Hasil Penelitian dengan Beberapa Hasil Penelitian Pembuatan WPC dengan Menggunakan RPP yang Telah
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1. Rumus Bangun Polipropilena ... 18
2. Kode Identitas Resin dari Polipropilena (PP) ... 19
3. Diagram Proses Dasar Pembuatan WPC ... 25
4. PP Gelas Air Mineral (Thermoforming)... 28
5. Diagram Proses Pembuatan Papan Komposit ... 29
6. Pola Pemotongan Contoh Uji Papan Komposit ... 31
7. Titik Pengukuran Dimensi Contoh Uji ... 33
8. Cara Pengujian Modulus of Rupture dan Modulus of Elasticity ... 35
9. Cara Pengujian Keteguhan Rekat ... 36
10. Posisi Sekrup pada Pengujian Kuat Pegang Sekrup ... 36
11. Grafik Nilai Kerapatan Papan Komposit... 38
12. Contoh Uji Papan Komposit dari Limbah Cangkang Sawit dan Plastik Daur Ulang ... 39
13. Grafik Nilai Kadar Air Papan Komposit ... 40
14. Grafik Nilai Daya Serap Air Papan Komposit dengan Perendaman 2 Jam 43
15. Grafik Nilai Daya Serap Air Papan Komposit dengan Perendaman 24 Jam ... 43
16. Grafik Nilai Pengembangan Tebal Papan Komposit Perendaman 2 Jam .. 46
17. Grafik Nilai Pengembangan Tebal Papan Komposit Perendaman 24 Jam 47
18. Grafik Nilai Modulus of Rupture (MOR) ... 48
19. Contoh Uji untuk Uji MOR dan MOE ... 49
20. Grafik Nilai Modulus of Elasticity (MOE) ... 51
22. Pengujian Contoh Uji Internal Bond ; Kerusakan pada Media Uji ... 54
23. Grafik Nilai Kuat Pegang Sekrup Papan Komposit ... 55
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Kerapatan ... 63
2. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Kadar Air ... 63
3. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Pengembangan Tebal (Perendaman 2 Jam) ... 63
4. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Pengembangan Tebal (Perendaman 24 Jam) ... 63
5. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Daya Serap Air (Perendaman 2 Jam) .... 63
6. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Daya Serap Air (Perendaman 24 Jam) .. 64
7. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk MOR ... 64
8. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk MOE... 64
9. Hasil Analisis Sidik Ragam untuk Kuat Pegang Sekrup ... 64
10. Hasil Uji DMRT Kadar Air untuk Faktor A ... 65
11. Hasil Uji DMRT Daya Serap Air dengan Perendaman 24 Jam untuk Faktor A ... 66
12. Hasil Uji DMRT Daya Serap Air dengan Perendaman 24 Jam untuk Faktor B ... 67
13. Hasil Uji DMRT MOR untuk Faktor A ... 68
14. Hasil Uji DMRT MOR untuk Faktor B ... 69
15. Hasil Uji DMRT MOE untuk Faktor A ... 70
16. Hasil Uji DMRT MOE untuk Faktor B ... 71
17. Hasil Uji DMRT KPS untuk Faktor A ... 72
ABSTRACT
The used of waste-palm shell and recycled plastic as composite board has been investigated. The recycled plastic was recycled polypropylene (RPP). The board samples target density was 1.00 g/cm3. Composition of palm shell-particle and plastic were 40 : 60, 50 : 50, 60 : 40 and 70 : 30 based on particle oven dry weight with adding maleated polypropylene (MAPP) and without MAPP treatment. Weight of MAPP was 5% of RPP weight. Pressing temperature, melting time, pressing time was 1750C, 10 minutes and 2 minutes respectively. The research results showed : (1). Generally, physical properties of the boards was fulfill with the JIS A 5908-2003 Standart. (2). Mechanical properties of the boards except MOE was fulfill with the JIS A 5908-2003 Standart. (3). The quality of boards with adding MAPP were better than boards without MAPP treatment. (4). The boards could be use to exterior application.
ABSTRAK
Pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit (Elaeis guineensis jacq) dan plastik daur ulang sebagai papan komposit telah diteliti. Plastik daur ulang yang digunakan adalah recycled polypropylene (RPP). Kerapatan sasaran papan komposit adalah 1,00 g/cm3. Komposisi bahan antara partikel cangkang sawit dengan plastik adalah 40 : 60, 50 : 50, 60 : 40 dan 70 : 30 berdasarkan berat kering oven partikel, dengan perlakuan penambahan maleated polypropylene
(MAPP) dan tanpa MAPP. Banyaknya MAPP yang ditambahkan adalah 5% dari berat RPP. Suhu kempa yang digunakan adalah 1750C, sedangkan waktu pelunakan (melting time) adalah 10 menit dan waktu kempa (pressing time) adalah selama 2 menit. Hasil dari penelitian ini adalah : (1). Secara umum, sifat fisis dari papan komposit yang dihasilkan memenuhi standar JIS A 5908-2003. (2). Sifat mekanis papan komposit juga memenuhi standar JIS A 5908-2003, kecuali MOE. (3). Kualitas papan komposit dengan penambahan MAPP lebih baik dibandingkan dengan papan komposit tanpa penambahan MAPP. (4). Papan komposit dapat digunakan untuk keperluan eksterior.
Kata kunci : cangkang sawit, papan komposit, recycled polypropylene (RPP),
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kebutuhan akan kayu semakin pesat dan meningkat dengan semakin
berkembangnya pembangunan di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu
penyebab dari sekian banyak faktor yang memicu laju kerusakan hutan sehingga
industri kehutanan akan kekurangan atau akan mengalami krisis bahan baku
akibat semakin menipisnya persediaan bahan baku dari sumbernya yaitu hutan.
Pada tahun 2006 produksi kayu Indonesia sebesar 21,7 juta m3 (Dephut, 2006), padahal menurut Walhi (2004), setiap tahun industri kayu Indonesia memerlukan
100 juta m3 kayu. Dengan demikian terjadi defisit sekitar 78 juta m3. Kekurangan
pasokan yang sangat besar tersebut perlu segera diantisipasi karena akan
membahayakan kelestarian hutan dan kelanjutan industri perkayuan di Indonesia.
Kini diperkirakan tutupan hutan Indonesia tinggal sekitar 98 juta hektar,
dan paling sedikit setengahnya diyakini sudah mengalami degradasi akibat
kegiatan manusia, mulai dari perladangan berpindah sampai pembukaan lahan
perkebunan dan lahan hutan industri (HTI). Upaya untuk memperbaiki kondisi
hutan Indonesia terus dilakukan, seperti yang dilakukan pemerintah melalui
program GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) atau yang
lebih popular dengan sebutan GERHAN. Selain itu juga muncul ide-ide untuk
melakukan efisiensi terhadap pemanfaatan kayu solid, yaitu dengan mencari
alternatif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan
kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya baik kayu maupun non kayu, salah
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman
berlignoselulosa yang kini banyak diteliti baik batang maupun tandannya.
Penelitian dilakukan guna meningkatkan manfaat tanaman kelapa sawit sebagai
alternatif pengganti produk berbahan dasar kayu. Tanaman ini memiliki potensi
besar dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 5,2 juta
ha dengan menghasilkan CPO (Cruide Palm Oil) sebesar 17 juta ton pada tahun
2007. Dalam proses pengolahannya, industri ini menghasilkan limbah cair dan
limbah padat seperti tandan kosong, serat dan cangkang buah.
Cangkang kelapa sawit sebagai salah satu limbah padat dari industri
pengolahan kelapa sawit merupakan bahan berlignoselulosa. Pemanfaatan limbah
cangkang kelapa sawit dirasa belum optimal mengingat potensinya yang cukup
besar. Pada tahun 2004, dari pengolahan 53,762 juta ton TBS (tandan buah segar)
menjadi CPO dihasilkan produk samping berupa cangkang dan serat sebesar
10,215 juta ton (Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, 2007). Kini pemanfaatan
limbah cangkang kelapa sawit hanya terbatas pada bahan bakar alternatif baik
secara langsung maupun dalam bentuk briket arang.
Cangkang kelapa sawit adalah bahan berlignoselulosa yang berpeluang
dapat diolah menjadi papan komposit ataupun papan partikel karena menurut
Tsoumis (1991) papan partikel dapat dibuat dengan merekatkan partikel berupa
potongan kayu yang kecil atau mineral lain yang mengandung lignoselulosa.
Dengan kata lain, semua bahan yang mengandung lignoselulosa termasuk
cangkang kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan papan
Di dalam pembuatan papan komposit juga diperlukan perekat ataupun
matriks sebagai pengikat bahan utama ataupun bahan pengisinya. Plastik
merupakan bahan sintetis yang kini juga banyak diteliti sebagai perekat ataupun
matriks dalam pembuatan papan komposit. Dalam hal ini sampah plastik adalah
objek yang tepat, karena sampah plastik masih dianggap berbahaya dan tak ramah
lingkungan karena bahan ini tidak mudah hancur di alam, membutuhkan puluhan
hingga ratusan tahun agar sampah ini hancur bahkan plastik busa tidak akan
hancur bila dibuang begitu saja di alam. Selain itu sampah plastik memiliki
potensi yang juga besar untuk dapat dikembangkan sebagai bahan perekat atapun
matriks dalam pembuatan papan komposit, karena dari sampah yang dihasilkan di
kota-kota besar di Indonesia, 30 – 40% nya adalah sampah anorganik termasuk di
dalamnya plastik. Sebagai contoh, kota Medan pada tahun 2002 memproduksi
sampah sebesar 1.200 ton/hari atau sekitar 480 m3/ hari, dan terus meningkat hingga 1.300 ton/ hari pada tahun 2006 yang didominasi oleh sampah organik
sebesar 60 – 70% dan sisanya sampah anorganik seperti plastik dan kaleng.
Namun untuk kemampuan penanganannya hanya sekitar 80% saja.
Sejalan dengan keberhasilan dari penelitian sebelumnya, muncul suatu
istilah Komposit Polimer Kayu atau Wood Polymer Composite (WPC) untuk
menyebutkan papan komposit yang menggunakan plastik sebagai matriksnya.
Pembuatan papan komposit dengan menggunakan matriks dari limbah atau
sampah plastik, selain dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu, juga dapat
mengurangi pembebanan lingkungan terhadap limbah plastik disamping
Hal-hal tersebut di ataslah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian
ini dengan judul ”Pemanfaatan Limbah Cangkang Kelapa Sawit (Elaeis
guineensis Jacq) dan Plastik Daur Ulang Sebagai Papan Komposit”.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sifat fisis dan mekanis
papan komposit dari limbah cangkang kelapa sawit dan plastik daur ulang.
Manfaat Penelitian
Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :
1. Hasil penelitian diharapkan menjadi suatu langkah dalam pemanfaatan
limbah cangkang kelapa sawit dan sampah khususnya sampah plastik yang
berbahan dasar polipropilena yang ada di lingkungan, sehingga
keberadaannya di lingkungan tidak dianggap sebagai sampah dan limbah
serta memberikan nilai tambah atau positif terhadap limbah cangkang
sawit dan sampah plastik.
2. Hasil penelitian dapat memberikan alternatif penggunaan bahan baku
pengganti kayu yang semakin berkurang ketersediaannya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah
kekurangan bahan baku untuk keperluan bahan bangunan dan mebel.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang digunakan adalah faktor komposisi bahan (perbandingan
partikel cangkang sawit dengan plastik), faktor perlakuan bahan aditif (tanpa
dan dengan penambahan maleated polypropylene) serta interaksi keduanya akan
TINJAUAN PUSTAKA
Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq)
Sejarah Singkat
Tanaman jenis palmae yang buahnya menghasilkan minyak sawit ini
dikenal dengan nama latin Elaeis guineensis Jacq, berasal dari Afrika. Tanaman
ini dibawa dan diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1848 oleh orang Belanda
yang menanamnya di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Sekarang sawit sudah
berkembang sangat pesat pesat, terutama di Indonesia dan Malaysia. Dikatakan
bahwa secara bersamaan Indonesia dan Malaysia menguasai lebih 95% produksi
sawit dunia (FWI/ GFW, 2001).
Di Indonesia perkebunan kelapa sawit pertama kali dikembangkan dan
diusahakan secara massal di Sumatera Utara dan Lampung sejak tahun 1970
(Bakar, 2003). Kelapa Sawit saat ini telah berkembang pesat di Asia Tenggara,
khususnya Indonesia dan Malaysia, dan justru bukan di Afrika atau Amerika yang
dianggap sebagai daerah asalnya (Risza, 1994). Sawit menjadi populer setelah
revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan permintaan minyak
nabati untuk bahan pangan dan industri sabun menjadi tinggi. Bagi Indonesia,
tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan
nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada
kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa bagi negara.
Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama minyak sawit. Penyebaran
kelapa sawit di Indonesia yaitu, di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, dan
Klasifikasi Tanaman Sawit
Klasifikasi botani kelapa sawit diuraikan sebagai berikut (Pahan, 2006) :
Divisi : Embryophyta Siphonagama
Kelas : Angiospermae
Ordo : Monocotyledonae
Famili : Arecaceae (dahulu disebut Palmae)
Subfamili : Cocoideae
Genus : Elaeis
Spesies : E. guineensis Jacq
E. oleifera (H.B.K.) Cortes
E. odora
Varietas kelapa sawit digolongkan berdasarkan (Fauzi et al, 2004) :
1. Ketebalan tempurung dan daging buah, diantaranya yaitu Dura, Pisifera,
Tenera, Macrocarya, dan Diwikka-wakka.
2. Warna kulit buah yaitu : Nigrescens, Virescens, dan Albescens.
Ciri Fisiologis
Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian
vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar,
batang, dan daun, sedangkan bagian generatif yang merupakan alat
perkembangbiakan terdiri dari bunga dan buah (Fauzi et al, 2004).
Kelapa sawit tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya
berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak berwarna merah
kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung
sedangkan ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut
bungkil itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam.
Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Kelapa sawit
berkembang biak dengan biji, tumbuh di daerah tropis, pada ketinggian 0 - 500
meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur, di tempat
terbuka dengan kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi itu antara lain ditentukan
oleh adanya curah hujan yang tinggi, yaitu sekitar 2000-2500 mm setahun
(Pahan, 2006).
Daun
Seperti tanaman palma lainnya, daunnya merupakan daun majemuk. Daun
berwarna hijau tua dan pelapah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya
sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu
keras dan tajam.
Batang
Batang tanaman diselimuti bekas pelapah hingga umur 12 tahun. Setelah
umur 12 tahun pelapah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip
dengan tanaman kelapa.
Akar
Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping.
Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping
atas untuk mendapatkan tambahan aerasi.
Bunga
Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan berbeda
lancip dan panjang sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar.
Tanaman sawit dengan tipe cangkang pisifera bersifat female steril sehingga
sangat jarang menghasilkan tandan buah dan dalam produksi benih unggul.
Buah
Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah
tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul
dari tiap pelapah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah
melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas (FFA, free fatty acid) akan
meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya.
Buah terdiri dari tiga lapisan, yaitu :
1. Eksoskarp, bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin.
2. Mesoskarp, serabut buah
3. Endoskarp, cangkang pelindung inti
Inti sawit merupakan endosperm dan embrio dengan kandungan minyak inti
berkualitas tinggi (Pahan, 2006).
Potensi Kelapa Sawit
Perkebunan kelapa sawit saat ini telah berkembang tidak hanya yang
diusahakan oleh perusahaan negara, tetapi juga perkebunan rakyat dan swasta.
Tahun 2003 luas areal perkebunan rakyat mencapai 1.827 ribu ha (34,9%),
perkebunan negara seluas 645 ribu ha (12,3%), dan perkebunan besar swasta
seluas 2.765 ribu ha (52,8%). Ditinjau dari bentuk pengusahaannya, perkebunan
rakyat (PR) memberi andil produksi Crude Palm Oil (CPO) sebesar 3.645 ribu ton
(37,12%), perkebunan besar negara (PBN) sebesar 1.543 ribu ton (15,7 %), dan
juga menyebar dengan perbandingan 85,55% Sumatera, 11,45% Kalimantan, 2%,
Sulawesi, dan 1% wilayah lainnya. Produksi tersebut dicapai pada tingkat
produktivitas perkebunan rakyat sekitar 2,73 ton CPO/ha, perkebunan negara 3,14
ton CPO/ha, dan perkebunan swasta 2,58 ton CPO/ha (Departemen Pertanian
Republik Indonesia, 2005).
Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit kedua
terbesar di dunia setelah Malaysia. Tahun 2005 diperkirakan luas areal kelapa
sawit di Indonesia sekitar 3.880.000 ha, sehingga kegiatan perkebunan kelapa
sawit ini akan menghasilkan limbah padat yang mengandung lignoselulosa yang
sangat banyak (Agus, 2002 dalam Silaban, 2006). Namun pada tahun 2007
produksi minyak sawit (CPO) Indonesia telah melebihi produksi Malaysia sekitar
1 juta ton. Indonesia berhasil memproduksi 17 juta ton dengan luas areal sekitar
5,2 juta ha, sedangkan Malaysia memproduksi 16 juta ton.
Selain minyaknya, bagian lain kelapa sawit bahkan limbah masih dapat
dimanfaatkan. Pemanfaatan tanaman kelapa sawit, diketahui bukan hanya sekedar
buahnya, namun juga banyak lainnya, misalnya sisa cangkang, pelepah daun, dan
tulang daun. Sehingga dari tanaman ini nyaris tak ada bagian yang terbuang.
Pemanfaatan bagian tanaman kelapa sawit yang tengah dikembangkan, di
antaranya adalah cangkang bungkil sawit, yang dapat dijadikan sumber bahan
bakar alternatif pengganti minyak solar, selain itu bagian lain seperti tandan
kosong sawit (tankos/ TKS) dapat dijadikan bahan baku pulp dan papan komposit,
Potensi Cangkang Sawit
Cangkang sawit merupakan produk limbah padat dari industri pengolahan
kelapa sawit. Dahulu cangkang sawit tidak begitu dimanfaatkan, hanya dianggap
sebagai sampah, paling berharga hanya dimanfaatkan sebagai pelapis atau
pengeras jalan di pedesaan. Namun kini, cangkang sawit jadi berharga, limbah
produksi pabrik pengolahan kelapa sawit itu tidak hanya dimanfaatkan untuk
menutup jalan kebun yang becek.
Untuk potensi cangkang kelapa sawit pada tahun 2004, Indonesia
menghasilkan TBS (tandan buah segar) sebesar 53,762 juta ton. Dari pengolahan
TBS menjadi CPO (Crude Palm Oil) dihasilkan produk samping berupa limbah
serat dan cangkang sebesar 10,215 juta ton (Lembaga Riset Perkebunan
Indonesia, 2007). Sedangkan menurut Agustina (2004), limbah serat yang
dihasilkan sebesar 20% dan 70 kg limbah cangkang dari setiap ton tandan buah
sawit. Jadi dari 53,762 juta ton TBS yang dihasilkan, menghasilkan limbah serat
sebesar 10,752 juta ton dan limbah cangkang sebesar 3, 763 juta ton.
Penggunaan cangkang kelapa sawit sudah dilakukan oleh PTPN VIII, di
antaranya sebagai bahan bakar alternatif untuk pengolahan teh. Langkah ini sudah
dicoba sejak beberapa bulan lalu, para sejumlah unit pabrik teh yang dikelola,
bahkan sudah melakukan kerjasama dengan PTPN IV Sumut untuk pemasokan
sampai sesuai kebutuhan. Hal ini dilatarbelakangi adalah terus melakukan
terobosan untuk mencari bahan bakar alternatif yang lebih efisien, tanpa
mengurangi kualitas produk. Di luar itu, biaya produksi teh terus meningkat,
Kini harganya cukup lumayan tinggi, mencapai Rp 150 per kg, bahkan PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero) memanfaatkannya sebagai bahan bakar
pengganti solar untuk proses pelayuan dan pengeringan daun teh. Oleh karena itu,
teknologi pemanfaatan cangkang kelapa sawit (shell) selain sebagai pengganti
bahan bakar solar, kini cangkang sawit juga laku dijual, dengan harga Rp150 per
kg. Selain itu, PTPN VII juga telah menguji coba pengolahan CPO menjadi
biodiesel berikut aplikasinya (PTPN VII, 2007).
Pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif berbahan bakar
cangkang bungkil kelapa sawit mulai dilakukan oleh PTPN VIII. Mereka memilih
menggunakan cangkang bungkil kelapa sawit, selain pemanfaatan sisa produksi
tanaman, juga sebagai alternatif pilihan dibandingkan penggunaan batu bara dan
bahan bakar lainnya (Pikiran Rakyat, 2007).
Alternatif lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah limbah padat
kelapa sawit yang paling sederhana adalah menjadikannya briket arang. Caranya
dengan pemadatan melalui pembriketan, pengeringan, dan pengarangan. Pusat
Penelitian Kelapa Sawit telah berhasil merancang bangun paket teknologi untuk
produksi briket arang ini, baik dari bahan TKKS maupun cangkang sawit. Karena
sifat bahan yang berbeda, bahan TKKS memerlukan tungku tipe vertikal, sedang
untuk cangkang diperlukan tungku horizontal guna menghasilkan arang bermutu
tinggi (Nilai Kalor > 5000 kalori/gram). Proses pembriketan dapat dilakukan
dengan mesin pembriket tipe ulir dengan kapasitas satu ton per hari. Mesin ini
menghasilkan briket arang berbentuk silinder dengan diameter 5 cm dan panjang
Keunggulan produk arang ini antara lain karena permukaannya halus dan tidak
meninggalkan warna hitam bila dipegang.
Cangkang kelapa sawit termasuk bahan berlignoselulosa yang berkadar
karbon tinggi dan mempunyai berat jenis yang lebih tinggi daripada kayu yang
mencapai 1,4, sehingga karakteristik ini sangat memungkinkan bahan tersebut
yaitu cangkang kelapa sawit baik untuk dijadikan arang aktif (Nurmala dan
Hartoyo, 1988 dalam Purwaningsih et.al. 2000). Arang aktif banyak digunakan
sebagai bahan adsorbsi polutan berkadar rendah dari produk-produk industri yang
tidak dapat dipisahkan secara kimia, fisik dan biologis. Karbon aktif merupakan
adsorben untuk mengurangi kadar benda-benda organik terlarut yang ada
(Sugiharto, 1987).
Dengan limbah cangkang sawit yang cukup melimpah diharapkan industri
pemanfaatannya juga semakin berkembang. Selain untuk hal-hal di atas,
diharapkan pemanfaatannya dapat lebih berkembang, seperti untuk papan
komposit yang teknologinya juga semakin berkembang, sehingga perpaduan
keduanya dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Polimer
Polimer adalah molekul raksasa (makromolekul) yang terbentuk dari
perulangan satuan-satuan monomernya. Istilah makromelekul lebih
menggarisbawahi struktur-struktur yang kompleks. Berkembang dari pangkal
polimer alam, kini telah dikembangkan pula berbagai sistem polimer sintetik yang
rumit dan kebanyakan berasal dari bahan baku turunan minyak bumi. Beberapa
sistem polimer yang paling penting secara industri adalah karet, plastik, serat,
Polimer merupakan obyek kajian yang amat rumit. Oleh karena itu, dibuat
pengelompokan-pengelompokan polimer. Menurut Hartomo et.al. (1992), polimer
dapat dikelompokkan berdasarkan :
1. Secara struktur, terdiri dari polimer yang merupakan molekul individual, ada
yang bercabang, ada yang merupakan jaringan raksasa makroskopik. Ada
yang bercabang, ada polimer linier. Gugus-gugusnya ada yang acak, ada yang
terarah tertentu.
2. Secara keadaan fisik, terdiri dari yang kristal, nirtata (disordered), yang nirtata
dapat gelas (sifatnya getas), yang lelehan bercirikan viskositas cairan, yang
elastis seperti karet.
3. Menurut reaksinya terhadap lingkungan, yang mempengaruhi pemrosesannya
dan penggunaannya, terbagi atas thermoplastic (mempunyai suhu defleksi/
menjadi lembek) dan thermoset.
4. Pengelompokkan secara kimia sesuai dengan gugus yang dikandungnya,
terbagi atas eter, ester, hidroksil, vinil dan sebagainya.
5. Menurut pemakaiannya polimer terbagi atas perekat, serat, karet, plastik,
pelapis dan sebagainya. Banyak polimer yang dapat berfungsi lebih daripada
kelompok tersebut.
Dalam mempergunakan polimer untuk suatu keperluan, termasuk selaku
perekat, beberapa sifat bahannya harus diperhitungkan, disamping pertimbangan
ekonomis-desainnya. Hal-hal itu ialah antara lain unjuk kerja, kekerasan, rapatan,
sifat mekanis, sifat termal, sifat listrik serta tahan kimia (asam, basa, pelarut,
Plastik
Sejarah Singkat
Penemuan ebonit atau karet keras pada tahun 1839 oleh Charles Goodyear
dan penemuan seluloid oleh J.W. Hyatt sekitar 1869, merupakan awal
perkembangan industri plastik. Pada tahun 1909, bahan yang paling penting yaitu
resin phenol formaldehida dikembangkan oleh kelompok yang dipimpin Dr. L.H.
Baekeland. Setelah itu penelitian mengenai bahan sintesis meningkat dengan
cepat dan mulai dikembangkan bahan buatan dengan berbagai sifat fisik Di
Indonesia pemakaian bahan plastik, baik untuk keperluan industri, rumah tangga,
pengemasan dan keperluan lainnya meningkat dengan cepat sekitar tahun 1970-an
(Amstead, 1993).
Pengertian dan Penggolongan
Istilah plastik mencakup semua bahan yang mampu dibentuk. Dalam
pengertian modern yang lebih luas, plastik mencakup semua bahan sintetik
organik yang berubah menjadi plastis setelah dipanaskan dan mampu dibentuk di
bawah pengaruh tekanan. Bahan ini secara bertahap mulai menggantikan gelas,
kayu dan logam di bidang industri bangunan dan digunakan juga sebagai pelapis
dan serat untuk tekstil (Amstead, 1993).
Nama plastik mewakili ribuan bahan yang berbeda sifat fisis, mekanis, dan
kimia. Secara garis besar plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar,
yakni plastik yang bersifat thermoplastic dan yang bersifat thermoset.
Thermoplastic dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi
kembali. Plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari
adalah dalam bentuk thermoplastic (Setyawati, 2003).
Menurut Amstead (1993), pada waktu pemberian bentuknya plastik
termoseting memerlukan panas dengan atau tanpa tekanan dan menghasilkan
produk yang tetap keras. Mula-mula panas yang diberikan melunakkan bahan
plastiknya, akan tetapi panas tambahan atau bahan kimia khusus akan
menimbulkan perubahan kimiawi yang disebut polimerisasi dan sesudah itu
plastik tidak dapat dilunakkan lagi. Polimerisasi adalah suatu proses kimia yang
menghasilkan susunan baru dengan berat molekul yang lebih besar dari bahan
semula. Sedangkan bahan termoplastik tidak mengalami perubahan dalam
susunan kimia sewaktu dicetak dan tidak akan menjadi keras meskipun ditekan
dan dipanaskan. Jenis plastik ini tetap lunak pada suhu yang tinggi dan baru
mengeras ketika didinginkan. Selain itu termoplastik dapat dicairkan kembali
berulang-ulang dengan pemanasan kembali.
Sedangkan Hartomo et.al. (1992) mengatakan bahwa plastik termoset
biasanya tak larut dalam pelarut namun pelarut tertentu membuatnya mekar
(mengembang), namun plastik termoplastik melarut pada pelarut tertentu, yang
amorf larut, yang kristal larut pada suhu tunggi.
Berikut adalah contoh-contoh bahan dari masing-masing golongan plastik
di atas menurut Amstead (1993) :
1. Plastik Thermosetting :
• Resin Amino, resin yang terpenting adalah formaldehida-urea dan
formaldehida-melamin, dipasarkan dalam bentuk serbuk untuk dicetak atau
dalam betuk larutan untuk perekat.
• Resin Furan, berasal dari pengolahan limbah pertanian seperti tongkol
jagung dan biji kapas.
• Epoksida, banyak diguakan untuk pengecoran, pelapisan dan perlindungan
bagian-bagian listrik, campuran cat dan perekat.
• Silikon, berbeda sekali dengan bahan plastik lainnya dengan bahan dasar
atom karbon.
2. Plastik Termoplastik :
• Selulosa, merupakan produk pengolahan khusus dari serat kapas dan kayu,
jenisnya seperti asetat-butirat selulosa dan etil selulosa.
• Polisteren, merupakan bahan pengganti karet yang baik untuk isolasi listrik.
• Polietilena, memiliki fleksibilitas pada suhu ruang dan suhu rendah, kedap
air, tahan terhadap zat kimia, dapat disambung dengan dipanaskan (dipatri)
dan dapat berwarna-warni.
• Polipropilen, memiliki sifat listrik yang baik, nilai kekuatan yang tinggi dan
sangat tahan terhadap suhu dan bahan-bahan kimia.
• Polisulfona, mempunyai sifat fisis dan daya tahan panas yang baik.
• Plastik ABS, merupakan campuran akriloniteril, butadien dan stirena. Bahan
ini sangat keras, fleksibel dan ulet.
• Poli-imida, bahan ini tahan terhadap panas hingga 4000C, mempunyai koefisien gesekan yang rendah, daya tahan terhadap radiasi yang tinggi dan
• Nilon (Poli-amida), digunakan sebagai serat tekstil atau filamen.
• Resin Aklirik, memiliki daya tembus cahaya yang sangat baik, mudah dibuat
dan tahan terhadap kelembaban, yang paling banyak digunakan ialah
metal-metalrilat dengan nama dagang Lucite (duPont) dan Plexiglas (Rohm Haas),
yang banyak digunakan sebagai jendela pesawat terbang.
• Resin Vinil, terdiri dari polivinil-klorida (mempunyai daya tahan baik
terhadap pelarut dan tidak mudah terbakar), polivinil-butirat (jernih, liat dan
produk cetak yang fleksibel) dan poliviniliden-klorida (digunakan untuk
pengemasan makanan dan pipa).
• Karet Sintesis, dibuat oleh negara-negara industri yang tidak memiliki
sumber karet alamiah, karet sintesis yang telah dikenal adalah GR-S, nitril,
thiokol, neopren, butil dan karet silikon.
Polipropilena
Polipropilena (PP) adalah merupakan salah satu polimer termoplastik,
yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi
seperti, pembungkus makanan, bahan tekstil, barang-barang plastik dan berbagai
jenis barang bekas yang boleh digunakan lagi serta komponen-komponen
otomotif. Menurut Amstead (1993), polipropilenadapat dibentuk dengan berbagai
teknik termoplastik. Bahan ini memiliki sifat-sifat listrik yang baik, nilai impak
dan kekuatan yang tinggi, sangat tahan terhadap suhu dan bahan-bahan kimia.
Filament tunggal polipropilena dianyam menjadi tali/ tambang, jala dan tekstil.
Contoh produk lain adalah alat untuk peralatan rumah sakit dan laboratorium,
mainan anak-anak, koper, perabot, lembaran untuk pengemasan makanan, kotak
Gambar 1. Rumus Bangun Polipropilena
Bost (1980) dalam Syarief et.al. (1989), mengatakan bahwa sifat-sifat
utama polipropilena yaitu :
1. Ringan (kerapatan 0,90 g/ cm3), mudah dibentuk, tembus pandang dan jernih dalam bentuk film.
2. Mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar dari polietilena, pada suhu rendah
akan rapuh, dalam bentuk murni pada suhu -300C mudah pecah sehingga perlu ditambah polietilena atau bahan lain untuk memperbaiki ketahanan terhadap
benturan.
3. Lebih kaku dari polietilena dan tidak gampang sobek sehingga lebih mudah
penanganannya.
4. Permeabilitas uap air redah, perrmeabilitas gas sedang.
5. Tahan terhadap suhu tinggi sampai dengan 1500C. 6. Titik leleh cukup tinggi pada suhu 1700C.
7. Tahan terhadap asam kuat, basa dan minyak, tidak terpengaruh oleh pelarut
pada suhu kamar kecuali HCl.
8. Pada suhu tinggi polipropilena akan bereaksi dengan benzene, siklena,
toluene, terpentin dan asam nitrat kuat.
Tabel 1. Karakteristik Polipropilena
Deskripsi Polipropilena
Kerapatan pada suhu 200C (g/ cm3) Suhu melunak (0C)
Titik lebur (0C) Kristalinitas (%) Indeks fluiditas MOE (x 104 kg/ cm2)
Tahanan volumetrik (ohm/ cm2) Konstanta dielektrik (60 – 108 cycles) Permeabilitas gas
Nitrogen Oksigen Gas karbon Uap air
[image:33.595.264.359.416.533.2]0,90 149 170 60 – 70 0,2 – 2,5 1,1 – 1,3 1017 2,3 - 4,4 23 92 600 Sumber : Bost (1980) dalam Syarief et.al. (1989)
Gambar 2. Kode Identitas Resin dari Polipropilena
Sampah ; Limbah Plastik menjadi Plastik Daur Ulang
Azwar (1990) mengatakan bahwa sampah adalah sebagian dari suatu yang
tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, umumnya berasal dari
kegiatan manusia dan bersifat padat. Pengertian dikemukakan oleh Hadiwijoto
(1983), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah
bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi
lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam.
Murtadho dan Gumbira (1988) membedakan sampah atas sampah organik
dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa
bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah
ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorgaisme dan mudah membusuk
karena memiliki rantai karbon relatif pendek. Sedangkan sampah anorganik
berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme
karena memilki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi,
plastik dan lain-lain.
Menurut Hadiwijoto (1983) kategori sumber penghasil sampah yang
sering digunakan adalah :
1. Sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman.
2. Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan
atau jasa komersial berupa toko, pasar, rumah makan dan kantor.
3. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari suatu proses produksi.
4. Sampah yang berasal selain dari yang disebutkan di atas misalnya sampah dari
pepohonan, sapuan jalan dan bencana alam.
Seperti penjelasan di atas bahwa sampah adalah barang yang dianggap
tidak bermanfaat, namun kini sampah merupakan salah satu peluang besar
sebagian besar rakyat miskin Indonesia untuk tempat mencari nafkah. Mereka
mengumpulkan kembali apa yang dianggap sampah, seperti sampah plastik untuk
Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan plastik terus
meningkat. Data BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa volume perdagangan
plastik impor Indonesia, terutama polipropilena (PP) pada tahun 1995 sebesar
136.122,7 ton sedangkan pada tahun 1999 sebesar 182.523,6 ton, sehingga dalam
kurun waktu tersebut terjadi peningkatan sebesar 34,15%. Jumlah tersebut
diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai
konsekuensinya, peningkatan limbah plastikpun tidak terelakkan. Menurut
Hartono (1998) komposisi sampah atau limbah plastik yang dibuang oleh setiap
rumah tangga adalah 9,3% dari total sampah rumah tangga. Di Jabotabek rata-rata
setiap pabrik menghasilkan satu ton limbah plastik setiap minggunya. Jumlah
tersebut akan terus bertambah, disebabkan sifat-sifat yang dimiliki plastik, antara
lain tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air,
maupun tidak dapat berkarat, dan pada akhirnya akhirnya menjadi masalah bagi
lingkungan (YBP, 1986).
Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya menekan pembuangan
plastik seminimal mungkin dan dalam batas tertentu menghemat sumber daya dan
mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Pemanfaatan limbah plastik dapat
dilakukan dengan pemakaian kembali (reuse) maupun daur ulang (recycle). Di
Indonesia, pemanfaatan limbah plastik dalam skala rumah tangga umumnya
adalah dengan pemakaian kembali dengan keperluan yang berbeda, misalnya
tempat cat yang terbuat dari plastik digunakan untuk pot atau ember. Sisi jelek
pemakaian kembali, terutama dalam bentuk kemasan adalah sering digunakan
untuk pemalsuan produk seperti yang seringkali terjadi di kota-kota besar
Pemanfaatan limbah plastik dengan cara daur ulang umumnya dilakukan
oleh industri. Secara umum terdapat empat persyaratan agar suatu limbah plastik
dapat diproses oleh suatu industri, antara lain limbah harus dalam bentuk tertentu
sesuai kebutuhan (biji, pellet, serbuk, pecahan), limbah harus homogen, tidak
terkontaminasi, serta diupayakan tidak teroksidasi. Untuk mengatasi masalah
tersebut, sebelum digunakan limbah plastik diproses melalui tahapan sederhana,
yaitu pemisahan, pemotongan, pencucian, dan penghilangan zat-zat seperti besi
dan sebagainya (Sasse et.al.,1995).
Terdapat hal yang menguntungkan dalam pemanfaatan limbah plastik di
Indonesia dibandingkan negara maju. Hal ini dimungkinkan karena pemisahan
secara manual yang dianggap tidak mungkin dilakukan di negara maju, dapat
dilakukan di Indonesia yang mempunyai tenaga kerja melimpah sehingga
pemisahan tidak perlu dilakukan dengan peralatan canggih yang memerlukan
biaya tinggi. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya industri daur ulang
plastik di Indonesia (Syafitrie, 2001).
Pemanfaatan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali barang-barang
plastik telah berkembang pesat. Hampir seluruh jenis limbah plastik (80%) dapat
diproses kembali menjadi barang semula walaupun harus dilakukan pencampuran
dengan bahan baku baru dan additive untuk meningkatkan kualitas produknya
(Syafitrie, 2001). Menurut Hartono (1998) empat jenis limbah plastik yang
populer dan laku di pasaran yaitu polietilena (PE), High Density Polyethylene
Wood Polymer Composite (WPC) ; Plastik Daur Ulang sebagai Matriks
Wood Polymer Composite (WPC) atau dalam bahasa Indonesia disebut
dengan Komposit Polimer Kayu adalah komposit yang mengandung kayu dari
berbagai bentuk yang berfungsi sebagai pengisi (filler) dan resin thermoset
ataupun thermoplastic yang berfungsi sebagai matriks atau perekat. Kelahiran
industri WPC menyangkut pertemuan dua industri yaitu, industri kayu dan plastik,
yang keduanya memiliki pengetahuan, kepakaran dan perspektif yang sangat
berbeda. Sampai saat ini industri WPC masih merupakan bagian kecil dari
keseluruhan industri perkayuan, namun sudah menciptakan pasar tertentu
terutama di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Menurut studi pasar terkini di
USA, pasar WPC adalah 320 ribu ton pada tahun 2001 dan diprediksi akan
meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2005 (Clemons, 2002).
Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk
yang terbuat dari lembaran atau potongan–potongan kecil kayu yang direkat
bersama-sama (Maloney,1996). Mengacu pada pengertian di atas, komposit
serbuk kayu plastik adalah komposit yang terbuat dari plastik sebagai matriks dan
serbuk kayu sebagai pengisi (filler), yang mempunyai sifat gabungan keduanya.
Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan mengurangi densitas,
meningkatkan kekakuan, dan mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu,
dengan adanya matrik polimer didalamnya maka kekuatan dan sifat fisiknya juga
akan meningkat (Febrianto, 1999).
Pembuatan komposit dengan menggunakan matriks dari plastik yang telah
didaur ulang, selain dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu, juga dapat
menghasilkan produk inovatif sebagai bahan bangunan pengganti kayu.
Keunggulan produk ini antara lain : biaya produksi lebih murah, bahan bakunya
melimpah, fleksibel dalam proses pembuatannya, kerapatannya rendah, lebih
bersifat biodegradable (dibanding plastik), memiliki sifat-sifat yang lebih baik
dibandingkan bahan baku asalnya, dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan,
serta bersifat dapat didaur ulang (recycleable). Beberapa contoh penggunaan
produk ini antara lain sebagai komponen interior kendaraan (mobil, kereta api,
pesawat terbang), perabot rumah tangga, maupun komponen bangunan (jendela,
pintu, dinding, lantai dan jembatan) (Febrianto, 1999: Youngquist, 1995).
Pada dasarnya pembuatan komposit serbuk kayu plastik daur ulang tidak
berbeda dengan komposit dengan matriks plastik murni. Komposit ini dapat
dibuat melalui proses satu tahap, proses dua tahap, maupun proses kontinyu. Pada
proses satu tahap, semua bahan baku dicampur terlebih dahulu secara manual
kemudian dimasukkan ke dalam alat pengadon (kneader) dan diproses sampai
menghasilkan produk komposit. Pada proses dua tahap bahan baku plastik
dimodifikasi terlebih dahulu, kemudian bahan pengisi dicampur secara bersamaan
di dalam kneader dan dibentuk menjadi komposit. Kombinasi dari tahap-tahap ini
dikenal dengan proses kontinyu. Pada proses ini bahan baku dimasukkan secara
bertahap dan berurutan di dalam kneader kemudian diproses sampai menjadi
produk komposit (Han dan Shiraishi, 1990). Umumnya proses dua tahap
menghasilkan produk yang lebih baik dari proses satu tahap, namun proses satu
Diagram proses dasar pembuatan produk disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Proses Dasar Pembuatan WPC
Pemanfaatan plastik daur ulang dalam bidang komposit kayu di Indonesia
masih terbatas pada tahap penelitian. Ada dua strategi dalam pembuatan komposit
kayu dengan memanfaatkan plastik, pertama plastik dijadikan sebagai binder
sedangkan kayu sebagai komponen utama; kedua kayu dijadikan bahan pengisi/
filler dan plastik sebagai matriksnya. Penelitian mengenai pemanfaatan plastik
polipropilena daur ulang sebagai substitusi perekat termoset dalam pembuatan
papan partikel telah dilakukan oleh Febrianto et.al. (2001). Produk papan partikel
yang dihasilkan memiliki stabilitas dimensi dan kekuatan mekanis yang tinggi
dibandingkan dengan papan partikel konvensional. Penelitian plastik daur ulang
sebagai matriks komposit kayu plastik dilakukan Setyawati (2003) dan Sulaeman
(2003) dengan menggunakan plastik polipropilena daur ulang. Dalam pembuatan
komposit kayu plastik daur ulang, beberapa polimer termoplastik dapat digunakan
sebagai matriks, tetapi dibatasi oleh rendahnya temperatur permulaan dan
pemanasan dekomposisi kayu (lebih kurang 200°C).
Berikut ini adalah hasil penelitian pembuatan papan komposit dengan
menggunakan polipropilena daur ulang sebagai perekat : Penyiapan Filler
Penyiapan Matriks
Tabel 2. Sifat Fisis Mekanis Beberapa Hasil Penelitian Pembuatan WPC dengan Menggunakan Polipropilena Daur Ulang
Sifat Fisis Mekanis SNI
03-2105-1996
JIS A 5908-2003
Setyawati (2003)
Mulyadi (2001)
Putri (2002)
Kerapatan (g/cm3) 0,5 – 0,9 0,4 - 0,9 0,64 - 0,66 0,73 0,77
Kadar Air (%) <14 5-13 3,30 - 4,07 4,00 1,37
Daya Serap air (%) - - 3,51- 17,36 8,50 7,92
Pengembangan Tebal (%) Maks 12 Maks 12 0 - 2,02 1,60 2,07
MOR (kg/cm2) Min 80 Min 80 125 - 176 79,68 95,03
MOE (x 104 kg/cm2) Min 1,5 Min 2,0 0,87 – 1,14 0,93 1,11
Internal Bond (kg/cm2) Min 1,5 Min 1,5 5,25 3,30
Kuat Pegang Sekrup (kg) Min 30 Min 30 49 - 64 43 78,90
Linear Expanssion (%) - -
Hardness (N) - -
METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2008 sampai dengan September
2008. Pembuatan papan komposit dilaksanakan di Laboratorium Kimia Polimer,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan di Laboratorium Teknologi
Hasil Hutan, Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera
Utara, pengujian sifat fisis dilaksanakan di Laboratorium Biologi Tanah, Fakultas
Pertanian, Universitas Sumatera Utara dan pengujian sifat mekanis di
Laboratorium Biokomposit, Departemen Teknologi Hasil Hutan, Fakultas
Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, mesin grinder
sebagai alat penghancur cangkang sawit menjadi partikel, ember, wadah plastik
dan kantung plastik sebagai tempat pengumpulan partikel, extruder sebagai alat
untuk mencampur atau alat pengadon plastik dengan partikel cangkang sawit agar
hasil lebih merata dan seragam, kaliper untuk pengukuran dimensi, oven untuk
pengeringan bahan baku dan pengujian sifat fisis, neraca untuk mengukur berat
bahan baku dan sampel, frame besi ukuran 25cm x 25cm x 0,5cmdan lembaran
besi tipis atau seng dengan ukuran ≥ 30cm x 30 cm untuk mencetak lembaran
papan, mesin circular saw untuk pemotongan contoh uji, mesin cold dan hot press
untuk pengempaan, alat Universal Testing Machine merk Instron untuk pengujian
sifat mekanis, alat tulis, penggaris dan kertas label, gunting dan cutter, kipas angin
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah partikel
cangkang sawit (Elaeis guineensis) sebagai filler (bahan pengisi), polipropilena
daur ulang atau recycled polypropylene (RPP) berbentuk pellet sebagai matriks
dan maleated polypropylen (MAPP) sebagai bahan aditif.
Persiapan Bahan Baku
Limbah cangkang kelapa sawit diperoleh dari pabrik kelapa sawit dipilih
dan dibersihkan dari kotoran lain seperti serat buah dan inti buah yang masih
bercampur dengan cangkang sawit. Lalu cangkang sawit dibersihkan dari kotoran
tanah atau debu yang terikut dengan cara dibersihkan dengan air, kemudian
dijemur hingga kering. Setelah kering cangkang sawit ditumbuk hingga berbentuk
partikel. Partikel tersebut dikeringkan hingga kadar air 4 – 6%.
RPP yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP yang berasal
dari gelas air mineral (thermoforming) yang telah didaur ulang dengan mesin
[image:42.595.188.436.479.666.2]boker hingga menjadi berbentuk pellet.
Proses Pembuatan Papan Komposit
Proses pembuatan papan komposit dapat dilihat dari diagram pada Gambar
[image:43.595.113.512.148.734.2]6 berikut :
Gambar 5. Diagram Proses Pembuatan Papan Komposit Limbah Cangkang Kelapa Sawit
Dicuci hingga bersih dan lalu dikeringkan
Ditumbuk dan dihancurkan hingga menjadi partikel
Pembentukan Papan WPC
Dikempa panas 1750C
Produk WPC dari Limbah Cangkang Kelapa Sawit dan RPP
Pengkondisian 10 hari
Pembuatan contoh uji
Pengujian sifat fisis dan mekanis
Kualitas Papan Komposit
Dikeringkan hingga kadar air 4– 6%
Pengadonan (Blending)
Ditambah MAPP Ditambah RPP
Pembuatan Adonan (Blending)
Serbuk atau partikel cangkang kelapa sawit yang telah dikeringkan dan PP
daur ulang (RPP) dimasukkan dalam bak pencampur kemudian dilakukan
pengadonan. Pengadonan dilakukan dengan alat extruder bertujuan agar hasil
campuran lebih merata dan seragam. Extruder terlebih dahulu dipanaskan pada
suhu 1750 C. Kemudian masukkan campuran bahan ke dalam extruder. Hasil adonan selanjutnya dibentuk kembali menjadi pellet dengan cara digunting.
Kebutuhan partikel cangkang dan PP daur ulang yang digunakan untuk
pembuatan sebuah papan komposit tergantung pada perlakuan yang dilakukan dan
[image:44.595.114.513.400.608.2]kerapatan sasaran. Kerapatan sasaran yang dipakai yaitu sebesar 1,00 g/cm3. Komposisi perbandingan dan banyaknya bahan baku disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Komposisi Kebutuhan Bahan Baku Papan Polimer.
Perlakuan Perbandingan
Bahan (%)
Partikel Cangkang (g)
RPP (g) MAPP (g)
Tanpa Aditif (tanpa MAPP) Serbuk + RPP
40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30
125 156,25 187,5 218,75 187,5 156,25 125 93,75 - - - - Penambahan Aditif (MAPP) Serbuk + RPP
40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30
125 156,25 187,5 218,75 187,5 156,25 125 93,75 9,375 7,81 6,25 4,69 Keterangan : Berat maleated polypropylene (MAPP) adalah 5% dari berat RPP.
Pengempaan
Setelah diadon, adonan diletakkan di antara dua plat alumunium dan
pelunakan (melting time) dan dua menit terakhir adalah waktu pengepresan
(pressing time).
Pengkondisian
Selanjutnya cetakan lembaran dikeluarkan dari alat kempa. Lembaran
yang masih dalam keadaan sangat lunak dibiarkan ± 10 menit agar terjadi
pengerasan plastik (matriks) sebelum dikeluarkan dari cetakan. Kemudian
dilakukan pengkondisian selama sepuluh hari untuk mencapai distribusi kadar air
yang seragam dan melepaskan tegangan sisa dalam papan akibat pengempaan.
Setelah itu, papan yang dihasilkan disimpan dalam plastik pengkondisian sebelum
diuji.
Pembuatan Contoh Uji
[image:45.595.170.464.444.699.2]Pola dan ukuran contoh uji dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini:
Keterangan :
A : Contoh Uji untuk Kadar Air dan Kerapatan (5 cm x 5 cm)
B : Contoh Uji untuk MOR dan MOE (15 cm x 5 cm)
C : Contoh Uji untuk Daya Serap Air dan Pengembangan Tebal (5 cm x 5 cm)
D :Contoh Uji untuk InternalBond (5 cm x 5 cm) E : Contoh Uji untuk Kuat Pegang sekrup (10 cm x 5 cm)
Pengujian
Pengujian sifat-sifat papan komposit menggunakan standar Japanesse
Industrial Standart (JIS) A 5908-2003, Based Particleboard dan Decorative
Particleboard, Type 8. Berdasarkan sifat mekanisnya, papan partikel
dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu :
a. Based Particleboard and Decorative Particleboard
b.Based Particleboard
c. Veneered Particleboard
Tabel 4. Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel dengan Standar JIS, Based Particleboard dan Decorative Particleboard, Type 8.
No. Sifat Fisis Mekanis JIS A 5908-2003
1. Kerapatan (g/cm3) 0,4-0,9
2. Kadar Air (%) 5-13
3. Daya Serap air (%) -
4. Pengembangan Tebal (%) Maks 12
5. MOR (kgf/cm2) Min 80
6. MOE (kgf/cm2) Min 2,0 x 104
7. Internal Bond (kgf/cm2) Min 1,5
[image:46.595.112.456.472.666.2]Pengujian Sifat Fisis Papan Komposit
a. Kerapatan
Pengujian kerapatan dilakukan pada kondisi kering udara dan volume
kering udara. Contoh uji berukuran 5cm x 5cm x 0,5 cm ditimbang beratnya, lalu
diukur rata-rata panjang, lebar, dan tebalnya untuk menentukan volume contoh
uji. Titik pengukuran dimensi disajikan pada Gambar 8. Nilai kerapatan papan
komposit dihitung dengan rumus :
Kerapatan (g/cm3) =
) (
) (
3 cm Volume
[image:47.595.206.416.345.536.2]gram Berat
Gambar 7. Titik Pengukuran Dimensi Contoh Uji
b.Kadar Air (KA)
Contoh uji berukuran 5cm x 5cm x 0,5cm yang digunakan adalah bekas
contoh uji kerapatan. Kadar air papan komposit dihitung berdasarkan berat awal
(BA) dan berat kering tanur (BKT) pada suhu 103 ± 2 0C hingga berat stabil. Nilai kadar air papan komposit dihitung berdasarkan rumus :
Kadar Air (%) =
BKT BKT BA−
c. Daya Serap Air
Contoh uji berukuran 5cm x 5cm x 0,5cm ditimbang berat awalnya (B1).
Kemudian direndam dalam air pada suhu kamar selama 2 dan 24 jam, setelah itu
ditimbang beratnya (B2). Nilai daya serap air papan komposit dihitung
berdasarkan rumus :
Daya Serap air (%) =
1 1 2 B B B − x 100%
d. Pengembangan Tebal
Contoh uji berukuran 5cm x 5cm x 0,5cm sama dengan contoh uji daya
serap air. Pengembangan tebal didasarkan pada tebal sebelum (T1) yang diukur
pada keempat sudut dan dirata-ratakan dalam kondisi kering udara dan tebal
setelah perendaman (T2) dalam air pada suhu kamar selama 2 dan 24 jam. Nilai
pengembangan tebal papan komposit dihitung berdasarkan rumus :
Pengembangan Tebal (%) =
1 1 2 T T T − x 100%
Pengujian Sifat Mekanis Papan Komposit
a. MOR (Modulus of Rupture)
Pengujian keteguhan patah dilakukan dengan menggunakan alat Universal
Testing Machine dengan lebar bentang (jarak penyangga) 15 kali tebal nominal.
Nilai MOR dapat dihitung dengan rumus :
MOR = 2
. . 2 . . 3 d b L P
Dimana : MOR : Modulus patah (kg/cm2) P : Beban maksimum (kg)
L : Jarak sangga (cm)
Contoh uji yang digunakan berukuran 0,5cm x 5cm x 15cm pada kondisi
kering udara dengan pola pembebanan disajikan pada Gambar 9.
P (tekanan)
Contoh Uji
L/2 L/2
[image:49.595.174.443.138.236.2]L
Gambar 8. Cara Pengujian Modulus of Rupture dan Modulus of Elasticity
b. MOE (Modulus of Elasticity)
Pengujian MOE dilakukan bersama-sama dengan pengujian keteguhan
patah dengan memakai contoh uji yang sama. Besarnya defleksi yang terjadi pada
saat pengujian dicatat pada setiap selang beban tertentu. Nilai MOE dapat
dihitung dengan rumus :
MOE = 3
3 . . . 4 . d b Y L P
∆∆ Dimana : MOE : Modulus lentur (kg/cm
2
)
∆P : Beban sebelum batas proporsi (kg) L : Jarak sangga (cm)
∆Y : Lenturan pada beban (cm) b : Lebar contoh uji (cm) d : Tebal contoh uji (cm)
c. Keteguhan Rekat Internal (Internal Bond)
Contoh uji berukuran 5cm x 5cm x 0,5cmdirekatkan pada dua buah blok
alumunium dengan perekat epoksi dan dibiarkan mengering. Kedua blok ditarik
tegak lurus permukaan contoh uji hingga beban maksimum. Pengujian keteguhan
rekat internal disajikan pada Gambar 10. Nilai keteguhan rekat internal dapat
IB =
A Pmax
Dimana : IB : Keteguhan rekat internal (kg/cm2) Pmax : Beban maksimum (kg)
[image:50.595.123.447.91.369.2]A : Luas permukaan contoh (cm2)
Gambar 9. Cara Pengujian Keteguhan Rekat
d. Kuat Pegang Sekrup (Screw Holding Power)
Gambar 10. Posisi Sekrup pada Pengujian Kuat Pegang Sekrup
Contoh uji berukuran 10cm x 5cm x 0,5cm. Sekrup yang digunakan
berdiameter 2,7 mm, panjang 16 mm dimasukkan hingga mencapai kedalaman 8
mm. Nilai kuat pegang sekrup dinyatakan oleh besarnya beban maksimum yang
[image:50.595.183.445.429.591.2]Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis ragam
Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu
komposisi bahan (partikel cangkang sawit dan RPP) dengan perbandingan 40 : 60,
50 : 50, 60 : 40 dan 70 : 30 dan perlakuan bahan aditif (tanpa dan dengan
penambahan MAPP), dengan kadar MAPP sebesar 5% dari berat RPP.
Masing-masing dengan 3 ulangan sehingga menghasilkan jumlah sampel papan sebanyak
24 papan. Sedangkan uji lanjutannya menggunakan Duncan Multiple Range Test
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Fisis Papan Komposit
Kerapatan
Kerapatan merupakan salah satu sifat fisis yang menunjukkan
perbandingan antara massa benda terhadap volumenya atau dengan kata lain
menunjukkan banyaknya massa zat persatuan volume. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai kerapatan papan komposit yang dihasilkan cukup
seragam berkisar antara 0,90 g/cm3 sampai dengan 0,98 g/cm3, yang terendah merupakan kerapatan pada papan komposit tanpa penambahan MAPP (pada
perbandingan komposisi 70 : 30) dan yang tertinggi merupakan papan komposit
dengan penambahan MAPP (pada perbandingan komposisi 40 : 60). Dari hasil
penelitian juga terlihat bahwa kerapatan papan komposit dengan penambahan
MAPP lebih tinggi dari pada papan komposit tanpa penambahan MAPP untuk
semua perbandingan komposisi bahan. Hasil kerapatan pada penelitian ini secara
lengkap disajikan pada Gambar 12.
0,91 0,98 0,940,95 0,950,95 0,90 0,97
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30
Komposisi Partikel Cangkang : RPP (%)
K
er
apat
an (
g/
c
m
3)
[image:52.595.161.536.527.708.2]Tanpa MAPP Penambahan MAPP
Gambar 11. Grafik Nilai Kerapatan Papan Komposit.
Kerapatan yang dihasilkan hampir mencapai kerapatan sasaran yang diinginkan
yaitu 1,00 g/cm3. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi partikel cangkang kelapa
sawit dengan Recycled Polypropylene (RPP) pada saat pembentukkan lembaran (mat
forming) papan komposit dapat dilakukan dengan cukup baik. Baiknya distribusi
juga disebabkan oleh adanya proses pengadonan (blending) dengan extruder
[image:53.595.180.445.245.441.2]sehingga hasil campuran lebih seragam.
Gambar 12. Contoh Uji Papan Komposit dari Limbah Cangkang Sawit dan Plastik Daur Ulang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa papan komposit yang dihasilkan
termasuk dalam kategori papan komposit dengan kerapatan tinggi. Kategori ini
disesuaikan dengan penggolongan menurut Tsoumis (1991) yang membagi papan
partikel menjadi papan partikel berkerapatan rendah (0,25-0,40 g/cm3), berkerapatan medium (0,40-0,80 g/cm3), dan berkerapatan tinggi (0,80-1,20 g/cm3).
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa kedua faktor yaitu
perlakuan bahan aditif (tanpa dan dengan penambahan MAPP) dan komposisi
bahan tidak menunjukkan adanya perbedaan hasil rata-rata, sehingga disimpulkan
komposit yang dihasilkan. Dari hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak ada
interaksi antara kedua faktor tersebut.
Japanesse Industrial Standart (JIS) A 5908-2003, Based Particleboard
dan Decorative Particleboard, Type 8, mensyaratkan nilai kerapatan papan
partikel sebesar 0,40 g/cm3 – 0,90 g/cm3. Semua papan komposit yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, bahkan sedikit melampaui standar
yang disyaratkan, kaarena memang dibuat pada kerapatan sasaran 1,00 g/cm3.
Kadar Air
Kadar air menunjukkan besarnya kandungan air di dalam suatu benda
yang dinyatakan dalam persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air
papan komposit yang dihasilkan berkisar antara 0,38% untuk perlakuan komposisi
40 : 60 dengan penambahan MAPP sampai dengan 2,64% untuk perakuan
komposisi 70 : 30 tanpa penambahan MAPP. Hasil kadar air pada penelitian ini
secara lengkap disajikan pada Gambar 14.
0,64
1,67 2,33 2,64
0,38
1,65 1,77 2,42
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30
Komposisi Partikel Cangkang : RPP (%)
K a d a r A ir (% )
[image:54.595.161.513.489.672.2]Tanpa MAPP Penambahan MAPP
Gambar 13. Grafik Nilai Kadar Air Papan Komposit.
Hasil penelitian menunjukkan nilai kadar air yang rendah. Hal itu
sehingga papan komposit tidak mudah menyerap uap air dari lingkungan. Kadar
air papan komposit yang dihasilkan lebih kecil dari pada kadar air bahan bakunya
yaitu partikel cangkang kelapa sawit (4 – 6 %), hal ini disebabkan oleh perlakuan
panas pada saat blending dan pada saat pengempaan panas yang keduanya
menggunakan suhu ekstrim 1750C. Selain itu plastik yang digunakan sebagai matriks akan menutupi sebagian permukaan papan komposit dan menyebabkan
partikel cangkang kelapa sawit tidak bebas menyerap air sebagai akibat adanya
ikatan rekat dari plastik. Keterangan tersebut sesuai dengan pernyataan Massijaya,
et.al. (1999) yang menyatakan bahwa umumnya kadar air papan partikel lebih
rendah dari pada kadar air bahan bakunya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari
perlakuan panas yang diterima papan partikel kayu pada saat pengempaan panas
dan secara teoritis penambahan partikel plastik akan mengurangi kemampuan
papan partikel secara keseluruhan untuk menyerap air.
Hasil penelitian yang terlihat pada Gambar 14 menunjukkan bahwa kadar
air rata-rata pada perlakuan penambahan MAPP sedikit lebih rendah dibanding
dengan tanpa penambahan MAPP untuk semua perbandingan komposisi bahan.
Hal tersebut terjadi karena penambahan MAPP akan memperbaiki ikatan antar
partikel, MAPP akan mengisi kekosongan rongga antara partikel cangkang
dengan plastik, sehingga meminimalkan penetrasi air yang masuk ke dalam
rongga papan. Sedangkan berdasarkan komposisi bahan menunjukkan semakin
banyak kadar serbuk cangkang kelapa sawit maka kadar air juga semakin tinggi.
Hal ini disebabkan oleh sifat cangkang kelapa sawit yang hidrofilik.
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa faktor perlakuan bahan
perbedaan hasil rata-rata, sehingga menunjukkan tidak begitu berpengaruhnya
faktor tersebut terhadap kadar air yang dihasilkan. Akan tetapi faktor komposisi
bahan memperlihatkan adanya perbedaan nilai rata-rata, sehingga disimpulkan
bahwa faktor tersebut berpengaruh terhadap kadar air papan komposit yang
dihasilkan. Analisis juga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara kedua
faktor tersebu