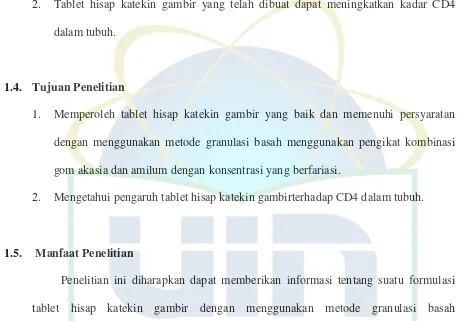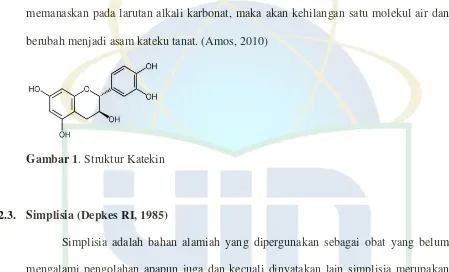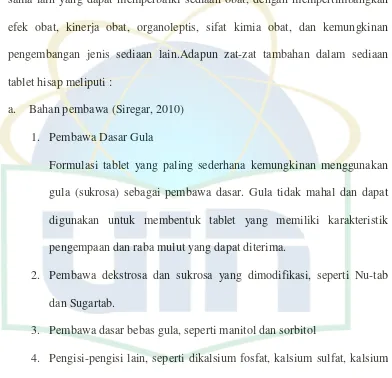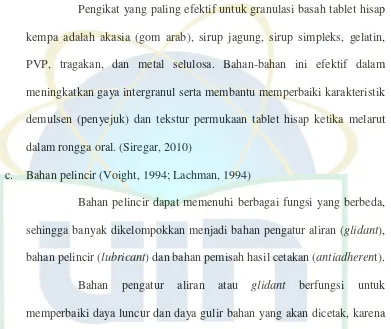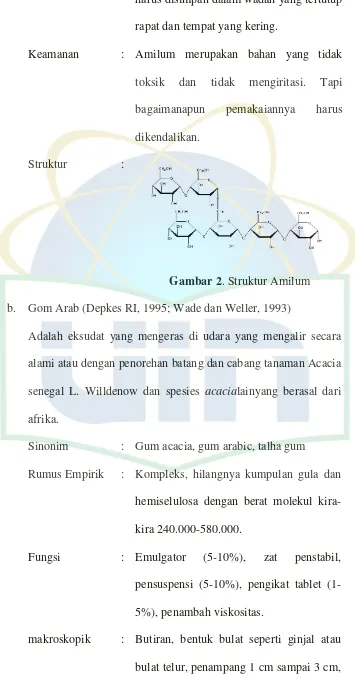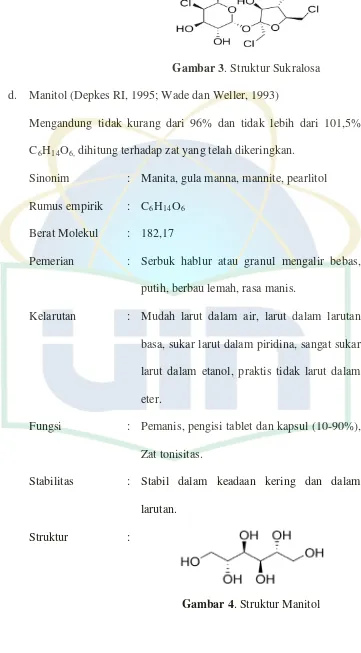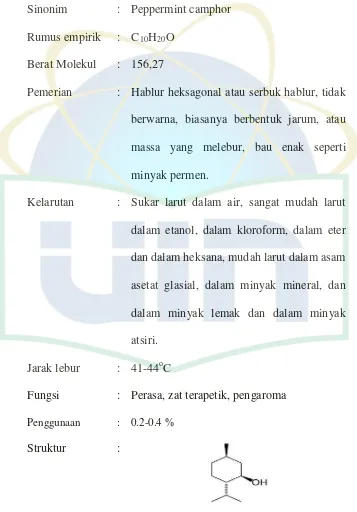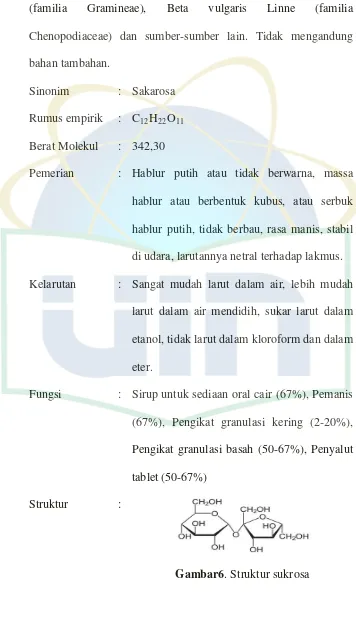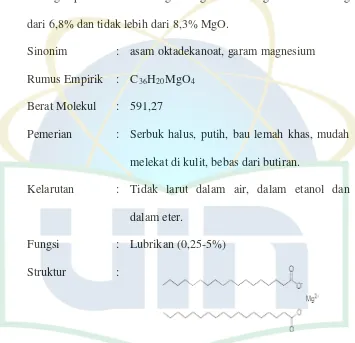FORMULASI SEDIAAN TABLET HISAP KATEKIN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DENGAN METODE
GRANULASI BASAH
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi
Disusun oleh : MAY MALIA DEWI
107102000187
PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
iv KATA PENGANTAR
Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad
SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga
akhir zaman.
Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun judul
skripsi ini adalah “Formulasi Sediaan Tablet Hisap Katekin Gambir (Uncaria gambir
Roxb) Sebagai Imunomodulator Dengan Metode Granulasi Basah”.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr, (hc) dr. M. K. Tadjudin, Sp.And selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc, Apt. selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas
kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga sebagai
pembimbing I yang tidak segan-segan untuk menyisihkan waktu serta memberikan
bimbingan dan ilmu kepada penulis.
3. Sabrina, M.Farm, Apt. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan
pikiran untuk membimbing penulis.
4. Ibu/Bapak Dosen dan Staf Akademia Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Orang tuaku Hasan Nausin dan Siti Yumnah S.Pd. yang tiada henti mendoakan dan
memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang kepada penulis.
6. Kakekku H.M. Yusuf Djaib serta keluarga besar H.M. Yusuf Djaib yang selalu
mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis.
7. Kakakku Abdul Rahman Hakim, S.Pd.I yang selalu mendoakan dan tanpa lelah
v adikku yang manis Dea Gustiana Putri yang selalu membuat penulis tersenyum saat lelah
dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman relawan CD4 Rizky kurniawan, Ridwan Maulana, Husain Nur Aminudin,
Ahmad Kurniawan, Abidilah Syawaludin dan Muhardi Ritonga.
9. Rachmadi Wibowo, Eris Risenti, Rani Hestiningrum, Lisna fauziah, Yopi mulyana,
Golda Liken, bapak Jejen, Bapak Irfan, Ibu Nilda dan Ibu Sri Makmal Terpadu
Imunoendokrinologi FKUI yang sangat membantu dalam proses penelitian Skripsi ini.
10. Katekiners dan Eugenolism St. Ratna Juminar, Hj. Tina Puspita , Iftitah Rahmah, Dahlia
Sari, Devy Hilfiani, Yunia Wiraswasti, Andriyani Rahmah, Shoimatul Ismah, Kiki
Zakiah, Fajri Syahri dan Silfia Windi.
11. Naftaleners sebagai sahabat, keluarga juga saudara yang mengisi hari-hari penulis
dengan kebersamaan, canda tawa, kasih sayang, kekompakkan baik di dalam kampus
maupun di luar kampus. Kalian harta yang sangat indah yang pernah penulis miliki.
12. Kak Hana, Kak Fatimah, Kak Nida dan para senior yang telah memberikan
masukan-masukan tentang formulasi.
13. Tim marawis Sakinatuzahro yang selalu kompak dan memberikan angin segar disela-sela
kesibukan dan kejenuhan penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat
disebutkan namanya satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih
jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk
perbaikan dalam pembuatan skripsi.
Jakarta, Februari 2012
vi DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ... i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……….. ii
LEMBAR PERNYATAAN………... iii
KATA PENGANTAR ... iv
2.1.8. Efek Farmakologi Gambir... 8
2.2. Katekin ... 9
vii
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 32
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 32
3.3.5. Pengujian Parameter Spesifik ... 37
3.3.6. Pengujian Parameter Non Spesifik ... 37
3.3.7. Pengambilan Katekin Gambir ... 40
3.4. Formula Tablet Hisap ... 41
3.5. Pembuatan Tablet Hisap ... 41
3.6. Evaluasi Granul ... 42
3.7. Evaluasi Tablet Hisap ... 43
3.5. Uji CD4 ... 45
viii
3.7. Alur Penilitian ... 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 48
4.1. Hasil ... 48
4.1.1. Determinasi ... 48
4.1.2. Identifikasi Gambir ... 48
4.1.3. Uji Cemaran Urea ... 48
4.1.4. Penapisan Fitokimia Gambir ... 49
4.1.5. Pengujian Karakteristik Katekin ... 51
4.1.6. Penetapan Kadar Katekin Fraksi Etil Asetat ... 51
4.1.7. Evaluasi Granul ... 54
4.1.8. Evaluasi Tablet ... 57
4.1.9. Uji CD4 ... 63
4.2. Pembahasan ... 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 71
5.1. Kesimpulan ... 71
5.2. Saran ... 71
DAFTAR PUSTAKA ... 72
ix DAFTAR TABEL
Tabel l. Hubungan Persentase Kompresibilitas Terhadap Sifat alir Granul 24
Tabel 2. Komposisi Tablet Hisap Katekin Gambir ... 41
Tabel 3. Hasil Identifikasi Bongkahan Gambir ... 48
Tabel 4. Hasil Pengujian Cemaran Urea ... 49
Tabel 5. Hasil Penapisan Fitokimia ... 49
Tabel 6. Hasil Pengujian Karakteristik Katekin ... 51
Tabel 7. Hasil Absorbansi Katekin ... 52
Tabel 8. Hasil Evaluasi Granul ... 54
Tabel 9. Persen Fraksi masing-masing Formula... 54
Tabel 10. Hasil Pengamatan Organoleptik Tablet Hisap ... 57
Tabel 11. Hasil Uji Keseragaman Bobot ... 58
Tabel 12. Hasil Uji Keseragaman Ukuran ... 59
Tabel 13. Hasil Uji Kekerasan Tablet Hisap ... 59
Tabel 14. Hasil Uji Persen Friabilitas Tablet Hisap ... 60
Tabel 15. Hasil Absorbansi katekin dalam Sediaan Tablet Hisap ... 60
x DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Katekin ... 9
Gambar 2. Struktur Amilum ... 17
Gambar 3. Struktur Sukralosa ... 19
Gambar 4. Struktur Manitol ... 19
Gambar 5. Struktur Mentol ... 20
Gambar 6. Struktur Sukrosa... 21
Gambar 7. Struktur Mg Stearat ... 22
Gambar 8. Kurva Kalibrasi Katekin Pembanding ... 52
Gambar 9. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 1 ... 55
Gambar 10. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 2... 55
Gambar 11. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 3... 56
Gambar 12. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 4... 56
xi DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Determinasi Gambir………..……... 75
Lampiran 2. Alat dan Bahan yang Digunakan………... 76
Lampiran 3. Hasil Identifikasi……… 77
Lampiran 4. Sertifikat Kadar Katekin Pembanding...….……… 78
Lampiran 5. Hasil Pengujian Karakteristik Katekin Fraksi etil asetat... ……… 79
Lampiran 6. Pembuatan Larutan untuk Kurva Kalibrasi... 82
Lampiran 7. Panjang Gelombang Maksimum Katekin Fraksi Etil Asetat... 83
Lampiran 8. Skema Pembuatan Katekin Fraksi Etil Asetat………... 84
Lampiran 9. Rumus Perhitungan Dosis Hewan dan Tabel Konversi Dosis Hewan ke HED Berdasarkan BSA………..……… 85
Lampiran 10. Perhitungan Dosis Sediaan Tablet Hisap Katekin Gambir..….……….….……….. 86
Lampiran 11. Gambar Tablet Hisap Katekin Gambir…………....………….. 87
Lampiran 12. Hasil Evaluasi Granul……….…………..……. 88
Lampiran 13. Perhitungan untuk Pengambilan Sampel……… 92
Lampiran 14. Hasil Uji Statistik………... 93
xii ABSTRAK
FORMULASI SEDIAAN TABLET HISAP KATEKIN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DENGAN METODE GRANULASI BASAH
Telah dilakukan penelitian aktivitas imunomodulator katekin gambir (Uncaria gambir Roxb)
secara in-vivo. Gambir digunakan sebagai bahan obat karena kandungan katekin yang dapat
berfungsi sebagai imunomodulator. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan sediaan
dalam bentuk tablet hisap, selanjutnya dilakukan pengukuran kadar CD4 dalam darah.
Ekstrak gambir diformulasi menjadi tablet hisap dengan pengikat kombinasi gom dengan
amilum, dilanjutkan dengan uji mutu fisik tablet hisap dan uji CD4 dalam darah panelis.
Hasil evaluasi yang ditinjau dari mutu fisik tablet hisap menunjukkan bahwa formula 2
dengan konsentrasi gom sebesar 60% dan amilum 40% dalam 10% konsentrasi pengikat
memiliki mutu fisik tablet lebih baik dibandingkan formula lainnya, dengan nilai kekerasan
adalah 10.828 kg/cm3, uji keseragaman bobot dan keseragaman ukuran yang memenuhi
persyaratan serta nilai % friabilitas adalah 0.63%. Uji statistik terhadap %CD4 dan jumlah
mutlak CD4 panelis yang mengkonsumsi tablet hisap selama 5 hari berturut-turut
menunjukkan adanya perbedaan bermakna (p<0,05) antara data sebelum dan sesudah
perlakuan.
xiii ABSTRACT
FORMULATION DOSAGE LOZENGES OF CATECHIN GAMBIR (Uncaria gambier roxb) AS IMMUNOMODULATORY WITH WET GRANULATION METHOD
Research of immunomodulatory of catechin gambir (Uncaria gambir Roxb) has been
investigated in-vivo. Gambir is applied as component of drug by contents of catechin and
tannin that can serve as immunomodulator. This research is about preparation of Lozenges
and also measurement of rate CD4 in blood. Catechin formulated into lozenges with binder
combination of gum acacia and starch, followed by the physical quality test lozenges and
CD4 blood test panelists. Evaluation results in terms of physical quality lozenges shows that
the formula 2 with a concentration of 60% gum acacia and starch 40% in 10% binder
concentration have a physical quality tablet better than other formulas, with a hardness value
is 10.828 kg/cm3, the uniformity test of weights and measures that meet the requirements of
uniformity and the value of % friabilitas is 0.63%. Statistical tests for CD4% and CD4
absolute number of panelists who consume lozenges for 5 consecutive days showed
significant difference (p< 0.05) between before and after treatment.
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Gambir merupakan ekstrak yang dihasilkan dari daun dan ranting tanaman
gambir yang dipanen/dipangkas setelah tanaman berumur 1,5 tahun dan dilakukan 2-3
kali setahun dengan selang waktu 4-6 bulan. Pangkasan daun dan ranting harus segera
diolah karena jika pengolahan ini ditunda lebih dari 24 jam, getahnya akan berkurang
(Hayani, 2003).
Gambir (Uncaria gambir Roxb) adalah komoditas perkebunan rakyat yang
terutama ditujukan untuk ekspor yang termasuk ke dalam family Rubiaceae.Spesies
Uncaria gambir merupakan salah satu tanaman tahunan penghasil getah penting yang
banyak digunakan untuk keperluan industri maupun farmasi. (Jamsari dkk, 2007)
Usahatani gambir adalah salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan
pendapatan petani. Gambir juga sebagai komoditas ekspor yang memiliki sumbangan
besar terhadap pendapatan daerah yang meningkatkan devisa Negara. 80% kebutuhan
gambir dunia dipasok oleh Provinsi Sumatera Barat dengan negara tujan Bangladesh,
India, Pakistan, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Perancis , dan Swiss. Permintaan
terhadap gambir terus meningkat sepanjang tahun dan selama periode lima tahun (2000
– 2004) peningkatan volume ekspornya mencapai 87,49% dan nilainya meningkat
17,16%. (Dhalimi, 2006).
Kegunaan gambir antara lain yaitu untuk zat pewarna dalam industri batik,
industri penyamak kulit, ramuan makan sirih, sebagai bahan obat dan digunakan juga
sebagai bahan baku pembuatan permen dalam acara adat di India dan sebagai penjernih
2
Berdasarkan hasil penelitian Thorpe dan Whiteley (1921) Kandungan kimia
utama gambir adalah katekin (7-33%) dan asam kateku tanat (20-50%). Selanjutnya
Burkill (1935) dengan penelitiannya menambahkan dan menguraikan kandungan
lainnya selain katekin dan asam kateku tanat dengan komposisi katekin 7-33%, asam
kateku tanat 20-55%, pyrokatekol 20-30%, gambir fluoresensi 1-3%, kateku merah
3-5%, quersetin 2-4%, fixed oil 1-2%, lilin 1-2%, dan mengandung sedikit alkaloid.
(Dhalimi 2006;Amos, 2010)
Berdasarkan penelitian dari Ilja C. W. Arts pada 24 jenis buah-buahan dan 27
jenis sayur-sayuran dan polong-polongan yang mengandung katekin, kandungan jenis
katekin yang terbanyak adalah katekin dan (-)-epikatekin sisanya adalah
(+)-gallokatekin (GC), (−)-epigallokatekin (EGC), (−)-epikatekin gallat (ECG), dan (−)
-epigallokatekin gallat (EGCG). (Arts, 2000)
Berdasarkan stándar mutu SNI 01-3391-1994 kadar katekin minimal dalam
gambir berhubungan dengan mutu gambir yaitu mutu I mengandung katekin minimal
40 persen, mutu II mengandung katekin minimal 30 persen dan mutu III mengandung
katekin minimal 20 persen. (Amos, 2010)
Pada penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa (-) epikatekin dan derivatnya
dapat menghambat interleukin 1-β(IL 1-β) dan interleukin 6 (IL-6) terutama pada
cysteamineepicatechin (Vinardellet al, 2008 ).
Selain itu, Julia Herzig dan Michael W. Pfaffl melaporkan bahwa (−)
-epigallokatekin gallat (EGCG) dan (+)-katekin memberikan efek imunostimulan
terhadap TNF-α, IL-1ß, IL-6.
Pemberian coklat dengan dosis tinggi yang mengandung (-)-epikatekin, katekin
dan prosianidin pada tikus merangsang respon T helper 1 (Th1) CD4 dan CD8 dan
3
Ekstrak gambir dapat berkhasiat sebagai imunomodulator secara in-vivo pada
dosis 400mg/kg BB (Amalia, 2009) dan telah dibuat sediaan tablet hisap ekstrak etanol
gambir pada dosis 2000 mg/hari dan dapat mempengaruhi jumlah mutlak CD4 dan
persentase CD4 dalam darah (Hana, 2010).
Mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa katekin
dapat meningkatkan sistem imun. Dilakukanlah penelitian lebih lanjut tentang efek
immunomodulator terhadap CD4 pada limfosit dari katekin gambir yang diperoleh dari
fraksi etil asetatnya yang kemudian dibuat tablet hisap dengan metode granulasi basah.
Pemilihan tablet hisap ini karena mudah digunakan dan menyenangkan untuk
dikonsumsi, selain itu juga tablet hisap dapat memberikan efek yang diinginkan lebih
cepat karena zat aktif langsung diabsorpsi melalui mukosa mulut kemudian masuk ke
pembuluh darah. (Kuncoro dkk, 2008)
1.2. Perumusan Masalah
1. Apakah katekin gambir dapat dibuat dalam sediaan tablet hisap dengan metode
granulasi basah menggunakan pengikat kombinasi gom akasia dan amilum dengan
konsentrasi yang berfariasi?
2. Apakah tablet hisap katekin gambir yang telah dibuat dapat meningkatkan kadar
4 1.3. Hipotesa
1. Katekin gambir dapat dibuat dalam sediaan tablet hisap dengan metode granulasi
basah menggunakan pengikat kombinasi gom akasia dan amilum dengan
konsentrasi yang berfariasi.
2. Tablet hisap katekin gambir yang telah dibuat dapat meningkatkan kadar CD4
dalam tubuh.
1.4. Tujuan Penelitian
1. Memperoleh tablet hisap katekin gambir yang baik dan memenuhi persyaratan
dengan menggunakan metode granulasi basah menggunakan pengikat kombinasi
gom akasia dan amilum dengan konsentrasi yang berfariasi.
2. Mengetahui pengaruh tablet hisap katekin gambirterhadap CD4 dalam tubuh.
1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang suatu formulasi
tablet hisap katekin gambir dengan menggunakan metode granulasi basah
menggunakan pengikat kombinasi gom akasia dan amilum dengan konsentrasi yang
berfariasi, serta memberikan informasi tentang pengaruh tablet hisap katekin
5 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Tanaman Gambir
2.1.1. Klasifikasi Ilmiah (United States Department of Agriculture)
Tanaman gambir diklasifikasikan ke dalam :
Kingdom : Plantae
Sub Kingdom : Tracheobionta
Super Divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Asteridae
Ordo : Rubiales
Familia : Rubiaceae
Genus : Uncaria
Spesies : Uncaria gambir (Hunter) Roxb.
2.1.2. Nama Lain(Ditjenbun, Depkes RI, 1989)
Sumatera : Gambee, gani, kacu, sontang, gambie,
gambu,gimber, pengilom, sepelet.
Jawa : Santun, ghambhir.
Kalimantan : Kelare,gamer, kambin, sori.
Nusa Tenggara : Tagambe, gambele, gamelo, gambi, gambiri,
gata, gaber.
6
tagabere, gagabere, gabere.
Aceh : Gambe, gambie
Minangkabau : Gambie
Ternate : Gamber
Jepang : Gambiitsu
Malaysia : Gatta
Inggris : White cutch
2.1.3. Deskripsi (ditjenbun)
Merupakan jenis tanaman berkayu dan bersemak, akar serabut,
mempunyai batang yang merambat atau memanjat dengan ketinggian 1-2 m
mempunyai dahan dan ranting, daun berbentuk oval sampai dengan bulat
dengan ukuran panjang 10-17 cm, lebar 6-8 cm, tebal 0,25-0,5 mm, bunga
berbentuk bonggol bulat dengan warna waktu muda hijau sedangkan waktu
mekar berwarna kuning kemerahan, buah termasuk buah polong dengan
jumlah polong pertangkai antara 20-60 buah, warna buah muda hijau sampai
hijau kemerahan sedangkan yang matang berwarna kuning kecoklatan, biji
sangat kecil dengan panjang 1-2 mm dengan bagian luar bersayap.
2.1.4. Makroskopik (Depkes RI, 1989)
Umumnya berbentuk kubus tidak beraturan atau agak silindrik
pendek, kadang-kadang bercampur dengan bagian-bagian yang remuk. Tebal 2
cm sampai 3 cm, ringan, mudah patah, warna permukaan luar coklat muda
7
dipatahkan coklat muda sampai coklat kekuningan, kadang-kadang terlihat
garis-garis yang lebih gelap.
2.1.5. Mikroskopik (Depkes RI, 1989)
Dilihat dalam kloralhidrat terlihat adanya pollen, sel batu besar,
dinding agak tipis, lumen besar, atau kadang-kadang kecil memanjang, lumen
sempit.Sel parenkim besar, dinding tipis.Hablur kalsium oksalat bentuk jarum
dan bentuk prisma.Rambut penutup terdiri dari satu sel ujung runcing.
2.1.6. Persebaran (Ditjenbun)
Asal : India
Sentra Produksi : Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan
2.1.7. Kandungan Kimia
Berdasarkan hasil penelitian Thorpe dan Whiteley (1921) Kandungan
kimia utama gambir adalah katekin (7-33%) dan asam kateku tanat (20-50%).
Selanjutnya Burkill (1935) dengan penelitiannya menambahkan dan
menguraikan kandungan lainnya selain katekin dan asam kateku tanat dengan
komposisi katekin 7-33%, asam kateku tanat 20-55%, pyrokatekol 20-30%,
gambir fluoresensi 1-3%, kateku merah 3-5%, quersetin 2-4%, fixed oil 1-2%,
lilin 1-2%, dan mengandung sedikit alkaloid. (Amos, 2010)
Berdasarkan stándar mutu SNI 01-3391-1994 kadar katekin minimal
8
katekin minimal 40 persen, mutu II mengandung katekin minimal 30 persen
dan mutu III mengandung katekin minimal 20 persen.
Ekstrak gambir mengandung beberapa komponen flavonoid yaitu
katekin (7-33%), pirokatekol (20-30%) quersetin (2-4%). Selain itu ada
flavonoid lain dari dimer flavan-kalkan yaitu gambiriin A1, A2, A3
(streokimia belum diketahui) bersamaan dengan dimer proantosianidinyaitu
gambiriin C. Getah gambir murni mengandung d dan dl-catechin (3-35%) dan
produk kondensasi asam katechutannat (sekitar 24%), quersetin, asam gallat,
katekol, pigmen dan lain-lainnya. d-katekin merupakan komponen yang
terbanyak.(Ridawati dkk)
2.1.8. Efek Farmakologi Gambir
Secara turun temurun gambir digunakan oleh nenek moyang kita
sebagai teman makan sirih bersama kapur sirih.Namun sekarang telah banyak
dilakukan penelitian secara ilmiah efek farmakologi dari gambir.
Senyawa fungsional gambir yaitu fenol dan katekin dapat berperan
menjadi antioksidan, antibakteri dan antikarsinogenik alami (Susanti, 2008)
Gambir telah dikembangkan di Jepang sebagai permen pelega
tenggorokan khusus untuk para perokok karena kemampuannya menetralisir
nikotin.Di Singapura gambir dikembangkan untuk obat sakit perut dan sakit
gigi (Bakhtiar 1991).
Tingginya kandungan senyawa flavonoid di dalam gambir telah
dimanfaatkan menjadi bahan baku dalam pembuatan obat-obatan antihepatitis
B, antidiare, penghambat pembentuk plak gigi, antimikroba, dan antinematoda
9 2.2. Katekin
Katekin merupakan kandungan utama dari gambir yang merupakan
senyawa kompleks dari golongan polifenol dengan struktur flavonoid, di mana asam
kateku tanat(C15H12O5
Apabila katekin dipanaskan pada temperatur 110
) merupakan anhidrat dari katekin. Katekin biasa disebut asam
katekuat atau katekiat. (Muchtar, 2008)
o
C atau dengan cara
memanaskan pada larutan alkali karbonat, maka akan kehilangan satu molekul air dan
berubah menjadi asam kateku tanat. (Amos, 2010)
Gambar 1. Struktur Katekin
2.3. Simplisia (Depkes RI, 1985)
Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum
mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia merupakan
bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, dan
simplisia pelikan atau mineral.
- Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau
eksudat tanaman. Eksudat tanaman ialah isi sel yang secara spontan keluar dari
tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati
lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya.
- Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau
10
- Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau
mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum
berupa zat kimia murni.
2.4. Ekstrak dan Ekstraksi
Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia
menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung. (Depkes RI,
2000)
Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari
simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai kemudian
semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa
diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. (Depkes RI,
1995)
Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia nabati, yang mengandung etanol
sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. (Depkes RI,
1995)
2.5. Metode Ekstraksi (Depkes RI, 2000)
a. Cara dingin, yaitu:
1. Maserasi
Adalah pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali
pengadukan pada suhu kamar.Prinsip dasarnya pencapaian konsentrasi pada
11
2. Perkolasi
Adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature yang selalu baru sampai
sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur
ruangan.
b. Cara panas, yaitu:
1. Refluks
Adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu
tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya
pendinginan yang baik.
2. Soxhlet
Adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan
dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi terus menerus dengan jumlah
pelarut relatif konstan dengan pendinginan baik.
3. Digesti
Adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan terus menerus) pada temperatur
yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada
temperatur 40-50o
4. Infusa
C.
Adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus
tercelup dalan penangas air mendidih), temperatur terukur 96-98oC selama
12 2.6. Tablet Hisap
2.6.1. Definisi Tablet Hisap
Tablet hisap adalah suatu sediaan padat yang mengandung satu atau
lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang
dapat melarut atau hancur perlahan-lahan di dalam mulut (Depkes RI, 1995).
Tablet hisap adalah bentuk lain dari tablet untuk pemakaian dalam
rongga mulut. Tablet ini digunakan dengan tujuan memberi efek lokal pada
mulut atau kerongkongan yang umumnya diberikan sebagai pengobatan sakit
tenggorokan atau untuk mengurangi batuk pada influenza, atau dapat pula
mengandung anastetika lokal, berbagai antiseptik dan antibakteri, demulsen,
astringen dan antitusif. Jenis tablet ini dirancang agar tidak hancur di dalam
rongga mulut tetapi melarut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam waktu
30 menit atau kurang. (Lachman, 1994)
Tablet hisap adalah bentuk sediaan obat tablet yang diberi penambah
rasa untuk dihisap dan didiamkan (ditahan) di dalam mulut atau faring.
(Siregar, 2010)
Berbeda dengan tablet biasa, pada tablet hisap tidak digunakan bahan
penghancur, dan bahan yang digunakan sebagian besar adalah bahan-bahan
yang larut air. Tablet hisap cenderung menggunakan banyak pemanis (50%
atau lebih dari berat tablet keseluruhan) seperti sukrosa, laktosa, manitol,
sorbitol, dan sebagainya. Selain itu diameter tablet hisap umumnya lebih besar
yaitu >18 mm. Ta*4blet hisap yang baik memiliki kekerasan sebesar >10
13 2.6.2. Bahan Tambahan
Bahan tambahan atau bahan pembantu tabletasi dapat diartikan sebagai
zat-zat yang memungkinkan suatu obat atau bahan obat yang memiliki
beberapa sifat khusus untuk dibuat menjadi suatu sediaan yang cocok satu
sama lain yang dapat memperbaiki sediaan obat, dengan mempertimbangkan
efek obat, kinerja obat, organoleptis, sifat kimia obat, dan kemungkinan
pengembangan jenis sediaan lain.Adapun zat-zat tambahan dalam sediaan
tablet hisap meliputi :
a. Bahan pembawa (Siregar, 2010)
1. Pembawa Dasar Gula
Formulasi tablet yang paling sederhana kemungkinan menggunakan
gula (sukrosa) sebagai pembawa dasar. Gula tidak mahal dan dapat
digunakan untuk membentuk tablet yang memiliki karakteristik
pengempaan dan raba mulut yang dapat diterima.
2. Pembawa dekstrosa dan sukrosa yang dimodifikasi, seperti Nu-tab
dan Sugartab.
3. Pembawa dasar bebas gula, seperti manitol dan sorbitol
4. Pengisi-pengisi lain, seperti dikalsium fosfat, kalsium sulfat, kalsium
karbonat, laktosa.
b. Bahan pengikat
Bahan pengikat adalah bahan tambahan yang diperlukan untuk
memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan
memberikan sifat kohesif yang telah ada pada bahan pengisi sehingga
dapat membentuk struktur tablet yang kompak setelah pencetakan dan
14
penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah butiran granulat. Bahan
pengikat dapat ditambahkan ke dalam bahan yang akan dicetak dalam
bentuk kering, cairan, atau larutan, tergantung pada metode pembuatan
tablet (Depkes RI, 1995)
Pengikat yang paling efektif untuk granulasi basah tablet hisap
kempa adalah akasia (gom arab), sirup jagung, sirup simpleks, gelatin,
PVP, tragakan, dan metal selulosa. Bahan-bahan ini efektif dalam
meningkatkan gaya intergranul serta membantu memperbaiki karakteristik
demulsen (penyejuk) dan tekstur permukaan tablet hisap ketika melarut
dalam rongga oral. (Siregar, 2010)
c. Bahan pelincir (Voight, 1994; Lachman, 1994)
Bahan pelincir dapat memenuhi berbagai fungsi yang berbeda,
sehingga banyak dikelompokkan menjadi bahan pengatur aliran (glidant),
bahan pelincir (lubricant) dan bahan pemisah hasil cetakan (antiadherent).
Bahan pengatur aliran atau glidant berfungsi untuk
memperbaiki daya luncur dan daya gulir bahan yang akan dicetak, karena
itu menjamin terjadinya keteraturan aliran dari corong pengisi ke dalam
lubang cetakan. Glidan juga berfungsi untuk mengurangi penyimpangan
massa, memperkecil gesekan sesama partikel, dan meningkatkan
ketepatan takaran tablet. Contoh zat yang dapat digunakan sebagai glidan
yaitu talk, kalsium/magnesium stearat, asam stearat, PEG, pati, dan
aerosil.
Bahan pelincir atau lubricant berfungsi untuk mengurangi
gesekan logam (stempel di dalam lubang ruang cetak) dan gesekan tablet
15
Pada umumnya lubrikan bersifat hidrofobik sehingga cenderung
menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Oleh karena itu
kadar lubrikan yang berlebihan harus dihindarkan. Contoh lubrikan antara
lain talk, kalsium atau magnesium stearat, asam stearat, PEG, pati, dan
paraffin.
Bahan pemisah hasil cetakan ataau antiadherent adalah bahan
yang berfungsi untuk mencegah lekatnya bahan yang dikempa pada
permukaan stempel atas. Contoh bahan ini adalah talk, amilum maydis,
Cab-O-Sil, natrium lauril sulfat, kalsium/magnesium stearat.
d. Zat warna
Penggunaan zat warna dalam tablet memberikan keuntungan
yaitu menutupi warna obat yang kurang baik, identifikasi hasil produksi
dan membuat suatu produk menjadi lebih menarik. Penyediaan
warna-warna alami dari tumbuh-tumbuhan dibatasi karena warna-warna-warna-warna ini
seringkali tidak stabil. (Lachman, 1994)
Zat pewarna larut air dapat ditambahkan pada campuran serbuk
selama pembuatan pembawa granulasi basah sebelum dilakukan granulasi
eksipien dan zat aktif.Selain itu, pewarna dapat dilarutkan dalam larutan
penggranulasi dan ditambahkan pengikat.(Siregar, 2010)
e. Pemberi Rasa
Bahan pemberi rasa biasanya digunakan pada tablet kunyah
atau tablet lainnya yang ditujukan larut dalam mulut. Pada umumnya zat
pemberi rasa yang larut dalam air jarang dipakai dalam pembuatan tablet
16
Untuk tablet hisap, waktu huni tablet yang lama dalam rongga
mulut mensyaratkan agar formulator mengembangkan tidak saja produk
dengan penambah rasa yang menyenangkan, tetapi juga produk yang
penambah rasanya dapat menutupi dasar pahit yang mungkin dimiliki
formulasi. (Siregar, 2010)
2.6.3. Monografi Bahan
a. Amylum (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Sinonim : Amido, amilo, amidon, starch.
Rumus empirik : (C6H10O5)n,
Fungsi
dimana n = 300-1000
: Glidan, pengisi tablet dan kapsul,
penghancur tablet dan kapsul (3-15%),
pengikat tablet (5-25%)
Pemerian : Berbentuk serbuk, Bau dan rasa lemah,
berwarna putih terdiri dari butiran bulat
atau bulat telur yang sangat kecil yang
ukuran dan bentuk yang khas untuk
masing-masing varietas tanaman.
Kelarutan : Praktis tidak larut dalam etanol dingin
(95%) dan air dingin.
Stabilitas : Kering, amilum yang tidak dipanaskan
stabil jika terlindung dari lembab yang
tinggi. Larutan amilum atau pasta yang
dihangatkan tidak stabil dan dapat rusak
17
harus disimpan dalam wadah yang tertutup
rapat dan tempat yang kering.
Keamanan : Amilum merupakan bahan yang tidak
toksik dan tidak mengiritasi. Tapi
bagaimanapun pemakaiannya harus
dikendalikan.
Struktur :
Gambar 2. Struktur Amilum
b. Gom Arab (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Adalah eksudat yang mengeras di udara yang mengalir secara
alami atau dengan penorehan batang dan cabang tanaman Acacia
senegal L. Willdenow dan spesies acacialainyang berasal dari
afrika.
Sinonim : Gum acacia, gum arabic, talha gum
Rumus Empirik : Kompleks, hilangnya kumpulan gula dan
hemiselulosa dengan berat molekul
kira-kira 240.000-580.000.
Fungsi : Emulgator (5-10%), zat penstabil,
pensuspensi (5-10%), pengikat tablet
(1-5%), penambah viskositas.
makroskopik : Butiran, bentuk bulat seperti ginjal atau
18
warna putih kekuningan, kuning atau
coklat muda, kadang-kadang berwarna
merah muda, rapuh buram, seringkali
dengan permukaan yang retak, mudah
pecah menjadi fragmen bersudut tidak
beraturan dengan patahan melengkung,
berwarna agak putih atau agak
kekuningan.
Mikroskopik : Serbuk berupa potongan mengkilat tidak
beraturan, tidak berwarna terlihat sedikit
pati atau jaringan tanaman, tidak terlihat
adanya lapisan membran.
Pemerian : Tidak berbau dan berasa lemah.
pH : 4,5-5 (5% w/v larutan)
Kelarutan : Larut dalam 20 bagian gliserin, dalam 20
bagian propilen glikol, dalam 2 bagian air,
praktis tidak larut dalam etanol (95%)
Stabilitas : Mudah terkontaminasi mikroba
c. Sukralosa (International Food Information Council Foundation)
Rumus Empirik : C12H19Cl3O
Sinonim
8
: Triclorogalacto-sucrose
Berat Molekul : 397.64 g/mol
Kelarutan : 283 g/L (20 °C) dalam air
Fungsi : Pemanis 600 kali dari sukrosa
19
Struktur :
Gambar 3. Struktur Sukralosa
d. Manitol (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Mengandung tidak kurang dari 96% dan tidak lebih dari 101,5%
C6H14O6,
Sinonim
dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan.
: Manita, gula manna, mannite, pearlitol
Rumus empirik : C6H14O
Berat Molekul
6
: 182,17
Pemerian : Serbuk hablur atau granul mengalir bebas,
putih, berbau lemah, rasa manis.
Kelarutan : Mudah larut dalam air, larut dalam larutan
basa, sukar larut dalam piridina, sangat sukar
larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam
eter.
Fungsi : Pemanis, pengisi tablet dan kapsul (10-90%),
Zat tonisitas.
Stabilitas : Stabil dalam keadaan kering dan dalam
larutan.
Struktur :
20
e. Mentol (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Adalah alkohol yang diperoleh dari bermacam-macam minyak
permen atau yang dibuat secara sintetik, berupa l-mentol atau
mentol resemik.
Sinonim : Peppermint camphor
Rumus empirik : C10H20
Berat Molekul
O
: 156,27
Pemerian : Hablur heksagonal atau serbuk hablur, tidak
berwarna, biasanya berbentuk jarum, atau
massa yang melebur, bau enak seperti
minyak permen.
Kelarutan : Sukar larut dalam air, sangat mudah larut
dalam etanol, dalam kloroform, dalam eter
dan dalam heksana, mudah larut dalam asam
asetat glasial, dalam minyak mineral, dan
dalam minyak lemak dan dalam minyak
atsiri.
Jarak lebur : 41-44o
Fungsi
C
: Perasa, zat terapetik, pengaroma
Penggunaan : 0.2-0.4 %
Struktur :
21
f. Sukrosa (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Adalah gula yang diperoleh dari saccharum officinarum Linne
(familia Gramineae), Beta vulgaris Linne (familia
Chenopodiaceae) dan sumber-sumber lain. Tidak mengandung
bahan tambahan.
Sinonim : Sakarosa
Rumus empirik : C12H22O
Berat Molekul
11
: 342,30
Pemerian : Hablur putih atau tidak berwarna, massa
hablur atau berbentuk kubus, atau serbuk
hablur putih, tidak berbau, rasa manis, stabil
di udara, larutannya netral terhadap lakmus.
Kelarutan : Sangat mudah larut dalam air, lebih mudah
larut dalam air mendidih, sukar larut dalam
etanol, tidak larut dalam kloroform dan dalam
eter.
Fungsi : Sirup untuk sediaan oral cair (67%), Pemanis
(67%), Pengikat granulasi kering (2-20%),
Pengikat granulasi basah (50-67%), Penyalut
tablet (50-67%)
Struktur :
22
g. Magnesium stearat (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Mg stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran
asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama
terdiri dari magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam
berbagai perbandinan. Mengandung setara dengan tidak kurang
dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO.
Sinonim : asam oktadekanoat, garam magnesium
Rumus Empirik : C36H20MgO
Berat Molekul
4
: 591,27
Pemerian : Serbuk halus, putih, bau lemah khas, mudah
melekat di kulit, bebas dari butiran.
Kelarutan : Tidak larut dalam air, dalam etanol dan
dalam eter.
Fungsi : Lubrikan (0,25-5%)
Struktur :
Gambar 7. Struktur Mg Stearat
h. Talkum (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)
Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang
mengandung sedikit alumunium silikat.
Sinonim : Magsil Osmanthus, Magsil Star
Rumus Empirik : Mg4(Si2O5)4(OH)
Pemerian
4
: Serbuk hablur sangat halus, putih atau putih
23
dan bebas dari butiran.
Kelarutan : Praktis tidak larut dalam asam dan alkali,
pelarut organik, dan air.
Fungsi : lubrikan (1-10%); diluent (5-30%)
i. Metil Paraben
Sinonim : Nipagin
Rumus Empirik : C6H6O
Kelarutan
3
: Larut dalam 2 bagian etanol, 3 bagian etanol
(95%), 6 bagian etanol (50%), 200 bagian
etanol (10%), 10 bagian eter, 60 bagian
gliserin, 400 bagian air dingin, 50 bagian air
hangat (50oC), dan dalam 30 bagian air
panas (80o
Fungsi
C).
: Antimikroba (0.02-0.3 %)
2.6.4. Metode Pembuatan
Metode pembuatan tablet hisap dapat dilakukan dengan cara peleburan
atau dengan proses penuangan kembang gula. Selain itu dapat dibuat juga
dengan cara mengempa seperti halnya tablet biasa. (Lachman, 1994)
Ada beberapa metode dalam pembuatan tablet, namun yang relatif
lebih sering digunakan adalah metode granulasi basah, granulasi kering, dan
24 2.6.5. Evaluasi Granul
a. Uji Kadar Lembab (Voight, 1994)
Pengukuran kadar lembab dilakukan dengan menggunakan alat yang
disebut moisture balance. Syarat kadar lembab yang baik adalah 2 – 5 %
b. Kompresibilitas (Aulton, 1988; Voight, 1994)
Uji kompresibilitas dilakukan dengan alat yang disebut bulk density.
Persen kompresibilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
% kompresibilitas = BJ mampat – BJ Bulk
BJ mampat x 100%
Tabel 1. Hubungan Persentase Kompresibilitas Terhadap Sifat Alir
Granul. (Foe, 2008)
Persen Kompresibilitas Sifat Aliran
5-15
Sangat buruk sekali
c. Distribusi Ukuran Partikel (Voight, 1994)
Distribusi ukuran partikel sangat penting untuk memperoleh granul yang
kompak dan tidak mudah hancur. Distribusi ukuran partikel diperoleh
dengan metode pengayakan dengan menggunakan alat yang disebut
sieving analyzer (Voight, 1994).
d. Sifat Alir (Aulton, 1988; Lachman, 1994)
Untuk menentukan sifat alir berlaku sudut kemiringan aliran, jika suatu
25
adapun untuk mengukur sudut henti adalah dengan mengukur tinggi dan
diameter kerucut yang dihasilkan, sedangkan untuk mengukur laju alir
adalah dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk
dapat habis melewati corong (Voight, 1994). Syarat sudut henti yang baik
adalah < 30o dan laju alir yang baik adalah 4-10 gram/detik. (Lachman,
1994)
2.6.6. Evaluasi Tablet
a. Pemeriksaan Organoleptik (Ansel, 1989)
Pemeriksaan organoleptik meliputi warna, rasa, bau, penampilan, tekstur
permukaan, derajat kecacatan seperti serpihan, dan kontaminasi benda
asing (rambut, tetesan minyak, kotoran). Warna yang tidak seragam dan
adanya kecacatan pada tablet selain dapat menurunkan nilai estetikanya
juga dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakseragaman kandungan
dan kualitas produk yang buruk.
b. Keseragaman Bobot (Depkes, 1979)
Pada tablet yang didesain mengandung sejumlah obat di dalam sejumlah
formula, bobot tablet yang dibuat harus diperiksa secara acak untuk
memastikan bahwa setiap tablet mengandung obat dengan jumlah yang
tepat. Syarat keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia Jilid III
adalah bila bobot rata-rata lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu
tidak lebih dari 2 buah tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang
5% dari bobot rata-ratanya, dan tidak ada satu pun tablet yang bobotnya
26
c. Keseragaman Ukuran
Ukuran tablet meliputi diameter dan ketebalan. Ketebalan inilah yang
berhubungan dengan proses pembuatan tablet, karena harus terkontrol
sampai perbedaan 5% dari nilai rata-rata. Pengontrolan ketebalan tablet
diperlukan agar dapat diterima oleh konsumen dan dapat mempermudah
pengemasan. (Ansel, 1989)
Syarat keseragaman ukuran berdasarkan farmakope jilid III adalah
kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak
kurang dari 11/3 kali tebal tablet.
b. Friabilitas (Lachman, 1994)
Friabilitas dinyatakan sebagai persentase selisih bobot sebelum dan
susudah pengujian, dibagi dengan bobot mula-mula.Tablet yang baik
memiliki keregasan kurang dari 1%.
c. Kekerasan (Parrot, 1971)
Tablet harus memiliki kekuatan atau kekerasan tertentu agar tahan
terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan,
dan transportasi.Tablet hisap biasanya memiliki kekerasan lebih tinggi
dibandingkan dengan tablet biasa. Syarat kekerasan tablet hisap adalah
lebih dari 10 kg/cm3. (Hasyim dkk, 2008)
2.7. Sisitem Imun (Bratawidjaja. 2006)
Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit terutama penyakit infeksi. Gabungan sel,
molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut sistem
27
bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Pertahanan
imun terdiri atas sistem imun alamiah atau nonspesifik dan didapat atau spesifik.
2.7.1. Imunomodulator
Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki
sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan yang fungsinya
berlebihan.Obat golongan imunomodulator bekerja menurut 3 cara, yaitu
melalui:
- Imunorestorasi
Ialah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu
dengan memberikan berbagai komponen sistem imun, seperti:
immunoglobulin dalam bentuk Immune Serum Globulin (ISG),
Hyperimmune Serum Globulin (HSG), plasma, plasmapheresis,
leukopheresis, transplantasi sumsum tulang, hati dan timus.
- Imunostimulasi
Imunostimulasi yang disebut juga imunopotensiasi adalah cara
memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang
merangsang sistem tersebut.
- Imunosupresi
Merupakan suatu tindakan untuk menekan respons imun.Kegunaannya di
klinik terutama pada transplantasi untuk mencegah reaksi penolakan dan
pada berbagai penyakit inflamasi yang menimbulkan kerusakan atau
28 2.7.2. Cluster of Differentiation
Cluster of Differentiation (CD) adalah istilah untuk molekul
permukaan leukosit yang merupakan epitop dan dapat diidentifikasikan
dengan antibody monoclonal. Sel limfosit yang ada dalam berbagai fase
pematangan dapat dibedakan dari ekspresi molekul membran yang dapat
ditentukan dengan menggunakan antibody monoclonal yang spesifik untuk
epitop tunggal antigen.Kelas limfosit dengan fungsi tertentu mengekspresikan
protein permukaan tertentu pula.Molekul permukaan inilah yang disebut
dengan Cluster of Differentiation (CD).Ekspresi molekul membran sel T
seperti CD4, CD8, CD28 dan CD45R berperan sebagai molekul aksesori
dalam fungsi sel T atau dalam transduksi sinyal (Baratawidjaja, 2009).
CD4 adalah bagian dari populasi limfosit T yang disebut sebagai sel T
helper.Cara kerja sel ini adalah sebagai penolong, misalnya melepaskan suatu
senyawa yang mengaktifkan sel-sel lain untuk mematikan atau mengeliminasi
antigen (benda asing). Fungsi utama CD4 dalam imun adalah meregulasi
sistem imun agar bekerja dengan baik, dengan merangsang sistem imun
nonspesifik berupa fagosit untuk kemotaksis dan proses fagositosis benda
asing. Peran CD4 dalam sistem imun spesifik humoral adalah merangsang sel
B (Limfosit B) untuk menghasilkan antibodi dan mengatur produksi antibodi,
sedangkan dalam sistem imun seluler berfungsi dalam mengatur CD8 dan NK
untuk membunuh sel sasaran yang terkena infeksi virus.
CD4 adalah sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan
sel-sel darah putih manusia, terutama sel-sel limfosit.CD4 pada orang dengan
sistem kekebalan yang menurun menjadi sangat penting, karena berkurangnya
29
putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam memerangi infeksi yang
masuk ke tubuh manusia.
Analisa CD4 dipengaruhi oleh tiga parameter, yaitu % limfosit, %
CD4, dan jumlah mutlak CD4.Jumlah CD4 absolut adalah jumlah sel CD4
yang ada dalam sistem kekebalan tubuh.Pada orang dengan sistem kekebalan
yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400-1500. Ukuran CD4 persentase
memberi sedikit informasi tambahan pada jumlah CD4 mutlak dalam
peramalan risiko jangka pendek pengembangan penyakit, karenanya jumlah
CD4 mutlak merupakan ukuran status kekebalan yang lebih penting dan
pilihan terbaik dibandingkan dengan CD4 persentase, misalnya untuk
mengambil keputusan pengobatan dalam orang dewasa terinfeksi HIV.
Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah CD4 antara lain meliputi
perbedaan analisis, perbedaan musim, beberapa penyakit bersamaan, dan
penggunaan kortikosteroid. Di samping itu, terdapat pula beberapa faktor yang
dilaporkan memberikan sedikit pengaruh terhadap jumlah nilai CD4, yaitu
gender, usia (pada orang dewasa), faktor risiko, stres psikologis, stres fisik,
dan kehamilan.
Di lingkungan sekitar sangat banyak infeksi yang beredar, baik berada
dalam udara, makanan ataupun minuman.Namun manusia tidak setiap saat
menjadi sakit, karena CD4 masih bisa berfungsi dengan baik untuk melawan
infeksi ini. Jika CD4 berkurang, mikroorganisme yang patogen akan dengan
mudah masuk ke tubuh kita dan menimbulkan penyakit pada tubuh manusia
30 2.7.3. Kontrol Pembanding
IM® mengandung Echinaceapurpurea 250 mg, ekstrak Black
eldelberry 400mg, dan Zinc picolinate 5 mg, dikemas dalam sediaan kaplet
.IM®
Telah terbukti bahwa Echinacea merupakan imunostimulan non
spesifik, dengan kata lain Echinacea tidak mempunyai hubungan antigenik
dengan patogen-patogen spesifik.Hal ini merupakan hasil dari stimulasi respon
imun seluler seperti fagositosis dan pelepasan sitokin serta faktor-faktor serum
lainnya.Fagositosis (proses ingesti atau menghancurkan mikroorganisme, sel
dan partikel) oleh sel-sel pada sistem retikuloendotelial, telah digunakan
sebagai indikator aktifitas imunostimulan dari Echinacea (Bradley, 2006). membantu memperbaiki daya tahan tubuh atau respon imun tubuh, juga
digunakan sebagai terapi pendamping untuk infeksi yang akut dan kronis,
terutama untuk infeksi saluran pernafasan & genitalia seperti kandidiasis dan
vaginitis.Echinacea adalah tumbuhan pertama yang dibuktikan secara ilmiah
khasiat stimulasinya terhadap sistem imun.(Tjay et al., 2002).
2.8. Kerangka Teori
Gambir merupakan komoditas ekspor yang memiliki sumbangan besar terhadap pendapatan daerah
31 BAB III
Dilakukan penelitian lebih lanjut dari potensi gambir sebagai imunomodulator yang dapat Kegunaan gambir antara lain untuk zat
pewarna dalam industri batik, industri penyamak kulit, ramuan makan sirih, sebagai obat untuk penyakit tertentu, bahan baku pembuatan permen dalam acara adat di India dan sebagai penjernih pada industri air (Hadad et al 1991 dan Azmi 2006).
Kandungan kimia utama gambir adalah katekin (7-33%) dan asam kateku tanat (50%), pyrokatekol 20-30%, gambir fluoresensi 1-3%, kateku merah 3-5%, quersetin 2-4%, fixed oil 1-2%, lilin 1-1-2%, dan mengandung sedikit alkaloid.
Penelitian sebelumnya ekstrak etanol gambir pada dosis 2000 mg/hari dapat mempengaruhi jumlah mutlak CD4 dan persentase CD4 dalam darah (Hana, 2010).
32
METODOLOGIPENELITIAN
3.1. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium kimia makanan halal, Laboratorium kimia
analisis, Laboratorium bahan alam, laboratorium Drug Research dan Laboratorium
teknologi sediaan tabletProgram Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Laboratorium
Makmal Terpadu Imunoendokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Penelitian dilakukan dari bulan Mei2011 sampai bulan Januari 2012.
3.2. Alat dan Bahan
3.2.1. Alat Penelitian
Alat yang digunakan adalah gelas ukur, beaker glass, corong pisah, pipet
volum, pipet tetes,penggiling (blender), hot plat, kertas saring, lemari asam,
lumpang dan alu, termometer, cawan penguap, kapas,alat pencetak tablet,
pengayak, desikator, hardness tester, uji kerapuhan atau friabilator, moisture
contentbalance,sievinganalyzer,neraca analitik, jangka sorong, rotary
evaporator, erlenmeyer, cawan porselen,corong,statif,krusplatina,batang
pengaduk, spatula,oven,mikro pipet, labu ukur, spektro UV-Vis, vortex, lemari
pendingin, Sysmex Pouch 100i, FACSCalibur, serta peralatan yang lazim
digunakan di laboratorium.
33
Bahan-bahan yang digunakan adalah ekstrak kering air gambir yang berasal
dari Payakumbuh-Padang, aquades, etil asetat, ammonia (10%,25%),kloroform,
HCl (1%, 1:10), pereaksi Dragendorff, pereaksi Mayer, aquadest, lempeng
magnesium, HCl pekat, butanol, larutan besi (III) klorida (FeCl3) 1%,
pereaksi Stiasny, NaOH 1 N, eter, asam asetat anhidrat, H2SO4 pekat,
pereaksi Libermann-Burchard, petroleum eter, amilum,gom akasia,talkum, Mg
stearat, manitol, mentol, sukrosa,sukralosa, aerosil, FD&C yellow, reagen BD
Tritest CD4, lysing solution.
3.3. Prosedur Penelitian
3.3.1. Pembuatan Serbuk Gambir
Bongkahan ekstrak kering air gambir yang telah ditimbang kemudian
diserbukan dengan cara digerushingga menjadi serbuk.
3.3.2. Identifikasi Gambir (Depkes, 1989)
1. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes asam sulfat P
terbentuk warna coklat merah
2. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan asam sulfat 10 N terbentuk
warna coklat muda
3. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes Na hidroksida 5% dalam
etanol terbentuk warna coklat merah
4. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes ammonia 25% terbentuk
warna coklat merah
5. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes larutan FeCl3 5%
34 3.3.3. Identifikasi Urea(BPOM, 1995)
Sebanyak 500 mg serbuk gambir dipanaskan dalam tabung reaksi hingga
meleleh dan bau ammonia. Pemanasan dilanjutkan hingga cairan keruh lalu
didinginkan dan dilarutkan dalam campuran 10 mL air dan 0.5 mL larutan
NaOH P, ditambahkan 1 larutan tembaga (III) sulfat P, terjadi perubahan warna
violet. Melarutkan 100 mg dalam 1 mL air asam nitrat P, terbentuk endapan
hablur putih.
3.3.4. Uji Penapisan Fitokimia(Fransworth, 1966)
a. Identifikasi golongan alkaloid
Sebanyak 2 gram sampel ditambahkan dengan 5 mL ammonia 25%, digerus
dalam mortir, kemudian ditambahkan 20 ml etil asetat dan digerus kembali
dengan kuat, campuran tersebut disaring dengan kertas saring. Filtrat
berupa larutan organik diambil (sebagai larutan A), sebagian dari larutan A
(10 mL) diekstraksi dengan 10 ml larutan HCl 1:10 dengan pengocokan
dalam tabung reaksi, diambil larutan bagian atasnya (larutan B). Larutan A
diteteskan beberapa tetes pada kertas saring dan ditetesi dengan pereaksi
Dragendorff. Jika terbentuk warna merah atau jingga pada kertas saring
maka hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan alkaloid dalam
sampel.
Larutan B dibagi dalam dua tabung reaksi, ditambahkan masing-masing
pereaksi Dragendorff dan Mayer. Jika terbentuk endapan merah bata
dengan pereaksi Dragendorff dan endapan putih dengan pereaksi Mayer
35
b. Identifikasi golongan flavonoid
1 gram sampel ditambahkan 50 mL air panas, dididihkan selama 5 menit,
disaring dengan kertas saring, diperoleh filtrat yang akan digunakan sebagai
larutan percobaan. Ke dalam 5 mL larutan percobaan (dalam tabung reaksi)
ditambahkan serbuk atau lempeng magnesium secukupnya dan 1 ml HCl
pekat, serta 5 mL butanol, dikocok dengan kuat lalu dibiarkan hingga
memisah. Jika terbentuk warna pada lapisan butanol (lapisan atas) maka hal
itu menunjukkan adanya senyawa golongan flavonoid.
c. Identifikasi golongan saponin
Sebanyak 10 mL larutan percobaan yang diperoleh dari percobaan B
(identifikasi golongan flavonoid), dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan
dikocok secara vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan selama 10
menit. Jika dalam tabung reaksi terbentuk busa yang stabil dan jika
ditambahkan 1 tetes HCl 1% busa tetap stabil maka hal itu menunjukkan
adanya senyawa golongan saponin.
d. Identifikasi golongan steroid dan triterpenoid
1 gram sampel ditambahkan dengan 20 mL eter, dibiarkan selama 2 jam
dalam wadah dengan penutup rapat lalu disaring dan diambil filtratnya. 5
mL dari filtrat tersebut diuapkan dalam cawan penguap hingga diperoleh
residu/sisa. Ke dalam residu ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1
tetes asam sulfat pekat (pereaksi Libermann-Burchard). Jika terbentuk
warna hijau atau merah maka hal itu menunjukkan adanya senyawa
golongan steroid dan triterpenoid dalam simplisia tersebut.
36
gram sampel ditambahkan 100 mL air, dididihkan selama 15 menit lalu
didinginkan dan disaring dengan kertas saring, filtrat yang diperoleh dibagi
menjadi dua bagian. Ke dalam filtrat pertama ditambahkan 10 mL larutan
FeCl3
Ke dalam filtrat yang kedua ditambahkan 15 mL pereaksi Stiasny
(formaldehid 30% : HCl pekat = 2 : 1), lalu dipanaskan di atas penangas air
sambil digoyang-goyangkan. Jika terbentuk endapan warna merah muda
menunjukkan adanya tanin katekuat. Selanjutnya endapan disaring, filtrat
dijenuhkan dengan serbuk natrium asetat, ditambahkan beberapa tetes
larutan FeCl
1%, jika terbentuk warna biru tua atau hijau kehitaman maka hal itu
menunjukkan adanya senyawa golongan tanin.
3
f. Identifikasi golongan kuinon
1%, jika terbentuk warna biru tinta maka menunjukkan
adanya tanin galat.
Diambil 5 mL larutan percobaan dari percobaan B (identifikasi golongan
flavonoid), lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan beberapa
tetes larutan NaOH 1 N. Jika terbentuk warna merah maka hal itu
menunjukkan adanya senyawa golongan kuinon.
a. Identifikasi golongan minyak atsiri
Sejumlah 2 gram sampel dalam tabung reaksi (volume 20 mL),
ditambahkan 10 mLpelarut petroleum eter dan dipasang corong (yang
diberi lapisan kapas yang telah dibasahi dengan air) pada mulut tabung,
dipanaskan selama 10 menit di atas penangas air dan didinginkan lalu
disaring dengan kertas saring. Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam cawan
penguap hingga diperoleh residu. Residu dilarutkan dengan pelarut alkohol
37
dalam cawan penguap, jika residu berbau aromatik/menyenangkan maka
hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan minyak atsiri.
b. Identifikasi golongan kumarin
2 gram sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi (volume 20 mL),
ditambahkan 10 mL pelarut kloroform dan dipasang corong (yang diberi
lapisan kapas yang telah dibasahi dengan air) pada mulut tabung, dipanaskan
selama 10 menit di atas penangas air dan didinginkan lalu disaring dengan
kertas saring. Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam cawan penguap hingga
diperoleh residu. Residu ditambahkan air panas sebanyak 10 mL lalu
didinginkan. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi,
ditambahkan 0,5 mL larutan ammonia (NH4OH) 10 %. Lalu diamati di
bawah sinar lampu ultraviolet pada panjang gelombang 365 nm. Jika terjadi
fluoresensi warna biru atau hijau maka hal itu menunjukkan adanya senyawa
golongan kumarin.
3.3.5. Pengujian Parameter Spesifik (Depkes RI, 2000)
Pemeriksaan Organoleptik yaitu mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan
rasa.
3.3.6. Pengujian parameter Non Spesifik (Depkes RI, 2000)
a. Kadar abu
Sebanyak lebih kurang 1-2 gram serbuk simplisia yang telah digerus dan
ditimbang seksama, dimasukan ke dalam krus platina atau krus silikat
yang telah dipijarkan dan ditara. serbuk simplisia diratakan kemudian
38
ditimbang. Jika arang tidak dapat hilang, ditambahkan air panas,
disaring dengan menggunakan kertas saring bebas abu. Sisa abu dan
kertas saring lalu dipijarkan dalam krus yang sama. Filtrat dimasukkan
ke dalam krus, diuapkan, dipijarkan hingga bobot tetap, ditimbang.
Kadar abu dihitung terhadap berat ekstrak dan dinyatakan dalam % b/b.
b. Kadar air
Pengukuran kadar air dilakukan dengan cara kurang lebih 3 gram serbuk
simplisia dimasukkan dan ditimbang seksama dalam wadah yang telah
ditara. Ekstrak dikeringkan pada suhu 105o
c. Penetapan Kadar katekin (Lucida et al., 2007).
C selama 5 jam dan ditimbang.
Pengeringan dilanjutkan dan ditimbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan
antara 2 penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25 %.
1. Penentuan panjang gelombang maksimal
Sebanyak 25 mg katekin pembanding ditimbang dan dilarutkan dalam
etil asetat hingga 25 mL (larutan induk konsentrasi 1 mg/mL). Dari
larutan induk diencerkan hingga menjadi konsentrasi 0.02 mg/mL.
Diukur panjang gelombang maksimal dengan spektrofotometer UV.
2. Pembuatan kurva kalibrasi
Dari larutan induk diatas dibuat larutan katekin standar dengan berbagai
konsentrasi: 0.02 mg/mL, 0.03 mg/mL, 0.04 mg/mL, 0.05 mg/mL dan
0.06 mg/mL. Kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometer UV
pada panjang gelombang 279 nm dan dibuat kurva kalibrasi
sertapersamaan regresi linearnya.
39
Penetapan kadar katekin sampel dengan cara sebanyak 25 mg sampel
ditimbang dan dilarutkan dalam etil asetat hingga 25 mL, lalu dibuat
larutan katekin total menggunakan etil asetat dengan berbagai
konsentrasi, yaitu 0.02 mg/mL, 0.03 mg/mL, 0.04 mg/mL, 0.05 mg/mL,
dan 0.06 mg/mL. Kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometri
UV pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Kadar katekin
dalam larutan dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi.
d. Pengujian Jarak Lebur
Menempatkan sejumlah katekin ke dalam tabung kapiler lalu dipanaskan
dalam tangas udara atau tangas cair kemudian suhu dicatat pada saat zat
melebur dan pada saat semua dimana semua zat melebur. Dengan demikian
jarak lebur dicatat sebagai jarak antara suhu permulaan dan suhu akhir
peleburan yang sempurna. Laju pemanasan alat diatur sekitar 10oC per
menit, ketika mencapai suhu 165-170oC diatur kembali hingga kenaikannya
sekitar 1oC per menit (DepKes RI, 1979). Jarak lebur katekin pada literatur
adalah 175-177o
e. Rendemen Katekin
C (WHO, 1998).
Rendemen katekin dihitung dengan membandingkan berat awal serbuk
dengan berat akhir katekin total yang dihasilkan.
Rendemen = Bobot serbuk katekin diperoleh
Bobot serbuk gambir diekstraksi × 100%
40
500 gram serbuk gambir diinfus dengan pelarut air pada temperatur 90-96oC
selama 15-20 menit sambil diaduk. Selanjutnya, infusa disaring dalam keadaan
panas menggunakan corong yang dilapisi dengan kertas saring (DepKes RI,
1986). Residu dibilas kembali dengan air panas (90oC) dan disaring hingga
jernih. Filtrat yang diperoleh dipartisi dengan etil asetat dengan perbandingan
filtrat:etil asetat yaitu 1:½ kemudian ditambahkan dengan NaCl jenuh. Fase air
dipartisi kembali dengan etil asetat yang dilakukan hingga lima kali, kemudian
fase air dibuang dan fase etil asetat yang diperoleh dikumpulkan dalam labu
evaporator kemudian dievaporasi hingga kental yang selanjutnya dikeringkan
dengan menggunakan oven hingga didapatkan ekstrak kering. Ekstrak kering
tersebut dicuci dengan air dingin, bagian yang tidak larut dan berwarna putih
kekuningan disaring dan dikumpulkan. Residu yang tidak larut air dan terdapat
dikertas saring tersebut merupakan katekin kemudian dikeringkan menggunakan
oven pada suhu 50oC hingga terbentuk serbuk, lalu dilakukan penetapan
spektrum UV dan kadar katekin yang dibandingkan dengan katekin standar,
penetapan kadar air, kadar abu, uji jarak lebur dan penghitungan rendemen
katekin.
41 Tabel 2.Komposisi Tablet Hisap Katekin Gambir
Bahan
3.5. Pembuatan Tablet Hisap
1. Semua bahan-bahan yang digunakan ditimbang.
2. katekin, sukrosa, manitol, sukralosa dan aerosil dicampurkan.(m1
3. Membuat larutan pengikat kombinasi amilum dan gom akasia kemudian
ditambahkan FD&C yellow ke dalam larutan pengikat.
)
4. Pengikat yang telah dibuat dimasukkan ke dalam m1 sampai terbentuk massa yang
dapat dikepal yang kemudian diayak dengan ayakan no mesh 16 sehingga didapat
granul yang selanjutnya dikeringkan dalam oven suhu 40-50o
5. Granul yang telah kering diayak kembali dengan ayakan no mesh 18 kemudian
dilakukan evaluasi granul.
42
6. Mentol dilarutkan dengan etanol 96% kemudian dikeringkan dan diserbuk
selanjutnya ditambahkan ke dalam granul.
7. Granul tersebut di tambahkan dengan talkum dan Mg stearat dan kemudian
dikempa sehingga terbentuk tablet dan dilakukan evaluasi tablet.
3.6. Evaluasi Granul
a. Kadar lembab (Voight, 1994)
Sebanyak 1 gram granul dimasukkan ke dalam alat moisture balance. Granul
diratakan dan kemudian alat dijalankan, selanjutnya diperoleh data kadar lembab
yang terkandung dalam granul.
b.
Syarat : 2 – 5%
Kompresibilitas (Aulton, 1988; Voight, 1994)
Granul ditimbang sebanyak 20 gram (m) kemudian dimasukkan ke dalam gelas
ukur 100 mL dan dicatat volumenya (v0). Granul tersebut kemudian
diketuk-ketukkan sebanyak 500 kali dan dicatat kembali volume setelah pengetukan (vt).
Data yang diperoleh dihitung BJ bulknya yaitu sebelum diketuk dengan cara m/v0
dan BJ setelah diketuk dengan cara m/vt, kemudian dimasukkan ke dalam rumus:
% kompresibilitas = BJ mampat – BJ Bulk
BJ mampat � 100%
c.
Syarat :5-15 (sangat baik), 12-16 (baik), 18-21 (cukup baik), 23-35 (buruk), 35-38
(sangat buruk), > 40 (sangat buruk sekali)
Distribusi Ukuran Partikel (Voight, 1994)
Masing-masing ayakan pada sieving analyzer disusun berturut-turut mulai dari
yang teratas adalah mesh 12, 14, 16, 18 dan 20.Kemudian 20 gram granul
43
didapat pada masing-masing ayakan ditimbang lalu dihitung persen bobot granul
pada masing-masing ayakan baru kemudian didapat rata-rata diameter partikelnya.
d. Laju alir (Lachman, 1994; Aulton, 1988)
Dua puluh gram granul ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam corong yang
tertutup dan diratakan. Kemudian penutup corong dibuka dan dicatat waktu yang
diperlukan seluruh granul habis melewati corong.
e.
Syarat : 4-10 gram/detik
Sudut henti (Voight, 1994)
Dihitung diameter dan tinggi kerucut yang terbentuk pada gundukan granul pada
uji laju alir, kemudian dicari besar sudut henti dengan rumus :
tan α = 2ℎ �
dimana : h = tinggi kerucut gundukan granul
d = diameter gundukan granul
Syarat :<30o
3.7. Evaluasi Tablet Hisap
a. Pemeriksaan organoleptik
Tablet yang dihasilkan diamati warna, bau, tekstur,
b. Keseragaman bobot (Depkes RI, 1979)
Masing-masing ditimbang sebanyak 20 tablet yang diambil secara acak,
kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet.
Syaratnya bila bobot rata-rata lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu tidak
lebih dari 2 buah tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang 5% dari
bobot rata-ratanya, dan tidak ada satu pun tablet yang bobotnya menyimpang lebih
44
c. Keseragaman ukuran
Diambil secara acak sebanyak 20 buah tablet, diukur diameter dan tebal tablet
dengan menggunakan jangka sorong.
Syarat: diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1⅓ kali tebal
tablet.
d. Friabilitas (Lachman, 1994)
Ditimbang sebanyak 10 buah tablet yang diambil secara acak dan dibersihkan
dari debu. Kemudian diletakkan dalam alat friabilator dan alat dijalankan sebanyak
100 putaran dengan kecepatan 25 rpm.
Syarat : < 1%
e. Kekerasan (Kuncoro, 2008; Ansel, 1989; Parrot, 1971)
Diambil sebanyak 10 tablet secara acak kemudian ditentukan kekerasannya
dengan alat hardness tester. Pada umumnya kekerasan tablet hisap lebih tinggi
dibandingkan dengan tablet biasa.
Syarat : >10 kg/cm
f. Uji akurasi
3
Akurasi adalah suatu ukuran keterdekatan hasil analisis yang diperoleh
menggunakan metode tersebut dengan harga yang sebenarnya. Akurasi metode
analisis biasanya dinyatakan dengan persen perolehan kembali (% recovery)
terhadap sampel yang kadarnya telah diketahui pasti. Persyaratan perolehan
kembali anjuran Food and Drugs Administration (FDA) untuk suatu metode
analisis adalah 80-120% dari kadar tertera pada label.
3.8. Uji CD4