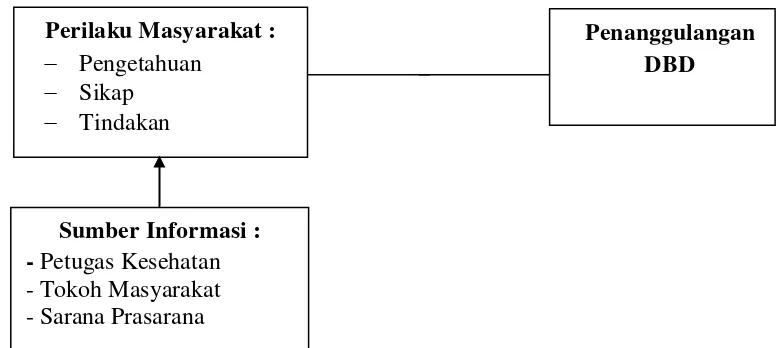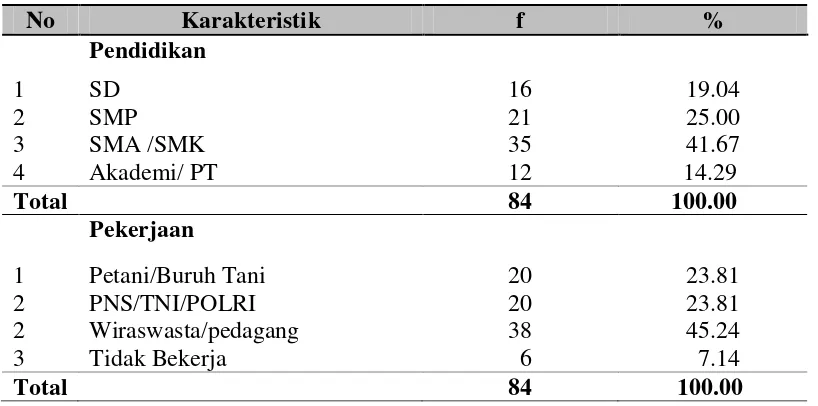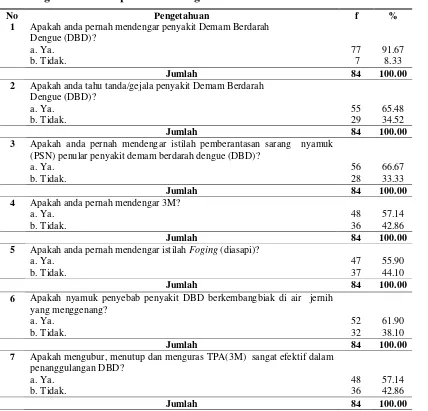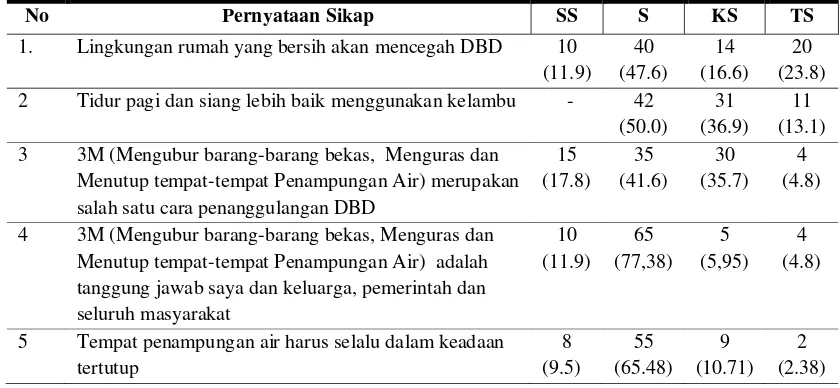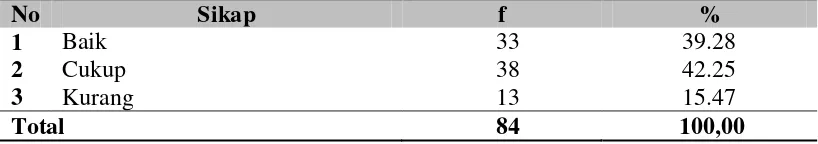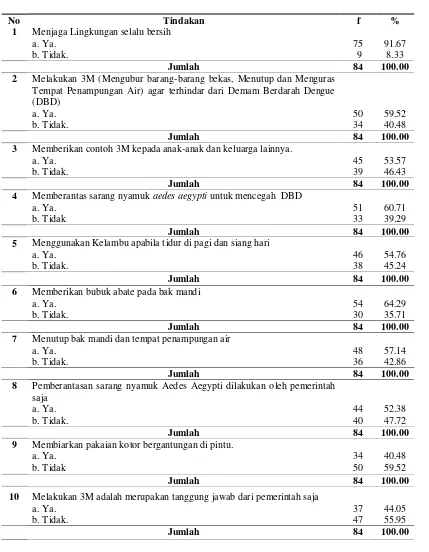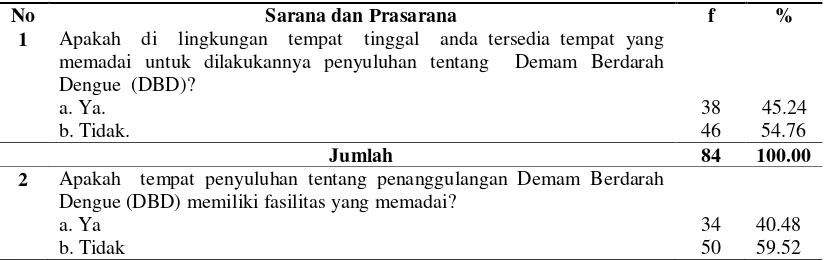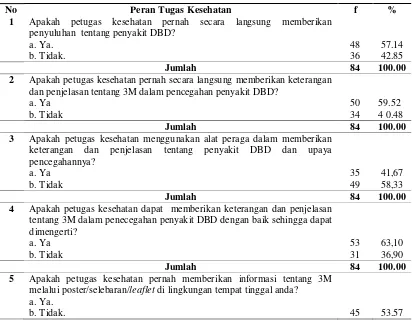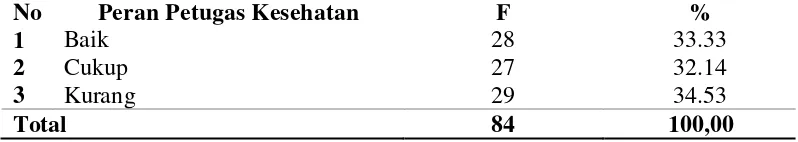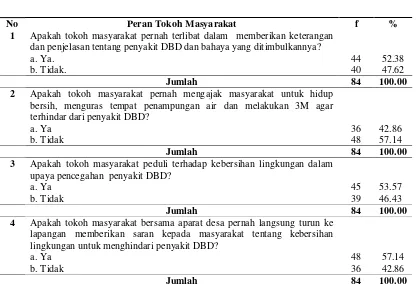NAGORI RAMBUNG MERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN 2014
Oleh :
DEARMAN ANDRI MAGISTARIO PURBA
NIM. 091000081
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
GAMBARAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM
PENANGGULAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI
NAGORI RAMBUNG MERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN 2014
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat
Oleh:
DEARMAN ANDRI MAGISTARIO PURBA
NIM. 091000081
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang dapat menyerang manusia, siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes agepty. Terjadinya kasus DBD di berbagai tempat tidak terlepas dari perilaku masyarakat. Oleh karena itu perilaku masyarakat dalam penanggulangan DBD menjadi isu yang penting dan urgen untuk diteliti.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran perilaku masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden penelitian adalah SMA/SMK dan pekerjaan responden mayoritas adalah wiraswasta/ pedagang. Pengetahuan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori baik. Sikap responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten berada pada kategori cukup baik. Tindakan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun mayoritas berada pada kategori cukup baik. Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori kurang. Peran Tenaga kesehatan dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori cukup baik. Peran Tokoh masyarakat penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori kurang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu semakin ditingkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam penanggulangan DBD dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peran petugas, serta tokoh masyarakat agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a contagious disease that can infect humans , anyone , anytime and anywhere . Dengue disease transmitted through the bite of aedes agepty. The occurrence of dengue cases in various places can not be separated from people's behavior . Therefore, the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) become an important and urgent issue to be investigated .
This study is a descriptive survey research and aims to identify and analyze the picture of the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever in Nagori Red Rambung Simalungun 2014 .
The results showed that the majority of survey respondents were in high school and most work as an entrepreneur. The knowledge of the respondent to prevent of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were good. The attitude of the respondents to prevent DBD were quite well. The action of the respondents in quite well. Infrastructures to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less category. The role of health workers to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were quite good. The role of community leaders to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less.The suggestions in this research were need to be improved knowledge, attitudes and actions of the community to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) by more communication, information and education to the community on regular, improve the quality and quantity of infrastructure, the role of health workers, and the community leaders in the future.
BIODATA
Nama : Dearman Andri Magistario Purba
Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 7 April 1992
Agama : Kristen Protestan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Rumah : Kompleks Setia Budi Vista Blok B No. 7 Jl. Lizadri
Putra, Selayang Medan Tuntungan
Nama Orangtua : Dr. Ir. Sukarman Purba, Drs, MPd
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun 1997-2003 : SD Budi Murni-2 Medan
Tahun 2003-2006 : SMP Negeri 19 Bandung
Tahun 2006-2009 : SMA Immanuel Medan
Puji dan syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Mahaesa atas berkat dan
hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul “Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Nagori Rambung Merah
Kabupaten Simalungun Tahun 2014”, dapat diselesaikan dengan baik guna
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara.
Pada penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan dan
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatran ini sudah
sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :
1. Dr. Drs. Surya Utama, MS, selaku. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara.
2. Drs. Tukiman, MKM, selaku Ketua Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu
Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan
sekaligus sebagai dosen penguji saya yang telah banyak memberikan inspirasi
dan motivasi saya.
3. Drs. Alam Bakti Keloko, MKes, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak
memberikan perhatian, bimbingan, dukungan dalam penyusunan skripsi ini dan
menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis.
4. Drs. Eddy Syahrial, MSi, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak
mengajari, memberikan perhatian, bimbingan, dukungan serta arahan dalam
inspirasi saya.
6. Seluruh dosen dan pegawai terutama di Departemen Pendidikan Kesehatan dan
Ilmu Perilaku FKM USU yang telah banyak memberi masukan dan berkat ilmu
pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yaitu dr. Jan Maurisdo Purba
beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan data yang diperlukan dalam
penelitian ini.
8. Kepala Nagori Rambung Merah , Martua Simarmata, AMd beserta jajarannya
yang telah member ijin dan data penelitian yang dibutuhkan.
9. Responden penelitian yaitu masyarakat Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun yang telah bersedia menjadi sampel penelitian dan mengisi angket
dan menjawab pertanyaan penelitian ini.
10. Kedua orangtua yang sangat kusayangi Dr. Ir. Sukarman Purba, Drs, MPd dan
ibunda Prof. Dr. Erika Revida Saragih, MS yang telah melahirkan, mendidik dan
membimbing dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat abangda Deardo Chandra Vaskanus Purba, ST, MT dan adikku Dearni
Anggita Krismayani Purba yang telah terus menerus mendukung dan
mengingatkan saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Buat semua temanku Dapot, Fredy, Lucky, Hotman dan semua
Kiranya Tuhan Yang Mahaesa lah yang dapat membalas budi baik, berkat dan
melimpahkan berkat dan anugrahNya kepada kita semua. Semoga karya ilmiah ini
dapat berguna bagi nusa dan bangsa khususnya bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara.
Medan, Pebruari 2015 Penulis,
3.4.2. Data Sekunder ... 35
3.5. Defenisi Operanional ... 35
3.6. Metode Pengukuran ... 36
3.7. Metode Pengolahan dan Analisa Data ... 38
3.7.1. Metode Pengolahan Data ... 38
3.7.2. Analisa Data ... 39
BAB IV HASIL PENELITIAN ... 40
4.1. Lokasi Penelitian ... 40
4.2. Karakteristik Responden ... 40
4.3. Analisa Univariat ... 42
4.3.1. Distribusi Pengetahuan Masyarakat ... 42
4.3.2. Distribusi Sikap Masyarakat ... 45
4.3.3. Distribusi Tindakan ... 50
4.3.4. Distribusi Sarana dan Prasarana ... 53
4.3.5. Distribusi Peran Petugas Kesehatan ... 57
4.3.6. Distribusi Peran Tokoh Masyarakat ... 62
BAB V PEMBAHASAN ... 68
5.1. Gambaran Pengetahuan Masyarkat ... 68
5.2. Gambaran Sikap Masyarakat ... 71
5.3. Gambaran Tindakan Masyarakat ... 74
5.4. Gambaran Sarana dan Prasarana ... 75
5.5. Gambaran Peran Petugas Kesehatan ... 77
5.6. Gambaran Peran Tokoh Masyarakat ... 78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 83
6.1. Kesimpulan ... 83
6.2. Saran ... 84
DAFTAR PUSTAKA ………. 86
Halaman
Tabel 4.1.Distribusi Karakteristik Pendidikan dan Pekerjaan Responden Di
Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014…..…... 41
Tabel 4.2.Distribusi Jawaban Responden tentang Pengetahuan dan Pemahaman dalam Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... .. 42
Tabel 4.3.Distribusi Kategori Pengetahuan Responden tentang Pemahaman dalam Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... … 44
Tabel 4.4.Distribusi Jawaban Responden tentang Sikap Responden Terhadap
Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... … 45
Tabel 4.5.Distribusi Kategori Sikap Masyarakat Terhadap Pencegahan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... … 50
Tabel 4.6.Distribusi Jawaban Responden tentang Tindakan Masyarakat terhadap Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... ...51
Tabel 4.7.Distribusi Kategori Tindakan Masyarakat terhadap Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... ...52
Tabel 4.8.Distribusi Jawaban Responden tentang Sarana Prasarana terhadap
Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun
Tahun 2014……….. 53
Tabel 4.9. Distribusi Kategori Sarana dan Prasarana Terhadap Penanggulangan DBD
di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014……… 57
Tabel 4.10. Distribusi Jawaban Responden tentang Peran Petugas Kesehatan Terhadap Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun Tahun 2014………58
Tabel 4.13. Distribusi Kategori Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pencegahan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun
Lampiran 1. Sebaran Data Pengelitian
Lampiran 2. Distribusi Tingkat Kategori
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang dapat menyerang manusia, siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes agepty. Terjadinya kasus DBD di berbagai tempat tidak terlepas dari perilaku masyarakat. Oleh karena itu perilaku masyarakat dalam penanggulangan DBD menjadi isu yang penting dan urgen untuk diteliti.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran perilaku masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden penelitian adalah SMA/SMK dan pekerjaan responden mayoritas adalah wiraswasta/ pedagang. Pengetahuan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori baik. Sikap responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten berada pada kategori cukup baik. Tindakan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun mayoritas berada pada kategori cukup baik. Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori kurang. Peran Tenaga kesehatan dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori cukup baik. Peran Tokoh masyarakat penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori kurang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu semakin ditingkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam penanggulangan DBD dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peran petugas, serta tokoh masyarakat agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a contagious disease that can infect humans , anyone , anytime and anywhere . Dengue disease transmitted through the bite of aedes agepty. The occurrence of dengue cases in various places can not be separated from people's behavior . Therefore, the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) become an important and urgent issue to be investigated .
This study is a descriptive survey research and aims to identify and analyze the picture of the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever in Nagori Red Rambung Simalungun 2014 .
The results showed that the majority of survey respondents were in high school and most work as an entrepreneur. The knowledge of the respondent to prevent of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were good. The attitude of the respondents to prevent DBD were quite well. The action of the respondents in quite well. Infrastructures to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less category. The role of health workers to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were quite good. The role of community leaders to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less.The suggestions in this research were need to be improved knowledge, attitudes and actions of the community to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) by more communication, information and education to the community on regular, improve the quality and quantity of infrastructure, the role of health workers, and the community leaders in the future.
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-undang Nomor 36
tahun 2009).
Salah satu program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan di bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular. Program tersebut dilaksanakan untuk mencegah berjangkitnya penyakit,
atau mengurangi angka kematian dan kesakitan, dan sedapat mungkin menghilangkan
akibat buruk dari penyakit menular tersebut.
Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemoragic Fever (DHF)
adalah salah satu jenis penyakit menular akut yang dapat menyerang manusia dengan
manifestasi pendarahan dan bertendensi menimbulkan shock yang dapat
menyebabkan kematian, penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes
aegypti dan Aedes albopictus yang telah terinfeksi virus dengue. Faktor-faktor yang
mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus DBD ini sangat kompleks, yaitu
pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkontrol, tidak
adanya kontrol terhadap vektor di daerah endemik, dan peningkatan sarana
Besaran masalah penyakit DBD di setiap wilayah dari waktu ke waktu sangat
bervariasi seiring dengan semakin padatnya penduduk suatu daerah dan arus
transportasi yang lancar. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes
aegypti dan Aedes albopictus termasuk golongan B Arthropod Borne Virus dan
terdapat di seluruh pelosok Indonesia kecuali di tempat-tempat dengan ketinggian
1000 meter di atas permukaan laut (Sumunar, 2007).
Penyakit DBD di Asia pertama sekali ditemukan di Manila (Filipina) pada
tahun 1953, dan pada tahun 1958 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit
Demam Berdarah Dengue di Bangkok (Thailand), selanjutnya penyakit ini menyebar
ke berbagai negara di dunia (Soedarmo, 1995).
Di Indonesia, Demam Berdarah Dengue (DBD) pertama sekali dicurigai di
Surabaya pada tahun 1968. Di Jakarta, kasus pertama dilaporkan pada tahun 1969.
Kemudian DBD berturut-turut dilaporkan di Bandung dan Jogyakarta (1972).
Epidemi pertama di luar Jawa dilaporkan pada tahun 1972 di Sumatera Barat dan
Lampung, pada tahun 1973 di Riau, Sulawesi Utara dan Bali. Kemudian pada tahun
1974, epidemi dilaporkan di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Suroso T,
dkk, 1999).
Penyakit DBD sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan
jumlah kasus yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2002 sebanyak 40.377 kasus
dengan Insidens Rate (IR) 19,24 per 100.000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR
1,3%) , pada tahun 2003 sebanyak 51.439 kasus dengan IR 23,87 per 100.000
Pada tahun 2004 penyakit DBD dilaporkan di 30 provinsi pada 309
kabupaten/kota dengan jumlah penderita 70.926 kasus dengan IR 37,11 per 100.000
penduduk dan CFR 1,12% (794 kematian). Provinsi-provinsi yang dinyatakan KLB
DBD di Indonesia adalah sebanyak 12 provinsi yaitu NAD, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, D.I. Jogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan
Timur, dan Sulawesi Utara. Kasus dan angka kesakitan tertinggi dilaporkan di
provinsi DKI Jakarta sebesar 19.569 kasus dengan IR 173,97 per 100.000 penduduk
dan 85 kematian (CFR 0,43%). Jawa Barat dengan 17.797 kasus dan 191 kematian
(CFR 1,07%), Kalimantan Timur dengan IR 72,94 per 100.000 penduduk, Bali
dengan IR 57,81 per 100.000 penduduk, dan Jogyakarta dengan IR 57,04 per 100.000
penduduk. Angka kematian tertinggi terjadi di provinsi Kalimantan Barat (CFR
6,67%), disusul NAD (CFR 4,37%), dan Sulawesi Utara (CFR 3,88%), dan pada
tahun 2005 jumlah penderita DBD di Indonesia sebanyak 95.279 kasus dengan IR
43,42 per 100.000 penduduk dan CFR 1,36%. Hingga pertengahan tahun 2013
jumlah penderita DBD di Indonesia tercatat 48.905 orang, 376 di antaranya
meninggal dunia (Muhadir dalam Majalah Tempo, 26 Juli 2013).
Di propinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 ada sebanyak 4535 orang dan 56
orang yang meninggal. Pada tahun 2012 tercatat ada sebanyak 6032 orang penderita
DBD dan yang meninggal 85 orang, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 3589 orang
dan yang meninggal sebanyak 30 orang (Profil Kesehatan Sumatera Utara, 2013).
Kabupaten Simalungun adalah salah satu daerah kabupaten yang ada di
propinsi Sumatera Utara yang mempunyai kasus DBD yang cukup tinggi. Di
sebanyak 582 kasus dan 2 orang yang meninggal, tahun 2012 sebanyak 697 orang
dan 18 orang yang meninggal dunia. Pada tahun 2013 ada sebanyak 433 kasus dan
yang meninggal ada 2 (dua) orang (Profil Kesehatan Kabupaten Simalungun, 2013).
Di Nagori Rambung Merah Simalungun sendiri berdasarkan data yang diperoleh
langsung dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, pada tahun 2011 ada
sebanyak 30 kasus dan 2 orang yang meninggal. Tahun 2012 ada sebanyak 45 kasus
dan 5 orang yang meninggal dan tahun 2013 ada terdapat 15 kasus dan tidak ada yang
meninggal dan hingga bulan Juli 2014 tercatat ada 15 orang yang sudah menderita
penyakit DBD dan belum ada yang meninggal dunia. Walaupun jumlah penderita
DBD tampaknya mengalami penurunan, hal ini tidak boleh dianggap pencegahan
penyakit DBD sudah selesai, karena nyamuk Aedes Aegypti dapat seketika muncul
secara tiba-tiba dan perilaku masyarakat dalam penangulangan DBD tidak dikontrol
dengan baik.
Sesungguhnya telah banyak program dan upaya yang dilakukan pemerintah
dalam penanggulangan DBD antara lain melalui gerakan pemberantasan sarang
nyamuk, 3M (Mengubur, Menguras dan Menutup tempat penampungan air, fogging,
penyuluhan kebersihan lingkungan, menggunakan lotion dan kelambu dan
sebagainya. Namun dalam prakteknya jumlah penderita DBD masih saja
menunjukkan angka yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Hal inilah yang
mendasari perlunya dilakukan penelitian tentang “Gambaran Perilaku Masyarakat
Dalam Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nagori Rambung Merah
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut diatas maka rumusan masalah penelititian ini adalah
“Bagaimana gambaran perilaku masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah
Dengue (DBD) di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014?”.
1. 3. Tujuan Penelitian. 1.3.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan
Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun
Tahun 2014.
1.3.2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan
Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui gambaran sikap masyarakat dalam penanggulangan Demam
Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun
Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui gambaran tindakan masyarakat dalam penanggulangan
Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun Tahun 2014.
4. Untuk mengetahui gambaran sarana prasarana dalam penanggulangan Demam
Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun
5. Untuk mengetahui gambaran peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan
Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun Tahun 2014.
6. Untuk mengetahui gambaran peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan
Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun Tahun 2014.
1. 4. Manfaat Penelitian.
Adapun manfaat daripada penelitian ini diharapkan sebagai berikut :
a. Sebagai informasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk
mengambil kebijakan penatalaksanaan dan penanggulangan Demam Berdarah
Dengue (DBD).
b. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Tim
Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nagori Rambung Merah
Kabupaten Simalungun.
c. Untuk meningkatkan motivasi masyarakat tentang penanggulangan Demam
2.1. Perilaku
2.1.1. Pengertian Perilaku
. Menurut Notoatmodjo (2003) perilaku manusia adalah pengetahuan, sikap,
tindakan/kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang
tidak dapat diamati oleh pihak luar. Selanjutnya, Skinner (dalam Notoatmodjo, 2003),
merumuskan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau
rangsangan dari luar. Teori ini disebut Stimulus Organisme Respons (SOR).
Perilaku manusia terbentuk berdasarkan interaksinya dengan lingkungan-nya.
Sesungguhnya ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku manusia
yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri manusia yaitu
pengetahuan, persepsi, emosi, kecerdasan, dan lain-lain yang mengolah
rangsangan/stimulus dari luar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal
dari luar diri manusia antara lain linkungan manusia baik fisik maupun nonfisik
seperti cuaca, manusia lainnya, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.
2.1.2. Determinan Perilaku
Secara umum, walaupun lingkungan mempengaruhi perilaku manusia namun
respons yang ditimbulkan belum tentu sama untuk setiap manusia. Kekuatan
pengaruh lingkungan luar sangat tergantung pada karakteristik dan kekuatan faktor
rangsangan/stimulus yang berbeda-beda ini disebut dengan istilah determinan
perilaku. (Notoatmodjo, 2007).
Secara umum determinan perilaku manusia dibedakan ke dalam dua
determinan yaitu determinan internal dan eksternal. Determinan internal adalah
karakteristik yang sudah dimilikinya sejak lahir (bawaan) dengan istilah sudah
“given” seperti misalnya jenis kelamin, tingkat kecerdasan, tingkat emosional dan
sebagainya. Determinan eksternal adalah lingkungan fisik dan nonfisik yang berada
di luar diri manusia yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik dan iklim/cuaca.
Determinan eksternal merupakan faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi
perilaku manusia.
Bloom yang dikutip oleh Notoatmojo (2003) membagi perilaku manusia ke dalam
tiga tingkatan yaitu : Pengetahuan (knowledge), Sikap (attitude) dan Tindakan
(practice). Pengetahuan (knowledge) adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil
tahu seseorang terhadap obyek tertentu melalui indera yang dimilikinya. Sikap
(attitude) adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu,
yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi, sedangkan Tindakan (practice)
merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, yang merupakan
bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki manusia.
Perilaku manusia pertama sekali terbentuk melalui pengetahuan kognitif melalui
proses membaca ataupun melihat dan mendengar sehingga menimbulkan
pengetahuan baru baginya yang selanjutnya menimbulkan respons batin yaitu
membentuk sikap baru terhadap respons tersebut. Sikap baru ini akan membentuk
menerima, menolak atau diam. Ada dua jenis teori determinan perilaku yang
ditawarkan para ahli yaitu dikenal dengan Teori Lawrence Green, dan Teori Model
Kepercayaan Kesehatan Rosenstock.
1. Teori Lawrence Green.
Menurut Lawrence Green dan M. Kreuter (2005), faktor-faktor penentu perubahan
perilaku manusia adalah :
a. Faktor Predisposisi (Predisposing factor) adalah faktor yang mempermudah
atau mempredisposisi timbulnya perubahan perilaku manusia antara lain
pengetahuan manusia, sikap, kepercayaan, tindakan, norma dan tradisi yang
ada dalam kehidupan manusia.
b. Faktor Pendukung (Enabling factor) yaitu faktor yang memungkinkan atau
memfasilitasi terjadinya perilaku atau tindakan manusia yaitu faktor
tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta kemudahan untuk
memperolehnya.
c. Faktor Penguat (Reinforcing factor) adalah faktor yang memperkuat terjadinya
suatu tindakan dalam bentuk perilaku yang mendorong perubahan perilaku
manusia seperti perilaku petugas kesehatan, kepala desa/lurah/nagori, tokoh
masyarakat dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat
perubahan perilaku manusia.
2. Teori Model Kepercayaan Kesehatan Rosenstock.
Menurut teori Model Kepercayaan Kesehatan Rosenstock, manusia akan melakukan
suatu tindakan apabila ia merasa akan terjadi suatu hal yang akan mengancam dirinya
lain, perubahan perilaku manusia akan terjadi jika dia mengetahui dampak yang
serius apabila tidak melakukan suatu tindakan.
Ada lima unsur utama dalam Teori Model Kepercayaan Kesehatan Rosenstock yaitu :
a. Persepsi manusia tentang kemungkinannya terkena suatu penyakit (perceived
susceptibility). Manusia yang merasa akan dapat terkena penyakit tertentu
akan lebih cepat merasa terancam.
b. Pandangan manusia tentang beratnya penyakit tersebut (perceived
seriousness), yaitu risiko dan kesulitan apa saja yang akan dialaminya dari
penyakit itu.
c. Pandangan manusia terhadap besarnya ancaman suatu penyakit yang dapat
menyerangnya (perceived threats). Ancaman ini mendorong manusia untuk
melakukan tindakan pencegahan atau penyembuhan penyakit.
d. Pandangan manusia tentang besarnya manfaat dan besarnya hambatan dari
suatu alternaltif yang diajukan oleh petugas kesehatan (perceived benefits and
barriers). Unsur ini diambil manusia untuk mengurangi rasa terancam
terhadap suatu penyakit.
e. Faktor pencetus (cues to action) yang dapat timbul dari dalam individu
(munculnya gejala-gejala penyakit itu) ataupun dari luar (nasihat orang lain,
kampanye kesehatan, seorang teman atau anggota keluarga terkena oleh
penyakit yang sama).
Kwick (dalam Notoatmodjo, 2003) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau
perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku
mengadakan tindakan terhadap suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan
adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap
hanyalah sebagian dari perilaku manusia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan
perilaku masyarakat dalam hal ini adalah pengetahuan, sikap dan tindakan
masyarakat terhadap sesuatu hal.
2.1.3. Perilaku Kesehatan
Masyarakat yang sehat adalah produk dari perilaku sehat. Perilaku kesehatan adalah
suatu respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit
penyakit, sistem pelayanan kesehatan, lingkungan dan sebagainya. (Notoatmodjo,
2003).
Perilaku kesehatan masyarakat secara lebih terperinci meliputi hal-hal sebagai berikut
:
1. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit yaitu bagaimana manusia
berespons, baik secara pasif (mengetahui, bersikap dan mempersepsi
penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya) maupun
secara aktif (tindakan) yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan
sakit tersebut.
2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah respons seseorang
terhadap sistem pelayanan kesehatan baik modern maupun tradisional.
3. Perilaku terhadap makanan (nutrition behavior) meliputi pengetahuan,
persepsi, sikap dan praktek terhadap makanan sehubungan dengan
4. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan (environmental health behavior).
Menurut Blum (dalam Nasrul, 1998) bahwa derajat kesehatan masyarakat
dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yaitu genetik (ketutunan), pelayanan
kesehatan, perilaku masyarakat dan lingkungan (fisik,biologis, sosial budaya),.
a. Faktor Genetik
Faktor genetik paling kecil pengaruhnya terhadap kesehatan perorangan atau
masyarakat dibandingkan dengan faktor yang lain. Pengaruhnya pada status
kesehatan perorangan terjadi secara evolutif dan paling sukar dideteksi. Untuk itu
perlu dilakukan konseling genetik. Untuk kepentingan kesehatan masyarakat atau
keluarga, faktor genetik perlu mendapat perhatian dibidang pencegahan penyakit.
Misalnya seorang anak yang lahir dari orangtua penderita diabetas melitus (DM) akan
mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan anak yang lahir dari orang tua bukan
penderita DM. Untuk upaya pencegahan, anak yang lahir dari penderita DM harus
diberi tahu dan selalu mewaspadai faktor genetik yang diwariskan orangtuanya. Oleh
karenanya, ia harus mengatur dietnya, olah raga yang teratur dan upaya pencegahan
lainnya sehingga tidak ada peluang faktor genetiknya berkembang menjadi faktor
resiko terkena penyakit pada dirinya. Dengan perkataan lain, semakin besar penduduk
yang memiliki resiko penyakit bawaan akan semakin sulit upaya meningkatkan
derajat kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya konseling perkawinan yang baik
untuk menghindari penyakit bawaan orang tuanya dan dapat dicegah muncul pada
dirinya. Teknologi dan kemampuan tenaga ahli dan petugas kesehatan harus
diarahkan untuk lebih meningkatkan upaya mewujudkan derajat kesehatan
b. Faktor Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan
berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan
petugas kesehatan yang diimbangi dengan kelengkapan sarana/prasarana, dan dana
yang signifikan akan menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
yang baik akan mampu mencegah dan mengurangi ataupun mengatasi masalah
kesehatan yang berkembang di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Misalnya,
jadwal imunisasi yang teratur dan penyediaan vaksin yang cukup dan sesuai dengan
kebutuhan, serta informasi tentang pelayanan imunisasi yang memadai kepada
masyarakat akan meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi
akan menekan angka kesakitan akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.
Saat ini pemerintah telah berusaha memenuhi 3 aspek yang sangat terkait dengan
upaya pelayanan kesehatan, yaitu upaya memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dengan membangun Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Bidan
Desa, Pos Obat Desa, dan jejaring lainnya. Pelayanan rujukan juga ditingkatkan
dengan munculnya rumah sakit-rumah sakit baru di setiap Kabupaten/Kota.
c. Faktor Perilaku Masyarakat
Faktor Perilaku Masyarakat di negara berkembang paling besar pengaruhnya
terhadap munculnya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan di masyarakat.
Tersedianya jasa pelayanan kesehatan (health service) tanpa disertai perubahan
tetap potensial berkembang di masyarakat. Misalnya, Penyediaan fasilitas dan
imunisasi tidak akan banyak manfaatnya apabila ibu-ibu tidak datang ke pos-pos
imunisasi. Perilaku ibu-ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang
sudah tersedia adalah akibat kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang manfaat
imunisasi dan efek sampingnya. Pengetahuan ibu-ibu akan meningkat karena adanya
penyuluhan kesehatan tentang imunisasi yang di berikan oleh petugas kesehatan.
Perilaku masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang sehat juga akan
berpengaruh pada faktor lingkungan yang memudahkan timbulnya suatu penyakit.
Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya
hidup masyarakat. Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan diri kita
dari banyak penyakit, diantaranya penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kegemukan,
diabetes mellitus (DM) dan lain-lain. Perilaku/kebiasaan mencuci tangan sebelum
makan juga dapat menghindarkan diri dari penyakit saluran cerna seperti diare dan
sebagainya.
d. Faktor Lingkungan
Lingkungan yang mendukung gaya hidup bersih juga berperan dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari hari di sekitar kita dapat
dirasakan, daerah yang kumuh dan tidak dirawat dengan baik pada umumnya banyak
masyarakatnya yang mengidap penyakit seperti : gatal-gatal, infeksi saluran
pernafasan, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit demam berdarah merupakan
bersih, banyaknya tempat penampungan air yang tidak pernah dibersihkan dan tidak
ditutup akan memyebabkan perkembangan nyamuk Aedes Aegypti yang merupakan
penyebab penyakit demam berdarah meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat di
sekitar memiliki resiko tinggi untuk tergigit nyamuk Aedes Aegypti dan tertular
penyakit demam berdarah.
Begitu pentingnya faktor perilaku manusia dan lingkungan, sehingga dapat dikatakan
merupakan faktor yang paling dominan dalam penanggulangan penyakit DBD. Oleh
karena itu perilaku sehat masyarakat merupakan hal yang uugen dan utama yang
harus diperhatikan dalam kesehatan masyarakat dengan tepat sasaran.
Menurut Bloom (dalam Notoatmodjo, 2003), perilaku dapat dibagi ke dalam tiga
domain (ranah atau kawasan), meskipun ketiga domain (ranah atau kawasan) tersebut
tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Pembagian domain (ranah atau
kawasan) ini dilakukan hanya untuk kepentingan dan tujuan pendidikan. Ketiga
domain (ranah atau kawasan) tersebut adalah domain kognitif, afektif dan
psikomotor.
Dalam perkembangan selanjutnya dan untuk kepentingan oleh para ahli pendidikan
melakukan pengukuran hasil pendidikan pada ketiga domain yaitu kognitif, afektif
dan psikomotorik yang diukur dari :
a) Pengetahuan (knowledge)
b) Sikap atau tanggapan (attitude)
a. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia yang diperoleh melalui penginderaan
terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif manusia merupakan domain
yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior).
Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu:
1. Tahu (know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall)
terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang
telah diterima.
2. Memahami (comprehension)
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang
objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,
menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek
yang dipelajari.
3. Aplikasi (application)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah
dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.
4. Analisis (analysis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam
komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan masih ada
5. Sintesis (synthesis)
Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan
kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari
formulasi-formulasi yang ada.
6. Evaluasi (evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau
penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penelitian ini didasarkan pada suatu
kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada.
b. Sikap (attitude)
Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu
stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2003). Secara umum sikap dapat dirumuskan
sebagai kecenderungan untuk berespons (secara positif atau negatif) terhadap orang,
objek, atau situasi tertentu. Sikap mengandung suatu penilaian emosional yang afektif
(senang, benci, sedih, dan sebagainya), di samping komponen kognitif (pengetahuan
tentang objek tersebut) serta aspek konotatif (kecenderungan bertindak). Sikap itu
tidaklah sama dengan perilaku dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap
seseorang, sebab seringkali terjadi bahwa seseorang memperlihatkan tindakan yang
bertentangan dengan sikapnya. Sikap seseorang dapat berubah dengan diperolehnya
tambahan informasi tentang objek tersebut, melalui persuasi serta tekanan dari
kelompok sosial (Sarwono, 1997).
Menurut Newcomb yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), salah seorang ahli
seseorang untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap
belum merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Seperti halnya dengan
pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni:
1. Menerima (receiving)
Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang
diberikan (objek).
2. Merespons (responding)
Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang
diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.
3. Menghargai (valuing)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain
terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.
4. Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko
merupakan sikap yang paling tinggi.
Pengukuran sikap dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara
langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan respons terhadap
suatu objek.
c. Tindakan
Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk
mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau
fasilitas juga diperlukan faktor pendukung (support) dari pihak lain misalnya dari
suami atau istri, orangtua atau mertua dan lain-lain (Notoatmodjo, 2003).
Tindakan mempunyai beberapa tingkatan, yakni:
1. Persepsi (perception)
Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan
diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.
2. Respons terpimpin (guided respons)
Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh
adalah merupakan indikator praktik tingkat dua.
3. Mekanisme (mechanism)
Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau
sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga.
4. Adopsi (adoption)
Adopsi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan
itu sudah dimodifikasikannya tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.
2.2. Demam Berdarah Dengue (DBD)
2.2.1. Pengertian Demam Berdarah Dengue (DBD)
Penyakit Demam Berdarah Dengue yang sering disingkat dengan akronim DBD
adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan serangga
nyamuk Aedes Aegypti. Nyamuk ini ditemukan di negara-negara terletak diantara
garis lintang 450 Lintang Utara dan garis 350 Lintang Selatan, kecuali
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu jenis penyakit menular
yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD
ditandai dengan demam mendadak dua sampai tujuh hari tanpa penyebab yang jelas,
lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai dengan tanda-tanda perdarahan di kulit
berupa bintik-bintik perdarahan (petechiae), lebam (ecchymosis) atau ruam
(purpura). Kadang-kadang mimisan, feses berdarah, muntah darah, kesadaran
menurun atau renjatan atau syok (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000).
Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue termasuk kelompok B Arthropod Borne
Virus (Arboviruses) yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, family
Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis streotipe, yaitu ; 1, 2, 3,
DEN-4. Infeksi salah satu streotipe akan menimbulkan antibody terhadap sterotype yang
bersangkutan, sedangkan antibody yang terbentuk terhadap streotype lain sangat
kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap
sterotipe lain tersebut. Keempat sterotipe virus dengue dapat ditemukan di berbagai
daerah di Indonesia. Sterotype DEN-3 merupakan sterotype yang dominan dan
diasumsikan banyak yang menunjukkan gejala klinis (Depkes, RI, 2004).
Suatu studi tentang padatnya jumlah populasi nyamuk di Indonesia menunjukkan
tidak terdapat perbedaan yang bermakna dan signifikan antara musim kemarau dan
musim penghujan, artinya kapan saja populasi nyamuk Aedes Aegypti dapat
berkembang dan menyerang mangsanya. Ada juga ada peneliti lain yang menyatakan
bahwa kepadatan populasi nyamuk Aedes Aegypti meningkat pada musim penghujan
2.2.2. Vektor Penular
Nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus merupakan vektor penularan virus
dengue dari penderita kepada orang lain melalui gigitannya. Nyamuk Aedes aegypti
merupakan vektor penting di daerah perkotaan (daerah urban) sedangkan daerah
pedesaan (daerah rural) kedua spesies nyamuk tersebut berperan dalam penularan.
Menurut riwayatnya nyamuk penular penyakit demam berdarah disebut nyamuk
Aedes aegypti itu, awal mulanya berasal dari Mesir yang kemudian menyebar ke
seluruh dunia, melalui kapal laut dan udara. Nyamuk hidup dengan subur di belahan
dunia yang mempunyai iklim tropis dan subtropis seperti Asia, Afrika, Australia dan
Amerika. Nyamuk Aedes aegypti hidup dan berkembang biak pada tempat
penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah. Di
Indonesia, nyamuk Aedes aegypti tersebar di seluruh peosok tanah air, baik di kota
maupun di desa, kecuali di wilayah yang ketinggian lebih dari 1000 meter di atas
permukaan laut (Suroso 2004).
Menurut Depkes RI (2004), ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut :
1. Nyamuk Aedes aegypti berwarna hitam dengan belang-belang (loreng) putih
pada seluruh tubuhnya.
2. Hidup di dalam dan sekiyar rumah, juga di tempat umum
3. Mampu terbang sampai 100 meter.
4. Nyamuk betina aktif menggigit (menghisap) darah pada pagi hari yaitu pukul
09.00-10.00 dan sore hari yaitu pukul 16.00-1700. Nyamuk jantan biasa
5. Umur nyamuk Aedes aegypti rata-rata 2 minggu, tetapi sebagian diantaranya
dapat hidup hidup 2-3 bulan.
Adapun siklus nyamuk Aedes aegypti adalah telur → jentik → kepompong
(pupa) → nyamuk. Perkembangan dari telur sampai menjadi nyamuk kurang lebih 9
-10 hari. Tempat hinggap yang paling disenangi adalah benda-benda yang tergantung
seperti pakaian, kelambu, atau tumbuh-tumbuhan di dekat tempat berkembang
biaknya, biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab.
Kepadatan nyamuk ini akan meningkat pada musim hujan, dimana terdapat banyak
genangan air bersih yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes
aegypti,selain nyamuk Aedes aegypti , penyakit demam berdarah juga dapat
ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus, yang kurang berperan dalam menyebarkan
penyakit DBD, jika di banding nyamuk Aedes aegypti. Hal ini karena nyamuk Aedes
albopictus hidup dan berkembang biak di kebun atau semak-semak, sehingga lebih
jarang kontak dengan manusia dibandingkan dengan nyamuk Aedes aegypti yang
berada di dalam dan sekitar rumah (Suroso dan Umar, 2004)
Menurut Anonim (dalam Suroso dan Umar, 2004), genangan yang disukai sebagai
tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti berupa genagan air yang tertampung di
suatu wadah yang biasa disebut container atau tempat penampungan air (TPA),
antara lain:
1. TPA yang digunakan sehari-hari seperti drum, tempayan, bak mandi, bak WC,
ember dan sejenisnya.
2. Tempat perindukan tambahan atau non-TPA, seperti tempat minum hewan,
3. TPA alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung
kelapa, kulit kerang, pangkal pohon pisang, potongan bambu dan lain-lainnya.
2.3. Penularan Virus Dengue 2.3.1. Mekanisme Penularan
Demam berdarah dengue tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia.
Virus dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui
nyamuk. Oleh karena itu, penyakit ini termasuk kedalam kelompok arthropod borne
diseases. Virus dengue berukuran 35-45 nm. Virus ini dapat terus tumbuh dan
berkembang dalam tubuh manusia dan nyamuk. Terdapat tiga faktor yang memegang
peran pada penularan infeksi dengue, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara.
Virus dengue masuk ke dalam tubuh nyamuk pada saat menggigit manusia yang
sedang mengalami viremia, kemudian virus dengue ditularkan kepada manusia
melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti danmAedes albopictus yang infeksius.
Seseorang yang di dalam darahnya memiliki virus dengue (infektif) merupakan
sumber penular DBD. Virus dengue berada dalam darah selama 4-7 hari mulai 1-2
hari sebelum demam (masa inkubasi instrinsik). Bila penderita DBD digigit nyamuk
penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung
nyamuk. Selanjutnya virus akan berkembangbiak dan menyebar ke seluruh bagian
tubuh nyamuk, dan juga dalam kelenjar saliva. Kira-kira satu minggu setelah
menghisap darah penderita (masa inkubasi ekstrinsik), nyamuk tersebut siap untuk
sepanjang hidupnya. Oleh karena itu nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap
virus dengue menjadi penular (infektif) sepanjang hidupnya.
Penularan ini terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit (menusuk), sebelum
menghisap darah akan mengeluarkan air liur melalui saluran alat tusuknya (probosis),
agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersama air liur inilah virus dengue
dipindahkan dari nyamuk ke orang lain. Hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang
dapat menularkan virus dengue.
Nyamuk betina sangat menyukai darah manusia (anthropophilic) dari pada darah
binatang. Kebiasaan menghisap darah terutama pada pagi hari jam 06.00 hingga sore
hari jam 18.00. Nyamuk betina mempunyai kebiasaan menghisap darah
berpindah-pindah berkali-kali dari satu individu ke individu lain (multiple biter). Hal ini
disebabkan karena pada siang hari manusia yang menjadi sumber makanan darah
utamanya dalam keadaan aktif bekerja/bergerak sehingga nyamuk tidak bisa
menghisap darah dengan tenang sampai kenyang pada satu individu. Keadaan inilah
yang menyebabkan penularan penyakit DBD menjadi lebih mudah terjadi.
2.3.2. Diagnosis DBD
Terdapat empat gejala utama DBD, yaitu demam tinggi, fenomena perdarahan,
hepatomegali, dan kegagalan sirkulasi (Hadinegoro, 2004). Infeksi oleh virus dengue
dapat bersifat asimtomatik atau simtomatik. Gejala klinik utama pada DBD adalah
demam dan manifestasi perdarahan baik yang timbul secara spontan maupun uji
tourniquet (Soegianto, 2004).
Menurut WHO dalam Tumbelaka (2004), pedoman untuk membantu menegakkan
a. Secara Klinis, antara lain :
1. Demam mendadak tinggi
2. Perdarahan (termasuk uji bendung/tourniquet (+) seperti petekie apistaksis,
hematemesis, dan lain-lain
3. Hepatomegali
4. Syok : nadi kecil dan cepat dengan tekanan nadi ≤ 20 mmHg, atau hipotensi
disertai gelisah dan menggigil.
b. Laboratoris :
1. Trombositopenia (< 100.000/μl)
2. Hemokonsentrasi (kadar Ht ≥ 20% dari normal)
c. Berat penyakit :
1. Derajat I : demam uji bendung (+)
2. Derajat II : derajat I ditambah perdarahan spontan
3. Derajat III : nadi cepat dan lemah, tekanan nadi ≤ 20 mmHg (hipotensi),
menggigil
4. Derajat IV : syok berat, nadi tak teraba, tekanan darah tak terukur
Dua gejala klinis pertama ditambah dua gejala laboratories dianggap cukup
untuk menegakkan diagnosis kerja dari penyakit DBD.
Selain demam dan perdarahan yang merupakan ciri khas DBD, gambaran
klinis lain yang tidak khas dan biasa dijumpai pada penderita adalah:
1. Keluhan pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, sakit waktu menelan.
2. Keluhan pada saluran pencernaan : mual, muntah, tak nafsu makan
3. Keluhan sistem tubuh yang lain : nyeri atau sakit kepala, nyeri pada otot,
tulang dan sendi (break bone fever), nyeri otot abdomen, nyeri ulu hati,
pegal-pegal pada seluruh tubuh, kemerahan pada kulit, kemerahan(flushing)
pada muka, pembengkakan sekitar mata, lakrimasi dan fofobia otot-otot
sekitar mata sakit bila disentuh dan pergerakan bola mata terasa pegal
(Effendi, 1995).
2.4. Upaya Penanggulangan DBD
Mengingat obat dan vaksin penanggulangan penyakit DBD hingga saat ini
belum ditemukan, maka upaya untuk penanggulangan penyakit DBD dititikberatkan
pada pemberantasan nyamuk penularnya (Aedes aegypti) di samping kewaspadaan
dini terhadap kasus DBD untuk membatasi angka kematian (Suroso dan Umar, 2004).
Penyakit DBD perlu diberantas karena penyakit ini menimbulkan wabah dan
menyebabkan kematian pada banyak orang dalam waktu singkat. Penyakit DBD
semakin menyebar luas sejalan dengan meningkatnya arus transportasi dan kepadatan
penduduk. Semua desa/kelurahan mempunyai risiko untuk terjangkitnya penyakit
DBD karena nyamuk penularnya (Aedes aegypti) tersebar luas di seluruh pelosok
tanah air (Suroso dan Umar, 1994).
Menurut Notoatmodjo (2003), partisipasi masyarakat di bidang kesehatan
berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menanggulangi masalah
kesehatan mereka sendiri. Di dalam partisipasi, setiap anggota masyarakat dituntut
suatu kontribusi atau sumbangan yang diwujudkan dalam 4 M, yakni man power
(manusia), money (uang), material ( benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, dan
Partisipasi masyarakat (perorangan, keluarga dan masyarakat) dilibatkan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberantasan vektor di wilayahnya
masing-masing. Kegiatan ini dimaksud untuk meyakinkan masyarakat bahwa program ini
perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di lingkungannya.
Melalui kegiatan ini dapat menaikkan rasa percaya diri masyarakat dalam ikut
melaksanakan pembangunan kesehatan. Peningkatan partisipasi masyarakat
menumbuhkan berbagai peluang yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat
untuk secara aktif berkontribusi dalam pembangunan kesehatan sehingga dapat
menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh warganya (Depkes RI, 2000).
Adapun cara-cara untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti menurut Depkes
RI (2008) adalah:
1. Penyemprotan
Nyamuk Aedes aegypti dapat diberantas dengan menyemprotkan racun serangga,
termasuk racun serangga yang dipergunakan sehari-hari di rumah tangga. Melakukan
penyemprotan saja tidak cukup, karena dengan penyemprotan itu yang mati hanya
nyamuk (dewasa) saja. Selama jentiknya tidak dibasmi, setiap hari akan muncul
nyamuk baru yang menetas dari tempat perkembangbiakannya.
2. PSN DBD (Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue)
PSN DBD dilakukan dengan cara 3M yaitu:
1) Menguras tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu
sekali.
3) Menguburkan atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat
menampung air hujan seperti kaleng bekas, ban bekas, plastik bekas, dan
lain-lain
Selain itu ditambah dengan cara lain (yang dikenal dengan istilah 3M plus) seperti:
a. Ganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat lainnya seminggu sekali.
b. Perbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar/rusak.
c. Tutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon dan lain-lainnya misalnya
dengan tanah.
d. Bersihkan/keringkan tempat-tempat yang dapat menampungan air seperti pelepah
pisang atau tanaman lainnya termasuk termpat-tempat yang dapat menampung air
hujan di pekarangan, kebun, pemakaman, rumah-rumah kosong, dan lain-lain.
e. Abatisasi
f. Ikanisasi, pelihara ikan pemakan jentik
g. Pasang kawat kasa di rumah.
h. Pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
i. Jangan membiasakan menggantung pakaian di dalam rumah.
j. Tidur menggunakan kelambu.
k. Gunakan obat nyamuk (bakar, gosok, oles, semprot/spray) dan lain-lain untuk
mencegah gigitan nyamuk.
3. Larvasiding
Larvasiding adalah tindakan menaburkan bubuk abate atau altosid ke dalam
Menurut Suroso dan Umar (2004), kegiatan pokok penanggulangan penyakit
DBD antara lain:
1. Penemuan dan pelaporan penderita
2. Penanggulangan fokus
3. Pemberantasan vektor intensif, meliputi: 1) Fogging focus. 2) Abatisasi. 3)
Penyuluhan dan pergerakan masyarakat dalam PSN DBD (Gerakan 3M). 4)
Penyuluhan kepada masyarakat. 5) Pemantauan jentik berkala (PJB).
2.5. Upaya Pemberantasan Vektor DBD.
Pemberantasan DBD jangka panjang dilaksanakan melalui pendidikan/
penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal ini pendidikan kepada anak anak melalui
sekolah serta kepada orangtua, agar pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sebagai
bagian dari kebersihan lingkungan dapat dilakukan di rumah dan di lingkungan
masing-masing.
Menurut Departemen Kesehatan (2006), hal-hal yang dapat dilakukan oleh
kader dan tokoh masyarakat dalam pencegahan DBD adalah :
1. Memberikan informasi dan penyuluhan kepada warga tentang DBD seperti
memberikan penyuluhan DBD kepada keluarga, penyuluhan di posyandu, di
arisan, PKK, kelompok agama, memberikan informasi kepada teman dan
tetangganya, menyampaikan pesan-pesan bahaya penularan DBD melalui
poster, spanduk, dan selebaran.
2. Mengajak masyarakat untuk kerja bakti secara berkala, seperti membersihkan
mengumpulkannya ke tempat pembuangan sampah umum, menabur bubuk
abate, membersihkan genangan air.
3. Kunjungan rumah secara berkala memberikan penyuluhan dan pemeriksaan
jentik Salah satu cara untuk mencegah dan menaggulangi penyakit DBD
adalah dengan gerakan PSN-DBD yang dilakukan masyarakat dan pemerintah
secara berkesinambungan. Melalui gerakan ini semua masyarakat diharapkan
untuk :
a. Melakukan konsultasi (memeriksakan) kepada petugas jika ada anggota
kelurga yang sakit dan diduga menderita penyakit DBD.
b. Melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan jika ada anggota keluarga
yang menderita penyakit DBD.
c. Membantu kelancaran penaggulangan kejadian penyakit DBD yang
dilakukan oleh petugas kesehatan.
Untuk memberantas penularan DBD secara tuntas yang paling penting
adalah usaha-usaha masyarakat sendiri dalam memelihara kebersihan lingkungan
rumah, tempat kerja dan tempat-tempat umum agar bebas dari nyamuk penular
demam berdarah.
Cara yang paling tepat dalam pemberantasan penyakit DBD adalah
melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yaitu kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat dengan membasmi jentik nyamuk penular demam berdarah dengan
cara 3M (Sutrisna, 2003).
Ahmad (2004) mengemukakan bahwa kegiatan pemberantasan sarang
penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali dan menutup rapat-rapat atau
menaburkan racun pembasmi jentik (abatisasi), mengubur atau menyingkirkan
barang-barang bekas dan sampah-sampah lainnya yang dapat menampung air hujan
sehingga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk.
2.7. Kerangka Konsep
Perilaku masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam
penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD). Perilaku masyarakat terdiri dari
pengetahuan, sikap dan tindakan msyarakat. Kurangnya pengetahuan, sikap serta
tindakan masyarakat dalam penanggulangan DBD dan berperilaku hidup sehat serta
memperhatikan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi isu yang menarik
untuk diteliti hingga saat ini. Namun, masih kurangnya sosialisasi pemerintah dan
petugas kesehatan yang ajek dan kontinyu tentang mewujudkan perilaku hidup sehat
merupakan salah satu sebab masih menjamurnya penderira DBD hingga saat ini. Oleh
karena itu, berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang diajukan, maka
kerangka konsep Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan Demam
Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun
2014 diajukan sebagai berikut :
Perilaku Masyarakat : Pengetahuan
Sikap
Tindakan
Penanggulangan DBD
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survai bersifat deskriptif yang
bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan
Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar
Simalungun Tahun 2014.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagori Rambung Merah Kabupaten
Simalungun. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini sebagai berikut :
a. Belum pernah dilakukan penelitian yang serupa di Nagori Rambung Merah
Kabupaten Simalungun
b. Termasuk daerah yang penderita Demam Berdarah Dengue (DBD)nya relatif
cukup tinggi
3.2.2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Nopember-Desember 2014 yang
dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan interpretasi data
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 3.3.1. Populasi Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di
Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Simalungun pada tahun 2014 yaitu
sebanyak 661 KK.
3.3.2, Sampel Penelitian
Sampel penelitian adalah sebahagian dari jumlah populasi. Adapun
Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan teknik sampling acak sederhana
(Simple Random Sampling), dengan besar sampel yang di hitung dengan rumus
Lemeshow (Sugiono, 2000) sebagai berikut :
Keterangan
= Ukuran sampel
= Besar sampel populasi sasaran
= Perkiraan proporsi (prevalensi) variabel dependen pada populasi
=
= Statistik Z (misalnya Z= 1,96 untuk = 0,05)
d = Delta, presisi absolut atau margin of error yang diinginkan di kedua sisi proporsi (misalnya 10%)
n = 83.9. Dalam penelitian akan diambil jumlah ssmpel sebanyak 84 kepala keluarga
(KK).
3.4. Metode Pengumpulan Data 3.4.1. Data Primer
Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada Kepala
Keluarga (KK) yang telah menjadi sampel penelitian yaitu 84 KK di Nagori
Rambung Merah Kabupaten Simalungun tahun 2014. Selain itu juga dilakukan
pengamatan (observasi) langsung terhadap sampel penelitian.
3.4.2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi baik diperoleh dari
buku-buku maupun dari data dan dokumen yang ada di Nagori Rambung Merah dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Simalungun hingga tahun 2014.
3.5. Definisi Operasional
a. Pengetahuan Masyarakat adalah pemahaman responden dalam
penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) meliputi penyebab, cara
penularan, gejala-gejala dan cara pencegahannya.
b. Sikap adalah pernyataan responden dalam penanggulangan Demam Berdarah
Dengue (DBD) meliputi penyebab, cara penularan, gejala-gejala dan cara
c. Tindakan adalah segala sesuatu cara dan upaya yang dilakukan oleh
masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)
d. Sarana Prasarana adalah tempat atau fasilitas yang mendukung dalam
penanggulangan DBD
e. Petugas Kesehatan adalah Tenaga kesehatan yang bekerja dan menangani
masalah-masalah kesehatan.
f. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar
di komunitas atau masyarakat.
3.6. Metode Pengukuran a. Pengetahuan
Pengetahuan diukur dengan cara memberi skor/nilai pada 10 pertanyaan dengan
skor untuk jawaban yang benar 1, dan salah 0. Variabel pengetahuan memiliki
skor tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Berdasarkan skor kemudian variabel
pengetahuan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :
Baik bila jawaban responden benar > 75 % dari total skor yang diperoleh
Cukup bila jawaban responden benar 45 - 75% dari total skor yang diperoleh
Kurang bila jawaban responden benar < 45% dari total skori yang diperoleh.
b. Sikap
Sikap masyarakat dalam penanggulangan DBD yakni dengan memberikan 10,
dengan sistem skor : 4 untuk jawaban yang sangat setuju, 3 untuk jawaban
tertinggi 40 dan nilai terendah 10. Berdasarkan skor kemudian variabel sikap
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :
Baik bila jawaban responden benar > 75 % dari total skor yang diperoleh
Cukup bila jawaban responden benar 45 - 75% dari total skor yang diperoleh
Kurang bila jawaban responden benar < 45% dari total skori yang diperoleh
c. Tindakan
Tindakan diukur dengan cara memberi skor/nilai pada 10 pertanyaan dengan
skor untuk jawaban ya 1, dan tidak 0 untuk pertanyaan yang positif, dan
jawaban ya 0, dan tidak 1 untuk peratnayaan yang negatif. Variabel tindakan
memiliki skor tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Berdasarkan skor kemudian
variabel tindakan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :
Baik bila jawaban responden benar > 75 % dari total skor yang diperoleh
Cukup bila jawaban responden benar 45 - 75% dari total skor yang diperoleh
Kurang bila jawaban responden benar < 45% dari total skor yang diperoleh
d. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana diukur dengan cara memberi angket dengan 10
pertanyaan, dengan skor untuk jawaban ya 1, dan tidak 0 untuk pertanyaan yang
positif, dan jawaban ya 0, dan tidak 1 untuk peratnayaan yang negatif. . Variabel
sarana dan prasarana memiliki skor tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Berdasarkan
skor kemudian sarana dan prasarana dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :
Lengkap bila jawaban responden > 75 % dari total skor yang diperoleh